Dalam Filosofi Teras, Henry Manampiring mencoba menghadirkan filsafat kuno Stoisisme sebagai kiat dalam menghadapi tekanan hidup. Henry lebih jauh memberi sentuhan kepedulian sosial kepada Stoisisme meskipun beberapa prinsip filsafat ini tampak menyarankan apatisme.
SENGSARA melahirkan filsafat. Mungkin ini ungkapan yang tepat bagi Zeno, pedagang kaya dari Citium–sebuah kerajaan kuno di bibir pantai selatan Siprus.
Kira-kira lebih dari 2.000 tahun lalu, Zeno berlayar dari Phoenica (kini berada di sekitar Lebanon dan Suriah) menuju Peiraeus (kota pelabuhan di Athena) melintasi Laut Mediterania. Di tengah perjalanan, kapalnya karam. Barang dagangannya tenggelam. Dia terdampar dan terlunta-lunta di Athena.
Menggelandang di tempat kelahiran para filsuf besar Yunani Kuno– seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles–rupanya mendatangkan berkah bagi Zeno. Pedagang kaya yang jatuh miskin dalam sekejap itu tertarik dengan sebuah buku yang menggambarkan Socrates. Dia bertanya kepada pemilik toko buku, di manakah dia bisa menemukan orang seperti Socrates. Kebetulan saat itu Crates dari Tivai, seorang filsuf aliran Sinisisme yang menjalani hidup asketis di jalan-jalan Athena, lewat. Si pemilik toko kontan mengarahkan Zeno agar mengikuti Crates.
Setelah berguru kepada Crates dan sejumlah filsuf, Zeno mengembangkan sistem pemikiran sendiri. Karena senang mengajar di stoa, teras berpilar di Agora (semacam alun-alun di Athena), filsafat Zeno kemudian mendapat sebutan “Stoisisme”.
Berbeda dengan filsafat pendahulunya yang kerap membahas persoalan-persoalan pelik (seperti realitas, manusia, dan pikiran) Stoisisme lebih menekankan kepada etika, lebih tepatnya tentang kebajikan dan ketenangan jiwa. Mungkin karena ceruk yang unik ini, Stoisisme menjadi populer dan bahkan berkembang hingga periode Romawi Kuno, atau lebih dari enam abad setelah kelahirannya.
Baiklah. Kita tinggalkan dulu Zeno dari Citium. Kini kita melintasi ruang dan waktu menuju Abad ke-21, era pascamodern.
Di Jakarta, lebih dari 9.000 kilometer jauhnya dari Athena, Henry Manampiring menerima “vonis” menderita depresi dari psikiater. Dia bilang “vonis” itu, “bagaikan petir di siang bolong”.
Henry merepresentasikan profil manusia pascamodern. Ia punya karir yang bisa dibilang mentereng di dunia nyata: profesional di bidang periklanan. Di dunia maya, Ia juga populer. Pengikutnya di Twitter mencapai lebih dari 126 ribu (konon sudah bisa dibilang selebtwit).
Depresi memang bukan barang langka bagi manusia modern. Data Global Health Data Exchange 2017–yang dibuat Institute for Health Metrics and Evaluation, sebuah pusat riset kesehatan di Universitas Washington–menunjukkan setidaknya satu dari sepuluh orang Indonesia, atau 27,3 juta, mengalami masalah kejiwaan, dan depresi menduduki peringkat kedua dengan 6,6 juta orang. 1Nibras Nada Nailufar, “Merefleksikan Joker (3): 1 dari 10 Orang Indonesia Alami Gangguan Jiwa”, Kompas.com, diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/13/100000265/merefleksikan-joker-3-1-dari-10-orang-indonesia-alami-gangguan-jiwa?page=all, pada 21 Oktober 2019.
Hanya karena stigma buruk–masalah kejiwaan kerap dianggap identik dengan “gila”–cuma delapan persen orang dengan masalah kejiwaan yang meminta bantuan profesional, termasuk salah satunya Henry.
Dia bilang, dia dulu selalu berpikiran negatif sehingga mudah cemas. Kondisi ini berpengaruh terhadap perilakunya yang mudah marah, sehingga berdampak buruk bagi keluarga dan lingkungannya. Ia pun memutuskan mendatangi dokter jiwa. Tapi, terapi plus obat-obatan, menurutnya, tak mengatasi depresi itu. Kecemasan berlebihan itu terkadang kambuh.
“Dan terjadi lagi….”2Potongan syair lagu “Separuh Aku” yang dinyanyikan Noah ‘Sengsara’ kembali membawa orang kepada filsafat. Seperti Zeno dari Citium, Henry menemukan suaka dalam filsafat.
Dia memperoleh ketenangan permanen dari membaca sebuah buku berjudul How to be a Stoic karya Massimo Pigliucci, seorang profesor filsafat di City College, New York. Buku inilah gerbang awal Henry memasuki dan kemudian kian mereguk kenikmatan filosofis Stoisisme.
Setelah itu, ia tampaknya melahap sejumlah buku tentang filsafat kuno tersebut, baik edisi terjemahan dari karya para stois Romawi Kuno seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius maupun karya kontemporer seperti yang ditulis Pigliucci, Ryan Holiday, dan William Irvine. Tak hanya mengonsumsi, Henry juga memproduksi. Dia menyusun karyanya sendiri tentang Stoisisme: Filosofi Teras: Filsafat Yunani-Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini.

- Judul: Filosofi Teras: Filsafat Yunani-Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini
- Penulis: Henry Manampiring
- Penerbit: Penerbit Buku Kompas
- Tahun Terbit: 2019
- Tebal: xix + 320 halaman
Seperti Stoisisme yang menjadi populer dan berkembang sebagai salah satu mazhab utama filsafat Yunani Kuno, Filosofi Teras juga laris manis di pasaran. Aplikasi Gramedia digital hingga Oktober 2019 mencatat buku ini sebagai salah satu karya non-fiksi terpopuler.
Dalam Filosofi Teras, Henry membuat Stoisisme menjadi kian praktis saja (filsafat ini dari orok memang sudah berfokus kepada kebijaksanaan praktis: bagaimana seharusnya kita hidup). Dia menyusun kiat-kiat sederhana untuk mempraktikkan ajaran para stois dalam kehidupan sehari-hari, berikut contoh-contoh yang dekat dengan generasi milineal dan Z, seperti masalah yang dihadapi di sekolah, di tempat kerja, dalam hubungan percintaan, hingga di media sosial.
Popularitas Stoisisme di era pascamodern sebenarnya bukan fenomena baru. Dalam dua dekade terakhir, filsafat ini seperti terlahir kembali di Barat, sebagian besarnya dipopulerkan sebagai materi-materi self-improvement. Pertemuan tahunan dan bahkan mingguan, baik online maupun offline, selalu diikuti ribuan peserta. Sebagian besarnya adalah para profesional, pejabat publik, politisi, dan pebisnis. Ryan Holiday, misalnya, yang menulis The Daily Stoic, adalah bekas eksekutif teras American Apparel, sebuah perusahaan multinasional di bidang garmen.
Dalam bukunya, Henry menunjukkan bagaimana kita menggunakan Stoisisme untuk membangun karakter mental dan mendapatkan ketenangan jiwa. Bagi Anda yang kerap overthinking, peduli berlebihan kepada anggapan orang lain dan lingkungan, serta cemas tidak karuan dengan pesan-pesan di media sosial, apa yang ditawarkan Stoisisme bisa berdampak positif.
Ada dua prinsip dasar Stoisisme yang bisa membawa Anda kepada ketangguhan mental dan ketenangan jiwa. Keduanya sering diulang-ulang Henry dalam bukunya.
Pertama, apa yang disebut dengan “dikotomi kendali”, yakni bahwa terdapat “hal di dalam kendali” dan “hal di luar kendali” manusia. Menurut Stoisisme, kita seharusnya hanya berfokus kepada apa yang berada di dalam kendali. Yang di dalam kendali kita, menurut para stois, adalah pikiran kita. Yang di luar kendali kita adalah hal-hal selain itu: pikiran dan tindakan orang lain; kondisi saat lahir (orang tua, tempat kelahiran, dan asal suku bangsa); bencana alam; kekayaan; kecantikan; dan kesehatan.
Henry memberi contoh. Perjalanan karier, menurutnya, berada di luar kendali. Sekeras dan sebaik apa pun usaha kita dalam mengerjakan tugas-tugas kantor dan menunjukkan kompetensi, perjalanan karier tetaplah bergantung kepada hal-hal di luar kendali, seperti atasan yang subjektif, kolega yang malas, kebijakan politik, atau gosip di tempat kerja.
Kedua–dan ini masih berkaitan dengan prinsip pertama–apa yang disebut dengan indifferent, yakni bahwa hal-hal di luar pikiran (kendali) pada hakikatnya tak memiliki pengaruh apa pun terhadap baik-buruknya atau bahagia-sengsaranya kita. Pikiran kitalah satu-satunya yang berpengaruh: menentukan “baik” dan “buruk” atau “bahagia” dan “sengsara”. Itu berarti bahwa kekayaan atau kemiskinan (hal-hal di luar kendali) bukanlah kondisi yang mendatangkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Bahagia atau sengsara, menurut Stoisisme, bergantung kepada pikiran kita sendiri sebagai hal di dalam kendali.
Kondisi buruk, dan bahkan ekstrem sekalipun, bisa mendatangkan kebahagian jika pikiran kita mempersepsi bahwa kondisi itu berada di luar kendali lalu fokus kepada hal di dalam kendali. Sebagai contoh, jika dipecat oleh perusahaan, Anda bisa memikirkan hal itu di luar kendali dan kemudian fokus kepada hal di dalam kendali, misalkan ini mungkin kesempatan bagi Anda untuk mengembangkan karier di tempat lain; peluang untuk membuka usaha; lumayan dapat pesangon; atau ini ujian bagi kesabaran dan keuletan.
Jika kamu merasa susah karena hal eksternal, maka perasaan susah itu tidak datang dari hal tersebut. Tetapi oleh pikiran/persepsimu sendiri. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran dan persepsimu kapan pun juga.
Marcus Aurelius, seorang stois yang juga Kaisar Romawi

Dengan dua prinsip dasar tersebut, Stoisisme ingin mengatakan, apa pun yang kita lakukan dalam menginginkan (dan mempertahankan) atau menghindari (dan melawan) sesuatu di luar kendali adalah sebuah kesia-siaan. Filsuf stois memang menyebut ada hal di luar kendali yang lebih disukai atau preffered indifferent, seperti kekayaan dan kesehatan. Disebut demikian karena hal-hal seperti itu bisa menjadi sarana untuk mencapai kebajikan. Tapi, berfokus kepada hal itu tetaplah kesia-sian dan bisa mendatangkan kesusahan karena kekayaan dan kesehatan amat rapuh, bisa lenyap dalam sekejap.
Demikian juga, menghindari kemiskinan, kesusahan, atau kematian (unpreffered indifferent) sama sia-sianya. Sebab, upaya seperti itu bakal mendatangkan kecemasan dan keresahan tak berkesudahan.
Cukup bagi seseorang, menurut para stois, untuk berfokus kepada yang bisa dikendalikan karena kebahagiaan dan ketenangan berasal dari sana. Jika hasil atau tujuan tak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kita bisa mengendalikan pikiran untuk menghasilkan interpretasi yang membuat kita bahagia dan tenang.
Bagi Stoisisme, hal eksternal (di luar kendali) bisa menghambat jalan seseorang menuju kebajikan (virtue). Kebajikan, menurut filsuf stois, adalah “hidup selaras dengan Alam” (dengan “A” besar). Hidup selaras dengan Alam adalah hidup sesuai penciptaan manusia sebagai makhluk bernalar (kira-kira dalam bahasa agama disebut fitrah).
Oleh karena itu, menurut Stoisisme, kebahagiaan dan ketenangan jiwa adalah hasil dari nalar yang sehat. Kondisi ini pada gilirannya akan menghasilkan empat kebajikan (virtue), yakni kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan moderasi (pengendalian diri).
Sebaliknya, kesengsaraan dan kesusahan lahir dari nalar yang sesat. Kondisi ini kemudian akan mendatangkan empat emosi negatif, yaitu kebodohan, kedengkian, ketakutan, dan kemarahan (hilangnya kendali diri).
Ajaran tersebut bisa dibilang cukup revolusioner, setidaknya bagi individu secara internal. Stoisisme bisa menjadi rem bagi manusia yang saat ini dikendalikan oleh hasrat perburuan atas simbol-simbol status sosial.
Di situlah, Stoisisme bisa berperan sebagai katarsis diri dan menjadi suaka bagi jiwa-jiwa yang resah.
Namun, apakah prinsip-prinsip etika Stoisisme bisa peran dalam “mengatasi masalah dunia”, seperti yang diinginkan Henry dalam bukunya? Jawabannya meragukan. Sebab, tercium aroma determinisme atau kepasrahan terhadap realitas eksternal dalam Stoisisme.
“Dikotomi kendali”, misalnya, lahir dari pandangan teologis sebagian filsuf stois bahwa realitas telah ditentukan (predetermined) dan diatur secara kaku dalam sebuah mekanisme interkonektivitas. Alam beroperasi dalam sebuah rancangan keterkaitan antarperistiwa (sebab-akibat), sedemikian rupa sehingga tindakan manusia seakan tak berefek apa pun terhadap mekanisme tersebut.
Sejak dulu para filsuf memperdebatkan persoalan tersebut. Pertanyaan utamanya adalah di manakah peran kehendak-bebas (free will) manusia dalam mekanisme sebab-akibat?
Satu pandangan menilai kehendak-bebas manusia sangat terbatas di hadapan mekanisme sebab-akibat. Mereka memandang mekanisme kausalitas ini bersifat mekanis dan kaku. Tampaknya Stoisisme masuk ke dalam pandangan ini.
Pandangan lain justru menafikan prinsip kausalitas. Bagi pandangan ini, apa pun yang terjadi adalah kebetulan belaka.
Lalu, pandangan ketiga melihat sebab-akibat sebagai sebuah sistem yang luwes, tidak mekanistik. Sebab-akibat dan kehendak-bebas manusia saling mempengaruhi satu sama lain dalam sebuah proses sistemik.
Stoisisme membedakan “hal di dalam kendali” dengan “hal di luar kendali”. Kehendak-bebas manusia berada dalam “hal di dalam kendali”, yaitu pikiran.
Dengan demikian, sebenarnya tak pernah benar-benar ada “hal di dalam kendali” sebab, bagi para stois, yang berpengaruh hanyalah pikiran dan persepsi. Tak ada tindakan manusia yang bisa berdampak terhadap realitas eksternal, kecuali kemampuan pikiran kita dalam mempersepsi apa yang telah ditentukan oleh mekanisme sebab-akibat.
Henry pun sebenarnya mengakui persoalan ini dan mencoba menjawabnya. Dia berupaya membantah penilaian bahwa Stoisisme adalah ajaran kepasrahan total.
Dia menulis, “Di semua situasi, bahkan saat kita merasa tidak ada kendali sekalipun, selalu ada bagian di dalam diri kita yang tetap merdeka, yaitu pikiran dan persepsi.”
Jika dipecat oleh perusahaan, menurut para stois, Anda harus menerima itu sebagai kenyataan di luar kendali. Anda masih bisa mengendalikan pikiran dan mengarahkannya kepada persepsi atas peristiwa itu (misalnya, mungkin ini kesempatan untuk membuka usaha atau setidaknya Anda mendapat pesangon). Tapi, jika Anda berupaya melawan atau mengubah kebijakan perusahaan, upaya Anda akan sia-sia.
Pemecatan memang bisa terjadi karena hal di luar kendali, misalnya bencana alam yang membuat perusahaan merugi dan bahkan bangkrut. Tapi, jika dipecat karena atasan yang dengki atau subjektif, bukankah Anda memiliki pilihan lain daripada sekadar “pasrah”, misalnya menggugat? Apakah opsi menggugat adalah sebuah kesia-siaan? Belum tentu. Kalaupun hasilnya Anda tetap kalah, Anda setidaknya memiliki opsi tindakan daripada sekadar mengendalikan pikiran atau persepsi.
Sejarah menunjukkan bagaimana pilihan tindakan bisa berdampak terhadap realitas eksternal. Kebijakan delapan jam kerja yang kita nikmati saat ini, misalnya, tak akan ada jika kaum buruh hanya pasrah dan tak berdemonstrasi besar-besaran di Lapangan Haymarket, Chicago, pada 4 Mei 1886–yang kemudian memicu kerusuhan dan menewaskan empat buruh (peristiwa ini diperingati sebagai May Day setiap tahunnya). Sistem apartheid di Afrika Selatan mungkin tak akan pernah berakhir jika Nelson Mandela cuma duduk manis di kantor pengacaranya dan tak menggerakkan demonstrasi demi demonstrasi untuk menggulingkan rezim rasis kulit putih.
Jadi, dalam apa yang disebut “hal di luar kendali”, manusia sebenarnya masih memiliki pilihan bebas untuk mempengaruhi prosesnya. Sebab, “hal di luar kendali” itu sebenarnya bisa terjadi karena “metaphysically given” atau “made-man”.3Istilah metaphysically given dan man-made ini dipinjam dari filsuf Objektivisme Ayn Rand dalam esainya “The Metaphysical Versus The Man-Made” yang diterbitkan dalam buku antologi pemikirannya, Philosophy: Who Needs It
Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu “metaphysically given”. Tapi, tragedi jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan pada 26 Maret 2009–yang memicu banjir bandang dan menewaskan 100 orang–itu adalah “man-made”. Sebab, bendungan dirancang untuk tidak jebol dan jika jebol, maka bisa jadi insinyurnya salah kalkulasi atau perawatannya tak diperhatikan (terbukti kemudian ada kelalaian dalam perawatan ketika sisi tanggul yang retak tidak diperbaiki meskipun ada warga yang telah melaporkannya).
Setelah terjadi, tragedi Situ Gintung adalah “takdir” dan memang tak ada yang bisa dilakukan untuk mengubah atau membaliknya. Tapi, sebelum tragedi itu terjadi, manusia memiliki pengaruh terhadap prosesnya. Kelalaian akan membawa proses berujung kepada tragedi sementara ketelitian dan profesionalitas justru akan mencegahnya.
Di sinilah, prinsip sebab-akibat dan kehendak-bebas manusia saling mempengaruhi. Dalam sekuen sebab-akibat, terdapat faktor kehendak-bebas manusia sedangkan kehendak-bebas juga dipengaruhi oleh faktor sebab-akibat.
Tentu saja, tiap-tiap kita tak bertanggung jawab atas kelalaian pengelola tanggul. Tapi, sebagai makhluk sosial (ini juga sebenarnya ajaran Stoisisme), kita bisa menuntut pengelola bertanggung jawab atas kelalaian dan memperbaiki kinerja di masa depan. Di sinilah, tindakan manusia tidak sia-sia atau berpengaruh dalam proses terjadinya “hal di luar kendali”.
Filsuf muslim kontemporer, Murtadha Muthahhari, juga menjelaskan hal tersebut dengan membagi takdir menjadi dua macam: “takdir definitif” (tak dapat diubah) dan “takdir tidak definitif” (dapat diubah). Menurutnya, itulah mengapa ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang bermakna paradoks (seolah-olah bertentangan). Satu kelompok ayat berbicara soal kekuasaan mutlak Tuhan dalam menentukan segala hal sedangkan kelompok ayat lain menyebut bahwa kehendak manusialah yang bisa menggubah keadaan.4Murtadha Muthahhari, Perspektif Al-Quran tentang Manusia dan Agama, (Bandung: Mizan, 1984)
Di sinilah, prinsip “dikotomi kendali” dalam Stoisisme justru tampak kontradiktif dengan prinsip interkonektivitas (sistem sebab-akibat).
Dalam Filosofi Teras, Henry mencoba menjawab kontradiksi ini dengan mengajukan konsep “trikotomi kendali” yang diramu oleh seorang stois modern, William Irvine, dalam A Guide to Good Life: The Ancient Art of Stoic Joy. Selain “hal di dalam kendali” dan “hal di luar kendali”, Irvine menambahkan “hal yang sebagiannya berada di dalam kendali”.
Kategori ketiga tersebut diterapkan Irvine dengan memisahkan tujuan di dalam diri (internal goal) dan hasil di luar diri (external outcome). Internal goal sepenuhnya berada di dalam kendali sementara external outcome di luar kendali. Berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan internal goal (belajar hingga memahami materi ujian) itulah yang harus kita fokuskan sedangkan menjadi resah atau cemas karena memikirkan external outcome (kelulusan) adalah sia-sia dan irasional.
Penjelasan di atas seperti kembali ke titik nol, dimana Stoisisme meyakini tidak ada hubungan “kausal” antara kekuatan tindakan manusia dalam mewujudkan tujuan internal (internal goal) dengan hasil (external outcome). Alhasil, apa yang disebut Irvine sebagai “hal yang sebagiannya berada di dalam kendali” menjadi tak bermakna apa pun. Ini bisa terjadi karena pemisahan (dikotomi atau trikotomi) kaku antara “sistem sebab-akibat” dengan “kehendak-bebas” manusia.
Terlepas dari hal itu, tentu saja “terlalu” memikirkan external outcome adalah irasional dan bisa mendatangkan kecemasan berlebihan. Dalam konteks ini, sekali lagi, Stoisisme harus diakui bisa berdampak positif terhadap respons internal kita atas realitas (bisa menghasilkan ketenangan).
Namun, dampaknya terhadap respons eksternal kita atas realitas patut dipertanyakan. Sebab, seberapa pun maksimal respons eksternal kita, realitas tetaplah di luar kendali.
Modifikasi atau revisi terhadap prinsip Stoisisme memang dilakukan sejumlah penganjur baru filsafat ini, seperti Irvine dan Pigliucci. Namun, profesor filsafat Universitas McGill, Carlos Fraenkel, bertanya, apakah dengan revisi itu prinsip Stoisisme masih bisa dipertahankan? Jika jawabannya “tidak”, lantas apakah semua itu masih bisa disebut “Stoisisme”? Jika jawabannya “ya”, Fraenkel pun tetap ragu apakah “Stoisisme baru” ini menyediakan prinsip-prinsip etika yang tepat untuk menjawab masalah-masalah Abad ke-21.5Carlos Fraenkel, “Can Stoicism Make Us Happy?”, The Nation, diakses dari https://www.thenation.com/article/massimo-pigliucci-modern-stoicism-book-review/, pada 21 Oktober 2019.
Karena prinsip “dikotomi kendali” bertentangan dengan prinsip “interkonektivitas”, maka prinsip “indifferent” juga kontradiktif dengan prinsip “interkonektivitas”. Bagaimana mungkin impresi (atas realitas eksternal) tak berpengaruh terhadap interpretasi (oleh pikiran) jika semua hal di alam ini saling berkaitan? Bagaimana mungkin impresi bisa dipandang “netral” atau “bebas nilai”, dan “baik-buruk” hanya bergantung kepada interpretasi?
Sebagai praktisi periklanan, Henry pasti paham betul bahwa impresi itu tidak “bebas nilai”. Iklan, misalnya, bisa menciptakan impresi “baik” atas produk barang dan jasa yang sebenarnya berkualitas “buruk”, sehingga bisa menghasilkan interpretasi “baik” pula.
Contohnya adalah kiat praktis yang diajukan Henry: S-T-A-R (Stop, Think and Assess, Respond). Dengan S-T-A-R, menurut Henry, seseorang semestinya bisa menghindari intepretasi spontan atas sebuah impresi (peristiwa yang terjadi). Jika mau, dia bisa memeriksa peristiwa itu dan kemudian memutuskan makna apa yang ingin dia berikan. Henry pun membedakan interpretasi atas sebuah peristiwa menjadi interpretasi otomatis (kira-kira tanpa nalar) dan interpretasi rasional (dengan nalar).
Karena mesti rasional, maka sebenarnya interpretasi tak bisa semau gue. Interpretasi justru tak bisa terlepas dari kaidah-kaidah berpikir rasional (koherensi logis). Demikian juga, impresi mesti diperiksa kesesuaiannya dengan kenyataan (korespondensi empiris).
Henry memberi contoh tentang kemacetan lalu lintas yang dulu kerap membuatnya marah-marah. Lalu, setelah mempelajari Stoisisme, dia menerapkan S-T-A-R seperti berikut.
- Stop: begitu kita terjebak dalam kemacetan, dan merasakan emosi negatif, berhenti dulu, jangan terlanjur terbawa perasaan!
- Think and Assess: berpikir dan menilai kemacetan ini di luar kendali kita. Karena demikian, mengapa kita mesti gusar dan marah-marah karena toh emosi tidak akan mengubah situasi.
- Respond: karena kemacetan di luar kendali, maka tak usah gusar, isi waktu dengan membaca e-book saja, sehingga kemacetan menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri (membaca).
S-T-A-R di atas bisa sangat berguna untuk menenangkan perasaan dan pikiran tapi tak bisa bergerak lebih jauh daripada itu. Bayangkan jika peristiwa yang terjadi lebih besar–atau lebih mengubah kehidupan–daripada sekadar kemacetan.
Kita juga bisa meningkatkan skala kemacetan ini ke level sosial atau publik. Sebab, kemacetan toh sebenarnya “man-made”. Ia bisa disebabkan oleh kebijakan manajemen lalu lintas yang buruk, ketiadaan transportasi massal, atau karena ada sekelompok orang yang menggunakan badan jalan bukan demi kepentingan publik (perayaan, konser musik, atau iring-iringan motor gede).
Pertanyaannya, dalam konteks kemacetan seperti itu, apakah S-T-A-R yang Henry lakukan cukup menjadi respons eksternal. Jawabannya “tidak cukup”, terkecuali jika kita memutuskan untuk menjadi makhluk anti-sosial.
Contoh peristiwa lain, yakni ujaran kebencian terhadap kelompok dan golongan tertentu di masyarakat, seperti “bunuh”; “bakar”; “serang”; dan “usir” (ujaran kebencian tak sesederhana yang dibayangkan banyak orang, harus mengandung kata-kata kekerasan seperti itu). Mari kita menggunakan kiat S-T-A-R.
- Stop: begitu mendengar ujaran kebencian, kita merasakan emosi negatif, seperti marah. Berhenti dulu, jangan terlanjur terbawa perasaan seperti itu! Jika kita mengungkapkan langsung kemarahan saat itu juga, itu tak akan mengubah situasi, dan bahkan bisa memperburuknya.
- Think and Assess: berpikir dan memeriksa apakah ujaran kebencian itu benar-benar terjadi, apa pemicunya, siapa pelakunya. Kita lalu menyadari ujaran seperti itu tak boleh dianggap wajar dan dibiarkan. Ia bisa merusak ikatan antarwarga dan memicu kerusuhan sosial.
- Respond: karena ujaran kebencian itu man-made dan bukan metaphysically given, maka ia bisa dicegah dan diperbaiki. Kita bisa memilih tindakan yang akan kita ambil sesuai kapasitas, seperti memberi pencerahan kepada masyarakat–atau orang-orang terdekat–bahwa ujaran seperti itu bisa merusak keharmonisan hidup dan dilarang oleh hukum; atau melaporkan pelakunya kepada aparat penegak hukum.
Jadi, seharusnya ada dua respons yang dihasilkan dari proses interpretasi rasional (koherensi logis) atas impresi yang telah terverifikasi (korespondensi empiris): respons internal dan eksternal. Secara internal, interpretasi kita bisa mengerem spontanitas (entah marah, gusar, kecewa, atau takut) dan membantu kita memikirkan tindakan-tindakan yang terukur. Secara eksternal, kita tidak cuek dengan peristiwa yang terjadi. Bisa jadi peristiwa itu suatu saat menimpa kita karena manusia adalah makhluk sosial yang saling terhubung satu sama lain.
Mungkin kita akan berpikir, bukankah respons seperti itu justru akan mendatangkan kecemasan dan ketakutan, apalagi jika pelaku ujaran kebencian adalah orang yang berpengaruh di masyarakat, entah secara sosial, ekonomi, maupun politik? Bisa jadi ketakutan dan kecemasan itu tidak hilang. Tapi, apa yang salah dengan “takut” dan “cemas” (dan emosi-emosi lainnya seperti bersedih dan menangis) selama semuanya terukur, tidak berlebihan. Toh, kecemasan dan ketakutan adalah karakter alamiah manusia (selaras dengan Alam).
Justru, sudah banyak bukti bahwa kebahagiaan datang ketika manusia melampaui ketakutan dan kecemasaannya demi melakukan kebaikan dan memperjuangkan keadilan. Kita juga kadang merasakan kebahagiaan selepas bersedih dan menangis.
Dalam Filosofi Teras, Henry berharap Stoisisme bisa dibawa ke ranah sosial dan berkontribusi “mengatasi persoalan dunia”. Sayangnya, prinsip dasar filsafat ini (“dikotomi kendali” dan “indifferent”) tidak menopang harapan itu. Karena dua prinsip tadi, Stoisisme hanya bisa diarahkan kepada kebajikan-kebajikan individual, seperti tidak berbuat jahat kepada orang lain, jujur, atau tidak rakus dengan kekayaan (sampai-sampai korupsi)–hal yang sebenarnya juga penting dilakukan.
Henry sendiri mengakui bahwa sebagian stois tak menyentuh persoalan-persoalan besar dunia saat mereka berbicara tentang Stoisisme.
Dia menulis:
Tidak semua pemikir dan praktisi Filsafat Teras memiliki satu pemahaman menyangkut masalah-masalah besar dunia seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, rasisme, atau kemiskinan. Sebagian menginterpretasikan filosofi ini sebagai hanya mementingkan kualitas dari hal-hal yang ada di dalam diri kita. Kualitas karakter, moral, dan persepsi kita sudah cukup menjadi pusat perhatian kita. Segala hal eksternal dianggap sebagai indifferent yang tidak perlu mendapatkan prioritas perhatian kita. Karenanya, segala urusan dunia eksternal (termasuk masalah lingkungan dan sosial) dianggap tidak menjadi tanggung jawab, apalagi kewajiban seorang praktisi Stoisisme…sebagian pemikir dan praktisi Stoisisme lainnya mengambil interpretasi berbeda…saya mengambil posisi yang sama dengan kelompok yang percaya bahwa mempraktikkan Stoisisme artinya juga peduli pada masalah dunia dan umat manusia, dan sebisa mungkin berkontribusi dalam solusinya.
Henry tidak sendirian. Eric Scott, seorang profesional di bidang IT, juga menyampaikan harapan yang sama saat menulis dalam sebuah blog tentang Stoisisme modern.6Eric Scott, “Stoics Do Care about Social Justice: A Response to Irvine”, Modern Stoicism, diakses dari https://modernstoicism.com/stoics-do-care-about-social-justice-a-response-to-irvine-by-eric-o-scott/, pada 21 Oktober 2019 Dalam tulisan itu, Scott mengungkapkan kecemasannya terhadap pandangan stois lainnya, William Irvine, ketika nama terakhir menyampaikan presentasi dalam Stoicon 2016 di New York.
Irvine menjelaskan bahwa Stoisisme bisa mengajarkan orang menjadi tangguh dalam menghadapi ketidakadilan. Ketidakadilan bagi para stois tidak akan berdampak apa pun secara emosional. Sikap pasifis, menurut Irvine, bisa melindungi orang dari gangguan emosional.
Irvine tidak hanya menganjurkan pasifisme tapi lebih jauh merisak para aktivis keadilan sosial. Menurut Irvine, ketidakadilan sosial sistemik yang coba dibongkar para aktivis itu hanyalah produk imajinasi dari lemahnya penalaran. Dia bahkan menyebut aktivisme cuma buah dari hipersensitivitas para aktivis.
Dalam bukunya A Slap in the Face: Why Insults Hurt–And Why They Shouldn’t, Irvine menulis sebagai berikut:
Jika filsuf stois, Epictetus, masih hidup untuk menyaksikan maraknya undang-undang anti-kebencian, dan secara lebih umum, gerakan kebenaran politik (political corectness movement), ia akan menggelengkan kepala, tak percaya. Menurutnya, cara terbaik untuk menyelamatkan orang dari rasa sakit karena terhina adalah tidak mengubah dunia sehingga mereka tidak pernah merasa terhina; melainkan mengubah orang sehingga mereka, pada dasarnya, kebal terhadap penghinaan.
Bagi Scott, cara pandang semacam itu hanya akan memperkuat anggapan bahwa Stoisisme pada dasarnya tidak tertarik kepada isu-isu keadilan sosial. Bahkan, Stoisisme modern tidak hanya akan jauh dari aktivisme sosial tapi juga memusuhi penderitaan dan keprihatian kaum marginal.
Dalam ceramahnya di College de France pada sekitar 1980-an, The Hermeneutics of the Subject–yang kemudian ditranskrip dan diterbitkan pada 2005–filsuf Perancis, Michel Foucault, menilai Stoisisme klasik (terutama yang berkembang di era Romawi Kuno) memang hanya berfokus kepada persoalan “diri saya” (myself). Karenanya, Foucault menilai Stoisisme punya kontribusi signifikan bagi perkembangan filsafat Subjektivisme dalam sejarah peradaban Barat.
Dengan demikian, Henry dan Scott tampaknya mewakili tafsir progresif atas Stoisisme klasik. Jika dibandingkan dengan tafsir Irvine, keduanya seperti telah “melampaui Stoisisme”.[]
(Foto utama: Stoa Attalus di Athena, Yunani, oleh Gertjan R. Sumber: Wikipedia.org)


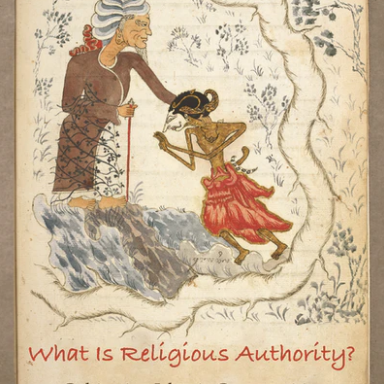




🙂 Tulisan yang bagus. Barangkali tertarik juga membaca info-info tentang stoisisme dari blog yang telah terkurasi KaryaKarsa ini:
-Kaum Stoa penganut Stoisisme, Pengguna Istilah “Logika” Pertama Kali
https://rk-awan.blogspot.com/2019/10/kaum-stoa-stoisisme-pengguna-istilah-logika-pertama-kali.html
-Marcus Aurelius, penganut Stoisisme yang pernah menjadi “Kaisar Bersama” Romawi, dan saat meninggal “diangkat menjadi Dewa” oleh Senat Romawi
https://rk-awan.blogspot.com/2019/10/meditations-patung-berkuda-kaisar-bersama-marcus-aurelius.html