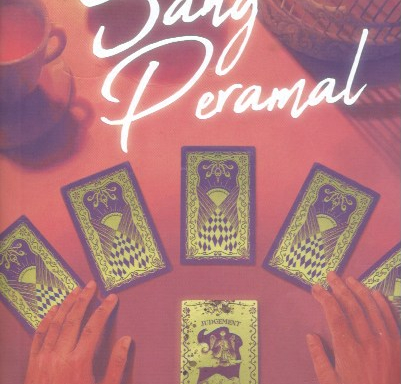Lebih daripada sekadar urban thriller, novel karya Chandra Bientang ini mengetengahkan dilema moral manusia; batas-batas tipis antara kewarasan dan kegilaan.
PEMBUNUHAN berantai terjadi di bilangan Jatinegara, Jakarta Timur. Korbannya anak-anak jalanan. Mayat-mayat mereka dipamerkan bak karya seni: digantung di flyover dan tiang listrik.
Nyaris tak ada yang terlampau peduli. Tak ada juga media yang menyelidiki. Pers lebih asyik memberitakan penikahan atau perceraian selebritas, tingkah lagu selebgram, atau silat lidah para politisi.
Hanya seorang yang peduli. Namanya Elang. Dia kadet polisi yang mangkir dari Akademi Kepolisian. Ia mengendus kejanggalan. Baginya, rentetan peristiwa itu bukan kematian biasa, seperti perkelahian antaranak jalanan. Ada perburuan terhadap anak-anak itu, pikir Elang.
Begitulah latar peristiwa Dua Dini Hari karya Chandra Bientang. Novel ini disebut sebagai debut Bientang meskipun pada 2019 dia pernah menulis cerita pendek Anak Kucing Leti, karya yang membuatnya terpilih sebagai salah satu Penulis Emerging Indonesia 2019 dalam ajang Ubud Writers and Readers Festival. Lewat Dua Dini Hari, nama Bientang semakin moncer. Novel ini meraih dua penghargaan Scarlet Pen Award 2020 sebagai “Best Novel dan “Best Crime Drama & Thriller”. Bientang sendiri dinobatkan sebagai “Author of the Year”.

- Judul Buku: Dua Dini Hari
- Penulis: Chandra Bientang
- Penerbit: Noura Books
- Terbit: Agustus 2019
- Tebal: 248 halaman
Lantas, apakah kita telah menemukan Agatha Christie versi Indonesia? Ataukah setidaknya penerus ratu penulis thriller kriminal Indonesia era 1980-an, S Mara Gd?
Di awal buku, anda setidaknya akan merasakan seperti itu. Dua Dini Hari membawa anda ke peristiwa pembunuhan demi pembunuhan mengerikan; suasana “perkampungan” di Jatinegara yang muram, seakan anda membayangkan Gotham City yang gelap dalam trilogi Dark Knight Christopher Nolan; dan misteri demi misteri yang disimpan rapat-rapat nyaris setiap karakter dalam novel.
Tapi, anda kemudian akan tersadar. Ini bukan sekadar thriller, kisah kriminal, atau cerita detektif. Ini lebih daripada itu.
Dua Dini Hari tak mengajak anda terlibat dalam penyelidikan induktif atas bukti-bukti empiris ala Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle) atau menyelami alam pikir deduktif Hercule Poirot (Agatha Christie). Alih-alih demikian, novel ini mengundang anda ke batas-batas tipis antara kewarasan dan kegilaan; kepada dilema moral manusia. Ia bukan sekadar thriller tapi novel filosofis.
Pertanyaan utamanya, apakah kita bisa dibenarkan membunuh segelintir kehidupan demi menyelamatkan nyawa yang lebih banyak – apalagi yang segelintir itu “cuma” anak-anak jalanan yang tak jelas identitas dan asal usulnya? Ini dilema klasik moral manusia yang tergambar dalam pergulatan filosofis antara dua pandangan etika: utilitarianisme versus deontologi.
Pada 1967, filsuf Inggris Philippa Foot memperkenalkan model eksperimen untuk menggambarkan dilema tersebut. Model itu diberi nama “Problem Troli”.
Gambaran umumnya begini. Ada sebuah troli meluncur tanpa kendali di atas rel. Di depannya ada lima orang terikat; tak bisa bergerak. Troli akan langsung membunuh kelima orang itu. Lalu anda sendiri berdiri agak jauh dari troli, di dekat tuas pengendali rel. Jika anda menarik tuas itu, troli akan meluncur ke trek yang berbeda. Tapi, di atas trek ini, ada satu orang, juga terikat tak bisa bergerak. Anda hanya dua pilihan: tidak melakukan apa-apa, sehingga troli akan membunuh lima orang. Atau anda menarik tuas, sehingga troli “cuma” membunuh satu orang. Yang manakah di antara dua pilihan itu yang benar?
Pandangan etika utilitarian akan memilih yang kedua, bahkan meski perbandingannya membunuh 1.000.000 nyawa demi menyelamatkan 1.000.001 nyawa. Bagi pandangan ini, benar-salahnya perbuatan seseorang ditentukan oleh baik-buruknya hasil atau tujuan. Karenanya, menurut mereka, tujuan menghalalkan cara.
Sebaliknya, bagi etika deontologis, benar-salahnya perbuatan seseorang mesti dinilai berdasarkan perbuatan itu sendiri, terlepas dari apa konsekuensi atau tujuannya. Karenanya, bagi pandangan ini, membunuh tetaplah buruk terlepas dari apa pun tujuannya.
Dalam sejarah, para penguasa kerap menggunakan dalih etis utilitarianisme demi menjustifikasi kebijakan mereka. Eks Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, misalnya, pernah mengatakan dia lebih baik membunuh 1.000 orang demi menyelamatkan 250 juta orang. Jauh sebelum Basuki, utilitarianisme pernah dipraktikkan dalam kebijakan klandestin pada periode 1983-1985, yang kemudian tenar dengan sebutan “Penembakan Misterius” atau Petrus. Tanpa proses peradilan, sekitar 2.000 hingga 10.000 (tak pernah ada angka yang secara resmi diakui) bramacorah, gali, begal, dan penjahat kelas teri diburu dan dibunuh dalam gaya eksekusi; dengan tangan dan leher terikat. Mayat-mayat mereka kemudian dibuang begitu saja di depan rumah, pinggir jalan, sawah, kali, dan hutan.
Kebijakan tersebut berdalihkan etika utilitarian. Dalam biografinya Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (Ramadhan, KH: 1989), Soeharto sendiri mengatakan:
“Yang melawan, mau tidak mau, harus ditembak. Karena melawan, mereka ditembak. Lalu, ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk shock therapy, terapi goncangan. Ini supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas perikemanusiaan itu. Maka, kemudian meredalah kejahatan-kejahatan yang menjijikkan itu.”
Ketua MPR saat itu, Amir Machmud, membela cara-cara Orde Baru menggelar Operasi Celurit (nama resmi Petrus). Dia mengatakan, “Setuju mengenai adanya penembak-penembak misterius dalam menumpas pelaku kejahatan. Demi untuk memberikan rasa aman kepada 150 juta rakyat Indonesia, tidak keberatan apabila ratusan orang pelaku kejahatan harus dikorbankan.” (Sinar Harapan, 21 Juli 1983)
Dilema moral itulah yang dihadirkan Bientang dalam “Dua Dini Hari”. Anak-anak jalanan harus disingkirkan demi menjaga kewarasan dan ketertiban kota. Lagipula, siapa yang bakal peduli dengan mereka; anak-anak dekil, bau, dan kasar. Toh, bukankah mereka juga merugikan kota: membuat macet, mengganggu pemandangan, atau bahkan mencopet serta merampok?
“Dua Dini Hari” tak akan memberi anda akhir hitam-putih tentang dilema itu. Seperti juga dalam “Problem Troli”, dimana perbedaan pilihan si pemegang tuas amat tipis, begitu pula tipisnya perbedaan antara yang “waras” dan “gila” dalam novel ini. Yang tampak gila kadang menyuarakan kebenaran sedangkan yang mengklaim waras justru melakukan kegilaan.
Pada akhirnya, setipis apa pun jarak benar-salah dan baik-buruk, setiap perbuatan tetaplah memiliki konsekuensi moral. Terpecahkannya misteri dalam novel ini bukanlah akhir dari cerita. Ia justru awal dari sebuah lingkaran setan; konsekuensi moral tadi: dimana dusta meniscayakan dusta berikutnya.[]