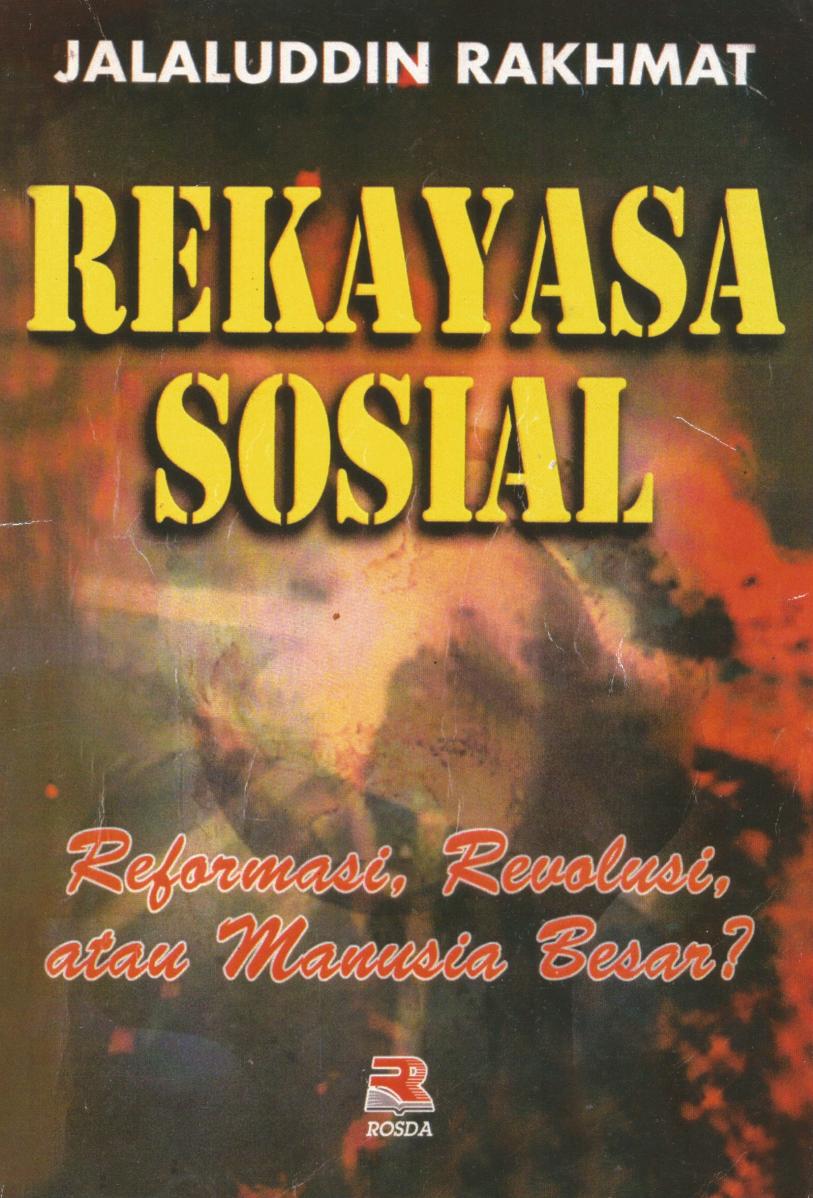Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar (1999) menghimpun kuliah Jalaluddin Rakhmat sejak akhir 1980-an hingga 1990-an di hadapan mahasiswa dan aktivis LSM. Buku ini memberi gambaran pemikiran Jalaluddin pada masa awal Reformasi.
REKAYASA Sosial: Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar adalah buku karya Jalaluddin Rakhmat. Diterbitkan pada Juni 1999 oleh Remaja Rosdakarya, Bandung, buku ini kumpulan kuliah Jalaluddin—atau akrab disapa Kang Jalal—pada dekade akhir 1980-an hingga 1990-an. Menurut Jalaluddin, dia menyampaikan kuliah (atau yang dia sebut juga “pengajian”) bertema “Rekayasa Sosial” berpindah-pindah dari satu mesjid ke mesjid lain di Bandung hingga berakhir di lembaga yang dia kelola: Yayasan Muthahhari. Pesertanya terutama mahasiswa dan aktivis LSM yang mungkin pada saat itu terlibat dalam demonstrasi menentang kekuasaan Soeharto.
Buku ini memberi gambaran umum tentang gagasan Jalaluddin menjelang dan setelah Reformasi 1998. Jalaluddin sendiri pribadi cukup kaya dan menarik. Sebagai ilmuwan sosial, terutama komunikasi, dia menulis Psikologi Komunikasi, buku yang menjadi rujukan utama mahasiswa psikologi dan komunikasi. Aktivitas akademik tak menghentikannya menjadi cendekiawan muslim. Dia kerap melontarkan gagasan baru dalam wacana keislaman. Usai reformasi, Jalaluddin lebih lekat dengan citra sebagai pemimpin organisasi muslim. Dia sempat melipir ke jalur politik menjadi politisi di DPR (2014-2019) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
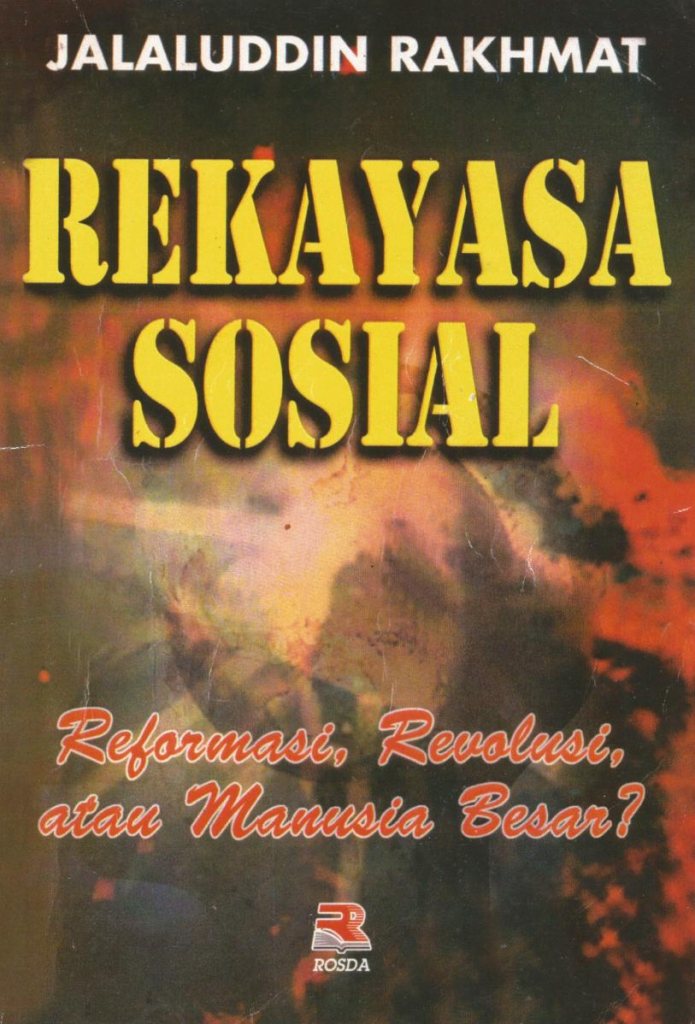
- Judul Buku: Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar?
- Penulis: Jalaluddin Rakhmat
- Penerbit: Remaja Rosdakarya
- Terbit: Juni 1999
- Tebal: xxi + 225 halaman
Isi Buku
Buku ini dimulai dengan pembahasan kerancuan berpikir dan mitos. Jalaluddin menyatakan, perubahan sosial yang bergerak melalui rekayasa sosial harus dimulai dengan perubahan cara berpikir (hal. 3). Di era Orde Baru dan hingga kini, menurutnya, “pengacauan intelektual” kerap terjadi, dan dilakukan dengan cara halus. Para pejabat seringkali menyampaikan pernyataan-pernyataan yang jatuh ke dalam “kebuntuan intelektual” (intellectual cul-de-sac).
Dia lalu membagi apa yang disebutnya sebagai “kebuntuan intelektual” dalam sejumlah kesalahan berpikir.
Fallacy of Dramatic Intense: ini diawali dengan kecenderungan over-generalisation. Satu atau dua kasus pengalaman empiris digunakan untuk mendukung argumen bersifat umum. Contohnya, anggapan bahwa kemiskinan disebabkan oleh kemalasan, kebodohan, dan ketidaktekunan. Anggapan ini mencoba membantah teori “kemiskinan struktural”, yang mengatakan kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan struktur ekonomi. Jatuh ke dalam fallacy of dramatic intense, anggapan ini lalu mengambil contoh seorang buruh berpenghasilan kecil yang akhirnya menjadi pengusaha karena bekerja keras, tekun, dan tabah. Jelas, ini kesalahan dari sebuah contoh dramatis pengalaman pribadi yang di-over-generalisasikan kepada kasus-kasus lain yang bercakupan lebih luas (hal. 6).
Fallacy of Restrospective Determinism: ini kecenderungan untuk berargumen bahwa masalah sosial yang ada sekarang sudah ada sejak dulu, sehingga tak bisa dihindari. Misalnya, karena sudah ada sejak zaman baheula, maka pelacuran tak bisa dibasmi. Yang bisa kita lakukan hanya melokalisasinya, agar dampak-dampaknya tidak meluas. Argumen seperti ini melihat masalah sosial sebagai sesuatu yang sudah ditakdirkan (determined) dengan melihat ke masa lalu.
Post Hoc Ergo Propter Hoc: secara harfiah artinya, sesudah itu—karena itu—oleh sebab itu. Di sini, maksudnya adalah kecenderungan membangun argumen sebab-akibat hanya berdasarkan urutan temporal peristiwa. Yang datang pertama sebagai sebab sedangkan yang datang kemudian menjadi akibat. Kerancuan berpikir model begini banyak dilakukan pejabat secara halus. Misalnya, dia mengatakan bahwa setelah pemerintahannya berkuasa, kemiskinan turun atau daya beli meningkat, padahal penyebabnya belum tentu kekuasaannya. Lalu contoh lain yang kerap terdengar pada era reformasi adalah pernyataan bahwa reformasi membuat harga sembako naik. Menurut argumen ini, justru karena reformasilah, ekonomi rusak.
Fallacy of Misplaced Concretness: kerancuan berpikir ini muncul karena seseorang mengkonkretkan sesuatu yang pada hakikatnya abstrak. Misalnya, jika terjadi bencana alam atau wabah, seorang pejabat mengatakan itu semua sudah takdir Tuhan. Dalam istilah logika, Jalaluddin menyamakan kerancuan berpikir ini dengan reification, atau menganggap real sesuatu yang hanya berada dalam pikiran kita. Argumentasi seperti ini, menurut Jalaluddin, membuat kita tak mampu merumuskan solusi konkret. Persoalan atau pembahasannya selesai sampai di situ. Oleh sebab itu, pemikiran seperti ini kita sebut intellectual cul-de-sac (hal. 16).
Argumentum ad Verecundiam: berargumen dengan menggunakan otoritas, padahal otoritas itu tak relevan atau ambigu. Misalnya, orang berargumen dengan mengutip teks suci demi membela kepentingannya. Padahal, yang dia ajukan sebenarnya bukan otoritas teks suci itu tapi pemahamannya akan teks suci. Sebab, orang lain belum tentu memahami teks suci seperti pemahamannya. Inilah yang disebut dengan otoritas ambigu. Orang yang mengutip teks suci demi membenarkan argumennya, menurut Jalaluddin, memiliki tendensi untuk membungkam lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya membantah, dia akan mengkafirkannya. Padahal, yang lawan bicaranya bantah bukanlah otoritas teks suci itu tapi penafsirannya. Kalaupun mengutip teks suci, seseorang bisa mengatakan, menurut saya, sehingga ia membuka bagi kemungkinan adanya penafsiran dan pemahaman berbeda. Ia tak mengklaim otoritas itu untuk diri dan kepentingannya sendiri.
Fallacy of Composition: kecenderungan untuk berasumsi bahwa yang baik dan manjur bagi seseorang atau sekelompok orang adalah juga pasti baik dan manjur bagi yang lain secara keseluruhan. Contohnya bisa dilihat dalam banyak fenomena sosial. Misalnya, ketika satu atau sekelompok orang sukses menjadi ojek, maka berbondong-bondong orang beralih profesi menjadi ojek.
Circular Reasoning: argumen berputar, yakni menggunakan kesimpulan untuk mendukung asumsi, yang kemudian menujuk kepada kesimpulan semula. Jalaluddin mengajukan contoh dalam dialog berikut.
Mahasiswa: apabila organisasi dikembangkan dengan baik, maka program transmigrasi akan berjalan lancar.
Dosen: apa bukti organisasi itu dikembangkan dengan baik?
Mahasiswa: kalau programnya lancar
Dosen: apa arti program lancar?
Mahasiswa: kalau pengembangan organisasinya baik.
Selain kerancuan atau kebuntuan berpikir, mitos sosial, menurut Jalaluddin, juga bakal menghambat perubahan sosial melalui rekayasa sosial. Mitos tersebut dia bagi dua, yakni (1) mitos deviant; dan (2) mitos trauma.
Mitos deviant: ini berawal dari pandangan fungsionalisme struktural, yakni bahwa masyarakat itu stabil, statis, dan tidak berubah. Segala sesuatu dalam masyarakat memiliki fungsi dan manfaatnya. Jika terjadi perubahan, maka perubahan itu dipandang sebagai penyimpangan terhadap stabilitas. Orang miskin dikatakan tetap memiliki fungsi di masyarakat. Orang miskin berfungsi melakukan pekerjaan kotor dan berbahaya yang tak mungkin dilakukan orang kaya. Jadi, menurut pandangan ini, mengentaskan kemiskinan berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat.
Jalaluddin berpendapat, fungsionalisme struktural tak bisa digunakan untuk menganalisis dinamika sosial. Jika menggunakan fungsionalisme struktural, kita justru akan menjadi anti-perubahan dan pro-status quo.
Mitos trauma: ini mengatakan bahwa setiap perubahan pasti mendatangkan krisis (trauma). Krisis ini lalu memicu reaksi anggota masyarakat. Reaksi itu pada gilirannya bakal menimbulkan masalah sosial. Jadi, masalah sosial justru terjadi karena perubahan sosial.
Mitos ini didasarkan pada teori cultural lag (kesenjangan budaya) dari William F Ogburn dan Meyer F Nimkoff. Menurut keduanya, cultural lag terjadi apabila satu aspek kebudayaan mengalami perubahan sebelum atau dalam derajat yang lebih besar ketimbang yang terjadi pada aspek lain. Akibanya, terjadi ketakseimbangan dan ketaksesuaian dalam jalinan kebudayaan.
Jalaluddin membantah teori tersebut. Pertama, tak setiap perubahan menimbulkan goncangan. Ada perubahan yang malah disambut dengan gembira, dan bahkan diharap-harap masyarakat. Kedua, perubahan akan ditolak masyakat apabila mengancam basic security (rasa aman, rasa tenteram yang sangat dasar). Ancaman terhadap basic security juga sangat bergantung kepada persepsi individu-individu dalam masyarakat.
Dia lalu mengutip ayat al-Quran, “Kami turunkan pada setiap kaum seseorang yang memberi peringatan, maka selalu saja orang kaya dari kaum itu mengatakan, ‘Kami kafir dengan apa-apa yang diturunkan Tuhan kepadamu.’” Menurut Ali Syari’ati yang menafsirkan ayat ini, semua orang kaya atau kelas kapitalis akan terus merintangi setiap perubahan. Namun, Murtadha Muthahhari mengatakan, penentangan tidak hanya akan datang dari semata kelas kapitalis tapi siapa pun yang mempersepsi perubahan bakal mengancam stabilitas dan kemapanan status quo. Jika mempersepsi perubahan itu akan menguntungkan mereka, kelas kapitalis justru akan mendukungnya. Karena itu, penentangan terhadap perubahan sosial bukan soal kapitalis atau proletar, tapi persepsi ancaman terhadap basic security.
Jadi, orang atau masyarakat akan menolak perubahan apabila muncul hal-hal berikut: pertama, perubahan itu diduga/dipersepsi mengancam basic security; kedua, perubahan itu tidak dipahami dengan baik dan meliputi berbagai ketidakpastian; ketiga, dirasakan adanya paksaan kepada mereka; keempat, dianggap bertabrakan dengan nilai atau norma yang lebih tinggi; kelima, tidak sesuai dengan kalkulasi rasional… (hal. 31-32).
Pada Bab II, Jalaluddin mulai membahas mengapa kuliahnya (dan buku ini) diberi judul “rekayasa sosial”. Dia memandang ada dua model perubahan sosial. Pertama, yang tak direncanakan, dan ini berlangsung terus dalam masyarakat secara perlahan. Kedua, yang direncanakan. Perubahan model kedua ini juga dirumuskan oleh para pemikir dalam beberapa istilah. M.N. Ross menyebutnya dengan social planning. Lalu, Ira Kaufman mengistilahkannya dengan change management. Kemudian Less dan Presley menamakannya social engineering. Istilah terakhir ini yang menjadi pilihan Jalaluddin.
Setiap perubahan sosial, menurutnya, memiliki sejumlah aspek: faktor penyebab, agen, waktu atau durasi, dan juga dampak. Sepanjang sejarah, ada beberapa teori yang mencoba menetapkan sebab perubahan sosial. Max Weber misalnya percaya bahwa perubahan sosial didorong oleh ide. Dalam The Sociology of Religion dan The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Weber mengakui peran besar ideologi sebagai variabel independen bagi perkembangan masyarakat (hal. 47).
Jalaluddin sendiri menjelaskan bagaimana Al-Quran memengaruhi ide dalam perkembangan masyarakat Arab di awal Islam. Kitab suci itu memperkaya makna idiom-idiom yang sudah ada. Misalnya, kata taqwa yang awalnya hanya bermakna ‘takut’ diperkaya maknanya oleh Al-Quran. Di sini, menurut Jalaluddin, Al-Quran melakukan perubahan sosial melalui ide. Bahkan, secara keseluruhan, Al-Quran menaruh perhatian besar kepada pembaruan ide.
Teori kedua mengatakan bahwa sebab atau pendorong perubahan adalah tokoh besar, yang kerap juga disebut heroes (pahlawan). Salah satu pengusung teori ini adalah Thomas Carlyle. Dalam bukunya On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History, Carlyle menulis, “Sejarah dunia… adalah biografi orang-orang besar.” Tokoh besar atau pahlawan ini mampu memikat dan menarik perhatian anggota masyarakat untuk menjadi pengikut setianya, dan kemudian bersama-sama melancarkan gerakan.
Teori ketiga berpendapat perubahan sosial didorong oleh sebuah gerakan sosial (social movement). Organisasi-organisasi masyarakat madani, seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan yayasan bisa menjadi penggerak gerakan sosial ini.
Menurut Jalaluddin, sebenarnya Orde Baru sendiri melakukan rekayasa sosial melalui apa yang disebut “ideologi pembangunan”, atau developmentalisme. Rekayasa sosial model begini banyak terjadi di negara-negara “Dunia Ketiga” mulai era 1970-an. Salah satu konsep developmentalisme ini adalah modernisasi, atau bagaimana mengubah nilai-nilai tradisional yang berlaku di masyarakat dengan apa yang dianggap sebagai nilai-nilai modern.
Biasanya metode yang ditempuh adalah dengan mengubah struktur dan sistem ekonomi. Karena itu, para pengusung developmentalisme lazim bersandar pada Ekonomi Klasik. Dan Orde Baru, menurut Jalaluddin, menjadikan Ekonomi Klasik, khususnya Teori Pertumbuhan Rostow, sebagai cetak biru pembangunan ekonomi Indonesia selama 32 tahun.
Konsep lain developmentalisme adalah teori kebergantungan, yang menemukan bentuknya di Amerika Latin pada 1950-an. Teori ini berasumsi bahwa keterbelakangan negara-negara “Dunia Ketiga” tak hanya disebabkan oleh faktor internal, tapi juga oleh banyaknya rintangan eksternal. Salah satu pencetus teori ini adalah Paul Prebisch. Bagi Prebisch, ekonomi dunia ini terbagi menjadi menjadi “pusat” yang merupakan negara industri maju dan “pinggir”, yang kebanyakan merupakan negara agraris. Dia bilang, “pinggir” selalu memerlukan bantuan “pusat”.
Konsep terakhir dari developmentalisme adalah teori pembangunan ekonomi global. Menurut teori ini, perubahan sosial dilakukan melalui rekayasa sistem ekonomi dan politik global.
Terdapat sejumlah strategi untuk melakukan perubahan sosial. Pertama, strategi normative-reeducative. Normative adalah kata sifat dari norm atau norma, yang berarti aturan yang berlaku di masyarakat. Norma ini terpatri dalam masyarakat melalui pendidikan. Karena itu, strategi ini berupaya mengubah paradigma berpikir lama masyarakat dan menggantinya dengan yang baru melalui jalan reeducation (pendidikan-ulang). Strategi ini tentu saja tak langsung menunjukkan hasil karena bertahap.
Strategi kedua adalah strategi persuasif. Strategi ini mencoba membentuk opini dan pandangan masyarakat. Dalam strategi ini, peran media massa sangat besar. Seperti halnya strategi normative-reeducative, strategi persuasif ini juga akan berlangsung bertahap.
Strategi terakhir adalah strategi dengan kekuasaan atau kekuatan (power strategy). Bentuknya adalah revolusi atau peopel’s power. Menurutnya, inilah puncak dari semua bentuk perubahan sosial. Sebab, revolusi menyentuh segala sudut dan dimensi sosial secara radikal, massal, cepat, mencolok, dan mengundang gejolak intelektual dan emosional dari semua orang yang terlibat di dalamnya (hal. 53).
Namun, sebelum melakukan rekayasa sosial, kita harus lebih dulu mengenali apa itu problem sosial dan membedakannya dari problem individual. Tanpa ini, maka alih-alih melakukan rekayasa sosial untuk menyelesaikan problem sosial, kita mungkin malah menambah problem sosial baru.
Jalaluddin memahami problem sebagai perbedaan antara das Sollen (yang seharusnya) dengan das Sein (yang terjadi). Misalnya, kita mendamba sebuah sistem yang adil tetapi yang kita dapat sistem yang lalim. Kita mengharapkan rezim yang peka terhadap aspirasi rakyat tetapi yang kita peroleh rezim yang sensitif kepada aspirasi diri, keluarga, dan kelompok elite. Di sinilah terjadi perbedaan antara yang ideal dan yang real. Dan jika demikian, ada problem.
Jalaluddin kemudian menjelaskan bagaimana membedakan antara problem individual dan problem sosial. Ini menjadi penting karena kita seringkali mencoba mengobati problem sosial dengan cara-cara individual. Secara mudah, Jalaluddin membedakan keduanya dengan melihat kuantitas korban problem tersebut. Jika orang miskin berjumlah sedikit dan tak merata, itu artinya kemiskinan tersebut problem individual, yakni karena kemalasan, ketidakmampuan, atau keyakinan tertentu.
Lebih dalam, Jalaluddin memetakan perbedaan problem sosial dan problem individual dalam suatu kriteria. Kita harus melihat dari sisi sebab. Jika sebab suatu problem hanya ada di lingkungan tertentu, maka itu problem individual. Menurutnya, apa yang disebut Oscar Lewis sebagai culture of poverty (budaya kemiskinan) seperti malas, merasa tak berharga, dan minder adalah problem individual. Tapi, jika kemiskinan disebabkan faktor sosial, seperti struktur dan sistem ekonomi, maka itu berarti problem sosial.
Ketidakmampuan mengidentifikasi mana problem individual dan mana problem sosial bisa berujung kepada praktik blaming the victim, atau menyalahkan korban dari problem tersebut. Jalaluddin memberi contoh begini. Banyak orang, dan bahkan para cendekiawan, menganggap keterbelakangan umat Islam di negara-negara bermayoritas penduduk muslim disebabkan oleh kebodohan dan ketidakmauan umat menghayati ajaran Islam. Bagi Jalaluddin, mereka sudah jatuh ke dalam blaming the victim.
Jadi, menurut saya, kemiskinan di kalangan umat Islam itu bukan karena orang-orang Islam tidak menghayati agama, atau karena mereka bodoh, tapi karena sistem sosial yang menindas dan karena kekayaan negara dikuasai oleh segelintir orang. Saya tidak melihat kemiskinan yang terjadi di negara-negara Islam sebagai masalah personal, tapi sebagai masalah sosial (Hal. 63).
Bagi penulis, argumen bahwa orang miskin bodoh karena kurang makanan bergizi juga hanya menggunjingkan persoalan personal. Kebodohan orang miskin justru karena sistem lebih berpihak kepada mereka yang berpunya. Sistem tak memberi orang miskin akses kepada sumber makanan bergizi, institusi pendidikan berkualitas, dan sumber literasi serta fasilitas belajar.
Blaming the victim tadi, menurut Jalaluddin, bisa berdampak terhadap korban problem sosial, yang berupa perasaan—yang disebut dalam psikologi—benci kepada diri sendiri (self-hate). Begitu membenci dirinya, orang miskin itu akan menderita perasaan tak mampu, resah, stres, suka bertengkar dengan orang lain, dan akhirnya menggantung diri.
Kalau masalah kemiskinan itu dipersepsi sebagai masalah sosial, tidak akan ada orang miskin yang membenci dirinya sendiri atau menderita sense of inadequacy (perasaan tidak mampu). Dia akan bangkit dan mengarahkan serangannya kepada institusi-institusi sosial, bukan kepada dirinya sendiri (hal. 67).
Sejak sekarang, kalau saya berjumpa dengan orang-orang yang tidak bisa makan karena harga beras naik, saya tidak akan mengatakan, “Anda tidak bisa makan karena Anda berdosa dan sering meninggalkan salat!” Sebab, pernyataan itu terlalu merujuk pada masalah-masalah personal. Kepada orang-orang yang kelaparan itu, akan saya katakan, “Kalian tidak bisa makan karena institusi-institusi sosial secara sengaja menindas kalian, karena saluran distribusi beras dimanipulasi justru oleh penyalur utama beras itu!” Jadi, mereka tidak akan menyalahkan orangtua atau lingkungan terdekat, tetapi, pergi ke lembaga pemerintah yang menyalurkan sembako dan minta pertanggungjawaban publik dari pejabatnya. Dengan kesadaran semacam itu, barulah masalah sosial itu akan dipecahkan melalui collective action (tindakan bersama) (hal. 68).
Ada beberapa problem sosial yang seringkali disebut para ilmuwan sosial. Pertama, kemiskinan. Kedua, kejahatan. Problem yang satu ini berjenjang dari blue collar crime hingga white collar crime. Jika yang pertama adalah kejahatan yang dilakukan kelas sosial rendah, maka yang kedua merupakan kejahatan kelas sosial atas, seperti para ustad kenamaan, eksekutif, birokrat, politisi, dan kelas elite lain. Di sini, Jalaluddin melihat ada lapis lain problem sosial, yakni bagaimana sistem membedakan penanganan terhadap blue collar crime dan white collar crime. Seringkali kita menemukan rakyat jelata yang dihukum penjara dan bahkan disiksa polisi sampai mati hanya karena mencuri buah atau beberapa kayu di hutan sedangkan yang menjarah kekayaan alam Indonesia hingga bernilai miliaran dolar dibiarkan. Problem sosial ketiga adalah konflik sosial. Problem ini bisa berbentuk etnis, rasial, sektarian, atau ideologis. Dalam kerangka-pikir Marxian, menurut Jalaluddin, perubahan sosial radikal hanya akan terjadi melalui konflik.
Problem sosial tak bisa diselesaikan kecuali dengan aksi sosial, yang menurut Jalaluddin bisa berupa aksi kolektif, gerakan sosial, dan bahkan revolusi. Sebelum membahas ini, dia mengutip sebuah ayat Al-Quran surah Al-Hadid ayat 25: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Al-Mizan supaya menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Dan Kami turunkan besi yang di dalamnya terdapat kekuatan yang dahsyat dan manfaat bagi manusia. Dan supaya Allah mengetahui siapa yang membela-Nya dan membela rasul-rasul-Nya dengan gaib. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”
Kitab-kitab tafsir menjelaskan ayat itu menegaskan bahwa setiap rasul diutus untuk menegakkan keadilan dan menentang kezaliman secara terang-terangan. Mereka dilengkapi dengan tiga cara: (1) al-kitab; (2) al-mizan (timbangan); (3) al-hadid (besi). Tiga cara ini merujuk kepada strategi perubahan sosial yang disebutkan sebelumnya. Pertama, para rasul akan mengajak manusia mengikuti nilai-nilai yang diturunkan Tuhan (al-kitab). Tapi, tak semua manusia bisa diubah dengan al-kitab, sehingga diperlukan al-mizan, yang dimaknai sebagai argumentasi rasional. Tak cuma itu. Para rasul juga dibekali dengan besi atau power strategy (strategi kekuasaan). Dalam pandangan Islam, orang yang ingin melakukan perubahan sosial harus juga siap menggunakan al-hadid atau power strategy (hal. 60).
Selanjutnya, Jalaluddin mengulas apa yang disebut oleh para developmentalis sebagai “lingkaran setan kemiskinan”. Ini juga menunjukkan developmentalisme melihat kemiskinan sebagai problem sosial. Lingkaran setan itu adalah produktivitas rendah menghasilkan pendapatan rendah. Pendapatan rendah menyebabkan pendidikan juga rendah. Pendidikan rendah melahirkan sumber daya manusia berkualitas rendah. Kualitas sumber daya manusia rendah menyebabkan produktivitas rendah, dan terus begitu.
Para developmentalis mempunyai ambisi utama memotong “lingkaran setan” tadi dan mengubahnya menjadi “lingkaran malaikat”. Cara mereka adalah menambah pendapatan masyarakat dengan subsidi, utang, dan pinjaman modal. Dengan begitu, mereka yakin “lingkaran malaikat” akan tercipta, di mana pendidikan tinggi—kualitas manusia tinggi—produktivitas tinggi—pendapatan tinggi. Begitulah teori Walter W Rostow yang dikenal pula dengan istilah Teori Indeks dalam Pembangunan (Hal. 76).
Alhasil, pembangunan di “Dunia Ketiga” sarat dengan beban utang. Dan utang itu digunakan untuk membangun segala rupa infrastruktur untuk memenuhi indeks pembangunan. Sebab, sebuah bangsa akan dinilai maju oleh teori itu jika telah memiliki sekian panjang jalan, sekian pabrik, sekian sekolah, sekian bendungan, sekian rumah, atau sekian jumlah televisi di dalam rumah. Teori Indeks dari Rostow yang saya ceritakan itu memang punya lima tahapan perkembangannya. Tentu, yang paling kita hapal adalah tahapan take off (lepas landas). Sekarang, kata orang, tahapan lepas landas itu telah jadi tahapan mati di landasan. Atau, lepas kandas (Hal. 76).
Teori Indeks dikritik habis-habisan. Teori itu sama saja dengan cerita dua orang bertetangga: yang satu kaya sementara lainnya miskin. Saat melihat yang kaya, si miskin bertanya kepada dirinya sendiri, “Mengapa sih tetangga saya itu disebut kaya?” Dia kemudian tahu bahwa ciri-ciri kaya itu adalah punya mobil, televisi besar, dan rumah dua tingkat. Lalu, bagaimana caranya agar dia juga bisa kaya? Akhirnya, si miskin ini berutang ke bank lalu membangun rumah dua lantai, membeli mobil, dan membeli televisi baru.
Jelas, kita menganggap tetangga miskin itu tolol. Tapi, kita sebut negara yang begitu sebagai negara maju atau negara industri baru (new industrializing countries). Orang yang punya rumah tangga seperti itu kita sebut pemimpin rumah tangga yang konyol, yang ingin kaya hanya dengan memenuhi indikator-indikator kekayaan yang melulu kuantitatif. Tetapi, kalau dia pemimpin negara, kita sebut dia sebagai Bapak Pembangunan (Hal. 78).
Dengan mengutip Phillip Kotler, Jalaluddin memerinci unsur-unsur aksi sosial ke dalam “Lima S”: (1) Sebab (cause). Ini tujuan yang disepakati dan diyakini oleh para pelaku rekayasa sosial, dan dapat memberi jawaban kepada problem sosial.; (2) Sang Pelaku (agent). Ini organisasi yang tujuan utamanya melakukan perubahan sosial; (3) Sasaran (target). Ini bisa kelompok atau lembaga yang ditetapkan sebagai sasaran perubahan; (4) Saluran (channel). Ini media yang berperan dalam menyampaikan pesan dan pengaruh dari setiap pelaku perubahan; (5) Strategi.
Taktik yang ditetapkan pelaku perubahan untuk menimbulkan dampak terhadap sasaran perubahan.
Dalam konteks reformasi di Indonesia pada 1998, Jalaluddin menyebut aksi sosial yang terjadi sebagai perubahan sosial yang bertujuan memperbarui lembaga-lembaga negara yang dianggap menjadi sebab problem sosial. Salah satu lembaga itu adalah tentara, atau yang dulu dikenal dengan nama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia—di mana Kepolisian masuk di dalamnya).
Dengan mengutip buku Harold Crouch, Army and Politics in Indonesia, Jalaluddin menyatakan ABRI memiliki daftar panjang dosa yang menyebabkan problem sosial. Saat terjadi peralihan kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto, ABRI mengambil alih seluruh perkebunan milik negara. ABRI juga memasukkan perwira-perwiranya ke dalam lembaga-lembaga sipil. Jadilah mereka menteri, dirjen, irjen, sekjen, gubernur, bupati, camat, dan lurah. Mereka tetap tentara tapi merangkap jabatan sipil. Akibatnya, menurut penulis, lembaga-lembaga sipil itu membusuk dan bobrok. Sebab, karakter dan struktur militer tidaklah demokratis, sehingga mengharapkan tentara menjadi pelopor demokrasi adalah impian di siang hari bolong…(hal. 85).
Aksi sosial yang terjadi pada 1998 adalah reformasi, kata Jalaluddin. Ia bukan revolusi karena tidak bertujuan menghancurkan dan mengganti lembaga-lembaga negara yang berlumur dosa. Dalam buku ini, Jalaluddin tampak lebih bersepakat dengan revolusi ketimbang reformasi.
Pernah saya diwawancarai oleh RCTI. Saya ditanya: “Apa yang harus dilakukan oleh gerakan reformasi sekarang ini?” Saya jawab: “Mengganti semua institusi yang menimbulkan kesengsaraan rakyat.”…Tapi, Mas Amien (Rais) mengatakan, “Kasihanlah rakyat! Sudah terlalu banyak jadi korban. Kalau ada revolusi, rakyat akan makin malang.” (Hal. 86). [Bersambung]