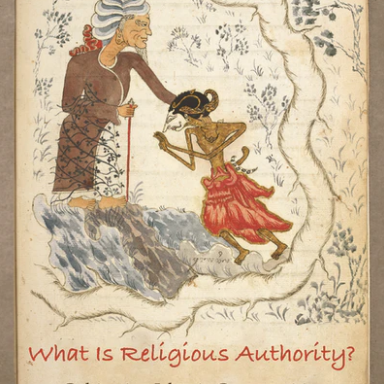Apa sasaran pendidikan: memintarkan atau membahagiakan anak? Pertanyaan itu diajukan Haidar Bagir dalam bukunya Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia. Haidar mengkritik sekolah yang terobsesi memintarkan anak, sehingga mengabaikan kekuatan terdahsyat manusia: imajinasi dan intuisi.
Suatu hari, saat saya menjemput anak pulang sekolah, anak saya (bersekolah di SMP negeri) dengan wajah murung meminta berhenti sekolah. Tentu saja saya terkejut dan menanyakan alasannya.
Ternyata hari itu, dia baru saja dihukum seorang guru karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah: membuat rangkuman materi pelajaran IPS satu semester berikut menjawab soal-soal latihannya! Mendengar itu, keterkejutan saya menjadi-jadi. Bagaimana bisa merangkum pelajaran masih menjadi metode pengajaran di sekolah-sekolah kita saat ini? Sebuah tugas yang bagi saya bukan hanya membebani anak tapi juga tidak penting karena merangkum tak berkaitan dengan pemahaman siswa akan materi.
Keterkejutan saya rupanya belum habis. Di depan kelas, anak saya kabarnya diancam sang guru tidak akan naik kelas. Kok bisa anak dipermalukan seperti itu di depan teman-temannya? Apakah ini cara yang baik untuk memotivasi anak?
Ancaman itu bukan isapan jempol. Saat penerimaan rapor semester gasal, wali kelas mengingatkan saya bahwa anak saya berpotensi tidak naik kelas karena nilai tiga mata pelajaran masih berada di bawah Kriteria Kelulusan Minimal (termasuk tentu saja IPS). Padahal, di mata pelajaran lain, nilainya di atas standar tersebut, dan bahkan dia meraih nilai nyaris sempurna dalam bahasa Inggris.
Saya tak mau berdebat dengan wali kelas. Saya hanya menceritakan bahwa anak ini memiliki ketertarikan lebih pada bahasa Inggris, dan hal yang sama tidak terjadi pada mata pelajaran lain. Ketertarikannya pada bahasa Inggris karena dia sangat menggemari permainan rubik dan game online Minecraft. Dua permainan yang saya tahu sangat menyita waktunya dan tak jarang melibatkan dia dalam chat online dengan penggemar dua permainan itu di negara lain.
Jujur saya tidak membatasinya. Saya setidaknya tahu dua permainan itu tak memiliki dampak negatif yang berlebihan, dan bahkan bisa merangsang kecerdasan.
Selain itu, anak saya sangat senang aktif dalam Pramuka, ekstrakurikuler yang juga kadang membuat dia harus pulang menjelang magrib, dan kelelahan saat tiba di rumah. Dengan semua aktivitas yang menurut saya membuatnya bahagia itu, lantas apakah dia harus tinggal kelas hanya karena nilai tiga mata pelajaran berada di bawah standar kelulusan?
Di sini, saya merasa sistem persekolahan kita justru memusuhi kebahagiaan anak. Sistem apakah yang menjadikan kelulusan hanya ditentukan oleh satu, dua, atau tiga mata pelajaran, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain?
Tentu saja perasaan itu subjektif, dan mungkin cuma anak saya yang mengalaminya. Toh, bisa jadi ada yang mengatakan, banyak anak lain yang bisa sukses secara akademik sambil masih tetap menjalani hobinya.
Saya pun merasa sendirian.
Perasaan sendirian itu hilang ketika saya membaca Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia: Meluruskan Kembali Falsafah Pendidikan Kita karya Haidar Bagir. Buku ini dimulai dengan kutipan provokatif John Holt dalam How Children Fail: “Kegagalan akademis siswa bukanlah akibat tidak adanya/kurangnya upaya oleh sekolah, melainkan justru akibat ‘ulah’ sekolah.” Bahkan, Haidar pun tak kalah provokatifnya ketika menambahkan: “Kalau saya … bisa memilih dengan bebas, saya akan pilih model sekolah yang hampir-hampir tidak ada sama-samanya dengan sekolah yang dikenal sekarang ini.”

- Judul Buku: Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia
- Penulis: Haidar Bagir
- Penerbit: PT Mizan Publika
- Tahun Terbit: 2019
- Tebal: 212 halaman
Wow! Saya bergumam. Pernyataan-pernyataan tersebut sangat mewakili perasaan saya.
Saya jadi teringat dengan lirik lagu rock opera gubahan band Inggris Pink Floyd pada 1979 “Another Brick in the Wall (Part II)”. Tentu pembaca sudah hafal dengan lirik lagu legendaris ini, tapi ada baiknya saya kutip di sini.
We don’t need no education
We don’t need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave them kids alone
Hey! Teachers! Leave them kids alone
All in all it’s just another brick in the wall
All in all you’re just another brick in the wall
Lagu ini tak ayal memicu kontroversi. Otoritas pendidikan di Inggris menyebutnya agitasi terhadap moralitas publik sementara Perdana Menteri Margaret Thatcher dilaporkan sangat membencinya. Di sisi lain, lagu ini merajai tangga lagu selama beberapa pekan di sejumlah negara Eropa, seperti Finlandia, Jerman, dan Irlandia, serta didaulat Rolling Stone sebagai salah satu dari 500 lagu terbaik sepanjang masa.
Saya menduga Roger Waters, penggubah lirik sekaligus pentolan band, tidaklah anti-pendidikan. Dia hanya mengkritik sistem persekolahan yang kaku: sarat dengan ambisi untuk menyeragamkan pikiran, tindakan, dan perasaan siswa.
Dalam Memulihkan Sekolah, Haidar melakukan hal yang kurang-lebih sama. Dia, misalnya, mempertanyakan, apakah tujuan pendidikan itu menciptakan manusia pintar atau manusia bahagia?
Kedua hal ini (pintar dan bahagia), menurut Haidar, sebenarnya tak perlu dipertentangkan. Keduanya memiliki fungsi masing-masing yang saling mendukung. Kepintaran bisa membantu mendatangkan kebahagiaan, dan kebahagiaan bisa melejitkan kepintaran.
Namun, persoalannya, Haidar bilang, adalah obsesi kita untuk memintarkan anak lebih besar daripada membahagiakan mereka. Sekolah pun lebih sibuk dengan upaya menjejalkan pengetahuan siap pakai kepada anak. Kita tentu ingat konsep pendidikan tabularasa John Locke yang menganggap anak bak bejana kosong yang harus diisi, padahal sesunggunya pendidikan bukanlah mengisi bejana itu (yang tentu saja tidak kosong) tapi menyalakan api potensi di dalamnya agar menjadi aktual.
Ambisi “memintarkan anak”, diakui atau tidak, masih mendominasi persekolahan di negeri ini meski kurikulum sudah diperbarui berulangkali (dan menurut saya sebagus apa pun model kurikulum yang dipakai selama praktik pengajaran di sekolah masih berparadigma kuno, persekolahan tak akan pernah bersahabat bagi perkembangan anak). Pengalaman saya berinteraksi dengan anak-anak saya–dan mendengar keluh kesah mereka sepulang sekolah–mengungkap bahwa praktik pengajaran di sekolah masih menerapkan cara-cara lama. Akuisisi pengetahuan siap pakai (menghapal, meringkas) lebih dikedepankan daripada pemaknaan.
Misalnya, anak masih tetap saja dituntut untuk menghafal tanggal-tanggal dan nama-nama tempat serta tokoh sejarah. Padahal, menurut saya, sejarah akan lebih mengasyikkan jika siswa diberi ruang untuk memaknai mengapa suatu peristiwa terjadi atau mengapa seseorang mengambil tindakan tertentu dalam momen menentukan. Lalu, siswa juga bisa membayangkan apa yang akan mereka lakukan seandainya berada dalam momen-momen bersejarah itu.
Bahkan dalam pengajaran sastra sekalipun, siswa masih diminta menyebutkan ciri-ciri puisi (bahkan puisi saat ini sudah tak lagi bisa dicirikan), menghafal puisi, dan menyebut nama-nama penyair. Padahal, yang lebih penting adalah bagaimana siswa mengapresiasi sebuah karya sastra setelah membacanya. Jangankan mengapreasiasi, siswa mungkin tak pernah diberi ruang dan kesempatan untuk membaca karya-karya besar sastrawan Indonesia.
Saya ingat. Saya dulu merasa iri dalam hal tersebut dengan siswa di negara lain. Di film-film Barat, saya menyaksikan bagaimana siswa diminta membaca karya-karya Barat klasik lalu menceritakannya kembali di depan kelas sambil memberi respons atas karya-karya itu. Saya membayangkan, akan mengasyikkan jika siswa di sini menceritakan kembali novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer atau Para Priyayi karya Umar Kayam di hadapan teman-teman mereka.
Persoalan lain–dan ini disebut Haidar dalam buku ini–adalah penekanan kepada aspek pengetahuan ketimbang praktik, apalagi perilaku dan akhlak. Satu contoh kecil adalah bagaimana anak dibebani hafalan nama-nama hukum tajwid dalam membaca Al-Quran. Saya pernah melihat sendiri bagaiamana nyaris seperlima soal ujian Pendidikan Agama Islam (PAI) berisi pertanyaan, apa hukum bacaan ini dan itu. Padahal, selama anak bisa membaca Al-Quran sesuai tajwid, apalah petingnya nama hukumnya.
Menurut Haidar, semua itu terjadi karena pola pikir praktisi pendidikan masih terbelenggu oleh apa yang dia sebut sebagai “McNamara Fallacy”1Istilah ini merujuk kepada nama Robert McNamara, Menteri Pertahanan AS pada masa agresi negara itu atas Vietnam. McNamara dikenal memiliki obsesi untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang bersifat kuantitatif: obsesi untuk mengukur segala sesuatu secara kuantitatif. Akibatnya, aspek kognitif dan psikomotorik (yang lebih mudah diukur secara kuantitatif) lebih menonjol sementara aspek afektif dan spiritual (yang konon sulit untuk diukur) terpinggirkan atau bahkan terabaikan sama sekali.
Paradigma kecerdasan sudah jauh berkembang, tak lagi mendewakan IQ. Pada 1983 Howard Gardner memperkenalkan paradigma kecerdasan majemuk (multiple intelligences). Lalu, ada kecerdasan emosional (emotional intelligence) oleh Daniel Goleman pada 1995 dan kecerdasan spiritual (spiritual intelligence) oleh Danah Zohar dan Ian Campbell pada 1999 (ketiganya diulas dalam Memulihkan Sekolah).
Saya yakin banyak praktisi pendidikan tahu perkembangan ini. Tapi, paradigma memang bukan cuma soal pengetahuan. Ia adalah cara pandang, pola pikir, dan kebiasaan yang membutuhkan waktu untuk diubah.
Karena aspek afeksi dan spiritual dipinggirkan, menurut Haidar, daya imajinasi dan intuisi siswa tak berkembang. Ini berakibat kepada miskinnya kreativitas sumber daya manusia Indonesia. Persekolahan kita menghasilkan manusia yang hanya mampu mengoperasikan mesin dan mengerjakan konsep yang dirancang dan dikendalikan manusia dari negara lain. Padahal, keterampilan Abad ke-21 menuntut manusia yang mampu berpikir generalis, berpikir kritis, dan berpikir sosial-kultural.
Imajinasi dan intuisi, menurut saya, salah satu yang penting digarisbawahi dari penjelasan Haidar dalam buku ini. Dia menyajikan ulasan segar tentang keduanya.
Tanpa mengenyampingkan pentingnya kemampuan rasional, Haidar menyatakan bahwa imajinasi (kemampuan membayangkan sesuatu tanpa melalui prosedur persepsi) justru sumber kreativitas (kemampuan memunculkan gagasan baru). Sebab, kreativitas dipercaya bakal dihasilkan ketika orang betul-betul “menikmati apa yang dilakukan, kehilangan sense waktu, pikiran terpusat pada momen sekarang, merasa dalam kontrol penuh atas segala sesuatu, dan merasa benar-benar bebas”.
Daya imajinasi dan khayal, dalam anggapan kebanyakan orang, mungkin cuma omong kosong. Namun, inovasi besar–bahkan dalam ranah sains–justru berawal dari imajinasi dan khayalan. Haidar menyebut beberapa contohnya: penemuan rumus benzene oleh Kekule yang didasarkan atas mimpinya melihat ular menggigit ekornya sendiri; hukum gravitasi yang dicetuskan saat Isaac Newton tengah terkantuk-kantuk di bawah pohon apel; dan prinsip Archimedes yang ditemukan saat dia berendam dalam bak air. Bahkan Albert Einstein merumuskan teori relativitas saat membayangkan dirinya sebagai foton yang berada di horizon kecepatan-kecepatan.
Imagination is more important than knowledge
Albert Einstein
Imajinasi, khayal, dan mimpi, menurut Haidar, bukan tak berdasar realitas tapi memiliki realitasnya sendiri. Realitasnya berada di antara dunia fisik dan dunia spiritual. Filsuf Perancis Henry Corbin menyebutnya sebagai “dunia imajinal” (untuk membedakannya dengan imajiner yang tak memiliki pijakan realitas), dan ia menjadi awal sekaligus landasan dari terbentuknya realitas empiris.
Intuisi bahkan menjadi fondasi dari pengetahuan. Mengutip Aristoteles, Haidar menyatakan bahwa, tanpa intuisi atau pengetahuan swabukti (self evident), maka seseorang tak bisa menyusun premis pertama, apalagi membuktikan premis-premis selanjutnya. “Jika tak ada sesuatu yang bersifat swabukti (self evident), tak ada yang bisa dibuktikan,” kata CS Lewis, pemikir dan sastawan Inggris (pengarang The Chronicles of Narnia).
Menurut Haidar, spiritualisme menyebut intuisi berasal dari ilham ketuhanan, ilham spiritual, atau setidaknya ilham dari alam antara.
Bagi Haidar, imajinasi dan intuisi adalah potensi daya atau kemampuan tertinggi manusia, yang tak akan pernah mampu digantikan oleh apa pun, bahkan oleh Artificial Intelligence (AI) secanggih apa pun. Alih-alih AI akan menjadi kiamat bagi keberadaan ras manusia–sebagaimana dicemaskan banyak kalangan, Haidar justru berpandangan bahwa perkembangan AI bakal mendorong manusia untuk melejitkan potensi terdahsyatnya: imajinasi, intusi, dan moral. Tentu saja, itu akan terjadi seandainya kita mulai sekarang mengembangkan metode pendidikan yang mengembangkan daya imajinasi dan intuisi tadi.
Memulihkan Sekolah penting untuk dibaca para praktisi pendidikan, pengambil kebijakan, dan orang tua. Meskipun, dalam beberapa bagian, pembahasan terasa tak tuntas (mungkin karena ini merupakan kumpulan tulisan), buku ini tetap menghadirkan pikiran-pikiran segar tentang falsafah, paradigma, dan bahkan metode pendidikan.
Sudah terlalu lama kita berputar-putar soal model kurikulum apa yang sesuai bagi Indonesia, sampai-sampai ada ungkapan “ganti menteri, ganti kurikulum”. Sudah saatnya kita memulai perubahan dengan hal yang lebih mendasar: membebaskan diri dari obsesi “memintarkan anak” dan obsesi “mengukur kesuksesan dengan aspek nilai atau prestasi akademik semata”. Jadikan sekolah tempat menyenangkan dan membahagiakan bagi anak! Kuncinya, kalau anak milenial bilang, santuy!
Memang itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Ibarat supertanker, perubahan haluan di dunia pendidikan (dengan 300 ribuan sekolah dan 50 jutaan siswa) membutuhkan waktu. Tapi, jika tak dimulai dari sekarang, kapan lagi?
Guru di sini berperan penting. Jika ingin membuat sekolah menjadi tempat mengasyikkan dan membahagiakan, kita harus lebih dulu membahagiakan guru, dan ini bukan cuma soal kesejahteraan. Bebaskan mereka dari beban-beban yang tak perlu, seperti kewajiban menghadiri seremoni birokrasi dan membuat laporan administrasi!
Dalam transkrip pidatonya yang viral kala Hari Guru 2019, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim tampaknya sudah menyadari itu. Kini saatnya, Menteri Nadiem menunjukkannya dalam kebijakan konkret.
Jika mau, ia bisa ‘mengintervensi’ penunjukkan kepala-kepala dinas pendidikan di daerah, agar diisi oleh orang-orang visioner, bukan sekadar birokrat yang business as usual atau bahkan orang-orang titipan karena kedekatan dengan kepala daerah. Sebab, guru tak mungkin bisa merdeka, bebas, dan santai jika birokrat yang mengurusi mereka cuma bisa menekan sana-sini.[]