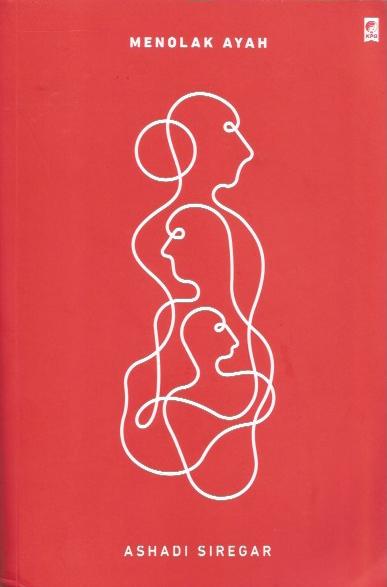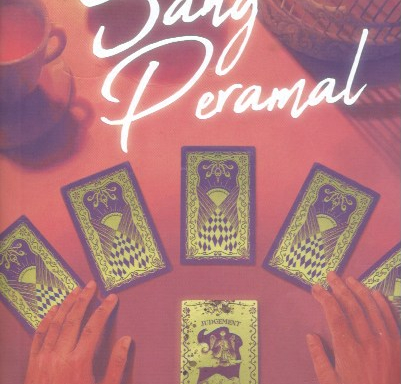Setelah menjani hiatus 30 tahun dari dunia kepengarangan, Ashadi Siregar (Cintaku di Kampus Biru) kembali dengan Menolak Ayah pada 2018. Novel ini, menurut Nestor Rico Tambunan, mengungkap banyak hal yang tak terungkap dalam sejarah, budaya orang Batak, dan kehidupan manusia Indonesia pada umumnya. Ia juga membangkitkan pathos, membantu kita lebih memahami manusia dan kemanusiaan.
ASHADI Siregar dan Marga T adalah dua tokoh pengarang pencipta novel populer gaya baru di Indonesia pada 1970-an. Ashadi dengan Cintaku di Kampus Biru, Kugapai Cintamu, Terminal Cinta Terakhir, dan Sirkuit Kemelut. Marga T lewat novel-novel Karmila, Badai Pasti Berlalu, Bukan Impian Semusim. Semua karya mereka ini difilmkan.
Disebut “gaya baru” karena mereka menampilkan gaya bercerita, materi, dan setting yang berbeda dengan pengarang angkatan sebelumnya (Motinggo Busye Cs). Novel dengan tokoh-tokoh anak muda, dengan setting kehidupan kampus dan keluarga kelas sosial baru, sejalan dengan kehidupan Orde Baru yang mulai tumbuh pada 1970-an.
Novel populer gaya baru ini mendapat sambutan hangat. Mereka kemudian diikuti pengarang-pengarang lain seperti Mira W, Maria A Sardjono, dan sebagainya.
Ashadi melahirkan sekitar 10 novel hingga awal 1980-an. Setelah itu ia berhenti menulis novel, dan lebih dikenal sebagai ilmuwan ilmu komunikasi di UGM dan praktisi pers Iewat lembaga penelitian dan pendidikan penerbitannya. Karena itu, sangat lumrah kalau menjadi perhatian banyak orang ketika pada 2018 ia menerbitkan novel Menolak Ayah, setelah istirahat 30 tahun lebih.

- Judul Buku: Menolak Ayah
- Penulis: Ashadi Siregar
- Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia
- Tahun Terbit: 2018
- Tebal: vi + 434 halaman
Setting Waktu/Peristiwa
Menolak Ayah bercerita tentang perjalanan hidup tokoh bernama Tondinihuta (Tondi) dalam pusaran nasib dan peristiwa. Setting utama peristiwa/waktu novel adalah masa pemberontakan PRRI (1956) hingga peristiwa G3OS (1965) — peralihan pemerintahan dari Sukarno ke Soeharto. Namun, karena novel ini juga bercerita banyak tentang latar belakang kehidupan Tondi sebagai cucu Ompu Silangit, seorang mantan ulubalang Raja Sisingamangaraja XII, setting novel sejatinya menjadi sangat panjang, dari Perang Batak (1878-1907), pendudukan Jepang, Perang Kemerdekaan, bahkan juga menyebut-nyebut Tingki Ni Pidari (Perang Paderi).
Panjangnya setting waktu dan banyaknya peristiwa membuat Menolak Ayah membutuhkan banyak penjelasan dalam ceritanya. Saya kira Ashadi menghabiskan cukup banyak waktu untuk mencari informasi, mencek ulang fakta mengenai hal-hal tersebut. Termasuk mengenai sejarah, kepercayaan asli, dan adat istiadat orang Batak.
Hal itu membuat pembaca Menolak Ayah mendapat banyak informasi, atau pemahaman mengenai sejarah dan berbagai hal yang berkaitan dengan setting waktu dan peristiwa di atas, meskipun informasi itu mungkin tidak sepenuhnya akurat. Salah satu contoh pemahaman itu, bahwa gerakan PRRI, yang oleh Pemerintah RI disebut pemberontakan, sebenarnya tuntutan keadilan pembangunan dan nasib kesatuan militer di wilayah Sumatera bagian Utara dan Tengah. Hal ini juga membuat setengah novel Menolak Ayah alurnya terasa lambat. Beruntung, Ashadi punya kemampuan bahasa yang memikat.
Sejauh pengetahuan saya, ini novel kedua Ashadi ber-setting perang setelah Warisan Sang Jagoan. Namun, saya pribadi menilai tak perlu menganggap Menolak Ayah sebagai novel sejarah atau budaya. Sebagaimana umumnya, roman memang membutuhkan latar belakang waktu, tempat, peristiwa, budaya, dan psikologis. Ini pilihan Ashadi untuk karya terbarunya. Saya ingin menganggap dan dianggap seperti itu.
Tentang Batak
Meskipun bukan novel budaya, Menolak Ayah cukup banyak berbicara soal Habatahon (hukum dan adat istiadat Batak). Seperti saya sebut di atas, bahkan setengah dari novel ini terasa lamban karena banyak narasi alur/plot yang menjelaskan latar belakang kehidupan Tondi.
Buat pembaca non-Batak, alur/plot narasi tentang Habatahon ini mungkin terasa memberi banyak pengetahuan. Tapi buat pembaca orang Batak, terutama yang tidak terlalu memahami “realitas dalam fiksi” dan “realitas dalam kehidupan”, barangkali narasi tersebut akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan atau bahkan protes. Maklum, kehidupan dan adat istiadat orang Batak itu kompleks dan relatif ketat. Banyak aturan yang tak bisa dikompromikan dan berlaku hingga kini. Seperti dikatakan tokoh Ompu Silangit, “Agama kita itu adat Batak.”
Salah satu hukum itu, dan menjadi yang paling dasar, adalah hukum marga. Bahwa setiap orang punya marga, dan terikat dengan marga itu, Dan marga itu juga membuat setiap orang terikat dengan marga lain sesuai dengan rumus Dalihan Na Tolu, yang menjadi sistem kemasyarakatan dan sistem sosial masyarakat Batak. Kau marga apa? Marga A dari mana? Itu dongan tubu-nya. Istrimu, ibumu, nenekmu marga apa? Itu menjadi Hula-hula yang harus dihormati. Dan orang-orang yang mengambil istri dari keluargamu, margamu, akan menjadi Boru yang harus menghormati.
Rumus itu berlaku permanen bagi tiap orang/kelompok marga. Acara adat tidak bisa dilaksanakan tanpa unsur-unsur Dalihan Na Tolu ini. Apalagi acara margondang seperti waktu meninggalnya Ompu Silangit dan istrinya. Itu harus melibatkan teman semarga, hula-hula, dan boru. Dan gondang tidak sembarangan bisa dilaksanakan kalau orang belum saurmatua; semua putra-putrinya sudah berumah tangga dan memberi cucu. Pardomutua, bapak Tondi, tidak bisa datang sendirian, tanpa istri dan anak, karena mereka semua itu ada fungsinya dalam adat margondang dan penguburan. Dalam konteks itu juga, Pardomutua tidak boleh meninggalkan dan menelantarkan Halia, ibu Tondi begitu saja. Hula-hula dari Halia akan marah dan campur tangan.
Orang Batak bisa mempertanyakan hal-hal ini. Mungkin Ashadi tidak menyadari itu. Atau bisa jadi justru menyadari, tapi sengaja menghindari. Karena bahkan marga asli Ompu Silangit, Pardomutua (bapak Tondi), dan Tondi sendiri tidak ia sebut.
Banyak hal yang bisa dipertanyakan, namun juga banyak nilai yang “sangat Batak” dalam novel ini. Antara lain, penolakan Halia ketika mau dikawini dan dibawa ke Aceh oleh dokter Herman. Dia tidak mau kehilangan statusnya sebagai istri marga suaminya. Lalu pengakuan Tondi terhadap anak hasil hubungan gelap dengan Habibah (Tando) dan Longgom (Tarsingot). Dalam konteks hukum marga tadi, perkawinan sah atau tidak sah secara hukum/agama, bahwa darah daging adalah anak yang harus diakui. Begitu pula pengakuan dan tanggung jawab Tondi terhadap tiga putri Pardomutua, setelah Pardomutua masuk penjara, bahwa mereka ito-nya.
Soal Hubungan Laki-laki dan Perempuan
Hal lain yang mungkin mendapat perhatian pembaca dan menarik dibicarakan dari Menolak Ayah adalah nasib perempuan dan hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam novel ini, tokoh-tokoh perempuan terkesan termarjinalkan. Halia, ibu Tondi, yang ketika baru menikah cuma dijadikan pemuas nafsu, ketika melahirkan anak, ditinggal selingkuh dengan nyonya Belanda, lalu ditinggal pergi ke Jawa dan tak pernah diingat lagi. Tapi ia menolak ketika mau dinikahi Herman, dokter Belanda atasannya.
Habibah, yang bernasib seperti ranting kering. Menikah dengan Masrul, punya anak tiga, tapi sebenarnya sekadar upaya Masrul mencoba jadi laki-laki karena sejatinya dia transgender. Bahkan, akhirnya Masrul tidak mampu berhubungan badan dengan istrinya itu, sehingga pergi ikut perang. Tapi Habibah berusaha tabah dan bertahan.
Lalu ada Longgom, yang mengasingkan diri ke hutan bersama kedua orangtua dan suaminya untuk menghindari rasa malu. Suaminya kena guna-guna, gila, dan impoten sejak malam pengantin mereka.
Tiga perempuan ini seperti diperlakukan tidak adil. Tapi, bagaimanapun derita mereka, dan apa pun dosa yang mereka lakukan, mereka mendapat empati dari Ashadi, menerima penghormatan tersendiri karena sikap-sikap teguh mereka. Bagaimanapun bentuknya, mereka memiliki kehormatan.
Berkaitan dengan perempuan ini, seperti dalam banyak novel Ashadi yang lain, Menolak Ayah menampilkan adegan-adegan hubungan badan, terutama antara Tondi dengan perempuan-perempuan di atas. Sebagian adegan itu terkesan liar dan gila. Hubungan badan dengan Habibah berlangsung di bangku belakang bus Sibualbuali yang sedang meluncur menembus malam. Hubungan dengan Longgom berlangsung semalaman di kebun kopi. Hubungan dengan germo Mami Ana berlangsung three-some bersama seorang anak buah si mami. Kesannya kurang ajar (atau enak benar) si Tondi.
Tapi ada satu hal yang menjadi ciri khas Ashadi dalam plot seperti ini. la pintar menggambarkan adegan hubungan badan perempuan dengan metafor-metafor, sehingga tidak jatuh menjadi adegan murahan. Untuk orang dewasa, tidak terlalu panas lah. Satu hal lagi, dalam novel-novel Ashadi, hubungan seperti ini, bagaimanapun haramnya, selalu dibalut suasana “kesetaraan”, bukan dominasi satu pihak atau pemerkosaan. Bahwa semacam itu kebutuhan dua pihak, jadi dosa bersama. Lelaki mendambakan perempuan. Tapi perempuan juga menghendaki laki-laki. Agak jujur, dan equal.
Sekadar Catatan
Bagi saya pribadi, membaca Menolak Ayah seperti memuaskan rasa rindu. Ashadi memiliki kemampuan gaya bahasa yang hebat dan khas. Kalimat-kalimat yang lancar, sering mengejutkan dan menghujam, dan banyak menggunakan metafor-metafor yang unik. Saya menemukan semua kekhasan itu dalam Menolak Ayah. Ya, jujur, saya berharap akan ada novel berikutnya.
Apa yang bisa diberikan Menolak Ayah?
Sejak dulu, baik kalangan kebudayaan Timur maupun Barat sama-sama berpendapat sastra bagian penting dalam pembelajaran budaya dan kemanusiaan. Salah satu keunikan karya sastra, ia sering mengungkapkan sisi buruk, atau sesuatu yang kontradiktif dari kehidupan, untuk menyampaikan moral yang baik. Sastra memperkaya imajinasi, menjembatani pertentangan-pertentangan dan mengungkapkan yang tak terungkap dalam kehidupan, atau yang disebut the ultimate reality. Dengan itu, sastra memperkuat dan menajamkan sense of humanity.
Seperti dikemukakan Budi Darma datam tulisan “Moral dalam Sastra” dalam buku Budaya dan Sastra, salah satu hakikat sastra menggambarkan manusia sebagaimana adanya. Karya sastra yang baik akan mengajak pembaca melihat karya tersebut sebagai cermin dirinya sendiri, dengan jalan menimbulkan pathos, yaitu simpati dan merasa terlibat dalam peristiwa mental yang terjadi dalam karya tersebut.
Novel Menolak Ayah, saya kira, memberikan dua esensi berharga itu. Ia mengungkapkan banyak hal yang tak terungkap (the ultimate reality) dalam kehidupan orang Batak dan kehidupan manusia Indonesia secara umum, dan membangkitkan pathos. Dua-duanya “memberi gizi” dan membantu kita menjadi insan-insan yang lebih memahami manusia dan kemanusiaan, lebih berbudaya dan beradab.[]
(Ulasan ini pernah disampaikan Nestor Rico Tambunan dengan judul “Catatan untuk Novel Menolak Ayah Karya Ashadi Siregar” dalam diskusi yang diselenggarakan Komunitas Percakapan Buku Guntur 49 pada 7 Desember 2018)