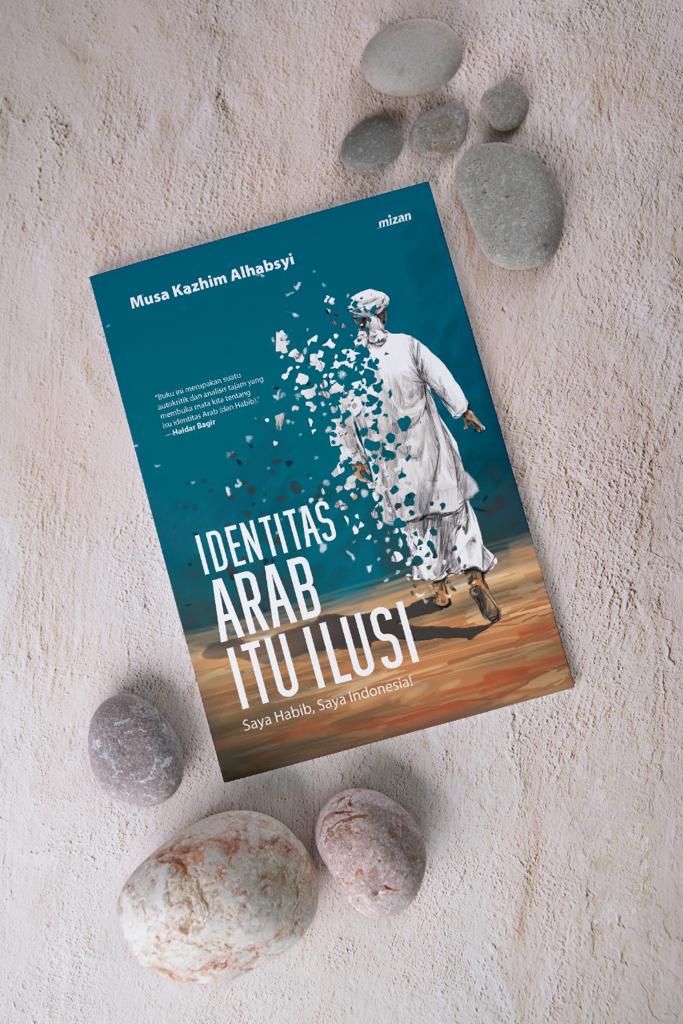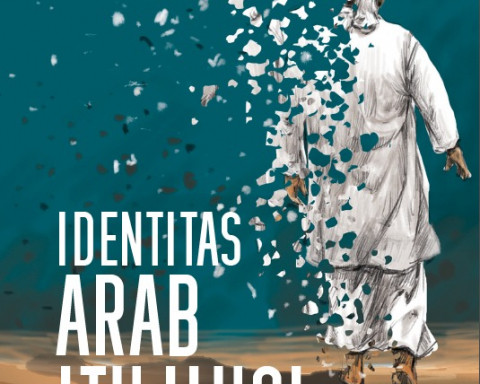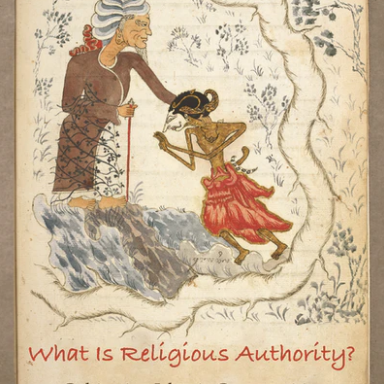Buku ini membawa diskusi lebih tinggi mengenai soal-soal identitas keturunan Hadhrami dalam kajian ilmiah populer. Argumentasi utama penulis melalui pendekatan linguistik dan sejarah telah membentuk argumentasi yang solid untuk menguliti apa yang disebut sebagai ilusi identitas Arab.
Sebagai peneliti awam non-Hadhrami yang mengkaji kalangan keturunan Hadhrami di Indonesia, saya selalu dihadapkan pada pertanyaan: mengapa harus mendalami Hadhrami di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia? Saya mengakui tidak mudah menjawab pertanyaan tersebut. Awalnya niat saya ingin mendalami kajian ini dikarenakan hanya melihat fenomena kebangkitan tokoh-tokoh Hadhrami dalam skena politik di Tanah Air dalam upayanya menjadi agen penyeimbang pemerintah. Tidak lebih.
Dalam pengembaraan saya mendalami kelompok Hadharim di berbagai daerah di Indonesia, saya bertemu dengan penulis buku Identitas Arab itu Ilusi: Musa Kazhim Al Habsyi. Maret 2022, saat saya pertama kali menemuinya, buku ini memasuki tahap finalisasi sebelum diterbitkan. Saya sedikit waswas: barangkali topik saya sudah dikuliti habis di dalam buku ini. Sampai saya membacanya, dan saya gembira luar biasa.
Walaupun buku ini bukanlah buku ilmiah, saya menyebutnya semiilmiah karena berisi refleksi kritis nan teoritis dari seorang Hadhrami-Alawiyin mengenai eksistensi identitas kelompoknya. Setelah membacanya, saya baru menyadari betul bahwa buku ini membantu saya menjawab pertanyaan di atas.
Kajian ilmiah mengenai Hadhrami sebagai sebuah kelompok sosial berpengaruh di Indonesia masih sangat kurang. Dalam satu tarikan napas, saya mungkin saja bisa menyebut karya-karya klasik tentang Hadhrami Indonesia dari van den Berg, Engseng Ho, Huub de Jonge, Natalie Kesheh, hingga yang kontemporer seperti Ismail Fajrie Alatas atau Syamsul Rijal. Meskipun kajian ilmiah mengenai Hadhrami secara kuantitas terbilang cukup banyak, bangunan intelektual atas kajian Hadhrami di Asia Tenggara masih jauh dari bangunan konseptual kajian lain, semisal tesis-tesis mengenai etnis Tionghoa yang dimotori secara mapan oleh Wang Gungwu, Leo Suryadinata, atau yang terbaru oleh Johanes Herlijanto atau Taomo Zhou. Bahkan tanpa sadar, kita sering meminjam konsep-konsep yang dilahirkan dari bangunan kajian Tionghoa seperti konsep totok dan peranakan yang walaupun memiliki arti yang sama tapi memiliki nuansa yang berbeda dengan wulaiti dan muwallad.
Nah, buku ini membawa diskusi lebih tinggi mengenai soal-soal identitas keturunan Hadhrami dalam kajian ilmiah populer yang tidak terlalu ramai diperdebatkan dan didiskusikan secara ilmiah. Walaupun ditulis dalam bentuk refleksi, argumentasi utama penulis melalui pendekatan linguistik dan sejarah telah membentuk argumentasi yang solid untuk menguliti apa yang disebut sebagai ilusi identitas Arab.
Penulis buku ini mencoba menggoyang kemapanan konseptual pembaca yang mungkin sebagian besar adalah kalangan non-Arab untuk berpikir ulang mengenai terminologi “orang Arab”. Saya pikir sumbangsih terbesar buku ini adalah upaya redefinisi “orang Arab” sebagai bukan hanya ekspresi identitas yang dangkal, namun juga problematik secara faktual. Walaupun tidak akan berkomentar mengenai sisi linguistik karena memang bukan seorang yang terlatih berbahasa Arab, saya sangat berharap tesis tersebut memicu perdebatan yang intens, khususnya di kalangan sarjana-sarjana antropologi dan linguistik.
Salah satu keunggulan lain buku ini dalam khasanah ilmu sosial humaniora di Indonesia adalah bahwa buku ini lahir dalam momentum kebangkitan kembali (reawakening, atau yang penulis buku ini sebut: born-again) kristal-kristal identitas kalangan Alawiyyin yang memang menjadi kajian sentral dalam buku ini. Hal ini membantu saya dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepada saya di awal tulisan ini.
Saya menyadari bahwa fenomena kebangkitan kembali identitas Alawiyyin di Indonesia mendorong peran-peran habaib menjadi sangat signifikan dalam berbagai bidang. Hadhrami, khususnya kalangan Alawiyyin, adalah kelompok minoritas tapi sangat dominan (dominant minorities) khususnya dalam sosial, keislaman, dan (perlahan merambah) politik.
Disukai atau tidak, saya menduga bahwa kalangan Hadhrami dan khususnya Alawiyyin telah menjadi dominant minorities jauh sebelum bangsa ini ada. Salah satu ciri penting dominant minorities dalam proses pembentukan bangsa yang heterogen menurut Anthony D Smith adalah adanya ikatan kesamaan nilai-nilai (berupa mitos, epos, agama, konsep kepahlawanan, bahasa, dan budaya) yang dipengaruhi dan dibentuk oleh sebuah etnik yang dominan.
Saya menduga bahwa peran keturunan Hadhrami dalam pembentukan nilai-nilai pembentuk negara jauh lebih besar daripada kelompok etnis dan suku apa pun, bahkan Jawa sekalipun yang selalu dikatakan sangat dominan di Indonesia. Saya mendasarkan dugaan saya pada dua hal. Pertama, hampir tidak ada sebuah suku di Nusantara yang daya penyebaran dan penjelajahannya semasif Hadhrami yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Kedua, Islam sebagai agama dan nilai mayoritas disebarkan sebagian besar oleh kelompok keturunan Hadhramaut di Nusantara, sedangkan tradisi Islam di masyarakat tradisional di Indonesia saat ini sangat banyak dipengaruhi oleh tradisi-tradisi Hadhramaut, khususnya dari kalangan Alawiyyin. Namun sekali lagi ini adalah dugaan, yang menurut saya sangat menarik untuk diteliti lebih jauh.
Alih-alih penghormatan itu jatuh dari langit, kelompok Hadhrami dan Alawiyyin sudah memiliki sebuah modal besar untuk menjadi kelompok terhormat di Indonesia. Namun, pertanyaan yang juga diresahkan di buku ini adalah mengapa muncul sebuah penghormatan yang hampir dikatakan berlebihan kepada habib, khususnya dalam periode 20 tahun terakhir. Penulis buku mengutarakan bahwa keterbukaan Yaman pasca kolapsnya pemerintahan Komunis menjadi faktor utama dalam penguatan identitas Alawiyyin di ruang publik, sehingga kalangan Alawiyyin yang mampu ke Yaman mempertebal pertalian ke leluhur dan tanah asal usul mereka. Sehingga menurut penulis, muncullah kecenderungan kelahiran kembali generasi baru Alawiyyin yang mempertahankan status quasi-native dengan mempertahankan tradisi Arab-Alawiyyin di satu kaki dan mencoba menjadi Indonesia di kaki yang lain. Penebalan identitas tersebut justru direspons positif dengan penghormatan oleh kalangan non-Hadhrami yang semakin membahana, atau yang dikenal sebagai muhibbin (pecinta habaib). Kekhawatiran penulis beralasan karena penghormatan yang dinilai berlebihan tersebut akan berdampak negatif pada intelektualisme dan bahkan berpotensi mengancam eksistensi Alawiyyin dalam jangka panjang.
Namun pertanyaan utamanya adalah mengapa Alawiyyin mampu mengakumulasikan dan membentuk perilaku kolektif kalangan di luar Hadhrami untuk memberi penghormatan kepada habaib terutama dalam 20 tahun terakhir? Di sisi inilah menurut saya penulis buku ini mengabaikan sentuhan konteks nasional Indonesia yaitu demokratisasi. Selain keterbukaan Yaman, menurut saya, demokratisasi yang diwujudkan dalam kebebasan berekspresi dan politik elektoral menjadi faktor penting, terutama bagi kalangan Alawiyyin dalam mengakumulasi modal sosial dan kultural mereka di Indonesia.
Saya ingat betul majelis-majelis zikir habaib yang bermunculan mendatangi para jamaah dimulai di awal-awal 2000-an, menggantikan majelis-majelis zikir di lingkungan habaib hingga muncul sebuah adagium “jika pada awalnya jamaah majelis taklim mendatangi habaib, maka saat ini habaib mendatangi para jamaah”. Melalui modal sejarah dan tradisi sebagai pewaris ajaran Nabi Muhammad Saw, habaib mampu mendatangkan ratusan bahkan ribuan jamaah. Hal ini tentunya memudahkan habaib untuk menebarkan kebaikan dan juga menegaskan posisinya sebagai pewaris ajaran Nabi.
Hal inilah yang membuat peran habaib signifikan dalam politik elektoral: kemampuan menggerakan dan bahkan mengakumulasikan jumlah massa. Jika Tarim dan Hadhramaut adalah pohon penghasil bibit, maka demokrasi adalah pupuk yang menyuburkan tanaman identitas tersebut.
Meskipun demikian, penulis buku ini sudah menyenggol beberapa kata kunci yang identik dalam demokrasi, semisal:
… belakangan mulai dijadikan ajang provokasi, agitasi, dan kampanye politik (hlm.199)
Hemat saya, kalangan Alawiyyin dengan segala kemapanan status sosial di dalam masyarakat dihadapkan pada situasi yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya di masa demokrasi ini: masa di mana perputaran akumulasi modal sosial dan kultural terjadi begitu cepat dan menstimulasi modal material yang diawali dengan jumlah jamaah yang banyak, yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Jika kesenjangan yang terbatas dalam ruang-ruang kultural dan agama telah bertransformasi menjadi kesenjangan material yang besar di ranah sosial, maka di titik itulah potensi masalah besar yang belum pernah dibayangkan sebelumnya akan muncul.
Terlepas dari analisis sok-sokan saya di atas, saya sangat berharap buku ini mampu menstimulasi perdebatan soal Hadhrami dan Alawiyyin secara akademis dan terbuka. Tentu saja bagi internal Alawiyyin, upaya-upaya ini dibutuhkan untuk selalu mendorong kelompok agar senantiasa menjawab tantangan zaman dan menempatkan diri dalam roda sejarah supaya tidak tergilas.
Untuk sebuah harapan: mengabdi pada kebaikan dan ketulusan.[]
Geradi Yudhistira adalah peneliti antropologi politik University of Amsterdam