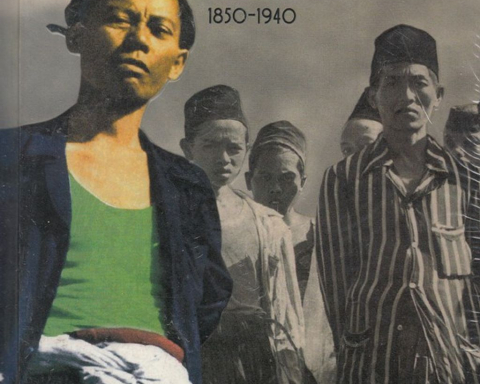Untuk membuka tulisan ini, cukuplah kita mengutip pendapat Robert Hefner, “Buku yang terpenting [dan] terbaik, an interesting and well written book (sebuah buku yang menarik dan ditulis dengan baik) yang telah saya baca dalam 10 tahun terakhir.” Robert Hefner, yang akrab disapa Pak Bob oleh rekan-rekannya di Indonesia, adalah Profesor Antropologi dan Direktur Institute on Culture, Religion, and World Affairs, Boston University.
Pak Bob berbicara sebagai salah satu penanggap—dengan bahasa Indonesia yang cukup lancar—dalam acara peluncuran buku karya Inaya Rakhmani yang berjudul Pengarusutamaan Islam di Indonesia: Televisi, Identitas, dan Kelas Menengah, yang diselenggarakan oleh Asia Research Centre Universitas Indonesia (ARC-UI) pada 19 Juli 2022 secara daring.

Buku ini sebelumnya pernah diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul Mainstreaming Islam in Indonesia: Television, Identity & the Middle Classoleh Palgrave Macmillan, New York, Amerika Serikat. Buku ini kemudian diterbitkan kembali ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Grup Mizan pada Juli 2022.
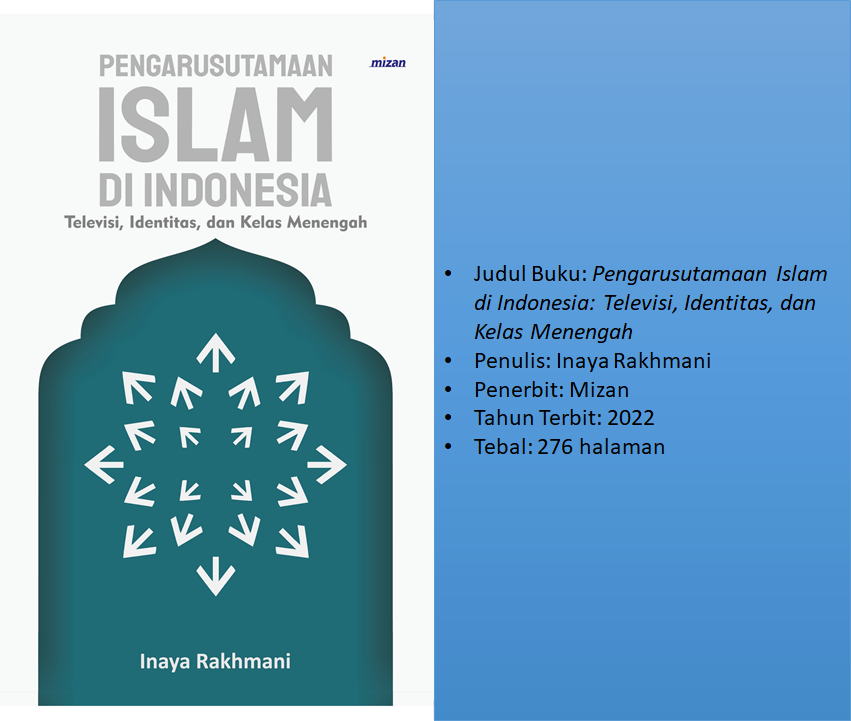
Mengawali tentang buku ini, Inaya menulis, “Argumen buku ini cukup sederhana. Ia menyoal peran media dalam perubahan sosial, dan bagaimana media kadang justru menghambat perubahan.”
Dari sekian banyak kelompok masyarakat yang ada, Inaya menyoroti kelompok kelas menengah Muslim yang cara pikir mereka dipengaruhi oleh media, yang pada gilirannya justru mereka juga mampu mengubah lanskap sosial dan politik di Indonesia.
Kendatipun secara umum tidak ada kata sepakat dengan siapa yang dimaksud dengan kelas menengah, Inaya memberikan batasan tersendiri, “Kelas menengah yang dikaji di sini adalah kalangan yang mendapat manfaat dari efisiensi yang disediakan masyarakat urban modern.”
Lebih spesifik, kelas menengah di sini maksudnya adalah masyarakat Muslim Indonesia yang awalnya mendapatkan manfaat dari liberalisasi dan deregulasi, serta melesatnya pertumbuhan ekonomi pada 1980-an; yang seiring berjalannya waktu, keberadaan mereka juga semakin bertambah banyak.
Keberadaan kelas menengah ini diawali dari Ibu Kota Jakarta, yang dalam waktu singkat gaya hidup mereka menjadi standar bagi penduduk kota lain yang ingin diakui dan terlibat dalam kancah pergaulan global.
Jumlah kelas menengah di Indonesia terus bertambah, menurut laporan Bank Dunia, per 2021 jumlahnya diperkirakan mencapai 50 juta orang. Penilaian ini didasarkan pada penduduk yang berpenghasilan mulai dari Rp 1,2 juta hingga Rp 6 juta per bulannya.
Kebangkitan Media Televisi
Salah satu produk utama yang dikonsumsi oleh kelas menengah adalah televisi. Sebagai gambaran, pada 1990 pemilik televisi hanya 4% dari seluruh penduduk Indonesia, pada 1997 naik menjadi 10%, dan pada periode 2000-an, jumlah penikmat televisi beserta media-media turunannya (koran, tabloid, majalah, dan lain-lain) secara drastis naik menjadi 90%.
Inaya menjelaskan, Televisi Republik Indonesia (TVRI) didirikan 1962 pada masa pemerintahan Soekarno, yang secara strategis dicanangkan untuk menyatukan bangsa yang heterogen dalam satu semangat pasca-kolonial. TVRI secara efektif digunakan Soekarno untuk unjuk simbol tentang lambang kebesaran dan kedaulatan nasional.
Masuk era Presiden Soeharto dengan Orde Baru-nya, TVRI digunakan untuk menggelorakan persatuan nasional, modernisasi, dan pembangunan yang berlangsung kurang lebih sejak 1962 hingga 1987. Selain itu, TVRI juga terus didorong untuk menyuarakan Pancasila dan doktrin anti SARA (Suku, Agama, Ras, Antar-Golongan).

Hingga pada periode 1980-an, Pemerintah Orde Baru mengadopsi sistem ekonomi Liberal, yang salah satu efeknya memunculkan regulasi baru, yaitu bahwa antena parabola, jaringan kabel, dan rental video kaset boleh didistribusikan ke masyarakat. Penikmat dari kebijakan ini tiada lain adalah kelompok kelas menengah.
Dengan segera kelas menengah menikmati produk-produk televisi dan film asing, utamanya dari Barat. Setelah terpapar program televisi asing, permintaan pemirsa dalam negeri akan program yang berkualitas pun meningkat—lebih dari kemampuan produksi TVRI.
Dengan desakan atas kebutuhan ini, Soeharto berkompromi untuk memprivatisasi izin siar yang tadinya dimonopoli oleh TVRI, meskipun hanya dibagikan kepada kroni-kroni terdekatnya. Pada tahun-tahun itu maka berdirilah lima stasiun televisi swasta di Indonesia: RCTI (1987), SCTV (1989), TPI (1990), ANTV (1993), dan Indosiar (1995).
Kelas Menengah menjadi Pangsa Pasar Televisi
Pada tahun 1998, Soeharto lengser dan mediapun mendapatkan kebebasan yang lebih luas lagi. Di sini, para pelaku industri televisi menangkap peluang besar—yang sudah disadari dari sejak dulu namun baru memungkinkan untuk dieksekusi pada momen ini—untuk mengeksploitasi Muslim kelas menengah.
Pada 2000-2002, ketika Indonesia dipimpin Presiden B. J. Habibie, pemerintah memberikan izin berdirinya lima stasiun televisi komersial baru: Metro TV, Trans TV, Global TV, TV 7, dan LaTivi. Dengan penambahan ini, maka stasiun televisi swasta di Indonesia menjadi berjumlah sepuluh. Namun berbeda dengan lima stasiun swasta sebelumnya yang dimiliki kroni-kroni Soeharto, yang baru ini dimiliki oleh pengusaha-pengusaha baru
Demikian seterusnya, media berkembang hingga pada masa-masa berikutnya melahirkan raksasa-raksasa media seperti MNC Group, Jawa Pos, Kompas Gramedia Group, Trans Corp, dan Mahaka Media Group.
Dengan masuknya era kebebasan media, pada 1998 Raam Punjabi—produser film dan sinetron Indonesia keturunan India—dengan cermat melihat keberadaan Muslim kelas menengah yang jumlahnya besar untuk dijadikan pangsa pasar. Dia memproduksi drama televisi Islami yang disiarkan setiap hari selama Ramadan pada tahun itu.
Punjabi menuai kesuksesan dan gerak langkahnya segera diikuti oleh produser-produser lain. Dengan segala dinamika pencarian ceruk pembeda, akhirnya muncul segmentasi-segmentasi pasar Muslim baru. Inaya membaginya ke dalam tiga kelompok segmen penikmat konten: drama supernatural, melodrama islami, dan komedi islami.
Konten-konten Islami ini pada gilirannya tidak terpaku hanya sebatas ditayangkan pada bulan Ramadan saja, melainkan menjadi setiap hari dan pada jam-jam utama. Para stasiun televisi ramai-ramai memproduksi konten jenis seperti ini. Tidak ada agama lain yang dikaitkan dengan sinetron religi meskipun ada sekitar 20 persen pemirsa yang beragama dan berkeyakinan selain Islam di Indonesia. Pada perkembangannya, stasiun televisi juga memproduksi konten selain sinetron, seperti kompetisi dakwah dan mengaji.

Meskipun sudah terbagi-bagi ke dalam segmentasi, setelah melalui pengamatan terhadap ratusan episode sinetron religi, Inaya menyimpulkan, bahwa jelas narasi-narasi yang ditampilkan mencerminkan kecemasan kelas menengah dalam menghadapi perubahan sosial yang khas, dan bagaimana pandangan Islam dapat membantu mereka bernavigasi secara sosial.
Kecemasan tersebut bisa diklasifikasikan berdasarkan segmentasi tadi. Dalam drama supernatural, sasarannya adalah kelompok kelas menengah rentan, yaitu kaum Muslim terpinggirkan yang memiliki keterbatasan materi dan mengalami ketimpangan sosial. Dengan demikian, drama ini menampilkan kisah-kisah kaum miskin yang penderitaannya menjadi ringan karena mendengar berbagai kutipan ayat Al-Quran yang menjanjikan bahwa Allah akan menolong mereka melalui kejadian-kejadian supernatural yang misterius.
Dalam melodrama islami, tokoh yang ditampilkan adalah penduduk urban yang menguasai berbagai keterampilan sosial modern sehingga mereka lebih berdaya. Namun dalam perjalanannya ini, mereka terpapar gaya hidup materialis dan hedonis yang mencemari kesalehan islami. Kisah selanjutnya sudah dapat ditebak, bahwa mereka akan mengalami pertobatan dan menjalankan kesalehan pribadi. Sinetron jenis seperti ini lebih menggambarkan Islam sebagai agama yang privat dan pribadi.
Dan dalam komedi islami, konflik sosial diselesaikan lewat penerapan etika islami, sehingga menggambarkan Al-Quran dan Hadis sebagai panduan untuk persoalan sehari-hari. Muslim kelas menengah rentan didorong untuk mengangkat status sosial mereka melalui pekerjaan dan pendidikan modern untuk dapat berpartisipasi dalam produksi ekonomi. Musala menjadi ruang yang menyelaraskan urusan publik dan etika Islami, karena di sinilah perbincangan soal bisnis dan ibadah dapat dilakukan. Dengan begitu, praktik keagamaan tidak diprivatisasi melainkan digambarkan sebagai kegiatan komunal yang menyeimbangkan hubungan sosial antara sesama Muslim.
Kesimpulan
Kesimpulan dari buku Pengarusutamaan Islam di Indonesia ini cukup mengejutkan, bahwa ternyata televisi komersial dalam konten islaminya bukan semata mencari keuntungan dari iklan dan pangsa pasar yang luas. Menurut Inaya, televisi komersial pada kenyataannya masih membawa-bawa agenda penguasa lama, yaitu rezim Soekarno dan Soeharto. Inilah yang dimaksud Inaya dengan “pengarusutamaan Islam”.
Meskipun pengelolaan televisi komersial sudah menjadi lebih liberal, namun dalam hal agenda keislaman mereka masih menjaga agar arus utama nilai-nilai lama terjaga. Nilai lama yang dibawa dari era Soekarno adalah semangat anti-kolonialisme, bahwa meskipun berbeda-beda bangsa ini mesti tetap bersatu. Kelemahan dari arus lama ini adalah penegasian terhadap penjajahan lokal yang sebenarnya pernah terjadi atau bahkan masih terjadi.
Inaya menggambarkan bahwa raja-raja Aceh dulu pernah “menjajah” daerah pesisir Minangkabau, raja-raja Bugis dulu pernah memperbudak orang-orang pedalaman Toraja, para bangsawan Jawa pernah berusaha menaklukkan dataran tinggi Sunda, atau raja-raja Bali pernah menguasai pulau suku Sasak. Karena itu, Islam arus utama menyingkirkan sumber-sumber “perbedaan”.
Adapun pengarusutamaan yang dibawa dari era Soeharto adalah rekayasa budaya negara developmentalis ala Orde Baru yang hanya merangkul identitas etnis dan agama yang mayoritas saja. Terlepas dari kebijakan dan regulasi yang lebih terbuka dan baru pada masa tersebut, narasi yang ditampilkan masih tetap sama, yaitu dukungan terhadap modernitas demi persatuan nasional. Kelemahan dari arus utama ini adalah mereka terus menyisihkan kelompok sosial tradisional, rural, dan indigen sebagai kelompok primitif. Posisi kultural Muslim, Jawa, dan Jakarta—atau pusat—yang sudah mapan justru dijadikan tolok ukur bagi agama, etnis, dan daerah lain—atau pinggiran—untuk mereka samai.
Dengan adanya tolok ukur Muslim, Jawa, dan Jakarta sebagai yang utama, maka kelompok lain merasa perlu menyaingi kelompok dominan ini. Sayangnya ketika berhasil menyaingi kelompok dominan ini dengan standar-standarnya, menurut Inaya, sesungguhnya mereka sedang memupus akses kelompok minoritas (yang masih dalam kategori kelas menengah) di daerahnya sendiri, yaitu akses untuk mendapatkan kesetaraan.
Kritik
Meski buku ini mendapatkan sanjungan dari Robert Hefner, namun beliau sendiri berpendapat bahwa uraian di dalam buku ini lebih luas dari kesimpulannya. Artinya, ada kemungkinan bahwa beberapa pembahasan di dalam uraian, sebetulnya ada yang kurang relevan dengan kesimpulan.
Hal lainnya adalah, Inaya tidak menjelaskan bagaimana pengaruh media yang begitu besar terhadap kelas menengah ini dapat merembes kepada kelas-kelas lainnya. Misalnya masyarakat kelas bawah yang jumlahnya jauh lebih besar daripada kelas manapun. Di dalam buku dijelaskan, bahwa pada awalnya memang betul, yang mampu memiliki televisi hanya kelas menengah. Tapi belakangan, Inaya sendiri menjelaskan, bahwa media televisi dengan berbagai turunannya telah mampu menjangkau 90% populasi. Jika masyarakat kelas menengah yang lebih terdidik saja bisa begitu terpengaruh, bagaimana hasilnya untuk masyarakat kelas bawah?
Jika kita hendak memaklumi, buku ini awalnya memang sebuah disertasi. Sebagaimana karya-karya ilmiah lainnya, maka subjek pembahasan perlu dibatasi. Namun, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif—yang mungkin dibutuhkan oleh pembaca—dan memuaskan rasa keingintahuan khalayak yang lebih luas, ada baiknya buku ini juga membahas pengaruh media terhadap kelas-kelas lainnya. Hal lainnya yang kurang disinggung oleh Inaya adalah pergeseran konsumsi media, dari televisi menjadi internet (lebih tepatnya media sosial). Sudah banyak lembaga survei yang memberikan laporan bahwa pengguna internet di Indonesia naik secara drastis dalam setiap tahunnya. Sebagaimana yang terjadi melalui televisi, mestinya internet pun juga mampu atau potensial “mengarusutamakan” kalangan Islam di Indonesia.[PH]