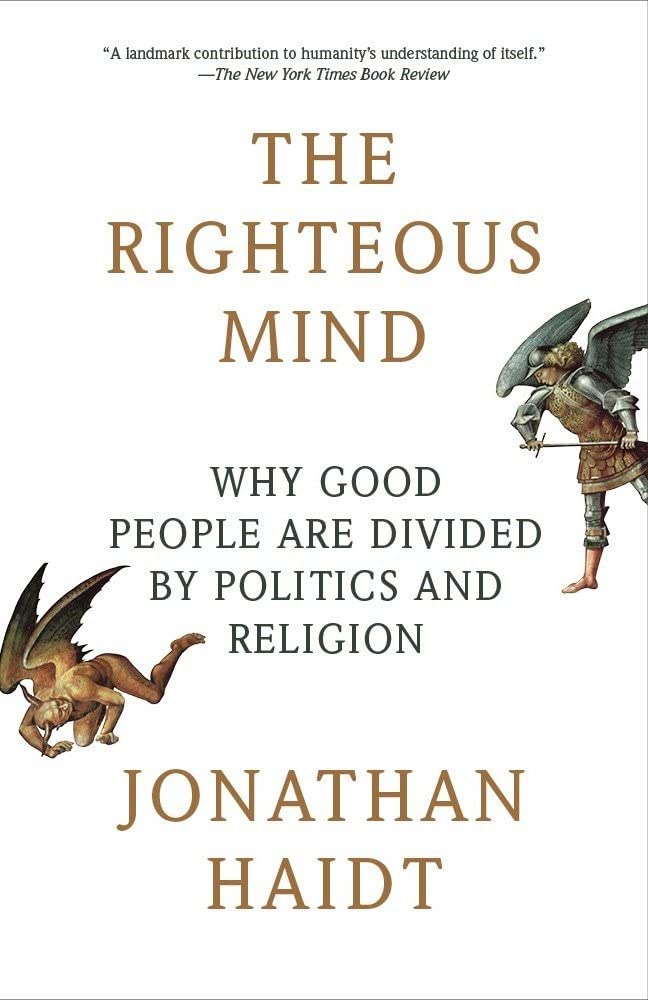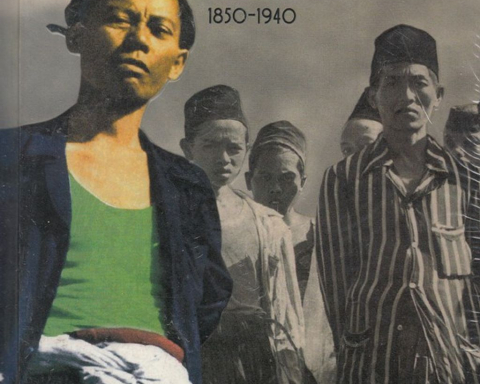Keterbatasan biologis, psikologis, dan budaya mempersulit komunikasi dan saling mengerti di antara sesama manusia. Lalu, masih bisakah kita akur dalam ketidaksetujuan?
Selama kira-kira sepuluh tahun belakangan ini, masyarakat Amerika Serikat terbelah sengit dalam dua kubu: konservatif dan liberal; kubu Partai Republik dan kubu Partai Demokrat.
Keterbelahan itu tidak seperti beberapa puluh tahun sebelumnya. Lebih berat. Tiap-tiap berpikir betapa salahnya posisi dan keyakinan kubu lain. Seolah dalam peperangan, nasib kehidupan mendatang sangat ditentukan oleh kemenangan kubu “kita” dalam pemilu.
Keadaan kita di Indonesia tidak sepenuhnya sama, tapi mungkin tidak jauh berbeda. Maka, pertanyaan yang sama kadang muncul juga dalam benak kita: kenapa orang-orang baik terbelah karena politik dan keyakinan?
Jonathan Haidt, seorang psikolog dari Universitas Virginia, berusaha menjawab soal tersebut dalam bukunya yang terbit 10 tahun lalu: The Righteous Mind. Why Good People are Divided by Politics and Religion. The Righteous Mind bisa dibilang lama tapi saya melihatnya masih sangat relevan untuk saat ini, dan masih sangat perlu dibaca. Meskipun sudah pasti banyak teori lain yang menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi, paparan Haidt dalam buku ini tetap sangat menarik.
Haidt menunjuk pada tiga hal mendasar: masalah biologi, budaya, dan psikologi.
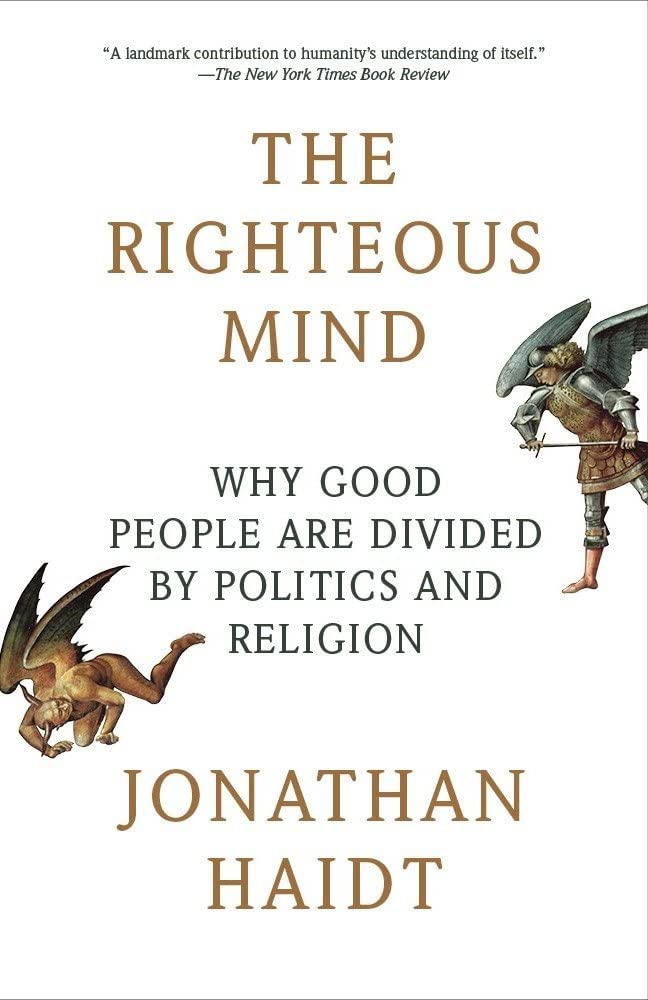
- Judul buku: The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion
- Penulis: Jonathan Haidt
- Penerbit: Knopf Doubleday Publishing Group
- Terbit: 12 Februari 2013
- Tebal: 528 halaman
Masalah biologi
Kita tentu tidak asing dengan situasi saat perilaku mengalahkan nalar. Anda mungkin mengalami itu ketika pernah mencoba berhenti merokok dan gagal, ketika menunda-nunda sesuatu yang Anda tahu penundaan itu bakal membuat Anda kesulitan, ketika alarm gagal membangunkan Anda, ketika makan berlebihan, ketika tahu harus berolahraga tapi selalu malas memulainya, ketika marah dan mengatakan sesuatu yang kelak Anda sesali, ketika tidak menerima nasehat orang yang anda tahu itu benar, dan seterusnya.
Kenapa itu bisa terjadi?
Para psikolog menerangkan, otak memiliki dua sistem independen yang bekerja bareng setiap saat. Yang pertama, sisi emosional. Ia adalah bagian dari diri kita yang naluriah, yang merasakan sakit dan senang. Yang kedua, sisi rasional, yang juga dikenal sebagai sistem reflektif atau kesadaran. Ia adalah bagian dari diri kita yang memikirkan dan menganalisis serta melihat ke masa depan. Walaupun bekerja bareng, dua sistem ini tidak selalu seiring, malahan sering tarik-menarik dan menciptakan ketegangan.
Dalam beberapa dekade terakhir, para psikolog telah belajar banyak tentang kedua sistem itu. Namun, umat manusia tentu saja sudah sejak lama menyadari ketegangan tersebut. Plato mengatakan, di kepala kita, ada kusir rasional yang harus mengendalikan kuda nakal yang hampir-hampir kebal terhadap cambuk dan tongkat pengarah. Sigmund Freud menulis tentang id yang egois dan superego yang bertanggung jawab, hati-hati, dan teliti, juga tentang ego, yang menjadi perantara di antara keduanya. Baru-baru ini, para ekonom perilaku menjuluki kedua sistem itu sebagai “perencana” dan “pelaku”.
Dari berbagai penjelasan yang ada, agaknya penjelasan paling sederhana dan pas adalah analogi “Gajah” dan “Penunggang “ yang digunakan oleh Haidt. Analogi ini pertama kali muncul dalam bukunya The Happiness Hypothesis.
Haidt mengumpamakan sisi emosional kita sebagai “Gajah” dan sisi rasional kita adalah “Penunggangnya”. Bertengger di atas “Gajah”, “Penunggang” memegang kendali dan tampaknya menjadi pemimpin. Namun, “Penunggang” itu sangat kecil jika dibandingkan dengan “Gajah”. Setiapkali “Gajah” seberat enam ton dan Penunggang tidak setuju arah mana yang harus ditempuh, “Penunggang” pasti kewalahan, tidak berdaya, dan kalah.
Selain punya daya besar, Sang “Gajah” memiliki kekuatan besar lain: cinta, welas asih, serta kesetiaan. Kekuatan ini adalah kekuatan insting sengit yang diperlukan ketika kita menjaga anak dari segala marabahaya, misalnya, atau juga kekuatan agar kita bisa tegak percaya diri.
Namun, “Gajah” punya kelemahan besar. Dia condong kepada kenikmatan segera. Itu berlawanan dengan kecenderungan “Penunggang”, yang mampu merencana jangka panjang jauh ke depan (kita berhemat sekarang untuk tabungan hari depan, menolak es krim sekarang untuk kesehatan jangka panjang, dan lain sebagainya).
Maka, dalam segala perubahan yang diinginkan, “Gajah”-lah yang memegang peran utama. Untuk bisa bergerak maju menuju suatu tujuan, diperlukan energi dan dorongan dari “Gajah”. Dalam hal tersebut, “Penunggang” atau nalar punya kelemahan besar. Dia cenderung terlalu lama dan ruwet berpikir untuk sampai pada suatu keputusan. Maka, “Gajah” biasanya akan mengambil alih membuat keputusan.
Jika menginginkan perubahan, kita harus menarik keduanya. “Penunggang” menyediakan perencanaan dan arahan sementara “Gajah” menyediakan energi. Jika hanya mencapai “Penunggang”, kita memiliki arah tapi tanpa motivasi. Jika mencapai “Gajah” saja, kita cuma punya hasrat yang tanpa arah. Keduanya melumpuhkan. Namun, saat “Gajah” dan “Penunggang” bergerak bersama, perubahan bisa datang dengan mudah.
Bagaimana cara menarik keduanya? Bagaimana membujuk “Gajah” agar “Penunggang” atau nalar bisa didengar?
Itu sebetulnya adalah masalah komunikasi. Komunikasi dalam diri kita sendiri ketika kita akan mengadakan perubahan, atau komunikasi dengan orang lain agar penalaran kita dapat dipahaminya.
Haidt menyimpulkan bahwa ketidaktahuan kita pada struktur otak adalah penyebab pertama terjadinya keterbelahan. Kita keliru dalam cara berkomunikasi. Orang pada umumnya langsung bicara dari nalar menuju nalar, kepada sang “Penunggang”, dan bukan bicara kepada “Gajah” terlebih dahulu. Semestinya buka dulu hatinya, kemudian baru jelaskan penalarannya.
Komunikasi politik biasanya terjadi dalam perdebatan, dalam modus pertarungan (combat mode), yang bertujuan terutama untuk mematahkan argumen lawan. Pendekatan tersebut tidak bakal berguna. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. “Gajah” yang intuitif dengan cepat akan menolaknya, dan nalar malahan akan mencari pembenaran dari penolakan tersebut. Seharusnya pertukaran pendapat dilakukan terlebih dahulu dalam modus persahabatan (relationship mode), yang kemudian bisa meningkat pada modus penemuan (discovery mode) di mana tiap-tiap pihak, “Gajah” dan “Penunggang”, bersama-sama akan bisa menemukan perspektif baru, perspektif orang lain.
Sebagai catatan, ada satu buku khusus tentang bagaimana teknik mengusahakan perubahan. Buku tersebut adalah Switch: How to Change Things When Change Is Hard, sebuah buku laris karangan dua bersaudara Chip dan Dan Heath. Isinya tentang bagaimana membujuk “Gajah” agar mau mendengar pendapat “Penunggang”.
Masalah Kebudayaan
Dari pengalaman dan penelitiannya, Haidt menyusun teori yang dinamakan “Teori Fondasi Moral” (Moral Foundation Theory). Begini penjelasannya.
Manusia mempunyai lima reseptor rasa pada lidahnya, yang berfungsi mengecap berbagai rasa: manis, asam, asin, pahit, dan gurih. Tergantung dari budaya apa seseorang berasal, kebiasaan menyebabkan manusia lebih suka masakan yang lebih manis atau lebih asin, dan seterusnya.
Nah, selain reseptor rasa, manusia juga punya indera pengecap moral. Ada enam macam reseptor moral menurut Haidt. Keenamnya adalah kepedulian/membahayakan (care/harm), keadilan/kecurangan (fairness /cheating), loyalitas/pengkhianatan (loyalty/betrayal), kewenangan/pembangkangan (authority/subversion), kesucian/kejijikan (sancity/degradation), dan kemerdekaan/penindasan (liberty/oppression).
Fondasi kepedulian/membahayakan berkembang dari insting melindungi anak yang rentan dari marabahaya. Itu menyebabkan kita sensitif terhadap tanda-tanda penderitaan makhluk dan permintaan tolong. Itu mengakibatkan kita membenci kekejaman dan mendorong kita memberi pertolongan.
Fondasi keadilan/kecurangan berkembang secara evolutif dari meraih keuntungan kerjasama tanpa dirugikan. Itu membuat kita sensitif terhadap tanda-tanda sifat baik atau buruk dari seseorang untuk diajak bekerja sama saling menguntungkan. Landasan tersebut membuat kita ingin menjauhi dan menghukum pelaku kecurangan.
Fondasi loyalitas/pengkhianatan berkembang dari membentuk dan menjaga perkawanan atau koalisi. Itu membuat kita sensitif terhadap orang-orang yang menunjukkan tanda-tanda sebagai (atau bukan) pemain tim yang baik. Itu membuat kita mempercayai dan mengganjar baik orang tersebut, dan membuat kita ingin melukai, mengecilkan, dan bahkan membunuh orang yang mengkhianati kelompok.
Fondasi kewenangan/pembangkangan berkembang dari tantangan adaptif untuk menjalin hubungan yang akan menguntungkan kita dalam hierarki sosial. Itu membuat kita peka terhadap tanda-tanda pangkat atau status, peka terhadap tanda-tanda bahwa orang lain berperilaku pantas (atau tidak) dalam posisi yang dipunyainya. Dari landasan ini, muncul sikap menghormati orang lebih tua, respek kepada orang tua, menghargai atau tidak kurang ajar kepada pimpinan.
Fondasi kesucian/kejijikan berkembang dari dilema manusia sebagai pemakan segala atau omnivora, atau terhadap tantangan yang lebih luas dari hidup di dunia patogen dan parasit. Kita memilih makanan tertentu dan jijik pada makanan yang dianggap kotor. Ini termasuk sistem kekebalan perilaku, yang dapat membuat kita waspada terhadap beragam objek dan ancaman simbolis.
Itu memungkinkan orang untuk memberi nilai irasional dan ekstrem—baik positif maupun negatif—pada pelbagai perilaku, yang dianggap penting untuk menjaga kelestarian kelompok. Fondasi ini sering sama sekali tidak dirasakan oleh sebagian masyarakat liberal Barat. Mengapa Muslim bersikap keras terhadap penghinaan Nabi Muhammad, pembakaran al-Quran, dan lain sebagainya. Kaum liberal juga tidak mengerti kenapa ada yang tidak suka pada seks bebas atau LGBT. Kenapa ada pengertian halal dan haram dalam berbagai agama.
Fondasi kemerdekaan/penindasan berkembang dari pengalaman kelompok kecil yang bila diberi kesempatan, akan mendominasi, menggertak, dan membatasi orang lain. Hal tersebut membuat orang waspada terhadap tanda-tanda percobaan dominasi. Ini memicu dorongan bersatu melawan perundungan dan menggulingkan para tiran. Fondasi ini mendukung egalitarianisme dan anti-otoritarianisme.
Seperti juga masakan, keyakinan moral seseorang tidak hanya terdiri dari satu atau dua fondasi moral tadi. Itu biasanya berupa kombinasi banyak komponen landasan moral dengan takaran masing-masing yang berbeda. Itu bergantung pada kebiasaan, lingkungan hidup dia berasal, dan bahkan dari bawaan DNA. Itu membuat dia lebih berselera pada yang lebih manis, atau yang lebih asin, atau yang lebih gurih. Tapi kemudian selera juga bisa berkembang dari pergaulan antarorang, atau antarmasyarakat dan antarbudaya. Hal tersebut merupakan pengalaman kesempatan mencicipi masakan moral berbeda.
Soal selera adalah soal yang hanya bisa dipahami, bukan dicari penalarannya. Berdasarkan penelitian survei yang ekstensif, Haidt menyimpulkan bahwa individu yang mengidentifikasi diri sebagai liberal memiliki perasaan kuat pada dua landasan moralitas care/harm dan fairness/cheating, sementara kaum konservatif menggunakan keenamnya. Haidt kemudian berani menyimpulkan bahwa kemampuan Partai Republik untuk berbicara kepada pemilih dengan keenam landasan moral telah memberi keuntungan menang pada pemilihan presiden beberapa kali sejak 1980.
Masalah psikologi
Gustave Le Bon (1841-1941), bapak psikologi massa, dalam The Crowds: A Study of Popular Mind bicara bahwa dalam kerumunan, manusia bisa kehilangan diri. Bagai kesurupan, individu-individu menjelma menjadi makhluk baru yang jauh lebih besar daripada dirinya.
Haidt bicara soal yang sama dari perspektif berbeda. Menurutnya, manusia itu makhluk ganda. Makhluk individual tapi sekaligus “makhluk kawanan” seperti kawanan lebah. Manusia itu selfish, mementingkan diri sendiri tapi pada suatu ketika sekaligus groupish, mementingkan kawanannya sendiri.
Ada sakelar “berubah makhluk” dalam diri manusia. Alat itu bekerja pada beberapa kondisi tertentu saja. Ketika terpukau oleh dahsyatnya atau indahnya alam, sakelar bekerja. Tiba-tiba kita merasa cuma sebagai bagian kecil dari alam raya. Ketika dalam perang, seorang tentara bisa mengorbankan nyawanya tanpa banyak perhitungan buat keselamatan kawanan regunya, persis seperti seekor lebah yang rela mati demi keselamatan sarangnya. Satu mati bukan apa-apa, bagian sangat kecil dari yang jauh lebih besar.
Ya, orang sering egois, dan sebagian besar perilaku moral, politik, dan agama dapat dipahami sebagai cara terselubung untuk mengejar kepentingan pribadi (lihat saja kemunafikan yang mengerikan dari begitu banyak politisi dan pemimpin agama). Namun, juga benar bahwa manusia itu senang bergabung ke dalam tim, atau senang kumpul-kumpul, groupish. Kemudian dengan memasang identitas kelompok, mereka bekerja bahu-membahu dengan banyak orang asing untuk tujuan bersama. Egoistis individual kemudian menjelma menjadi egoistis kelompok.
Bermacam pengikat kelompok yang jadi identitas seperti persamaan keyakinan, moralitas, bangsa, warna kulit, partai politik, dan lain-lain. Semuanya dibela mati-matian dengan cara apa saja. Membela grup membutakan segala penalaran. Seperti dalam permainan olahraga, tiap-tiap grup cuma berusaha mendapatkan gol untuk mengalahkan lawan.
Kita semua tersedot masuk ke dalam fenomena buta dalam kerumunan. Kita berkerumun pada suatu nilai-nilai yang kita anggap suci, kemudian menyemburkan pernyataan bahwa kitalah yang sangat benar. “Orang sana, kelompok sana, itu jelas buta terhadap kebenaran, buta pada sains, dan tidak menggunakan asal sehat”, dan lain-lain. Kita tidak sadar, bahwa yang terjadi sebenarnya adalah kita semua ini buta pada yang dianggap penting oleh orang lain.
Kesimpulan: masih bisakah kita akur dalam ketidaksetujuan?
Penjelasan Haidt dalam The Righteous Mind rupanya menegaskan kembali bahwa perbedaan adalah fitrah bagi kemanusiaan. Bagaimana keterbatasan biologis, psikologis, dan budaya mempersulit komunikasi dan saling mengerti antarsesama. Ketidaksetujuan kemudian adalah keniscayaan
Pertanyaannya, masih bisakah kita akur dalam ketidaksetujuan?
Saya tidak mendapatkan resep khusus dari Haidt untuk pertanyaan yang dia ajukan. Mungkin tujuan utama buku ini hanyalah menggambarkan keadaan lebih jelas mengapa terjadi keterbelahan.
Dari situ, dia mengharapkan orang-orang baik dari kedua belah pihak berusaha memahami yang lain dengan lebih baik. Berusaha berkomunikasi yang lebih baik, bicara pada “Gajah”, dan bukan hanya pada “Penunggang”. Open the heart first, and then see the logic. Bicara lebih santun. Kemudian lebih sadar pada banyak halangan psikologis dalam diri kita manusia.
Tapi ada satu kalimat penting yang saya ingat dari buku ini: “…kalau Anda ingin bisa paham jalan pikiran grup lain, maka cari tahu soal yang oleh mereka dianggap prinsip yang paling suci.”[]