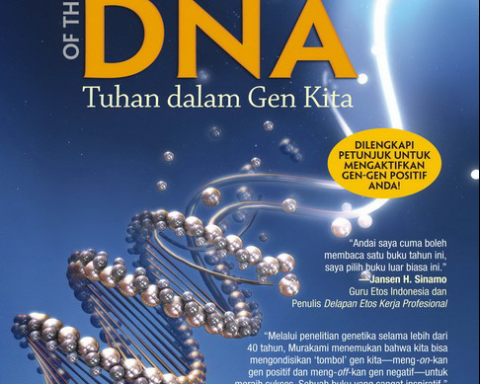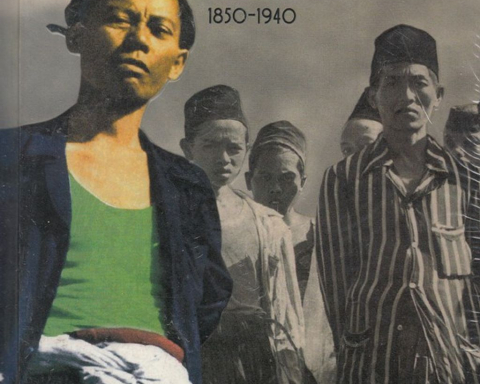Dengan mengulas penelitian para saintis, dalam Humandkind, a Hopeful History, Rutger Bregman mengungkap bahwa daya tahan keberlangsungan hidup manusia bukanlah karena kompetisi seperti dalam Darwinisme sosial, tapi kemampuan kita saling bekerja sama dan mencintai.
Hadiah Nobel Kedokteran 2022 baru saja diumumkan dan diraih oleh pakar Genetika Evolusi asal Swedia, Svante Paabo. Karyanya membantu meluruskan pemahaman kita tentang evolusi manusia.
Dengan mengungkap perbedaan genetik yang membedakan semua manusia yang hidup dari hominin yang punah, penemuan Paablo memberi dasar bagi kita untuk mengeksplorasi apa yang membuat kita menjadi manusia yang unik. Dia menemukan bahwa transfer gen telah terjadi dari hominin yang kini punah ke Homo Sapiens setelah migrasi keluar dari Afrika sekitar 70 ribu tahun lalu.
Penelitian genetika yang berhubungan dengan evolusi justru berkembang setelah pencetus utama teori evolusi, Charles Darwin, yang saat itu belum menggunakan basis genetika, membangun teorinya. Ahli genetika Jepang, Motoo Kimura, kemudian mengemukakan “neutral theory” yang menyatakan gen netrallah yang memicu adanya mutasi menuju evolusi. Dalam konteks ini, Richard Dawkins menggunakan istilah “selfish gene” (gen egois) sebagai pusat evolusi.
Pembahasan teori evolusi menjadi bagian penjelajahan sains yang makin memikat dalam mempelajari manusia dan peradabannya. Ikutan dari teori evolusi memberi paradigma yang melihat manusia dan perilaku kehidupannya. Keterkaitan evolusi dengan genetika ini mengarah kepada pemodelan budaya manusia.
Teori evolusi Darwin ikut memunculkan gagasan “survival of fittest”, bahwa organisme terbaik dalam beradaptasi dengan lingkungan adalah yang paling berhasil dalam bertahan hidup. Di tangan Herbert Spencer (1820-1903), sosiolog dan filosof Inggris, ungkapan ini diselaraskan dengan teorinya di bidang ekonomi terkait dengan “seleksi alam” atau kelangsungan hidup individu-individu terkuat.
Pendapat Spencer masuk ke dalam kategori kelompok Darwinisme Sosial. Istilah terakhir singkatnya dipahami sebagai teori yang memaklumkan bahwa “mereka yang kuat pantas mendapatkan kesuksesan, dan mereka yang lemah layak gagal”.
Dalam perkembangannya, baik setelah Darwin maupun Dawkin, banyak bermunculan saintis yang tidak sejalan dengan mereka, terutama pada aspek penyimpulan pemodelan budaya manusia. Pada 1902, profesor biologi Pyotr Alexeyevich Kropotkin, menerbitkan buku Mutual Aid: A Factor of Evolution (Kerjasama: Sebuah Faktor Evolusi), yang di dalamnya ia mempunyai pandangan alternatif dalam proses keberlangsungan hidup pada binatang dan manusia, melampaui klaim “Survival of the Fittest”.
Argumentasi utama Kropotkin adalah kehidupan sosial dan ekologis kita sejatinya menunjukkan kekuatan kerja sama, alih-alih kompetisi. Kropotkin menafsirkan kembali teori evolusi Darwin dan membalikkan asumsi bahwa evolusi manusia didorong karena kompetisi sengit untuk mempertahankan diri. Berlawanan dengan hal itu, Kropotkin menyatakakan evolusi manusia sangat ditunjang oleh cara manusia melindungi sesamanya.
Sejalan dengan itu, muncul pertanyaan mengenai kepunahan manusia purba yang digantikan oleh Homo Sapiens. Apakah benar Homo Sapien lebih kuat ataukah lebih cerdas?
Dalam kaitan itu, sejarawan mutakhir Rutger Bregman dalam bukunya Humandkind: a Hopeful History mengulas penemuan para saintis yang menyimpulkan bahwa Neandertal lebih kuat secara fisik. Lalu kecerdasan mereka? Otak Neandertal rata-rata 15 persen lebih besar daripada otak kita sekarang. Mereka lebih cerdas.
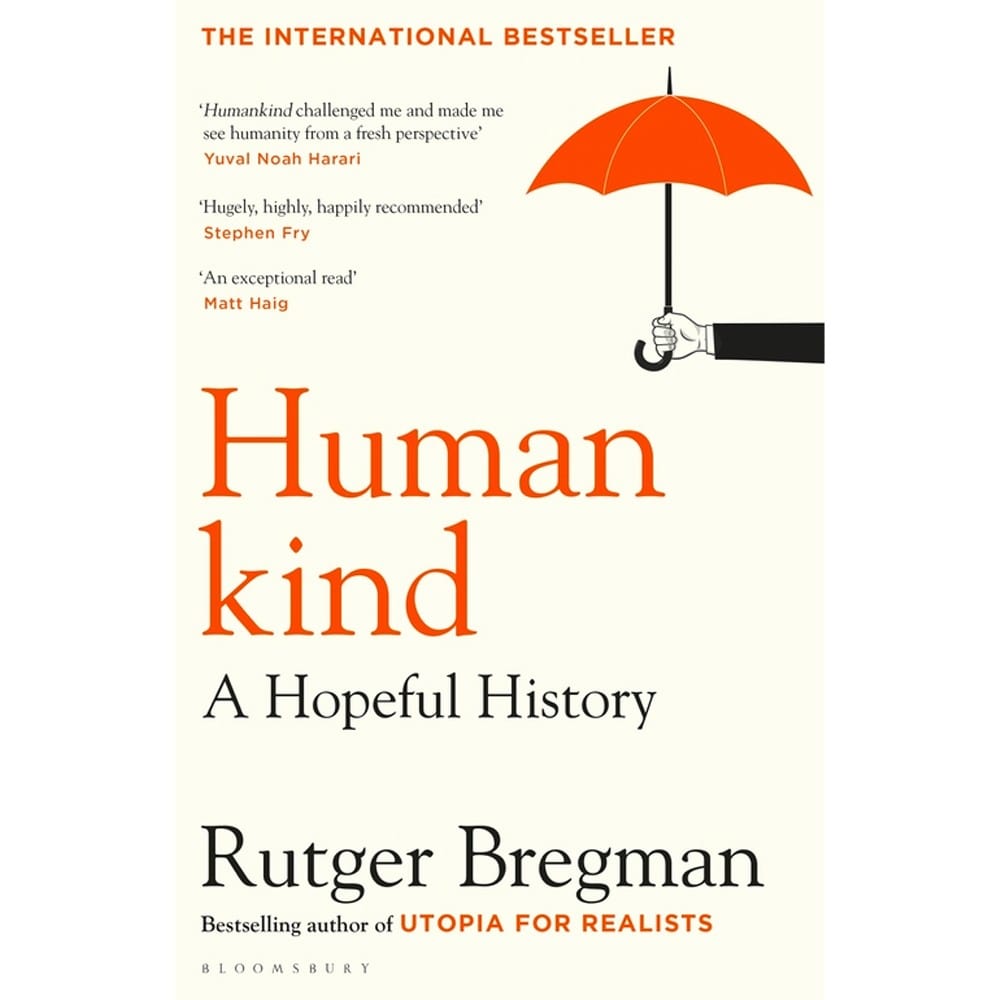
- Judul Buku: Humankid: A Hopeful History
- Penulis: Rutger Bregman
- Penerbit: Bloomsbury
- Terbit: September 2019
- Tebal: 496 halaman
Muncullah hipotesis bahwa seandainya kita, Homo Sapiens, tidak lebih kuat, tidak lebih berani, atau tidak lebih pintar daripada genus Homo yang telah punah itu, barangkali Homo Sapiens lebih kejam. Yuval Noah Harari berspekulasi, “Ketika Sapiens berjumpa Neandertal, hasilnya adalah kampanye pembersihan etnis pertama dan terpenting dalam sejarah.”
Apakah itu benar?
Berkat penemuan Svante Paabo, kita memahami bahwa urutan gen kuno dari kerabat kita yang telah punah mempengaruhi fisiologi manusia masa kini. Populasi Neandertal tinggal di Eurasia barat, sedangkan Denisovan menghuni bagian timur benua. Selama ekspansi keluar Afrika, Homo Sapiens tidak hanya bertemu tapi kawin dengan Neandertal dan Denisovan. Telah terjadi transfer gen dari manusia purba ke Homo Sapiens.
Dalam Humankind, Bregman secara menarik membahas penelitian yang dilakukan Dmitri Balyaez, seorang ahli zoologi dan genetika, bersama Lyudmila Trut, ahli biologi di Universitas Moskwa. Mereka meneliti rubah perak di Siberia sekitar 1958. Rubah perak adalah hewan yang tidak pernah dijinakkan sebelumnya. Penelitiannya untuk menjawab pertanyaan bagaimana mengubah pemangsa ganas menjadi hewan peliharaan jinak?
Seratus tahun sebelumnya, Darwin sudah memperhatikan bahwa hewan-hewan jinak, seperti kelinci, domba, babi, menunjukkan beberapa kemiripan mencolok. Hewan jinak lebih kecil daripada leluhurnya yang liar. Otak dan giginya lebih kecil. Kadang telinganya terkulai dan ekornya keriting.
Pada 1964, di generasi keempat dari percobaan, kedua ahli tersebut mulai mendapatkan rubah yang mengibaskan ekor. Di alam liar, rubah menjadi lebih agresif pada umur sekitar delapan minggu, tapi rubah biakan selektif kedua ahli tersebut tetap bersifat seperti anak rubah, suka bermain seharian.
Ada perubahan fisik yang tampak. Telinga rubah terkulai, ekornya melengkung, dan rambutnya mulai tampak berbintik. Moncong memendek, tulang mengecil, dan pejantan makin mirip betina. Bahkan rubah-rubah itu menggonggong seperti anjing.
Pada 1978, dua puluh tahun sesudah percobaan itu, dalam Kongres Genetika International, Dmitri memaparkan temuannya yang membuat para tamu terkesan. Dmitri menyampaikan gagasan revolusionernya. Dia menduga perubahan rubah disebabkan hormon. Rubah yang lebih ramah menghasilkan lebih sedikit hormon stres serta lebih banyak serotonin (“hormon bahagia”) dan oksitosin (“hormon cinta”).
Dua tahun setelah Dawkins menerbitkan buku laris mengenai “gen egois”, yang menyimpulkan bahwa manusia “terlahir egois”, Dmitri justru menyatakan bahwa manusia adalah spesies jinak. Selama puluhan ribu tahun, manusia yang paling ramah mendapat keturunan paling banyak. Evolusi spesies kita adalah “kelestarian yang paling ramah”.
Ketika pada 2014, satu tim saintis Amerika mengamati tengkorak manusia dari berbagai zaman selama 20 ribu tahun terakhir, mereka bisa melihat satu pola: mendapati wajah dan tubuh kita menjadi lebih lembut, lebih muda, dan lebih feminim. Otak kita mengecil 10 persen sementara gigi dan rahang menjadi pedomorfik (mirip anak kecil).
Jika dibandingkan dengan Neandertal, perbedaan itu sangat mencolok. Tengkorak kita lebih pendek dan bulat, dengan alis tak menonjol. Perbedaan kita dengan Neandertal mirip perbedaan anjing dan serigala. Manusia berevolusi tampak seperti anak.
Lalu, mengapa Homo Sapiens bisa lebih mengubah dunia? Neandertal punya otak lebih besar secara individu, tapi secara kolektif mereka tak secerdas Homo Sapiens. Homo Sapiens hidup dalam kelompok lebih besar, berpindah pindah dari satu kelompok ke kelompok lain dengan lebih sering. Beberapa saintis berteori bahwa berkembangan bahasa manusia merupakan produk sifat sosial Homo Sapiens itu.
Hal ini dipertegas oleh penelitian dua ahli kognisi, Steven Sloman dan Philip Fernbach, dalam buku The Knowledge Illusions: Why We Never Think Alone. Gagasan bahwa manusia itu makhluk berpikir individual merupakan mitos belaka. Manusia berpikir dalam kelompok. Fenomena antropologis yang menunjukkan hal itu membawa Sloman dan Fernbach pada kesimpulan bahwa manusia lebih unggul daripada makhluk lain dan mengubah diri menjadi penguasa planet bukanlah rasionalitas individual, melainkan kemampuan kita berpikir dalam kelompok.
Jadi, apa yang terjadi dengan Neandertal? Apakah Homo Sapiens menghabisi mereka?
Rutger Bregman berpendapat, “Gagasan itu boleh jadi cocok untuk buku dan dokumenter yang seru, tapi tak ada bukti arkeologis yang menyokongnya. Teori yang lebih masuk akal adalah bahwa kita, Homo Sapiens, lebih mampu menghadapi kondisi iklim keras pada zaman es terakhir (115.000-15.000 tahun lalu) karena kita mampu mengembangkan kemampuan bekerja sama.”
Ketika Darwinisme sosial berpendapat manusia yang akan bertahan adalah yang menang dalam kompetisi, sementara Dawkin menggagas tentang “gen egois”, maka semua itu seolah ikut membentuk pandangan bahwa manusia sebenarnya punya sifat dasar kompetisi, ketidakpedulian dan mau menang sendiri. Darwinisme sosial mengarah ke suatu bentuk liberalisme radikal yang menetapkan individualisme dan persaingan antarkelompok. Bahkan, Darwinisme sosial dimanfaatkan oleh penguasa untuk mengembangkan penjajahan, Nazisme, dan rasialisme.
Pada gilirannya terjadilah pelumrahan perseteruan antarmanusia dalam bentuk perang dan kehidupan dipenuhi oleh orang yang berusaha untuk menang dengan segala cara. Sering kita berujar ketika mengomentari peristiwa peperangan: ah biasa, namanya juga manusia. Terbentuk keyakinan bahwa manusia pada dasarnya jahat.
Pola pikir tersebut pada gilirannya membentuk perilaku kehidupa sehari-hari manusia. Maka, perubahan pola pikir (mindset) ini sangat penting dalam gagasan pemodelan pola pikir pembentuk budaya yang menjadi ikutan teori evolusi.
Inilah yang mendorong World Economic Forum (WEF) 2021 mencetuskan gagasan “Great Reset”, upaya menata kembali kehidupan dunia, yang landasan pertamanya adalah perlunya kita me-reset pola pikir (mindset) dalam memandang dunia. Landasan ini, terinspirasi dari gagasan Bregman yang berdasarkan atas studi sejarah panjang manusia, adalah bahwa manusia itu punya sifat dasar baik dan umat manusia mempunyai sejarah penuh harapan.
Jadi, keberlangsungan kehidupan manusia bukan dikarenakan kompetesisi saling mengalahkan, bukan karena yang kuat mengalahkan yang lemah, bukan karena egoisme yang membentuk keketertutupan. Bertahannya kehidupan manusia dikarenakan kemampuan manusia saling bekerja sama, penuh keramahan, dan dibangun di atas cinta.[]