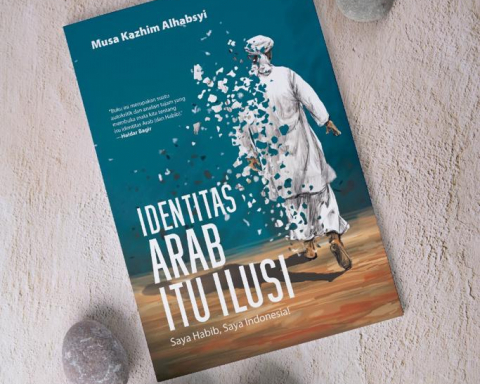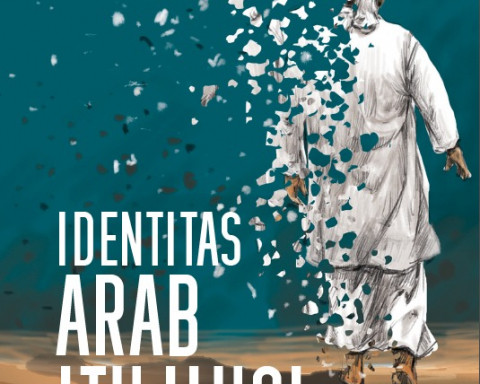Dalam artikel ini, Habib Ali Al-Jufri menyatakan kefanatikan bisa terjadi pada siapa pun terlepas dari agama atau ideologinya. Jadi, sebelum beragama dan berideologi, seseorang harus terlebih dahulu membersihkan jiwanya.
Oleh Habib Ali Al-Jufri
Segala puji bagi Allah Swt.
MINGGU lalu, saya mendapat kesempatan menyenangkan berdiskusi dengan sejumlah anak muda. Beberapa memiliki pertanyaan tentang agama mereka, beberapa memiliki keraguan, dan beberapa menganggap diri ateis.
Seorang pemuda menanyakan pendapat saya tentang Marxisme. Saya berkata, ada aspek-aspek dari Marxismeyang bisa kita terima dan ada aspek-aspek yang kita tolak. Jika tidak ada sedikit pun kebenaran di dalamnya, Marxisme tidak akan pernah menjadi ideologi. Kepalsuan murni tidak akan mampu bertahan begitu lama, dan Marxisme tidak akan dapat bertahan sebagai ideologi yang dipercayai oleh mereka yang mencari kebenaran. Allah berfirman: Sungguh, yang batil itu pasti lenyap (Q.S. Al-Isra [17]: 81). Di luar berbagai kesalahan di dalamnya, Marxisme sangat peduli dengan keadilan sosial, meskipun kita tidak sepakat dengan cara sang filsuf mengenai mencapainya. Tidak diragukan lagi, ini merupakan ideologi yang dapat kita diskusikan.
Masalah terbesar dengan Marxisme dimulai ketika ia beranjak dari teori ke praktik di bawah kekuasaan Lenin dan Stalin. Kaum buruh yang merasa menang secara emosi hanya berujung sebagai korban pertama dari pembantaian yang dilakukan oleh negara-negara pendukung Lenin dan Stalin. Kita mengalami kengerian akibat implementasi ideologi ini di Yaman Selatan segera setelah negara tersebut meraih kemerdekaannya dari pendudukan Inggris dan bergabung dengan Blok Timur.
Saya berkata kepada mereka, “Marx adalah seorang pemikir, Lenin adalah seorang penipu, dan Stalin adalah tukangjagal.”
Pemuda itu berusaha menjelaskan kenapa Stalin membunuh, mengasingkan, dan membuat jutaan rakyatnya sendiri kelaparan, dan menjustifikasi tindakannya dengan dalih melindungi negara dan memungkinkan “proyek” tersebut untuk terus berlanjut. Negara pemuda itu juga menjustifikasi tindakannya dengan dalih melindungi negara dan memberikan stabilitas, meskipun dia tetap mengecamnya. Meskipun kesalahan negaranya tidak dapat dibandingkan dengan kejahatan Stalin, pemuda itu siap membela Stalin, tetapi tidak siap membela negaranya. Inilah contoh kesetiaan dan kefanatikan buta.
Saya menyinggung diskusi tersebut dalam tulisan ini untuk menekankan pentingnya prinsip-prinsip dialog yang membangun. Ketika anak-anak muda ini ingin mendiskusikan Islam dan iman, mereka meminta diskusi tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak dibatasi. Saya menerima permintaan mereka, dengan syarat diskusi dilakukan dengan mengutamakan fakta dan kritik yang santun. Salah satu dari mereka bertanya, apakah parameter kritik yang santun itu. “Apakah Anda mengizinkan saya menggambarkan sosok yang Anda anggap sakral itu sebagai penipu dan tukang jagal, persis seperti cara Anda menggambarkan Lenin dan Stalin?” Saya berhenti sejenak dan merenung.
Pertanyaannya membuat saya tersadar akan standar ganda yang kita terapkan saat kita bicara tentang aturan dialog dan tentang kefanatikan tersembunyi yang mendikte cara kita berperilaku. Saya memohon maaf kepada mereka atas syarat yang saya ajukan dan mengakui telah menerapkan standar ganda tanpa menyadarinya.
Diskusi itu berlangsung hingga nyaris fajar. Kami mendiskusikan bukti-bukti rasional mengenai eksistensi Tuhan dan pengaruh dari pemikiran, hati, jiwa, ruh, dan jasmani terhadap keyakinan seseorang dan reaksinya terhadap hal-hal di sekelilingnya. Saya mengakhiri diskusi dengan benar-benar merasa bahwa saya telah mempelajari sesuatu yang baru tentang jiwa saya. Saya meninggalkan diskusi tersebut dalam keadaan yang lebih baik daripada saat memulainya. Saya berharap, hal yang sama juga dirasakan oleh anak-anak muda tersebut.
Saya menunaikan shalat Shubuh di Masjid Imam al-Husain di Kairo dan kemudian, mengadakan kajian mengenai kitab Ihya Ulum al-Din karya Imam al-Ghazali. Kemudian, saya pergi tidur, tetapi pikiran saya terus diganggu oleh beberapa pertanyaan dan masalah yang tetap tidak terpecahkan saat saya menuliskan artikel ini.
Kenapa kamu masih sedemikian bodohnya? Apakah etikamu terhadap orang lain hanyalah kulit luar semata? Kapankah kamu akan berhenti dibohongi oleh nafsu yang terus mendorongmu ke kejahatan? Apakah ini sebentuk kefanatikan yang menjijikkan dan buta? Apakah gunanya mengajari orang lain bagaimana memperbaiki karakter mereka dan memurnikan hati mereka, padahal karaktermu masih tidak menyenangkan dan hatimu penuh kebusukan? Bagaimana kamu bisa tertipu?
Beberapa hari kemudian, Muhammad Qutb—seorang pemikir dan penulis Islam terkemuka dan saudara Sayyid Qutb—wafat. Saya terkejut membaca berita yang beredar di media sosial yang menuduh saya tidak mau mendoakan jiwa beliau. Pesan-pesan tersebut begitu tegas. Tuduhan tersebut menunjukkan sikap mereka terhadap saya. Saya menjawab bahwa saat itu saya tidak mengetahui kewafatan beliau sehingga bagaimana mungkin saya dituduh telah menolak mendoakan beliau? Saya bertanya-tanya di dalam hati, mengapa mereka yang mengklaim sebagai pendukung tujuan Islami dapat menikmati kepuasan dari menyebarkan kebohongan semacam itu.
Seorang tokoh yang saya hormati mengajukan keberatan: bagaimana bisa Anda memuji kebajikan Mandela, tetapi mengabaikan sosok yang hebat ini? (Dia merujuk pada sebuah artikel yang saya tulis tentang meninggalnya Mandela). Saya menjawab bahwa upaya Mandela untuk menciptakan perubahan dilakukan secara damai. Itu sangat jauh berbeda dengan sebuah ideologi yang secara tegas menyatakan sesama Muslim (yang berbeda pendapat dengan mereka) sebagai orang tak beriman (takfir) dan menghalalkan darah mereka.
Saya tidak terlalu memperhatikan reaksi yang muncul dari jawaban saya. Anda selalu mendapatkan beragam jenis reaksi ketika Anda mengekspresikan pendapat tentang isu-isu seperti itu. Sebagai sebuah umat, kita perlu waktu untuk belajar menerima perbedaan pendapat. Kita perlu menyadari perbedaan antara kritik atas ideologi dan serangan personal, dan perbedaan antara membela prinsip-prinsip mulia atau mempromosikan ide -ide yang keji.
Namun, ada komentar dari salah satu kerabat almarhum, yang menegur saya dari segi moral karena telah mengomentari keyakinan almarhum ketika sanak saudaranya masih berduka atas kepergiannya. Setelah merenung, saya akui dia benar. Saya menyesali tindakan saya, meminta maaf setulusnya, dan memberikan penghiburan kepada kerabat tersebut.
Ada masalah serius tentang standar ganda dan kefanatikan tak berdasar di kalangan umat kita. Banyak dari reaksi dan pendirian kita yang jika dilacak, berasal dari kedua sikap tersebut. Akar masalahnya terletak pada jiwa kita dan diperburuk oleh ideologi yang kita ikuti, yang kemudian kita manfaatkan demi keuntungan kita di ranah agama, politik, ekonomi, sosial, dan media.
Misalnya kasus kaum liberal yang bicara panjang-lebar tentang kebebasan berpendapat. Mereka menyerang lawan-lawan mereka dan menuduh mereka tidak mengizinkan perbedaan pendapat. Mereka mendesak dibuatnya Undang-Undang untuk mencegah wacana agama terlibat dalam urusan politik. Mereka menjustifikasi pendapat mereka agar mencegah orang-orang beragama memiliki suara dalam politik atas dasar bahwa orang biasa dapat salah menilai dan mengira pendapat orang-orang beragama dengan sendirinya mencerminkan agama dan siapa pun yang menentangnya berarti juga menentang agama bersangkutan. Namun, mereka tidak menyadari fakta bahwa pendekatan mereka membuat orang mengira keterlibatan kaum liberal merepresentasikan kebebasan dan kemajuan, sedangkan keterlibatan lawan-lawan mereka dianggap sebagai tindakan yang opresif dan penanda kemunduran.
Di lain pihak, kaum Islamis bisa mengkritik atau bahkan mengutuk para sarjana Muslim (kalangan ulama) karena sikap bias mereka terhadap mazhab-mazhab hukum Islam, pemujaan terhadap para ulama pendahulu mereka, atau penolakan untuk mengkritik pendapat para ulama klasik. Namun, begitu seorang pemimpin kaum Islamis yang mana pun dikritik, mereka langsung menyerang si pengkritik dengan aneka tuduhan, mulai “orang yang bodoh”, “menjual agama kepada penguasa” hingga “mengkhianati agama”!
Seorang revolusioner sosialis mungkin juga mengutuk rezim penguasa karena tidak menghormati keinginan rakyat dan kebebasan memilih. Namun, ketika orang-orang tidak memilih partai mereka, dia menuduh rakyat sebagai orang-orang yang bodoh dan terbelakang.
Masalah standar ganda dan kefanatikan dalam sikap atau tindakan merupakan isu yang mendunia. Kita menyaksikan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Ini kita sadari telah mengakar dalam sejarah umat manusia, bahkan sudah menetap jauh di dalam jiwa kita sendiri.
Sebagian besar dari kita menuntut keadilan serta mengutuk kefanatikan dan standar ganda. Kita mengutuk orang lain karena memiliki sifat-sifat ini, tetapi kita sering jatuh ke dalam perangkap yang sama, meskipun mungkin kita mengekspresikannya secara berbeda. Perhatikan bagaimana suara kubu pendukung dan penentang rezim di suatu negara. Begitu situasi berbalik, kita melihat orang-orang di kedua kubu akan melakukan hal yang persis sama dengan apa yang mereka kritik dari kubu lawannya.
Akar persoalannya muncul dari kelemahan-kelemahan yang tersembunyi di dalam jiwa rendah kita, atau hawa nafsu, sehingga kita merasa kita tidak perlu mengatasinya dan menyelamatkan diri kita sendiri dari bahaya yang disebabkannya.
Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudaraku seiman: apa pun ideologi kalian, tujuan, atau pemahaman yang kalian ikuti, ingatlah bahwa kelemahan kita berasal dari dalam jiwa kita sendiri, melebihi kelemahan yang ada dalam ideologi, tujuan, dan pemahaman kita. Kita harus menghadapi kelemahan internal ini jika kita ingin memperbaiki diri kita sendiri, negara kita, umat Islam, dan umat manusia sebagai keseluruhan.
Kita bisa mulai dengan memiliki keberanian untuk terlibat dalam proses kritik diri yang membangun, yang dapat membuat jiwa kita mengobati kelemahannya. Al-Quran mengingatkan soal ini: Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Pengetahuan membantu kita menyadari kelemahan dari jiwa dan kita harus berhati-hati untuk membuat dalih untuknya: bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.[]
[Dinukil dari: Habib Ali Al-Jufri. 2020. Kemanusiaan sebelum Keberagamaan. Jakarta: Noura Books. Hlm. 22-27]

Habib Ali Al-Jufri
HABIB Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri atau yang dikenal dengan Habib Ali Al-Jufri lahir di Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat 16 April 1971 M atau 20 Safar 1391 H. Habib Ali belajar ilmu-ilmu keislaman (Al-Quran, hadis, fiqih, tasawuf) sejak usia belia. Beliau berguru kepada banyak syaikh besar seperti Habib Muhammad bin Alawi al-Maliki, Habib Abu Bakr al-Masyhur al-Adni, Habib Umar bin Hafizh, dan lain-lain. Saat ini, beliau dikenal sebagai ahli tasawuf dan fiqih mazhab Syafi’i.
Sebagai dai, beliau telah berdakwah ke berbagai negara di Amerika, Afrika, Eropa, Asia, termasuk Indonesia. Beliau juga memberi kuliah dan berceramah di beberapa kampus dan lembaga di Eropa dan Amerika, antara lain Santa Clara University, San Diego University, University of Miami, University of Southern California, S.O.A.S London, Wembley Conference Centre London, House of Lords London.
Habib Ali juga aktif terlibat dalam konferensi-konferensi keislaman tingkat dunia, antara lain Conference on A Common Word di London dan Cambridge (12-15 Oktober 2008), Conference on A Common Word di Yale University bekerja sama dengan Princeton University dan Georgetown University (24-31 Juli 2008), konferensi tahunan ke-2 tentang Dialogue and Understanding di Paris (2006), forum tahunan ke-7 tentang Al-Quran sebagai Ajaran dan Jalan Hidup di Frankfurt, Jerman (2005), simposium tentang Islamic Unity di Damaskus (2004), dan konferensi tentang Unity for the Sake of Peace di Sri Lanka (2003).
Beliau adalah Direktur Utama Yayasan Thaba (sejak 2005). Sejak 1997 beliau menjadi dosen tamu di Dar al-Mustafa for Islamic Studies di Tarim, Yaman Selatan. Beliau juga anggota Dewan Direksi Dar al-Mustafa for Islamic Studies di Tarim, sejak 2003. Selain itu, beliau anggota Dewan Pengawas Akademi Eropa untuk Budaya Islam dan Sains di Brussels, Belgia, sejak 2003. Beliau adalah anggota aktif Yayasan Aal al-Bayt untuk Pemikiran Islam di Amman, Yordania, sejak 2007.[]