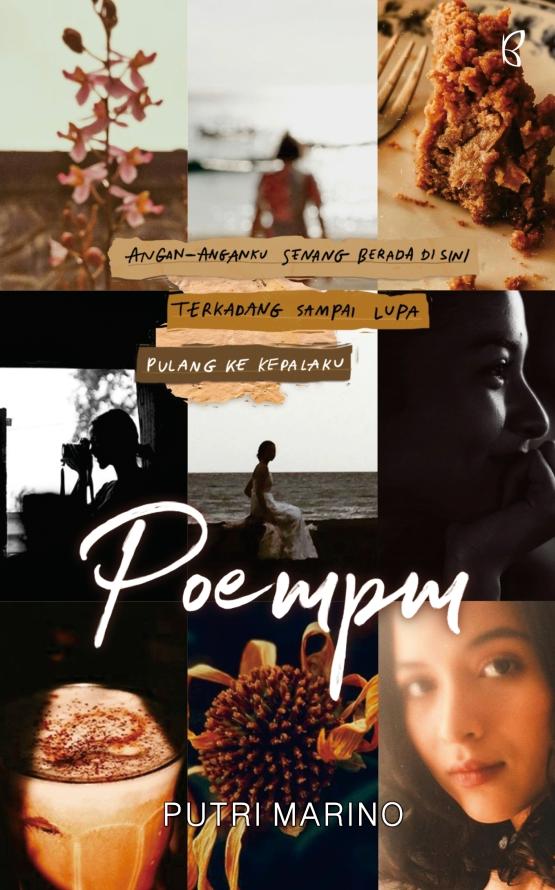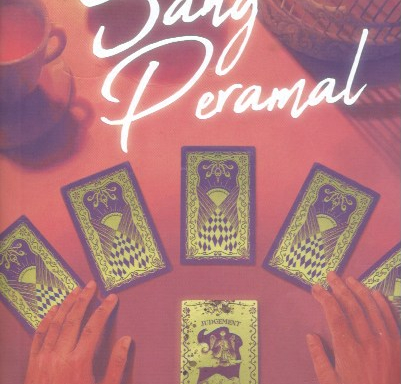PoemPm, karya Putri Marino, adalah tentang kepedihan pecinta; hubungan yang nyaris pupus; kasih tak sampai. Ini bukan wacana baru. Mungkin ada miliaran manusia di planet ini merasakan hal sama. Lantas, apakah karya itu bisa disebut puisi?
PUTRI Marino sungguh beruntung. Di awal tahun, buku pertamanya terbit. Dan, yang mengejutkan, buku itu memicu perbincangan publik, setidaknya di media sosial.
Perbicangan itu – atau bolehlah dibilang perdebatan – bukan soal sepele. Soal sastra. Soal puisi atau bukan puisi. Dulu, perbincangan semacam ini dipicu orang ‘sekelas’ Arief Budiman, Ariel Heryanto, Mochtar Lubis, atau Taufik Ismail. Tapi sekarang, berkat media sosial, cukuplah ‘seorang’ Putri Marino.
Ada yang bilang PoemPm – buku Putri Marino – bukan puisi. Itu cuma kumpulan curhat pribadi. Ada juga yang mengatakan ‘puisi-puisi’ Putri seperti iklan yang habis baca bisa dibuang. Atau cibiran yang bernuansa serangan pribadi, seperti “jika bukan Putri Marino seorang aktris dan selebgram, tak mungkin puisi-puisi itu diterbitkan”.
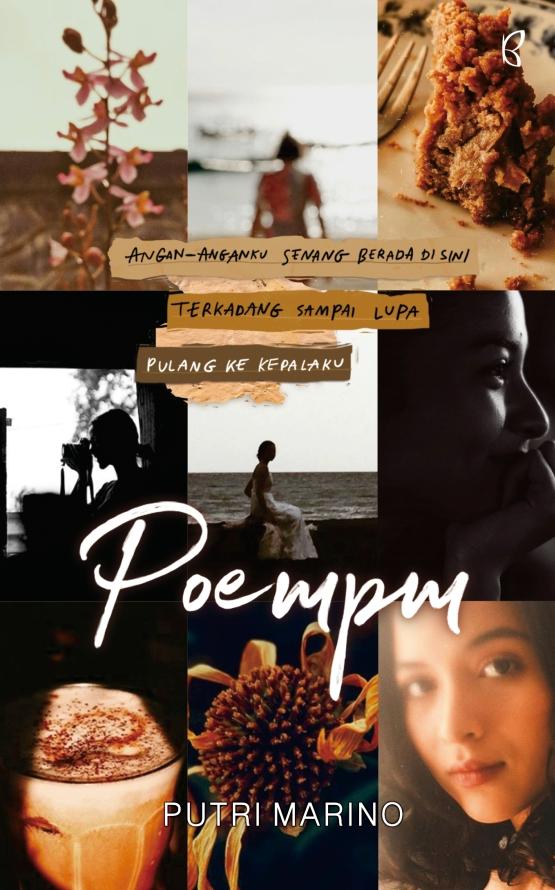
- Judul Buku: PoemPm
- Pengarang: Putri Marino
- Penerbit: Bentang Belia (PT Bentang Pustaka)
- Terbit: Januari, 2020
- Tebal: 104 halaman
Tapi, tak sedikit yang membelanya. Kata mereka, puisi toh ekspresi pribadi seseorang. Tak ada yang salah. Yang salah ya pikiran orang yang membacanya. Di antara pembelaan, juga ada yang keluar dari persoalan: “Putri Marino sudah bisa menulis buku, lah kamu yang mengkritik sudah buat apa?”
Perbicangan seperti itu sudah jamak dalam dunia kreatif, dan akan selalu terjadi. Sebab, dunia kreatif tak mudah didefinisikan. Ia proyeksi jiwa manusia, dan jiwa itu eksesif; tak bertepi; dan – menurut filsuf dan sufi – tak fana.
Karena proyeksi, maka kreasi manusia itu mewujud: karya. Dan ‘karya’ menjadi karya jika ia dinikmati orang banyak, bukan disimpan di laci meja, di folder rahasia, atau di cloud privat. Alhasil, karya punya risiko: dipuji atau dimaki.
Jadi, kritik pada dasarnya adalah respons penikmat. Seperti karya, ia juga bisa beragam, sesuai selera tiap-tiap penikmat. Dan seperti juga pencipta, penikmat harus mempertanggungjawabkan pilihannya jika disampaikan kepada orang lain (dituliskan) – terkecuali kesukaan atau ketidaksukaan anda simpan dalam hati saja.
Tentu saja tak semua respons bisa dianggap kritik. Semestinya sebuah kritik mengandung penalaran di dalamnya. Entah itu empiris, logis, atau intuitif. Pendeknya, ia tak asal bunyi. Di sinilah, lahir kajian sejarah dan teori, tak terkecuali dalam dunia kreatif beraksara, seperti sastra.
Bagi saya sendiri, ukuran sebuah karya adalah apakah ia bisa dinikmati atau tidak. Tapi di luar kenikmatan sensasi, emosi, dan rasio, sebuah karya akan memiliki nilai lebih jika mampu menggugat cara pandang mapan atau menawarkan cara pandang baru terhadap realitas. Di level inilah – sekali lagi bagi saya – sebuah karya beraksara bisa disebut “sastra”.
Sebuah puisi, misalnya, bisa tampil ‘sangat bersahaja’ dalam bentuk, diksi, dan majas. Tapi, dia menampilkan ketidaklaziman dalam menerima peristiwa-peristiwa. Dia berjarak dari wacana dominan. Puisi seperti ini bisa jadi akan bertahan dalam ingatan kita.
Saya, misalnya, selalu mengingat puisi WS Rendra “Sajak Sebatang Lisong”. Puisi ini membongkar persepsi saya bahwa sastra adalah karya linuhung yang tak terjangkau dunia rendah manusia. Atau, seperti kata Abdul Hadi WM, seorang penyair itu harus “merenggut keabadian yang muncul di permukaan kesementaraan”. Ia seakan melangit; tak berjejak di negeri manusia.
Tapi Rendra menyatakan:
...
Aku bertanya,
tetapi pertanyaanku
membentur jidat penyair-penyair salon,
yang bersajak tentang anggur dan rembulan,
sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya
dan delapan juta kanak-kanak tanpa pendidikan
termangu-mangu di kaki dewi kesenian.
…
Inilah sajakku
Pamplet masa darurat.
Apakah artinya kesenian,
bila terpisah dari derita lingkungan.
Apakah artinya berpikir,
bila terpisah dari masalah kehidupan.
(“Sajak Sebatang Lisong” dalam Potret Pembangunan dalam Puisi [Pustaka Jaya, 1996.])
Mungkin karena kesadaran baru itu, saya tak bisa menikmati dan memahami puisi-puisi Sutardji Calzoum Bachri — meski tentu saja karyanya diakui dan dipuji arus utama kesusastraan. Ia punya kredo estetis membebaskan kata dari beban makna; mengembalikan puisi ke fungsi asal: mantra. Kebetulan saya manusia pemuja makna, dan mantra, seperti kata Goenawan Mohamad, tak berkaitan dengan makna tapi dengan tuah. Atau mungkin benar, seperti kata Sutardji, orang seperti saya perlu dididik lagi untuk bisa mengapresiasi karya avant-garde-nya.
Kembali ke PoemPm. Saya merasa bisa menikmati sebagian “catatan” Putri Marino dalam buku ini. Beberapa “catatan” itu bahkan mengandung elemen-elemen puitis, seperti majas personifikasi. Putri, misalnya, menggambarkan “diri” yang terpisah dari “aku”. Atau di tempat lain, dia membayangkan “angan” yang bisa “menampar”.
Semoga kau masih mencintaiku ….
Inilah doaku setiap malam ….
sampai akhirnya anganku datang
dan menamparku dengan keras
sambil berkata …
Sejak kapan dia mencintaimu ….
Suka atau tidak suka, gaya bahasa seperti itu salah satu elemen puitis. Dan dalam batas tertentu, saya bisa menikmatinya.
Tapi, apakah “catatan” Putri bisa dikatakan puisi. Nanti dulu!
Puisi memang kadang dibangun oleh permainan bunyi – asonansi-disonansi – permainan diksi, atau gaya bahasa untuk memicu imaji atau sugesti akan makna. Tapi, seperti yang saya yakini, “puisi” menjadi puisi jika ia mampu menawarkan cara pandang baru akan dunia – atau semesta, kata yang banyak dibunyikan sang narator dalam PoemPm.
Semesta “sang pencerita” dalam PoemPm adalah “aku” dan “kamu”. “Aku” berbicara dengan “diri” tentang “kamu” yang diam seribu bahasa; bisu.
Ini catatan seorang pecinta yang lari dari masalah ke masalah, yang menciptakan alur dan plotnya sendiri. “Aku” yang berbicara tentang “kamu” yang dulunya “hangat” kini menjadi “dingin”; kamu yang awalnya “menerima” kini “menolak”.
PoemPm adalah tentang kepedihan pecinta; hubungan yang nyaris pupus; kasih tak sampai. Ini bukan wacana baru. Mungkin ada miliaran manusia di planet ini yang merasakan hal sama – dan mungkin juga karena itu buku ini bisa laris.
Saya berharap “kamu” bisa bicara. Bukankah sangat mungkin “kamu” juga merasakan kepedihan tapi dengan persepsi berbeda? Mengapa hanya “aku” yang merasa menjadi korban? Ataukah, jangan-jangan semesta sang narator hanyalah “aku”?
Baiklah. Itu hanya satu tawaran bagaimana sebuah karya bisa dilihat berbeda dari yang lain. Banyak hal lain yang bisa dilakukan. Ataukah, saya berharap terlalu banyak?
Lepas dari soal itu, di beberapa bagian, sang narator juga terjebak dalam “bahasa orang ramai” karena sepertinya hanya mampu “menemui” bahasa tapi tak bisa “menemukan” bahasa (meminjam Franz Kafka). Di sinilah, “catatan” sang narator kadang seperti khotbah para motivator pengembangan diri – dan tak ada yang salah juga tentang ini.
Mengakhiri ulasan subjektif ini, saya ingin mengingatkan warga net yang terlibat dalam kehebohan “puisi” Putri Marino. Dalam bukunya, Putri tak pernah menyatakan dia menulis puisi. Begitupun penerbitnya. PoemPm hanya disebut “catatan” – tentu saja dengan tambahan “yang dirangkai dengan kata-kata indah”.
Jadi, tak perlu risau apakah PoemPm itu puisi atau bukan. Sebab, ia memang bukan puisi, tetapi “poem”.[]