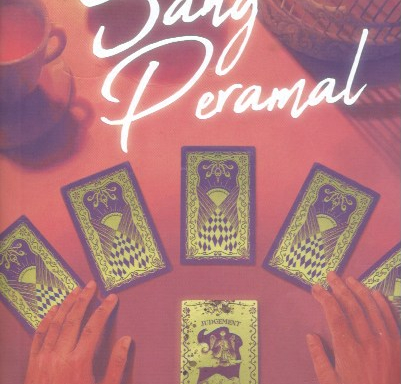Seperti Sartre dan Camus, Iwan Simatupang mendedah pemikiran filosofisnya melalui novel. Tapi, gaya penceritaan tak masuk akal membuat filsafatnya seperti mengendap-endap.
ZIARAH adalah novel karya Iwan Simatupang (1928-1970). Diterbitkan pertama kali oleh Djambatan pada 1969, naskah karya ini disebut sudah rampung sembilan tahun sebelumnya.
Alur yang aneh dan cerita yang tak masuk akal kabarnya membuat penerbit meminta Iwan mengubah naskah tersebut. Tapi, Iwan ngotot menolak. Dia bilang, jika cerita diubah, ia berarti telah menulis novel lain.1
Sebagian besar karya Iwan bernasib serupa: selesai jauh sebelum waktu penerbitannya. Merahnya Merah terbit pada 1968 meskipun naskahnya selesai ditulis pada 5 Oktober 1961. Kering selesai pada 5 Desember 1961 tapi baru terbit pada 1972. Kooong selesai pada 1968 dan terbit pada 1975.2
Menurut Ensiklopedia Sastra Indonesia Kemendikbud, Ziarah memenangi hadiah sastra SEA Write Award pada 1977, atau setelah tujuh tahun sang pengarang dijemput maut. Anehnya, penghargaan di Bangkok, Thailand, ini baru dimulai pada 1979.
Banyak kritikus menilai gaya penulisan novel ini tak lazim: melabrak format yang dianggap semestinya ada dalam sebuah karya sastra, setidaknya dalam cara pandang strukturalisme. Novel ini pun kerap ditahbiskan sebagai perintis gaya baru penulisan novel di Indonesia—merujuk kepada istilah nouveau roman di Perancis pada 1950-an.
Karakter dalam Ziarah tak bernama. Mereka hanya disebut dalam kata yang menunjukkan hubungan sosial, seperti pekerjaan, keluarga, dan pernikahan.

- Judul Buku: Ziarah
- Pengarang: Iwan Simatupang
- Penerbit: Noura Books (edisi digital)
- Terbit: 1969 (Edisi pertama oleh Djambatan)
- Tebal: 223 halaman
Tokoh utama disebut “Pelukis” di satu bagian dan “Bekas Pelukis” atau “Pengapur” di bagian lain. Ini karena ia berganti-ganti pekerjaan sepanjang cerita. Tokoh lainnya antara lain disebut “Opseter”, “Walikota”, “Istri Pelukis”, dan “Ibu Hipotesis”.
Tokoh tanpa nama biasanya kita temukan dalam cerpen. Tapi, dalam novel atau roman yang melibatkan latar waktu berbeda, kita amat jarang mendapati kasus seperti itu.
Bukan cuma pembaca yang tak mengetahui nama tokoh dalam novel ini. Tokoh-tokoh novel ini sekalipun tak saling memanggil dengan nama. Bahkan, pelukis dan istrinya tidak mengingat nama satu sama lain.
Nama! Adakah dia tahu nama suaminya? Adakah dia tahu, siapa suaminya? Dia bahkan tak tahu, apakah suaminya ada mempunyai nama atau tidak. Di kantor catatan sipil dulu, sewaktu perkawinan mereka, suaminya menuliskan hanya: Ganda En (NN) saja, sambil menyikut dia diam-diam dengan geli … (Halaman 154).
Satu-satunya nama yang disebut pengarang berupa inisial: Ganda En (NN), alias No Name (tanpa nama). Iwan jelas menyatakan bahwa nama tak penting ada dalam novelnya.
Akibatnya, Anda bakal kesulitan mengidentifikasi siapa yang dimaksud pengarang dengan “Walikota”. Tokoh dengan sebutan ini muncul dalam empat episode waktu berbeda.
Ada Walikota yang mati menderita di tengah jalan. Ada Walikota yang menggantung diri di ruang kerjanya. Sosok lain Walikota menerima mahasiswa filsafat sebagai opseter pekuburan. Satu lagi, Walikota yang mengurus pemakaman istri pelukis.
Anda setidaknya bisa menyimpulkan ada dua tokoh Walikota. Walikota yang mati di jalan dan bunuh diri di ruang kerja jelas bukan satu tokoh yang sama. Seseorang tak mungkin mati dua kali, bukan?
Tapi itu cara pikir rasional sementara Ziarah tak bisa didekati dengan cara seperti itu. Anda harus siap mencampakkan logika saat membacanya.
Logika mana bisa menerima orang yang menjatuhkan diri dari lantai empat sebuah hotel tidak terluka sedikit pun atau bahkan mati. Dia malah menimpa seorang gadis untuk kemudian keduanya bercinta di tengah jalan.
Dalam ceritanya sendiri, Iwan seperti sudah mewanti-wanti pembaca akan hal ini. Ini bisa Anda lihat dalam bagian dialog antara pelukis dengan istrinya.
“… eh, apa karanganmu itu, romankah? Novel? Esai?”
“Novel esai.”
“Jenis apa pula ini?”
“Novel masa depan. Novel tanpa pahlawan, tanpa tema, tanpa moral.” (Halaman 145)
Anda tak bisa hanya berfokus pada alur penceritaan novel ini. Bukan hanya karena penceritaan di dalamnya tak masuk akal tapi berganti-ganti sedemikian cepat. Belum tandas satu plot, plot lain menyusul masuk tiba-tiba. Dua plot kadang ditumpuk jadi satu, menciptakan plot sama sekali baru.
Latar tempat juga dibuat tak jelas. Pengarang hanya menyebut kota dengan wilayah pantai. Latar waktu juga demikian. Tak ada batas dalam cerita yang menunjukkan kepada pembaca mana alur maju atau mundur.
Pembaca diminta meraba sendiri. Iwan tak mau repot, tampaknya. Bagi dia, yang terpenting adalah pikiran dan perasaannya sendiri, yang dijejalkannya ke dalam tokoh-tokohnya. Dia tak ambil pusing, apakah pembaca bakal paham atau tidak.
Menjengkelkan, bukan? Tapi, novel ini akan mengaktifkan sel abu-abu di dalam otak. Pikiran Anda akan mencipta makna dalam dialog dengan pikiran pengarang.
Pengarang tak bermurah hati mendiktekan makna itu bagi Anda. Ini serupa permainan pikiran yang biasanya dilakukan para filsuf dalam mendedah konsep filsafat mereka.
Lalu apa yang bisa kita pahami dari novel ini? Anda bisa memaknainya macam-macam.
Saya kali ini berusaha mengajukan pemahaman versi saya. Ini saya lakukan dengan melihat fenomena apa dialami empat tokoh utamanya dan respons apa yang mereka pilih.
Pelukis atau Bekas Pelukis
Si Pelukis hanya mau menjadi pelukis. Tak kurang dan tak lebih. Dia menikmati luapan imajinasi yang dia salurkan ke atas kanvas. Itu sudah cukup.
Dia tak peduli apa kata kritikus seni, padahal karyanya dianggap puncak seni lukis. Bahkan, suatu waktu sejarawan dan ahli seni luar negeri membayar mahal salah satu lukisannya.
Dia pun resah dengan perhatian besar publik kepada dirinya. Keresahan ini kemudian mendorongnya mengambil langkah nekat. Dia terjun dari lantai empat sebuah hotel ke aspal jalanan.
Tapi dia tak mati. Dia malah menjumpai seorang gadis yang kemudian menjadi “Istri Pelukis”.
Wanita ini melejitkan energi kreatifnya hingga orang makin mengaguminya lebih daripada karyanya. Sayang, Istri Pelukis kemudian mati.
Kematian ini membuat Pelukis membuang seluruh lukisannya ke laut. Dia menggantung kuas.
Dia juga tak mengakui kematian istrinya. Kepada setiap orang, dia bilang bahwa mayat itu bukan lagi istrinya. Istrinya adalah sosok yang hidup.
Dia tak peduli dengan urusan penguburan istrinya. Dia memang mengikuti proses pemakaman tapi bertingkah bak orang asing di tengah kerumunan pengantar jenazah.
Setelahnya, dia menolak menziarahi makam itu—dan bahkan tak tahu di mana lokasi tepatnya. Yang dia lakukan setiap hari berharap menemui wanita itu di sebuah tikungan jalan. Sampai kemudian dia menerima tawaran Opseter untuk mengapur tembok pekuburan tempat istrinya ditanam.
Opseter
Kata opseter berasal dari bahasa belanda yang berarti ‘pengawas bangunan’. Opseter dalam Ziarah adalah pengurus pekuburan yang membawahi mandor dan para buruh penggali kubur.
Ada dua tokoh yang disebut “opseter” dalam karya ini: Opseter lama yang mati gantung diri dan Opseter baru. Opseter baru kemudian disebut “Opseter” sepanjang novel.
Dia awalnya mahasiswa filsafat tingkat doktoral. Dia juga anak pengusaha terkaya di kota. Sebagai mahasiswa, dia yang terbaik di kampusnya hingga mahagurunya sendiri mengakui kejeniusannya. Si mahaguru, profesor filsafat, bahkan kemudian mengikuti Opseter bekerja di pekuburan sebagai penjaga malam karena keinginannya untuk selalu belajar dari muridnya itu.
Seorang mahasiswa filsafat sekaligus anak orang kaya memilih bekerja menjadi pengawas pekuburan adalah satu dari banyak keanehan (invraisemblable) yang dihadirkan Iwan dalam novel ini.
Opseter menghargai dunia orang mati lebih daripada siapa pun. Dia menganggap kehidupan manusia disempurnakan oleh kematian. Baginya, orang mati adalah sarjana kehidupan: mereka yang lulus dari ujian kehidupan.
Bahkan, dia menyebut bumi ini sejatinya adalah negeri para mayat. Orang-orang mati yang “hidup” di dalam tanah jauh lebih banyak daripada mereka yang hidup melata di permukaan bumi.
Saking tingginya menilai kematian, dia hidup menyendiri dari dunia orang hidup. Hidupnya dihabiskan di seputar pekuburan. Bahkan, selama 27 tahun, dia mengucilkan diri di dalam rumah dinasnya di dalam kompleks pekuburan. Dia hanya menerima laporan dan mengirimkan tugas harian kepada anak buahnya melalui kertas yang ditancapkan pada sebuah tiang.
Di kemudian hari, dia merasa kecewa karena tahu orang hidup ternyata membunuh orang mati berkali-kali. Ini dipicu oleh kebijakan kota untuk mengubur mayat-mayat baru di atas kuburan lama karena makin sempitnya lahan. Si opseter merasa bertanggung jawab atas kebijakan ini.
Rasa tanggung jawab itulah yang mendorongnya meminta Bekas Pelukis untuk mengapur tembok perkuburan. Dia berharap Bekas Pelukis akhirnya mau menziarahi kuburan istrinya. Sebab, salah satu kuburan yang tergusur karena kebijakan tadi adalah tempat Istri Bekas Pelukis bersemayam.
Tapi, Bekas Pelukis—yang anehnya diam-diam mengetahui maksud Opseter—acuh tak acuh. Dia asyik saja mengapur dan tak pernah menunjukkan gelagat ingin menyambangi atau setidaknya mencari tahu lokasi kuburan istrinya.
Sikap tak peduli Bekas Pelukis makin menambah kemasygulan Opseter. Bagi Opseter, ternyata ada orang yang memandang sebelah mata terhadap kematian, dan menganggap apa yang dia hargai selama ini cuma angin lalu. Begitu kecewanya dengan sikap Bekas Pelukis, Opseter kemudian memilih bunuh diri seperti pendahulunya.
Walikota
Dari keempat “Walikota” dalam novel ini, tiga di antaranya menghadapi situasi mirip, yakni pertentangan antara hasrat pribadi dengan tuntutan kepentingan umum. Tapi, masing-masing memilih respons yang berbeda terhadap situasi tersebut.
Walikota pertama menyimpan hasrat pribadi untuk membalas dendam terhadap orang-orang kecil, yang dia sebut “kerdil, dekil, pandir, bernaluri makan dan pakaian saja” (Halaman 40). Tapi, selama menjabat, dia tak bisa melaksanakan agenda aneh itu karena selalu berhadapan dengan tuntutan bahwa seorang pejabat publik ideal mesti mengutamakan kepentingan umum.
Di sini, Iwan menghadirkan paradoks. Jika hari-hari ini kita menyaksikan banyak pejabat lebih mementingkan agenda pribadi dan kelompok daripada kepentingan umum, Iwan justru menampilkan sosok pejabat yang menindas hasrat gelap pribadinya untuk menindas orang kecil demi memajukan kepentingan umum.
Iwan seakan ingin menyatakan bahwa seorang penguasa, betapa pun adilnya, tetap menyimpan agenda tersembunyi menindas rakyat. Iwan seolah tak percaya ada orang yang bisa berkuasa demi kesejahteraan orang banyak, atau sosok pahlawan pembela proletar dalam cita-cita (kerap disebut utopia) orang-orang komunis. Kalaupun orang itu ada, ia sebenarnya melakukan itu dengan menindas kemerdekaan pribadinya.
Deritanya adalah derita dari kelas tengah yang barusan saja dibebaskan oleh revolusi, tapi kemudian gagal mendirikan aristokrasi dan monarki baru bagi dirinya. Anehnya, semua ini mereka lakukan dengan mempergunakan dalih-dalih proletar. (Halaman 49-50)
Menghadapi pertentangan tersebut, Walikota pertama akhirnya sekarat di jalanan. Saat menjelang ajal, dia menyaksikan orang-orang kecil nan dekil mengurumuninya; orang-orang yang dia anggap musuh sejatinya; orang-orang yang dia benci dan ingin dia tindas.
Sementara itu, Walikota ketiga menghadapi masalah tuntutan agar negara memperlakukan baik pelukis pujaan dunia yang tinggal di gubuk tepi pantai bersama istrinya. Dia berupaya memindahkan keduanya ke tempat yang layak.
Tapi, pelukis menolak dan ngotot tinggal di gubuk. Di tengah tuntutan pemerintah pusat dan penolakan pelukis, Walikota ketiga tak bisa berbuat apa pun. Dia akhirnya menggantung diri di ruang kerja.
Walikota keempat, pengganti Walikota ketiga, sebaliknya bisa mengambil keputusan saat harus mengatasi keresahan publik terkait pemakaman Istri Pelukis. Meskipun aturan tak memungkinkan pemakaman itu karena Istri Pelukis tak memiliki dokumen yang dipersyaratkan, dan juga karena Pelukis menghilang tak tentu rimba, Walikota keempat mengambil risiko menguburkan Istri Pelukis.
Pada akhirnya, menurut dia, seseorang harus memilih dan memutuskan sesuatu. Bahkan, tidak memilih pun sebenarnya adalah sebuah pilihan.
Istri Pelukis
Tokoh ini bahagia setelah bertemu Pelukis yang jatuh dari lantai empat sebuah hotel bak jodoh yang dikirim dari surga. Dia tak peduli Pelukis adalah lelaki bau apak karena pria itu tak pernah mandi dan gosok gigi.
Dia merasa menemukan dirinya pada diri Pelukis, dan begitu sebaliknya. Ketika Pelukis mulai menunjukkan gejala mengikuti pandangan umum dengan pindah ke rumah dinas bekas Walikota ketiga dan membuat kartu nama, Istri Pelukis kecewa dan kemudian tidur di kamar terpisah. Dia bahkan sibuk menulis novel berjudul “Di sorga tidak ada kartu nama”.
Pelukis akhirnya memutuskan kembali ke gubuk di tepi pantai. Dia juga membakar semua kartu nama yang sudah tercetak. Karena tanpa istrinya yang dulu, daya kreasinya mengering.
Tapi, masalah lain muncul. Begitu mereka kembali ke gubuk, orang beramai-ramai mengunjungi mereka bak hewan di kebun binatang. Orang-orang itu hanya ingin memandangi mereka berdua; kebahagiaan sepasang suami-istri.
Tapi, bagi Pelukis dan istrinya, ini kesengsaraan. Mereka menderita karena menjadi objek sorotan mata banyak orang.
Di antara orang-orang itu, ada satu perempuan tua yang menatap lekat-lekat kepada Istri Pelukis dengan tatapan aneh. Sorot mata perempuan itu—yang kemudian kita kenal dengan tokoh “Ibu Hipotesis”—seperti menarik istri pelukis ke masa lalu; kenyataan yang membuat dia menderita.
Kita tahu kemudian bahwa Istri Pelukis adalah anak perempuan tua itu. Ia buah dari pemerkosaan yang dilakukan banyak lelaki di masa perang. Perempuan tua itu—Ibu Hipotesis—meninggalkan anak itu di panti karena mencoba menepis kenyataan pilu itu sampai kemudian menemukan anaknya sebagai istri pelukis kondang.
Kata hipotesis tampaknya digunakan Iwan untuk menggambarkan absurditas. Perang adalah sejarah absurditas manusia, dan karenanya Istri Pelukis adalah anak absurditas sementara perempuan tua itu hanya melahirkannya secara hipotesis.
Absurditas Manusia
Keempat tokoh utama novel ini berhadapan dengan absurditas. Mereka ingin bebas dan merdeka tapi pada saat yang sama terbelenggu oleh pilihan dan masa lalu mereka sendiri.
“Manusia dikutuk untuk bebas”, demikian kata Jean-Paul Sartre dalam Existentialism is a Humanism (1946). Tapi, kebebasan itu meniscayakan tanggung jawab atas pilihan yang seseorang buat di masa lalu. Konsekuensi kebebasan itu ironisnya membelenggu manusia. Kata dikutuk menggambarkan bagaimana kebebasan bukanlah sesuatu yang bernilai karena pada akhirnya manusia dibelenggu oleh konsekuensi kebebasan.
Itulah absurditas, tema yang banyak dibahas Sartre dan juga karib sekaligus rivalnya, Albert Camus. Dalam The Myth of Sisyphus (1942), esai filsafat Camus, kita bisa memahami bahwa absurditas adalah kondisi yang muncul dari dua hal bertentangan tapi konsekuensional: kehidupan meniscayakan kematian dan kebebasan meniscayakan keterbelengguan.
Absurditas adalah kesia-siaan. Percuma seseorang merdeka karena pada saat yang sama terbelenggu. Kesia-siaan, dalam penjelasan Sartre atau Camus, bisa dilihat pada betapa tak pedulinya (indifferent) realitas eksternal manusia dengan apa yang dia pikirkan, rasakan, dan lakukan.
Pelukis hanya ingin hidup melukis, tapi pilihan itu membuat dia terpenjara sorotan banyak orang, dari warga biasa sampai kritikus seni luar negeri. Opseter ingin menghargai kematian tapi terusik oleh sikap Pelukis yang memandang kematian tak bermakna apa-apa. Walikota ingin melampiaskan dendam kepada orang kecil tapi jabatan publik memaksanya mendahulukan kepentingan publik. Istri Pelukis hanya ingin hidup bahagia bersama Pelukis tapi tetap tak bisa bebas dari masa lalu.
Semua absurd. Semua merasakan eksistensi mereka sebagai manusia seperti kesia-siaan tak berujung, mirip Sisifus yang mendorong batu besar ke puncak gunung untuk kemudian batu itu meluncur kembali, dan begitu terus selamanya.
Kesengsaraan tokoh-tokoh Ziarah juga bisa dilihat dari apa yang dilakukan dan dilihat orang terhadap mereka. Dalam konsep Sartre, inilah yang dia sebut “bad faith”. Seseorang selalu berupaya menjadi objek (being-in-itself) bukan subjek (being-for-itself). Seseorang merasa terus terperangkap dalam penjara persepsi di luar dirinya.
Pelukis hanya ingin melukis tapi orang lain terus menganggapnya seniman besar dan jenius. Istri Pelukis hanya ingin hidup bersama pelukis tapi masa lalu terus menghantuinya dalam bentuk sorotan mata “Ibu Hipotesis”.
Sartre menyebut situasi itu dengan “hell is other people”. Orang lain adalah penjara kita. Hal di luar diri kita adalah kesengsaraan kita.
Di sinilah mungkin kenapa Iwan sengaja tak memberi nama pada karakter-karakternya. Nama adalah pemberian orang lain; orang tua. Nama seringkali memanggul beban berat suatu makna; yang muluk-muluk.
Karena itu, bagi iwan, yang penting bukan nama tapi apa yang tokohnya lakukan: melukis, menjadi walikota, atau sebagai opseter pekuburan. Sartre pun menilai berbuat atau melakukan sesuatu (to do) lebih bernilai daripada menjadi sesuatu (to be).
Lalu adakah jalan keluar dari absurditas? Di sini, Sartre dan Camus berpisah jalan meskipun sama-sama meniti jalan pemberontakan.
Bagi Sartre, jalan keluar itu adalah dengan menolak segala “keniscayaan” yang diciptakan oleh kecenderungan menjadi objek (being-in-itself). Dalam lapangan politik, Sartre melihat kapitalisme sebagai mesin raksasa objektivikasi, pencipta berbagai “keniscayaan” hidup yang sebenarnya tak ada: kita harus bekerja delapan jam sehari; kita harus membeli produk tertentu; dan (dalam konteks Ziarah) kita harus punya kartu nama.
Sartre menjelaskan bahwa begitu banyak kemungkinan lain untuk hidup di luar “keniscayaan”. Karena itu, dalam hidupnya, dia terlibat dalam aksi-aksi protes sosial di jalanan Paris pada dekade 1960-an. Dia juga mengagumi pemimpin komunis, seperti Che Guevara dan Fidel Castro.
Sementara itu, Camus menjelaskan dua pilihan yang dilakukan manusia saat mencoba bebas dari absurditas: bunuh diri fisik dan bunuh diri filosofis. Camus uniknya tak memilih salah satunya sebab, menurutnya, keduanya sama-sama bentuk nihilisme.
Menurut camus, bunuh diri filosofis sama nihilistiknya dengan bunuh diri fisik. Camus merujuk bunuh diri filosofis kepada upaya agama dan ideologi mencipta “utopia penyelamatan”.
Agama mewartakan kedatangan sang juru selamat, yang akan membebaskan manusia dari absurditas kehidupan dan memberi makna kepada kesengsaraan mereka selama ini. Sementara, ideologi mencita-citakan “pemberontakan sosial” melawan ketidakadilan—sesuatu yang menurut Camus adalah kesia-siaan.
Camus mengatakan manusia harus menyadari bahwa mereka sia-sia. Kita harus sepakat bahwa kita adalah anak-anak absurditas seperti Istri Pelukis.
Jika kesadaran itu muncul, maka kita bisa menjalani kebahagiaan bersama, seperti Sisifus yang bahagia meskipun melakukan pekerjaan sia-sia seumur hidup. Bagi Camus, menjalani kebahagiaan adalah menikmati kesengsaraan ini semaksimal mungkin: bercinta; makan-minum, atau plesiran. Pokoknya, bersenang-senanglah sebab hidup pada akhirnya toh akan dilupakan.
Dalam Ziarah, Iwan tampaknya lebih Camusian daripada Sartrean. Tokoh utamanya, kecuali Pelukis, mati bunuh diri atau sengsara.
Sementara itu, Pelukis memilih menikmati semaksimal mungkin kehidupan, seperti yang dilakukan Camus. Dia menenggak tuak di warung pinggir jalan, tertawa keras-keras, menangis keras-keras, dan mengerjakan apa pun yang ia suka.
Dalam Ziarah, Iwan tak sedang bercerita tapi menyampaikan risalah filsafat. Seperti Sartre dan Camus, dia memilih novel sebagai medianya.
Jika kita bandingkan Ziarah dengan Nausea, novel pertama Sartre, misalnya, Iwan lebih memilih gaya surrealis ketimbang realis yang digunakan Sartre. Pilihan ini membuat pikiran-pikiran filosofisnya mengendap-endap dalam penceritaan tak masuk akal. Dengan kata lain, filsafat tentang absurditas disampaikan Iwan dengan gaya absurd.
Alhasil, sebagai cerita, novel ini kurang bisa dinikmati. Tapi, sebagai risalah filsafat, Ziarah menarik untuk ditelusuri lebih dalam.[]
1“Ziarah (1969)”, Ensiklopedia Sastra Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam http://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/artikel/Ziarah, diakses pada 28 Juli 2020.
2Irfan Teguh, “Kisah Iwan Simatupang Menjadi Manusia Hotel”, dalam https://tirto.id/kisah-iwan-simatupang-menjadi-manusia-hotel-cGoc, diakses pada 28 Juli 2020.