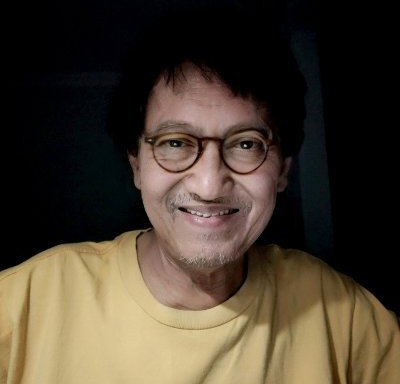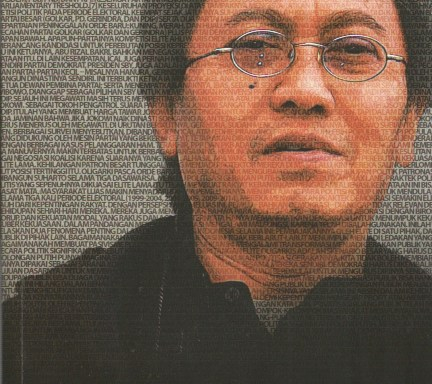Oleh Mohammad Hatta
Demokrasi Kita tulisan Mohammad Hatta yang dimuat dalam Pandji Masjarakat pada 1960. Tapi, majalah itu kemudian dibredel oleh Pemerintah Soekarno. Pada 1966, tulisan ini diterbitkan sebagai buku. Kami akan memuatnya dalam dua bagian.
SEJARAH Indonesia sejak 10 tahun yang akhir ini banyak memperlihatkan pertentangan antara idealisme dan realita. Idealisme, yang menciptakan suatu pemerintahan yang adil yang akan melaksanakan demokrasi yang sebaik-baiknya dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.1
Realita dari pada pemerintahan, yang dalam perkembangannya kelihatan makin jauh dari demokrasi yang sebenarnya.
Tindakan-Tindakan Presiden
Apalagi sedak dua tiga tahun yang akhir ini kelihatan benar tindakan-tindakan pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Presiden, yang menurut Undang-Undang Dasar tahun 1950 adalah Presiden konstitusional yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diganggu-gugat, mengangkat dirinya sendiri menjadi formatur kabinet. Dengan itu ia melakukan suatu tindakan yang bertanggung jawab dengan tiada memikul tanggung jawab. Pemerintah yang dibentuk dengan cara yang ganjil itu diterima begitu saja oleh Parlemen dengan tiada nyatakan keberatan yang prinsipiel. Malahan ada yang membela tindakan Presiden itu dengan dalil “keadaan darurat”.
Kemudian Presiden Soekarno membubarkan Konstituante yang dipilih oleh rakyat, sebelum pekerjaannya membuat Undang-Undang Dasar baru selesai. Dengan suatu dekrit dinyatakannya berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Menurut Undang-Undang Dasar ‘45 itu Presiden Republik Indonesia adalah kepala ekskutif. Parlemen yang ada menurut Undang-Undang Dasar 1950 dan tersusun menurut pemilihan umum pada tahun 1955 diakui sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sementara sampai terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sungguh pun tindakan Presiden itu bertentangan dengan Konstitusi dan merupakan suatu coup d’état, ia dibenarkan oleh partai-partai dan suara yang terbanyak di dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Golongan minoritas menganggap perbuatan Presiden itu sebagai suatu tindak-perkosa, tetapi menyesuaikan dirinya kepada kenyataan yang baru itu. Dengan pendirian sedemikian Dewan Perwakilan Rakyat sudah melepaskan sendiri hak kelahirannya.
Tidak lama sesudah itu Presiden Soekarno melangkah selangkah lagi, setelah timbul perselisihan dengan Dewan Perwakilan Rakyat tentang jumlah anggaran belanja. Dengan suatu penetapan Presiden Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan dan disusunnya suatu Dewan Perwakilan Rakyat baru menurut konsepsinya sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat baru itu anggotanya 261 orang, separuh terdiri dari anggota-anggota partai dan separuh lagi dari apa yang disebut golongan fungsional, yaitu buruh, tani, pemuda, wanita, alim-ulama, cendekiawan, tentara, dan polisi. Semua anggota ditunjuk oleh Presiden. Anggota-anggota partai politik yang 130 orang itu sebagian besar dipilihnya sendiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bersidang sampai sekarang, dengan menyingkirkan sama sekali anggota-anggota yang termasuk golongan oposisi.
Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden Soekarno mendasarkan segala tindakannya itu atas pendapat, bahwa revolusi Indonesia untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur belum selesai. Sebelum tercapai Indonesia yang adil dan makmur, revolusi masih berjalan terus dan segala susunan yang ada itu bersifat sementara. Ia, katanya, tidak menentang demokrasi, malahan menuju demokrasi yang sebenarnya, yaitu demokrasi gotong-royong seperti yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yang asli. Ia mencela demokrasi cara Barat yang berdasarkan free fight, hantam-menghantam, yang sebegitu jauh dipraktikkan di Indonesia. Free fight democracy ini menimbulkan perpecahan nasional, sehingga usaha-usaha pembangunan jadi terlantar.
Demokrasi liberal itu hendak digantinya dengan apa yang disebutnya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin, seperti yang dimaksudkannya itu ialah suatu cara bekerja yang melaksanakan suatu program pembangunan yang direncanakan dengan suatu tindakan yang kuat di bawah suatu pimpinan. Cita-cita itu harus didukung oleh kerja sama yang baik antara empat golongan besar yang berpengaruh di dalam masyarakat, yaitu golongan-golongan nasional, Islam, komunisme, dan tentara. Titik berat dari pada pemerintahan dan perundang-undangan tidak lagi terletak pada Parlemen, melainkan pada dua badan baru yaitu Dewan Nasional, yang sekarang berubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perancang Nasional.
Dalam sistem ini Dewan Perwakilan Rakyat tugasnya hanya memberikan dasar hukum saja kepada keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau usul dari dua badan tersebut tadi. Dengan cara begitu, menurut pendapat Soekarno, segala perundingan dapat berlaku dengan cepat, dengan tiada bertele-tele seperti yang terjadi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat sampai sekarang. Kedua badan tersebut, Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perancang Nasional, berhubung dengan susunannya seperti yang ditentukan sendiri oleh Presiden Soekarno, bisa merupakan suatu “pressure group”, golongan pendesak.
Tetapi dengan perubahan Dewan Perwakilan Rakyat yang terjadi sekarang, di mana semua anggota ditunjuk oleh Presiden, lenyaplah sisa-sisa demokrasi yang penghabisan. Demokrasi terpimpin Soekarno menjadi suatu DIKTATOR yang didukung oleh golongan-golongan yang tertentu.
Krisis Demokrasi
Oleh karena itu tidak heran, kalau banyak orang menyangka, bahwa demokrasi lenyap dari Indonesia. Tetapi pendapat semacam itu tidak benar. Itu suatu pendapat yang diperoleh dari penglihatan sepintas lalu saja atas proses politik yang berlaku di Indonesia sejak beberapa tahun yang akhir ini. Demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Berlainan dari pada beberapa negeri lainnya di Asia, demokrasi di sini berurat-berakar di dalam pergaulan hidup. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya.
Apa yang terjadi sekarang ialah KRISIS dari pada demokrasi. Atau demokrasi di dalam krisis. Demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaannya lupa syarat-syarat hidupnya dan melulu menjadi anarki lambat-laun akan digantikan oleh diktator. Ini adalah hukum besi dari pada sejarah dunia! Tindakan Soekarno yang begitu jauh menyimpang dari dasar-dasar konstitusi adalah akibat dari pada krisis demokrasi itu.
Demokrasi dapat berjalan baik, apabila ada rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Inilah yang kurang pada pemimpin-pemimpin partai seperti yang telah berkali-kali saya peringatkan. Pada permulaan kemerdekaan, sesudah proklamasi 17 Agustus 1945, orang merasai benar-benar tanggung jawabnya. Tetapi setelah kemerdekaan itu diakui oleh seluruh dunia, sebagai hasil dari pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada akhir tahun 1949, orang lupakan syarat-syarat untuk membangun demokrasi di dalam praktik.
Semangat yang ultra-demokratis yang merajalela dalam dada pemimpin-pemimpin partai mengubah sistem pemerintahan dari pemerintah presidensial yang tertanam di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kabinet parlementer. Sistem kabinet parlementer seperti yang berlaku di Eropa Barat, di mana Pemerintah bertanggung jawab kepada Parlemen, orang anggap lebih demokratis dari sistem pemerintah presidensial. Orang lupa, bahwa Indonesia dalam masa peralihan ke pemerintahan nasional yang demokratis perlu akan suatu pemerintah yang kuat. Sejarah Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 menyatakan bahwa pemerintah yang kuat di Indonesia ialah pemerintah presidensial di bawah dwitunggal Soekarno-Hatta. Lahirnya ide dwitunggal di waktu itu bukanlah suatu hal yang dibuat-buat, melainkan suatu kenyataan yang dikehendaki oleh keadaan.
Di masa Republik Indonesia yang pertama itu telah dicoba mengubah sistem pemerintah presidensial menjadi sistem kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, yang bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Alasan yang dikemukakan ialah supaya Presiden dan Wakil Presiden tetap dan tidak terganggu gugat di dalam memimpin negara. Presiden dan Wakil Presiden diperlindungi oleh Kabinet yang bertanggung jawab politik, yang setiap waktu dapat diganti kalau perlu. Tetapi dalam praktik ternyata, bahwa bukan kabinet yang memperlindungi Presiden dan Wakil Presiden, memagari mereka dengan tanggung jawabnya, melainkan sebaliknya. Di mana-mana Presiden dan Wakil Presiden harus bertindak dengan mempergunakan kewibawaannya untuk memperlindungi kabinet dari kecaman dan serangan rakyat yang tidak puas. Sampai ke dalam sidang Komite Nasional Pusat Wakil Presiden terpaksa bersuara untuk mempertahankan politik Pemerintah yang digugat dan dikecam sehebat-hebatnya oleh berbagai golongan di dalamnya. Dan pada saat yang genting seperti dengan peristiwa 3 Juli 1946 orang berpegang kembali kepada Kabinet Presidensial. Demikian juga sesudah penandatanganan Perjanjian Renville pada permulaan tahun 1948, yang menimbulkan perpecahan besar dan pertentangan politik yang hebat dalam masyarakat, orang kembali kepada pemerintah presidensial di bawah Wakil Presiden. Pemerintah itulah yang stabil sampai pada pemulihan kedaulatan pada akhir tahun 1949 oleh Nederland.
Tetapi sesudah itu semangat ultra-demokratis muncul kembali. Dalam Undang-Undang Dasar 1950 ditetapkan sistem kabinet parlementer. Dwitunggal Soekarno-Hatta dijadikan simbol negara belaka dalam kedudukan Presiden dan Wakil Presiden yang konstitusional, yang tidak dapat diganggu gugat. “Menteri-Menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”. Dan mulai saat itu tamatlah pada hakikatnya sejarah dwitunggal dalam politik Indonesia.
Pelaksanaan Demokrasi
Negara baru yang dibentuk dari menggabungkan 16 negara bagian Republik Indonesia Serikat menurut putusan K.M.B menjadi suatu negara kesatuan yang daerahnya meliputi seluruh Indonesia dengan Irian Barat sebagai daerah sengketa—negara baru ini akan menghadapi seribu satu soal dan kesulitan. Justru pada saat itu dua orang yang benar-benar mempunyai kewibawaan dibebaskan dari pimpinan negara paling riil dan dijadikan simbol belaka.
Sebenarnya ada suatu pertentangan perasaan dari dalam yang sukar mengatasi. Sistem dwitunggal itu sudah menjadi suatu mitos yang mempengaruhi jalan pikiran bangsa kita. Dalam alam pikiran rakyat yang banyak, segala kesulitan akan dapat diatasi selama dwitunggal itu berada di atas pucuk pimpinan negara. Sebaliknya orang ingin mempunyai suatu sistem pemerintahan yang lebih demokratis, yaitu di mana Pemerintah bertanggung jawab kepada Parlemen setiap waktu. Menurut jalan pikiran ini, di antara badan-badan yang kerja sama dalam melakukan pemerintahan, Parlemen dan Pemerintah, Parlemenlah yang terkuat. Sistem itu tidak jalan terhadap dwitunggal dengan kewibawaannya yang besar terhadap rakyat. Dalam pada itu ada pula aliran yang berpendapat, bahwa figur orang yang dua itu akan menjadi penghalang bagi tenaga-tenaga politik baru untuk maju ke muka. Ini merugikan bagi latihan demokrasi. Sebab itu perlu mereka meluangkan tempat dalam kekuasaan politik bagi pemimpin-pemimpin yang lain itu. Segala pertimbangan itu melupakan kepentingan yang lebih besar dan mendesak di waktu itu, yaitu bahwa negara perlu akan suatu pemerintah yang kuat yang mempunyai kewibawaan besar untuk mengatasi berbagai kesulitan.
Salah satu dari kesulitan yang terutama ialah bahwa cita-cita demokrasi memang ada di Indonesia, tetapi pelaksanaannyalah yang kurang. Selain dari itu pengalaman dalam pemerintahan demokrasi sedikit sekali: di luar daerah Republik Indonesia yang pertama yang hanya meliputi Jawa dan Sumatera hampir tak ada. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang pertama kali mewakili seluruh Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1950 bukanlah anggota yang dipilih oleh rakyat, melainkan diangkat oleh Pemerintah negara-negara bagian lama. Lebih dari separuh berasal dari pegawai negeri yang dalam zaman Hindia Belanda tidak mempunyai pengalaman politik.
Sebab itu tidak mengherankan, kalau di dalam Dewan Perwakilan Rakyat itu jumlah partai politik makin lama makin banyak. Akhirnya terdapat 19 buah. Orang dapat mengira betapa sulitnya membentuk suatu Pemerintah yang akan memperoleh dukungan oleh suara yang terbanyak di dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Tiap-tiap pemerintah mempunyai corak pemerintah koalisi, tersusun dari sedikit-dikitnya 7 atau 8 partai. Alangkah sulitnya menyusun program bersama dan menyetujui orang-orang yang akan duduk sebagai menteri. Dan kalau Pemerintah sudah berjalan dan kemudian ada partai dalam koalisi itu yang tidak mendapat kepuasan, lalu ia menarik menterinya keluar. Maka timbullah krisis kabinet. Kabinet jatuh karena kelemahan dari dalam, bukan karena votum dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Berkali-kali Pemerintah mengundurkan diri, tetapi belum ada yang jatuh di muka Parlemen karena salah suatu votum tidak-percaya. Dengan sendirinya pemerintah-pemerintah semacam itu, yang setiap waktu menghadapi soal politik di dalam dan di luar Dewan Perwakilan Rakyat, tidak cukup mempunyai kesempatan untuk memikirkan soal ekonomi dan pembangunan. Rencana yang diperbuat sudah terlantar lagi kalau Pemerintah sudah jatuh. Pemerintah yang menggantikan memikirkan lagi rencana baru.
Sesudah pemilihan umum tahun 1955 jumlah partai itu tidak berkurang, malahan bertambah sampai 28. Ini disebabkan oleh sistem pemilihan yang terlalu demokratis. Sebenarnya tiga partai yang terbesar di dalam Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu P.N.I, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama memperoleh suara terbanyak yang mutlak. Tetapi di antara Masyumi dan dua lainnya itu sukar mencapai persesuaian paham.
Kalau di negeri-negeri yang sudah lama menjalankan demokrasi masih terdapat perbuatan menyalahgunakan kekuasaan, apalagi dalam negeri yang masih muda seperti Indonesia. Bagi beberapa golongan menjadi partai pemerintah berarti “membagi rezeki”. Golongan sendiri dikemukakan, masyarakat dilupakan. Seorang menteri memperoleh tugas dari partainya untuk melakukan tindakan-tindakan yang memberi keuntungan bagi partainya. Seorang menteri perekonomian misalnya menjalankan tugasnya itu dengan memberikan lisensi dengan bayaran yang tertentu untuk kas partainya. Atau dalam pembagian lisensi itu kepada pedagang dan importir atau eksportir, orang yang separtai dengan dia didahulukannya. Keperluan uang untuk biaya pemilihan umum menjadi sebab kecurangan itu.
Partai yang pada hakikatnya alat untuk menyusun pendapat umum secara teratur, agar supaya rakyat belajar merasa tanggung jawabnya sebagai pemangku negara dan anggota masyarakat—partai itu dijadikankan tujuan dan negara menjadi alatnya.
Juga dalam hal menempatkan pegawai pada jabatan umum di dalam dan di luar negeri orang lupa akan dasar tanggung jawab dan toleransi dalam demokrasi. Seringkali keanggotaan partai menjadi ukuran, bukan dasar “the right man in the right place”. Pegawai yang tidak berpartai atau partainya duduk di bangku oposisi merasa kehilangan pegangan dan menjadi patah hati. Ini merusak ketenteraman jiwa bekerja, mendorong orang ke jalan curang dan korupsi mental. Aturan memperkuat budi pekerti, karakter pegawai, dengan politik kepartaian itu orang menghidupkan yang sebaliknya, mengasuh orang luntur karakter. Akhirnya orang masuk partai bukan karena keyakinan, melainkan karena ingin memperoleh jaminan.
Suasana politik semacam itu memberi kesempatan kepada berbagai jenis petualang politik dan ekonomi serta manusia profetir maju ke muka. Segala pergerakan dan semboyan nasional diperalatkan mereka, partai-partai politik ditungganginya, untuk mencapai kepentingan mereka sendiri. Maka timbullah anarki dalam politik dan ekonomi. Kelanjutannya, korupsi dan demoralisasi merajalela.
Demokrasi dan Diktator
Di mana-mana orang merasa tak puas. Pembangunan dirasakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang diharapkan. Kemakmuran rakyat yang dicita-citakan masih jauh saja, sedangkan nilai uang makin merosot. Rencana yang terlantar banyak sekali. Keruntuhan dan kehancuran barang-barang kapital tampak di mana-mana, seperti rusaknya jalan-jalan raja, irigasi, pelabuhan, berkembangnya erosi dan lain-lain.
Pembangunan demokrasi pun terlantar karena percekcokan politik senantiasa. Indonesa yang adil yang ditunggu-tunggu masih jauh saja. Pelaksanaan otonomi daerah dengan urusan keuangan sendiri yang lama sekali menunggu menjadi sebab timbulnya pergolakan daerah.
Daerah-daerah yang begitu banyak menghasilkan devisa buat negara, sedangkan mereka tidak melihat pembangunan di daerahnya, mulai menentang pemerintah pusat.
Sudah lebih dahulu angkatan perang merasa tak puas dengan jalannya pemerintahan di tangan partai-partai. Percekcokan politik di pusat besar pengaruhnya ke bawah. Pada daerah-daerah yang belum aman gerakan gerombolan makin menjadi. Semuanya itu harus dihadapi tentara. Aturan menyiapkan diri untuk tugasnya yang sebenarnya, yaitu melatih diri dan mengadakan perlengkapan untuk menghadapi musuh dari luar, ia terus-menerus saja disuruh melakukan tugas polisi ke dalam. Pada tahun 1952 pernah pimpinan angkatan perang memohon kepada Presiden supaya Presiden sudi mengakhiri cara Dewan Perwakilan Rakyat bekerja yang selalu menimbulkan politik yang tidak stabil. Petisi itu tidak berhasil, sebab Presiden menunjukkan kepada kedudukannya sebagai Kepala Negara yang konstitusional.
Akhirnya pesertaan tentara dengan gerakan rakyat pada beberapa daerah untuk menentang pemerintah pusat memaksa Pemerintah pusat mengumumkan keadaan bahaya. Sejak itu mulailah campur tangan angkatan perang dalam pemerintahan. Persengketaan tentang Irian Barat yang makin memuncak memberi kesempatan kepada beberapa golongan pemuda untuk mengambil alih beberapa perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Untuk menghindarkan kekacauan Pemerintah memberi tugas kepada angkatan perang untuk mengawasi semuanya itu. Dengan itu bertambah luaslah kekuasaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada tentara. Kalau mereka yang harus bertanggung jawab dalam berbagai bidang keamanan dan keselamatan umum, maka menurut pendapat mereka sudah selayaknya mereka ikut serta dalam pemerintahan negara. Untuk menanggalkan kekuasaan partai-partai politik dalam pemerintah, tentara menganjurkan ide: kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem Kabinet presidensial, itu disokong oleh beberapa golongan kecil yang merasa berjasa dalam revolusi tahun 1945 tetapi tak pernah terhitung dalam politik selama itu. Sudah tentu dengan interpretasi sendiri! Dari kanan dan kiri Presiden didesak supaya mengambil tindakan yang tegas untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan anti-konstitusional dianjurkan.
Maka terjadilah peristiwa yang disebut tadi pada permulaan karangan ini. Perkembangan politik yang berakhir dengan kekacauan, demokrasi yang berakhir dengan anarki membuka jalan untuk lawannya: diktator. Seperti diperingatkan tadi, ini adalah hukum besi dari pada sejarah dunia. Tetapi sejarah dunia memberi petunjuk pula bahwa diktator yang bergantung kepada kewibawaan orang seorang tidak lama umurnya. Sebab itu pula sistem yang dilahirkan Soekarno itu tidak akan lebih panjang umurnya dari Soekarno sendiri. Umur manusia terbatas. Apabila Soekarno sudah tidak ada lagi, maka sistemnya itu akan roboh dengan sendirinya seperti satu rumah dari kartu. Tidak ada seorang juga dari tim kerja sama yang diadakannya itu yang mempunyai kaliber dan kewibawaan untuk meneruskannya. Tidak pula ada bayangan dalam masyarakat, bahwa sistem itu disukai orang.
Konsepsi Soekarno
Kalau kita perhatikan golongan-golongan dalam Dewan Perwakilan Rakyat gotong-royong itu, yang akan mendukung sistem Soekarno, di situ tidak ada homogenitas. Malahan mereka itu terdiri dari berbagai aliran yang bertentangan satu sama lain, yang batas-membatasi dan hambat-menghambat. Mereka dapat kerja sama dengan musyawarah, karena ada Soekarno yang menentukan dan mereka mengiyakan.
Dalam keadaan semacam itu, tenaga-tenaga demokrasi dalam masyarakat terpaksa menunggu dengan sabar, apa yang akan dilahirkan oleh konsepsi Soekarno itu. Selama politiknya didukung oleh aliran-aliran politik yang terbesar jumlahnya dan golongan yang berkuasa, semuanya dengan semangat totaliter, aliran demokrasi tidak dapat berbuat apa-apa. Semangat totaliter sedang kuat berhubung dengan pemberontakan pada beberapa daerah.
Bagi saya yang lama bertengkar dengan Soekarno tentang bentuk dan susunan pemerintahan yang efisien, ada baiknya diberikan fair chance dalam waktu yang layak kepada Presiden Soekarno untuk mengalami sendiri, apakah sistemnya itu akan menjadi suatu sukses atau suatu kegagalan. Sikap ini saya ambil sejak perundingan kami yang tidak berhasil kira-kira dua tahun yang lalu. Ada ukuran yang objektif yang akan menentukan dalam hal ini. Tercapailah atau tidak kemakmuran rakyat dengan itu, kemakmuran rakyat yang Soekarno sendiri juga menciptakannya dengan sepenuh-penuh fantasinya? Sanggupkah ia menahan kemerosotan taraf hidup rakyat dalam tempo yang singkat? Dapatkah ia menyetop inflasi yang terus-menerus dalam waktu yang tidak terlalu lama, inflasi yang membawa orang putus harapan?
Itulah ukuran objektif yang tepat terhadap konsepsinya itu!
Bahwa Soekarno seorang patriot yang cinta pada Tanah Airnya dan ingin melihat Indonesia yang adil dan makmur selekas-lekasnya, itu tidak dapat disangkal. Dan itulah barangkali motif yang terutama baginya untuk melakukan tindakan yang luar biasa itu, dengan tanggung jawab sepenuhnya pada dirinya. Cuma, berhubung dengan tabiatnya dan pembawaannya, dalam segala ciptaannya ia memandang garis besarnya saja, yang mengenai detail, yang mungkin menyangkut dan menentukan dalam pelaksanaannya, tidak dihiraukannya. Sebab itu ia sering mencapai yang sebaliknya dari yang ditujunya.
Dalam suatu kritik terhadap konsepsinya kira-kira tiga tahun yang lalu saya bandingkan dia dengan Mephistopheles dalam hikayat Goethe’s Faust. Apabila Mephistopheles berkata, bahwa dia adalah “Ein Teil jener Kraft, die stets das Bose will und stets das Gute schafft”—satu bagian dari suatu tenaga yang selalu menghendaki yang buruk dan selalu menghasilkan yang baik—Soekarno adalah kebalikan dari gambaran itu. Tujuannya selalu baik, tetapi langkah-langkah yang diambilnya kerap kali menjauhkan dia dari tujuannya itu. Dan sistem diktator yang diadakannya sekarang atas nama demokrasi terpimpin akan membawa ia kepada keadaan yang bertentangan dengan cita-citanya selama ini.
Tadi saya katakan, bahwa demokrasi tidak akan lenyap dari Indonesia. Mungkin ia tersingkir sementara, seperti kelihatan sekarang ini, tetapi ia akan kembali dengan tegapnya. Memang tak mudah membangun suatu demokrasi di Indonesia yang lancar jalannya. Tetapi bahwa ia akan muncul kembali, itu tidak dapat dibantah.
Ada dua hal yang memberikan keyakinan itu kepada saya. Pertama, cita-cita demokrasi yang hidup dalam pergerakan kebangsaan di masa penjajahan dahulu, yang memberikan semangat kepada perjuangan kemerdekaan. Kedua, pergaulan hidup Indonesia yang asli berdasarkan demokrasi, yang sampai sekarang masih terdapat di dalam desa Indonesia.
Sudah biasa dalam sejarah, bahwa cita-cita yang murni dan indah tentang pergaulan hidup manusia dan bangsa lahir dalam masa penderitaan. Rakyat Indonesia menderita, berabad-abad lamanya, di bawah penjajahan Belanda. Kesengsaraan hidup, penghinaan bangsa oleh berbagai peraturan diskriminasi, pemerasan nasional di bawah suatu kekuasaan otokrasi kolonial, sifat pemerintahan jajahan sebagai suatu negara-polisi yang menindas segala cita-cita kemerdekaan—semuanya itu menghidupkan dalam pangkuan pergerakan kebangsaan cita-cita tentang persatuan Indonesia, perikemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Semuannya itu tergaris sedalam-dalamnya dalam jiwa rakyat Indonesia, sekalipun mereka hanya sanggup menyatakannya secara pasif. Tetapi di dalam kalbu orang pergerakan cita-cita itu hidup sebagai keinsafan hukum, yang harus memberi corak kepada Indonesia Merdeka.
Sejak dari masa penjajahan diciptakan bahwa Indonesia Merdeka di masa datang mestilah NEGARA NASIONAL, bersatu dan tidak terpisah-pisah! Ia bebas dari penjajahan asing dalam rupa apa pun juga, politik maupun ideologi. Dasar-dasar perikemanusiaan harus terlaksana dalam segala segi penghidupan, dalam perhubungan antara orang dengan orang, antara majikan dan buruh, antara bangsa dan bangsa. Lahir dalam perjuangan menentang penjajahan, cita-cita perikemanusiaan tidak saja bersifat anti-kolonial dan anti-imperialis, tetapi juga menuju kebebasan manusia dari segala tindasan. Pergaulan hidup harus diliputi oleh suasana kekeluargaan dan persaudaraan. Literatur sosialis yang banyak dibaca dan pergerakan kaum buruh Barat yang dilihat dari jauh dan dari dekat, memperkuat cita-cita itu menjadi keyakinan.
[Dinukil dari: Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, (Jakarta: Pustaka Antara), 1966, hlm. 5-22]
1Ejaan dalam tulisan asli telah diperbarui oleh redaksi.