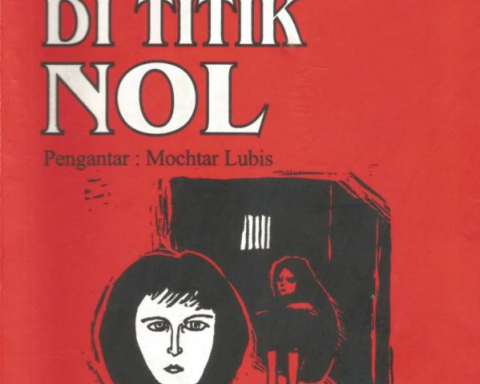Bagaimana para pengarang menghasilkan karya mereka? Berikut kami nukil beberapa jawaban dari Pramoedya Ananta Toer, Nasjah Djamin, Umar Kayam, Satyagraha Hoerip, dan Hamsad Rangkuti. Ada yang menjelaskannya secara filosofis, dan bahkan mistis, tapi ada juga yang teknis.
Pramoedya Ananta Toer (1925-2006)
Pulau kebahagiaan ini—karena tidak pernah mempelajari psikologi aku tak tahu namanya—mengandung dalam dirinya kebebasan, kemerdekaan mutlak untuk survive sebagai diri sendiri, intensif, kalis dari segala kekuatan politik, militer, sosial, dan ekonomi dengan semua sistemnya yang mungkin, sebuah khalwat persemadian, suatu conditio sine qua non, yang bagiku memberi kemungkinan untuk kerja kreatif. Pulau itu adalah sebuah mistikum, pulau di mana kawula meleburkan diri pada Gustinya, pulau di mana sang waktu berhenti bekerja, dan kerja kreatif di dalamnya merupakan keimanan. Ya, kerja kreatif adalah suatu bentuk keimanan.
Di pulau itu kutulis sejumlah karangan, termasuk di dalamnya Perburuan dan Keluarga Gerilya. Mungkin buat orang lain merupakan lelucon. Apa boleh buat. Tentang itu aku sendiri tidak memerlukan kepercayaan orang. Di kemudian hari kuketahui juga bahwa melalui rasio pulau itu pun dapat dilahirkan…
Di pulau yang kunamai mistikum itu kerja kreatif adalah mengagungkan Sang Gusti yang menghidupi, melahirkan kenyataan baru, yang kemudian hidup di luar waktu. Ia tetap dalam keadaannya sewaktu dilahirkan, tak peduli dua tiga atau empat generasi telah datang dan pergi…
Nasjah Djamin (1924-1997)
Dan yang paling penting ialah masuk ke dunia itu sendiri (dunia seni lukis dan dunia sastra), berhubungan langsung dan berdialog dengan hasil-hasil karya yang telah diciptakan manusia sebelumnya. Ya, faktor yang menentukan ialah hal tercampak dan dicampakkan ke dalam dunia itu sendiri…
Ternyata dunia “nyeni” bukan hanya kerja kemahiran tok, atau kerja perasaan tok, atau kerja pengetahuan tok. Ketiganya bergabung menjadi satu, ditambah “sesuatu”. “Sesuatu” inilah yang membuat karya si seniman punya arti dan nilai. Mungkin sesuatu ini berupa mengerti hidup dan kehidupan, mengerti manusia dan kemanusiaan, atau merupakan kepribadian dan sikap hidup. Bila hanya memiliki kemahiran atau teknik saja, maka ia akan jatuh pada keahlian “tukang” belaka…
Menulis sebuah novel—maksud saya memulai untuk mengerjakannya—amatlah sukar bagi saya. Sebab, memulai mengerjakan sesuatu seharusnya bila sudah siap segalanya. Saya sebenarya iri pada pengarang yang setiap hari dapat menyelesaikan sedikitnya 5 halaman-tik karangan. Juga iri pada Motinggo Busye, yang kadang kala dapat menyelesaikan dua novel sebulan. Mungkin ini disebabkan ingin ber-“santai” ala si Tambi yang saya angan-angankan sejak kecil. Tapi bila saya sudah mulai, sirnalah kesantaian; yang ada hanya mengetik siang malam. Memulai dapat saja tiba-tiba datangnya. Ini bukan soal “menunggu ilham” atau “menunggu waktu yang baik”. Tetapi karena semuanya dalam diri sudah siap dan matang, dan kini tinggal menggarapnya saja.
Yang saya maksud dengan siap atau matang ialah apa yang akan diungkapkan: cerita, setting, lokasi, tokoh-tokoh dan wataknya, hingga tokoh-tokoh sampingan. “Mempersiapkan” inilah yang amat utama dan penting, serta memakan waktu yang lama. Kadang-kadang memakan waktu dua tiga tahun. Biarpun dalam “mempersiapkan” saya tidak membuat catatan dan tidak mengerjakan sesuatu (seakan-akan bersantai belaka), novel yang akan digarap hari demi hari, minggu, bulan, dan tahun, kian mendapat bentuk dalam diri saya. Hingga pada suatu hari tiba-tiba mesin tik keluar, kertas dipasang, dan mulailah pekerjaan digarap.
Karangan langsung ditik tanpa ingat waktu dan hanya berhenti kalau lapar, minum, atau merokok. Semuanya keluar seperti meluncur tak terbendung. Dan demi mengejar luncuran yang deras itu, mau tak mau langsung diketik agar tidak ketinggalan atau kehilangan apa-apa yang menggebu keluar.
Apa yang sudah keluar dan terketik di atas kertas, tidak saya lihat atau baca kembali, kecuali kalau kehilangan jalur cerita atau tokoh. Tentu saja dalam mengetik pikiran berbelok di luar jalur yang sudah “siap” di dalam, dan belokan ini ikut tertera di kertas mengikuti derasnya “luncuran” pikiran. Mungkin saya termasuk orang “pengotor” dalam mengetik naskah, tidak mementingkan koreksi, tidak mementingkan salah tik dan segala kerapian penulisan naskah. Sebab ada perasaan pada saya bahwa apa yang keluar menggebu dan sudah tertera di atas kertas, “tidak dapat ditarik” lagi. Apa yang sudah terucapkan, tak dapat ditelan kembali…
Umar Kayam (1932-2002)
Barangkali ini masuk wilayah apa yang disebut “misteri penciptaan” itu. Penciptaan atau sebut saja “tulisan” sering maunya menentukan jadwal waktunya sendiri. Bahkan seringkali juga “malu” atau “segan” untuk tampil lagi selama-lamanya. Seperti Emily Brontë yang selama hidupnya hanya menulis satu roman Wuthering Heights, tetapi yang ternyata tidak kunjung padam membakar perhatian orang dan berbagai kalangan dan lapisan masyarakat—hingga sekarang!
Menulis, pada mulanya, ternyata adalah masalah kemauan yang pribadi sekali. Masalah determinasi. Selanjutnya, ternyata, boleh apa saja ikut terjadi…
Satyagraha Hoerip (1934-1998)
Seperti halnya pengarang lain, saya juga mengarang dengan metode blasteran. Maksud saya: mencampur imajinasi dengan realitas. Mengaduk-aduk khayalan dengan kenyataan. Dalam hal ini, pengalaman (baik pribadi atau dari orang lain yang saya dengar) saya nilai sebagai kenyataan juga. Nah, pengalaman dan khayalan ini, ditambah dengan gejolak atau gelitik yang sedang melanda diri saya, pada saat-saat yang khusus akan melahirkan cerpen atau novelet saya—yang tidak seberapa banyak.
Anehnya, sekarang ini saya bahkan ingat bahwa yang senantiasa sulit bagi saya ialah justru bagaimana memulai. Kata-kata atau kalimat pembukaan itulah agaknya yang selalu membuat saya gelisah, mencoba dan mencoba: bagaimanakah—setidak-tidaknya menurut saya sendiri—mendapatkan pembukaan yang enak, baik pembukaan yang mencekam atau sekadar mengasyikan pembaca? Memang, adakalanya sebelum memulai karangan itu, terlebih dahulu saya sudah punya angan-angan, yaitu ke manakah kira-kira cerpen itu nanti akan saya arahkan? Namun, tidak jarang pula bahwa saya menulis dengan sama sekali membukakan diri, kepada apa saja yang nanti akan mengalir ke mesin tik lewat jari-jari tangan saya. Semacam sumonggo kerso, begitu.
Tetapi, apa yang saya maksud dengan “saat-saat yang khusus” tadi? Itukah proses kreativitas? Yang saya maksudkan tak lain ialah saat-saat yang tidak berketentuan rentang waktunya. Ada kalanya berbilang jam, tapi tak jarang pula berbilang hari. Bahkan satu-dua ada yang berbilang minggu. Nah, pada saat-saat serupa itu, saya seolah seperti orang kerasukan. “Suasana” di atas kertas sering seakan-akan sepenuhnya saya kuasai. Apa pun yang terketikkan di atas kertas itu sesuai benar dengan yang dimaukan oleh otak saya. Akan tetapi, juga amat sering otak saya seolah-olah tergeser menjadi outsider, yang kadang kala saja mencoba berteriak sayup-sayup sampai dari atas tebing yang tinggi. Entah itu memberi saran, usul, koreksian, upaya untuk menyingkat kalimat, dan sebagainya. Tetapi pada umumnya lebih banyak diam dan membukakan diri saja pada segala yang melintas—sumonggo kerso…
Hamsad Rangkuti (1943-2018)
Saya adalah seorang pengelamun yang parah. Saya suka duduk berjam-jam di atas pohon membiarkan pikiran saya terbang ke mana dia suka tanpa saya mengontrolnya dan saya merasa nikmat. Seolah saya berada di alam lain… Barangkali kebiasaan seperti itulah yang sekarang saya tuliskan.
Pulang sekolah, saya tidak langsung ke rumah. Saya pergi ke kantor Wedana. Saya tahan berdiri berjam-jam di bawah papan di mana tertempel bermacam-macam koran yang terbit di Medan. Di bawah papan penempelan koran-koran itulah saya berkenalan dengan dunia fiksi. Saya tidak pernah membaca buku cerita yang bisa saya miliki atau bisa saya pinjam di kota kecil saya itu. Di koran yang ditempel di papan pengumuman di halaman kantor Wedana itulah saya membaca cerpen-cerpen. Pada penerbitan hari minggu, koran-koran itu memuat cerita pendek. Ada sebuah koran yang setiap minggu memuat cerpen-cerpen karya terjemahan. Koran itu masih saya ingat: Mimbar Umum. Di situlah saya mengenal Anton Chekov, Gorky, Hemingway, O. Henry, dan lain-lain. Saya pikir sekarang ini, koran Mimbar Umum itulah yang telah mengarahkan selera baca saya. Karena seringnya saya membaca karya-karya bernilai seperti itu, saya menjadi tidak suka membaca karya-karya pengarang lokal. Pada karya-karya mereka saya tidak mendapatkan gangguan batin seperti kalau saya membaca karya-karya terjemahan, kecuali beberapa nama yang karya mereka dimuat di koran-koran minggu yang terbit di Medan, seperti Bokor Hutasuhut, Partahi H Sirait, Ananta Pinola, dan SM Taufiq. Dari karya-karya merekalah saya menjadi tahu karya yang baik. Baik menurut ukuran saya waktu itu ialah mampunya karya itu mengganggu batin saya setelah saya selesai membaca sebuah karya. Kadang-kadang gangguan batin itu berminggu-minggu lamanya mengganggu pikiran saya. Maka timbul keinginan dalam diri saya untuk menjadi orang yang bisa menghasilkan karya tulis yang bisa mengganggu ketenangan orang lain…
Saya tergolong penulis berbakat alam. Saya tidak mendapatkan pendidikan khusus tentang kepengarangan. Saya hanya mendapatkan teori penulisan dari buku Teknik Mengarang Mochtar Lubis. Oleh sebab itulah barangkali saya menjadi pengarang yang tidak produktif. Tidak sebagai tukang cerita yang setiap saat bisa menghasilkan karya. Saya memerlukan waktu berbulan-bulan untuk bisa menghasilkan karya yang baru setelah saya menghasilkan sebuah karya…
Tahun 1975 merupakan tahun pergeseran saya dari penulis berbakat ke alam penulis yang menguasai unsur teknik. Tahun itu saya mendapat kesempatan mengikuti workshop penulisan skenario di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ). Workshop itu merupakan kerja sama antara Departemen Penerangan RI dan LPKJ. Di situlah saya mendapatkan ilmu penulisan. Saya mengenal unsur-unsur yang harus dikuasai oleh seorang penulis. Ternyata semua keahlian ada ilmunya. Tidak terkecuali di dunia penulisan. Apakah ilmu itu mendatangkan kebaikan kepada kepengarangan saya? Yang jelas saya bisa menulis banyak. Saya sudah dikatakan orang penulis yang produktif. Satu bulan bisa menulis beberapa cerita pendek…
Sekarang saya sudah bisa menjadikan sebuah cerpen dari apa yang saya dengar. Saya menjadikan cerpen dari apa yang saya lihat. Saya menjadikan cerpen dari apa yang saya baca di koran…
Menurut pengalaman saya, saya tentukan dulu teknik apa yang akan saya pakai setiap saya memulai sebuah cerita. Saya tidak bisa trance seperti orang lain. Saya tidak perlu membentuk mood baru saya mengarang. Saya tidak bisa mengarang dari nol. Cerita sudah selesai di dalam kepala saya, baru saya mengarang. Ada pun dialog-dialog yang muncul pada saat saya mengarang adalah semacam orang berjalan melihat sesuatu di sepanjang perjalanannya…
Pada dasarnya mengarang bagi saya adalah berpikir. Menimbang-nimbang komposisi, menyeleksi informasi, membangun unsur dramatik, dan memasukkan unsur keindahan. Bukan berhanyut-hanyut dengan kata-kata, atau menjadi pedagang kata-kata. Apakah saya berhasil? Saya berusaha…
[Dinukil dan disarikan dari: Erneste, Pamusuk (editor). 2009. Proses Kreatif: Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang (Jilid 1). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.]