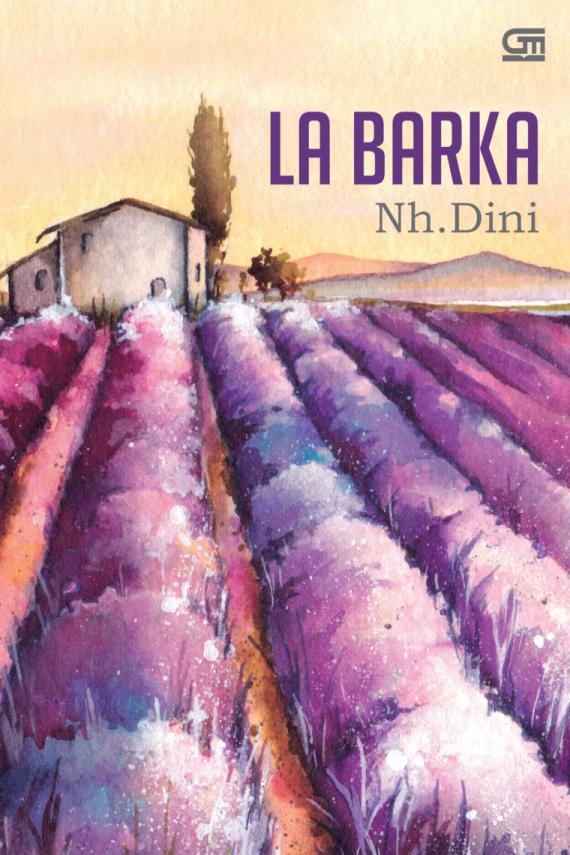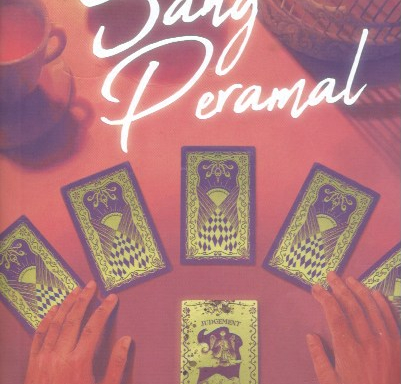Pada 29 Februari lalu, mendiang NH Dini berulang tahun ke-84. Salah satu novel yang dianggap karya terbaiknya adalah La Barka. Novel ini menggambarkan pemberontakan perempuan atas relasi yang timpang dalam pernikahan.
NAMA NH Dini selalu tampak menonjol di antara nama-nama pengarang dan sastrawan dalam buku pelajaran bahasa dan sastra. Tak hanya karena mudah diingat, NH Dini satu-satunya nama perempuan di tengah kerumunan nama laki-laki. Sependek pengalaman saya, setidaknya hingga awal 1990-an, anak sekolahan hanya mengenal satu nama pengarang-sastrawan perempuan dalam khazanah kesusastraan Indonesia: NH Dini. Meskipun nama-nama pengarang perempuan seperti Marga T atau Mira W populer pada 1980-an di kalangan penikmat novel percintaan, hanya NH Dini yang tetap bertakhta dalam lembar-lembar buku pelajaran bahasa dan sastra.
Pada 29 Februari lalu, Nurhayati Sri Hardini—nama lengkap NH Dini—berulang tahun ke-84. Google Indonesia mendedikasi doodle di halaman muka mesin pencarinya untuk mengenang pengarang yang wafat pada 4 Desember 2018.
Dini sudah mulai menulis sejak 1950-an, atau saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Cerita-cerita pendeknya kemudian mengisi koran-koran di Jakarta dan Yogyakarta. Bahkan, dia pernah mendapatkan penghargaan penulis sandiwara radio terbaik pada 1955. Di antara banyak karya Dini, yang paling melekat dalam ingatan saya kala sekolah adalah tiga novelnya: Pada Sebuah Kapal (1973), La Barka (1975), dan Namaku Hiroko (1977).
Dalam kesempatan mengenang 84 tahun NH Dini, saya akan memberi catatan terhadap La Barka. Ensiklopedia Sastra Indonesia menyebut novel ini salah satu karya terbaik Dini. Novel ini terbit pertama kali pada 1975 di tangan penerbit Dunia Pustaka Jaya. Pada 2000, penerbitannya diambil alih penerbit Grasindo dan kemudian Gramedia Pustaka pada 2010.
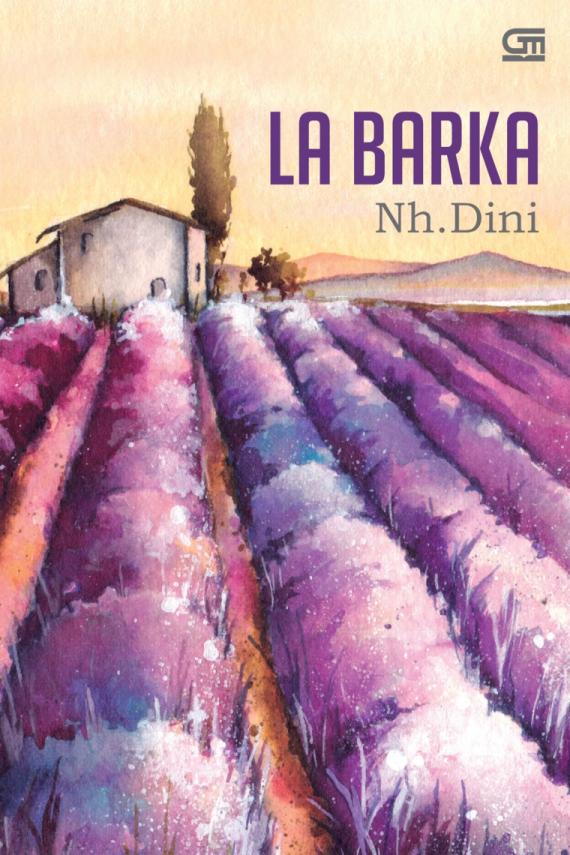
- Judul Buku: La Barka
- Pengarang: NH Dini
- Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama
- Terbit: April 2019 (cetakan kelima)
- Tebal: 248 halaman
Dini mengatakan, novel ini awalnya berjudul Musim Berlalu. Tapi, karena banyak novel pada saat itu menggunakan kata musim dalam judul, penerbit meminta Dini mencarikan judul lain. Dia pun akhirnya memilih La Barka.1Lihat Proses Kreatif: Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang Jilid 2. (Pamusuk Erneste: Editor). 2009. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 146.
Pilihan itu tepat karena pengisahan dalam novel ini. La Barka merupakan rumah perkebunan. Di rumah inilah, karakter utama, Rina Bonin, dan nyaris seluruh karakter berada di persimpangan jalan hidup mereka masing-masing. La Barka menjadi semacam titik pusat tali temali kompleksitas peristiwa dan perasaan di antara karakter-karakter novel.
La Barka bercerita dalam bentuk buku harian yang ditulis Rina untuk “kamu”, seorang wartawan perang yang bertugas di Saigon, Vietnam. “Kamu” adalah kekasih Rina saat Rina tengah menanti perceraian dari suaminya. Tidak jelas benar kapan peristiwa dalam La Barka terjadi. Kemungkinan yang paling mendekati adalah periode Perang Vietnam karena Rina menyebut kekacauan di Saigon dan insiden penyerangan atas Keduataan Besar Amerika Serikat di sana (catatan sejarah menunjukkan penyerangan ini terjadi pada 31 Januari 1968).
Rina sendiri warga Indonesia yang dibesarkan di rumah yatim piatu Katolik. Nasib mempertemukannya dengan seorang insinyur Perancis. Mereka pun kemudian menikah. Tapi, pernikahan tak berjalan mulus. Saat menanti perceraian, Rina berlibur bersama anaknya yang berusia tiga tahun di La Barka, kediaman sahabatnya Monique.
La Barka dikisahkan berlokasi di Desa Trans-e-Provence, Perancis Selatan. Dalam novel ini, kita akan mendapati lukisan cukup detail tentang suasana desa itu, kota terdekat bernama Draguignan, dan kota-kota lain di pesisir Laut Tengah. Dini memang pernah hidup di Perancis, sehingga wilayah ini tampak tak asing baginya.
Trans dan Draguignan adalah lingkungan kecil. Warganya saling mengenal. Hal ihwal mengenai seseorang pun bisa cepat tersebar, tak terkecuali perselingkuhan. Mereka sudah seperti kerabat, sehingga tak aneh jika seseorang tinggal menumpang di rumah orang lain selama berhari-hari, dan bahkan berbulan-bulan.
Demikianlah pula yang terjadi di La Barka. Tamu-tamu datang dan pergi. Mereka membawa kisah masing-masing. Lewat buku harian, Rina pun mengisahkannya untuk kita, dan menyampaikan perasaan dan penilaiannya atas kisah-kisah tersebut. Di antara beragam kisah itu, pengisahan utama La Barka adalah pernikahan yang berantakan, pemberontakan atas kemapanan sosial yang mendefinisikan relasi pria-wanita serta pertanyaan tentang cinta dan persahabatan.
La Barka—rumah berlantai dua dengan perkebunan seluas tujuh hektare—seakan menjadi garis pemisah antara generasi tua dan anak-anak mereka. Orang-orang tua bertahan dalam pernikahan meskipun tak bahagia. Tapi, generasi lebih muda tak bisa menanggung beban kemeranaan tersebut. Perempuan-perempuan dalam novel ini pun memberontak dan berupaya membebaskan diri dari pernikahan yang menyengsarakan, membelenggu kebebasan, dan bahkan menempatkan mereka sekadar pemuas birahi para suami.
Nyaris seluruh karakter perempuan dalam La Barka berada di ambang perceraian atau telah bercerai dan memiliki kekasih tanpa ikatan apa pun. Ironisnya, perkawinan mereka hancur justru ketika mereka tengah menikmati kesuksesan secara ekonomi. Kemapanan finansial malah membuat hubungan suami-istri menjadi tak seperti yang diimpikan. Tak ada lagi obrolan tentang “kita”, pandangan mesra, kecupan kasih di pipi atau kening, dan pelukan hangat seperti yang pernah dilakukan di saat-saat awal pernikahan.
Rina pun menggugat pernikahan.
“Dari pengalaman aku tahu, perkawinan bagiku tidak lagi merupakan tanda percintaan yang disatukan. Itu adalah pengesahan hukum yang dikarang manusia, di mana dua orang yang barangkali saling mecinta, setelah lima, sepuluh atau dua puluh tahun hidup bersama, tidak lagi menemukan pokok pembicaraan yang menarik satu sama lain. Dua orang yang kemudian disebut suami-istri, yang melanjutkan kehidupan sebagai otomat tanpa berpikir maupun berkehendak.”
Di sini, tak sedikit kritikus yang menilai Dini pengarang perempuan pertama yang menyuarakan feminisme dalam kesusastraan Indonesia. Bisa jadi demikian. Karakter utama yang dia ciptakan dalam La Barka, Rina, sampai pada kesimpulan: kalaupun harus berhubungan lagi dengan laki-laki, dia akan memilih relasi tanpa ikatan pernikahan; hubungan yang membebaskan.
Dia menilai dunia yang diciptakan masyarakat tak adil bagi perempuan. Suami punya seribu satu cara untuk memuaskan nafsu mereka sementara perempuan harus mengisap kesepian menanti kehadiran suaminya—yang bisa jadi telah menghabiskan malam-malam dengan banyak perempuan lain. Jika perempuan memilih peran bekerja, maka stigma yang akan muncul adalah risiko ditinggal dan dijauhi suami. Laki-laki, menurut Rina, tak bakal menghadapi stigma seperti itu.
Rina kemudian merasa dia bisa setia dengan satu cinta meskipun “bercinta” dalam maknanya yang banal dengan banyak laki-laki. Kesetiaan tak lagi dihubungkan dengan “bercinta” hanya dengan satu orang, tapi dengan mencintai, mengasihi, dan menghargai satu orang dalam kebebasan dan kesetaraan.
Namun, La Barka seakan menyiratkan pilihan sikap itu menentang sifat alamiah perempuan. Misalnya, Rina justru menyesal setelah bercinta dengan Robert, seorang mahasiswa yang lebih muda tujuh tahun. Padahal, laki-laki yang dia sebut “kamu”—yang dinanti-natikannya dengan setia itu—sudah tak pernah lagi berkirim kabar. Bahkan, saat tahu “kamu” telah berada dalam dekapan Sophie—perempuan bertubuh menggiurkan teman Monique—Rina pun masih tak bisa mengubur cintanya.
Di sisi lain, Rina sangat membenci Sophie yang memanfaatkan kemolekan tubuh demi mendapatkan kepuasan dari satu laki-laki ke laki-laki lain. Dari sudut pandang sebagian feminis, karakter Sophie justru mencerminkan otonomi seksual perempuan. Sophie membebaskan tubuhnya dari belenggu penguasaan eksklusif satu laki-laki. Dia lebih jauh menjadikan tubuh media ekspresi kebebasan seksualitasnya. Tentu saja tak semua feminisme memiliki pandangan seperti ini.
Pada akhirnya, La Barka menunjukkan bahwa NH Dini adalah pendongeng ulung. Dia telaten melukis, bukan hanya suasana pedesaan di Trans-e-Provence, tapi juga bentuk fisik dan watak setiap karakter—sampai-sampai Jakob Sumardjo menyebut novel ini “kanvas sesak” karena saking banyaknya lukisan watak.
Selain itu, lewat novel ini, Dini menempuh jalur penciptaan realisme tulen. Kisah Rina tak berakhir pada satu kesimpulan; satu penyelesaian. Sebab, bukankah begitu kenyataan hidup manusia? Segala sesuatu masihlah kisah yang tak berujung.[]