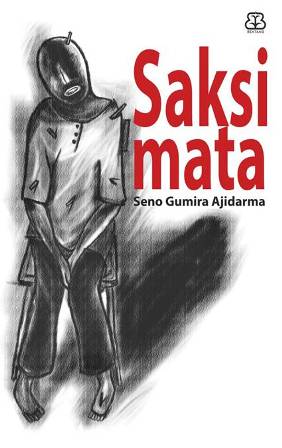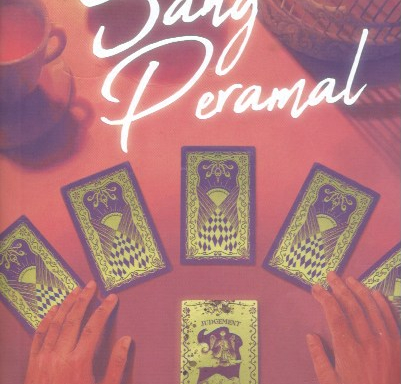Saksi Mata karya Seno Gumira Ajidarma menampilkan kekejaman seakan sesuatu yang normal. Kumpulan cerpen ini ingatan kolektif tentang catatan kelam negara. Lantas, mengapa manusia bisa sekeji itu terhadap sesamanya?
APA yang akan terjadi seandainya seorang saksi tiba di ruang pengadilan tanpa sepasang mata, dengan kedua lubang matanya masih menganga, dan darinya mengucur darah yang membasahi pakaian, mengaliri lantai hingga bahkan menggenangi jalanan di luar gedung?
Semua orang bisa dipastikan bakal lari tunggang langgang menyaksikan pemandangan horor itu. Hakim mungkin tak akan sempat mengetuk palu untuk menghentikan persidangan. Dan petugas pengadilan mungkin bakal segera membawa saksi itu keluar.
Tapi, itu tak terjadi dalam cerpen “Saksi Mata”, satu dari 16 cerpen dalam Saksi Mata karya Seno Gumira Ajidarma. Pengunjung pengadilan memang gempar, tapi itu tak berlangsung lama. Hakim segera menguasai keadaan dan melanjutkan pemeriksaan si saksi. Semua berjalan normal, seperti lazimnya persidangan.
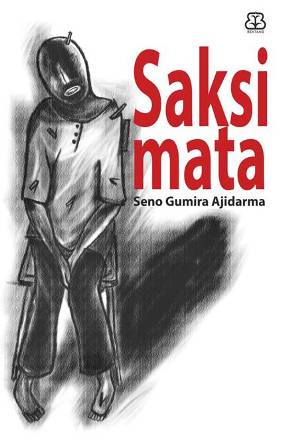
- Judul Buku: Saksi Mata
- Pengarang: Seno Gumira Ajidarma
- Penerbit: Bentang Pustaka
- Terbit: April, 2016
- Tebal: 168 halaman
Sungguh bukan gambaran riil tentang dunia manusia!
Begitulah pilihan estetika Seno dalam cerpen ini. Dia tak sedang mengaburkan batas antara gambaran dunia nyata dan fantasi dalam fiksi. Bukan itu! Keadaan tak masuk akal itu memang digambarkan “terjadi” dalam setting dunia riil manusia; suasana persidangan.
Bahkan, si saksi kemudian bersaksi bahwa kedua matanya dicongkel dengan sendok dalam mimpi oleh segerombolan orang. Di sini, Seno menciptakan lapisan fantasi di atas fantasi. Dia melakukan itu tanpa menjelaskan mengapa semua itu bisa terhubung dengan gambaran kenyataan. Dan memang tak perlu dijelaskan karena realisme magis—pilihan estetika itu—menganggap apa yang tak masuk akal itu adalah sebuah kenormalan atau kelaziman, dan sama pentingnya dengan apa yang dianggap masuk akal.
Realisme magis—yang kerap dihubungkan dengan kesusastraan di Amerika Latin, terutama dengan pengarang seperti Gabriel Garcia Marquez atau Jorge Luis Borges—mengajak pembaca mencari tahu apa yang ada di balik fiksi dan fakta. Dengan pilihan estetika ini, Seno seakan ingin mengatakan kekejaman yang terjadi secara faktual bisa sama—atau bahkan lebih—sadis dengan gambaran fiktifnya. Atau bahwa kekejaman faktual itu bisa begitu lazimnya terjadi seperti begitu normalnya semua orang di persidangan saat melihat saksi tanpa mata itu.
Perbedaannya, jika di dunia nyata coba ditutupi, kekejaman dalam fiksi tak bisa dibendung. Ia mengucur deras seperti darah yang mengaliri seluruh lantai dan jalanan di luar gedung pengadilan.
Lihat pula cerpen “Telinga” dalam kumpulan cerpen ini. Bagaimana seorang serdadu mengirim telinga mata-mata musuh ke pacarnya sebagai suvenir. Bukan cuma satu tapi ratusan telinga. Bukannya syok, sang pacar malah menjadikan telinga-telinga itu hiasan rumah, gantungan kunci, dan bahkan anting-anting. Betapa kekejaman berlangsung normal, dan bahkan dianggap cendera mata—sesuatu yang bisa dikenang atau diglorifikasi.
Banalitas kekejaman atau banality of evil merupakan istilah yang diciptakan Hanna Arendt dalam Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963). Itulah yang digambarkan Seno dalam Saksi Mata. Sepanjang buku, Seno melukiskan kengerian demi kegerian. Selain mata yang dicongkel (“Saksi Mata”) dan telinga yang dipotong (“Telinga”), ada wajah yang tak lagi berbentuk setelah didera penyiksaan hebat (“Maria”); mayat yang diseret kuda di atas jalan berdebu (“Salvador”); dan kepala yang ditancapkan di pagar rumah (“Kepala di Pagar Da Silva”).
Semua diceritakan dengan acuh tak acuh; dingin. Bahkan, dalam “Listrik”, Seno masih sempat-sempatnya mengisahkan sejarah penemuan setrum yang ternyata tak cuma berguna untuk menyalakan lampu tapi juga menyiksa tawanan. Di sini, Ia juga menyelipkan humor tentang kedunguan serdadu yang cuma bisa bilang “siap” kepada komandannya.
Tanpa membaca catatan pengarang di awal buku, generasi yang lahir setelah Orde Baru mungkin agak sulit mendeteksi latar peristiwa dan tempat segala kengerian itu terjadi. Seno memang sengaja menyembunyikannya demi meloloskan cerpen-cerpennya ke media massa pada sekitar 1993.1Lihat Seno Gumira Ajidarma. 2010. Trilogi Insiden. Yogyakarta: Bentang Pustaka. Hlm. 371.
Tapi, dia memberi petunjuk dalam nama-nama khas Portugis pada tokoh-tokoh cerpennya. Ya, kumpulan cerpen ini memang tentang kekejaman tentara Indonesia selama pendudukan Timor Leste, dan terutama setelah insiden Pembantaian Santa Cruz, Dili, pada 12 November 1991.
Cerpen-cerpen ini, bagi Seno, bentuk sublimasi setelah laporan jurnalistik majalah Jakarta Jakarta tentang insiden Dili membuat murka tentara dan penguasa. Perusahaan media itu kemudian mengeluarkan Seno dan dua redaktur lain dari redaksi Jakarta Jakarta pada 1992. Dia lalu memutuskan menuangkan laporan-laporan reporternya dari Dili, termasuk yang tercecer karena sensornya sendiri menjadi 12 cerpen yang terbit di sejumlah media massa dalam periode dua tahun.
Seno mengatakan, ini bentuk perlawanan rendah hatinya. “Cacing diinjak pun menggeliat, apalagi manusia,” katanya.2Ibid. Hlm 370.
Saksi Mata—yang kemudian diterbitkan sebagai kumpulan cerpen oleh Bentang Budaya pada 1994—justru menggema lebih keras dan luas daripada laporan jurnalistiknya. Buku ini telah diterjemahkan ke sejumlah bahasa asing, dibacakan di Taman Ismail Marzuki oleh sejumlah seniman pada 1994, dan dibuatkan buku audio pada 2014 dengan narator para selebritas.
Sebagai ingatan tentang kekejaman, Saksi Mata layak dijadikan bacaan bagi anak-anak sekolahan. Sebab, buku-buku sejarah mereka hanya menyinggung Timor Leste pada saat jajak pendapat 1999. Tak ada bab atau catatan singkat sekalipun tentang dampak pendudukan Indonesia di sana—yang kabarnya menewaskan ratusan ribu warga sipil.
Mengapa ini harus diketahui? Bukankah ini sejarah kelam negara ini yang memalukan?
Ini bukan soal membuka borok negara sendiri. Ini tentang keadilan sejarah, bukan hanya bagi korban—yang ironisnya hingga kini belum mendapatkan keadilan hukum—tapi juga bagi generasi muda bangsa ini. Kita pasti malu dengan catatan ini. Tapi dengan mengakuinya, kita akan mampu melewatinya dan tak mengulanginya—terlebih di hari-hari ketika kita masih mendengar kabar tentang kekejaman serupa terjadi di Papua.
Kembali ke Saksi Mata. Ada pertanyaan di balik banalitas kekejaman. Mengapa manusia bisa sampai sekeji itu terhadap sesamanya? Mengapa kekejaman itu berlangsung “biasa” dan bahkan diglorifikasi (pelakunya tak jarang disanjung bak pahlawan)?
Immanuel Kant percaya bahwa manusia pada dasarnya cenderung memilih perbuatan yang secara moral baik. Kalaupun pada akhirnya memilih perbuatan jahat, manusia dikendalikan oleh apa yang ia sebut cinta-diri (self-love). Karena itu, Kant tak percaya ada manusia yang berbuat jahat karena perbuatan itu an sich jahat. Hukum moral dan cinta-dirilah yang bertarung dalam diri manusia, dan pemenangnya akan menentukan pilihan moralitas manusia.3Lihat “The Concept of Evil” dalam The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 26 November 2013.
Arendt kurang lebihnya sependapat dengan Kant ketika menyimpulkan observasinya atas pengadilan Adolf Eichmann, di Yerusalem. Menurut Arendt, penjahat perang Nazi Jerman itu tak menunjukkan tanda psikopatik, atau dengan kata lain dia layaknya orang “normal”. Karenanya, Arendt berpandangan bahwa kekejaman terjadi karena ada insentif, dan dalam kasus Eichmann berupa iming-iming kenaikan pangkat dan kondisi totalitarian rezim Nazi. Tapi, Arendt buru-buru menegaskan bahwa manusia—bahkan yang paling lemah sekalipun—tetaplah memiliki pilihan moral meski berada di bawah kondisi yang memaksa.4Ibid.
Tak semua sependapat dengan Kant dan Arendt. Mereka memandang bahwa ada manusia yang sirkuit empati di otaknya sejak awal tak berkembang, alias tak mampu menempatkan diri dalam kondisi orang lain. Seiring waktu dan dipengaruhi sejumlah faktor, ia mengalami fenomena yang disebut “erosi empati”. Hasilnya, ia memandang orang lain sebagai bukan sepenuhnya manusia. Pendapat ini merujuk kepada tragedi-tragedi genosida yang mendehumanisasi para korbannya dengan sebutan-sebutan merendahkan, seperti “monyet”, “kecoa”, dan “cacing”.
Ahli psikologi Paul Bloom menilai pendapat “kekurangan empati” di atas tak bisa menjelaskan sepenuhnya akar dari kekejaman manusia. Dia bertanya, bagaimana mungkin seseorang mendehumanisasi orang lain jika tak menganggap korbannya sebagai manusia? Justru karena memandang korbannya sebagai manusia, ia menghinakannya. Sebab, ia tahu penghinaan itu akan membuat si korban menderita.5Lihat Paul Bloom. “The Root of All Cruelty?”. www.newyorker.com. 20 November 2017.
Singkatnya, Bloom menyimpulkan bahwa manusia bisa brutal terhadap sesamanya karena memandang yang lain sebagai ancaman bagi status dan cara hidupnya. Pelaku memandang para korban tak berperilaku sesuai apa yang dia inginkan. Mereka bahkan dia anggap bertindak lebih daripada apa yang sepatutnya. Dengan kata lain, kekejaman datang dari hasrat pelaku menghegemoni para korbannya.
Dalam “Darah Itu Merah, Jenderal”, Seno menghadirkan kisah dari kaca mata seorang pensiunan jenderal. Sang jenderal bangga dengan statusnya sebagai seorang prajurit. Bagi dia, tentara adalah pekerjaan termulia karena telah menjanjikan pengorbanan nyawa. Dia tak ingin apa yang telah diraih oleh kebanggaan ini diusik oleh berita wartawan, unjuk rasa mahasiswa, dan tuntutan merdeka.
“Mereka tahu apa? Bisanya cuma ngomong doang!” katanya. “Daerah itu kita rebut dengan mengorbankan beribu-ribu nyawa, apa sekarang kita harus menyerahkannya kembali?”
Dalam teks keagamaan, iblis—makhluk supranatural yang kerap jadi “kambing hitam” kekejaman manusia—dikisahkan menolak penciptaan manusia karena statusnya terancam terusik oleh kehadiran makhluk baru itu. Dia merasa makhluk termulia karena dicipta dari api sedangkan manusia dari tanah.
Ketakutan tampaknya melahirkan kesombongan—sebagai upaya untuk menutupi kelemahan. Karena sombong, seseorang bisa kehilangan empati. Kesombongan juga tak lain adalah cinta-diri (self-love) yang tanpa sadar menjadi kekuatan pendorong (insentif) kepada kekejaman atas sesama manusia.[]