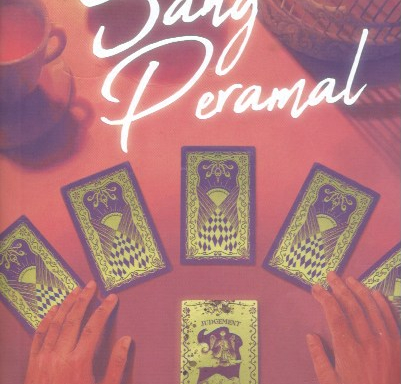Di tengah pandemi Covid-19, kami merekomendasikan Blindness. Novel karya pengarang peraih Nobel, Jose de Sousa Saramago, ini mengungkap kerapuhan kemanusiaan dan kemunculan kebinatangan manusia di hadapan krisis yang menghancurkan.
KETIKA pandemi Covid-19 mengguncang dunia saat ini, saya teringat dengan Blindness, novel karya pengarang peraih Nobel asal Portugal, Jose de Sousa Saramago. Novel ini memang tidak bercerita tentang virus yang menyerang sistem pernapasan tapi sesuatu yang surreal: wabah kebutaan tiba-tiba.
Kebutaan—setidaknya dalam perkembangan dunia kedokteran hingga kini—bukanlah sesuatu yang bisa datang tanpa gejala dan juga tak bakal menular hingga menjadi wabah. Tapi dalam dunia realisme magis Saramago, fakta medis itu dijungkirbalikkan.
Saramago memiliki strategi kepengarangan khas. Karya-karyanya seolah selalu bertanya, “bagaimana seandainya..?” Dalam The Stone Craft, misalnya, dia membayangkan Semenanjung Iberia terpisah dari Eropa dan mengambang di samudra layaknya atol. Lalu, dalam The Gospel According to Jesus Christ, dia berandai-andai Injil ditulis oleh Yesus sendiri sebagai manusia yang penuh hasrat dan keraguan.
Dalam Blindness, kebutaan tiba-tiba menimpa seseorang dan menular ke nyaris seluruh penduduk suatu kota. Kisahnya berfokus pada tujuh karakter: dokter spesialis mata, istri si dokter, perempuan berkacamata hitam, anak bermata juling, pria buta pertama, istri si pria buta pertama, dan pria tua bertampalan mata. Mereka dipersatukan oleh naluri bertahan hidup dalam mengarungi horor karantina di bangsal bekas rumah sakit jiwa dan di kota penuh orang buta.
Novel ini pertama kali terbit dengan judul Ensaio sobre a cegueira pada 1995. Giovanni Pontiero kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris pada 1997. Pada 2015, terjemahannya bahasa Indonesia novel ini diterbitkan oleh Penerbit Matahari, tapi tampaknya tak terlalu terdengar di pasaran.

- Judul Buku: Blindness
- Pengarang: Jose Saramago
- Penerjemah: Giovanni Pontiero
- Penerbit: Harcourt
- Terbit: September, 1998
- Tebal: 304 halaman
Blindness menjadi karya Saramago yang paling terkenal, mungkin antara lain karena sutradara asal Brazil Fernando Meirelles pernah mengadaptasinya ke layar lebar pada 2008. Film yang dibintangi oleh Julianne Moore dan Mark Rufallo ini sayangnya kurang memperoleh apresiasi positif kritikus sinema.
Jika dibandingkan dengan film karya Steven Soderbergh, Contagion (2011) yang banyak disebut-sebut di media sosial, novel Blindness kurang memiliki kemiripan dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini. Tapi, novel ini menggambarkan kerapuhan kompas moral manusia di hadapan ancaman wabah secara lebih intens dan ekstrem. Kelebihan utamanya terletak pada pilihan Saramago menjadikan kebutaan sebagai wabah.
Penglihatan merupakan indera terpenting manusia. Jika terinfeksi virus, kita masih bisa memenuhi sebagian kebutuhan dasar sendiri. Misalnya, kita masih bisa mengawasi sekitar kita, mengambil makanan, dan pergi ke toilet untuk buang hajat. Sebaliknya, jika buta, kita bergantung kepada orang lain yang bisa melihat sampai terbiasa dengan kebutaan. Persoalannya, dalam novel ini, nyaris semua orang buta mendadak kecuali “istri si dokter” yang tetap bisa melihat hingga akhir cerita.
Walhasil, novel ini melukiskan dengan banal karut marutnya situasi. Di bangsal karantina, bekas makanan dan kotoran manusia bertebaran di mana-mana. Bahkan, mayat manusia pun dibiarkan tak terkubur selama beberapa hari karena tentara penjaga bangsal takut tertular.
Di kota, keadaan jauh lebih kacau. Layanan utilitas publik—seperti air, listrik, dan telepon—kolaps karena para operatornya tentu saja buta. Lalu lintas menjadi arena mematikan karena tiba-tiba saja pengemudi menjadi buta. Orang-orang buta memenuhi jalanan dan saling bertubrukan layaknya barisan semut. Toko-toko rusuh karena orang tak lagi bisa melakukan aktivitas jual-beli.
Semua lukisan itu menunjukkan kerapuhan struktur yang menopang kehidupan manusia modern. Wabah kebutaan mendadak ini—yang disebut “white sickness” karena penderita seperti tenggelam ke dalam lautan susu—membuat teknologi secanggih apa pun tak bisa mengendalikan situasi. Pemerintah, dokter, dan para ahli tak bisa berbuat apa-apa untuk menemukan penawar karena tiba-tiba juga buta. Teknologi pada akhirnya sia-sia tanpa ada manusia bisa melihat yang mengoperasikannya.
Tapi, semua itu belum seberapa. Kebutaan juga memicu kerapuhan sosial. Ikatan sosial, seperti kewargaan, persahabatan, dan bahkan keluarga, cerai berai. Manusia tak lagi saling mengenal. “Si perempuan berkacamata hitam” tak lagi mengenali pria yang semalam bercinta dengannya meski keduanya berada dalam satu bangsal di karantina. “Pria buta pertama” juga tak menyadari kehadiran pria pencuri mobilnya meskipun mereka hanya dipisahkan satu ranjang. “Anak bermata juling” bahkan terpisah dari ibunya hingga akhir cerita.
Dunia serba putih. Dalam kebutaan “putih” ini, tak ada otoritas politik, sosial, dan akademik. Seseorang hanya berkuasa sejauh juluran tangan. Seseorang hidup untuk dirinya dan bahkan memandang yang lain sebagai ancaman. Bahkan, “si dokter” yang mencoba mengorganisasi bangsal pun tak bisa berbuat banyak ketika seseorang berkata kepadanya, “Mengapa kami harus menuruti Anda? Meskipun dokter, Anda sama-sama buta.”
Bahkan dalam krisis selevel Covid-19 saat ini, kita bisa menyaksikan sisi buruk manusia muncul ke permukaan. Memborong bahan makanan di supermarket. Berebut tisu toilet. Menimbun hand sanitizer dan masker.
Dengan menjadikan kebutaan sebagai wabah, Saramago juga mempertanyakan kesopanan dan kehormatan manusia. Apakah keduanya hanya ada karena ada mata-mata yang melihat? Dalam dunia yang serba buta, norma-norma kesopanan pun digambarkan menjadi tak berarti. Kita bisa telanjang, meraba tubuh orang lain, dan bercinta dengan siapa pun. Toh, tak ada seorang pun yang melihat. Benteng kemanusiaan pun jebol, dan sifat kebinatangan pun tampak.
Semua itu menjadi “kenormalan baru”. Tapi, siapakah yang bisa menyadari kebejatan di balik “kenormalan baru” itu. Dialah “istri si dokter”, satu-satunya orang yang masih bisa melihat–dan pura-pura buta supaya bisa bersama suaminya di karantina. Dia menanggung penderitaan “kenormalan baru” ini lebih berat daripada orang-orang buta dadakan tersebut karena dia menyaksikan semuanya. Hingga pada suatu kesempatan, dia bahkan berharap ikut buta.
Di sini, Saramago menunjukkan mengapa ia pantas diganjar Nobel Kesusastraan pada 1998. Blindness secara metaforis menggambarkan bahwa derita umat manusia bukanlah karena buta “mata fisik” tetapi buta “mata hati”.
Saramago tak tanggung-tanggung menjadikan “kebutaan” sebagai penggerak cerita. Tak hanya dalam substansi cerita, kebutaan juga tergambarkan dalam bentuk penuturan. Saramago tak memberi nama pada karakter-karakternya. Hanya sebutan-sebutan seperti “si dokter”, “istri si dokter, atau “si perempuan berkacamata hitam”. Apalah artinya nama jika kita tak bisa melihat? Lalu, dia juga tak menggunakan tanda petik pada dialog-dialog. Koma juga kerap dipakai sebagai pengganti titik. Dengan gaya ini, dia seakan meminta pembaca untuk meraba-raba layaknya orang buta.
Novel ini kemudian menunjukkan ketimpangan yang terus dipertahankan meski wabah kian menyebar. Otoritas politik memperlakukan yang buta layaknya binatang di karantina. Jatah makanan dibagikan seadanya. Tak ada perawatan medis bagi yang sakit dan terluka. Tentara penjaga karantina hanya punya satu tugas: menembak siapa pun yang berupaya keluar dari karantina.
“Rabies seekor anjing disembuhkan oleh alam,” kata seorang komandan penjaga karantina. Kata-kata ini menggambarkan kebijakan otoritas politik yang berharap para penghuni karantina mati pelan-pelan, dan wabah pun mereda.
Tapi, wabah pada akhirnya menginfeksi siapa pun, tak terkecuali mereka di pucuk kekuasaan.
Di tengah kekacauan dan krisis yang serba membingungkan itu, manusia membutuhkan seseorang dengan “penglihatan”; “visi”: seorang pemimpin. “Istri si dokter” tampil memimpin kelompok tujuh orang itu melewati krisis di tengah “kebutaan masyarakat”. Kepemimpinan di sini digambarkan tidak lahir dari status politik, sosial, dan akademik, tapi dari “visi”.
Pilihan Saramago kepada seorang perempuan untuk menjadi “pahlawan” dalam novelnya juga menarik untuk diperhatikan. “Istri si dokter” cuma ibu rumah tangga tapi tampil memimpin—bahkan memimpin suaminya sendiri. Dia juga menjungkalkan kekuasaan menindas yang coba dibangun oleh “pria bersenjata api” di dalam karantina.
Bagian ini salah satu kisah paling memukau dari novel ini. “Si pria bersenjata api” memerintahkan setiap bangsal menyerahkan perempuan untuk ditukar dengan jatah makanan, atau apa yang ia sebut “women for food”. Ini menunjukkan bahwa, dalam setiap krisis, perempuan rentan menjadi korban paling menderita.
Ketika wabah itu menghilang, dan satu demi satu orang mendapatkan penglihatannya kembali, eks orang-orang buta ini justru melihat hikmah di balik kebutaan. Saat buta, mereka justru bisa merasakan betapa rapuhnya teknologi yang diandalkan itu, ikatan sosial, dan kompas moral kemanusiaan. Kerapuhan ini tak pernah mereka rasakan saat mereka menikmati penglihatan. Kebutaan pada akhirnya bukanlah soal tak bisa melihat, tapi soal ketidakmampuan berempati dengan sesama.
“Si dokter mengatakan:
Tak ada orang buta, yang ada hanya kebutaan.
Lalu, “istri si dokter” juga mengatakan:
Saya rasa kita buta, buta tapi melihat. Orang buta yang melihat, tetapi tidak melihat.