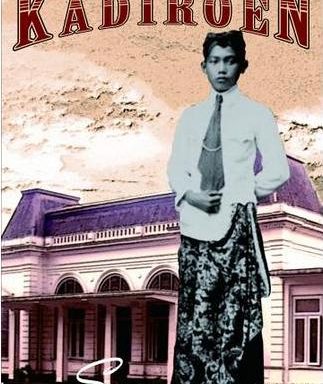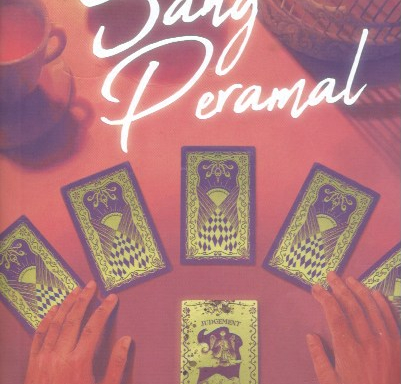Student Hidjo karya Mas Marco Kartodikromo tersisih dalam sejarah arus utama kesusastraan awal Indonesia karena tak direken Balai Pustaka, penerbit pemerintah kolonial. Padahal, kritikus sastra menilai imajinasi novel ini tak tertandingi oleh karya klasik populer, seperti Sitti Nurbaya dan Salah Asuhan.
ADAT dan gaya hidup bangsawan Jawa; kehidupan orang Belanda di Hindia dan pergaulan mereka dengan bangsawan Jawa; kehidupan pelajar Jawa di Den Haag dan romansanya dengan gadis-gadis Jawa dan Belanda, semua bisa Anda nikmati dalam Student Hidjo. Novel ini juga menyelipkan sedikit-banyak tentang pergerakan nasional, terutama perkumpulan Sarekat Islam pada awal Abad ke-20 dan persepsi berbeda dari dua karakter orang Belanda terhadap tanah jajahan mereka.
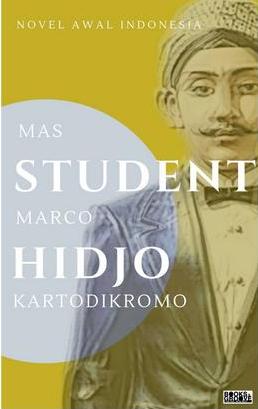
- Judul Buku: Student Hidjo
- Penulis” Mas Marco Kartodikromo
- Penerbit: Sinar Hindia (1918), Masman & Stroink (1919), Bentang Budaya (2000), Narasi (2010), Books & Groove (2019, digital)
- Terbit: 2019 (digital)
- Tebal: 143 halaman
Student Hidjo ditulis oleh Mas Marco Kartodikromo, salah seorang jurnalis awal di tanah Hindia. Dia pernah menulis untuk Medan Prijaji yang berbasis di Bandung (dan dikelola oleh Tirto Adhi Soerjo) dan Doenia Bergerak di Surakarta. Sempat tinggal lima bulan di Belanda dari akhir 1916 hingga awal 1917, Mas Marco terkenal dengan tulisan tajam mengkritik kebijakan pemerintahan kolonial dan tradisi feodal di negerinya. Sikap itu kemudian membawanya ke balik jeruji besi di Sawah Besar, Batavia. Dari balik terungku inilah, dia menulis Student Hidjo yang terbit berseri dalam majalah Sinar Hindia pada 1918.
Novel ini bisa dibilang karya klasik Indonesia, bertahan lebih daripada satu abad dan melalui berbagai kebijakan standarisasi ejaan bahasa Indonesia. Setahun setelah terbit berseri, NV Boekhandel en Drukkerij Masman & Stroink menerbitkan karya Mas Marco ini dalam bentuk buku. Penerbit pemerintah kolonial, Balai Pustaka, tak menganggap karya ini layak terbit karena penggunaan bahasa Melayu di dalamnya tak sesuai standar ejaan versi pemerintah. Mudah dipahami Student Hidjo nyaris hilang dari ingatan publik Indonesia, terutama dari buku-buku pelajaran sastra dan bahasa. Padahal, seperti ditulis kritikus sastra, Hendrik Menko Jan Maier, imajinasi novel ini melampaui karya-karya klasik populer seperti Sitti Nurbaya (1922, Marah Roesli) dan Salah Asuhan (1927, Abdoel Moeis).
Pada 2000, Bentang Budaya menerbitkan ulang novel ini dengan mengadaptasi ejaannya ke Ejaan Yang Disempurnakan. Edisi paling baru dirilis kembali dalam format digital oleh Books & Groove.
Melihat sepak terjang jurnalisme dan aktivisme Mas Marco (terutama keterlibatannya dalam pemberontak PKI pada 1926 yang menyeretnya ke kamp Bovel Digul, Papua, hingga akhir hayat pada 1932), Anda akan terkejut saat tak menemukan konflik antara rakyat jajahan dan rezim penjajah dalam novel ini. Satu-satunya konflik yang terasa justru antara dua orang Belanda saat Kontrolir Walter menentang keras persepsi negatif Sersan Djerpis tentang warga pribumi yang dianggapnya kasar dan bodoh. Sebagian besar konflik dalam novel ini bersifat laten. Karakter-karakter utama selalu berupaya menenggang rasa dan menjaga kesopanan pergaulan meskipun hati mereka memendam tanya dan gusar.
Mas Marco—yang lahir dari keluarga priyayi rendah di Blora, Jawa Tengah—memang bercerita dengan latar dua keluarga priyayi: keluarga seorang regent (bupati) di Jarak dan keluarga seorang priyayi pedagang di Surakarta. Dari keluarga terakhirlah, tokoh utama novel ini, Hidjo, berasal.
Pada awal Abad ke-20, ketika gerakan nasionalisme mulai menggeliat, bangsawan-bangsawan Jawa ini menghadapi dilema benturan budaya. Sementara tetap memegang teguh tradisi Jawa, mereka sehari-harinya lebih banyak berbicara dalam bahasa Melayu dan Belanda. Politik etis pemerintah Kerajaan Belanda pada masa itu menghadirkan sebagian kecil kebebasan di tanah koloni, seperti hak pendidikan bagi warga pribumi, terutama dari kalangan priyayi, di sekolah-sekolah Belanda. Di sekolah-sekolah inilah, mereka belajar, bukan hanya bahasa Belanda, tapi adat pergaulan Eropa.
Dilema tersebut tampak nyata pada diri Hidjo, terutama ketika mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan insinyur di Delft, Belanda. Mas Marco bahkan seakan menyandingkan Hidjo dengan Faust, karakter dalam legenda Jerman yang menjual jiwanya kepada iblis demi ilmu pengetahuan dan kenikmatan duniawi. Lihatlah Hidjo! Dia lebih menyukai makanan Eropa daripada masakan Jawa. Dia tergoda oleh kecantikan Betje, gadis Belanda, dan melupakan tunangannya, Raden Ajeng Biru, di tanah Jawa. Dia bahkan mengatakan: “Kalau kulit saya bisa menjadi putih, seperti orang-orang Belanda, memang saya senang menjadi orang Belanda, tetapi karena kulit saya ini bruin (merah tua), baiklah saya jadi orang Hindia saja.”
Satu hal menarik dari kisah romansa Hidjo dan Betje adalah keberanian Mas Marco untuk melukiskan berahi di antara keduanya dalam hubungan setara, dan bukan hubungan tuan dan nyai sebagaimana banyak ditampilkan dalam cerita dari masa itu. Meskipun tak vulgar, Mas Marco pada masa itu sudah menunjukkan bahwa seksualitas dalam kesusastraan Indonesia bukanlah tabu, dan bahkan itu ia tampilkan dalam hubungan perselingkuhan (karena Hidjo telah terikat pertunangan dengan Biru).
Kebalikan dari Hidjo, Walter dan Betje justru bersimpati dan menyukai tanah dan orang Hindia. Kepada Djerpis, Walter mengatakan orang Hindia sepuluh kali lebih beradab daripada orang Eropa. Kontrolir di Jarak itu bahkan menggambarkan dampak penjajahan dalam dua kenyataan kontras. Sementara orang Belanda rendahan seperti Djerpis bisa mengepul dan menikmati kekayaan di tanah Hindia dengan hanya ongkang-ongkang kaki, orang Hindia mesti bekerja sampai mandi keringat demi sekadar sesuap nasi tapi tetap dipandang pemalas. “Sedang tanahnya adalah tanah yang kaya raya. Adakah di negeri Belanda orang bekerja seberat itu hanya mendapat bayaran 25 ct dan 30 ct seperti orang Jawa? Tidak ada, kan?”
Walter dan Betje adalah karakter menarik dalam novel ini. Mereka menggambarkan bahwa tak semua warga negara penjajah berargumen membela kebijakan pemerintahnya. Penjajahan jelas jahat, tapi orang-orang yang karena hereditas—dan bukan karena pilihan—terpaksa berada di sisi penjajahan belum tentu jahat. Di sini, Mas Marco menunjukkan bahwa nuansa dalam memandang suatu periode sejarah amatlah penting karena kita kerap terjebak dalam dikotomi narasi besar kejahatan versus kebaikan.
Hidjo menyukai tanah Belanda. Walter dan Betje menyukai tanah Hindia. Perasaan mereka mungkin terdorong oleh cinta kepada orang di luar identitas asal mereka. Hidjo dan Betje saling jatuh cinta sementara Walter mencintai Raden Ajeng Wungu, putri Regent Jarak, yang mencintai Hidjo. Cinta menembus batas-batas geografis, agama, budaya, dan bahkan kelas sosial yang diciptakan politik kolonial antara bangsa penjajah dan kaum jajahan.
Pada akhirnya, mereka toh menyerah juga kepada identitas. Hidjo menyadari perasaannya kepada Betje “berbahaya”. Dia bahkan menilai perasaan itu sebanding dengan pengkhianatan kepada tanah airnya. Walter tahu dia tak mungkin menikah dengan Wungu karena perbedaan budaya dan agama. Anak-anak manusia itu akhirnya mesti berpisah karena identitas meskipun dikisahkan tetap berbahagia menerima “takdir” tersebut.[]