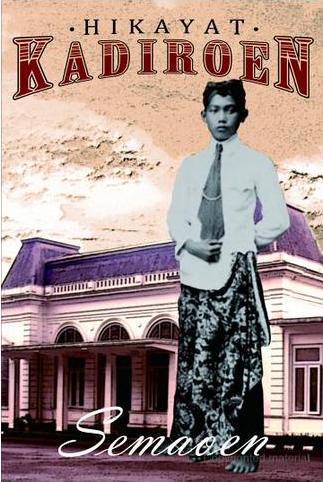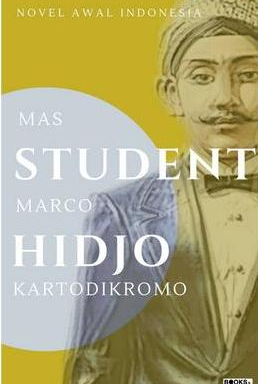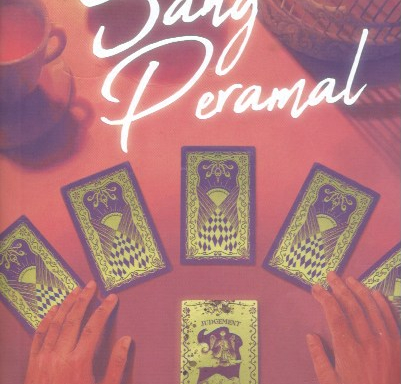Jika HB Jassin menilai Di Bawah Lindungan Ka’bah karya Hamka sebagai novel bercorak keislaman karena ada plot “jalan-jalan” ke Mekkah, lantas corak apa yang pantas disematkan pada Hikayat Kadiroen? Novel karya pendiri PKI, Semaoen, ini bahkan sudah membicarakan konsep “nur ilahi”.
STUDENT Hidjo (1918)—yang pernah kami ulas di sini—dan Hikayat Kadiroen (1919) adalah di antara karya sastra pertama yang terbit di tanah Hindia. Keduanya bahkan lebih awal hadir daripada Sitti Nurbaya (1922) dan Salah Asuhan (1926).
Periodisasi sastra yang dibuat A Teeuw dan HB Jassin tak memuat Student Hidjo dan Hikayat Kadiroen. Wajar, mereka berdua menganggap pengarang Indonesia baru bisa menulis sejak Balai Pustaka didirikan pemerintahan kolonial.
Balai Pustaka menilai kedua novel itu—dan sejumlah karya lain seperti Rasa Mardika (1924)—bacaan liar, karena di antaranya menggunakan gaya bahasa tak sesuai standar mereka. Jika dibandingkan dengan gaya bahasa para pengarang Poedjangga Baroe yang berputar-putar dan mendayu-dayu, Mas Marco Kartodikromo (Student Hidjo) dan Semaoen (Hikayat Kadiroen) menggunakan penuturan lugas, to the point, dan terkadang menyimpan geram.
Pramoedya Ananta Toer pada 1963 memperkenalkan karya Mas Marco dan Semaoen itu sebagai benih sastra realisme sosialis. Disebut “benih” karena realisme sosialis sendiri baru ditetapkan sebagai “kanun” kesusastraan—dan kesenian pada umumnya—gerakan komunis pada 1931 di kediaman pengarang kenamaan Soviet, Maxim Gorky. Pramoedya lebih lanjut mendaulat Mas Marco sebagai pengarang pelopor realisme sosialis di Indonesia.
Realisme sosialis sebenarnya mengundang perdebatan, baik di dunia maupun di Indonesia. Konsepsinya tak pernah terang benderang. Apakah ia teori kesusastraan atau ideologi politik yang menyatukan sekumpulan pengarang? Jika ingin dibedakan dari realisme Barat—dan tampaknya itu yang diinginkan—realisme sosialis tak sekadar melukis realitas sebagaimana adanya tapi juga berpihak pada perjuangan kelas proletar melawan kelas borjuis yang menindas mereka serta menggambarkan proses perjuangan itu menuju cita-cita komunisme: masyarakat tanpa kelas.
Dalam konteks tersebut, sastra realisme sosialis setidaknya bisa dilihat dari fitur-fitur yang dirumuskan kritikus Barat1. Fitur-fitur itu adalah: (1) protagonisnya digambarkan dalam psikologi dua dimensi, perannya lebih impersonal, dan berjuang menjadi sosok ideal “komunis” yang bermoral tangguh (berbeda dengan sastra Barat yang menggambarkan protagonis dalam psikologi kompleks, penuh keraguan, dan mencari identitas personal); (2) konfliknya lebih berkaitan dengan perjuangan kelas: antara kelas proletar melawan kelas borjuis (sementara sastra Barat kerap menyajikan konflik personal, khususnya percintaan); (3) berisi plot yang dipenuhi oleh retorika dan bahkan “pidato-pidato” politik; (4) sangat jarang ada ironi, menghindari ambiguitas penyelesaian masalah, dan membatasi sudut pandang (sementara ironi, ambiguitas, dan keragaman sudut pandang dinilai luhur dalam kesusastraan Barat); dan (4) akhir yang kuat, bahagia, dan konstruktif.
Fitur-fitur tersebut bermasalah karena teramat sempit. Quite Don, novel epik Mikhail Aleksandrovich Sholokhov (salah satu sastrawan realisme sosialis), menampilkan protagonis-protagonis dengan kepribadian kompleks, memiliki plot romansa, dan berakhir ambigu. Di Indonesia, sastrawan besar realisme sosialis, Pramoedya Ananta Toer, juga mewarnai penceritaannya dengan plot romansa (sampai-sampai seorang sutradara film salah memahami Bumi Manusia sekadar kisah percintaan remaja). Beberapa protagonis juga mengalami pergulatan psikologis dalam jiwa mereka. Yang paling kental dari karya Pramoedya adalah akhir yang sedih. Protagonisnya kerap kalah dalam pertarungan melawan kelas borjuis.
Kalaupun diterapkan, fitur-fitur itu hanya pas dengan karya-karya di Soviet pada masa kekuasaan Stalin2. Sastra di negara satelit Soviet dan sastra Soviet sebelum atau setelah Stalin belum tentu bisa didekati dengan cara tersebut.
Sementara itu, di Indonesia, jika menggunakan fitur-fitur tersebut, kita justru akan menemukan bahwa Hikayat Kadiroen adalah contoh “sempurna” novel realisme sosialis tahap awal jika dibandingkan dengan Student Hidjo. Dalam Student Hidjo, cerita masih berpusat pada seorang pribumi yang kepincut peradaban dan gaya hidup Eropa (termasuk kecantikan wanitanya)—tema sentral yang juga kita temukan dalam Salah Asuhan karya Abdul Muis. Bedanya dalam Student Hidjo, Hidjo menyadari kepribumiaannya meskipun alam pergaulan Eropa siap menyambutnya. Hidjo juga menganggap menjadi Belanda sama seperti Faust yang menjual jiwa kepada iblis. Sementara, Hanafi dalam Salah Asuhan justru merana karena terombang-ambing dalam dua dunia.
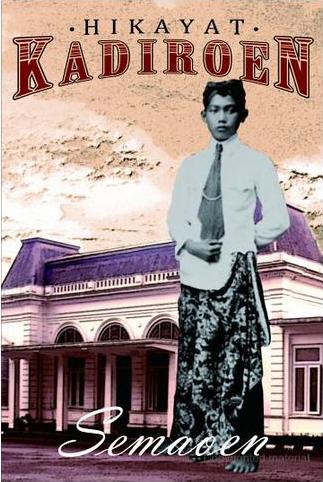
- Judul Buku: Hikayat Kadiroen
- Penulis: Semaoen
- Penerbit: OCTOPUS Publishing House
- Terbit: 2014 (Terbit pertama kali 1919)
- Tebal: ix + 277 (versi digital)
Semaoen sudah melampaui tema itu dalam Hikayat Kadiroen. Ia bercerita tentang keresahan seorang priyayi akan kemiskinan penduduk Hindia meskipun telah melakukan berbagai upaya sesuai kapasitasnya.
Semaoen menulis novel ini pada usia sekitar 21 tahun, saat dipenjara pemerintah kolonial karena menggerakkan pemogokan buruh pada 1918. Dalam usia tersebut, Semaoen bukan cuma telah menjadi pengarang tapi juga propagandis Serikat Buruh Kereta Api dan Trem (VSTP) di usia 18 tahun dan Ketua Sarekat Islam (SI) Semarang di usia 19 tahun.
Kadiroen adalah karakter ideal realisme sosialis meskipun datang dari latar belakang keluarga priyayi kecil. Ia priyayi yang jujur, berani, dan cerdas. Jiwanya tak pernah ragu dalam melihat mana yang benar dan salah. Sifat-sifat itu mengesankan atasannya orang Belanda, seperti asisten residen dan residen, sehingga karir kepriyayiannya terus menanjak hingga menjadi wakil patih.
Dalam birokrasi, musuh Kadiroen justru datang dari priyayi kolot, yang ingin menjilat Gubermen. Ini menunjukkan bahwa kolonialisme melintasi sekat identitas bangsa, ras, dan warna kulit.
Dalam jabatannya, Kadiroen berupaya memakmurkan pribumi. Tapi, sekeras apa pun upayanya hingga membuatnya jatuh sakit, penduduk Hindia tetap miskin dan tertindas. Berbagai kebijakan yang dia usulkan ke atasannya selalu terbentur tembok birokrasi Gubermen di Batavia.
Dia pun heran dan resah. Dia belakangan menemukan jawaban atas semua itu setelah mendengar pidato Tjitro, seorang propagandis Perkoempoelan Komunis (PK) dalam vergadering (rapat besar) di alun-alun sebuah kota.
Pidato Tjitro yang dicatat Kadiroen diceritakan detail, seolah Semaoen sendiri tengah mempropagandakan PKI yang dia dirikan pada 1920 kepada pembacanya. Karakter Tjitro yang berasal dari keluarga tukang batu tapi mampu berbahasa Belanda berkat kursus di sore hari juga seperti merujuk kepada riwayat hidup Semaoen.
Pidato ini menarik karena menyajikan pelajaran sejarah perubahan sosial masyarakat Hindia. Membaca pidato ini membuat kita teringat dengan analisis Karl Marx dan Freidrich Engels dalam The Communist Manifesto.
Marx dan Engels menjelaskan bagaimana masyarakat Eropa berubah dari masa Romawi kuno (dengan kelas sosial seperti ningrat, ksatria, rakyat jelata, dan budak) hingga feodalisme Abad Pertengahan (dengan kelas sosial seperti tuan tanah, mandor, petani, pekerja bebas, dan budak). Kelahiran modus produksi kapitalisme dalam revolusi Industri tidak menghapuskan pertentangan di antara kelas-kelas tersebut tapi menyederhanakannya dalam dua kelas besar: borjuis (pemilik modal) dan proletar (pemberi tenaga kerja).
Dalam pidatonya, Tjitro mengurut perubahan sosial masyarakat Hindia dari kepemimpinan bangsa Hindia sendiri, penguasaan bangsa Belanda yang dibantu raja-raja Hindia taklukan (yang kemudian diberi jabatan wedono, patih, dan regent), hingga periode liberalisasi ekonomi pada awal Abad ke-20 saat pemodal-pemodal besar Belanda datang. Tjitro kemudian mengungkap kunci dari kemiskinan dan ketertindasan penduduk Hindia. Mereka kehilangan “alat-alat produksi” seperti tanah dan hewan-hewan ternak.
Meskipun pekerjaan semakin banyak dan beragam karena berdirinya perkebunan dan pabrik, rakyat tak bisa lagi mengonsumsi dari apa yang mereka produksi sendiri (sawah sudah diubah jadi wilayah industri) serta daya beli berkurang karena harga ditentukan kartel kapitalis (sindikat pabrik gula). Pada saat yang sama, mereka bersaing satu sama lain berebut jatah pekerjaan di perkebunan dan pabrik dengan upah murah. Kehidupan keluarga dan sosial kemudian rusak karena rakyat tak bebas menentukan waktu kerja sendiri, seperti kala bertani atau mencari ikan di laut. Menurut Tjitro, perasaan merdeka rakyat telah hilang saat itu.
Dalam pidatonya, Tjitro juga memandang kemajuan lahir yang datang ke Hindia justru menyumbang kepada dekadensi moral dan spiritual. Kesusahan hidup lahir telah menjauhkan rakyat dari kehidupan batin. Pada masa itu, menurut Tjitro, mulai muncul berbagai jenis kejahatan.
Jika memandang komunisme itu ateisme dan anti-agama, Anda akan terkejut saat membaca novel buah pikir pendiri dan ketua pertama PKI ini. Isinya sarat dengan nasehat ajaran agama, dan bahkan terkesan ia seperti karangan seorang ustaz.
Ketika memutuskan menjadi simpatisan dan kemudian anggota PK, Kadiroen tidak ragu dengan agamanya. Ia justru bimbang dengan pekerjaannya. Dia harus memilih apakah tetap meniti karir di dunia priyayi atau melepas semua kemakmuran dan kebanggaan itu dengan mengabdikan diri di jalan pergerakan sebagai seorang komunis.
Sariman, pemimpin redaksi koran Sinar Ra’jat (tampaknya merujuk kepada Sinar Hindia, media milik SI), memberi banyak nasehat keagamaan kepada Kadiroen, yang kemudian menjadi redaktur koran tersebut. Dalam satu bagian, Sariman bahkan menyampaikan konsep “nur ilahi” dalam ajaran Islam.
Kepada Kadiroen, Sariman menyampaikan, dalam berjuang, jangan mencari kehormatan dan ketenaran. Dia mengatakan:
“Nama harum sejati, kemasyhuran sejati dan kehormatan sejati ialah cahaya jiwa. Manusia hanya bisa bercahaya kalau mendapat bintang dari Tuhan Allah, yaitu bintang yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah kepada manusia. Dan bintang itu oleh kebanyakan orang Islam dinamakan nur… Kita manusia bisa mendapatkan anugerah bintang jiwa itu, tetapi jiwa kita mesti membuktikan lebih dahulu bahwa memang sudah adil kita mendapatkan bintang atau nur itu. Bagaimana bisa membuktikan, tidak lain hanya melalui jalan berbuat baik buat beribu-ribu manusia yang ada dalam kesusahan, kesukaran, kebodohan, penindasan, atau kemiskinan. Sudah tentu manusia yang mau berbuat baik buat semua manusia lain itu, mesti memperbaiki batinnya lebih dahulu. Hanya jika memperbaiki batin tersebut dilakukan sebagai tujuan penghabisan, tentu ia lalu bisa hidup selamat, senang, dan tenteram.”
Alhasil, jika HB Jassin menilai Di Bawah Lindungan Ka’bah karya Hamka sebagai novel bercorak keislaman karena ada plot “jalan-jalan” ke Mekkah, lantas corak apa yang pantas disematkan pada Hikayat Kadiroen? Apakah kita bisa menyebut novel ini “sastra komunis-religius”?[]
1Lihat Gary Saul Morson, “Socialist Realism and Literary Theory” dalam The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 38, No. 2 (Winter, 1979), hlm. 121-133.
2Ibid.