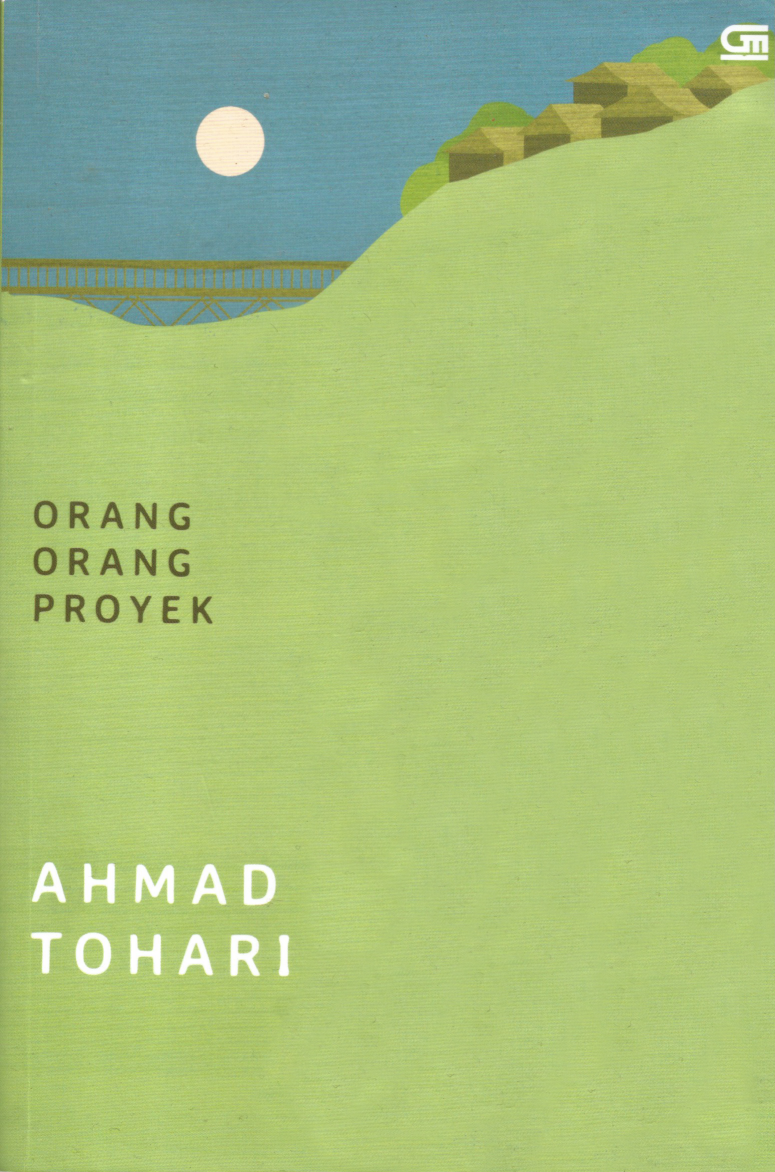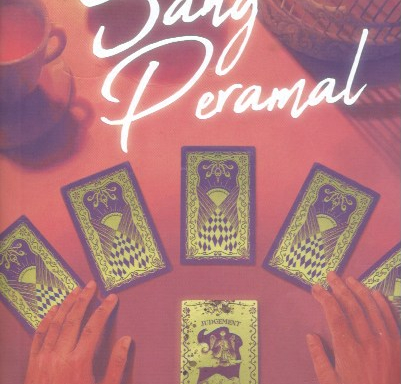Dalam Orang-Orang Proyek, Ahmad Tohari tampak lebih percaya kepada karakter manusia dalam membasmi korupsi daripada sekadar pembenahan sistem. Karakter itu membuat manusia berani mendengar suara nurani sendiri.
KETIKA membaca tuntas novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari, saya teringat kata-kata sineas Korea, Bong Joon-ho, pada resepsi pendaulatan dirinya sebagai sutradara terbaik Oscars 2020. “The most personal is the most creative, ujar Bong seraya mempersembahkan kata-kata itu kepada Martin Scorsese, sineas Amerika yang berada pada daftar nominasi kategori sama dan sudah dia anggap sebagai suhunya sendiri.
Orang-Orang Proyek, menurut saya, adalah cerminan dari “yang paling pribadi” dari Ahmad Tohari. Lupakan dulu soal tema novel ini! Nikmatilah bagaimana Tohari melukis suasana alam kampung, flora dan faunanya, serta gerak kehidupan sekitar. Lukisannya sungguh detail dan mengagumkan. Dia menceritakan bagaimana hewan dan tumbuhan tertentu berperan dalam suatu kelahiran dan jalinan rantai kehidupan di alam semesta.
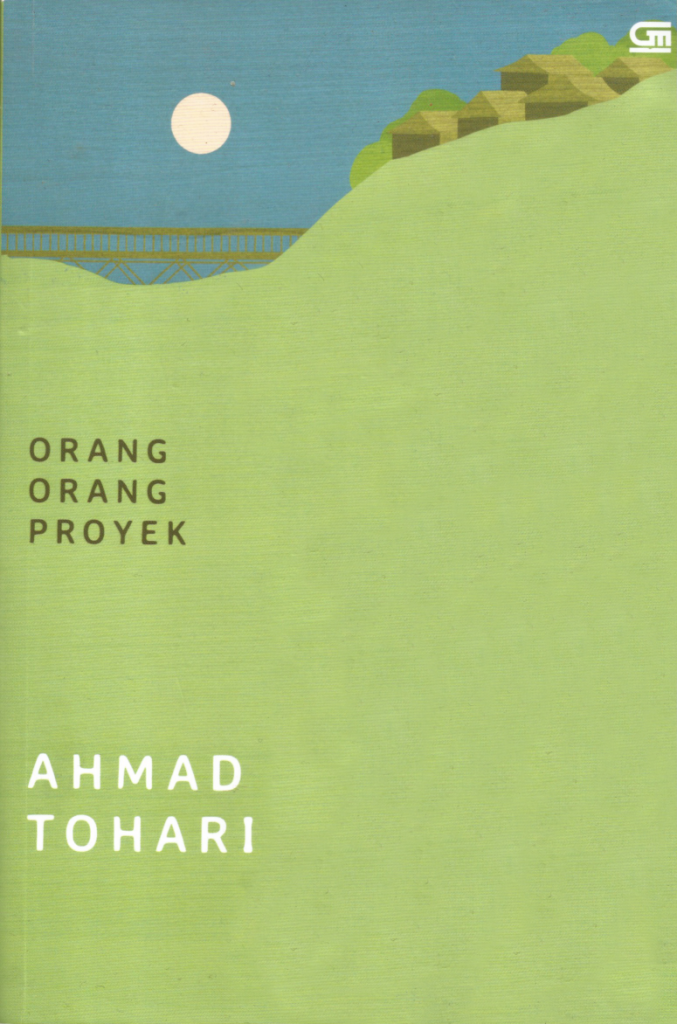
- Judul Buku: Orang-Orang Proyek
- Pengarang: Ahmad Tohari
- Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
- Terbit: 2007
- Tebal: 253 halaman
Selami pula pengisahan Tohari tentang kehidupan orang-orang proyek: pimpinan proyek, mandor, tukang, dan kuli. Dan bagaimana mereka yang mengais hidup di sekitar proyek: pemilik dan pelayan warung tegal serta waria penghibur. Bagian ini tak kalah rinci dan mengalir seakan sang pengarang pernah menjalani kehidupan seperti mereka.
Tohari anak kampung dari Banyumas. Dia juga berasal dari keluarga petani meskipun ayahnya kemudian sempat menjadi pegawai negeri di kantor urusan agama. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang ia cicipi semasa kecil meskipun latar belakang ini tak menghalanginya bergaul dengan komunitas abangan setempat.
Itulah mengapa karya-karyanya—setidaknya dua novelnya yang pernah saya baca; Ronggeng Dukuh Paruk dan Orang-Orang Proyek, sarat dengan lukisan keadaan alam perkampungan. Kearifan ala banyumasan juga kerap bisa kita jumpai. Lalu, satu unsur lagi yang tak boleh terlewat adalah bagaimana Tohari menyelipkan penafsiran progresif tentang ajaran Islam.
Sebagai contoh dalam Orang-Orang Proyek, perhatikanlah percakapan antara Kabul, karakter utama novel ini, Basar, dan Pak Tarya tentang hadis Nabi: Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak.
“Nanti dulu. Jadi, pengucapan syahadat, tindakan salat, dan seterusnya bukan tujuan keberagamaan kita?”
“Perhatikan lagi kata ‘kecuali’. Dengan demikian kita yakin bahwa tujuan keberagamaan kita adalah penyempurnaan budi luhur. Sedangkan kelima rukun itu hanya sarana untuk mencapai tujuan itu. Sarana, atau jalan, atau syariah. Tapi sepenting-pentingnya syariah, dia hanya jalan, bukan tujuan.”
Namu demikian, “yang paling pribadi” tak serta merta jadi “yang paling kreatif”. Di sini dibutuhkan kemampuan abstraksi seseorang. Inilah kualitas kepengarangan, menurut Pramoedya Ananta Toer. Seorang pengarang mampu memperlakukan pengalaman pribadi sebagai pengalaman bangsa, dan sebaliknya. Pengarang, masih menurut Pramoedya, mampu melahirkan kenyataan hilir; kenyataan sastrawi; kenyataan baru dari kenyataan hulu atau kenyataan sejarah (pengalaman).
Tohari menunjukkan kualitas kepengarangan seperti itu, baik dalam Ronggeng Dukuh Paruk maupun Orang-Orang Proyek.
Dari sini, kita memasuki tema novel ini. Dari judul, kita bisa menduga novel ini akan berkisah tentang korupsi dalam sebuah proyek pembangunan—sesuatu yang tampak jamak di negeri ini. Saking jamaknya, kata proyek menerima nuansa makna negatif: sesuatu yang bakal dieksploitasi untuk kepentingan tertentu; akal-akalan. Saya bahkan kerap harus mengganti kata proyek saat membuat proposal kegiatan, padahal kata itu objektif serapan dari project dalam bahasa Inggris yang berarti ‘upaya terencana’.
Ya, itulah tema utama novel ini. Kabul, seorang insinyur sipil bekas aktivis mahasiswa, harus menghadapi rongrongan demi rongrongan yang menggerogoti kualitas proyek pembangunan jembatan di atas Sungai Cibawor yang dia awasi. Latar waktu novel ini adalah 1991 dan menjelang pemilu 1992, saat Orde Baru sedang jaya-jayanya sekaligus dampak kejahatannya kian telanjang di depan mata.
Tohari menggambarkan korupsi dan bancakan proyek seperti aliran darah di urat nadi kita: sesuatu yang sudah menjadi bagian hidup kita sehingga kita tak merasakan ada yang salah atau aneh. Justru saat interupsi terjadi, kita memandangnya aneh. Dari pejabat elite, seperti menteri, ketua partai, bupati, serta anggota dewan, pengurus partai lokal, pemborong proyek, hingga bahkan warga desa, semuanya berburu rente dari proyek jembatan Cibawor. Pejabat pemerintah cum pembesar pusat partai berkuasa menangguk persenan sejak penganggaran, lelang, hingga perencanaan. Pengurus lokal partai merongrong lewat sumbangan untuk pembangunan jalan dan masjid kampung. Warga mencoba memungut remah-remah dari bahan-bahan bangunan dengan menyuap mandor atau kuli. Pokoknya, semua menyeleweng. Karena itu, ketika ada satu orang saja yang tak cawe-cawe, dia akan dianggap menyalahi “kodrat”; aneh, lugu, dan sok idealis.
Di tengah suasana seperti itu, novel ini menampilkan sejumlah karakter berbeda. Mereka semua tahu korupsi itu salah tapi respons mereka berlainan.
Dalkijo, si kepala pemborong proyek, menganggap korupsi adalah realitas yang tak hanya tak bisa dihindari tapi juga mesti dinikmati. Dia bilang, ini pembalasan atas kemiskinan yang ia derita di masa kecil. Inilah saatnya dia menikmati apa yang tak dinikmati dulu, bersenang-senang, sepuas-puasnya, dan selagi sempat. Korupsi, bagi Dalkijo, jalan satu-satunya bertobat dari kemelaratan lalu menjadi kaya raya. Tak ada gunanya idealisme melawan arus besar korupsi. Orang idealis tak mampu mengubah apa pun, tak juga sanggup melibas kuasa gelap korupsi. Idealisme hanya akan menghasilkan kemelaratan bagi si idealis sementara yang lain foya-foya.
Lalu ada Pak Tarya, bekas wartawan dan pensiunan pegawai negeri di kantor penerangan. Seperti Dalkijo, dia juga menyerah kepada realitas korupsi. Bedanya, Pak Tarya tak mau ikut edan. Dia lebih memilih menyendiri; menyepi, dan menikmati hidup. Memancing dan memainkan suling di bawah pohon mbulu adalah kesibukannya sehari-hari. Dia tak mau dibuat gelisah oleh realitas itu, apatah lagi melawannya. “Mengapa sampeyan gelisah? … Soal penyelewangan, di mana sih hal itu tidak terjadi?” kata Pak Tarya coba menenangkan Kabul.
Kabul berbagi kegelisahan bukan hanya dengan Pak Tarya tapi juga Basar, sesama mantan aktivis mahasiswa dari kampus yang sama. Basar memilih karir sebagai kepala desa usai kuliah. Dia juga merasa tertekan setiap kali pejabat lokal partai berkuasa Golongan Lestari Menang (tak salah lagi ini merujuk kepada Golongan Karya yang di era Orde Baru mustahil dikalahkan dari pemilu ke pemilu) menyambanginya untuk meminta ini dan itu. Basar menghadapi dilema antara menolak dengan risiko tersingkir dari jabatan atau menerima tekanan dan bertahan demi kebaikan warga kampung. Dia merasa masih bisa bersiasat menghadapi tekanan demi tetap bisa melayani dan memperbaiki kondisi warga dengan jabatan itu. Dalih ini kerap kita dengar dari bekas aktivis yang menjadi pejabat: membenahi kondisi dari dalam sistem, kata mereka. Pada akhirnya, tak ada yang bisa dilakukan Basar. Dia malah jadi sekrup dari mesin besar korupsi yang menggasak proyek Kabul.
Pada akhirnya adalah Kabul. Meski protagonis dalam novel ini, Kabul tak sepenuhnya ideal. Ini bukan proyek pertamanya bersama Dalkijo. Dia bertahan karena masih harus menanggung hidup ibu dan dua adik. Tapi, Kabul kemudian tak bisa lagi membendung kegelisahannya. Dia merasa keinsinyurannya dicabik-cabik kepentingan politik. Dia pun sampai pada satu titik di mana harus mengambil sikap; setidaknya sekali saja dalam hidup. Di antara dua pilihan dalam kata-kata Ki Hajar Dewantara numpak montor sinambi sawan tangis (punya kekayaan meski itu hasil mencuri dan hidup gelisah) atau mikul dhawet sinambi rengeng-rengeng (hidup sederhana tapi tenang), batin Kabul akhirnya memilih yang kedua. Dia teringat dengan ibunya yang dia sapa Biyung. Sang Biyung tetap sanggup menyekolahkan dia dan dua adiknya hingga perguruan tinggi dengan hidup sederhana: memilih menanak inthil daripada nasi sehingga bisa berhemat dan menabung.
Keempat karakter di atas masih bisa kita amati saat ini meskipun latar kisah dalam Orang-Orang Proyek terjadi 29 tahun lalu. Rupanya tak ada yang berubah di kolong langit negeri ini; semuanya berputar-putar di situ-situ saja. Meskipun era reformasi menyaksikan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, kuasa gelap itu tetap menghantui banyak orang, terutama mereka dengan akses kepada kekuasaan.
Modus korupsi saat ini bahkan lebih canggih. Istilah-istilahnya juga kian keren. Tak seperti dulu di mana pejabat dan birokrat menyebut persenan uang tanpa sungkan, kita saat ini mengenal istilah-istilah “apel washington”, “kardus durian”, dan bahkan istilah agama seperti “bisyarah”.
Sistem pemberantasan memang di awal tampak bekerja. Pejabat kelas teri sampai kakap, seperti menteri, gubernur, bupati, dan bos partai, digelandang ke dalam terungku KPK. Tapi, penjara kemudian dibuat nyaman untuk koruptor. Hukuman mereka terus dikentit, dikorting dengan berbagai dalih. Lalu, kalau bisa—dan tampaknya sudah dilakukan—lembaga pemberantasnya sendiri dirusak: dirundung dengan tuduhan “taliban” dan kemudian dilemahkan dari dalam.
Para teknorat pemuja sistem mungkin akan bilang bahwa resep membasmi korupsi adalah pembenahan sistem. Manusia seburuk apa pun tak bakalan korup dalam sistem baik. Sebaliknya, manusia sebaik malaikat pada akhirnya jadi iblis dalam sistem jahat. Tapi, dalam Orang-Orang Proyek, Tohari tampak lebih percaya kepada karakter manusia: dia yang berani mendengar suara hati nurani sendiri. Perang batin Kabul sepanjang novel ini menjadi gambarannya.
Secanggih apa pun, sistem itu mati. Manusialah yang hidup. Tentu saja perbaikan sistem tetap diperlukan. Tapi coba lihat, apa yang kurang di negeri ini setelah Orde Baru tumbang? Ribuan undang-undang dibuat. Lembaga-lembaga pengawas seperti Ombudsman dan KPK juga sudah dilahirkan. Toh, kuasa gelap korupsi masih kuat membayangi negeri ini.
Sementara itu, manusia berkarakter seperti Kabul bisa bersikap menolak korupsi, justru di tengah zaman yang katanya paling edan dalam sejarah Republik. Karakter itu Kabul dapatkan dari pendidikan di keluarga sejak kecil. Tohari menyebut karakter itu dalam istilah banyumasan: cablaka: terus terang; jujur; apa adanya.
Cablaka, menurut saya, adalah keberanian kita berbicara kepada nurani. Sebab, di dalam nurani, kata para sufi, Tuhan bersemayam. Persoalannya, manusia kerap gentar berjumpa dan berbincang dengan nurani sendiri karena nurani terlalu cablaka. Kegentaran itu datang karena kita kerap merasa lebih aman berkompromi dengan kenyataan di luar diri. Kita lebih memilih mencampakkan suara nurani daripada godaan materi, perkoncoan, atau jabatan.[]