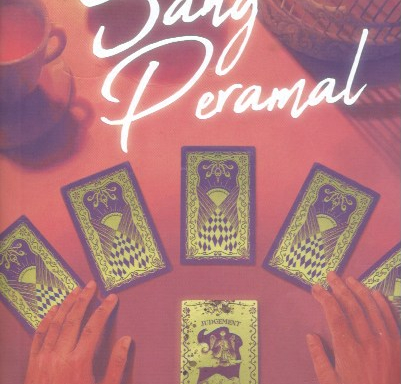Dia berlari dari Tuhan sejauh-jauh. Dia menepis keberadaan-Nya sekuat-kuat. Begitupun, dia selalu melafal-lafal Nama-Nya. Di saat ternista sekalipun, Nidah Kirani mengingat-Nya, “Tuhan, izinkan aku menjadi pelacur!”
NIDAH Kirani menjalani hidup dalam tikungan-tikungan tajam.
Dia periang dan sedikit bandel saat kanak-kanak. Dia berhenti mengaji karena tak suka ditakuti-takuti “si tua bongkok berjanggut belang-belang” tentang lidah si pendusta yang digunting; tentang kemaluan pelacur yang ditusuk tombak besi membara hingga tembus mulut; atau tentang punggung orang kikir yang disetrika di neraka.
Di bangku kuliah, Kiran membelok patah. Dia mengikuti pengajian, yang mengubahnya. Jubahnya gigantis. Jilbabnya menjuntai. Hidupnya berputar-putar di salat, zikir, dan membaca kitab suci. Dia menjadi bak “si tua bongkok”, sosok yang dibencinya dulu: tiap saat mengingatkan teman-teman kuliah dan pondoknya tentang Tuhan yang pemarah, agama yang menakutkan, dan neraka yang membakar.
Tikungan patah rupanya terus tersaji di hadapan Kiran. Dia kali ini menapaki jalan sebuah gerakan Islam bawah tanah; yang tak lagi bicara syariat dan dosa tapi politik dan kekuasaan. Kredo-kredo ditanamkan: bahwa syariat tak mungkin tegak tanpa daulah (kekuasaan); bahwa inilah saatnya kekuasaan direbut dari tangan pemerintahan kafir, demi tegaknya syariat, demi Tuhan.
Kecewa dengan para ksatria khilafah, bukan hanya tikungan patah yang Kiran alami, tapi juga iman yang berkeping-keping. Dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Tapi Sang Kekasih yang ia bela dengan raga, harta, dan jiwa selama empat tahun itu diam. Tak ada jawaban. Semua sunyi. Semua Senyap. Yang tinggal hanya gelisah.
Hilang Sang Kekasih Yang Mahakuasa, datanglah kekasih-kekasih karbitan; parade lelaki pengecut—baik dari persimpangan Kiri ataupun Kanan jalan—yang tak bertanggung jawab dan munafik. Tapi, dari tubuh, butir keringat asin, serta leleran cairan kehidupan barisan lelaki ini, Kiran menemukan kuasa. Dia merasa menaklukkan segalanya, bukan hanya Tuhan dengan segala tabu-Nya tetapi juga makhluk-Nya yang berfalus, yang mencipta citra diri dan dunia atas nama-Nya dan nama agama-Nya.
“Di atas ranjang ini, iman itu akan kutawar dengan tubuhku. Tuhan aku adalah kekasih yang Kau kecewakan. Maka Kau jangan keberatan apabila aku menguji iman lelaki ini, ustaz ini, hamba-Mu yang dipandang-pandang masyarakat sebagai orang saleh yang bersih diri ini.”
Sebuah pemberontakan dikumandangkan. Sebuah tubuh dibebaskan dari kuasa tabu dan dominasi. Sebuah perjalanan dalam dosa dihelat. Sebab, “Melalui dosa kita bisa dewasa.”
Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur! Memoar Luka Seorang Muslimah ditulis oleh Muhidin M Dahlan dalam bentuk catatan seseorang yang diceritakan kembali oleh sang narator, “aku”. Dalam “Surat Penulis: Memerkarakan Tuhan, Tubuh, dan Tabu” di bagian awal novel ini, narator mengatakan kisah ini direkam 18 jam selama sepekan, di setiap sore hingga azan Isya berkumandang.

- Judul Buku: Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur!: Memoar Luka Seorang Muslimah
- Pengarang: Muhidin M Dahlan
- Penerbit: ScriPtaManent
- Terbit: Maret 2016 (Cetakan ke-16)
- Tebal: 269 halaman
Karena ditulis dalam bentuk sebuah memoar yang dikisahkan kembali, novel ini bertutur hanya dari sudut pandang karakter utamanya, Nidah Kirani. Ia meloncati penggambaran karakter-karakter lain. Meski demikian, dari cerita Kiran, kita masih bisa sedikit membayangkan sejumlah karakter lain itu: Darul Rachim, mahasiswa aktivis Kiri yang perewa saat demonstrasi tapi pengecut setelah melukai keperempuanan Kiran; Kusywo, penyair sufistik yang fasih mengutip Iqbal, Attar, atau Rumi tapi hanya memanfaatkan kemaluan perempuan demi—dia bilang—“anak tangga menuju Sang Pecinta”; Rahmanidas Sira, lelaki yang bertekuk lutut di hadapan guagarba (kata ciptaan Muhidin yang tampaknya cukup asyik juga) Kiran hingga harus memutus hubungan dengan pacarnya yang setia; Didi Eka Tanjung, lelaki kasar nan posesif yang cuma bisa mengancam Kiran—dan pada suatu malam yang aneh memerkosanya; dan tentu saja Pratomo Adhiprasodjo, dosen cum anggota dewan dari partai Islam yang nyambi menjadi germo pelacur papan atas.
Tema novel ini sepintas bermiripan dengan karya klasik Achdiat K Mihardja, Atheis (1949). Seperti juga Hasan dalam Atheis, Kiran dalam novel ini mengalami goncangan-goncangan terhadap iman dan pandangan sosial yang terbentuk oleh keluarga dan masyarakat. Dorongan-dorongan akal terus mendesak-desak untuk menemukan jawaban rasional—pencarian yang tak pernah sampai pada titik cukup memuaskan.
Bagi Kiran, ide tentang Tuhan membingungkan. Sesuatu yang bisa jadi dirasakan banyak orang meski cuma sedikit yang mau mengakuinya. Kiran, misalnya, mempertanyakan apa perannya di dunia ini. Apa hanya sekrup yang berputar-putar pada mesin takdir Tuhan? Jika demikian, mengapa dia yang harus bertanggung jawab terhadap segala kemalangan dan tragedi yang menimpanya? Bukankah Tuhan yang mesti bertanggung jawab karena Dia sendirilah Penguasa Pemutar roda nasib?
Jawaban memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah dia temukan. Tuhan Sang Pengekang versi teolog; Tuhan Sang Pembebas versi ideolog; dan Tuhan Sang Pecinta versi penyair sufi tak pernah betul-betul meredakan kegelisahannya. Ia bahkan seringkali menghadapi sekat tabu ketika mempertanyakan hal itu. Tak boleh bertanya begitu. Kamu harus percaya. Bukankah Tuhan sendiri tak pernah benar-benar menjawabnya ketika Malaikat mempertanyakan penciptaan manusia. “Aku Maha Mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui,” cukup begitu jawab Tuhan.
Jika dilihat dari kronologi memoar ini, pertanyaan-pertanyaan kritis tentang Tuhan sebenarnya baru muncul selepas Kiran kecewa dengan organisasi pengusung negara Islam yang ia masuki. Selama berada di dalam organisasi itu, atau bahkan sebelumnya saat tenggelam dalam pengajian konservatif, Kiran tak sedikit pun memancarkan daya kritis tentang Tuhan. Dia masygul dengan organisasi khilafah itu justru karena tak menemukan semangat juang di dalamnya. Yang ia temukan malah aktivitas berleha-leha yang tak sepadan dengan misi gagah merebut kekuasaan dan mendirikan daulah. Ia juga kecewa karena perpecahan di dalamnya yang ditutup-tutupi.
Di ujung jalan ini, kekecewaan itu dia tumpahkan kepada Tuhan; Tuhan dalam citra organisasi itu. Atau Tuhan yang dia pikir dia cintai dan pahami selama ini, dan yang akhirnya dia tahu tak mengirimkan suara atau bisikan apa pun. Tuhan lindap dalam kegelisahan jiwanya.
Di tikungan yang lebih tajam, Kiran menghunjamkan kemarahan kepada Tuhan sekaligus lelaki. Baginya, Tuhan bersekongkol dengan lelaki.
Tuhan mencipta lelaki dalam citra-Nya. Lihatlah, bukankah semua nabi lelaki, katanya. Lihatlah, Tuhan menimpakan semua kesakitan dunia kepada perempuan; haid, hamil, dan melahirkan. Lihat pula, Tuhan merapal semua belenggu tabu atas perempuan. Bahkan, di surga sekalipun hanya ada bidadari sedangkan istri-istri setia bisa jadi hanya jadi babu seperti di dunia. Pada saat yang sama, lelaki menjajah perempuan dan membentuk dunia atas nama-Nya dan agama-Nya.
Dan Kiran pun menggugat cinta:
“Bagiku, cinta adalah abstraksi dari rasa ketertarikan, keterkaguman, keterpesonaan, sekaligus penasaran yang menuntut untuk dituntaskan. Penuntasan rasa ini akan dapat dilakukan melalui seks sampai penyatuan yang paling sempurna. Seks adalah titik orgasme yang tertinggi antara dua manusia. Seks, gairah, dan keterpesonaan itu lama-lama akan menjadi suatu fenomena dan seperti sebuah grafik yang mendatar lalu memuncak dan kembali mendatar. Itulah cinta. Seks itu puncak cinta.”
Baginya, cinta yang dilafal-lafalkan lelaki cuma senjata mereka untuk menguasai tubuh perempuan tanpa pertahanan apa pun dari pihak perempuan. Tapi pada seks, Kiran menemukan pula senjata pemberontakan, yang akan membalik kuasa, menelanjangi kelemahan lelaki, dan mengungkap ketololan mereka. “Ah, lelaki, kalian begitu kelihatan tegar ketika masih berpakaian, tapi ketika pakaian kalian lepas, terkuak juga kelemahannya, ketololannya.”
Dengan seks, Kiran merasa berkuasa atas tubuhnya. Dengan seks, dia mempertahankan harga diri—ya dengan mengendalikan harga untuk bersetubuh dengannya.
Menurutnya, pernikahan sama saja dengan pelacuran. Pernikahan adalah persetubuhan yang dihargai dalam bentuk mahar demi harga diri si wanita. Perbedaannya, pernikahan difasilitasi tradisi dan dibirokrasikan dalam catatan sipil. Tapi, dalam pelacuran, perbedaan ini terkompensasi. Dia tak harus dirumahkan dan dipaksa menikmati seks dengan lelaki yang itu-itu saja. “Seks akan tetap bernama seks meski dilakukan dengan satu atau banyak orang.”
Juga dengan seks, Kiran merasa dia mengambil alih kuasa dari Tuhan. Sebab, seks adalah satu belenggu tabu paling hina di dalam agama-Nya. Sebab, tubuh perempuan adalah aib untuk dipertontonkan. Darah kotornya saat datang bulan dianggap najis yang mesti dijauhkan dari kitab suci dan tempat ibadah.
Tapi tampaknya Tuhan tak pernah benar-benar bisa hilang dari memori dan kesadaran manusia. Dia disebut-sebut dalam doa tapi juga dikenang-kenang dalam dosa. Novel ini tampak berkisah tentang pemberontakan kepada Tuhan tapi sebenarnya pencarian tentang-Nya di saat-saat dan tempat-tempat paling lata sekalipun. Tuhan mungkin akan berkata, “Aku tak terhindarkan.”
Dan lihatlah Nidah Kirani! Sejauh apa pun berlari dari Tuhan, sekuat apa pun menepis keberadaan-Nya, dia selalu melafal-lafalkan nama-Nya. Bahkan di saat-saat paling nista sekalipun, dia tetap mengingat-Nya, “Tuhan, izinkan aku menjadi pelacur!”[]