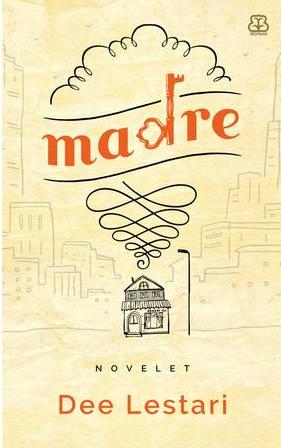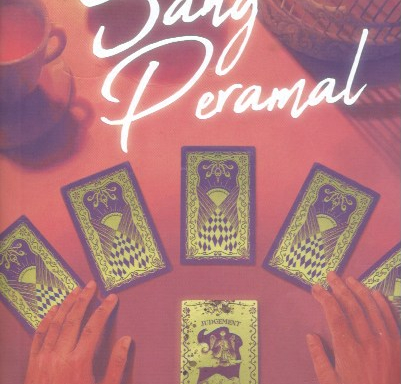Makanan memiliki banyak lapisan narasi, dan tiap lapisan punya kisahnya masing-masing. Dalam Madre, Dewi “Dee” Lestari menyajikan banyak dimensi dari adonan biang roti, utamanya tentang makanan sebagai relasi, yang menghubungkan manusia dengan manusia, dan manusia dengan momen.
DEWI “Dee” Lestari salah satu pengarang Indonesia yang menggarap fiksi berlatar budaya makanan—atau yang secara sempit disebut fiksi kuliner (kuliner lebih berhubungan dengan tradisi mengolah, menyajikan, dan menikmati makanan). Dee setidaknya sudah menghasilkan dua novelet dengan latar ini, yaitu Filosofi Kopi (2005) dan Madre (2011).
David Baker, pengarang Vintage—novel tentang pencarian sebotol anggur terkenal oleh seorang jurnalis kuliner—pernah mengatakan bahwa makanan memiliki banyak lapisan narasi, dan tiap lapisan memiliki kisahnya masing-masing yang bisa dikembangkan. “Ia kisah tentang budaya yang menciptakannya, tentang orang yang membuatnya, tentang bahan-bahannya dan dari mana semua itu berasal, tentang proses pembuatannya—baik sukses maupun gagal—dan tentang menikmatinya bersama-sama.”
Kita pernah mendengar petitih, “kita adalah apa yang kita makan”. Petitih ini bukan hanya soal, “jika anda makan babi, maka anda seperti babi”. Ia lebih daripada itu. Ia menggambarkan bahwa makanan adalah cermin kita; manusia. Cermin itu merefleksikan banyak hal tentang manusia: estetika, etika, histori, sains, politik, dan bahkan kesadaran-diri. Itulah kenapa dalam sejarah manusia, banyak “orang lain” (maksudnya bukan mereka yang bekecimpung secara khusus dalam makanan, seperti artisan, koki atau ahli nutrisi) berbicara tentang makanan. Nabi Muhammad berbicara tentang makanan. Begitu pun para filsuf seperti Aristoteles atau John Calvin dan bahkan politisi seperti Alexander The Great dan fisikawan peraih Nobel Niels Gustav Dalen.
Dalam Madre, Dee menyajikan banyak dimensi dari sebuah adonan biang, atau yang disebut juga dalam dunia perotian dengan sourdough—sejenis ragi yang dibiarkan berkembang secara alamiah bertahun-tahun lamanya. Dee secara cerdas menggunakan kata madre untuk menamai adonan biang tersebut. Kata ini berasal dari rumpun bahasa Romawi yang berarti ‘ibu’. Madre bukan hanya biang yang menghasilkan roti demi roti bagi Tan de Bakker, toko roti kuno milik Tan Sin Gie, tapi juga menghidupi banyak orang dan kemudian menjadi petunjuk genealogis bagi Tansen Roy Wuisan serta merefleksikan kecintaan kepada tradisi—dan bukankah memang begitu peran ibu: nukleus dari sebuah kehidupan.
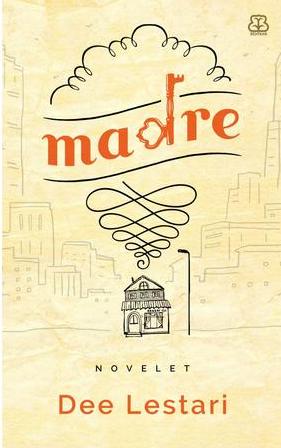
- Judul Buku: Madre
- Pengarang: Dee Lestari
- Penerbit: Bentang Pustaka
- Terbit: Juni, 2015
- Tebal: 51 halaman
Di bagian awal, novelet ini menununjukkan bagaimana Madre membawa Tansen kepada kenyataan dia keturunan separuh Tionghoa—sesuatu yang tak pernah dia bayangkan. Madre satu-satunya memori yang menghubungkan Tansen dengan Tan. Tak ada cerita neneknya, Lakshmi, dan ibunya, Kartika, tentang lelaki Tionghoa itu. Tak ada foto. Bahkan tak ada dokumen resmi seperti akta nikah atau kelahiran. Lebih dari itu, Madre adalah kultur roti yang menyimpan cerita rahasia cinta yang dipaksa tunduk pada pandangan sosial saat itu; bahwa Tan, seorang Tionghoa, tak mungkin menikah dengan Lakshmi, seorang India.
Di sini, Dee berbicara tentang makanan sebagai sebuah relasi, yang menghubungkan manusia dengan manusia dan manusia dengan momen. Kadang kita merindukan sesuatu atau seseorang saat menyantap suatu makanan. Kita merindukan seseorang yang pernah memasaknya atau dapur tempat makanan itu diolah—dengan berbagai aroma dan perkakas di dalamnya.
Madre membawa Tansen—dan pembaca—kembali kepada momen saat orang membuat roti dengan menciptakan kultur alami, yang menjadikan roti lebih renyah, wangi, berongga-rongga, serta berasa sedikit asam dan asin (dan bahkan menurut ahli nutrisi sourdough membuat roti lebih ramah bagi pencernaan dan bebas gluten). Momen ini kini berada di horizon kepunahan karena desakan industri pemburu profit. Dengan mantra “supply and demand”, industri memproduksi roti dengan ragi instan berbahan kimia. Karena nyaris punah, tradisi roti dengan adonan biang kini dianggap “klasik”, dan tentu saja berharga lebih mahal serta hanya bisa dinikmati kelas tertentu—dan sayangnya Dee pada akhirnya tetap tak bisa membebaskan Madre dari mantra “supply and demand”.
Relasi dengan momen juga bisa dibaca pada penantian panjang Pak Hadi dan kawan-kawannya sesama pekerja Tan de Bakker akan seorang keturunan Tan Sin Gie yang akan mengaktifkan kembali Madre dan menghidupkan toko roti itu. Penantian yang lahir dari kecintaan kepada tradisi dan nilai sejarah yang dikandungnya. Selama itu, mereka tetap menyimpan Madre hingga “sang juru selamat” itu datang. Mereka bahkan tak sependapat dengan Tansen ketika “sang messiah” ini malah hendak menjual Madre kepada Mei seharga 100 juta rupiah. Generasi milenial seperti Tansen digambarkan sulit menerima penghormatan kepada tradisi, terkecuali setelah memahami nilai momen tersebut bagi Pak Hadi dan kawan-kawan sezamannya. Dan Mei—yang seumuran dengan Tansen—memahami nilai itu juga karena terbuhul dengan momen ketika dia memecahkan stoples persedian adonan biang yang tersisa milik kakeknya.
Di sini, novelet ini dengan baik menggambarkan jurang antargenerasi itu. Dan Madre mempertemukan mereka semua pada satu momen di masa kini.
Dee menggarap novelet ini dengan baik. Dia menciptakan plot-plot yang kuat terhubung dengan tema dan pesan yang ingin disampaikan. Dia juga piawai melukis karakter tokoh-tokoh utamanya, yakni Tansen, Mei, dan Pak Hadi.
Sayangnya, Madre pada akhirnya tetap tak kuasa membendung desakan kapitalisasi dan industrialisasi Fairy Bread milik Mei. Pola kerja sama bisnis antara Tansen dan Mei tampak menjadi solusi dan akhir manis dari kisah ini—setelah sebelumnya Tansen merasa tak sanggup memenuhi demand dari Fairy Bread. Tapi industrialisasi—dengan kecenderungan kuat memburu profit berlipat-lipat—tetap punya potensi menggerus orisinalitas tradisi. Terlebih, bukankah Madre butuh waktu untuk bisa hidup dan berkembang baik?
Saya teringat dengan kisah Tante Oco, penjual Milu Siram yang laris di Gorontalo, dalam video dokumenter “Gorontalo Baik” produksi Watchdoc. Meskipun laris, Oco bertahan hanya mau memproduksi 70 bungkus per hari (dan sudah habis menjelang siang). Dia tak mau menambah modal untuk meningkatkan produksi dan membuka cabang. Kita bisa mengatakan Oco bodoh, tak menyadari potensi bisnisnya. Tapi bagi Oco dan keluarga yang mewarisi resep ini turun temurun, pada akhirnya, ekonomi tak harus mengejar keuntungan berlipat-lipat. Ia pada dasarnya usaha manusia memenuhi kebutuhan, bukan memburu profit.[]