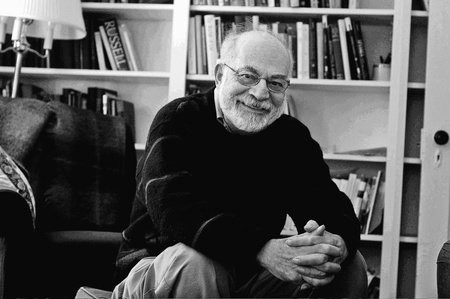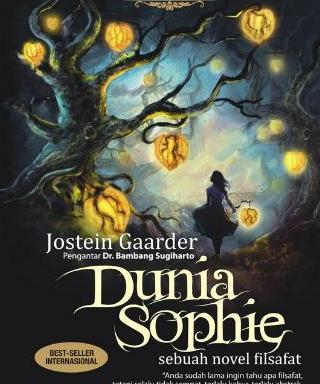Sebuah aliran mistisisme Islam yang berkembang pada Abad ke-17 ternyata mampu menjawab gugatan yang dihadirkan revolusi fisika kuantum terhadap sains modern. Aliran itu berdasarkan pengalaman mistis tapi sekaligus bersifat filosofis-rasional. Ia dijabarkan secara diskursif-logis tapi juga bersifat spiritual. Dalam Epistemologi Tasawuf: Sebuah Pengantar, Haidar memaparkan pandangan epistemologi aliran ini.
Bagaimanakah kita memperoleh pengetahuan? Bagaimanakah cara kita menguji kebenaran tentang apa yang kita pikir kita ketahui?
Pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan topik perenial para filsuf sejak sebelum era Plato terkait teori pengetahuan atau epistemologi.
Pada Abad ke-17, seorang filsuf-matematikawan Perancis, Rene Descartes (1596-1650), berupaya menemukan satu prinsip yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Seperti diceritakannya dalam Discourse on the Method of Rightly Conducting One’s Reason and Searching the Truth in the Sciences, dia memulai upaya itu dengan meragukan semua hal, bahkan termasuk apa pun yang dirasakan pancaindra.
Descartes, misalnya, menyatakan apa yang dia rasakan dalam keadaan terbangun dapat juga dia alami saat tertidur. “Objek yang pernah memasuki pikiranku saat terbangun, tidaklah memiliki di dalamnya kebenaran melebihi ilusi dari mimpiku.”1Rene Descartes. 1909. Discourse on the Method of Rightly Conducting One’s Reason and Searching the Truth in the Sciences. New York: P.F. Collier & Son
Ujung- ujungnya, Descartes menyadari bahwa dia tak mungkin bisa meragukan keragu-raguannya sendiri: pikirannya. Dia kemudian membangun sistem filsafatnya di atas kesadaran tersebut: cogito ergo sum (aku berpikir maka aku ada).
Penemuan filosfis tersebut melahirkan apa yang dinamakan “dualisme Cartesian”, yakni pemisahan ekstrem antara “sesuatu yang berpikir” (res cogitans) dengan “sesuatu yang tak berpikir” (res extensa). Bagi Descartes, res cogitans (pikiran) adalah sumber segala pengetahuan sementara res extensa (materi) hanyalah representasi dari aktivitas berpikir.
Dualisme Cartesian memicu perubahan besar dalam pandangan dunia Barat–sesuatu yang bisa jadi tak disadari Descartes sendiri. Era inilah–dan era seratus tahun berikutnya–yang disebut-sebut sebagai Age of Reason, Age of Enlightment, Abad Pencerahan. Meskipun garis waktunya bisa diperdebatkan, era ini pula yang menyaksikan apa yang disebut sebagai Scientific Revolution.
Pandangan dunia Barat mengalami perubahan besar, bergerak meninggalkan spiritualisme, esoterisme, dan mistisisme menuju humanisme, pandangan tempat manusia didudukkan sebagai pusat pengalaman dan pengetahuan. Melalui pengamatan indrawi yang digenapi dengan abstraksi logis pikirannya, manusia diyakini bisa memahami dan mengendalikan alam semesta.
Dualisme Cartesian pada gilirannya memprovokasi reduksionisme di lapangan sains. Materi sebagai objek tanpa kesadaran dipercaya baru bisa dijelaskan dengan mencacahnya menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah-pisah, dan bukan sebagai suatu keseluruhan, keutuhan. Descartes sendiri menyebut tubuh manusia tak ubahnya jam, atau tak lebih daripada sekadar otomat.
Perkembangan Scientific Revolution berpuncak pada penekanan kepada metode ilmiah (scientific method) sebagai satu-satunya model valid dalam memperoleh pengetahuan dan memverifikasi apa yang kita pikir kita ketahui. Metode ilmiah pada kenyataannya berdasarkan atas dua proses penalaran: induksi empiris (penarikan kesimpulan dari serangkaian data observasi indrawi) kemudian deduksi rasional (penarikan kesimpulan dari serangkaian premis atau argumen). Hasilnya diuji melalui seperangkat alat verifikasi, seperti koherensi (hubungan logis antarunsur dalam suatu argumen) dan korespondensi (kesesuaian argumen dengan kenyataan empiris).
Pada awal Abad ke-20, atau tiga ratus tahun setelahnya, perkembangan fisika menghadirkan problem besar bagi pandangan dunia Barat tersebut. Fisikawan-fisikawan terdepan, seperti Werner Heisenberg (1901-1976) dan Erwin Schrodinger (1887-1961) menemukan bahwa konsepsi dan bahasa sains modern tak cukup mampu menjelaskan fenomena yang dihadirkan penyelidikan mendalam atas partikel-partikel atom dan sub-atom (fisika kuantum).
Dalam tulisan-tulisan mereka, keduanya mengindikasikan bahwa ada relasi kuat antara substansi filosofis fisika kuantum dengan pengalaman-pengalaman mistik yang diungkap dalam tradisi agama dan filsafat klasik, terutama yang masih berkembang di Timur. Yakni, bahwa realitas pada dasarnya adalah keutuhan dan keseluruhan (wholeness) dan adalah keliru memahaminya dengan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil.
Fisikawan lain, Fritjof Capra, menjelaskan fenomena titik balik tersebut secara lebih populer. Dalam The Turning Point: Science, Society, and The Rising Culture, Capra menunjukkan bahwa, dalam fisika kuantum, realitas begitu sangat terkoneksi dan mempengaruhi satu sama lain. Bahkan dia mengatakan, partikel atom dan subatom itu pada akhirnya adalah energi bukan materi.
“Partikel-partikel subatomik bukanlah ‘sesuatu’ tapi interkoneksi antara ‘sesuatu’, dan ‘sesuatu-sesuatu’ ini pada gilirannya adalah interkoneksi antara ‘sesuatu-sesuatu’ yang lain, dan begitu seterusnya. Dalam teori kuantum, kamu tidak berakhir dengan ‘sesuatu’; kamu selalu berurusan dengan interkoneksi.”2Fritjof Capra. 1982. The Turning: Science, Society, and The Rising Culture. Toronto: Bantam Books. Hal. 80
Dalam ranah epistemologi, salah satu tantangan paling keras bagi sains modern datang dari Paul Feyerabend (1924-1994). Dia menolak adanya satu metode baku-universal dalam perolehan pengetahuan. Feyerabend menunjukkan bahwa kesuksesan sains modern bukanlah semata berkat metode ilmiah, tapi karena sains meminjam pengetahuan lama dari sumber-sumber non-ilmiah.
Dia menyatakan bahwa Revolusi Nicolaus Copernicus sangat dipengaruhi oleh Pytaghoras, yang pandangan-pandangannya sarat dengan elemen mistis. Tulisan-tulisan esoterik yang dirujuk kepada figur Hermes Trismegistus juga disebut berperan penting dalam karya-karya era Scientific Revolution, seperti Copernicus atau Isaac Newton.
Bagi Feyerabend, ide tentang satu metode baku-universal tidaklah realistik dan bahkan akan menghambat perkembangan pengetahuan itu sendiri. Dia mengajukan pendekatan “anything goes” terhadap metodologi atau yang dia sebut sebagai “anarkisme epistemologis”.
Persoalannya kemudian, apakah titik balik ini merupakan bandul yang berayun ekstrem ke arah lain: mencampakkan pemikiran rasional. Lalu, apakah mistisisme niscaya tak mungkin diverifikasi dengan metode ilmiah atau dibuktikan secara diskursif-logis?
Itulah persoalan yang coba dijawab Haidar Bagir dalam Epistemologi Tasawuf: Sebuah Pengantar. Menurut Haidar, dalam Islam, sebenarnya berkembang mistisisme yang berupaya mendeskripsikan dirinya dalam bahasa filsafat-rasional, seperti yang dikembangkan oleh Ibn Arabi (1165-1240) dan Suhrawardi (1154-1191). Tapi, sifat kognitif-rasional dan deskripsi diskursif-logis baru menjadi bagian tak terpisahkan pada aliran Hikmah Transenden (Al-Hikmah Al-Muta’aliyah) yang dikembangkan Mulla Shadra (1572-1640).

- Judul: Epistemologi Tasawuf: Sebuah Pengantar
- Penulis: Haidar Bagir
- Penerbit: Penerbit Mizan
- Tahun Terbit: 2017
- Tebal: 183 halaman
Epistemologi Tasawuf sebenarnya bagian dari disertasi doktoral Haidar di Program Studi Filsafat Universitas Indonesia. Disertasi itu berjudul “Pengalaman Mistis dalam Epistemologi Mulla Shadra dan Perbandingannya dengan Gagasan Heidegger tentang Berpikir (Denken).” Jadi, disertasi Haidar membahas dan membandingkan dua pemikiran epistemologi, yakni Mulla Sahdra dan Martin Heidegger, filsuf eksistensialis Barat paling berpengaruh pada Abad ke-20.
Namun, Haidar lebih memilih menerbitkan bagian pemikiran Shadra menjadi buku dengan tiga alasan: (1) topik epistemologi Shadra lebih dekat dengan spesialisasi Haidar dalam filsafat Islam; (2) buku tentang topik itu dalam bahasa Indonesia belum cukup tersedia, terutama dalam gaya penulisan populer; dan (3) topik tersebut lebih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ketimbang bagian tentang pemikiran Heidegger.
Walhasil, buku ini lahir dari setidaknya dua proses. Pertama, seleksi atas bagian dari disertasi. Kedua, revisi teknis penulisan dan kebahasaan untuk membuatnya sedikit lebih populer agar bisa dipahami peminat umum, dan bukan hanya peneliti filsafat.
Upaya pemopuleran tersebut tampaknya cukup berhasil. Hingga separuh buku, Epistemologi Tasawuf mulus menjelaskan perjalanan epistemologi dari kecenderungan rasionalisme pada Abad ke-17 hingga titik baliknya ke mistisisme pada Abad ke-20 dan bagaimana perkembangan mistisisme dalam filsafat Islam.
Namun, pembaca mulai bakal mengernyitkan dahi begitu memasuki bagian inti dari buku ini, yakni ketika Haidar mencoba menjelaskan apa itu pengetahuan presensial (ilmu hudhuri), konsep dasar epistemologi Shadra. Untungnya, Haidar menyertakan definisi sejumlah istilah teknis, baik dalam ranah ilmu-ilmu rasional maupun mistisisme Islam pada bagian awal buku. Glosarium itu cukup bisa membantu pembaca memahami penjelasannya di bagian akhir.
Seperti telah disebutkan, ada dua pertanyaan penting dalam epistemologi, yakni bagaimana pengetahuan diperoleh (context of discovery) dan bagaimana pengetahuan itu dinilai kebenarannya (context of justification). Namun, sebagaimana dipaparkan Haidar di beberapa bagian buku, pengalaman mistis berbeda dengan pengetahuan ilmiah-rasional. Yang pertama tak mesti menjelaskan context of discovery-nya.
Ahli filsafat sains Hans Reichenbach (1891-1953) memandang bahwa context of discovery sendiri sebenarnya bukanlah bagian penting dalam epistemologi. Reichenbach mencontohkan bagaimana ahli kimia Friedrich August Kekule menemukan formula cincin dari molekul benzene setelah mendapatkan visi dari mimpi di siang bolong tentang seekor ular yang mencengkeram ekornya sendiri.
Menurut Reichenbach, cukuplah bagi pengetahuan untuk lulus dari context of justification ketika ia dideskripsikan.
Seperti telah disinggung, ada tiga aliran mistisisme Islam yang mencoba mendeskripsikan dirinya ke dalam bahasa filosofis-rasional dan diuji context of justification-nya. Yaitu, irfan atau gnostisisme Ibn Arabi, iluminisme atau isyraqiyyah Suhrawardi, dan Hikmah Transenden Mulla Shadra. Meskipun memusatkan pembahasannya pada aliran terakhir, buku ini tetap menjelaskan dua aliran pertama
Dari penjelasan Haidar mengenai ketiga aliran tersebut, tampak bahwa ketiganya tak memiliki perbedaan prinsipiel, baik dalam ontologi maupun epistemologi, meskipun bervariasi dalam cara pendeskripsian. Ketiga aliran ini menunjukkan perkembangan filsafat Islam yang berkarakter mistis dalam pencapaian pengetahuan sekaligus diskursif-logis dalam pengungkapan. Perkembangan itu berpuncak pada Hikmah Transenden Mulla Shadra.
Shadra tak hanya menyintesiskan dua aliran sebelumnya–dan juga filsafat peripatetik Ibn Sina–tapi juga membawa sintesis itu ke level yang belum pernah dicapai filsuf-filsuf sebelumnya. Ahli fisafat Islam asal Jepang, Toshihiko Izutsu, misalnya, menyebut Hikmah Transenden sebagai “sesuatu yang didasarkan pada pengalaman transintelektual dan gnostik” sekaligus “sistem rasional yang solid”. Hikmah Transenden bukan hanya menjadi bukti masih dinamisnya filsafat Islam setelah Ibn Rusyd tapi juga menjadi filsafat Islam yang dapat berdialog dengan pemikiran Barat.
Jauh sebelum Descartes lahir, Shadra, misalnya, telah menyadari persoalan yang ada dalam postulat seperti cogito ergo sum. Filsuf-mistikus kelahiran Syiraz, Provinsi Fars, Iran, itu mengatakan, “Jika saya berupaya untuk membuktikan diri saya melalui tindakan saya, maka tak mungkin saya dapat mengetahui tindakan saya kecuali setelah saya mengetahui diri saya. Andai saya tidak dapat mengetahui diri saya kecuali setelah mengetahui diri saya, niscaya hal ini berujung kepada regresi tanpa akhir (tasalsul).”
Penjelasan itu menunjukkan bahwa pikiran atau keraguan bukanlah bukti keberadaan “diri saya”. Sebab, penisbatan pikiran (atau apa pun yang dipersepsi pikiran) kepada “saya” selalu mempraanggapkan adanya kesadaran-dasar tentang diri saya. Jadi, diri sayalah yang mengaitkan pikiran dengan diri saya, dan bukan sebaliknya.
Itulah prinsip epistemologi Shadra (dan juga Ibn Arabi dan Suhrawardi). Yakni, kesatuan subjek-objek pengetahuan dalam apa yang disebut wujud, ‘ada’. Prinsip ini sebenarnya bertitik tolak pada prinsip pertama ontologi Shadra, ashalah al-wujud atau fundamentalitas eksistensi atas esensi (ashalah al-mahiyah).
Pengetahuan tentang objek hadir begitu saja dalam subjek. Subjek tak membutuhkan representasi atau perantara untuk mengetahui objek. Inilah yang kemudian dikenal dengan ilmu hudhuri atau pengetahuan presensial.
Prinsip tersebut juga bisa dilacak kepada ontologi Ibn Arabi yang termasyhur: wahdatul wujud atau ketunggalan wujud. Bagi Ibn Arabi, wujud tak hanya berarti ‘ada’ tetapi juga ‘menemukan’ (akar kata w-j-d dalam bahasa Arab memang memiliki makna ‘menemukan’). Itu berarti wujud bersifat sadar-diri, yakni menemukan (menyadari, mengetahui) akan dirinya tanpa perantara apa pun. Ia ‘berada’ sekaligus ‘menyadari’ keberadaannya.
Selain itu, Shadra menyebut jenis pengetahuan lain. Pengetahuan ini mengambil bentuk yang di dalamnya “ada-nya” pengetahuan dan objek yang diketahui merupakan dua satuan berbeda. Dia mengistilahkan ini sebagai pengetahuan capaian atau ilmu hushuli. Dalam pengetahuan ini, subjek membutuhkan representasi atau perantara untuk mengetahui objek.
Meskipun demikian, Shadra tetap menyakni bahwa ilmu hudhuri atau pengetahuan presensial sebagai sumber pengetahuan yang utama, dan bahkan satu-satunya. Ilmu hushuli atau pengetahuan representasional tadi hanyalah kesan permukaan (prima facie) manusia saat memperoleh pengetahuan.
Pengetahuan representasional (ilmu hushuli) melibatkan ‘objek ganda’, yakni objek subjektif (objek yang berada di dalam subjek lewat representasi forma atau konsep mental) dan objek objektif (objek yang berada di luar subjek). Yang pertama disebut objek imanen, yakni yang hadir dalam pikiran subjek, sedangkan yang kedua disebut objek transitif, yakni yang realitasnya terpisah dari realitas di pikiran subjek. Pengetahuan diperoleh ketika objek subjektif merepresentasikan objek objektif lewat forma atau konsep di dalam pikiran subjek.
Menurut Shadra, proses seperti itu bukanlah perolehan pengetahuan yang utama sebab kebutuhan ilmu hushuli kepada perantaraan konsep meniscayakan kebutuhan konsep itu kepada perantaraan konsep lain, dan demikianlah seterusnya sehingga menciptakan regresi tanpa akhir. Oleh karena itu, seluruh pengetahuan manusia pada dasarnya diperoleh secara langsung atau hadir (presensial atau hudhuri).
Objek subjektif yang ada dalam pikiran subjek pengetahuan, bagi Shadra, adalah wujud atau eksistensi yang tak membutuhkan representasi forma atau konsep. Dia hadir sebagai eksistensi mental (wujud dzihni).
Di sinilah, kita mulai memasuki prinsip kedua ontologi Shadra, yakni tasykik al-wujud atau gradasi eksistensi. Eksistensi mental tersebut termasuk ke dalam salah satu dari gradasi tersebut, sebagaimana juga eksistensi materialnya di luar subjek.
Konsep tersebut diwarisi–dan kemudian disempurnakan–Shadra dari filsafat iluminasi Suhrawardi tentang wujud sebagai cahaya–dan lebih jauh dari filsafat paripatetik Ibn Sina tentang emanasi. Pada dasarnya, Wujud Utama atau Realitas Tunggal niscaya menyadari potensi yang tak terbatas dari Diri-Nya untuk tampil dalam modus-modus untuk ditemukan (maujud). Dari sinilah lahir secara niscaya gradasi atau tingkatan eksistensi sebab Yang Tunggal tak mungkin menghasilkan yang banyak. Jadi, yang terjadi bukanlah pembelahan Yang Tunggal tapi peluberan atau emanasi berupa modus-modus pengungkapan Diri-Nya.
Karena hasil emanasi, maka realitas saling terhubung (interkonektif), sinambung (kontinu), dan bergantung kepada Realitas Tunggal. Begitulah prinsip itu bekerja jika dilihat dari sisi emanasi atau tangga menurun. Jika dilihat dari sisi absorpsi atau tangga menaik, prinsip yang sama juga terjadi.
Karena pengetahuan Wujud Utama tentang realitas-realitas hasil emanasinya mengambil bentuk pengetahuan presensial (ilmu hudhuri), maka demikian juga pengetahuan realitas-realitas itu tentang Wujud Utama. Haidar menjelaskan, keidentikan emanasi dan absorpsi ini mengimplikasikan bahwa, bukan saja Tuhan mengetahui segala sesuatu mengenai emanasinya, maujud-maujud emanasinya pada dasarnya juga mengetahui pengetahuan ketuhanan. Inilah makna dari Hadis Nabi Muhammad, “Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya.”
Oleh karena itu, bagi Shadra, pengetahuan presensial adalah pengetahuan ketuhanan. Di sinilah, pengalaman mistik mesti ditempatkan.
Pengetahuan seperti itu, dalam epistemologi Hikmah Transenden, hanya bisa diperoleh melalui intusi atau iluminasi (dzauq atau isyraq), dan bukan lewat pengalaman indrawi ataupun penalaran rasio. Shadra percaya intuisi mengatasi penalaran dan pengalaman.
Walhasil, dalam sistem filsafatnya, mengetahui adalah sama dengan mengada. Pengetahuan manusia adalah modus eksistensinya. Semakin tinggi cara perolehan pengetahuan manusia, maka eksistensinya kian mendaki mendekati Wujud Utama.
Itulah prinsip ketiga Hikmah Transenden, al-harakah al-jauhariyyah atau gerak substansi. Agar pengalaman mistik tersingkap dan gerak substansi terjadi, Shadra mengatakan manusia harus menjalani disiplin penyucian jiwa dan penyempurnaan akhlak melalui pelaksanaan syariat.
Namun, pada saat yang sama, Shadra tetap percaya bahwa pengalaman mistik (yang diperoleh dengan ilmu hudhuri) harus diungkapkan dalam bangunan argumentasi diskursif-logis. “Sebab, sekadar penyingkapan (spiritual) saja–tanpa demonstrasi (logis)–tidaklah cukup dalam/bagi perjalanan spiritual, sebagaimana sekadar diskusi (logis) tanpa penyingkapan (spiritual) adalah ketaksempurnaan besar dalam perjalanan spiritual,” katanya.[]
(Foto utama: bagian dalam rumah tua di Kahak, sebuah desa dekat Qom, Iran, yang ditinggali Mulla Shadra saat diasingkan karena pemikiran-pemikirannya. Sumber foto: Wikipedia.org)