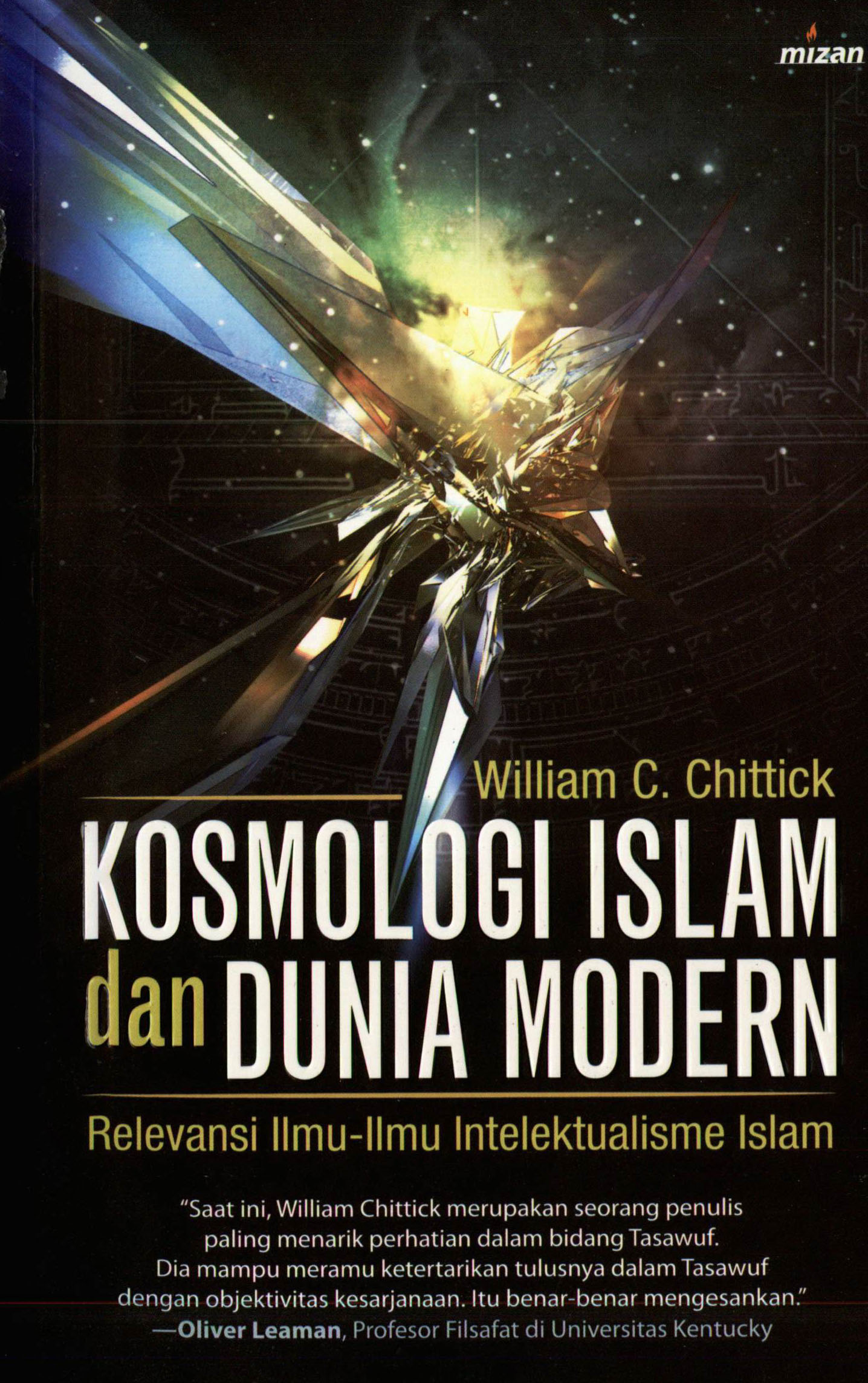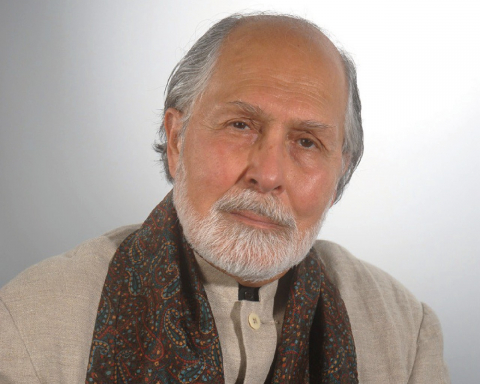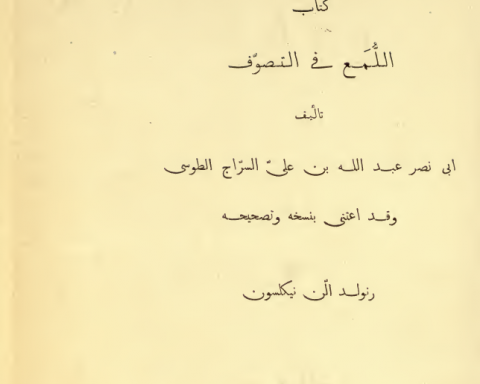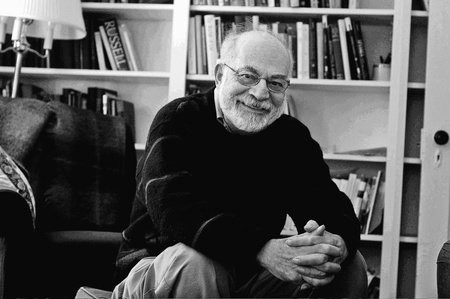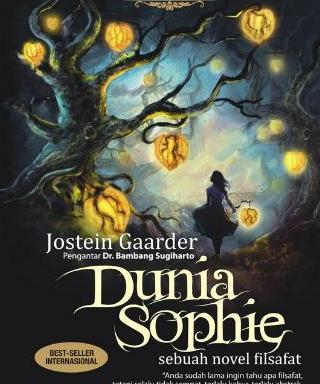Dalam Kosmologi Islam, William Chittick mengungkap bahwa sains tentang alam selalu berdampingan erat dengan sains tentang jiwa dalam pemikiran Islam. Itulah kenapa filsafat dan tasawuf bak dua sisi dari koin yang sama dalam Islam. Tapi sayangnya, dua sejoli pengetahuan ini kini banyak ditinggalkan kaum terdidik dan pranata pendidikan di dunia Islam. Chittick menyebutnya telah mati suri selama satu abad.
Bagi peminat Rumi dan Ibn Arabi, nama William C Chittick tentu sudah tidak asing lagi. Peneliti kelahiran Connecticut, Amerika Serikat, pada 1943 ini telah menulis banyak buku tentang kedua sufi besar tersebut. Yang paling terkenal di antara karya-karya tersebut adalah The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi dan The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-’Arabi’s Metaphysics of Imagination serta Imaginal Worlds: Ibn al-’Arabi and the Problem of Religious Diversity.
Menurut pengakuannya sendiri, Chittick mulai mempelajari pemikiran Islam pada 1965. Dia tertarik pada bidang ini melalui serangkaian kebetulan yang membawanya menghabiskan masa kuliah di Universitas Amerika di Beirut, Lebanon. Beruntung dia cepat menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih daripada sekadar pengetahuan permukaan seputar topik-topik ini adalah dengan mempelajari bahasa Arab dan Persia.
Kesadaran inilah yang pada 1974 membawanya ke Iran, persisnya ke Universitas Tehran. Di sana, dia berguru dari para sarjana orisinal Islam seperti Seyyed Hussein Nasr. Di kampus ini, dia mempelajari sastra Persia dan ilmu-ilmu intelektual Islam pada umumnya. Di sini pula dia akhirnya bertemu dengan Sachiko Murata, yang lalu menjadi soulmate-nya hingga sekarang, dan kelak pada 1994 menulis bersama sebuah karya empatik berjudul The Vision of Islam (New York: Paragon).
Setelah puluhan tahun mempelajari karya-karya klasik, menerjemahkan berpuluh-puluh pasase dari karya-karya tersebut dan melakukan riset kepustakaan, Chittick mulai menerbitkan hasil-hasil eksplorasinya dalam sejumlah buku. Perhatian utamanya dari awal adalah berusaha memahami apa yang dikatakan oleh kaum sufi dan para filsuf Muslim. Berbeda dengan kebanyakan sarjana Barat yang kerap memaksakan pandangan, dia lebih suka mengamati bagaimana realitas tampak pada sufi dan filsuf Muslim itu.
Dalam belasan karya itu, Chittick terpengaruh dengan pola para sarjana yang menekuni spiritualisme Islam Persia seperti Henry Corbin dan Toshihiko Isutzu: membiarkan para sufi dan ahli hikmah itu berbicara. Maka, dalam banyak karya para sarjana yang dididik dalam tradisi spiritualisme Islam Persia itu, Anda akan langsung diajak berkenalan dengan Rumi, Ibn Arabi, Shadruddin Qunawi, Abdurrahman Jami, Afdhaluddin Kasyani, Syams-i Tabrizi, Mulla Shadra, dan yang lainnya melalui karya-karya mereka sendiri. Sementara kita diminta duduk bersama layaknya audiens mendengarkan mereka bertutur.
Akan tetapi, dalam beberapa tahun silam, akibat pelbagai krisis yang melanda dunia, Chittick merasa ingin membawa wawasan yang telah dia serap dari bahan-bahan orisinal itu ke dalam konteks kekinian. Lebih daripada itu, mengingat keseriusan mendalam para penulis Islam klasik itu, Chittick merasa terdorong untuk mendedahkan pentingnya perspektif mereka secara khusus dalam konteks modern, seperti untuk menjawab peran sains dalam semangat zaman sekarang ini. Upaya menemukan relevansi kekinian itulah yang menjadi benang merah esai-esai dalam buku Kosmologi Islam dan Dunia Modern: Relevansi Ilmu-ilmu Intelektualisme Islam (diterjemahkan dari judul asli Science of the Cosmos, Science of the Soul: The Pertinence of Islamic Cosmology in the Modern World).

- Judul: Kosmologi Islam dan Dunia Modern: Relevansi Ilmu-Ilmu Intelektualisme Islam
- Penulis: William C Chittick
- Penerbit: Mizan
- Tahun: 2010
- Tebal: 216 halaman
Sebagian besar isi Kosmologi Islam merupakan implikasi dari perbedaan antara dua modus pengetahuan yang bersifat mendasar dalam agama-agama besar dengan beragam nomenklatur. Sialnya, perbedaan itu justru kerap diabaikan dalam perbincangan seputar isu-isu kontemporer. Sumber-sumber Islam klasik mengutarakan perbedaan itu dalam beragam cara. Tapi di buku ini, Chittick hanya berfokus pada perbedaan standar antara “ilmu nakliah” (naqlî)1Transmitted knowledge bisa diterjemahkan menjadi “pengetahuan nukilan” karena substansi pengetahuan nakliah bersandar pada teks al-Quran, Hadis, atau perkataan-perkataan para pengajarnya. Artinya ia adalah pengetahuan yang didapat dengan cara menukil teks-teks keagamaan tersebut dan “ilmu akliah” (‘aqly/intellectual).
Ilmu nakliah, tulis Chittick, dicirikan oleh fakta bahwa ia harus diteruskan/ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lain. Satu-satunya cara yang mungkin untuk mempelajarinya adalah dengan menerimanya dari orang lain. Sebaliknya, pengetahuan akliah tidak bisa ditransmisikan, sekalipun tetap saja seorang guru dibutuhkan guna membimbing penuntutnya ke arah yang benar.
Namun demikian, kata Chittick, cara menuntut ilmu akliah tidak bisa tidak harus dengan menemukannya dalam diri sendiri dengan latihan pikiran, atau sebagaimana yang disebutkan dalam banyak teks klasik, dengan “menjernihkan kalbu”. Tanpa menguak pengetahuan itu dari dalam diri sendiri, tulis Chittick, maka orang akan terus bergantung kepada yang lain dalam semua yang dia ketahui, dan itu pasti mustahil adanya.
Chittick menyebut bahasa, sejarah, dan hukum sebagai beberapa contoh ilmu nakliah. Sedangkan contoh-contoh ilmu akliah, sekalipun ia tidak memenuhi semua kriteria, adalah logika dan matematika.
Chittick lalu memberi ilustrasi, “Kita tidak mengatakan, ‘Dua ditambah dua sama dengan empat karena sejumlah pihak berwenang mengatakan demikian.’ Pikiran kita masing-masing mampu menemukan dan memahami kebenaran matematis itu dengan sendirinya.”

Ketika menemukannya dalam dirinya, seseorang tidak lagi bergantung kepada sumber dan otoritas eksternal untuk membenarkannya. Pengetahuan ini dinyatakan benar karena, ketika kita memahaminya, ia bersifat swabukti (self-evident). Kebenaran pengetahuan itu terbukti dalam dirinya sendiri, tanpa perlu pada dukungan bukti eksternal apa pun. Kita tidak bisa menyangkal kebenarannya sama seperti kita tidak bisa menolak kesadaran kita sendiri.
Sebaliknya, Chittick melanjutkan, ilmu nukilan bergantung kepada apa kata orang. Ini pengetahuan yang paling umum dalam semua budaya atau agama. Para penganut Buddha mungkin mengetahui bahwa pencerahan merupakan pengalaman yang melampaui bentuk pengetahuan konvensional. Tetapi, sampai mereka benar-benar mencapainya, mereka menerima pengetahuan itu sendiri melalui penukilan dan “katanya”. Kaum Muslim, tulis Chittick, mengetahui bahwa Allah menyeru mereka untuk mendirikan salat [wajib] lima kali sehari. Tetapi, mereka menukil pengetahuan ini pun dari ulama, yakni orang-orang yang telah mempelajari al-Quran dan Hadis. Mereka tidak dapat menemukan apa yang Allah inginkan dari mereka tanpa menukil dari sumber-sumber yang diwahyukan itu.
Begitu juga bagi sebagian manusia, tulis Chittick, penukilan dan “katanya” itulah yang membentuk ilmu mereka tentang bahasa, budaya, opini, pandangan dunia, dan praktis semua hal yang mereka anggap telah mereka ketahui. Sebaliknya, ilmu akliah adalah apa yang mereka ketahui dengan keyakinan penuh dalam relung jiwa mereka masing-masing, tanpa harus ada dukungan penukilan, “katanya”, atau bukti eksternal apa pun. Akan tetapi, Chittick mengakui, ilmu yang demikian ini amatlah langka.
Pencarian pengetahuan akliah dalam peradaban Islam tumbuh melalui dua bidang pembelajaran yang luas, yang masing-masingnya menelurkan pelbagai cabang dan mengalami banyak pasang surut dalam perjalanannya. Untuk mudahnya, Chittick menyebut dua bidang pembelajaran ilmu akliah itu dengan filsafat dan tasawuf. Filsafat dibangun di atas metodologi logis dan rasional yang telah disistematisasi oleh bangsa Yunani, sedangkan tasawuf sendiri didasarkan pada teknik-teknik kontemplasi dan tafakur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kedua bidang keilmuan itu seringkali tumpang tindih, terutama sejak Abad ke-13.
Filsafat dan tasawuf, tulis Chittick, berpisah jalan secara tajam dengan ilmu-ilmu nakliah karena mengakui secara tegas bahwa makna objek-objek di alam ini tidak dapat ditangkap tanpa secara berbarengan orang mencari makna diri yang mengetahuinya. Orang mempelajari alam memang untuk memahami fenomena (apa yang tampak). Tapi karena pemahaman itu merupakan sifat jiwa dari subjek yang mengetahui, maka tidak ada cara lain kecuali jiwa subjek itu harus dalam keadaan sadar dan mengerti.
Menurut Chittick, para begawan pendekatan intelektual percaya bahwa suatu makna bersembunyi di balik “tanda” (âyât) Tuhan. Lalu, seluruh fenomena (tanda) menunjuk kepada noumena (yang tak tampak), dan bahwa noumena itu hanya dapat disingkap dari dalam diri yang mengetahui. Chittick percaya bahwa tradisi intelektual pada umumnya jelas tidak membiarkan perbedaan tajam antara subjek dan objek sebagaimana yang menjadi prasyarat lahirnya sains modern.
Lalu dia berargumen: “Jika saya akhirnya lebih fokus kepada filsafat Islam ketimbang tasawuf di sini, maka itu sebagian karena adanya gagasan yang sering mengemuka dalam tulisan-tulisan sejarawan Barat dan para apologis Muslim zaman sekarang yang di dalamnya sains Islam—yang sebagian besarnya dikembangkan oleh para filsuf dan bukan kaum sufi—merupakan mukadimah penting bagi sains modern. Saya memilih judul “Sains Alam, Sains Jiwa” (Science of the Cosmos, Science of the Soul) persisnya karena ia menyoroti sains dan pada saat yang sama memunculkan istilah “jiwa”, yang demikian sentral dalam tradisi filsafat sekaligus sebagai istilah yang sangat tidak saintifik (baca: dalam tradisi sains modern).”
Dalam pengantar Kosmologi Islam, Chittick buru-buru mengingatkan betapa getirnya nasib pendekatan akliah yang dia tuliskan dalam buku ini. Meminjam ungkapannya sendiri, pendekatan ini sudah lebih daripada satu abad lalu mati suri. Tinggal segelintir kecil orang yang masih menekuni dan menyuarakannya, tapi suara sebagian besar mereka tak lagi terdengar.
Kekuatan ekonomi, politik, dan sosial yang mendorong aktivitas global telah berhasil menguasai dunia Islam. Umat Islam yang mampu menempuh pendidikan pun biasanya melakukannya untuk tujuan uang. Bidang-bidang teknis dan praktis yang dapat dikuasai dengan agak cepat itulah yang relatif menawarkan jaminan kenyamanan hidup yang paling menarik minat para mahasiswa terbaik.
Pikiran itu pula yang mendominasi universitas-universitas terkemuka di dunia Islam. Pranata-pranata pendidikan tradisional, yang dulunya menuntut para pelajar untuk mendedikasikan hidup mereka bagi pencarian pengetahuan dan kebajikan, hampir sepenuhnya punah. Sebagai gantinya, tumbuh pesat madrasah-madrasah “teologis” yang menernakkan kaum fanatik dan ideolog.
Dalam empat bab pertama buku ini, Chittick membahas sirnanya tradisi intelektual dan berbagai kendala yang menghalangi jalan pemulihannya. Bab Satu memberi penjelasan singkat watak tradisi ini dan menggambarkan berbagai kekuatan, baik dari dalam maupun luar komunitas Muslim, yang telah mengaburkan arti penting pendekatan ini.
Bab Dua membahas lebih jauh perbedaan antara ilmu akliah dan ilmu nakliah serta elemen-elemen dasar dari pandangan dunia filosofis dan sufi, dan mencoba melukiskan keganjilan situasi sejarah umat dari kacamata seorang intelektual Muslim yang autentik. Bab Tiga melanjutkan diskusi tentang hambatan pemulihan situasi yang ada dan cara-cara untuk mengatasinya. Bab Empat meninjau ideologi sebagai pilar pemikiran modern dan menyajikan cara bagaimana tradisi intelektual bisa membantu orang lepas dari sihirnya.
Tiga bab terakhir buku ini mencermati lebih teliti ajaran-ajaran sejati dari tradisi intelektual, dengan fokus kepada relevansinya dengan persoalan yang ada dalam sains dan makna. Bab Lima merefleksikan filsafat Seyyed Hossein Nasr, salah satu dari sedikit orang zaman ini yang masih menyokong tradisi ini. Bab Enam berupaya mendedah mengapa pandangan dunia filosofis menolak pembedaan tajam antara subjek dan objek, dan bagaimana upaya mengetahui diri sendiri merupakan kunci untuk memilah antara apa yang disebut sebagai sains Islam dan “sains” modern. Bab Tujuh mencari calon intelektual untuk mengatasi egosentrisme dan menentukan tujuan-tujuan agar dapat bebas dari segenap hambatan.
Chittick menulis semua bab buku ini pada awalnya sebagai bahan kuliah, terkecuali Bab Lima. Tapi dia sudah merevisi semuanya, bahkan sebagian dia tulis ulang, dengan tujuan mengintegrasikannya menjadi kesatuan utuh. Tiga bab pertama buku ini terkesan ingin disampaikan ke khalayak Muslim, untuk membantu mereka fokus lebih tajam kepada konsep-konsep Islam. Bab-bab seterusnya ditulis untuk khalayak lebih umum, karena itu banyak merujuk kepada tradisi agama dan intelektual selain Islam.[]