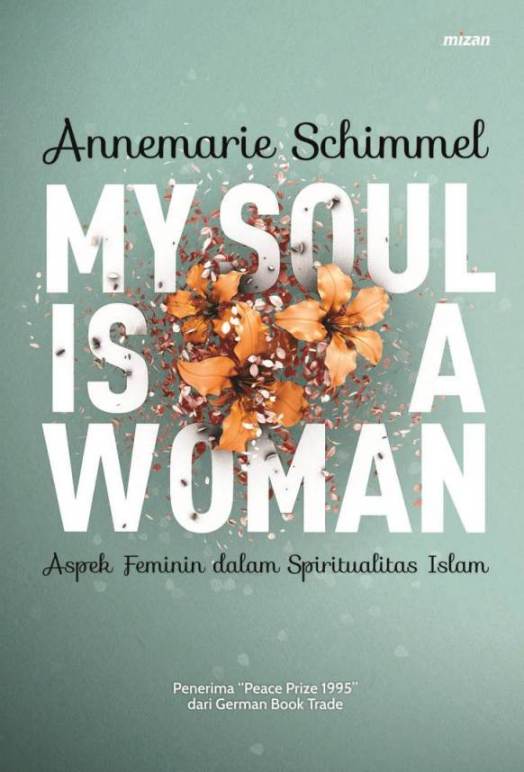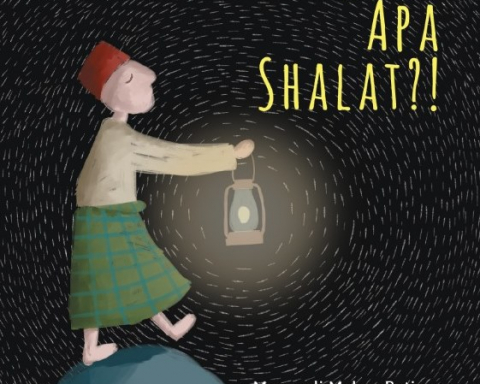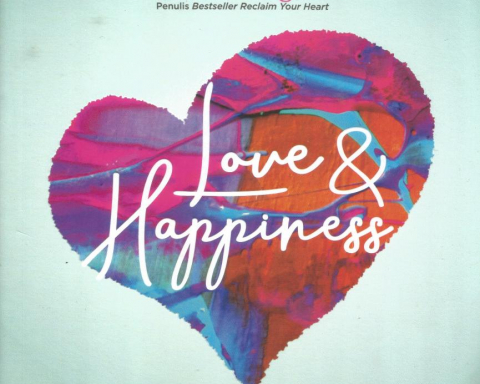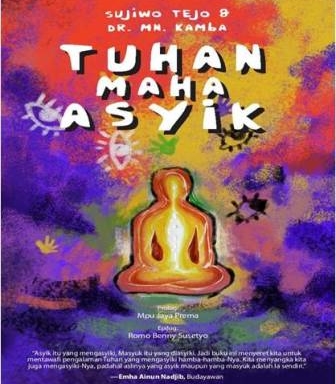Lepas dari hiruk pikuk perdebatan dalam diskursus feminisme, Annemarie Schimmel membawa isu gender ke wilayah yang belum banyak disentuh feminis: tasawuf. Dia percaya bahwa tasawuf sepenuhnya diwarnai aspek-aspek feminin.
Kutipan dua baris puisi Rainer Maria Rilke berikut mengawali paparan Annemarie Schimmel (1922-2003) dalam My Soul is A Woman: Aspek Feminin dalam Spiritualitas Islam.
Dan jiwaku adalah seorang wanita di hadapanmu;
Dia seperti Ruth, menantu perempuan Naomi.
Rilke adalah penyair liris kelahiran Austria yang dianggap sebagai pembaharu puisi Barat modern, terutama di daratan Eropa. Berkarya pada paruh pertama Abad ke-20, Rilke justru semakin populer pada paruh terakhir abad yang sama ketika banyak puisinya menjadi inspirasi–dan banyak dikutip–oleh pengusung New Age, gerakan keagamaan yang berorientasi kepada spiritualitas.
Karya Rilke dominan bernuansa mistis. Kutipan di atas, misalnya, diambil dari karyanya, The Book of Hours, kumpulan puisi tentang pencarian Tuhan.
Mengawali bukunya dengan dua baris puisi Rilke, Annemarie bertanya, apakah penggambaran jiwa sebagai wanita–seperti dalam puisi Rilke–tak lazim atau asing bagi tradisi keagamaan Islam? Benarkah Islam, sebagaimana pandangan banyak orang, merupakan agama yang semata berorientasi kepada lelaki?

- Judul: My Soul is A Woman: Aspek Feminin dalam Spiritualitas Islam
- Penulis: Annemarie Schimmel
- Penerbit: PT Mizan Pustaka
- Tahun Terbit: 2017 (Edisi Kedua)
- Tebal: 292 halaman
Dua pertanyaan tersebut menjadi tema sentral My Soul is A Woman. Dan, Annemarie adalah jaminan mutu dan otoritas dalam menjawabnya. Di usia delapan tahun, dia sudah terkagum-kagum dengan sebuah hadis Nabi Muhammad.1Hadis itu adalah “Manusia sebenarnya sedang tertidur, dan ketika meninggal, mereka terjaga.” Hadis ini menghiasi nisan makam Annermarie Schimmel di Bonn, Jerman Sejak usia 15 tahun, perempuan kelahiran Erfurt, Jerman, itu telah belajar bahasa Arab–sesuatu yang jarang dilakukan di masa ketika negeri Bavaria disapu gelombang fasisme Nazi. Lalu pada usia 21 tahun, dia sudah meraih doktor bidang peradaban Islam dari Universitas Berlin.

Pembahasan tentang gender, terutama peran perempuan, yang dikaitkan dengan pemahaman keagamaan memang tak habis-habis. Tradisi keagamaan menjadi target utama serangan feminisme radikal karena dianggap sebagai bagian dari sistem yang melestarikan patriarki.2Feminisme sendiri sebenarnya bukan gerakan sosial-politik yang monolitik. Gerakan ini bervariasi karena tiap-tiap variannya mendasarkan pada ideologi yang berbeda-beda, dan bahkan kadang saling bertentangan. Fokus tuntutan pun berkembang sesuai masanya. Feminisme radikal, misalnya, memandang bahwa untuk mewujudkan keadilan gender, maka sistem patriarkilah yang harus dibongkar, bukan sekadar memberi ruang kesetaraan bagi perempuan (Lihat: Tong, Rosemarie. 2009. Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction. Colorado: Westview Press. Hal. 2)
Hingga batas tertentu, harus diakui anggapan itu ada benarnya. Dalam pemahaman keagamaan tertentu–yang sayangnya dominan, perempuan menjadi “makhluk kelas dua” di bawah lelaki, sejak penciptaannya hingga perannya dalam masyarakat.
Kisah asal perempuan dari tulang rusuk bengkok lelaki membuat seakan ada “yang kurang” dalam diri perempuan atau hanya bagian dari “yang lengkap”, yaitu lelaki. Belum lagi cerita tentang “Hawa sang penggoda”, yang membuat Adam memakan buah terlarang dan melemparkan mereka berdua ke dunia demi menjalani “hukuman”.
Pemahaman keagamaan tak bisa disalahkan sendirian. Konstruksi sosial-budaya juga ikut berperan. Pandangan stereotip bahwa perempuan lebih emosional, tidak independen, dan lebih pasif-submisif melahirkan diskriminasi terhadap peran perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat.
Sejarah juga mencatat, bagaimana perempuan mengalami penderitaan akibat diskriminasi itu dari peradaban yang satu ke peradaban yang lain. Dalam peradaban Yunani dan Romawi, misalnya, mayoritas perempuan, terutama dari kalangan miskin, adalah budak. Jika merdeka, mereka tak lebih daripada objek pemuas seks lelaki. Meski ada catatan pengecualian di Athena, perempuan tetap tak memiliki hak berpartisipasi di ruang publik dan hak untuk mewarisi harta benda.
Hingga masa sebelum kemunculan Islam, kelahiran anak perempuan bukanlah kabar yang menggembirakan. Mereka menjadi pilihan utama untuk dikorbankan karena ritual persembahan kepada dewa, kesulitan ekonomi, atau anggapan bahwa mereka lebih berpotensi mendatangkan aib bagi keluarga ketimbang anak lelaki.
Di abad modern, ketimpangan gender itu tak serta merta menghilang. Bahkan ketika revolusi seksual terjadi pada 1960-an, saat kebebasan seksual dirayakan, perempuan justru tetap dipandang semata objek seksual lelaki. Satu kelompok feminis memandang bahwa perempuan bebas mengeksplorasi apa pun aktivitas seksual yang dia inginkan. Sebaliknya, kelompok feminis lain menganggap kebebasan seksual semacam itu justru menempatkan perempuan tetap di bawah kendali seksual lelaki.3Perdebatan ini terjadi di kalangan feminisme radikal sendiri. Rosemarie Tong mengklasifikasi kelompok feminis pertama sebagai femisnisme radikal libertarian dan yang kedua sebagai feminisme radikal kultural (Lihat: Tong, Rosemarie. 2009. Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction. Colorado: Westview Press. Hal. 3)
Dalam bukunya, Annemarie tidak hendak mengurai satu per satu tantangan yang dihadirkan feminisme terhadap tradisi keagamaan. Dia justru membawa perdebatan gender ke wilayah yang tak pernah disentuh feminisme: tasawuf, salah satu cabang mistisisme Islam. Menurutnya, tasawuf secara keseluruhan justru diwarnai aspek-aspek feminin.
Penggambaran jiwa sebagai perempuan seperti dalam puisi Rilke sudah lebih awal ada dan lazim dalam Islam. Annemarie utamanya mengambil kata nafs ‘jiwa’ (juga diterjemahkan ‘diri’) dalam al-Quran. Ia merupakan kata benda feminin dan muncul tiga kali dalam tiga makna berbeda: ‘jiwa yang menghasut kejahatan’ (QS Yusuf [12]: 53); ‘jiwa yang menyalahkan’ (QS al-Qiyamah [75]:2); dan ‘jiwa yang damai’ (QS al-Fajr [89]: 27-28).
Annemarie mengakui pemaknaan tersebut (terutama dua makna pertama) membuat kata nafs cenderung identik dengan “insting-insting rendah duniawi”. Gender feminin yang dikandung nafs kemudian melahirkan konstruksi sosial-budaya yang cenderung memandang perempuan sebagai personifikasi sifat-sifat serba-kurang (rendah): kurang akal dan kurang saleh (apalagi dalam bahasa Indonesia ada frasa hawa nafsu). Hal itu lalu dikaitkan dengan kata dunya yang secara gramatikal juga bergender feminin. Alhasil, tak sedikit gambaran yang muncul dalam tradisi keagamaan Islam–dan juga Kristianitas–tentang dunia sebagai “pelacur tua” yang merayu dan menipu kaum lelaki.
Gambaran-gambaran seperti itu, menurut Annemarie, tampak dalam bagaimana para sufi pada era awal mempraktikkan selibat. Mereka memandang pernikahan sebagai tirai yang bisa menghambat pencapaian spiritual dan intelektual. Kalaupun menikah, para sufi di era awal cenderung memposisikan istri mereka sebagai sarana untuk menguji kesabaran dan pada akhirnya menyempurnakan diri.4Sebagai contoh, Annemarie mengutip sebuah kisah dari Matsnawi karya Jalaluddin Rumi. Dikisahkan seorang murid ingin menemui syekh besar. Lalu, dia bertemu dengan istri syekh yang mengatakan hal-hal negatif tentang suaminya: bahwa suaminya orang yang tak berguna. Si murid pun kecewa dan pulang. Tapi di tengah hutan, dia melihat syekh sedang mengendarai seekor singa dan mengacung-acungkan ular sebagai cambuk. Sang syekh berkata kepada si murid bahwa inilah hadiah Tuhan karena dia berhasil menunjukkan kesabaran dalam menghadapi istrinya
Tentu saja praktik seperti itu sama sekali tak diajarkan Sang Nabi. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bahkan mengatakan, “Allah telah membuatku menyayangi dari duniamu, kaum perempuan dan wewangian, dan kebahagiaan bagi mataku adalah ketika salat.” Terdapat banyak kisah sufistik, bagaimana Nabi muncul dalam mimpi para sufi asketik itu dan menasehati mereka agar mengikuti tradisinya–yakni menikah–sehingga bisa menjadi bagian dari umatnya.
Bagi Annemarie, hadis tersebut sangat menarik. Ia menggambarkan bagaimana Nabi Islam itu memposisikan perempuan di masa ketika kelahiran anak perempuan saja masih dipandang berpontensi menjadi aib keluarga. Lebih daripada itu, acuannya kepada wewangian menempatkan perempuan dekat dengan keharuman dan kesucian. Apalagi, kata thib ‘wewangian’ yang bergender maskulin ditempatkan di antara dua kata feminin perempuan dan salat. Tak mengherankan jika hadis di atas menjadi sumber inspirasi yang kaya bagi para mistikus tentang hubungan misterius antara perempuan dan wewangian.
Oleh karena itu, pemaknaan nafs dalam al-Quran pun mengungkap metafora lain di kalangan para sufi. Yakni, kaum perempuan memiliki potensi yang sama dengan lelaki dalam mencapai kesempurnaan: jiwa yang damai (an-nafs al-muthmainnah). Makna nafs dalam al-Quran sebenarnya menunjukkan perjalanan spiritual setiap manusia, entah itu lelaki maupun perempuan, dari “jiwa yang menghasut” kepada “jiwa yang damai”.
Dalam metafora yang relatif sama, Annemarie juga menyelesaikan problem istilah “pria Tuhan” yang banyak dijumpai dalam karya kesusastraan sufistik, baik dalam bahasa Arab, Persia, Turki, maupun Indo-Pakistan. Istilah tersebut sekilas menunjukkan bahwa hanya lelakilah yang mungkin mencapai kesempurnaan spiritual. Tapi, sebuah penjelajahan literatur justru menjelaskan hal sebaliknya.
Nashir Khusraw, penyair-filsuf Persia Abad ke-11, misalnya, mengatakan bahwa “pria Tuhan” hanyalah Nabi Muhammad sementara manusia lainnya, baik perempuan maupun lelaki, belumlah mencapai derajat “pria Tuhan”. Demikian pula teosof besar Ibn Arabi menyatakan bahwa rajuliyah ‘kejantanan’ justru dicapai ketika seseorang disempurnakan oleh cahaya akal dan pentunjuk spiritual dan meninggalkan kegelapan insting-insting rendah duniawi. Dalam Futuhat al-Makiyyah, Ibn Arabi juga menulis, “Segala sesuatu yang kami bicarakan tentang orang-orang dengan menggunakan nama ‘pria’ juga dapat diterapkan pada kaum wanita di antara mereka.” Bagaimanapun kata rajul dalam al-Quran juga digunakan untuk menunjukkan kedua gender, baik maskulin maupun feminin.5Lihat Umar, Nasaruddin. 1999. Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Quran. Jakarta: Penerbit Paramadina. Hal. 152-154
Itulah kenapa penyair-sufi Nuruddin Abdurrahman Jami–atau yang lebih dikenal hanya dengan Jami–menggambarkan Rabi’ah al-‘Adawiyah (sufi perempuan sekaligus pengusung gerakan sufistik di era awal) sebagai sosok yang mengatasi perbedaan gender. Dalam hagiografinya, Nafahat al-Uns, Jami menulis tentang Rabi’ah sebagai berikut.
Jika semua wanita seperti apa yang telah kami katakan,
maka wanita akan lebih disukai daripada pria.
Sebab gender feminin itu bukan aib bagi matahari,
dan gender maskulin pun bukan kehormatan bagi bulan.
Kemudian, Annemarie pun menulis:
Itu berarti konsep pria dan wanita bersifat duniawi, terikat pada bentuk sementara yang terbuat dari debu, sedangkan jiwa tidak ada hubungannya dengan debu. Jika pria dan wanita akhirnya mencapai tingkat ‘penjelmaan’ sempurna, mereka tidak lagi mempunyai eksistensi individual.
Di titik inilah, Annemarie menunjukkan bahwa unsur-unsur feminin justru lebih memungkinkan seseorang untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Sebab, hanya perempuanlah yang dapat benar-benar merasakan prema atau kasih tak sampai dan kerinduan. Jika sang kekasih jauh di mata, hanya wanitalah yang bisa merasakan derita keterpisahan yang tak terucapkan sementara lelaki justru digambarkan sebagai sosok petualang yang bebas. Padahal, penderitaan karena keterpisahan dan kerinduan adalah tema sentral kaum sufi dalam meraih cinta Sang Kekasih Ilahi.
Dalam banyak karya mereka, para sufi kerap menggambarkan perjalanan spiritual melalui metafora kisah percintaan antara lelaki dan perempuan. Salah contohnya adalah puisi naratif Majnun Layla gubahan penyair Persia Nizami Ganjavi. Ini kisah tentang Qays yang menjadi gila (majnun) karena cintanya kepada Layla tak berbalas. Di ujung kisah, Qays yang terobsesi cinta itu pun tak lagi ingin melihat Layla sebab merasa telah hidup di dalam diri wanita itu. Kisah ini di mata para mistikus menjadi gambaran penyerapan total pesuluk (musafir di jalan spiritual) ke dalam diri Sang Kekasih Ilahi.
Menurut Annemarie, adalah Ibn Arabi yang berperan penting dalam menjelaskan makna unsur feminin dalam definisi-definisi yang dalam. Syekh Agung itu memandang bahwa bukan hanya nafs yang mengandung unsur feminin tapi juga Dzat ‘Esensi Ilahi’–sebuah simbolisme yang menurut Annemarie termasuk mengejutkan pada masanya. Menurut Ibn Arabi, aspek feminin justru membuat Tuhan dapat dikenali dengan lebih sempurna. Karena peran utama unsur-unsur feminin dalam Dzat (kata yang secara gramatikal juga bergender feminin), menurut Ibn Arabi, maka Nabi mengungkapkan kecintaan kepada perempuan dalam hadisnya.
Ibn Arabi menulis:
Tuhan tidak dapat dilihat lepas dari materi, dan Dia dilihat dengan cara lebih sempurna dalam materi manusia daripada di tempat lain, dan dengan cara yang lebih sempurna pada wanita dibanding pada pria.
Para sufi setelahnya bahkan menerapkan konsepsi tersebut dalam menjelaskan misteri cinta seksual antara pria dan wanita. Ya’qub Sarfi, sufi asal Kashmir, misalnya, melihat ada aspek mistis dalam kewajiban mandi besar setelah berhubungan seksual. Menurut Ya’qub, selama hubungan seksual, ruh terlibat sangat intens dengan manifestasi Ilahi sehingga kehilangan seluruh hubungannya dengan fisik. Maka, satu-satunya jalan untuk mengembalikan ruh ke dalam tubuh adalah dengan melakukan mandi besar.
Penggambaran bahwa Tuhan mengungkapkan diri-Nya paling indah melalui unsur feminin juga bisa dilihat dari penggunaan istilah “pengantin Tuhan” dalam banyak karya sufistik. Rumi, misalnya, menggambarkan jiwa sebagai “perempuan” yang tak bisa terus mendiami “istana tubuh” saat Sang Kekasih memanggilnya.
Jiwa wanita, yang duduk di istana tubuh,
melepas cadarnya dan berlari mendatangi cintanya.
Ayah Rumi, Baha-uddin Walad (juga seorang sufi dari Balkh) yang sangat berpengaruh bagi Rumi, pernah menulis interpretasinya terhadap cinta seksual. Dia menggambarkan kebahagiaan sepasang pengantin yang melihat seluruh bagian tubuh yang tersembunyi tak berbeda dengan kebahagiaan seorang hamba yang bersujud kepada Tuhan dalam penyerahan diri mutlak. Putranya, Rumi, pun menggemakan penggambaran itu dalam syairnya:
Denganmu aku lebih suka bertelanjang;
aku melepaskan pakaian dari tubuhku
Sehingga pangkuan kemuliaan-Mu
Berubah menjadi pakaian bagi jiwaku.
Bagi para sufi, jiwa yang telah terikat oleh perjanjian primordial dengan Sang Kekasih Ilahi pastilah menantikan perkawinan. Keterpisahan karena terlempar ke dalam kegelapan ruang dan waktu membuat jiwa selalu merindukan perjumpaan. Konsepsi sufistik ini sepenuhnya dekat dengan unsur-unsur feminin.
Oleh karena itu, menurut Annemarie, pesuluk di jalan Tuhan disebut juga sebagai “pengantin Tuhan”. Dan Rumi memberi interpretasi puncak ketika mengatakan bahwa kematian adalah pernikahan (‘urs) sejati, yakni saat jiwa akhirnya dipersatukan kembali dengan Kekasih primordialnya.
Jangan katakan “selamat jalan” ketika aku dimasukkan
ke dalam kubur
Selembar tirai menuju kebahagiaan kekal.
Pada akhirnya, membaca My Soul is A Woman seperti menyelam dalam keluasan jelajah literatur dan kedalaman paparan sang penulis. Annemarie dengan lincah berayun dari satu rujukan ke rujukan yang lain, baik itu ayat, hadis, syair, maupun metafora untuk menjelaskan konsepsi-konsepsi sufistik.
Pada intinya, Annemarie ingin mengatakan bahwa arus pemikiran liberal tentang gender tak bisa diterapkan secara universal. Ada cukup banyak tradisi, adat, dan kebiasan yang dianggap secara ekstrem sebagai bagian dari sistem patriarki tapi pada saat yang sama dipersepsi oleh kelompok perempuan tertentu bukan sebagai bentuk penindasan.
Pandangan seperti itu mungkin mirip dengan feminisme pascakolonial. Mereka menyadari bahwa keragaman etnis, identitas, agama, level pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, kondisi kesehatan, dan faktor-faktor kontekstual lainnya dapat membentuk pemahaman yang berbeda dari kelompok perempuan tertentu tentang bentuk-bentuk penindasan.
Rosemarie Tong menyebut pemikiran feminis tersebut sebagai feminisme multikultural–dan oleh sebagian lainnya disebut feminisme interseksional. Mereka, menurut Rosemarie, berupaya menolak esensialisme (pandangan bahwa setiap perempuan adalah sama) dan chauvinisme (pandangan bahwa perempuan dengan ‘hak istimewa’ dapat berbicara atas nama semua perempuan) dari diskursus feminisme.6Tong, Rosemarie. 2009. Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction. Colorado: Westview Press. Hal. 8
Itu tidak berarti Annemarie mengingkari bahwa ada persoalan diskriminasi gender dalam pemahaman atas teks suci Islam. Dia sebaliknya mengakui bahwa tafsir legalistik justru telah menjauhkan perempuan dari kedudukan yang mereka nikmati pada masa Nabi. Padahal, tafsir seperti itu sebenarnya tidak memiliki landasan kuat dari teks suci.
Bagi Annemarie, tasawuf menjadi wilayah ketika pembedaan gender tak lagi berlaku. Di wilayah inilah, perempuan menikmati hak dan peran yang sama dengan lelaki. Al-Quran, hadis, dan literatur sufistik tak hanya melambangkan jiwa manusia sebagai ‘wanita’ yang mendamba dan merindukan perjumpaan dengan Sang Kekasih tapi juga menampilkan sosok perempuan historis yang mencapai puncak kecemerlangan spiritual, intelektual, dan sosial.[]