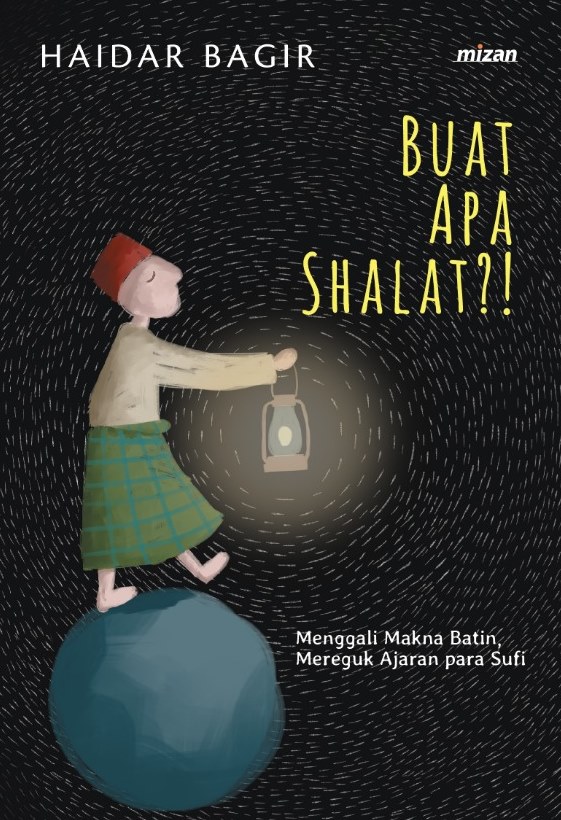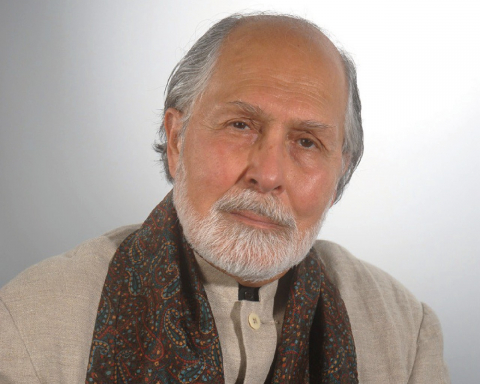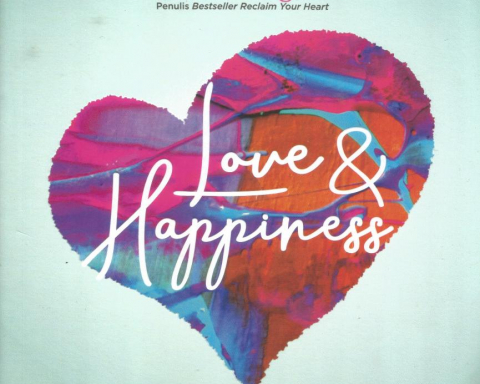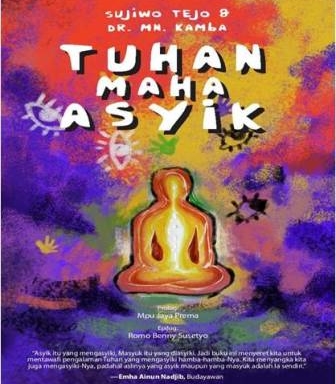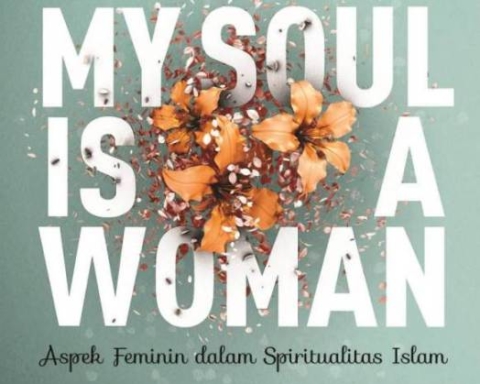Karya Haidar Bagir Buat Apa Shalat?! akan membuat Anda merasa merugi mengabaikan shalat. Ibadah ini bukan sekadar kewajiban syariat tapi fasilitas kenikmatan tertinggi yang pernah dianugerahkan kepada manusia.
KETIKA berita penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh KPK menyebar di Twitter, sebuah akun mencuit sarkastik, “Yang pasti dia rajin shalat.” Tak sedikit akun lain menyerang cuitan ini: menganggap perkara korupsi tak ada urusannya dengan shalat atau tidaknya seseorang.
Oke, cuitan itu mungkin terlampau sinis. Argumentasinya juga terlalu generalisasi. Toh, tak sedikit orang yang tidak mengerjakan shalat (dalam arti non-muslim) juga melakukan korupsi.
Namun, sebagai muslim, saya terkadang suka berpikir, mengapa orang yang mengerjakan shalat—bahkan pernah seorang menteri agama dan kiai—bisa menggarong uang rakyat. Bukankah Al-Quran bilang, shalat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji (merusak diri sendiri) dan mungkar (menzalimi orang lain)?
Apa yang dibilang Al-Quran (QS Al-’Ankabut:45) itu juga seolah tidak sesuai dengan kenyataan umum. Coba kita perhatikan Indeks Persepsi Korupsi 2020 yang menempatkan negara-negara berpopulasi mayoritas muslim di peringkat 100 ke bawah, termasuk Indonesia. Artinya, negara-negara yang sebagian besar isinya pelaku shalat justru tak becus mengelola harta publik. Bukankah negara berpenduduk mayoritas muslim setidaknya bisa memperoleh peringkat yang lebih baik daripada negara-negara “kafir”—yang sialnya nangkring di posisi-posisi atas dalam indeks tersebut?
Pertanyaan seperti itulah yang coba dijawab Buat Apa Shalat?! Menggali Makna Batin, Mereguk Ajaran Para Sufi karya Haidar Bagir. Bertitik tolak dari pertanyaan tersebut, Haidar membedah shalat secara rasional-filosofis sekaligus mistis. Dia menjelajahi ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, penghayatan kaum sufi, hingga pemikiran psikolog Barat, terutama yang mengusung mazhab psikologi positif.
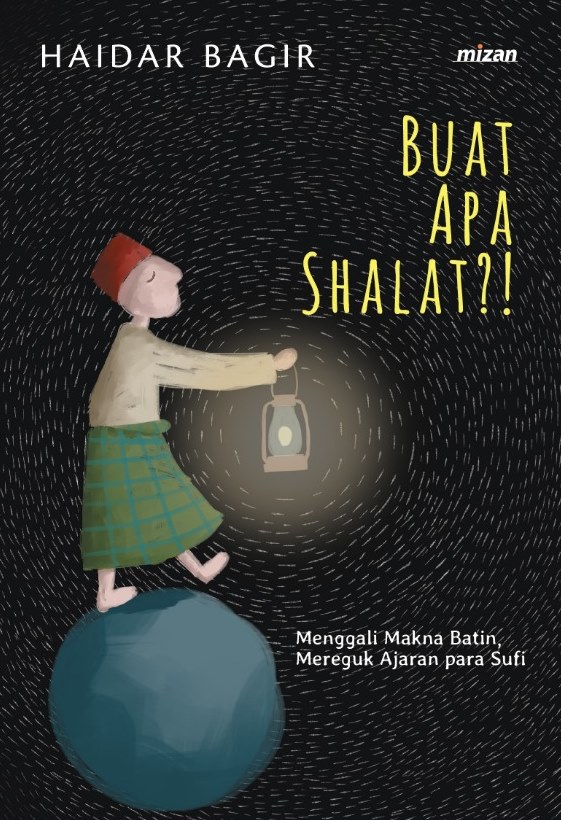
- Judul: Buat Apa Shalat?!: Menggali Makna Batin, Mereguk Ajaran para Sufi
- Penulis: Haidar Bagir
- Penerbit: PT Mizan Publika
- Terbit: 2020 (Edis Baru)
- Tebal: 272 halaman
Buku ini sebenarnya bukan terbitan baru. Ia terbit pertama kali pada 2007 dengan judul Buat Apa Shalat?! Kecuali Jika Anda Hendak Mendapatkan Kebahagiaan dan Pencerahan Hidup. Isinya nyaris tak berbeda, kecuali tambahan beberapa artikel pada bagian penghayatan ulama dan sufi terhadap shalat, sebuah tanya jawab, dan sebuah kesimpulan.
Meskipun demikian, penerbitan ulang buku ini dalam edisi baru patut diapresiasi. Pertanyaan di atas bagaimanapun masih relevan hingga kini.
Fenomena lain ikut mendorong Haidar Bagir menulis buku ini. Yaitu, kecenderungan berislam tanpa ritual, seperti terjadi di kalangan liberal yang mendorong berislam secara “rasional” atau di kalangan praktisi spiritual perkotaan yang lebih mengutamakan hakikat (hubungan manusia dengan Tuhan) daripada syariat (kewajiban ritual).
Mari kita kembali ke substansi buku ini.
Selain ayat dalam Surah Al’Ankabut di atas, Al-Quran dan hadis Rasulullah sangat menekankan shalat. Setidaknya ada 234 ayat mengenai shalat di dalam Al-Quran sementara tak terhitung banyaknya hadis yang membicarakan ibadah wajib ini.
Namun, sebagian ayat dan hadis itu justru mengecam atau memperingatkan pelaku shalat. Surah Al-Ma’un bahkan mendeklarasikan “kemalangan besar” bagi para pelaku shalat jika mereka menghalangi perbuatan baik kepada sesama. Pelaku shalat seperti ini disebut oleh surah itu sebagai “mereka yang lalai terhadap shalatnya” dan bahkan “mereka yang mendustakan agama”. Rasulullah juga pernah bersabda, “Tak melakukan shalat orang-orang yang shalatnya tidak menghindarkannya dari kekejian dan kemungkaran,” atau “Ada kalanya seseorang shalat terus-menerus selama 50 tahun, namun Allah tak menerima satu pun dari shalatnya.”
Menurut Haidar Bagir, itu berarti ada nilai di dalam shalat. Shalat tak semata ucapan dan gerakan yang diulang-ulang. Jika nilai ini tak ada di dalamnya, maka shalat itu bukanlah “shalat yang benar”. Bahkan, nilai ini sangat menentukan diterima atau ditolaknya shalat.
Nilai itu adalah berbuat baik dan menjauhi kekejian serta kemungkaran. Itulah mengapa sebagian besar ayat mengenai shalat selalu diiringi perintah untuk melakukan keduanya.
Jadi, menurut logika Al-Quran dan hadis, “shalat yang benar” niscaya mencegah pelakunya dari kekejian dan kemungkaran serta mendorongnya berbuat baik. Tanpa efek tersebut, maka shalat seseorang bukanlah “shalat yang benar” tapi “shalat yang tertolak”. Ini hubungan konsekuensi logis.
Artinya, jika orang yang mengerjakan shalat masih menggasak uang rakyat, shalatnya tertolak. “Shalat yang benar” juga tak bakal membuat pelakunya secara sengaja menabrak anjing hanya karena pendapat fikih menyatakan liur binatang itu najis.
Lalu, bagaimana “shalat yang benar itu”? Dan bagaimana pula “shalat yang benar” itu bisa menghasilkan dampak-dampak positif bagi pelakunya?
Di sini, Haidar memfokuskan pembahasannya kepada “khusyuk”. Khusyuk menjadi kunci yang membuka gerbang menuju selaksa kenikmatan dan kemanfaatan shalat. Itulah kenapa, dalam Surah Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, “Sesunggunya shalat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.” Berlandaskan ayat itu, Haidar berpendapat bahwa shalat hanya akan memiliki nilai—menjadi “shalat yang sebenarnya”—jika dilakukan dengan khusyuk.
Haidar mendefinisikan khusyuk sebagai “kesadaran penuh akan kerendahan kehambaan di hadapan keagungan ketuhanan”. Khusyuk di sini seperti kesadaran eksistensial kita sebagai manusia di hadapan Sang Maha Pencipta, Maha Mengetahui, dan Maha Pengasih. Khusyuk, menurut Haidar, lahir dari cinta kepada Zat serba maha itu, dan pada gilirannya akan menghasilkan cinta pula kepada ciptaan-Nya. Khusyuk juga akan melahirkan kerendahan hati pelaku shalat.
Ketika khusyuk dilatihkan melalui shalat lima waktu sehari semalam, orang-orang yang mengerjakan shalat dengan benar akan selalu merasakan kehadiran Tuhan, mewaspadai kecintaan berlebihan kepada selain-Nya, dan mencegah dirinya dari perbuatan yang akan menyakiti dirinya serta orang lain. Dengan terus menjaga kekhusyukan setiap harinya, pelaku shalat sejati tak memiliki tempat lain di dalam hatinya kecuali tempat itu dihuni oleh kesadaran-dirinya akan kehambaan dan ketuhanan.
Selain memahami makna ujaran-ujaran serta gerakan-gerakan di dalam shalat, untuk mencapai khusyuk, ada kata kunci lain yang Haidar bedah, yakni thuma’ninah. Kata ini disebut dalam kitab-kitab fikih sebagai syarat sah shalat. Ia didefinisikan sebagai ketenangan saat melafalkan bacaan dan melakukan gerakan di dalam shalat.
Dalam melakukan shalat, kita diminta untuk tidak terburu-buru: melakukan tiap-tiap rukun shalat satu demi satu; dan memberi waktu cukup bagi pelaksanaannya. Itulah pengertian thuma’ninah secara fikih.
Dalam buku ini, Haidar memberi penjelasan rasional-filosofis sekaligus mistis terhadap thuma’ninah. Kata ini memiliki akar kata yang sama dengan muthma’innah dalam Al-Quran. Ada bagian di dalam Al-Quran yang menggunakan kata muthma’innah untuk menjelaskan perjalanan jiwa dari dari al-nafs al-ammarah (‘jiwa yang menghasut’) dan al-nafs al-lawwamah (‘jiwa yang menyalahkan’) menuju al-nafs al-muthma’innah (‘jiwa yang damai atau tenang’).
Jiwa yang damai atau tenang digambarkan sebagai jiwa yang kembali kepada Pemiliknya, atau kepada asal-muasalanya—yakni Tuhan—dengan rela. Kerelaan atau kepasrahan kepada realitas ketuhanan mendorong jiwa untuk sepenuhnya sadar akan kerendahan kehambaan dan keagungan ketuhanan. Haidar karenanya menyatakan thuma’ninah dalam shalat merupakan pintu masuk menuju khusyuk.
Thuma’ninah dalam shalat juga bermakna bahwa “shalat yang sebenarnya” bisa mengantarkan jiwa manusia kepada kedamaian dan ketenangan, sebuah kondisi yang setiap manusia dambakan dalam kehidupan. Berada di hadapan Sang Mahadamai dan berkomunikasi dengan-Nya sudah semestinya membuat pelaku shalat selalu berada dalam keadaan damai. Tidak ada tempat dalam jiwanya bagi hasutan kepada hal-hal selain-Nya atau dorongan-dorongan untuk berbuat keji dan mungkar.
Kedamaian adalah puncak kenikmatan, dan itu bisa dicapai melalui shalat yang sebenarnya. Itulah mengapa Rasulullah menyatakan dalam sejumlah hadis bahwa shalat adalah “pelipur jiwanya” dan “penyejuk matanya”. Sebuah riwayat mengisahkan, tiap kali menghadapi kesedihan, Rasulullah suka meminta Bilal mengumandangkan iqamah lalu beliau kemudian mendirikan shalat. Hadis-hadis mengenai ini sangat menginspirasi kaum sufi dalam menghayati shalat mereka.
Haidar kemudian merujuk kepada psikologi positif yang memunculkan istilah “flow”. Istilah ini, menurutnya, menggambarkan thuma’ninah secara psikologis.
Mihaly Csikszentmihalyi, perintis mazhab psikologi positif, menjelaskan flow sebagai keadaan pikiran yang di dalamnya kesadaran manusia berada dalam keadaan teratur dan selaras. Flow dicirikan dengan konsentrasi mendalam (pikiran tidak bercabang-cabang), perasaan kendali penuh atas segala sesuatu, perasaan bahwa momen saat ini sebagai satu-satunya yang penting (dimensi waktu yang memecah durasi kehidupan seakan meluruh), dan hilangnya ego (batasan individual yang memisahkan seseorang dari yang lain).
Menurut psikologi positif, kondisi flow bisa mendatangkan kebahagiaan. Kondisi ini karenanya dipandang bisa berperan dalam penyembuhan sejumlah penyakit seperti jantung, stroke, dan depresi, seperti disimpulkan oleh Herbert Benson, ahli ilmu kedokteran Harvard University dalam bukunya Relaxation Response. Benson bahkan mengakui zikir (bacaan shalat mengandung zikir) bisa mendatangkan kondisi seperti ini.
Keadaan flow juga bisa memantik kreativitas (kemampuan memunculkan gagasan baru) atau mencerahkan intelektual kita. Dalam kondisi flow, otak manusia mentransmisikan gelombang tetha, gelombang yang berada di antara gelombang alpha (dipancarkan saat terjaga) dan gelombang betha (yang dipancarkan saat tertidur). Saat otak mentransmisikan gelombang tetha inilah, manusia memperoleh pemikiran terbaiknya.
Para filsuf muslim berpandangan bahwa pengetahuan tertinggi tidak lagi bisa diperoleh melalui penalaran rasional biasa, tapi berdasarkan kehadiran-diri melalui pengalaman spiritual yang disebut ilmu hudhuri. Itulah mengapa para filsuf muslim seperti Ibn Sina memilih mendirikan shalat ketika menghadapi problem-problem filosofis pelik, yang tak bisa mereka pecahkan.
Terkait kondisi flow, menurut Haidar, shalat adalah medium paling pas jika dibandingkan dengan jenis-jenis meditasi modern. Shalat memiliki bacaan dan gerakan fisik yang diulang-ulang. Karakter ini membuat shalat lebih mampu menjaga pelakunya dalam keadaan antara terjaga dan tertidur, apalagi jika kita bisa menghayati makna puitis dan simbolik di balik bacaan dan gerakan shalat seperti para sufi.
Di titik ini, Haidar telah menjawab pertanyaan di atas sekaligus menunjukkan bahwa shalat merupakan sarana menuju hakikat yang tak bisa diabaikan. Dia juga menunjukkan manfaat shalat dalam mencerahkan intelektual. Kalaupun shalat bukan kewajiban syariat, kemanfaatan dan kenikmatan yang dihadirkannya seharusnya membuat kita tidak menyia-nyiakan shalat.
Buat Apa Shalat?! akan membuat Anda merasa merugi meninggalkan shalat. Sebab, ibadah ini bukan sekadar kewajiban tapi kenikmatan tertinggi yang pernah dianugerahkan Allah Swt kepada manusia di dunia.[]