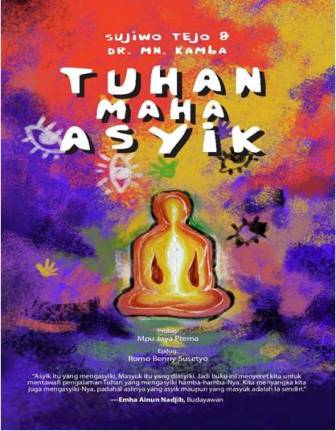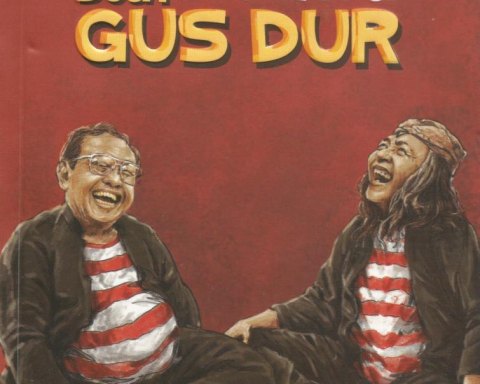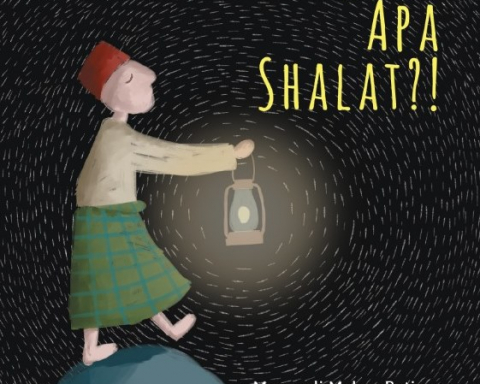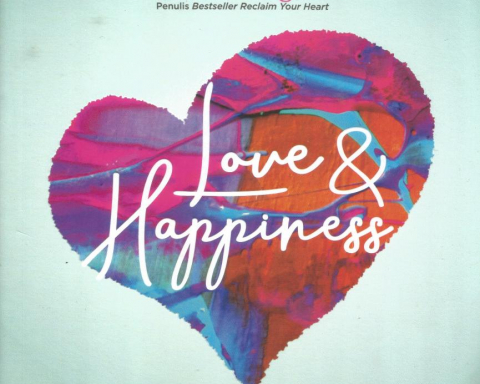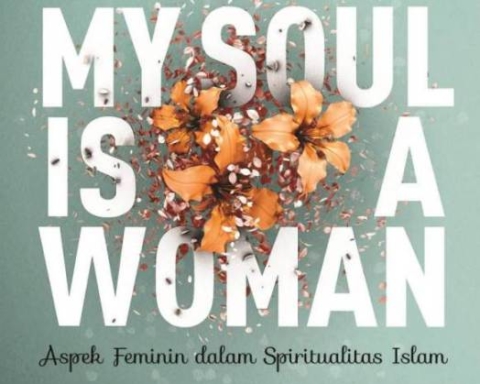Seperti judulnya, buku karya Sujiwo Tejo dan Nur Samad Kamba ini mencoba mengatakan bahwa kebertuhanan itu seharusnya menyenangkan, dan bukan malah menyusahkan serta melahirkan kebencian. Meskipun mencoba asyik, buku ini di beberapa bagian justru kurang mengasyikkan.
TUHAN Maha Asyik mencoba membahas banyak hal di seputar ketuhanan dengan santai. Awalnya, ada narasi. Anak-anak sekolahan berdialog; mempertanyakan banyak hal dari soal hubungan wayang dengan dalang, persepsi orang terhadap sesuatu, hubungan manusia dengan Tuhan dan alam, fungsi doa, pengetahuan, hingga soal bahasa. Lalu, setelah dialog anak-anak itu, buku ini menyajikan penjelasan yang bisa dibilang sufistik dan filosofis.
Cerita dialog anak-anak itu sarat dengan metafora, baik yang diambil dari kisah perwayangan maupun matematika. Sebagian besar cerita mengalir dan menarik untuk diikuti, terutama karena metafora-metaforanya. Pemilihan cerita dalam bentuk dialog anak-anak ini cerdas. Anak-anak bisa dianggap sosok yang polos, serba ingin tahu, dan karenanya suka bertanya. Tak jarang, gugatan lugu terhadap apa yang dianggap sebagai kemapanan datang dari anak-anak.
Tapi, upaya kedua penulis—Sujiwo Tejo dan Nur Samad Kamba yang tentu saja bukan anak-anak lagi—menyelami dunia polos anak-anak ini terkadang tergelincir di beberapa cerita. Anak-anak sekolahan itu tiba-tiba saja punya pikiran canggih untuk ukuran usia mereka. Ini membuat keluguan dan kepoloson mereka seperti ditelan oleh kedewasaan Tejo dan Kamba, dan sebagian cerita pada akhirnya malah tidak asyik. Misalnya, dalam “Pertanda”, seorang anak nyeletuk bahwa main manten-matenan dengan menggunakan daun-daunan adalah “bermain dengan ayat-ayat”. Entah saya ataukah kedua penulis yang kuper dengan kehidupan anak-anak, abstraksi alam sebagai “ayat-ayat” bagi saya masihlah terlalu kompleks buat anak-anak.
Kata, nama, dan bahasa dalam proses pembentukan makna “tanda-petanda” baru dipelajari di bangku perkuliahan, dan bahkan secara khusus oleh mahasiswa bahasa dan filsafat. Padahal, banyak keluguan dan kepolosan anak yang masih bisa diangkat untuk mempertanyakan dan menggugat banyak hal. Tapi, mungkin bukan itu inti buku ini. Cerita anak-anak ini mungkin memang sejak awal diarahkan hanya untuk menjadi pengantar bagi penjelasan di bawahnya.
Tapi, di beberapa bagian, saya justru lebih tertarik kepada cerita daripada penjelasannya. Sebagai contoh, dalam “Main-main”, buku ini mengisahkan Hanoman kecil yang bisa mengelilingi bumi tujuh kali hanya dalam sekali lompatan. Tapi, saat beranjak dewasa, Hanoman tak bisa lagi melakukan kesaktian itu. Ini karena kedewasaan telah membatasi imajinasi atau rasa bermain-main Hanoman.
Bagi saya, ini menarik karena menggambarkan bahwa imajinasi—sesuatu yang seringkali coba “dibunuh” oleh otoritas persekolahan dan keagamaan—justru sumber dari inovasi, terobosan, dan penemuan-penemuan baru di banyak bidang. Tapi, penjelasan atas cerita ini malah lebih fokus memaparkan kehidupan sebagai permainan, dan lebih sempit lagi sebagai kompetisi. Padahal, saya memahami rasa bermain-main sebagai upaya memahami kehidupan secara lebih imajinatif; tak terpaku pada satu penafsiran dan terus mencoba berbagai kemungkinan, seperti rasa ingin tahu yang terus membuncah dalam diri seorang bocah.
Meskipun berupaya untuk bertutur asyik dalam membahas tema-tema pelik, bagian penjelasan buku ini justru tampak tak terlampau asyik. Di sini, buku ini justru terjebak dalam pembahasan filosofis yang kadang rigid dan berbelit-belit, bukan dari sisi penggunaan kata atau istilah tapi penuturan. Bagian narasi yang metaforis dan kadang dibumbui satire seakan menguap dalam tikungan-tikungan tajam paparan di bagian penjelasan. Alangkah lebih asyiknya jika bagian penjelasan pun bisa mengalir seperti bagian narasinya. Mungkin akan lebih baik jika keduanya tak dipisahkan tapi melebur, sehingga cerita di buku ini pun tak seakan diletakkan begitu saja hanya untuk mengantar kepada penjelasannya.
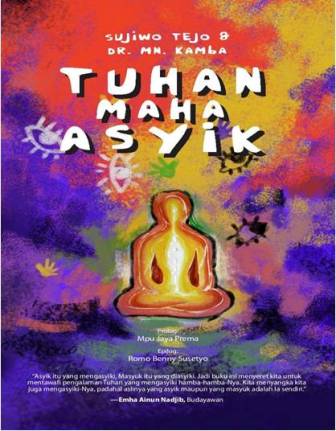
- Judul Buku: Tuhan Maha Asyik
- Penulis: Sujiwo Tejo dan MN Kamba
- Penerbit: Imania
- Terbit: November 2019 (Cetakan XIV)
- Tebal: 245 halaman
Buku ini menyajikan tema yang penting; bagaimana kehidupan keberagamaan seharusnya mempersatukan umat manusia, bukan malah memecah belahnya dan bahkan menimbulkan kebencian terhadap satu sama lain. Ini dimulai dengan mempertanyakan kembali pemahaman tentang Tuhan.
Apa yang manusia pahami tentang Tuhan pada dasarnya bersifat persepsional dan konsepsional. Pemahaman itu tak mampu menjelaskan Tuhan sebagaimana Dia adanya. Sebab, Tuhan Mahabesar dan Mahaluas daripada segala sesuatu; definisi, konsep, nama, dan bahkan sebutan tuhan itu sendiri. Membatasi Tuhan pada persepsi dan konsepsi yang kita pahami justru sebenarnya adalah kepongahan, dan bisa jadi telah mempersekutukan Tuhan.
Satu-satunya jalan manusia mengenal Tuhan adalah dengan mencintai-Nya. Dalam mencintai Tuhan, tak ada lagi jarak antara Tuhan dengan ciptaan-Nya; antara subjek dengan objek. Untuk mencintai Tuhan, manusia harus mengenal dirinya sendiri karena dirinyalah emanasi cahaya Tuhan.
Itulah mungkin cara kerja konsep “emanasi dan abstraksi” yang sepintas dijelaskan dalam buku ini. Ciptaan-ciptaan ada karena cahaya Tuhan menyinari meraka (emanasi), dan karenanya pengetahuan Tuhan akan ciptaan-ciptaan-Nya tak membutuhkan representasi. Demikian pulalah pengetahuan ciptaan-ciptaan-Nya akan Tuhan. Mereka tak membutuhkan representasi (nama, bahasa, pertanda) untuk menemukan Tuhan. Pengetahuan tentang Tuhan hadir melalui cinta (abstraksi).
Dan cinta kepada Tuhan, menurut kedua penulis, tidak bisa tidak harus melalui latihan-latihan peniadaan diri; penyucian diri dari hal-hal duniawi. Bak naluri seorang atlet yang rutin dilatih, sehingga mampu melakukan secara spontan gerakan-gerakan tertentu dan membaca pergerakan lawan, begitu pula seorang pejalan spiritual melatih intuisinya sehingga mampu menemukan Tuhan.
Seseorang yang mencintai Tuhan, menurut buku ini, akan mampu menginternalisasi ajaran-ajaran Tuhan dalam teks-teks suci. Keimanannya hening, tapi amal perbuatannya yang selaras dengan sifat-sifat ketuhanan nyaring bersuara. Karenanya, dia tak mudah membenci, baik dirinya sendiri yang mungkin hidup dalam kemalangan atau orang lain yang tak sepaham dengannya. Dia bisa menerima apa pun yang terjadi. Baginya, keburukan—yang dipahami sebagai ketidaksempurnaan kebaikan—hanyalah proses menuju kepada kebaikan. Penerimaan, dalam buku ini, menjadi penting untuk membuat kehidupan ini asyik.
Saya memahami “Tuhan Maha Asyik” sebagai “Tuhan Maha Pecinta”, dan karenanya manusia harus melalui cinta untuk menemukan Tuhan. Jika kembali menggunakan bahasa sebagai perangkat analisis, kata asyik sendiri bisa bermakna “tenggelam ke dalam sesuatu”. Entah apakah kata ini menyerap kata ‘isyq dalam bahasa Arab, ‘isyq juga bermakna “cinta yang sangat dalam”. Mungkin ini bisa menjelaskan mengapa Tejo dan Kamba memberi judul buku ini Tuhan Maha Asyik.
Uniknya, dalam bahasa Indonesia, asyik juga bermakna “menyenangkan”. Jadi, bisalah kita memaknai bahwa mencintai Tuhan itu seharusnya menyenangkan, dan bukan menyusahkan atau bahkan menyeramkan.[]