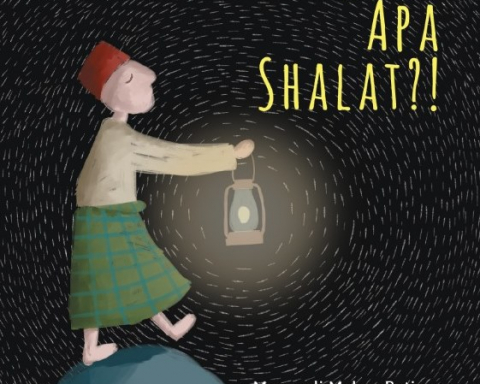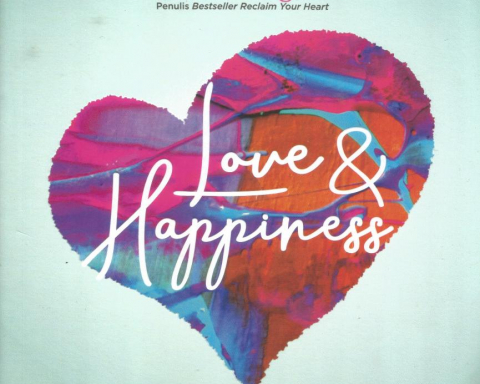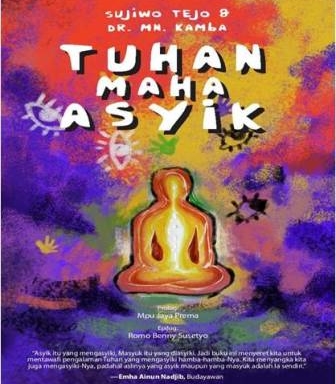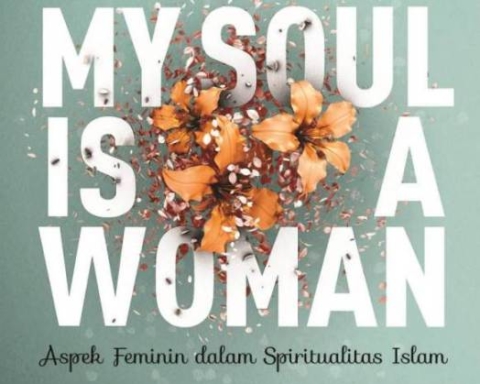Mengapa Jalaluddin Rumi memukau banyak orang dari beragam latar belakang melalui syair-syairnya? Dalam Belajar Hidup dari Rumi: Serpihan-serpihan Puisi Penerang Jiwa, Haidar Bagir menunjukkan itu karena, lewat syair, Rumi berbicara tentang kekuatan terdahsyat yang dimiliki manusia: Cinta.
Siapa saja yang berminat pada khazanah pemikiran Islam, khususnya bidang tasawuf, kemungkinan besar mengenal nama Jalaluddin Rumi. Maulana Rumi memang sangat populer, bahkan di luar lingkaran para peminat studi-studi Islam. Tidak kurang dari diva sekelas Madonna, Beyonce, aktris Goldie Hawn, Demi Moore, komposer Philip Glass, dan selebritas lain mengenal Rumi.
Tapi di situlah justru persoalan besarnya. Keterkenalan Rumi membuat puisi-puisinya yang penuh makna kerap disalahpahami. Ajaran-ajarannya berkembang menjadi popular belief, sedemikian sehingga tak sedikit orang menafsir atau membingkai sesuai seleranya sendiri. Orang-orang seperti itu lebih ingin menjustifikasi pemikiran dan keyakinannya sendiri ketimbang belajar dari sang sufi, penyair, ahli fiqih, teolog, dan mufasir agung ini.
Dalam konteks itulah agaknya buku Haidar Bagir Belajar Hidup dari Rumi: Serpihan-serpihan Puisi Penerang Jiwa ini menjadi relevan dan penting. Di tiap halamannya kita dituntun untuk belajar dari Rumi; bukan dari apa yang populer tentangnya, tapi dari potongan-potongan puisinya yang—setidaknya bagi sang penulis—paling mewakili pokok-pokok ajarannya.

- Judul: Belajar Hidup dari Rumi: Serpihan-Serpihan Puisi Penerang Jiwa
- Penulis: Haidar Bagir
- Penerbit: Mizania/Noura
- Tahun Terbit: 2015
- Tebal: xxxii + 293
Penulis mencoba menyusun, menerjemahkan, dan menafsirkan sederet potongan itu dengan tujuan membantu siapa saja yang ingin mengambil inspirasi dari Rumi. Memang ini bukan pekerjaan mudah, apalagi seperti diakui penulis, buku ini disusun dari rangkaian cuitan di Twitter. Dalam batas tertentu, buku ini mampu mengantar pembaca memahami kerangka utama ajaran-ajaran Rumi sekaligus memperkaya batin dan menerangi jiwa tiap pembacanya.
Untuk dapat menjadi buku panduan, Belajar Hidup dari Rumi mau tidak mau harus mampu merangkum pokok-pokok ajarannya. Penulis pun berusaha memungut saripati itu dari karya utama Rumi, yaitu Mastnavi-e Ma’navi (Kuplet Maknawi).
Mastnavi sendiri adalah karya besar yang terdiri dari sekitar 25.000 bait sajak. Karena itu, penulis cukup berhati-hati memilih potongan puisi yang mampu menggambarkan keutuhan pemikiran dan ajaran Rumi. Penulis pun lalu mengawali pilihan dari yang paling dasar, yakni dari kehidupan dan kematian kita sendiri. Puisi pertama buku ini, menariknya, entah disadari sejak awal atau tidak, semakna senada dengan puisi terakhir yang diawali dengan kalimat Pada hari kumati.
Potongan puisi pertama berjudul Aku mati sebagai mineral. Di situ Rumi berkisah tentang tahap-tahap perkembangan kehidupan. Penulis menyebutnya dengan ‘kisah evolusi manusia’, yakni kesinambungan gerak hidup dari satu tahap ke tahap lain tanpa henti. Mineral adalah titik tolak menuju ke fase tumbuhan, hewan, sampai jadi ‘manusia’. Lalu ‘manusia’ itu harus pula mati agar dia terlahir di alam malaikat (malakut) yang lebih tinggi, karena “Segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajah-Nya” (QS 28: 88). Setelah itu pun dia berlanjut memasuki kekosongan dan kesunyian, sampai terdengar suara: “Hanya kepada-Nyalah segala sesuatu kembali” (QS 2: 156).
Potongan pertama puisi ini sejatinya merupakan potongan yang kerap dikutip dalam menggambarkan ajaran Rumi tentang kematian sebagai tahapan kehidupan abadi, sebuah prinsip yang sebenarnya juga merupakan salah satu pokok ajaran Islam. Misalnya, dalam surah Al-Waqi’ah, Allah berfirman: “Kami telah menentukan kematian di antara kalian dan Kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kalian dengan orang-orang yang seperti kalian (di dunia) dan menciptakan kalian kelak dalam keadaan yang tidak kalian ketahui” (QS 56: 60-61).
Dalam puisi ini Rumi ingin menyampaikan bahwa kematian tiada lain kecuali suatu proses, suatu perpindahan menuju tahap-tahap berikutnya. Karena itulah, seperti kata Rumi, buat apa takut mati, buat apa merasa hilang dan ada yang pergi? Bagi yang menyadari kehidupan sebagai proses yang tiada berhenti, kematian justru momen pembebasan yang melegakan.
Rumi menyebut inilah makna dari inna ilayhi raji’un. Lalu, seperti ayat dalam surah Al-Waqi’ah di atas, Rumi bersyair: “Setelah itu aku masih harus mati dan menjelma sesuatu yang tak bisa kupahami. Ah, biarkanlah diriku lenyap memasuki kekosongan, kesunyian.” Terjemahan lain dari potongan puisi itu bisa seperti ini: “Lalu aku akan jadi ketiadaan, sebab ketiadaan akan berdendang bak organ, ‘Sesungguhnya hanya kepada-Nyalah segala sesuatu kembali’.”
Berangkat dari ajaran evolusi ruhani ini, penulis lalu mengutip tamsil seruling dari Rumi. Ini tamsil ihwal derita keterpisahan yang takkan reda kecuali dengan perjumpaan, peleburan, dan penyatuan kembali. Jeritan seruling itu, kata Rumi, adalah api, bukan angin. Itulah api yang akan mengobarkan gairah perjumpaan; luapan energi yang tak pernah padam.
Melalui metafora seruling ini Rumi ingin menggambarkan suka-duka perjalanan orang yang terpisah dari asalnya dan bertekad kembali kepadanya. “Jiwaku,” kata Rumi, “dari suatu negeri di sana. Di sana juga kumau berakhir.” Di tempat lain Rumi bersyair, “Wahai Kekasih, ambillah apa-apa yang kumaui, ambillah apa-apa yang kulakukan, ambillah apa-apa yang kubutuhkan, ambillah semua yang mengambilku dari-Mu.” Dan seperti itulah hakikat Cinta—kata yang senantiasa menghiasi sajak-sajak Rumi.
Tapi Cinta bagi Rumi jelas bukan semata bersifat ragawi, sehingga menjadi terlalu sementara dan terbatas. Cinta Rumi mencakup yang ragawi dan yang di luar raga, manusiawi dan yang di luar manusia, duniawi dan yang surgawi, dan segala yang ada di antara keduanya. Cinta di sini adalah samudra Tuhan yang mencakup permulaan sekaligus pengembalian, kehidupan sekaligus kematian, siklus yang terus-menerus tanpa batas. Rumi bersyair, Cinta adalah samudra Tuhan tak bertepi. Tapi, betapa mengherankan, ribuan jiwa tenggelam di dalamnya sambil berteriak lantang, ‘Tuhan tidak ada!’”
Cinta ini, dengan kata lain, adalah manifestasi Tuhan itu sendiri. Ia ada di mana-mana, bersama segala-galanya. Selain-Nya hanya ilusi yang muncul akibat kurangnya perhatian dan kesadaran. Perhatikan syair Rumi ini, “Wahai para pencinta, mau ke mana kalian? Siapa yang kalian cari? Kekasihmu ada di sini.” Lalu dia juga bersajak, “Kau berjalan ke sana kemari menunggang kudamu, dan bertanya ke setiap orang: ‘Mana kudaku?’” Dalam Cinta ini, yang lain adalah kealpaan dan kesirnaan. “Beginilah keinginanku tuk sirna dalam cintaku kepadamu: bak awan larut dalam cahya mentari.”
Haidar tak ayal berhasil meramu potongan-potongan puisi Rumi dalam buku kecil ini menjadi panduan hidup atau self-help ala Rumi. Pilihan puisi dalam buku ini begitu tertib mengungkap intisari Rumi, yakni Cinta sebagai awal, proses, dan tujuan. Pesan dan kesan utamanya pun tetap terkait dengan Cinta, karena apa yang di luar Cinta sebetulnya tidak ada. Dan yang tak kalah pentingnya, melalui buku mungil ini, penyusun membawa kita lebih dekat dan intim dengan Rumi, tanpa pretensi menggurui atau memaparkan seluruh kandungan makna dalam tiap potongan puisi yang dicantumkannya.
Setelah meraih respons antusias dari khalayak pembaca, Haidar kemudian menyusun buku lanjutan dengan judul Dari Allah Menuju Allah: Belajar Tasawuf dari Rumi. Buku kedua ini dapat disebut sebagai syarah dan pendalaman atas buku yang pertama. Meski tetap ringan dan ringkas, buku kedua tersusun dari serangkaian kuliah yang bersumber dari potongan-potongan puisi buku pertama. Dan karena alasan itu, buku kedua ini terkesan baku, sedangkan buku pertama yang diulas di sini terasa lebih intuitif—sesuatu yang mungkin dapat segera pembaca lihat dari pilihan diksi, gaya penyusunan dan desain buku.[]
(Foto utama: kompleks makam Jalaluddin Rumi di Konya, Turki, oleh Emad Nemati. Sumber foto: Wikimedia.org)