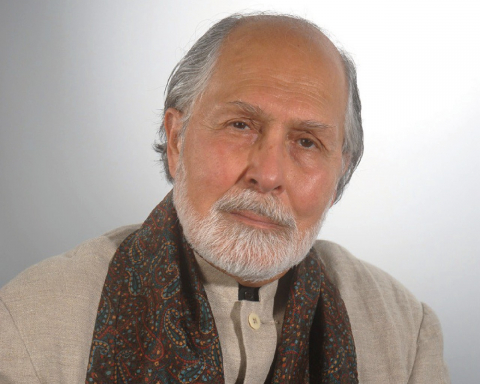The Plagues of Breslau bukan semata film thriller kejahatan. Ia juga mempertanyakan moral di balik vigilantisme. Apakah bertindak di dalam hukum selalu bermoral? Apakah beraksi di luar hukum selalu tidak bermoral?
LIMA pembunuhan terjadi dalam sepekan di Wroclaw, Polandia. Semuanya dilakukan secara spektakuler, dikemas menjadi tontotan publik. Tiap-tiap tubuh korban dicap dengan besi panas: “kemerosotan”; “penjarahan”; “penyuapan”; “fitnah”; dan “penindasan”.
Sutradara-penulis Polandia, Patryk Vega, menambah dosis daya tarik The Plagues of Breslau (Plagi Breslau) dengan karakter aneh dua detektif perempuan. Helena Rus (Malgorzata Kozuchowska) selalu memasang wajah murung, jarang bicara, dan berpenampilan mirip lady rocker: jaket kulit, sepatu bot, dan potongan rambut asimetris. Iwona Bogacka (Daria Widawska) banyak cakap tapi lidahnya sepahit empedu. Penampilannya juga tak kalah ganjil: bertopi pet dengan sweater dan celana training seperti orang mau joging.

- Judul Film: Plagi Breslau (The Plagues of Breslau)
- Sutradara: Patryk Vega
- Penulis: Patryk Vega
- Pemain: Malgorzata Kozuchowska, Daria Widawska
- Rilis: November 2018; April 2020 (Netflix)
- Durasi: 93 menit
Baik Helena maupun Iwona mempunyai sisi gelap yang menyatukan keduanya, dan menjadi dasar bagi plot twist film ini. Sisi gelap tokoh “hero” dalam tradisi literasi realisme Barat sangat lazim meskipun Polandia sebenarnya lama menjadi satelit realisme sosialis Soviet yang kerap menampilkan protagonis sebagai pribadi ideal, bermoral, dan tangguh.
Dari Iwona, kita kemudian mengetahui modus lima pembunuhan tadi merujuk kepada sejarah Breslau, nama kuno Wroclaw. Frederick Yang Agung, penguasa Prussia, menduduki kota itu pada pertengahan Abad ke-18. Raja Jerman dari Dinasti Hohenzollern ini bertekad membersihkan Breslau dari “wabah” amoral: kemerosotan, penjarahan, penyuapan, fitnah, penindasan, dan penyimpangan. Algojo Frederick dalam sepekan menghabisi siapa saja penduduk yang dianggap mengidap wabah itu; tanpa pengadilan.
Bagi penggemar thriller psikologi kriminal, tema tersebut membawa ingatan kepada karya terkenal David Fincher: Seven (1995). Dua detektif, William Somerset (Morgan Freeman) dan David Mills (Brad Pitt) memburu pembunuh berantai, John Doe (Kevin Spacey), yang beraksi berdasarkan tujuh dosa besar besar menurut ajaran Kristiani: kesombongan; keserakahan; kedengkian; kemarahan; nafsu birahi; kerakusan; dan kemalasan.
Tapi, The Plagues of Breslau tak berhenti di situ. Ia memasuki wilayah yang tak dijelajahi Seven: persoalan tentang moralitas vigilante.
Kata vigilante merujuk kepada orang atau sekumpulan orang yang mengambil langkah di luar hukum terhadap mereka yang dianggap pelaku kejahatan karena impotensi sistem peradilan. Vigilante dengan kata lain mengambil hukum ke tangannya sendiri. Dia penyidik, jaksa, hakim, dan sekaligus eksekutor. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenalnya dengan “main hakim sendiri”.
Tema ini juga bukan hal baru. Film-film Barat, khususnya Hollywood, penuh sesak dengan karakter vigilante berlabel “hero”. Tony Stark (Iron Man) menciptakan mesin perusak karena ingin mengamankan dunia dari penjahat super. Frank Castle (The Punisher) membuat bonyok dan meledakkan para mafia karena penegak hukum korup dan sudah terbeli. Robert McCall (The Equalizer) menghabisi para pembunuh dan pemerkosa karena ingin membawa rasa keadilan kepada para korban.
Kita tahu aksi-aksi mereka melanggar hukum. Tapi, kita memaafkan dan bahkan bersimpati kepada para vigilante tersebut. Sebab, rasanya ada dahaga akan keadilan yang terpuaskan. Ada kejahatan yang terbayar lunas.
Dalam The Plagues, ketika dikonfrontasi oleh Helena, si pembunuh berantai balik bertanya, “Siapa mereka (korban pembunuhan)?” Mereka adalah mandor yang menindas pekerja; lintah darat yang menangguk keuntungan berlipat dari riba; pejabat keuangan yang menerima suap; polisi korup; dan pengembang yang mengusir penduduk dari rumah karena mereka tak mampu bayar sewa.
Filsuf deontologis tak pernah bisa menjustikasi vigilantisme. Banyak argumen deontologis yang bisa diajukan untuk menolak vigilantisme: tak memenuhi prinsip due process (vigilante tak mengajukan bukti kejahatan; korban mereka tak mendapatkan kesempatan membela diri); melanggar prinsip demokrasi (menghilangkan hak orang lain; vigilante bukan orang yang dipilih untuk menegakkan hukum); dan akhirnya bisa merusak kepercayaan sosial (menjadi preseden bagi tiap-tiap orang untuk melakukan hal yang sama atau membalas aksi vigilante dengan cara serupa).
Keberatan-keberatan Kantian (filsuf deontologi) di atas bisa disimpulkan dalam proposisi: vigilante merusak hukum untuk menegakkan hukum. Bagi mereka, proposisi itu jelas kontradiktif. Vigilante tak bisa berdalih ia melawan kejahatan sementara pada saat yang sama berkontribusi kepada kejahatan. Menurut argumen Kantian, vigilantisme selalu irasional dan karenanya tak bisa diterima secara moral.
Ada dua dalih bantahan yang bisa diajukan terhadap argumen Kantian.
Pertama, hukum tak selalu merepresentasikan prinsip moral. Teori nature law, yang antara lain dikemukakan Thomas Aquinas, mengatakan hukum positif tidak akan dipandang valid kecuali ia bersesuaian dengan prinsip moral (nature law) meskipun hukum positif itu dilahirkan oleh orang-orang yang dipilih secara demokratis.
Kedua, sejarah mencatat tak sedikit vigilantisme berlangsung dalam kondisi hukum yang sudah impoten, entah itu karena korupsi ataupun diskriminasi. Sejarah perlawanan penduduk di tanah jajahan adalah contoh vigilantisme. Ia terjadi di bawah kondisi hukum kolonial yang menindas. Jadi, proposisi vigilante merusak hukum justru tak bisa diterima secara rasional dalam kondisi hukum yang tak memenuhi prinsip moral. Tak mungkin seseorang merusak sesuatu yang sudah rusak.
Vigilantisme karenanya bisa dijustifikasi hanya dalam kondisi sangat tertentu. Ia juga seharusnya menjadi opsi terakhir.
Dalam kondisi-kondisi amat terbatas tersebut, vigilantisme tak bisa dikatakan sebagai “tujuan menghalalkan cara”. Sebab, cara ideal untuk mencapai tujuan justru merintangi dan menutupi jalan pencapaiannya. Tak sedikit hukum positif yang kenyataannya malah mengorbankan keadilan. Dalam kondisi seperti ini, memaksa korban ketidakadilan untuk mematuhi hukum positif tak beda dengan meminta mereka tunduk kepada penindasan. Justru sangat alamiah dan rasional ketika mereka kemudian memilih langkah di luar hukum.
Tapi, vigilantisme tak bisa berlangsung selamanya. Ia bisa merusak kepercayaan sosial. Dalam konteks ini, vigilante seharusnya berkontribusi kepada pembangunan sistem baru yang jujur dan adil.
Dalam The Dark Knight (Christopher Nolan, 2008), Batman memahami hal ini. Dia harus “menghilang” agar sistem peradilan kembali berjalan normal. Dia bahkan menyadari seorang vigilante tak bisa dipuja-puja publik. Ia harus dikriminalkan, sehingga rela menanggung beban tuduhan kejahatan agar seorang jaksa idealis yang berubah jahat, Harvey Dent, tetap dipuja sebagai pahlawan. Ini akhir paling epik yang pernah dibuat dari sebuah film superhero.
Vega juga secara tersirat mengajukan argumen serupa. Si pembunuh menampilkan aksinya secara spektakuler agar publik dan politisi berkuasa tahu alasan di balik kejahatannya. Dia juga memutuskan bunuh diri. Sebab, ia sadar telah menyimpang dari moralitas. “Penyimpangan” adalah wabah amoral keenam yang ingin dibasmi Frederick. Dan, si penyimpang itu adalah si pembunuh itu sendiri.
The Plagues karenanya bukan semata thriller psikologi kriminal. Di sepertiga akhir durasinya, ia berubah menjadi thriller politik.[]