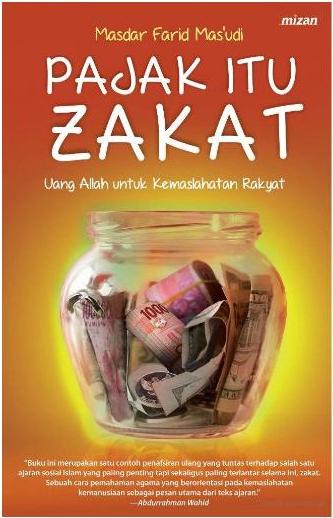Dalam buku ini, Masdar Farid Mas’udi memandang bahwa ajaran zakat itu sebenarnya adalah ruh etik sementara tubuh pelembagaannya adalah pajak. Sebab, Rasulullah dalam praktiknya tak pernah menerima dikotomi zakat dan pajak.
MENJELANG lebaran, kita biasanya akan mendapati berbagai kampanye untuk berzakat, entah itu zakat harta atau fitrah. Lembaga-lembaga amil zakat atau para dai biasanya akan mengatakan bahwa zakat akan memberdayakan umat.
Mereka tak jarang juga mengutip data hasil survei yang menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 233,84 triliun rupiah (dengan 59,47 persennya atau 139,07 triliun rupiah adalah zakat penghasilan). Tapi sayangnya, dari potensi tersebut, baru 10,16 triliun, atau 4,34 persen, yang berhasil dikumpulkan lembaga-lembaga amil zakat.
Itu berarti, menurut mereka, umat Islam belum sepenuhnya sadar akan kewajiban zakat. Umat juga dianggap baru mengetahui kewajiban zakat semata-mata zakat fitrah di bulan Ramadhan. Sebagian umat yang kaya raya juga tak jarang membagikan zakat atau sedekahnya secara langsung kepada fakir-miskin tanpa melalui lembaga-lembaga amil yang ada, sehingga pemanfaatan dana zakat tak maksimal.
Dalam bukunya Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat, Masdar Farid Mas’udi menolak larut dalam retorika di atas. Cendekiawan Nahdlatul Ulama itu bahkan menilai retorika semacam itu menunjukkan kejumudan umat dalam memandang dan mempraktikkan zakat.
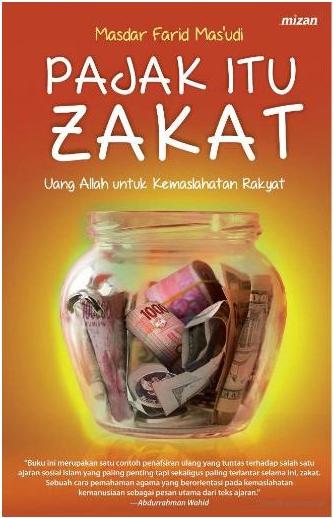
- Judul buku: Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat
- Penulis: Masdar Farid Mas’udi
- Penerbit: PT Mizan Pustaka
- Terbit: Agustus, 2010
- Tebal: 257 halaman
Retorika zakat seperti di atas, bagi Masdar, adalah cara pandang dogmatik-ritualistik terhadap konsep zakat dalam ajaran Islam. Cara pandang tersebut hanya terobsesi mengabadikan “hadis” Nabi Muhammad tapi mengabaikan pelestarian “Sunnah” Nabi.
Di sini, Masdar membedakan antara “hadis” dan “Sunnah”. “Hadis” adalah riwayat formal dan verbal tentang apa yang diucapkan, dilakukan, dan ditetapkan Nabi sedangkan “Sunnah” merupakan spirit dan substansi di balik ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi.
Bagi Masdar, yang abadi dan perlu dilestarikan dari ajaran Nabi Muhammad adalah spirit dan ruhnya, bukan semata bunyi formal-verbal hadis-hadisnya. Jika ini yang dilakukan, maka umat Islam tidak akan terperangkap dalam kejumudan dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Masdar pun menyarankan cara pandang seperti itu dalam mengkaji dan mempraktikkan konsep zakat. Kita, menurutnya, harus menggali nilai kontekstual dan historis dari praktik zakat di zaman Nabi. Jika itu tidak dilakukan, maka konsep zakat yang kita pahami dan praktikkan akan mengandung tiga kelemahan sekaligus: kelemahan filosofis, kelemahan pelembagaan, dan kelemahan operasional—dan inilah yang terjadi selama ini.
Dalam Pajak Itu Zakat, Masdar mengajukan premis bahwa zakat itu sebenarnya adalah ruh etik dan moral. Pelembagaannya atau tubuhnya bisa berbentuk apa saja, termasuk bahkan lembaga pajak di era negara-negara modern saat ini. Operasionalnya pun tidak bisa diserahkan kepada lembaga-lembaga amil partikelir—yang tak jarang berafiliasi dengan kelompok tertentu—tapi harus berada di tangan negara.
Premis Masdar berangkat dari penelaahannya terhadap praktik zakat di awal Islam—periode Nabi dan empat khalifah setelahnya. Pada masa tersebut, pengelolaan zakat dalam wujud kelembagaannya tidak lain adalah apa yang dalam administrasi kenegaraan saat ini dikenal sebagai pajak itu sendiri. Ia berada di bawah tanggung jawab pemerintah: dipungut dan dikelola oleh pemerintah.
Pada masa itu juga, kepercayaan umat kepada pemerintahan sangat besar. Pemerintahan benar-benar berorientasi kepada kepentingan rakyat. Zakat yang dikumpulkan benar-benar dibelanjakan untuk memenuhi tuntutan keadilan bagi yang lemah dan kemaslahatan bagi semua.
Namun seiring waktu, pemerintahan pada masa sesudahnya—dimulai sejak Mu’awiyah—dibangun atas dasar kekuatan dan dipertahankan dengan sistem pewarisan yang dilembagakan. Pemerintahan pada masa-masa ini lebih berorientasi kepada kepentingan penguasa dan segelintir elite.
Perubahan corak pemerintahan ini telah melahirkan reaksi dari kalangan rakyat. Rakyat yang semula bersikap partisipatif lalu berubah menjadi rakyat yang sebagian besarnya apatis dan sebagian kecilnya melawan.
Implikasi dari perkembangan politik itu adalah kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan yang mengelola zakat (pajak) makin lama makin pudar. Umat tidak bisa diyakinkan bahwa kewajiban zakat yang mereka tunaikan dengan niat luhur karena Allah akan dibelanjakan untuk tujuan yang dikehendaki Allah.
Demikianlah perlahan-lahan penanganan zakat makin tercabut dari tangan pemerintahan atau negara. Dengan lepasnya zakat dari pengelolaan pemerintahan, zakat pun akhirnya dipahami sebagai konsep kelembagaan yang berdiri sendiri di luar lembaga pajak dan negara. Padahal, seperti telah dipaparkan, zakat pada mulanya merupakan konsep keruhanian untuk tubuh bernama “pajak”.
Alhasil, jika beberapa waktu lalu Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah kalangan ngotot menggolkan Undang-Undang Zakat (dan berhasil pada 2011), maka mereka sebenarnya telah makin menyempurnakan pemisahan ruh zakat dari praktik kenegaraan dan pemerintahan—sesuatu yang justru menyalahi praktik zakat pada masa Nabi dan empat khalifah sesudahnya.
Penyapihan zakat dari praktik kenegaraan juga telah memunculkan ketidakadilan. Zakat hanya digunakan untuk melindungi dan melayani umat Islam. Padahal, pada masa Nabi, zakat dimanfaatkan untuk melayani rakyat yang paling lemah dan publik secara umum tanpa memandang agama.
Selain itu, penghimpunan dana keagamaan (zakat) di satu sisi dan dana kenegaraan (pajak) di sisi lain berarti dualisme pelembagaan antara “agama” dan “negara”. Keduanya berjalan terpisah dari satu sama lain. Jika logika ini dituruti, itu berarti munculnya “negara agama” (dengan dana zakatnya) di dalam “negara sekuler” (dengan pajaknya).
Sejumlah kalangan mungkin bisa menerima pemisahan seperti di atas. Namun, praktik pada masa Nabi dan empat khalifah sesudahnya, menurut Masdar, sebenarnya tidak pernah bisa menerima dikotomi seperti itu.
Di sisi lain, menurut Masdar, konsep zakat sebenarnya mengoreksi konsep “kontraprestasi” dalam lembaga pajak modern yang berlaku pada masa sekarang. Pajak-kontraprestasi secara moral mendefinisikan negara sebagai penjual jasa kepada para pembayar pajak, terutama pembayar pajak paling besar.
Kalangan kaya yang membayar pajak besar merasa berhak mendapatkan imbal-jasa kenegaraan yang besar. Kalangan lain yang membayar pajak kecil harus puas dengan jasa kenegaraan yang kecil. Rakyat miskin yang tidak mampu membayar pajak harus menerima nasib tidak dipedulikan oleh negara, kecuali sekadar menikmati tetesan berkah (trickle down-effect) dari kedermawanan belaka.
Padahal, negara dibentuk untuk memenuhi hak-hak rakyatnya, terutama yang paling lemah dan tak mampu membayar pajak. Pajak-kontraprestasi pada gilirannya secara struktural akan terus melanggengkan ketimpangan sosial karena menjadikan negara alat kaum elite semata, baik itu elite politik maupun ekonomi.
Dengan konsep zakat, Islam menunjukkan bahwa sebagian besar dana pajak harus dianggarkan dan dibelanjakan untuk kepentingan lapisan terbawah rakyat. Dalam Surah Al-Taubah ayat 60, Allah menjelaskan kepada siapa pajak-zakat itu diperuntukkan. “Sesungguhnya pajak-pajak itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amilin, para mualaf, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan ibn sabil, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”
Dari ayat di atas, Masdar berpendapat, terdapat delapan kelompok pemilik objektif uang negara dari pajak-zakat. Enam di antaranya adalah lapisan rakyat yang paling terpinggirkan: fakir, miskin, budak (kelompok tertindas), orang-orang terbelit utang, ibn sabil (tunawisma dan pengungsi), dan muallaf (penghuni penjara atau suku terasing). Hanya dua sektor yang secara jelas mewakili kepentingan umum, termasuk di dalamnya kepentingan kelompok warga yang sudah mampu, yakni sektor amilin (biaya rutin pemerintahan) dan sabilillah (keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta pengadaan sarana dan prasarana publik).
Dengan demikian, jika dalam wacana zakat disebut kepentingan rakyat, yang dimaksud adalah kepentingan segenap warga dengan prioritas lapisan masyarakat yang paling tidak berdaya.
Dalam konteks negara modern, delapan kelompok atau sektor itulah yang seharusnya menjadi patokan dalam penyusunan anggaran belanja, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada angka-angka anggaran belanja inilah, pemihakan negara kepada rakyat, khususnya yang kurang mampu, akan terlihat.
Oleh karena itu, Masdar berpandangan ruh ajaran zakat harus diinjeksikan ke dalam sistem perpajakan saat ini. Inilah yang harus dilakukan, dan bukan malah menuntut pelembagaan eksklusif zakat (di antaranya melalui undang-undang khusus zakat) sehingga zakat menjadi tubuh sendiri yang terpisah dari praktik kenegaraan.
Dengan mengajukan pandangan tersebut, Masdar tampaknya telah menyelesaikan dua problem sekaligus: problem pengelolaan zakat dan pajak. Di satu sisi, zakat yang menjadi acuan etik bagi sistem perpajakan akan memiliki dampak yang signifikan bagi rakyat karena dikelola penuh oleh negara. Di sisi lain, problem ketidakadilan yang inheren dalam logika pajak-kontraprestasi bisa dihapuskan karena anggaran akan dirancang sesuai dengan spirit zakat, yakni pemihakan kepada lapisan rakyat terlemah.
Masdar kemudian juga mengajukan penafsiran progresif terhadap detail penerapan pajak berkonsep zakat tersebut. Misalnya, dia mengusulkan tarif pajak-zakat agar disesuaikan dengan tantangan keadilan dan ketimpangan pada masa sekarang. Artinya, tarif pajak-zakat bisa ditentukan lebih besar daripada tarif pada masa Nabi atau tarif pajak-zakat pada masa Nabi ditetapkan sebagai tarif minimum.
Masdar juga menafsirkan delapan golongan pemilik (mustahiq) pajak-zakat yang mesti menjadi sasaran dalam alokasi anggaran negara. Dia mengelompokkan kedelapan mustahiq itu menjadi tiga sektor besar: (1) sektor pemberdayaan masyarakat lemah (fakir, miskin, muallaf, budak, orang berutang, dan ibn sabil); (2) sektor biaya rutin (amil); dan (3) sektor sabilillah (layanan publik).
Yang terpenting bagi Masdar, pajak berkonsep zakat harus memiliki ruh etika dari ajaran zakat itu sendiri. Yaitu, pemihakan yang tak kenal kompromi kepada rakyat lemah.[]