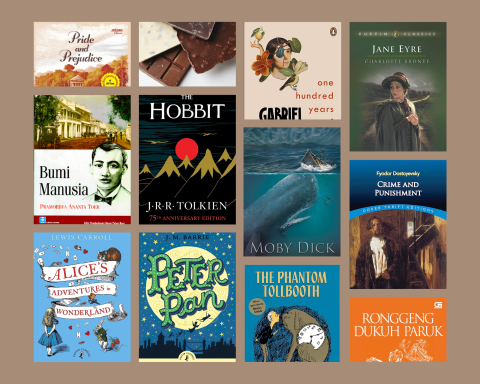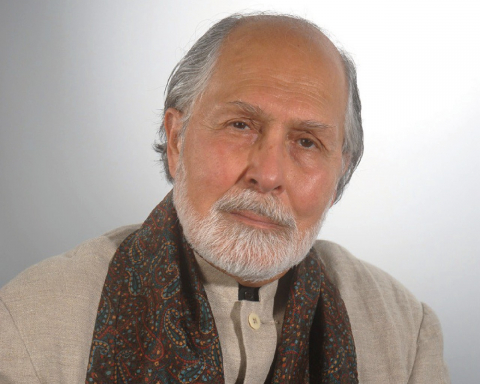Sebuah riset menunjukkan membaca memiliki kekuatan mengatasi masalah kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Persoalannya, sampai sejauh mana kepedulian kebijakan publik di negara ini bagi aktivitas literasi?
Saat menjenguk keluarga atau teman yang sedang sakit, apa yang biasanya anda bawa? Jawaban paling populer mungkin makanan, buah-buahan, atau bunga.
Tapi, mulai saat ini ada baiknya Anda membawa buku.
Sebuah laporan penelitian (A Society of Readers, 2018) yang disusun institusi riset Demos dan lembaga amal asal Inggris, Reading Agency, menyimpulkan bahwa membaca bisa membantu mengatasi gangguan kesehatan mental, problem mobilitas sosial, kesepian, dan bahkan mencegah demensia. Saking pentingnya membaca, laporan itu bahkan menyarankan Pemerintah Inggris menambah anggaran untuk aktivitas literasi (pengadaan buku, perpusatakaan, dan program membaca) hingga 200 juta paun (sekitar tiga triliun rupiah).1“Government should invest £200 million in reading to combat loneliness, new report recommends”. Readingagency.org.uk. Diakses pada 20 Desember 2019.
Di Inggris, kesepian memang persoalan bagi kesehatan mental penduduknya, terutama mereka yang memasuki usia lanjut. Bahkan di negeri itu, salah satu posisi kabinet adalah “Minister for Loneliness”. Kesepian disebut bakal menjadi epidemi kesehatan mental pada 2030. Nah, A Society of Readers mengajukan membaca sebagai salah satu solusi mengatasi problem itu.
Membaca, kata riset itu, bisa membebaskan kesadaran manusia dari penjara ruang dan waktu; meneleportasinya kepada kesadaran orang lain atau banyak orang. Dengan membaca, kita saling berbagi kemanusiaan dengan siapa pun, kapan pun, dan di mana pun. Kita menjadi tak merasa sendiri. Kita bisa merasakan bahwa kondisi yang kita alami juga dialami orang lain dan merasakan kondisi orang lain yang belum pernah kita alami; berempati dan bersimpati.
Riset juga menyebut kaitan antara membaca dengan tingkat kesejahteraan sosial; kebahagiaan hidup. Membaca bisa membangkitkan keterampilan hidup (life skill), sehingga orang memiliki peluang lebih besar dalam pelbagai sektor kehidupan. Singkatnya, kata laporan itu, untuk membangun masyarakat yang lebih produktif, kreatif, dan berkeadilan, maka akses kepada aktivitas literasi mesti dibuat universal, atau bisa dinikmati siapa pun terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi.
Luar biasa, bukan? Betapa sebuah aktivitas yang tampaknya remeh temeh itu bisa menjadi salah satu solusi bagi problem yang kelihatannya berskala besar.
Sebenarnya riset Demos dan Reading Agency bukan temuan yang sama sekali baru. Sudah sejak lama orang menyadari bahwa membaca memiliki kekuatan menyembuhkan luka jiwa, dan pada gilirannya luka tubuh. Bahkan, istilah biblioterapi pertama kali disebut pada 1914 oleh seorang pendidik, pengarang, dan pendeta asal Amerika Serikat bernama Samuel McChord Crothers.
Pada Perang Dunia I, aktivis-pustakawan asal Inggris, Helen Mary Gaskell, merintis apa yang kemudian dikenal dengan “war library”. May — demikian Helen biasa disapa — menggalang dana dan donasi buku untuk menjadi bacaan para serdadu yang terluka. May dan teman-temannya meyakini bahwa salah satu cara mempercepat penyembuhan luka fisik adalah dengan mengobati luka pikiran dan jiwa akibat trauma. Membaca, menurut mereka, bisa mendatangkan “arus kenyamanan” dalam pikiran.
May dan “war library-nya” mendapat sambutan positif, terutama dari Palang Merah Internasional. Sejak 1915, perpustakaan yang diinisiasi May diadopsi di mana-mana: di Amerika, Perancis, Mesir, dan Malta.2Sarah Haslam, Edmund King, dan Siobhan Campbell. 15 November 2018. “Bibliotherapy: how reading and writing have been healing trauma since World War I”. Theconversation.com. Diakses pada 20 Desember 2019.
Sedadu yang terluka rupanya bisa menjaga kewarasan pikiran mereka dengan membaca. Mereka pun lebih terbuka berbagi perasaan di antara sesama mereka saat memperbincangkan buku favorit mereka masing-masing.
Saat ini, tampaknya tingkat literasi suatu bangsa menunjukkan level kebahagiaan mereka. Lihat saja Indeks Kebahagiaan Dunia 2019 yang baru-baru ini dirilis United Nations Sustainable Development Solutions Network. Empat bangsa terbahagia di dunia ini adalah (1) Finlandia; (2) Denmark; (Norwegia); dan (4) Islandia. Keempat bangsa Nordik ini, menurut riset Central Connecticut State University di Amerika, berada di peringkat teratas dalam perilaku literasi: Finlandia (1); Denmark (4); Norwegia (2); dan Islandia (3).
Lalu bagaimana dengan kita, warga Indonesia?
Dalam Indeks Kebahagiaan Dunia 2019, kita tampaknya kurang bahagia — untuk tidak menyebut tidak bahagia sama sekali. Kita berada pada peringkat ke-92 dari 156 negara yang disurvei. Tingkat perilaku literasi kita pun sama jeblok, cuma berada di peringkat ke-60 dari 61 negara.
Indeks Kebahagiaan yang dirilis PBB memang tidak menjadikan riset Central Connecticut State University soal perilaku literasi sebagai acuan. Tapi, tampaknya ada hubungan antara minat baca dengan kebahagiaan hidup suatu bangsa, sebagaimana ditunjukkan oleh laporan riset Demos di atas.
Tingkat kunjungan perpustakaan di Indonesia terbilang sangat rendah, padahal perpustakaan semestinya menjadi tempat di mana aktivitas literasi berlangsung demokratis. Siapa pun — entah Anda anak taipan atau cuma anak buruh — bisa membaca dan mendiskusikan buku apa pun yang Anda suka di perpustakaan. Di Jakarta, misalnya, tingkat kunjungan perpustakaan hanya 400 ribu orang per tahun. Itu artinya kurang dari satu persen penduduk Jakarta yang mengunjungi perpustakaan tiap tahunnya. Bandingkan, misalnya, dengan Helsinki (6,2 persen); London (3,9 persen), New York (2,4 persen), dan Seoul (11 persen).
Kepedulian publik di Indonesia terhadap persoalan ini juga tak cukup besar. Tak banyak politisi atau aktivis yang gencar memelototi berapa uang rakyat yang dialokasikan pemerintah untuk aktivitas literasi. Kita juga mungkin tak bakal membayangkan orang-orang berunjuk rasa di jalanan menuntut peningkatan anggaran untuk perpustakaan. Bahkan, ketika aparat negara melarang buku dan membubarkan perpustakaan keliling, tak banyak orang yang peduli.
Tapi di Inggris, belum lama ini orang berdemo karena pemerintahnya memotong anggaran perpustakaan. Bagi mereka, pengurangan anggaran perpustakaan bukan semata hilangnya kemampuan perpustakaan menambah koleksi buku. Lebih daripada itu, kebijakan tersebut akan menutup peluang warga negara untuk hidup lebih baik, lebih setara, lebih demokratis, dan tentu saja lebih bahagia.3Arifa Akbar. 5 November 2018. “If books can cure loneliness why are we closing libraries?”. Theguardian.com. Diakses pada 20 Desember 2019.
Sumber foto: The Guardian.