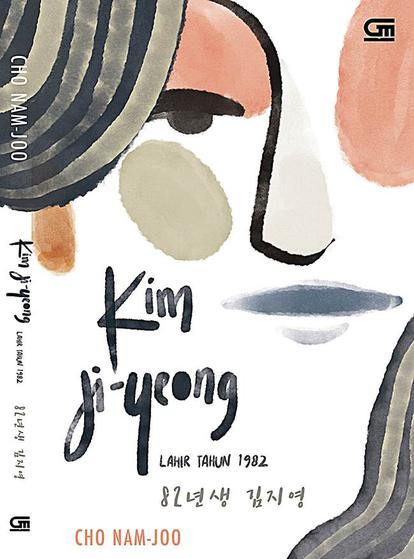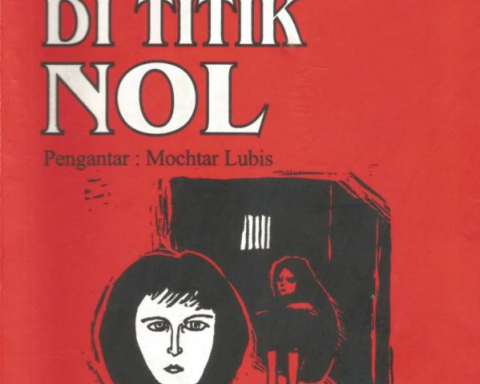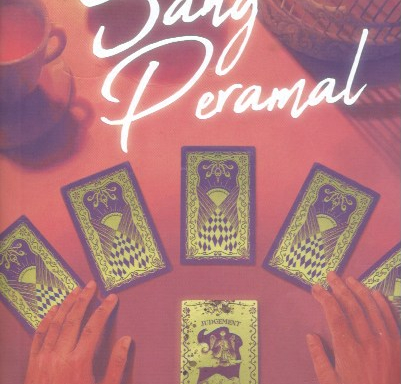Kim Ji-yeong, Lahir Tahun 1982 karya yang memicu kontroversi di Korea Selatan, baik saat terbit sebagai novel maupun ketika diangkat ke layar lebar. Novel ini mengisahkan perempuan biasa yang memikul beban pertanyaan tak biasa: gugatan terhadap “agama” bernama “kodrat wanita” dan “naluri keibuan”.
KOREA di tahun 1982. Orang tua lebih menyukai anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Para menantu perempuan akan merasa malu dan bersalah jika tak memberi mertua mereka cucu laki-laki.
Di tahun itulah, Kim Ji-yeong lahir. Sang ibu memeluknya seraya meminta maaf kepada ibu mertua karena sekali lagi melahirkan cucu perempuan. “Tidak apa-apa. Anak ketiga mungkin laki-laki,” kata si ibu mertua, enteng saja; tak memberi selamat atas kelahiran cucu keduanya.
Belum genap setahun usia Ji-yeong, ibunya kembali hamil. Malang, janin yang dikandung sekali lagi perempuan. Kali ini ibu Ji-yeong tak sanggup menanggung malu. Dia memilih aborsi.
Lima tahun berlalu, ibu Ji-yeong akhirnya melahirkan adik laki-laki. Tapi, ini justru awal derita Ji-yeong dan kakak perempuannya.
Anak laki-laki bak raja di keluarga Korea. Segala keperluannya diutamakan. Anak perempuan harus berkorban demi anak laki-laki: mengalah jika uang orang tua tak cukup dan bahkan bekerja paruh waktu demi membantu pendidikan anak laki-laki.
Novel Kim Ji-yeong, Lahir Tahun 1982 menggambarkan ketimpangan pandangan dan perlakuan terhadap perempuan. Ketimpangan sehari-hari dan di mana-mana: di rumah, sekolah, kantor, dan ruang pubik.
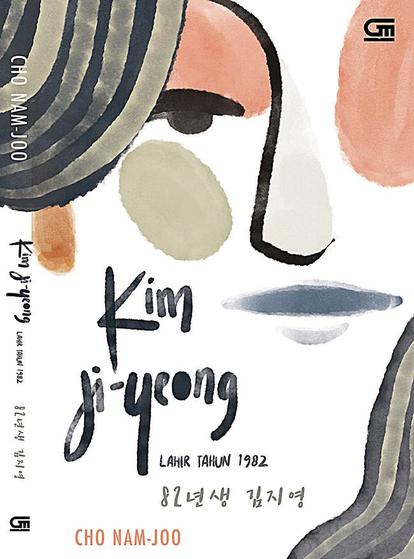
- Judul Buku: Kim Ji-Yeong, Lahir Tahun 1982
- Penulis: Cho Nam-joo
- Alih bahasa: Iingliana
- Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
- Tahun: 2019
- Tebal: 192 halaman
Cho Nam-joo menceritakan semua itu secara naratif. Mirip laporan jurnalistik. Sebagian besar plotnya pun lurus-lurus saja. Tapi, kesederhanaan itu justru yang membuat novel ini seperti bom: meledakkan pikiran dan perasaan.
Novel ini menggugat misogini dan patriarki tanpa harus sepatah pun menyebut kedua kata itu. Ia hanya bercerita dan terus bercerita. Tapi, cerita itu sendiri adalah gugatannya.
Mungkin karena itu, novel ini memicu kontroversi saat terbit pada akhir 2016. Kehebohan berlanjut ketika aktris Kim Do-young mengangkatnya ke layar lebar pada akhir 2019. Para aktor utama (Jung Yu-mi dan Gong Yoo – keduanya pernah beradu peran dalam Train to Busan) menjadi sasaran perisakan orang di dunia maya. Film dianggap tak adil menggambarkan laki-laki. Seperti biasa, zona nyaman memang tak mudah diusik.
Sebenarnya tak ada yang terlalu kontroversial dalam novel ini, misalnya jika dibandingkan dengan novel-novel feminisme. Ini kisah biasa dari seorang perempuan biasa. Tokoh utamanya, Kim Ji-yeong, bukan perempuan pendobrak kemapanan patriarki. Dia tipikal perempuan Korea yang kerap digambarkan drama-drama buatan negeri ginseng itu: pekerja keras; patuh kepada laki-laki di keluarganya; lucu dan menggemaskan saat jatuh cinta.
Tapi, di situlah formulanya. Novel ini mengungkap apa yang tak terkatakan oleh perempuan-perempuan seperti Ji-yeong. Ia mempertanyakan apa yang bagi kebanyakan tak perlu lagi dipertanyakan.
Sedari kecil, Ji-yeong mempertanyakan perlakuan berbeda yang ia dan perempuan lain dapatkan: selalu mengalah demi kepentingan anak laki-laki di rumah; mendapat giliran antre makan siang setelah anak-anak laki-laki di sekolah; kerap disalahkan jika laki-laki melecehkan mereka; terpaksa berhenti kerja saat melahirkan anak; harus membantu ekonomi keluarga di masa sulit; dan – setelah melakukan semua itu – perempuan tetaplah orang nomor dua di dalam keluarga, dan laki-lakilah pemilih saham terbesar.
Semua itu dipertanyakan Ji-yeong tapi hanya di dalam hati – yang kemudian ia ceritakan kepada seorang psikiater; narator dalam novel ini. Semua pertanyaan itu harus ia simpan, tekan, dan pendam dalam-dalam karena itu sudah kelaziman, dan bahkan sudah menjadi “agama” bernama “kodrat wanita” atau “naluri keibuan”.
Pertanyaan Ji-yeong justru diwakili oleh wanita-wanita lain di sekitarnya. Ada Yu-na di sekolah yang mempersoalkan, mengapa anak laki-laki selalu mendapat urutan pertama makan siang; teman sekolah yang berani mematahkan alat penunjuk guru yang sering digunakan untuk menyentuh dada siswa perempuan; seorang perempuan di dalam bus yang membantu Ji-yeong saat terancam oleh seorang pemuda; dan atasannya Kim Eun-sil yang melawan diskriminasi serta pelecehan di kantor. Atau bahkan ibunya sendiri yang akhirnya berani mengungkapkan pendapat di hadapan suaminya.
“Aku yang mengusulkan kita membuka restoran bubur. Aku juga yang membeli apartemen ini. Selama ini anak-anak yang mengurus diri mereka sendiri. Hidupmu memang sukses, tetapi bukan atas usahamu sendiri, jadi bersikaplah yang baik padaku dan anak-anak,” kata ibunya kepada ayahnya yang pulang malam, mabuk, seraya sesumbar betapa ia telah sukses membangun keluarga.
Ji-yeong memang sempat beberapa kali menyatakan pendapat, terang dan lugas. Tapi, setelahnya, dia merasa bersalah dan meminta maaf.
“Tidak bisakah kau berhenti mengoceh tentang bantuan? Kau membantu dalam urusan rumah tangga, membantu membesarkan anak, membantu urusan pekerjaanku. Memangnya rumah ini bukan rumahmu? Memangnya keluarga ini bukan keluargamu? Anak ini bukan anakmu? Lagipula, selama aku bekerja, memangnya hanya aku sendiri yang menikmati hasilnya? Kenapa kau bicara seolah-olah kau bersikap murah hati menyangkut pekerjaanku?” kata Ji-yeong kepada suaminya, Jeong Dae-hyeon, yang berjanji akan membantu mengurus anak, rumah, dan mencarikan pekerjaan untuk Ji-yeong ketika anak mereka dewasa.
Laki-laki bekerja di kantor dan perempuan mengurus rumah dan anak seakan sebuah kenormalan. Berondongan pertanyaan Ji-yeong membongkar ongkos dari kenormalan itu. Perempuan terpaksa meninggalkan pekerjaan yang ia sukai. Karier dan cita-cita tiba-tiba layu dan mati.
Semua ongkos itu ditanggung perempuan sementara laki-laki tak kehilangan apa pun. Kalaupun mencoba mengerjakan urusan rumah dan mengasuh anak, tolong jangan sebut itu belas kasihan untuk perempuan; pengorbanan laki-laki! Begitu pikir Ji-yeong.
Anda mungkin akan mengatakan, banyak perempuan yang bisa tetap bekerja meskipun menyusui dan mengasuh anak. Benar. Tapi, apakah itu terjadi pada banyak perempuan?
Tak banyak keluarga yang bisa membayar pengasuh anak atau asisten rumah tangga. Bahkan meski pemerintah Korea menyubsidi biaya penitipan anak, itu pun tak cukup. Perempuan-perempuan seperti Ji-yeong harus mencari jenis pekerjaan yang sesuai dengan waktu penitipan anak (antara pukul 10.00-16.00) dan memulai karir dari nol. Nam-joo dalam novelnya juga memberi catatan kaki berupa statistik bahwa angka perempuan bekerja di usia 29-39 tahun menurun jika dibandingkan dengan usia 20-29 tahun.
Laki-laki di dalam novel ini sebenarnya tak digambarkan serba “hitam”: bejat, main pukul, tukang mabuk, dan penganggur yang enak-enak di atas penderitaan istri. Ayah dan suami Ji-yeong pekerja keras, sayang anak, dan tak pernah kasar kepada istri mereka.
Sayangnya, mereka lemah; tak mampu membela perempuan mereka di saat paling dibutuhkan. Ketika ibu Ji-yeong cemas akan melahirkan anak perempuan lagi, suaminya cuma berkata, “Jangan berkata yang tidak-tidak.” Padahal, kata yang diharapkan keluar dari mulut laki-laki itu, “Jangan cemas. Laki-laki atau perempuan sama saja.” Ayahnya juga malah menyalahkan Ji-yeong saat dia merasa terancam oleh seorang pemuda. Kenapa ia harus kursus di tempat sejauh itu? Kenapa ia berbicara dengan sembarang orang? Kenapa ia memakai rok sependek itu?
Dae-hyeon tak jauh berbeda. Suaminya itu tak membelanya saat ibu mertuanya selalu menganggap bahwa memasak dan menyiapkan segala hal di hari raya itu tugas menantu perempuan. Dae-hyeon tak pernah bertanya apakah Ji-yeong tak lelah dengan pekerjaan itu; apakah Ji-yeong tak ingin sesekali berkumpul dengan keluarganya, alih-alih selalu dengan keluarga suaminya. Juga tak ada pembelaan Dae-hyeon saat keluarganya mempersoalkan Ji-yeong yang tak kunjung hamil.
Bagi ayah dan suaminya, hal-hal semacam itu mungkin sepele; sesuatu yang wajar saja jika terlupakan atau tak terpikirkan. Tapi bagi Ji-yeong dan mungkin banyak perempuan lain, yang “sepele” itu justru penting. Pembelaan akan menunjukkan bahwa Ji-yeong tak sendirian menghadapi dunia ini.
Di titik ini, Kim Ji-yeong, Lahir Tahun 1980 seakan membicarakan problem individual semata. Tapi, Nam-joo mampu mengaitkan problem Kim Ji-yeong dengan konteks sosial-politik. Pertanyaan besar yang ingin dia ajukan: jika keluarga dan anak sedemikian berharga bagi kita – bagi masyarakat dan negara– lantas mengapa semua itu cuma jadi urusan perempuan; mengapa hanya perempuan yang dipaksa mengorbankan banyak hal dalam hidupnya demi semua itu.
Dari sini, saya punya banyak pertanyaan untuk konteks Indonesia. Sebab, menurut saya, Kim Ji-yeong bukan semata kisah perempuan dari negara tertentu. Cara pandang misoginis dan patriarkis nyaris ada di setiap bangsa sejak zaman baheula. Hanya ragam dan intensitasnya yang berbeda-beda.
Di Indonesia, misalnya, pemerintah punya kampanye pemberian ASI eksklusif selama enam bulan. Tapi pada saat yang sama, kenapa cuti hamil dan melahirkan bagi pekerja perempuan hanya diberikan tiga bulan? Di Korea, di mana kisah Kim Ji-yeong lahir, pekerja perempuan mendapatkan cuti hamil dan melahirkan sampai satu tahun – meskipun banyak perempuan akhirnya lebih memilih berhenti bekerja.
Lalu, jika melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak bukan cuma tanggung jawab perempuan, mengapakah tak ada “cuti hamil dan melahirkan” untuk suami? Bukankah kehadiran suami saat proses persalinan, menyusui, dan pengasuhan juga penting?
Pertanyaan-pertanyaan di atas hanya sebagian dari banyak kemungkinan kebijakan publik yang bisa diambil pemerintah untuk mengoreksi ketimpangan gender. Legislasi, seperti undang-undang antidiskriminasi, memang penting. Tapi, yang tak kalah pentingnya adalah kebijakan praktis yang akan mengubah pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.
Di Korea sendiri, keberadaan beleid antidiskriminasi dan kementerian kesetaraan gender tak serta merta bisa mengubah cara pandang diskriminatif terhadap perempuan. Identitas ‘perempuan’ masih menjadi batu sandungan – yang kadang subtil – di banyak sektor kehidupan: keluarga, pendidikan, dan pekerjaan.
Di awal novel, Kim Ji-yeong diceritakan mengalami depresi. Dia kehilangan identitasnya sendiri; kadang menampilkan karakter dan identitas orang lain: ibunya, anaknya, dan temannya yang sudah meninggal.
Dia akhir novel, Nam-joo meninggalkan tanya: apakah Ji-yeong sembuh atau tidak? Psikiaternya sendiri – narator novel ini – sulit mendefinisikan depresi jenis apa yang Ji-yeong alami. Dia, sebagai laki-laki, hanya bisa sadar bahwa istrinya pun mungkin mengalami apa yang dialami Kim Ji-yeong.
Lantas, apakah jika sembuh, Ji-yeong akan kembali sebagai “pribadi dulu”: yang menerima “kenormalan-kenormalan” itu tanpa reserve? Ataukah dia justru terlahir sebagai “pribadi baru”: yang berani mengutarakan perasaan dan pendapatnya?
Tapi tampaknya, dengan membiarkan cerita berakhir menggantung seperti itu, Nam-joo justru ingin menyampaikan sebuah pesan. Bukan seorang Ji-yeong-lah yang mesti mencari jawabannya. Tapi kita. Ya, kita semua karena Ji-yeong mewakili apa yang kita hadapi atau yang coba kita hindari.[]