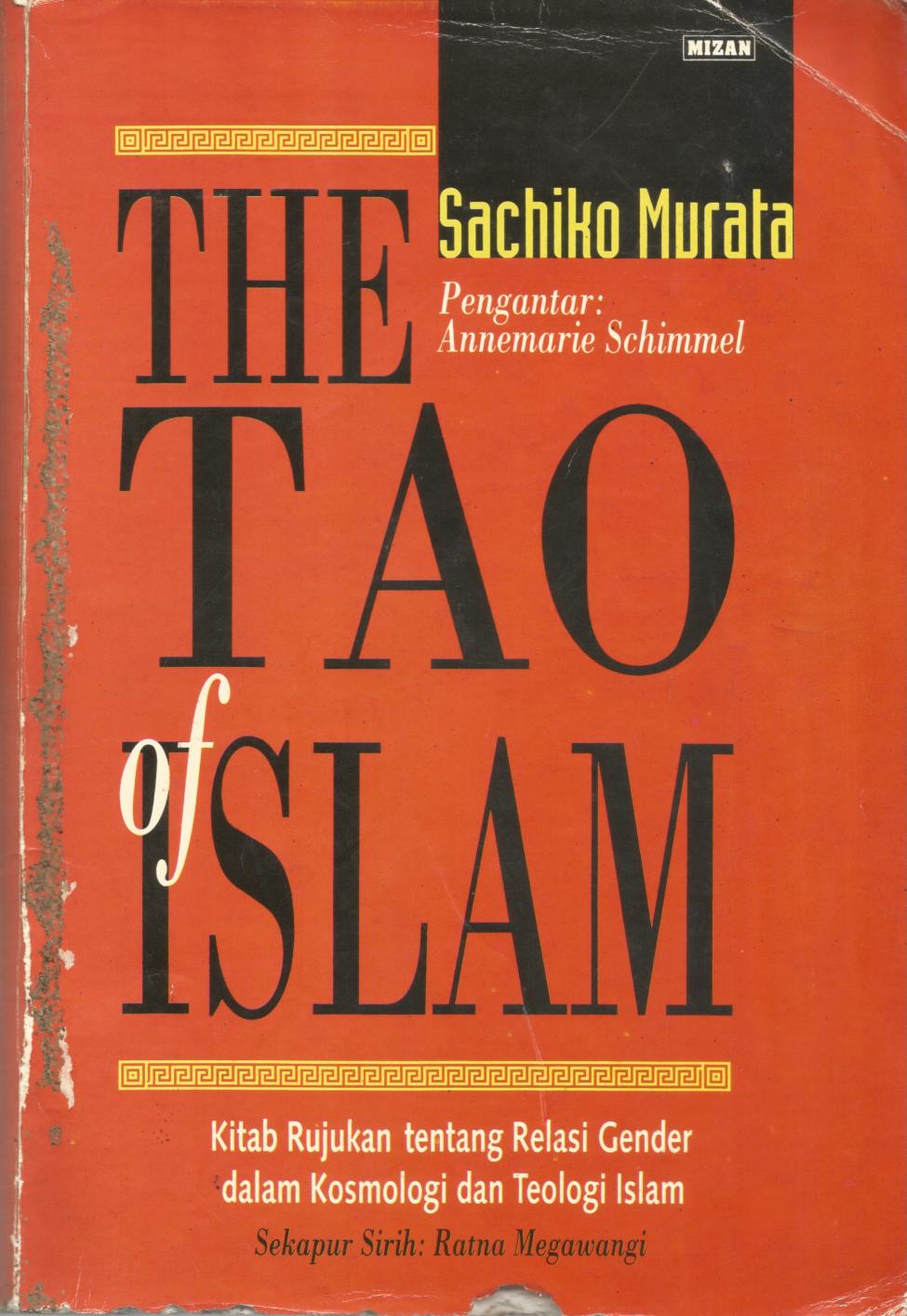Bagaimana mungkin sisi-sisi maskulin dan feminin tak sama penting? Karena tanpa kerja sama keduanya, tak akan ada kehidupan baru di muka bumi.
DALAM sambutan saya pada Kongres Internasional tentang Sejarah Agama di Roma pada Agustus 1990, saya mengemukakan beberapa hasil diskusi dan komentar dari banyak kolega dan mahasiswa saya, bahwa sudah tiba saatnya sejarah agama dikaji bukan hanya dari sudut pandang yang menguntungkan Barat semata, tetapi juga mempertimbangkan cara-cara lain dalam melihat berbagai konsep seperti agama, Tuhan, wahyu, dan sebagainya. Karena tentu saja ada sejumlah cendekiawan, khususnya dari Asia Timur, yang ikut memberi sumbangan besar terhadap sejarah atau fenomenologi agama, baik dalam tradisi agama mereka sendiri seperti Buddhisme, Konfusianisme, atau Shinto, maupun dalam bidang agama-agama lain seperti Islam. Sayangnya sikap para sarjana Barat tampaknya masih banyak dipengaruhi oleh latar belakang “biblikal” dan pendekatan “klasik” terhadap keilmuan.
Topik lain yang sering muncur selama diskusi-diskusi di Roma adalah tentang peran elemen feminin dalam berbagai tradisi agama. Di sini sekali lagi, cara pandang turun-temurun dalam mengkaji peran-peran wanita dari sudut Barat yang dianggap penting. Tetapi beberapa interpretasi lain, seperti “peran spiritual feminin” dalam sejarah agama-agama, juga disebut-sebut—aspek ini telah didiskusikan beberapa dekade yang lalu oleh mendiang guru dan rekan saya Professor Friedrich Heiler dalam kuliah-kuliahnya di Marburg.
Beliaulah yang senang mengutip – dengan kesedihan tertentu – ucapan Indologis Jerman, Moriz Winternitz: “Wanita selalu menjadi sahabat agama, tetapi umumnya agama bukan sahabat bagi wanita.”
Kebenaran ucapan Wintemitz semakin terbukti jika dikaitkan dengan kajian Islam dan posisi wanita dalam Islam. Islam hampir tidak pernah dikaji dari sudut pandang fenomenologis agar strukturnya dapat dipadukan dengan struktur agama-agama lain. Tidak ada satu pun buku tentang fenomenologi agama yang membahas Islam, yang sering dianggap tidak menarik dan tidak menimbulkan minat, serta dianggap sebagai contoh sempurna dari agama yang sarat dengan hukum-hukum (“legalis”). Memang lebih mudah mengkaji Islam hanya dari segi permukaannya saja, dan menilai negatif tentang poligami dan kemudahan bercerai, serta menuding konsep purdah (walaupun penekanan penerapannya berkembang hanya setelah periode tertentu), daripada berusaha untuk melihat sisi-sisi yang lebih positif dari Islam.
Para pakar dan bahkan publik umum mengutip pernyataan-pernyataan dari Barat Abad Pertengahan yang berpandangan bahwa wanita dalam Islam tidak mempunyai jiwa. Sangat sedikit cendekiawan yang mencoba melihat apa yang ada di bawah permukaan, dan menemukan struktur yang tentunya akan mengejutkan mereka yang terbina dengan sikap negatif terhadap Islam. Sayangnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini di dunia Islam telah mendukung keyakinan para pengkritik dan memperkuat kesan bahwa wanita, dalam sebuah masyarakat militan dan fundamentalis, merupakan sebuah kelompok tertindas tanpa hak, tidak mampu menyuarakan pendapat-pendapat mereka, atau terlibat dalam masalah-masalah agama mereka sendiri. Kajian mengenai peran wanita selama perang pembebasan Turki pada awal 1920-an atau partisipasi aktif wanita dalam gerakan kemerdekaan lndia dan perjuangan Pakistan pada 1940-an, adalah beberapa contoh yang menunjukkan hal yang sebaliknya.
Dengan adanya fakta-fakta tersebut mungkin tidak mengejutkan jika sebuah pendekatan baru tentang relasi gender dalam Islam datang dari seorang wanita Jepang, Sachiko Murata. Melalui kajiannya yang menyeluruh mengenai hukum Islam dan tradisi esoterik Islam, Dr Murata menawarkan hasil penelitiannya dan memberikan beberapa kesimpulan yang mungkin mengejutkan banyak pembaca melalui buku ini (The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought). Dr Murata secara lugas memperlihatkan bahwa dalam Islam, seperti halnya dalam setiap agama, prinsip kesatuan, yang memecah diri menjadi dualitas dan kemudian menjadi pluralitas, merupakan hal yang pokok. Oleh sebab itu bukunya diberi judul The Tao of Islam. Orang dapat mengatakan tanpa melebih-lebihkan bahwa masalah kesatuan dan fungsinya dalam penciptaan telah menjadi topik utama pemikiran teologis, khususnya mistis, dalam Islam. Ketika saya mengajar di Fakultas Teologi Islam (Illahiyat Fakultesi) di Ankara, Turki pada 1950-an, dan berusaha menjelaskan kepada mahasiswa-mahasiswa saya definisi Rudolf Otto tentang dua aspek Numen (Ilahi), yakni manifestasi mysterium tremendum dan mysterium fascinosum – Mahamulia, Maha Pemarah dan Maha Penyayang, aspek yang indah dari Ilahi – mahasiswa-mahasiswa saya bereaksi dengan penuh takjub: “Kami sudah tahu hal itu sejak dahulu!” kata mereka. “Kami selalu tahu bahwa Tuhan memiliki sisi jalal dan jamal, aspek-aspek Kemuliaan yang Luar Biasa dan Kebaikan yang Mengagumkan, dan bahwa dua hal ini menjadi sifat-Nya yang kamal, kesempurnaan.”

Pernyataan mereka begitu jelas, dan sebagai seorang fenomenolog agama saya merasa tak ada kesulitan menamakan kekuasaan, sifat maskulin, atau aspek jalal sebagai aspek yang dan kecintaan, kecantikan, sifat feminin, atau aspek jamal sebagai aspek yin. Setiap orang tahu bahwa hanya dengan penyatuan kedua prinsip inilah kehidupan dapat terus ada. Ke-hidupan tak mungkin ada tanpa systole dan diastole detak jantung, tanpa menghirup dan menghembuskan, atau kerja listrik tanpa adanya dua kutub. Dahulu kaum sufi menafsirkan perintah Ilahi dalam penciptaan dengan kun, “Jadilah!” (yang ditulis dalam bahasa Arab dengan dua huruf k-n) dengan menunjuk pada “benang dua warna” yang menyelubungi, seperti sehelai kain, kesatuan dasar Wujud Ilahi.
Maulana Jalaluddin Rumi secara khusus rnenggambarkan keadaan saling mempengaruhi yang konstan antara dua aspek kehidupan itu melalui prosanya yang terkenal Fihi mafihi dan menyebut-nyebut hal itu dalam begitu banyak versi lirisnya, Diwan dan Matsnawi. Dan bukankah interpretasi mistis dari huruf pertama abjad Arab, yang ramping dan tegak, alif, dengan nilai numerik satu, sebagai manifestasi pertama Keesaan Tuhan; dan huruf kedua, ba, dengan nilai numerik dua, merupakan permulaan penciptaan alam semesta? Karena huruf pertama al-Quran adalah ba dalam kata bismillah, “Dengan nama Allah”.
Dengan adanya kecenderungan umum dalam Islam untuk mengorganisasikan segala sesuatu ke dalam dua kelompok serta melihat segala penciptaan berdasarkan kedua aspek ini, bagaimana mungkin sisi-sisi maskulin dan feminin dalam kehidupan tidak dianggap sama-sama penting? Karena tanpa kerja sama keduanya, tak akan ada kehidupan baru di muka bumi. Tidak sia-sialah Rami melihat “ibu” di setiap tempat: Secara umum segala sesuatu dalam kosmos adalah ibarat seorang ibu, melahirkan sesuatu yang lebih tinggi daripada dirinya, apakah itu batu api yang “melahirkan” percikan, yang kemudian menghasilkan api apabila ditempatkan dalam pengantar panas yang baik, atau bumi yang disuburkan oleh awan, menghasilkan tumbuh-tumbuhan sebagai hasil hieros gamos, perkawinan suci. Bahkan Rumi menggambarkan wanita, dalam buku pertama Matsnawi, sebagai seseorang yang pantas disebut sebagai “pencipta”. Untuk mengoreksi kesalahpahaman umum tentang peran wanita dalam Islam, sebenarnya cukup dengan melihat bagaimana ucapan-ucapan dalam al-Quran muslimin wa muslimat, mu’minin wa mu’minat diletakkan sejajar: yaitu Muslim pria dan wanita, kaum beriman pria dan wanita. Wanita mempunyai kewajiban keagamaan yang sama seperti pria (dengan perkecualian bahwa mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban ini dalam keadaan tidak suci). Rasul sendiri menekankan dalam ucapannya yang terkenal, kenyataan bahwa “Allah telah menunjukkan kasih sayang-Nya kepadaku dengan wangi-wangian duniamu dan wanita, dan hiburan spiritualku ialah shalat” – sebuah ucapan yang mendasari pembahasan Ibn Arabi mengenai Muhammad dalam bukunya Fushush al-Hikam.
Peran yang dimainkan oleh istri pertama Rasul, Khadijah – “ibu kaum mukminin” – dalam perkembangan spiritualnya, adalah hal yang sangat nyata. Dengan kasih sayang dan pengertiannya, Khadijah memberi Rasul kekuatan dalam menghadapi pengalaman yang menegangkan dan mengguncang hatinya yang paling dalam saat menerima wahyu pertama yang diturunkan kepadanya, karena beliau percaya akan kerasulan suaminya. Berikutnya, istri termuda Rasul, Aisyah, bukan saja memainkan peran politis yang penting, tetapi juga merupakan sumber banyak hadis dengan cara menginformasikan pendengarnya tentang kebiasaan, dan ucapan-ucapan Rasul, sekaligus melantik sederet wanita yang mempelajari, menyampaikan, dan mengajarkan hadis pada Abad Pertengahan Islam.
Kita tidak boleh melupakan Fathimah, putri termuda Rasul, yang menikah dengan sepupunya, Ali, dan ibu dari Hasan dan Husain, Imam kedua dan ketiga dalam Islam Syi’ah. Dalam keyakinan Syi’ah, Fathimah dinaikkan ke posisi yang sangat tinggi, menjadi semacam mater dolorosa. Kedua anaknya menjadi korban pergolakan politik (walaupun hal itu terjadi beberapa dekade setelah kematian Fathimah). Fathimah pun dikenal sebagai perantara, atau dalam terminologi mistik, sebagai umm abiha, “ibu bagi ayahnya”.
Kita dapat melanjutkan dan menghitung para wanita yang memainkan peran dalam sejarah pemikiran dan praktik mistik, dan terbukti dari biografi-biografi sufi bahwa sebagian besar pemimpin spiritual, menerima inspirasi religius pertama dari ibu-ibu mereka yang saleh – bukankah Rasul menyatakan bahwa “Surga berada di bawah telapak kaki ibu”?
Sisi feminin dari kehidupan Islam ini biasanya tidak terlihat karena kebanyakan para cendekiawan, yang umumnya pria, belum pernah hidup bersama wanita dalam sebuah rumah Muslim, dan oleh karena itu belum melihat bagaimana pentingnya peran yang dimainkan seorang wanita, khususnya kaum ibu, dalam rumah-rumah mereka, apakah itu di Turki atau di belahan Indo-Pakistan. Para cendekiawan mungkin membaca mengenai beberapa ratu Muslim Abad Pertengahan, seperti Radhiyah Sultanah dari Delhi (1236-40) dan teman sejawatnya Syajarat Al-Durr dari Mesir (1246-49), atau sebutlah beberapa nama ratu yang mempengaruhi suami-suami mereka dalam keputusan-keputusan politik mereka dan dipuji oleh para penyair besar. Atau mereka mungkin telah mendengar sedikit wanita bangsawan yang disanjung dalam puisi, kaligrafi, dan karya-karya religius. Tetapi mengenai kehidupan dalam keluarga, hanya sedikit yang mengetahuinya. Lagi pula, memang sangat gampang mengkritik peradaban asing dengan memakai standar Barat Abad ke-20. Wiebke Walther, dalam kajiannya yang dalam dan luas Die Frau in Islam (Wanita dalam Islam), menyatakan bahkan di beberapa tempat di Jerman pada 1880-an kaum pria masih mempunyai hak untuk menyiksa istri mereka.
Ada satu ayat dalam al-Quran yang konteksnya seringkali disalahartikan, tetapi menurut pemahaman saya, justru tepat sekali dianggap sebagai hubungan gender yang ideal, “Istri-istrimu adalah pakaianmu, dan engkau adalah pakaian mereka” (QS. 2: 188). Menurut pemikiran religius kuno, pakaian diibaratkan sebagai “keakuan yang lain” (alter-ego). Pakaian dapat berfungsi sebagai pengganti untuk seseorang, dan dengan pakaian baru seseorang seolah mendapatkan kepribadian baru. Lebih jauh, pakaian menyembunyikan tubuh, menutupi pandangan terhadap bagian-bagian yang bersifat pribadi, dan melindungi pemakainya. Menurut interpretasi ini, suami-istri berbicara satu sama lain kepada alter-ego mereka, dan setiap diri melindungi kehormatan pasangannya. Hal ini memperlihatkan betapa baiknya prinsip yin-yang berlaku dalam hubungan perkawinan: suami-istri adalah setara dalam kebersamaan mereka yang sempurna.
Banyak pernyataan menghina tentang wanita, khususnya di antara para zahid dan kaum mistik, yang berasal dari fakta bahwa kata jiwa dalam bahasa Arab, nafs, adalah kata benda feminin dan, berdasarkan pernyataan dalam QS. 12: 53, kata tersebut sering kali dipahami sebagai nafs ammarah, “jiwa yang menghasut pada kejahatan”. Karena itu nafs biasanya mewakili citra keras kepala, kuda atau unta liar, anjing hitam, ular, tikus, dan juga wanita penyeleweng. Siapa pun yang membaca buku-buku berbahasa Arab dan Persia Abad Pertengahan sangat waspada akan penerapan istilah nafs, yang proyeksi eksternal utamanya adalah dunya, “hal-hal duniawi”, lagi-lagi kata benda feminin. Tetapi penggambaran yang merendahkan serupa mengenai bahaya wanita dan Frau Welt, “Nyonya Dunia”, juga dapat ditemukan dalam tulisan dan khotbah-khotbah Kristiani Abad Pertengahan, di mana yang disanjung hanyalah para perawan yang sedang berusaha keras untuk meneladani Maria.
Konsep mengenai “jiwa wanita” telah memperkaya literatur Islam. Contoh yang paling terkenal adalah sosok Zulaikha yang menenggelamkan dirinya dalam cinta kepada ketampanan Yusuf. Dia disucikan melalui penderitaan panjang untuk menjadi, seperti yang mungkin dikatakan oleh seseorang, nafs lawwamah, “jiwa yang gelisah” (QS. 75: 2). Akhirnya, dia disatukan dengan pujaannya yang hilang untuk menjadi nafs muthma’in-nah, “jiwa yang tenang” (QS. 89: 27). Perkem-bangan nafs melalui tahap-tahap yang disebutkan dalam al-Quran ini, telah menjadi inspirasi bukan saja bagi kaum mistik Persia dan Turki, tetapi juga para penyair Indo-Muslim yang tak terhitung banyaknya.
Didukung oleh kisah rakyat setempat yang cerita-ceritanya selalu berpusat di sekitar wanita, mereka menyanyikan pengembaraan wanita di padang pasir dan pegunungan dalam mencari pujaan hatinya yang hilang, hingga akhirnya sang wanita itu disucikan dan dipersatukan dalam cinta. Karena misteri terbesar dalam perjalanan mistik – penjinakan nafsu-nafsu rendah manusia melalui penyerahan diri dalam cinta – sangat tepat diekspresikan dengan simbol jiwa wanita. Melalui penyatuan dengan pujaan hatinya, dia dapat mencapai penyatuan sempurna antara jamal dan jalal, yin dan yang, dalam keseluruhan kamal, yaitu “kesempumaan Ilahi”.
Inilah sedikit pemikiran yang timbul ketika saya tengah membaca buku karya Sachiko Murata. Saya tahu bahwa ada beberapa orang yang menolak pendekatan mistiknya mengenai hubungan gender, yang mungkin dianggap terlalu jauh dari citra mereka terhadap Islam. Tetapi teks-teks yang diterjemahkan dalam buku ini – sebagian besar di antaranya baru pertama kali diterjemahkan – menunjukkan bahwa pendekatannya sangat valid. Sesungguhnya, sejumlah teks itu sendiri menyatakan aspek paling penting dari buku ini: teks-teks itu dengan sendirinya membentuk sebuah antologi kearifan mistik, dan seharusnya dikaji secara saksama oleh siapa pun yang berminat pada Islam. Bahkan seandainya ahl-i zhahir yang menilai peran wanita dalam Islam (dan Islam secara umum) dengan pendekatannya yang murni historis, sosiologis, atau filologis, tidak sepakat dengan beberapa kesimpulan Dr Murata, setidaknya mereka akan menemukan sejumlah besar sumber yang belum mereka ketahui sampai sekarang, yang mungkin dapat menolong mereka untuk memahami Islam dengan lebih baik.
Tampaknya pantas jika seorang wanita menulis buku mengenai hubungan gender ini, sebagaimana pendekatan historis pertama juga diberikan oleh seorang wanita Jerman, Wiebke Walther. Juga kajian independen pertama tentang Rabi’ah, wanita zahid pertama dalam Islam (w. 801 di Irak), ditulis pada 1928 oleh seorang wanita orientalis asal Inggris, Margaret Smith. Rabi’ah, yang memperkenalkan elemen kemurnian cinta pada awal gerakan asketik dalam Islam, disanjung oleh generasi penulis dan penyair-penyair sesudahnya. Kami ingin menutup prakata ini dengan baris-baris sajak yang dikutip Jami (w. 1492 di Herat) dari penyair Arab, al-Mutanabbi, untuk menghormati wanita suci dari Basrah ini:
Jika seluruh wanita seperti yang telah kita
ceritakan
Maka wanita akan lebih utama daripada pria
Karena gender feminin bukanlah
hal yang memalukan bagi matahari
Seperti halnya gender maskulin yang bukan
sebuah kehormatan bagi bulan sabit!
Annemarie Schimmel (1922-2003) adalah profesor Islam dan sufisme asal Jerman. Guru besar di Harvard Univeristy
Dikutip dari kata pengantar buku karya Sachiko Murata The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought (Bandung: Mizan, 1996)