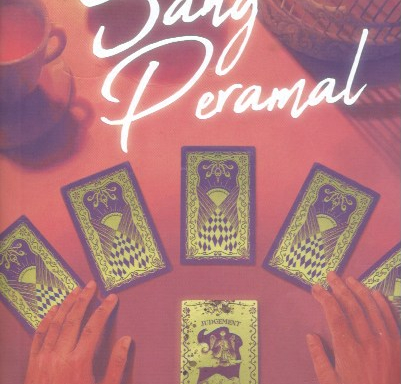Dalam karya solo pertamanya, Faizal Reza berhasil menghadirkan pengalaman menyegarkan tentang cinta dengan eksplorasi pengisahan yang tak lazim. Tapi lebih dari itu, ceritanya punya daya gedor.
MARTINI dan Scotch. Rokok dan kopi. Lorong-lorong kota. Kafe dan bar. Apartemen dan kamar kos. Dan Faizal Reza bercerita tentang cinta. Bukan cinta biasa. Cinta absurd, dan kadang surreal.
Itulah kesan pertama yang terlintas usai melahap 27 cerpen dalam Yang Diacak-acak Seprai, Yang Berantakan Hati – buku kumpulan cerpen pertama Faizal.

- Judul Buku: Yang Diacak-Acak Sepreai, Yang Berantakan Hati
- Pengarang: Faizal Reza
- Penerbit: PT Elex Media Komputindo
- Tahun: 2019
- Tebal: 163 halaman
Di awal, saya merasa seperti menemukan pengarang flash fiction pada diri Faizal. Cerpen-cerpen di bagian awal buku ini pendek-pendek. Tapi tak sependek karya Lydia Davis, pengarang flash fiction Amerika tersohor dan pemenang Man Booker International Prize 2013. Karya Lydia seringkali cuma separagraf atau bahkan sekalimat!
Flash Fiction – atau disebut juga cerpen pendek – sedang ngetrend belakangan ini. Mungkin karena genre ini pas dengan teknologi media baca saat ini: laptop, ponsel pintar, atau iPad. Atau mungkin juga justru berkat gawai-gawai itu, orang mulai tak bisa fokus (terhubung dengan dunia sekaligus terdistraksi darinya). Mungkin kita memang sudah tak punya banyak waktu untuk menikmati cerita mendayu-dayu dan bertele-tele.
Tak ada standar pasti seberapa panjang flash fiction. John Dufresne, profesor penulisan kreatif dari Florida International University, menyatakan dalam flash fiction, pengarang tak punya ‘kemewahan’ untuk subplot, karakter sampingan, atau cerita latar (backstory). Semuanya sesimpel, “Anda masuk, Anda keluar,” katanya.
Mungkin ada yang bakal berkomentar, gampang amat membuat cerpen pendek. Tak butuh subplot, karakter pun minimalis, dan tak perlu backstory. Satu paragraf atau bahkan satu kalimat sudah dibilang cerita; sastra, dan kemudian diterbitkan.
Mengarang flash fiction bisa jadi butuh waktu lebih singkat daripada membuat cerpen, novel atau bahkan roman. Jika cerpen mungkin sebulan, novel setahun, flash fiction bisa jadi cuma sepekan. Tapi, seperti dibilang Dufresne, menyingkat sesuatu justru membutuhkan pikiran yang lebih fokus; intens. Proses berpikir yang lebih lama. Jika roman, novel, cerpen butuh waktu lebih lama untuk ditulis mungkin flash fiction butuh waktu lebih lama untuk dipikirkan. Yang sebentar itu menuliskannya bukan memikirkannya.
Seperti karya bagus lainnya – atau sebut saja “sastra” – bagi saya, flash fiction semestinya juga punya daya gedor, racun, dan candu. Ia harus menghadirkan pengalaman segar dan cara pandang tak lazim. Dan ini tentu tak mudah diramu.
Untuk kualitas tersebut, saya berani mengatakan Faizal berhasil dalam karya solo pertamanya ini, setidaknya di sebagian besar cerita. Dia mempertanyakan hal yang sudah dianggap biasa, dan dengan cara pengisahan tak lazim.
“Menjadi Presiden”, misalnya. Cerpen ini bisa dibilang flash fiction. Hanya menghabiskan tiga halaman buku di versi digitalnya. Anda bisa membacanya sambil menunggu commuter line atau MRT, atau bahkan saat buang hajat.
Tak ada subplot. Tokohnya cuma “aku” dan “pacarku”. Memang ada cerita latar tapi sedikit tentang bagaimana keduanya bertemu, jatuh cinta, lalu “sesuatu” terjadi di apartemen.
Tapi, Faizal berhasil menghadirkan sebuah pertanyaan. Apakah hati (sebagai fakultas jiwa dan bukan organ tubuh manusia) bisa sebegitu berantakannya hingga logika pun tak bisa menatanya? Jawabannya, ya.
Si pacar memutuskan “aku” dengan alasan-alasan klise: “aku lebih nyaman kita temenan”; “aku belum siap punya hubungan serius”; “kita sudah enggak cocok lagi; aku pengen sendirian dulu; dan bla…bla…bla. Si “aku” diam, cuma bisa menggugat dalih demi dalih itu dalam hati: bukankah dulu dia yang ingin pacaran; siapa pula yang sudah mikir serius; emangnya pacaran mesti cocok; dan sebagainya.
Pendek kata, apa pun alasan kita untuk mencintai seseorang atau berhenti mencintainya, semua bakal tak masuk akal. Hati bukan dibuat berantakan, tapi memang punya potensi berantakan dalam dirinya sendiri: gampang berubah; mudah terombang-ambing. Mungkin karena itu, ada doa dalam agama agar Tuhan menetapkan hati kita. Karena itu juga, seorang penceramah tersohor pernah mengarang syair lagu tenar, “Jagalah hati, jangan kau kotori” meski kemudian kita tahu si penceramah tak bisa … (ah sudahlah. Anda sudah tahu ceritanya. Lagipula ini ulasan buku bukan artikel gosip).
Tema besar seperti itu bisa dikatakan mewarnai sebagian cerpen dalam buku ini. Tapi, sekali lagi, Faizal piawai mengeksplorasi ide dan cara pengisahan yang berbeda-beda: cinta yang banal; cinta dalam ilusi; cinta dalam pengkhianatan; antara “cinta yang tulus” dan “seks yang menggebu-gebu”; cinta segiempat – sepasang suami-istri berselingkuh dengan pasangan suami-istri lain.
Ada satu cerpen yang menurut saya agak berbeda dari keseluruhan. Yaitu, “Lelaki dalam Sel” (ini juga bisa dikategorikan flash fiction). Di sini, si narator bercerita tentang seorang pengarang bernama “Adam Pramoedya”. Si pengarang dibui oleh penguasa dan bukunya dilarang beredar. Bukan karena ia menulis soal pemberontakan atau penculikan presiden tapi kisah cinta.
Usai membacanya, saya membayangkan Pramoedya Ananta Toer, pengarang Bumi Manusia yang lama berada dalam terungku penguasa Orde Baru. Kita tahu buku itu – dan juga keseluruhan Tetralogi Pulau Buru – tak bicara soal pemberontakan melawan rezim Orde Baru. Ia justru berkisah tentang cinta di antara anak manusia dan utamanya cinta kepada bangsa dalam perlawanan terhadap kolonialisme.
Apresiasi saya di atas – dan ini suka-suka saya sebagai pembaca – membawa saya pada kesimpulan bahwa Yang Diacak-acak Seprai, Yang Berantakan Hati tak melulu tentang cinta dalam pengertian sempit. Cinta tak hanya bisa membuat hati seseorang berantakan tapi juga mengusik kekuasaan.
Ada satu cerpen lagi yang membuat saya tertegun usai membaca – tanpa mengabaikan kisah-kisah lainnya. Judulnya “Mengingat Dia”. Ini bukan flash fiction. Ceritanya cukup panjang meski karakternya minimalis. Di sini, si narator adalah “orang ketiga yang sok tahu”.
Dia berkisah tentang “kau”, seorang pria, dan “dia”, seorang wanita. “Kau” mencintai “dia”, tapi tak bisa atau tak mau menyatakannya. Keduanya hanya berteman. Cinta yang tulus, kata si narator. Tapi dalam satu momen di sebuah apartemen, terjadilah percintaan dalam maknanya yang banal. Semua terjadi begitu saja; tanpa pernyataan cinta.
Tapi, bukan itu inti ceritanya. Si narator kemudian bercerita mundur ke masa lalu dengan kata-kata “kalau saja”. Kalau saja “kau” tak menemui “dia” di apartemen itu. Kalau saja “kau” tak menonton film itu dan bertemu pertama kalinya dengan “dia” di bioskop. Kalau saja “kau” tak mengenal penulis skenario film itu. Kalau saja “kau” tak kuliah film. Dan banyak lagi “kalau saja” hingga akhirnya kita akan menemukan “kejutan” atau lebih tepatnya “teror” di akhir cerita.
Dalam cerita ini, Faizal seakan ingin mempertanyakan takdir. Apakah takdir sebuah jalan lurus kehidupan yang mau tak mau harus dijalani manusia tanpa ada pilihan; tanpa ada jalan bercabang? Ataukah takdir menyajikan kemungkinan-kemungkinan dimana manusia memiliki kebebasan memilih?
Bagaimanapun, si “aku” bebas-bebas saja memilih jalan hidupnya: menyukai sebuah film saat masih anak-anak; jatuh cinta dengan pemeran wanitanya yang cantik lagi seksi; memilih kuliah film; mengenal seorang penulis skenario; menonton film kenalannya itu; dan akhirnya bertemu dengan “dia”. Tapi, di sisi lain, obsesi si “aku” kepada pemeran wanita dalam film dari masa lalunya dan fantasi erotisnya akan adegan panas di film itulah yang seolah-olah mempertemukan “aku” dengan “dia”.
Namun, ada beberapa cerpen yang menurut saya menggantung atau lebih tepatnya tak sesuai dengan ekspektasi yang dipicu cerpen lainnya. Tak banyak sih, antara lain “Lelaki dari Masa Depan” dan “Ketika Hujan Turun”. Jika satu kutipan dalam buku ini bertanya, “bagaimana rasanya ditinggal saat sedang cinta-cintanya”, maka saya juga akan bertanya, “bagaimana rasanya cerita diakhiri begitu saja saat sedang asyik-asyiknya” atau “saat berharap akan ada kejutan”.[]