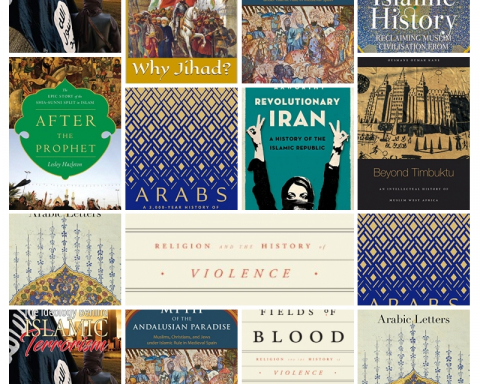Dalam pengantar untuk bukunya Sejarah Tuhan (Mizan, 2018), Karen Armstrong merefleksikan perjalanannya mencari makna “Tuhan”. Dia merasa pengetahuan tentang Tuhan tak berkembang lagi seperti pengetahuan lain.
SEJAK kecil saya telah memiliki kepercayaan keagamaan yang kuat, tetapi dengan sedikit keimanan kepada Tuhan. Ada perbedaan antara kepercayaan kepada seperangkat proposisi dengan keimanan yang memampukan kita menaruh keyakinan akan kebenaran proposisi-proposisi itu. Secara implisit, saya percaya Tuhan itu ada; saya juga beriman kepada kehadiran sejati Kristus dalam Ekaristi, kepada kebenaran sakramen, kepada kemungkinan keabadian neraka, dan kepada realitas objektif peleburan dosa. Akan tetapi, saya tidak bisa mengatakan bahwa kepercayaan saya terhadap semua ajaran agama tentang realitas sejati ini memberi bukti kepada saya bahwa kehidupan di dunia ini sungguh-sungguh baik atau bermanfaat. Keyakinan masa kecil saya tentang ajaran Katolik Roma lebih merupakan sebuah kredo yang menakutkan. James Joyce menyuarakan hal ini dengan tepat dalam bukunya Portrait of the Artist as a Young Man; saya mendengarkan khotbah tentang api neraka. Kenyataannya, neraka merupakan realitas yang lebih menakutkan daripada Tuhan karena neraka adalah sesuatu yang secara imajinatif bisa betul-betul saya pahami. Di pihak lain, Tuhan merupakan figur kabur yang lebih didefinisikan melalui abstraksi intelektual daripada imajinasi. Ketika berumur delapan tahun, saya pernah diharuskan menghafal jawaban katekismus terhadap pertanyaan “Apakah Tuhan itu?”: “Tuhan adalah Ruh Mahatinggi, Dia ada dengan sendirinya dan Dia sempurna tanpa batas.” Tidak mengherankan jika konsep itu kurang bermakna buat saya. Bahkan, mesti saya akui, hingga saat ini konsep itu masih membuat saya bergidik. Konsep itu juga merupakan sebuah definisi yang amat kering, angkuh, dan arogan. Sejak menulis buku ini (A History of God: The 4,000-Year of Quest of Judaism, Christianity and Islam–red), saya pun menjadi yakin bahwa konsep semacam itu juga tidak benar.
Ketika remaja, saya mulai menyadari bahwa ternyata ada sesuatu pada agama yang lebih daripada sekadar rasa takut. Saya telah membaca tentang kisah kehidupan para rahib, puisi-puisi metafisik, T.S. Eliot, dan beberapa tulisan mistik yang lebih sederhana. Saya mulai tergugah oleh keindahan liturgi dan, meskipun Tuhan masih tetap terasa jauh, saya dapat merasakan kemungkinan untuk mendekatkan jarak kepadanya dan bahwa penampakannya akan mengubah seluruh realitas ciptaan. Untuk mencapai ini, saya pun memasuki sebuah ordo keagamaan. Sebagai seorang biarawati yang masih baru lagi belia, saya belajar lebih banyak tentang iman. Saya mengkaji apologetika, kitab suci, teologi, dan sejarah gereja. Saya mempelajari sejarah kehidupan biara dan terlibat dalam pembicaraan panjang lebar tentang peraturan ordo saya yang konon mesti dipelajari melalui hati. Anehnya, Tuhan terasa tidak hadir di dalam semua ini. Perhatian justru dipusatkan kepada perincian sekunder dan aspek-aspek pinggiran dari agama. Saya bergulat dengan diri saya sendiri dalam doa, mencoba mendorong pikiran saya untuk menjumpai Tuhan. Namun, dia tetap terasa sebagai pengawas yang dengan ketat mencermati semua pelanggaran aturan yang saya lakukan atau benar-benar tidak hadir. Semakin banyak saya membaca tentang kekhusyukan para rahib dalam berdoa, semakin saya merasa gagal. Saya menjadi sadar betapa miskinnya pengalaman keagamaan saya, itu pun telah direkayasa oleh perasaan dan imajinasi saya sendiri. Terkadang, rasa pengabdian muncul sebagai respons estetik terhadap keindahan senandung Gregorian dan liturgi. Akan tetapi, tak satu pun yang sungguh-sungguh terjadi pada diri saya yang berasal dari kekuatan di luar diri saya. Saya tidak pernah membayangkan Tuhan sebagaimana digambarkan oleh para nabi dan kaum mistik. Yesus Kristus, yang lebih sering dibicarakan orang Kristen ketimbang “Tuhan” itu sendiri, tampaknya cuma merupakan figur historis murni yang terjalin erat dengan masa lalu. Saya juga mulai punya keraguan besar terhadap doktrin gereja. Bagaimana mungkin mengetahui dengan pasti bahwa Yesus sang manusia merupakan inkarnasi Tuhan dan apa arti kepercayaan itu? Apakah Perjanjian Baru benar-benar mengajarkan doktrin Trinitas yang rumit – dan sangat kontradiktif – atau, sebagaimana banyak aspek keimanan lainnya, merupakan hasil buatan para teolog berabad-abad setelah wafatnya Yesus di Yerusalem?
Akhirnya, dengan penuh penyesalan, saya meninggalkan kehidupan di biara, dan, segera setelah terbebaskan dari beban kegagalan dan ketakmampuan yang mengendap dalam diri saya, saya pun merasakan betapa keimanan saya kepada Tuhan diam-diam menyurut. Dia tidak pernah mengunjungi hidup saya walaupun saya telah mengerahkan segenap usaha terbaik untuk memungkinkan hal itu dilakukannya. Kini, saya tidak lagi merasa berdosa dan mencemaskannya. Dia terlalu jauh dari kemungkinan untuk menjadi suatu realitas. Akan tetapi, perhatian saya kepada agama terus berlanjut. Saya merancang sejumlah acara televisi mengenai sejarah awal Kristen dan hakikat pengalaman keagamaan. Semakin saya mempelajari sejarah agama, semakin saya mendapat pembenaran akan keraguan yang telah ada dalam diri saya sebelumnya. Doktrin-doktrin Kristen yang pernah saya terima dengan tidak kritis ketika kecil ternyata memang buatan manusia, yang telah dikonstruksikan selama berabad-abad silam. Sains tampaknya telah mengesampingkan Tuhan Pencipta dan para sarjana biblikal telah membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya suci. Sebagai pengidap epilepsi, saya kadang melihat kilasan yang saya ketahui sebagai sekadar gangguan neurologis semata: apakah penampakan dan kekhusyukan yang dialami orang-orang suci itu juga sekadar gangguan mental? Tuhan semakin tampak sebagai sesuatu yang sudah diterima begitu saja oleh manusia. Selama menjadi biarawati, saya tidak percaya bahwa pengalaman saya tentang Tuhan adalah pengalaman yang istimewa. Gagasan saya tentang Tuhan telah terbentuk di masa kecil dan tidak berkembang lagi seperti pengetahuan saya dalam disiplin ilmu yang lain. Saya telah memperbaiki pandangan kekanak-kanakan saya yang simplistik tentang Tuhan Bapa; saya telah mendapatkan pemahaman yang lebih matang tentang kompleksitas keadaan manusia daripada yang mungkin saya miliki di masa kanak-kanak. Namun, ide-ide masa kecil saya yang membingungkan tentang Tuhan belum berubah atau berkembang. Banyak orang yang tidak memiliki latar belakang keagamaan seperti saya mungkin juga mendapatkan bahwa pandangan mereka tentang Tuhan pun telah terbentuk di masa kecil. Sejak saat itu pula, kita telah meninggalkan hal-hal keka-nak-kanakan dan membuang gagasan tentang Tuhan masa kecil kita.
Namun, kajian saya tentang sejarah agama telah mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk spiritual. Ada alasan kuat untuk berpendapat bahwa Homo sapiens juga merupakan Homo religiosus. Manusia mulai menyembah dewa-dewa segera setelah mereka menyadari diri sebagai manusia; mereka menciptakan agama-agama pada saat yang sama ketika mereka menciptakan karya-karya seni. Ini bukan hanya karena mereka ingin menaklukkan kekuatan alam; keimanan awal ini mengekspresikan ketakjuban dan misteri yang senantiasa merupakan unsur penting pengalaman manusia tentang dunia yang menggentarkan, namun indah ini. Sebagaimana seni, agama merupakan usaha manusia untuk menemukan makna dan nilai kehidupan, di tengah derita yang menimpa wujud kasatnya. Seperti aktivitas manusia lainnya, agama dapat disalahgunakan, bahkan tampaknya justru itulah yang selalu kita lakukan. Ini bukanlah hal yang secara khusus melekat pada para penguasa atau pendeta sekular yang manipulatif, melainkan adalah sesuatu yang sangat alamiah bagi manusia. Sekularisme kita sekarang ini merupakan eksperimen yang sepenuhnya baru, yang belum pernah ada presedennya di dalam sejarah manusia. Kita masih perlu menyaksikan keberhasilannya. Namun, tak kalah benarnya jika dinyatakan bahwa humanisme liberal Barat bukanlah sesuatu yang secara alamiah datang kepada kita; sebagaimana apresiasi atas seni atau puisi, ia harus ditumbuhkan. Humanisme itu sendiri merupakan sebuah agama tanpa Tuhan – tidak semua agama, tentunya, bersifat teistik. Cita-cita etika sekular kita mempunyai disiplin pikiran dan hatinya sendiri dan menyediakan bagi manusia sarana untuk menemukan keyakinan pada makna tertinggi kehidupan manusia seperti yang pernah disediakan oleh agama-agama konvensional.
Ketika saya mulai meneliti sejarah ide dan pengalaman tentang Tuhan dalam tiga kepercayaan monoteistik yang saling berkaitan – Yahudi, Kristen, dan Islam – saya berharap menemukan bahwa Tuhan hanya merupakan proyeksi kebutuhan dan hasrat manusia. Saya kira “dia” akan mencerminkan rasa takut dan kerinduan masyarakat pada setiap tahapan perkembangannya. Prediksi-prediksi saya tidak seluruhnya tidak terbukti, tetapi saya benar-benar dikejutkan oleh beberapa penemuan saya. Seandainya saya telah mengetahui semua itu tiga puluh tahun lalu, ketika saya mulai menjalani kehidupan di biara, pengetahuan itu tentu akan menyelamatkan saya dari ketegangan ketika mendengar – dari para monoteis terkemuka ketiga agama itu – bahwa ketimbang menanti Tuhan untuk turun dari ketinggian, saya mesti secara sengaja menciptakan rasa tentang dia di dalam diri saya. Para rahib, pendeta, dan sufi yang lain menyalahkan saya karena mengasumsikan bahwa Tuhan – dalam pengertian apa pun – adalah realitas yang “ada di luar sana”. Mereka dengan tegas memperingatkan saya untuk tidak berharap mengalami Tuhan sebagai fakta objektif yang bisa ditemukan melalui proses pemikiran rasional biasa. Mereka tentu akan mengatakan kepada saya bahwa dalam pengertian tertentu, Tuhan merupakan produk imajinasi kreatif, seperti halnya seni dan musik yang bagi saya sangat inspiratif. Beberapa monoteis terkemuka bahkan dengan tenang dan tegas mengatakan kepada saya bahwa Tuhan tidak sungguh-sungguh ada – namun demikian “dia” adalah realitas terpenting di dunia.
Buku ini bukanlah tentang sejarah realitas Tuhan yang tak terucapkan itu, yang berada di luar waktu dan perubahan, melainkan merupakan sejarah persepsi umat manusia tentang Tuhan sejak era Ibrahim hingga hari ini. Gagasan manusia tentang Tuhan memiliki sejarah, karena gagasan itu selalu mempunyai arti yang sedikit berbeda bagi setiap kelompok manusia yang menggunakannya di berbagai periode waktu. Gagasan tentang Tuhan yang dibentuk oleh sekelompok manusia pada satu generasi bisa saja menjadi tidak bermakna bagi generasi lain. Bahkan, pernyataan “saya beriman kepada Tuhan” tidak mempunyai makna objektif, tetapi seperti pernyataan lain umumnya, baru akan bermakna jika berada dalam suatu konteks, misalnya, ketika dicetuskan oleh komunitas tertentu. Akibatnya, tidak ada satu gagasan pun yang tidak berubah dalam kandungan kata “Tuhan”. Kata ini justru mencakup keseluruhan spektrum makna, sebagian di antaranya ada yang bertentangan atau bahkan saling meniadakan. Jika gagasan tentang Tuhan tidak memiliki keluwesan semacam ini, niscaya ia tidak akan mampu bertahan untuk menjadi salah satu gagasan besar umat manusia. Ketika sebuah konsepsi tentang Tuhan tidak lagi mempunyai makna atau relevansi, ia akan diam-diam ditinggalkan dan digantikan oleh sebuah teologi baru. Seorang fundamentalis akan membantah ini, karena fundamentalisme antihistoris; mereka meyakini bahwa Ibrahim, Musa, dan nabi-nabi sesudahnya semua mengalami Tuhan dengan cara yang persis sama seperti pengalaman orang-orang pada masa sekarang. Namun, jika kita memperhatikan ketiga agama besar kita, menjadi jelaslah bahwa tidak ada pandangan yang objektif tentang “Tuhan”: setiap generasi harus menciptakan citra Tuhan yang sesuai baginya. Hal yang sama juga terjadi pada ateisme. Pernyataan “saya tidak percaya kepada Tuhan” mengandung arti yang secara sepintas berbeda pada setiap periode sejarah. Orang-orang yang diberi julukan “ateis” selalu menolak konsepsi tertentu tentang ilah. Apakah “Tuhan” yang ditolak oleh ateis masa sekarang adalah Tuhannya para patriark, Tuhan para nabi, Tuhan para filosof, Tuhan kaum sufi, atau Tuhan kaum deis Abad ke-18? Semua ketuhanan ini telah dimuliakan sebagai Tuhan Alkitab dan Al-Quran oleh umat Yahudi, Kristen, dan Islam pada berbagai periode perjalanan sejarah mereka. Kita akan menyaksikan bahwa mereka sangat berbeda satu sama lain. Ateisme sering merupakan keadaan transisi, makanya orang Yahudi, Kristen, dan Muslim disebut “ateis” oleh kaum pagan semasa mereka karena telah mengadopsi gagasan revolusioner tentang keilahian dan transendensi. Apakah ateisme modern merupakan penolakan serupa terhadap “Tuhan” yang tidak lagi memadai bagi persoalan di zaman kita?
Terlepas dari sifat nonduniawinya, agama sesungguhnya bersifat pragmatik. Kita akan menyaksikan bahwa sebuah ide tentang Tuhan tidak harus bersifat logis atau ilmiah, yang penting bisa diterima. Ketika ide itu sudah tidak efektif lagi, ia akan diganti – terkadang dengan ide lain yang berbeda secara radikal. Hal ini tidak dipusingkan oleh kebanyakan kaum monoteis sebelum era kita sekarang karena mereka tahu bahwa gagasan mereka tentang Tuhan tidaklah sakral, tetapi pasti akan mengalami perubahan. Gagasan-gagasan itu sepenuhnya buatan manusia – tak bisa tidak – dan jauh berbeda dari Realitas tak tergambarkan yang disimbolkannya. Ada pula yang mengembangkan cara-cara yang sangat berani untuk menekankan perbedaan esensial ini. Salah seorang mistikus Abad Pertengahan melangkah lebih jauh hingga mengatakan bahwa Realitas tertinggi itu – yang secara keliru dinamai “Tuhan” – bahkan tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab. Sepanjang sejarah, manusia telah mengalami dimensi ruhaniah yang tampaknya melampaui dunia material. Adalah salah satu karakteristik pikiran manusia yang mengagumkan untuk mampu menciptakan konsep-konsep yang menjangkau jauh seperti itu. Apa pun tafsiran kita atas hal itu, pengalaman manusia tentang yang transenden ini telah menjadi sebuah fakta kehidupan. Tidak semua orang memandangnya ilahiah; orang Buddha, sebagaimana nanti akan kita lihat, akan menolak bahwa visi dan wawasan yang diperoleh lewat pengalaman itu berasal dari suatu sumber supranatural. Mereka menganggapnya sebagai hal yang alamiah bagi kemanusiaan. Akan tetapi, semua agama besar akan sepakat bahwa adalah mustahil untuk menggambarkan transendensi ini dalam bahasa konseptual biasa. Kaum monoteis menyebut transendensi ini “Tuhan”, namun mereka membatasinya dengan syarat-syarat penting. Yahudi, misalnya, dilarang mengucapkan nama Tuhan yang sakral, sedangkan umat Islam tidak diperkenankan melukiskan Tuhan secara visual. Disiplin semacam itu merupakan pengingat bahwa apa yang kita sebut “Tuhan” berada di luar ekspresi manusia.
Ini bukan sejarah dalam pengertian biasa, sebab gagasan tentang Tuhan tidak tumbuh dari satu titik kemudian berkembang secara linear menuju suatu konsepsi final. Teori-teori ilmiah mempunyai sistem kerja seperti itu, tetapi ide-ide dalam seni dan agama tidak. Sebagaimana dalam puisi cinta, orang berulang kali menggunakan ungkapan yang sama tentang Tuhan. Bahkan, kita dapat menemukan kemiripan telak dalam gagasan tentang Tuhan di kalangan orang Yahudi, Kristen, dan Islam. Meskipun orang Yahudi maupun Islam memandang doktrin Trinitas dan Inkarnasi sebagai suatu kekeliruan, mereka juga mempunyai teologi-teologi kontroversial versi mereka sendiri. Setiap ekspresi yang amat bervariasi tentang tema-tema universal ini memperlihatkan kecerdasan dan kreativitas imajinasi manusia ketika mencoba mengekspresikan pe-mahamannya tentang “Tuhan”.
Karena ini merupakan sebuah subjek yang luas, saya sengaja membatasi diri hanya mengkaji tentang Tuhan Yang Esa yang disembah oleh umat Yahudi, Kristen, dan Islam meski terkadang saya juga menyinggung konsepsi kaum pagan, Hindu, dan Buddha tentang realitas tertinggi untuk memperjelas suatu pandangan monoteistik. Tampaknya, ide tentang Tuhan dalam ajaran agama-agama yang berkembang secara sendiri-sendiri tetap memiliki banyak keserupaan. Apa pun kesimpulan yang kita capai tentang realitas Tuhan, sejarah gagasan ini dapat mengatakan kepada kita sesuatu yang penting mengenai pikiran manusia dan inti aspirasi kita. Di tengah kecenderungan sekular di kalangan masyarakat Barat, ide tentang Tuhan masih mempengaruhi kehidupan jutaan orang; tetapi pertanyaannya adalah, “Tuhan” menurut konsep mana yang mereka anut?
Teologi sering memberikan penjelasan yang membosankan dan abstrak. Akan tetapi, sejarah Tuhan penuh gairah dan ketegangan. Tidak seperti beberapa konsep lain tentang realitas tertinggi, sejarah ini pada awalnya dipenuhi pertarungan dan tekanan yang mengakibatkan penderitaan. Nabi-nabi Israel mengalami Tuhan mereka sebagai penderitaan fisik yang menimpa segenap anggota tubuh mereka dan memenuhinya dengan suka maupun duka. Realitas yang disebut Tuhan acap dialami para monoteis dalam keadaan ekstrem: kita akan membaca tentang puncak gunung, kegelapan, keterasingan, penyaliban, dan teror. Pengalaman Barat tentang Tuhan tampak agak traumatik. Apa alasan bagi ketegangan inheren ini? Kaum monoteis lainnya berbicara tentang cahaya dan transfigurasi. Mereka menggunakan gambaran yang amat berani untuk mengungkapkan kerumitan realitas yang mereka alami, yang jauh melampaui teologi ortodoks.
Belakangan ini perhatian terhadap mitologi bangkit kembali, yang mungkin menunjukkan luasnya hasrat akan ekspresi yang lebih imajinatif tentang kebenaran agama. Karya mendiang sarjana Amerika Joseph Campbell telah menjadi begitu populer; dia melakukan pengkajian mendalam tentang mitologi perenial manusia, menghubungkan mitos-mitos kuno dengan mitos-mitos yang hingga kini masih hidup di kalangan masyarakat tradisional. Sering diasumsikan bahwa Tuhan ketiga agama besar itu sama sekali tidak memiliki simbolisme mitologi dan syair. Namun demikian, sekalipun kaum monoteis pada dasarnya menolak mitos-mitos tetangga pagan mereka, mitos-mitos itu ternyata sering kembali masuk ke dalam keimanan pada masa berikutnya. Kaum mistik melihat bahwa Tuhan berinkarnasi ke dalam tubuh seorang wanita, misalnya. Sementara yang lain secara khidmat memperbincangkan seksualitas Tuhan dan memasukkan unsur feminin kepada Tuhan.
Ini membawa saya ke titik yang sulit. Karena Tuhan ini telah terlanjur secara khusus dikenal sebagai berjenis “laki-laki”, dan dalam bahasa Inggris kaum monoteis lazim merujuk kepada-Nya dengan kata ganti “he”. Pada masa sekarang, kaum feminis dengan sangat sadar menaruh keberatan terhadap hal ini. Penggunaan kata ganti maskulin untuk Tuhan ini menimbulkan persoalan dalam sebagian bahasa bergender. Akan tetapi, dalam bahasa Yahudi, Arab, dan Perancis, gender gramatikal memberikan nada dan dialektika seksual terhadap diskursus teologis, yang justru dapat memberikan keseimbangan yang sering tidak terdapat di dalam bahasa Inggris. Misalnya, kata Arab Allah (nama tertinggi bagi Tuhan) adalah maskulin secara gramatikal, tetapi kata untuk esensi Tuhan yang ilahiah dan tak terjangkau – al-Dzat – adalah feminin.
Semua perbincangan tentang Tuhan adalah perbincangan yang sulit. Namun, kaum monoteis bersikap amat positif tentang bahasa sembari tetap menyangkal kapasitasnya untuk mengekspresikan realitas transenden. Tuhan orang Yahudi, Kristen, dan Islam adalah Tuhan yang – dalam beberapa pengertian – berkata-kata (berfirman). Firmannya sangat krusial di dalam ketiga agama besar itu. Firman Tuhan telah membentuk sejarah kebudayaan kita. Kita harus memutuskan apakah kata “Tuhan” masih tetap memiliki makna bagi kita pada masa sekarang.[]
(Dinukil dari kata pengantar buku Sejarah Tuhan: Kisah 4.000 Tahun Pencarian Tuhan dalam Agama-agama Manusia [Mizan, 2018] karya Karen Armstrong)
(Karen Armstrong adalah penulis sejumlah buku tentang agama, di antaranya The Case for God, A History of God, The Battle for God, Holy War, dan Jerusalem. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam 45 bahasa)