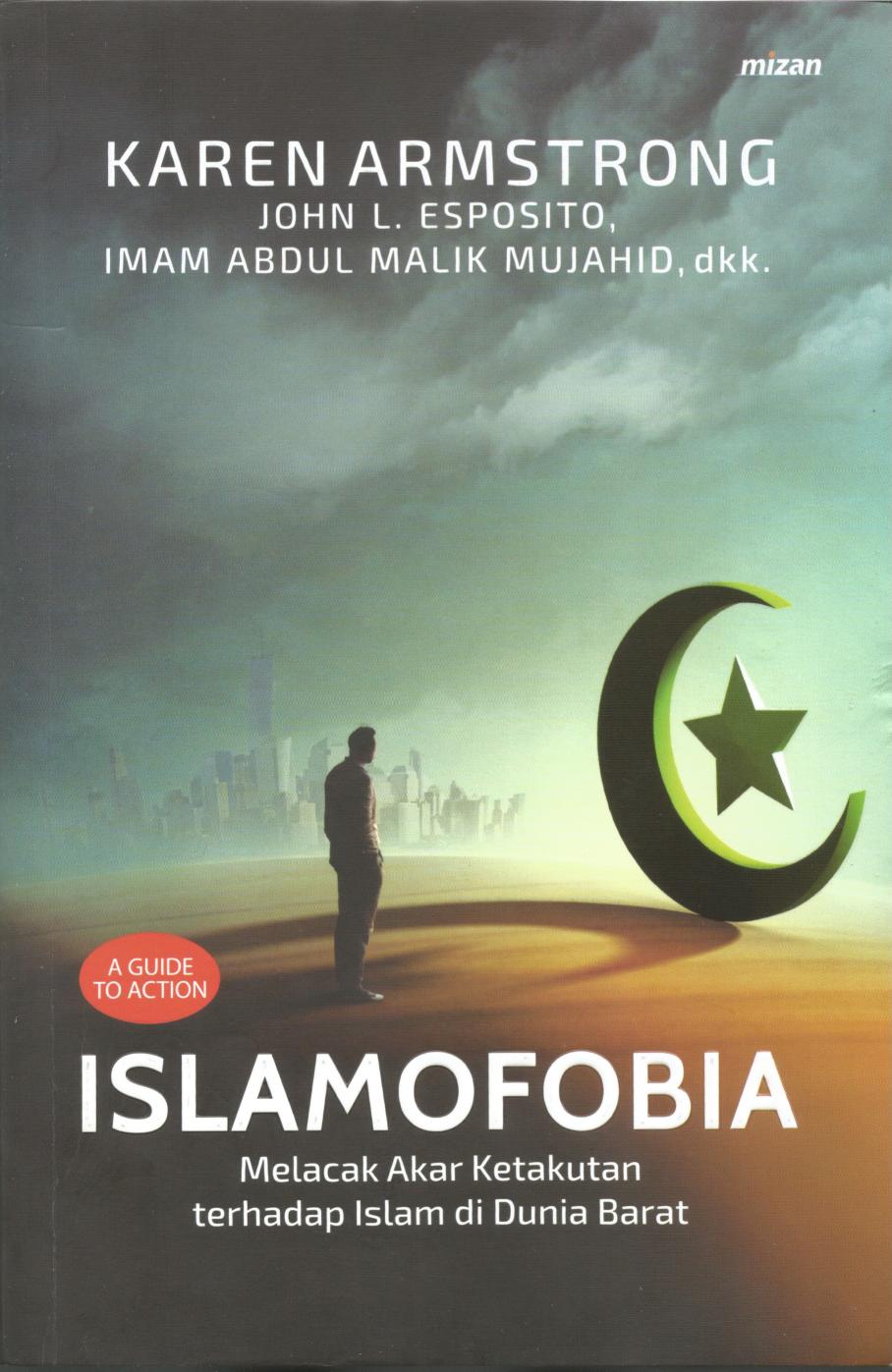Dalam Islamofobia: Melacak Akar Ketakutan terhadap Islam di Dunia Barat, Karen Armstrong dan Dilwar Hussain menunjukkan sekularisme tak datang secara alamiah tapi dipaksakan dengan kekerasan. Sekularisme puritan seperti ini malah bisa memicu benturan antarperadaban.
RATUSAN orang berduka di halaman perguruan tinggi ternama di Perancis, Universitas Sorbonne, Rabu, 21 Oktober 2020. Mereka mengenang Samuel Paty (47 tahun), guru sejarah dan kewarganegaraan di sebuah sekolah menengah. Delapan pria tegap berseragam membopong peti mati Paty ke lokasi perhelatan duka diiringi lagu One dari band rock asal Irlandia U2.
Lima hari sebelumnya, warga Perancis asal Chechnya, Abdoullakh Anzorov (18 tahun), memenggal Paty di kota pinggiran Paris. Paty diincar si pembunuh karena saat mengajarkan kebebasan berekspresi di kelas, menunjukkan kartun-kartun Nabi Muhammad yang pernah dimuat tabloid satire, Charlie Hebdo, beberapa tahun lalu.
Publik Perancis pun berduka dan marah. Seruan “Je suis Samuel” pun berkumandang di jalanan dan jagat maya. Tuduhan bahwa Islam sebagai sumber kekejaman dan teror kembali menggema. Suara publik perancis yang direkam jajak pendapat menyatakan kecemasan bahwa warga muslim—yang kebanyakan adalah imigran—tak mampu beradaptasi dengan nilai-nilai Perancis yang sangat dibanggakan: sekularisme atau disebut laïcité.
Sebelum dan setelah pembunuhan atas Paty, sejumlah kekerasan terjadi, baik terhadap warga muslim maupun non-muslim. Yang terakhir terjadi di Nice ketika warga keturunan Tunisia menggorok dua jemaat gereja dan menusuk hingga tewas satu jemaat lainnya1.
Warga dan organisasi muslim juga mengutuk tindakan Anzorov. Pada saat yang sama, mereka menyampaikan perasaan terintimidasi oleh kartun-kartun Charlie Hebdo dan bahkan menjadi target utama kebijakan-kebijakan laïcité.
Seperti pendahulunya, Nicolas Sarkozy dan François Hollande, Presiden Perancis Emmanuel Macron tampil di publik membela laïcité. “Kami tidak akan menyerah soal kartun,” kata politisi sayap tengah ini di hadapan 400-an pelayat Paty di Sorbonne. Pernyataan yang sebenarnya lazim keluar dari mulut elite politik Perancis itu kembali memicu protes keras di negeri-negeri muslim.
Tragedi yang menimpa Paty dan suasana yang melingkupinya bak dèjà vu. Lima tahun lalu, suasana serupa meruap setelah kantor redaksi Charlie Hebdo diserang ekstremis muslim hingga belasan orang terbunuh (termasuk dua muslim: seorang satpam dan pejalan kaki). Tak ada yang baru. Semuanya seperti film “rusak” yang diputar ulang. Ia terjadi lagi dan lagi, seakan umat manusia tak pernah bisa belajar dari sejarahnya sendiri.
Apa yang terjadi di Perancis pada tahun pandemi ini juga tak bisa dilepaskan dari sejumlah faktor. Pada awal Oktober, Macron mengajukan rancangan undang-undang anti-separatisme. Beleid ini, menurut sejumlah laporan, secara khusus menargetkan kelompok muslim yang dinilai “radikal”, atau yang dalam leksikon politik Perancis disebut “communitarianisme” dan kemudian diganti oleh Macron dengan istilah “separatisme”. Banyak analis menilai beleid itu bagian dari langkah politik Macron menjelang pemilihan presiden 2022, menghadapi kelompok sayap kanan yang menilainya terlalu lembek terhadap para communitarian2.
Lalu, persoalannya adalah benarkah ajaran Islam dan muslim secara umum tak kompatibel dengan sekularisme? Benarkah Islam, atau agama secara umum, menginspirasi kekerasan?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, saya teringat dengan Islamofobia: Melacak Akar Ketakutan terhadap Islam di Dunia Barat. Buku yang berjudul asli Islamophobia: Guidebook ini karya keroyokan sejumlah intelektual, seperti Karen Armstrong, John L Esposito, Tariq Ramadan, Vanita Gupta, Dilwar Hussain, dan Barbara Kaufmann. Sebagian besar isi buku sebenarnya lebih banyak memaparkan upaya-upaya praktis dalam merespons prasangka anti-muslim di Barat. Tapi, ada dua artikel yang secara khusus ditulis untuk mengulas sekularisme: “Sejarah Sekularisme yang Penuh Kekerasan” oleh Armstrong dan “Sekularisme dan Islam” oleh Hussain.
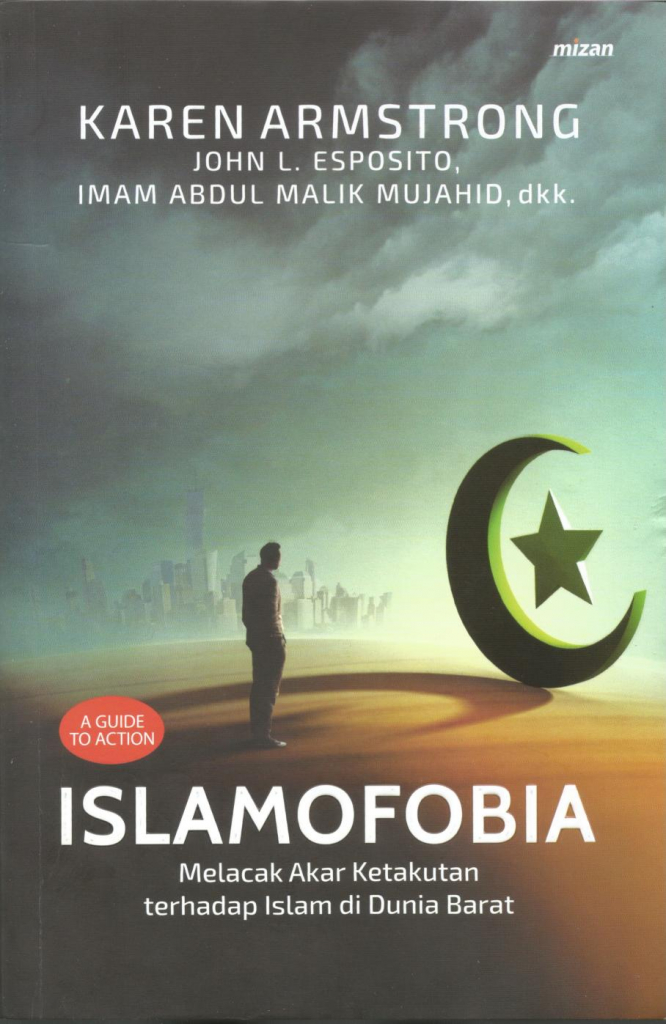
- Judul Buku: Islamofobia: Melacak Akar Ketakutan terhadap Islam di Dunia Barat
- Penulis: Karen Armstrong, dkk.
- Penebit: PT Mizan Pustaka
- Terbit: 2016
- Tebal: 349 halaman
Dua artikel itu menarik karena mengajukan antitesis atas anggapan bahwa agama sumber inspirasi kekerasan dan agama, atau Islam secara khusus, tak bersesuaian dengan sekularisme. Tesis Armstrong dan Hussain adalah: agama bukan faktor tunggal serangkaian kekejaman dalam peradaban manusia; sekularisme bukan gejala alamiah tapi dipaksakan dengan kekerasan; dan mayoritas muslim justru bisa menerima sekularisme.
Armstrong menunjukkan bukti historis untuk mendukung tesis di atas. Dalam Perang Tiga Puluh Tahun (1618-1648), yang termasuk ke dalam tiga abad Peperangan Agama di Eropa (Wars of Religion), sekalipun, agama bukanlah pemicu utama meskipun pihak-pihak yang meradang di dalamnya merasakan spirit sektarian. Perang ini justru lebih bisa dipahami sebagai “sekelompok pendiri negara melawan sekelompok pendiri negara lain” atau lebih bisa dikatakan diprovokasi oleh ambisi kekuasaan dan perluasan wilayah. Perang itu berujung dengan berdirinya negara-negara kecil di Eropa yang dikuasai para pangeran dan panglima perang sementara otoritas agama justru makin diasingkan dari dunia politik.
Bahkan, dalam peperangan yang kerap dianggap sebagai Protestan melawan Katolik itu, batas-batas keagamaan ternyata tak mudah ditentukan. Kekuatan Katolik di wilayah tertentu beraliansi dengan kekuatan Protestan melawan kekuatan Katolik di wilayah lain, dan begitu sebaliknya. Jadi, memisahkan Protestan dan Katolik dalam perang yang membunuh jutaan orang itu nyaris mustahil, atau dalam istilah Armstrong bak “mengeluarkan gin dari minuman koktail”.
Di Abad ke-21, perang di Suriah bisa menjadi contoh aktual. Perang yang “dipasarkan” sebagai Sunni versus Syiah ini terbukti melibatkan faktor-faktor lain (politik dan ekonomi) yang berkelindan dan bahkan lebih fundamental. Alhasil, tak mudah memberi batasan mana petempur Sunni dan Syiah dalam perang tersebut. Sebab, petempur Sunni, Syiah, dan bahkan Kristen bahu-membahu berjibaku melawan pasukan “Sunni” ekstremis yang didukung kekuatan-kekuatan Arab dan Barat.
Itu fakta dalam peperangan yang jelas-jelas disebut—atau setidaknya coba “dijual”—sebagai perang agama. Belum lagi jika diajukan bukti tak terbantahkan Perang Dunia I dan II yang membunuh puluhan juta manusia, jelaslah pernyataan “agama sumber kekejaman dan perang” lebih merupakan mitos daripada kenyataan.
Armstrong kemudian menyatakan, alih-alih agama sumber kekerasan, sekularisme justru lahir dari rahim kekerasan. Di Eropa—dan kemudian di negeri-negeri jajahan Eropa—sekularisme bukanlah sesuatu yang muncul alamiah akibat, katanya, kekecewaan orang terhadap kolusi kaum agamawan dengan kaum aristokrat. Tapi, sekularisme dipaksakan melalui jalan pedang. Itu juga berarti dunia politik dan domain publik yang disapih dari nilai-nilai agama tak serta merta mendatangkan kedamaian.
Perang Kaum Tani (Deutscher Bauernkrieg) di Jerman (1524-1525) dipicu oleh upaya count dan baron di Jerman mendirikan negara-negara baru absolut yang terpisah dari kekuasaan gereja. Mereka, dalam upaya itu, hendak merampas hak-hak tradisional kaum tani. Para bangsawan didukung reformis Protestan sekaligus salah satu penganjur awal sekularisme, Martin Luther.
Bagi Luther, kehidupan di dunia tak mungkin bisa damai tanpa ketidaksetaraan, sehingga agama yang penuh welas asih harus menyingkir dan berkonsetrasi di dunia spiritual nun jauh di sana. Rakyat harus menerima takdir mereka bekerja dan terus bekerja sementara para bangsawan mengelola kekuasaan.
Dalam tulisannya Against the Murderous, Thieving Hordes of Peasants, Luther terang-terangan menyebut pemberontakan kaum tani sebagai pekerjaan iblis. Dia juga menyerukan para bangsawan untuk memberangus para pemberontak layaknya sekumpulan anjing gila.
Armstrong menyatakan sekularisme awal adalah sebuah ide ekstrem. Sebab, hingga Abad ke-18, orang-orang Eropa tak pernah mengenal pemisahan nilai-nilai agama dalam kebijakan publik. Nilai-nilai agama juga tidak pernah dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebajikan publik, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Secara etimologis, Armstrong juga menunjukkan kata religion di Barat, dîn di Arab, atau dharma di Sankskerta mengacu kepada hal-hal luas dan inklusif. Dengan memisahkan agama dari politik, Armstrong menilai publik justru akan kehilangan nilai-nilai ajaran agama itu.
Dalam perkembangannya, menurut Armstrong, ketika menyingkirkan agama, sekularisme pada dasarnya menciptakan agama-agama dan tuhan-tuhan baru bernama “kebebasan” dan “negara-bangsa”. Kekejaman atas nama “negara-bangsa” bahkan mungkin lebih banyak terjadi daripada “atas nama agama”, baik itu di Eropa maupun kemudian di negeri-negeri jajahan. “Jika kita mendefinisikan ‘yang sakral’ sebagai apa yang kita tukarkan dengan nyawa kita, apa yang disebut Benedict Anderson sebagai ‘komunitas imajiner’ bangsa memang telah menggantikan Tuhan. Kini, mati demi negara dianggap mengagumkan, sedangkan mati untuk agama tidak,” tulis Armstrong.
Seperti halnya agama, sekularisme juga memendam benih puritanisme atau ambisi menjadi murni sehingga liyan harus beradaptasi dengannya. Gerakan Turki Muda di Turki, yang membangun rezim di atas fondasi sekularisme, berambisi menciptakan bangsa Turki yang murni. Ambisi inilah yang melahirkan horor pembantaian pertama di Abad ke-20 atas satu juta warga Armenia.
Puritanisme sekuler juga bisa kita lihat pada kolonialisme Eropa atas bangsa-bangsa Amerika, Afrika, dan Asia. Warga di tanah jajahan dipandang “kaum primitif” atau “nyaris manusia” sebagian besarnya karena kepercayaan, tradisi, dan agama mereka. Menurut Armstrong, itulah alasan mengapa para humanis-sekuler enggan memperluas cakupan kebebasan dan hak-hak asasi kepada warga tanah jajahan. Para penganjur sekularisme seperti Thomas Jefferson dan James Madison tetap memelihara budak-budak Afrika. Napoleon mewajibkan orang-orang Yahudi mengganti nama-nama mereka dengan nama-nama Perancis.
Di Eropa dalam periode yang dikenal dengan “Reign of Terror”, misalnya, banyak umat Katolik dibunuh, praktik-praktik keagamaan diberangus, dan “dewi-dewi akal” (diperankan sosok wanita dalam pakaian provokatif) dinobatkan di altar-altar gereja. Penghinaan terhadap agama mencapai klimaksnya pada masa-masa itu.
Charlie Hebdo mungkin representasi postmodern dari fanatisme anti-agama. Kartun-kartun mereka menunjukkan kevulgaran semata demi kevulgaran. Tabloid ini memperolok perilaku kelompok tertentu dari suatu agama dengan menistakan figur-figur sakral agama itu.
Sebelum kehebohan kartun Nabi Muhammad muncul, Vatikan mungkin sudah bosan memperingatkan Charlie Hebdo. Hingga 2011, organisasi-organisasi Katolik dilaporkan telah 13 kali menggugat tabloid tersebut3. Sebagai agama yang telah menghadapi fanatisme anti-agama selama ratusan tahun, menurut Pascal-Emmanuel Gobry, Gereja Katolik mungkin merasa kalah sehingga kini bisa “berdamai” dengan kaum fanatik anti-agama4.
Lantas, mengapa muslim tampak tidak bisa berdamai? Dan, bahkan sebagiannya memilih jalan kekerasan?
Hussain dalam “Sekularisme dan Islam” membagi sekularisme menjadi: (1) sekularisme berupa netralitas negara di ranah publik; (2) sekularisme berupa sentimen anti-agama yang ideologis, atau yang menurut saya bisa diistilahkan dengan “sekularisme puritan yang agresif”. Menurut Hussain, muslim bisa menerima sekularisme bentuk pertama. Ide khilafah dalam peradaban Islam, menurutnya, bukanlah pandangan normatif mayoritas muslim. Ide khilafah sesekali muncul ketika dunia muslim menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Nilai-nilai Islam, baik menurut Hussain maupun Armstrong, justru mempromosikan gagasan “kesetaraan, keadilan, kebebasan, dan hak asasi”—istilah-istilah sekuler-modern yang nilai-nilainya telah lebih dulu diajarkan para nabi dan orang bijak di masa lalu.
Hussain mengajukan sebuah terbitan British Secularism and Religion: Islam, Society and the State (2011) yang menyimpulkan warga muslim bisa menerima gagasan sekularisme bentuk pertama. Negara berposisi netral di ranah publik sementara pada saat yang sama nilai-nilai agama bisa diadopsi menjadi kebijakan publik setelah melalui deliberasi bernalar publik.
Jajak pendapat yang dilaksanakan Ifpod (Institut Perancis untuk Opini Publik) baru-baru ini juga menunjukkan bahwa hanya kurang dari 30 persen muslim Perancis (total sekitar empat jutaan) yang menolak hukum sekuler negara tersebut5. Artinya, mayoritas muslim menerima sekularisme. Tapi, ketika survei mengajukan pertanyaan seputar ekspresi privat tradisi keagamaan seperti hijab, burqa, atau burkini, sekitar 60 persen menyatakan akan membiarkan anak-anak perempuan mereka mengenakan model pakaian tersebut. Ini karena, menurut survei yang sama, duapertiga responden percaya bahwa laïcité membolehkan mereka mengekspresikan kultur keagamaan mereka.
Alhasil, ketika mengatakan ingin membangun Islam yang bisa beradaptasi dengan “Pencerahan” Eropa, Macron sebenarnya seperti mengajari ikan berenang. Mayoritas diam muslim sudah menunjukkan mereka bisa menerima sekularisme dalam bentuk netralitas negara dalam kebijakan publik.
Sebaliknya, sekularisme puritan-agresif itulah yang dirasakan mengintimidasi muslim. Sekularisme jenis ini tak hanya menuntut penyapihan agama dari domain publik tapi bahkan merepresi dan menista ekspresi privat tradisi keagamaan, seperti pemakaian simbol atau model berpakaian tertentu di ruang-ruang publik. Pemerintahan Macron belakangan malah berkeinginan menghidupkan kembali lembaga yang disebut “Secularism Observatory”, semacam “majelis ulama” di negeri-negeri muslim6.
Sosiolog Perancis, Farhad Khosrokhavar, memandang laïcité makin hari makin menjelma menjadi “agama baru” dengan seperangkat kode, aturan, dan kebijakan. Seperti juga agama konvensional, “agama baru” berupa “negara-bangsa” ini juga memiliki simbol sakral dan bahkan kultus, seperti bendera, lambang, lagu kebangsaan, hari raya, dan peristiwa-peristiwa sejarah7.
Sementara itu, minoritas muslim vokal yang menunjukkan ekstremisme ironisnya adalah kelompok yang justru dimanfaatkan Perancis dan Barat demi kepentingan politik, seperti dukungan mereka terhadap kelompok ekstremis dalam perang Suriah. Perancis adalah eksportir terbesar petempur asing di Suriah. Dari sekitar empat ribuan petempur asing di Suriah, Perancis menyumbang lebih daripada 900 orang8. Ini menunjukkan Perancis membiarkan warganya mengalami radikalisasi di luar negeri sementara setelah itu menolak merepatriasi para ekstremis itu. Dalam artikelnya yang lain, Armstrong juga menyinggung bahwa Barat harus bertanggung jawab kepada dunia terkait dukungannya kepada penyebaran ekstremisme dalam Islam, atau yang dia jelas-jelas sebut “wahabisme”.
Pada akhirnya, siapa pun dan kultur mana pun harus mau bergerak ke titik tengah dan menghindari polarisasi antara puritanisme sekuler dan puritanisme agama.[]
1Benoist, Chloé. “France tensions explained in six questions”. middleeasteye.net. 30 Oktober 2020.
2Bryant, Elizabeth. “As France mourns slain teacher Samuel Paty, some question secular values”. dw.com. 24 Oktober 2020.
3Karaian, Jason dan Gideon Lichfield. “Charlie Hebdo has had more legal run-ins with Christians than with Muslims”. qz.com. 8 Januari 2015.
4Gobry, Pascal-Emmanuel. “How the Catholic Church made its peace with Charlie Hebdo”. theweek.com. 9 Januari 2015.
5“Almost 30 percent of French Muslims reject secular laws, new poll finds”. france24.com. 18 September 2016.
6Bryant, Elizabeth. “As France mourns slain teacher Samuel Paty, some question secular values”. dw.com. 24 Oktober 2020.
7Ibid.
8The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union: Profiles, Threats and Policies. 2016. (The Hague: International Centre for Counter-Terrorism).