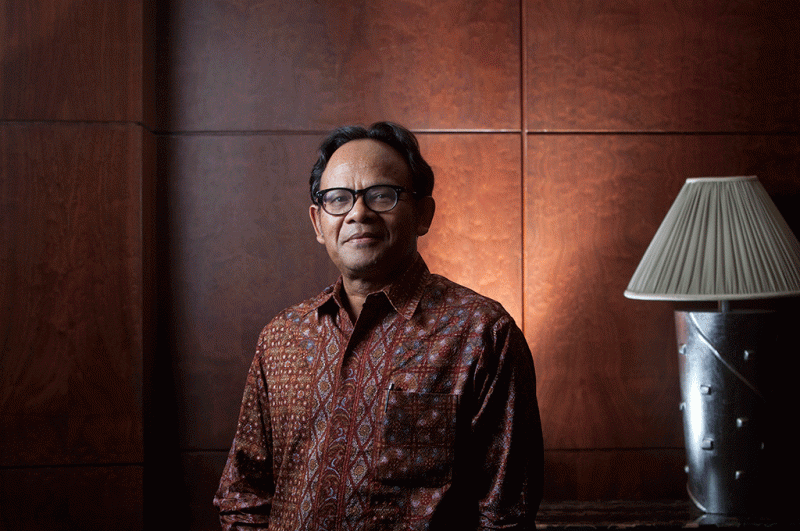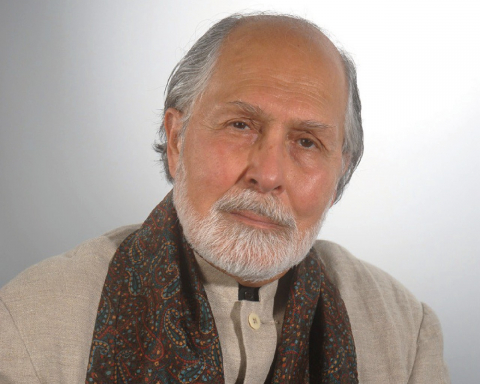Mengapa ada sebagian orang beragama yang selalu saja merasa tidak nyaman dalam hidupnya. Mereka mencari-cari kesalahan, menilai kesalehan, dan bahkan mengafirkan orang lain?
Oleh Komaruddin Hidayat
SALAH seorang pengagum Nelson Mandela suatu saat terlibat perbincangan dengannya. Dia begitu kagum, terutama setelah melihat langsung tempat tahanan Mandela yang pernah ditempatinya selama 14 tahun, dari keseluruhan masa hukuman selama 27 tahun secara berpindah-pindah. Sel tempat Mandela dihukum begitu sempit, bau, tak ada meja kursi, dan konon makanan yang disajikan seringkali basi. Dia bertanya, “Apakah Mandela yang kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan dan begitu dikagumi dunia tidak merasa geram dan dendam terhadap musuh-musuh politiknya di masa lalu? Apa jawab Mandela? “Kalau aku biarkan dan kupelihara terus kekesalan dan kebencianku kepada para penindas itu, mereka yang pernah menindas dan menyanderaku selama 27 tahun itu akan masih terus menyandera diri dan jiwaku. Aku ingin menjadi orang merdeka. Karena itu aku buang semua kebencian itu sehingga aku benar-benar merasa sebagai orang yang bebas dan merdeka.”
***
Suatu hari, saya datang pada seorang kiai untuk konsultasi agama. Saya bertanya, “Mengapa sesama muslim, bahkan di antaranya adalah tokoh agama, suka mencemooh Muslim lain yang berbeda pendapat? Bahkan, adakalanya mengafirkan serta menuduhnya sebagai ahli neraka. Kiai kampung tadi menjawab dengan datar, “Saya kurang tahu dalil apa yang dipakai. Kalau seseorang telah menyatakan dan menerima rukun iman dan rukun islam, dia tidak berhak disebut kafir. Jadi, saya tidak bisa menjawab mengapa kita mesti mengafirkan sesama muslim serta sibuk mau mengukur kedalaman imannya. Saya sendiri tidak berani menjamin diri saya masuk surga, terlebih menuduh orang lain. Jadi, maaf, coba saja tanyakan pada mereka yang suka mengukur-ukur ketakwaan orang.”
***
Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu hari Abu Bakar berjalan bersama Rasulullah. Di tengah jalan, tiba-tiba Abu Bakar dihadang oleh seseorang dan dicaci-maki. Abu Bakar merasa tidak kenal dan tidak bersalah sehingga dia diam saja sambil senyum-senyum. Abu Bakar tambah bingung lagi ketika melihat Rasulullah ikut senyum. Setelah orang itu agak lama melemparkan kata-kata cacian, Abu Bakar menjawab kelancangan orang tersebut. Ketika Abu Bakar membalas orang tersebut, Rasulullah berhenti tersenyum dan terus pergi.
Abu Bakar merasa penasaran akan sikap Rasulullah. Keesokan harinya, Abu Bakar bertanya pada beliau, “Mengapa Rasulullah tersenyum ketika orang itu mencaci maki dirinya yang tidak bersalah? Mengapa Rasulullah pergi ketika dirinya menjawab?” Rasulullah pun menjawab, “Ketika engkau tersenyum mendengarkan fitnah dan caci-maki tadi, engkau menerimanya dengan lapang karena engkau tidak bersalah. Aku pun tersenyum karena melihat malaikat sibuk memindahkan catatan amal kebajikan orang itu ke dalam dirimu, sedangkan catatan kesalahanmu dipindahkan ke orang itu.”
***
Pesan dan pelajaran apa yang bisa diambil dari tiga cerita pendek di atas? Dari kasus Mandela, saya memperoleh pelajaran bahwa kebahagiaan dan kemerdekaan berkait erat dengan sikap batin seseorang. Formula “to forgive and forget” terhadap tragedi masa lalu akan mampu mengubah dunia yang semula gelap gulita dan menyakitkan menjadi terang-benderang dan optimistik menapaki hari-hari esok. Semua ini kembali pada pribadi masing-masing orang. Akankah memelihara luka derita yang justru kian bertambah ketika diingat-ingat? Akankah mengurangi dan melupakannya, lalu diganti dengan cara pandang baru terhadap kehidupan?
Dari nasihat kiai tadi, saya belajar untuk hidup dengan bersangka baik dan rendah hati. Jangan merasa paling beriman dan bertakwa di hadapan orang lain. Saya jadi teringat sebuah hadis, berbahagialah mereka yang disibukkan dengan meneliti kesalahan dan kekurangan diri, lalu menutupinya dengan kebajikan daripada kerjanya sibuk melihat dan mengorek-ngorek kelemahan dan kesalahan orang lain. Kisah Abu Bakar mengajarkan kita untuk bersabar. Jika kita merasa benar, tak perlu takut akan kritik, kecaman, dan fitnah orang. Allah Mahatahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Lebih dari itu, mari kita jaga hati dan lisan agar tidak mudah menyakiti orang lain karena kita sendiri yang akan rugi.
Kisah-kisah kebajikan hidup seperti di atas mudah sekali kita temukan di sekeliling kita. Kalau saja kita mau membuka mata hati dan telinga, sehingga setiap hari pasti kita akan mendapatkan pembelajaran hidup yang bermakna.
Agama Ibarat Pakaian
Menyamakan agama dan pakaian tentu tidak terlalu tepat, meskipun keduanya memiliki kemiripan. Orang bisa melakukannya dengan mudah saja ketika berganti pakaian, kendaraan, kacamata, sepatu, bahkan berganti nama. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan ganti agama. Namun saya pun teringat sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, “Sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa.” (QS Al-A’raf [7]: 26). Takwa adalah hasil keberagamaan yang benar, sedangkan takwa oleh Allah dinyatakan sebagai sebaik-baik pakaian.
Apa dan mengapa pakaian? Mari kita renungkan dan bahas sejenak. Apa saja yang menjadi pertimbangan ketika kita mengenakan pakaian? Pertama, untuk menjaga kesehatan. Mereka yang tinggal di daerah dingin sangat sadar akan fungsi pakaian untuk menjaga kesehatan. Kedua, untuk menutup aurat. Fungsi ini mengingatkan kita terhadap cerita Adam yang terusir dari surga karena memakan buah khuldi. Lalu, Adam menemukan dirinya telanjang dan ia pun merasa malu. Ke-mudian, ia menutupi auratnya dengan dedaunan. Dan, salah satu aspek yang membedakan manusia dari monyet adalah manusia mengenal konsep aurat lalu mengenakan pakaian. Ketiga, orang berpakaian selalu mempertimbangkan aspek estetika atau seni agar indah dipandang. Bahkan, aspek keindahan ini telah membuat harga pakaian berlipat ganda ketika mendapat sentuhan perancang atau desainer ternama.
Inilah tiga fungsi utama pakaian yang bisa dianalogkan dengan agama. Seseorang yang beragama mestinya jiwa dan badannya menjadi sehat, kehormatan dirinya terjaga, dan perilaku serta tutur katanya enak dipandang dan didengar. Kalau ketiga hal tadi tidak ditemukan, pasti ada yang salah dengan dirinya atau ukuran pakaiannya yang tidak pas. Begitulah sikap keberagamaan. Ibarat pakaian yang ukurannya pas, mestinya dengan agama seseorang lebih percaya diri, enak bergaul, dan sehat jiwa raganya. Pendek kata, seseorang haruslah merasa nyaman terhadap dirinya di mana pun ia berada.
Tentu masih ada peran lain dari pakaian. Ada orang yang sengaja berdandan hanya untuk pamer. Maka dari itu, jangan heran, beragama pun bisa terkena jebakan pamer atau riya. Ada lagi pakaian yang dirancang untuk berperang. Jadi, bisa saja semangat beragama selalu disertai semangat untuk berantem dan mengalahkan orang lain.
Dari beragam pakaian yang ada, rasanya fungsi yang primer adalah tiga pertama yang disebutkan tadi. Hemat saya, beragama yang sehat dan benar adalah sikap keberagamaan yang mendatangkan rasa nyaman bagi diri sendiri dan enak dilihat bagi orang lain.
Seragam Itu Kurang Menarik
Sulit menerima kenyataan andaikan seluruh manusia telanjang bagaikan kerbau atau kambing. Akan tetapi, mari kita bayangkan andaikan semua penduduk bumi berpakaian, berbahasa, dan berperilaku seragam. Sungguh kurang menarik kalau dunia flora dan fauna semuanya seragam. Rasanya hidup membosankan dan sungguh tidak menarik. Jadi, apakah pluralitas agama dan budaya itu proses dan produk evolusi alam atau apakah hanya kehendak Sang Pencipta? Terserah orang mau memandangnya dengan teori apa, tetapi kenyataannya memang begitulah adanya. Boleh saja masing-masing misionaris agama berambisi untuk menyeragamkan keyakinan manusia agar terjadi monolitisme agama di muka bumi. Akan tetapi, sepanjang sejarah manusia rasanya keinginan itu sebuah utopia. Bahkan, semasa hidup para nabi, ada saja mereka yang berbeda dan membangkang.
Dalam dunia Islam pun muncul keragaman, pluralitas, dan warna-warni mazhab pemikiran agama, baik dalam ilmu fikih, ilmu kalam, tasawuf, filsafat, maupun pemikiran politik Islam. Belum lagi pemahaman, pengalaman, dan praktik pada level individu yang membuat keragamannya semakin kompleks. Ketika orang muslim sama-sama salat menghadap kiblat, misalnya, suasana batinnya berbeda-beda. Ketika sama-sama berdoa pada Allah, orang akan memilih pintu yang berbeda-beda dari 99 Asmaul Husna. Dan perlu diingat, angka 99 itu simbol dari pertemuan dua angka omega, artinya sifat dan kekuasaan Allah itu absolut dan tak terbatas. Orang yang lagi sakit akan lebih senang memanggil nama-Nya sebagai Tuhan sang Mahadokter (As-Syafy). Mereka yang merasa banyak dosa senang menyeru-Nya sebagai Sang Pengampun (Al-Ghafur). Demikianlah seterusnya.
Jadi, warna-warni pengalaman dan pemahaman beragama bisa terjadi pada wilayah esoterik (tidak kelihatan dari luar) dan ada yang terlihat dari luar (eksoterik), misalnya peristiwa perjalanan haji, jumlah rakaat dalam salat, dan semacamnya. Namun, kita tidak tahu secara pasti suasana batin di balik tindakan ritual keagamaan itu. Wilayah esoterik biasanya dikaitkan dengan pengalaman spiritual yang bersifat individual, sedangkan eksoterik lebih banyak menyangkut urusan prosedur dan formula hukum beragama (fikih).
Mahasiswa yang Usil
Seorang mahasiswa bertanya, “Mengapa masyarakat modern lebih menghargai jasa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) daripada agama? Mengapa mereka mau membayar mahal untuk membeli produk iptek modern, sementara panggilan agama kurang diperhatikan? Mengapa program studi agama kurang laku padahal ongkosnya jauh lebih murah ketimbang jurusan umum?”
Mahasiswa tadi melanjutkan kegelisihannya, “Jika posisi agama lebih tinggi ketimbang iptek, mengapa hidup ini lebih nyaman berkat jasa iptek daripada agama yang selalu menimbulkan perselisihan, konflik, dan peperangan? Ada sekelompok masyarakat atau bangsa yang merasa cukup nyaman tanpa agama, namun tidak bisa dipisahkan dari jasa iptek, supremasi hukum, dan kemakmuran ekonomi.”
Lagi-lagi, mahasiswa tadi meneruskan gejolak pikirannya. Coba kita amati kehidupan sekeliling. Sejak dari kondisi dalam rumah, di jalan, kantor, dan pusat-pusat keramaian serta gemerlapnya kota yang terlihat adalah produk iptek yang diharapkan dapat membuat kehidupan berlangsung lebih nyaman. Begitu juga halnya dengan televisi, jam tangan, kendaraan, alat perkantoran, teknologi perbankan, handphone, komputer, dan sekian peralatan teknis lain yang tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan ini. Jadi bagaimana kita mesti menimbang dan memosisikan agama yang akhir-akhir ini mengesankan sebagai sumber kegelisahan sosial? Bahkan, ketika iptek modern jatuh di tangan teroris dengan sandaran paham dan ideologi agama, daya rusak dan korbannya menjadi sangat mengerikan.
Iptek berkembang secara leluasa melewati batas etnis, negara, budaya, dan agama. Akan tetapi, kehadiran paham agama yang baru selalu memperoleh perlawanan. Jangankan antarpemeluk agama yang berbeda, di lingkungan sesama Kristen ataupun Islam saja penuh dengan catatan darah akibat saling bunuh.
Pertanyaan mahasiswa tadi muncul kembali di benak saya ketika dalam perjalanan pulang dari Hawai ke Jakarta pertengahan April lalu. Saya duduk bersebelahan dengan seorang berkebangsaan Amerika Serikat yang hendak jalan-jalan ke Philipina. Katanya, “Saya tidak bisa mengerti mengapa hanya karena beda agama orang saling bunuh? Apa yang membedakan antara Suni dan Syiah di Irak sehingga mereka saling meneror?” Untung, dia tidak menyinggung penyerbuan ke pusat ibadah Ahmadiyah di Indonesia.
Agama telah berjasa membangun peradaban dunia, hal itu tidak bisa diingkari. Ia memberikan makna hidup dan ketenteraman batin, hal itu juga mudah divalidasi. Akan tetapi, suatu kenyataan sosial-psikologis bahwa agama juga telah melahirkan sekian banyak pertumpahan darah dan sikap saling menghujat. Ibarat berpakaian, rasanya ada beberapa orang yang dalam beragama tidak pas desainnya, ukurannya, dan potongannya sehingga tidak nyaman dipakai dan tidak sedap dipandang.
Rasulullah bersabda, “Seorang muslim adalah dia yang tangannya dan lisannya senantiasa mendatangkan kedamaian dan keselamatan, bukannya malah mencelakakan orang.” Ada lagi sabdanya yang lain, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik budi pekertinya dan paling banyak memberikan manfaat dan pertolongan pada orang lain.” Pendeknya, keberagamaan itu mestinya senantiasa menyebarkan vibrasi damai dan kasih sayang bagi lingkungan (rahmatan lil alamin), bukannya menyebarkan rasa sesak.[]
Komaruddin Hidayat adalah akademisi dan intelektual muslim Indonesia. Dia pernah menjabat Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2006-2015). Lulusan Pondok Pesantren Pabelan, Magelang, dan Pondok Pesantren Al-Iman, Muntilan, ini meraih gelar doktor di bidang Filsafat Barat dari Middle East Technical University, Ankara, Turki. Sejak 2019, ia diserahi tugas memimpin Universitas Islam Internasional Indonesia. Komaruddin juga penulis prolifik. Salah satu karyanya yang menjadi bestseller adalah Psikologi Kematian (Penerbit Hikmah, 2005).
[Dinukil dari: Hidayat, Komaruddin. 2006. Psikologi Beragama: Menjadikan Hidup Lebih Nyaman dan Santun. Jakarta: Penerbit Hikmah]
[Sumber foto: Mediaindonesia.com]