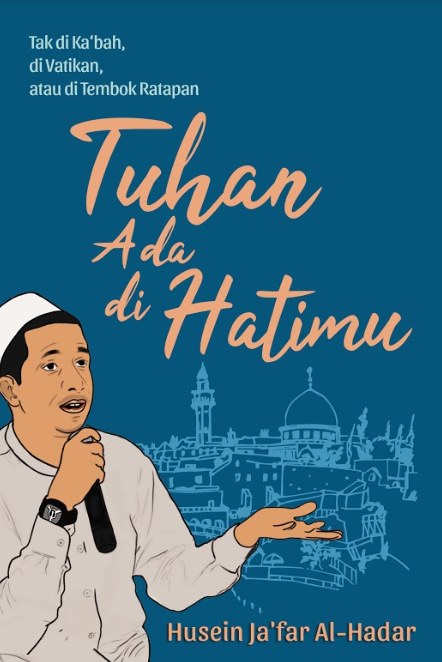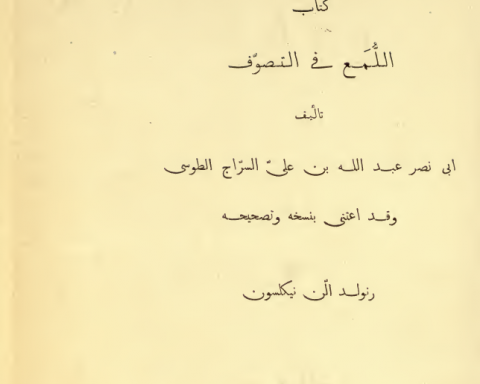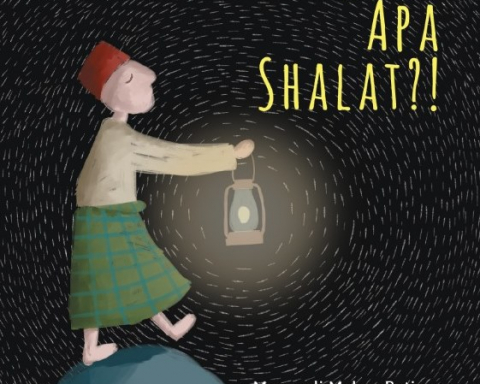Di tengah ekstremisme keagamaan yang cenderung meningkat, orang sering lupa sisi lainnya: generasi milenial yang makin tak peduli dengan agama. Husein Ja’far Al-Hadar dalam dakwahnya berusaha menemani mereka. Buku Tuhan Ada di Hatimu adalah salah satu upayanya.
APA yang mengkhawatirkan umat Islam akhir-akhir ini? Sebagian Muslim akan menjawab: ekstremisme atas nama Islam.
Begitulah setidaknya hasil survei Pew Research Center terhadap populasi Muslim di Amerika pada 2017. Sigi itu menunjukkan sekitar 8 dari 10 Muslim Amerika, atau 82 persen, cemas dengan ekstremisme global atas nama Islam.
Di Indonesia, kekhawatiran serupa juga ditunjukkan oleh sejumlah survei yang menyoroti kecenderungan intoleransi di kalangan generasi muda Islam. Survei The Wahid Foundation, misalnya, menyebut 60 persen responden aktivis rohis SMA dan SMK di seluruh Indonesia bersedia “berjihad” ke wilayah-wilayah konflik.
Dari fenomena di atas, sebenarnya ada sisi lain yang kerap terlupakan. Di tengah ekstremisme dan intoleransi yang meningkat, orang seringkali silap dengan kemungkinan potensi sebaliknya: Muslim yang makin merasa agamanya tak relevan. Mereka tak peduli dan bahkan menolak agama, baik itu dalam bentuk agnostisisme maupun ateisme.
Mereka merasa agama memicu polarisasi dan konflik di tengah. Mereka merasa ajaran agama mempersulit dan memperuwet hidup yang sudah rumit. Mereka melihat pemeluk agama kaku, jumud, dan anti-sains.
Mereka biasanya datang dari generasi milenial. Mereka lahir di era digital, yang menyajikan segala kemudahan sekaligus tekanan hidup. Sebab, standar-standar hidup terus diproduksi tanpa jeda oleh revolusi teknologi informasi.
Seberapa besar jumlah mereka jika dibandingkan, misalnya, dengan “generasi hijrah” yang belakangan semarak? Atau, seberapa besar mereka jika dibandingkan dengan kelompok yang terekam dalam survei The Wahid Foundation? Sayangnya, belum ada survei yang memotret mereka: generasi yang mulai tak acuh dengan Islam dan agama pada umumnya.
Kepada “kelompok” inilah, Husein Ja’far Al-Hadar memosisikan dirinya. Di kanal YouTube Deddy Corbuzier, dai muda ini pernah menganalogikan dirinya mengambil peran Sayydina Ali bin Abi Thalib yang tetap tinggal di Mekkah sementara sahabat lain berhijrah bersama Nabi Muhammad ke Madinah.
Husein seakan ingin mengatakan dia memilih kelompok generasi milenial yang apatis terhadap agama sebagai sasaran dakwahnya. Salah satu segmen di kanal YouTube-nya, “Jeda Nulis”, dinamakan “Pemuda Tersesat” Dia juga mengatakan lebih memilih Muslim milenial yang nongkrong di cafe-cafe ketimbang yang sudah “hijrah” dan rajin menyambangi masjid.
Husein lebih banyak berdakwah di media sosial, seperti Twitter, Instagram, dan terutama YouTube. Dia mencoba menjawab berbagai kegelisahan generasi milenial, terutama yang dipicu oleh pandangan keagamaan konservatif. Sebagai contoh soal halal-haram bermusik dan menonton film di bioskop. Dia juga menyampaikan pandangan tentang fenomena “hijrah” dan ekstremisme Muslim.
Lebih penting daripada itu adalah cara Husein mengemas diri dan dakwahnya. Dia tak berjubah kebesaran umumnya seorang dai atau habib. Dia cukup mengenakan sweater dan bercelana jin tanpa peci. Kalaupun kemudian memakai baju koko dan berpeci, dia menyembulkan sejumput rambut dari peci putihnya, yang menggambarkan kesantaian dan keluwesan. Dia tak lupa menggandeng musisi dan komika dalam video-video dakwahnya.
Positioning tersebut tampaknya tepat. Kanal YouTube-nya hingga September 2020 diikuti lebih daripada 250 ribu orang. Video-videonya rerata disaksikan lebih daripada setengah juta orang.
Pada Juli 2020, dia meluncurkan Tuhan Ada di Hatimu. Buku ini mendedah lontaran pemikiran Husein dalam dakwahnya di media sosial. Jika rajin mengikuti paparannya di media sosial, Anda pasti sudah terbiasa dengan lontaran khasnya seperti “berpikir substantif” atau “Islam lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas”.
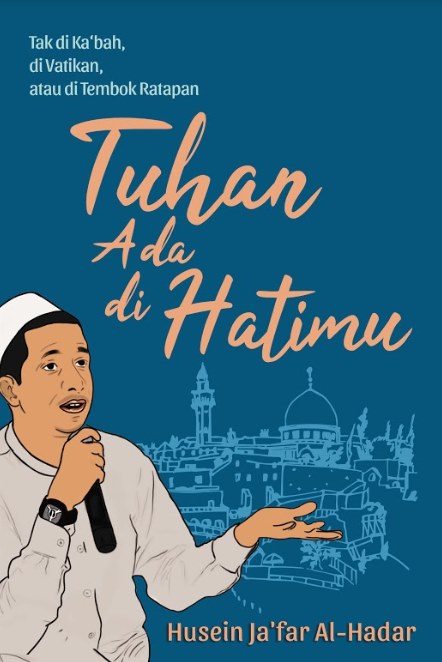
- Judul Buku: Tuhan Ada di Hatimu
- Penulis: Husein Ja’far Al-Hadar
- Penerbit: Noura Books
- Terbit: Juli 2020
- Tebal: 204 halaman
Buku ini menguraikan lontaran tersebut dalam argumentasi yang lebih kokoh tapi tetap mudah dipahami. Dia mendasarkan argumentasinya dengan menjelajahi khasanah klasik Islam dari mulai fikih, sejarah, hingga tasawuf. Dia menyajikan penjelajahannya ini tanpa terjebak ke dalam keruwetan istilah teknis yang hanya bisa dipahami oleh pelajar ilmu keislaman. Bisa dibilang penjelajahannya sederhana tapi mengena.
Dari 19 esai terpisah yang ada dalam buku ini, kita bisa menarik benang merah. Ajaran Islam tak bisa hanya didekati oleh pemahaman literal atas teks-teks suci, apalagi sekadar bermodalkan terjemahan.
Sebagaimana lazimnya praktik berbahasa manusia, kata selalu memiliki keterbatasan dalam menyampaikan makna. Karenanya, dalam ilmu linguistik, kita mengenal gaya bahasa, seperti alegori, metafora, simile, dan tropus. Bahkan, kata kadang juga bisa dipahami dari peristiwa yang melingkupi waktu pengucapannya (konteks), sehingga muncullah bidang ilmu seperti sosiolinguistik dan psikoliguistik.
Jika kata belum mampu mengungkap sepenuhnya makna yang diinginkan oleh manusia, apalagi firman Allah, Zat yang tak terbatas. Al-Quran sendiri mengisyaratkan dirinya memiliki lapisan-lapisan makna, sehingga membutuhkan tafsir.
Saat masih hidup, Nabilah sang penafsir paling otoritatif. Sepeninggal Nabi, tafsir tentu saja tak boleh berhenti. Sebab, Islam terus hidup mengarungi ruang dan waktu yang berbeda. Peradaban manusia berkembang sementara Islam menyebar ke berbagai wilayah yang jauh dari pusat kelahirannya.
Konsekuensinya, ilmu-ilmu keislaman lahir dan berkembang. Untuk menguasai ilmu-ilmu keislaman, seseorang pun harus menguasai ilmu bahasa sebagai alatnya.
Intinya, seseorang tidak mungkin mencapai pemahaman yang benar tentang teks suci tanpa menguasai ilmu-ilmu tersebut. Bagi orang awam, pilihannya adalah mengikuti ulama yang telah terbukti menguasai ilmu-ilmu tersebut.
Itu sangat alamiah dalam kehidupan manusia. Di bidang non-agama sekalipun, kita logikanya pasti mencari informasi tentang bidang tertentu dari orang-orang yang menguasai dan mengikuti perkembangan bidang tersebut. Di bidang kesehatan, dokter adalah rujukan kita. Di bidang penanggulangan wabah, kita mendengar saran dari epidemiolog dan virolog.
Oleh karena itu, orang yang ngotot mencoba memahami Al-Quran dan hadis semata secara literal akan tertambat di masa lalu. Jargon “Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah” pun, menurut Husein, tak pas. Dia mengajukan jargon baru “Berangkat dari Al-Quran dan Sunnah”.
Namun, menurut Husein, kebenaran yang dihasilkan oleh ilmu-ilmu itu pun belum cukup menghasilkan kebijaksanaan jika kita mengabaikan kebaikan dan keindahan. Bagaimanapun, perbedaan niscaya lahir dari upaya ulama menafsir teks suci. Karenannya, kebenaran harus diramu bersama dengan kebaikan dan keindahan. Dari ramuan itu, kebijaksanaan akan lahir—atau bolehlah dikatakan ini yang Husein maksud dengan hijrah sesungguhnya.
Di titik ini, Husein mengajak pembaca tak melupakan dimensi esoteris ajaran Islam: tasawuf. Dimensi ini berkaitan dengan pengaktifan hati atau jiwa manusia. Mungkin karenanya, buku ini diberi judul Tuhan Ada di Hatimu.
Dalam banyak tradisi spiritual, hati dipandang tempat persemayaman kesadaran ilahiah manusia. Suara hati lebih bisa mendekati kebenaran jika dibandingkan dengan pikiran. Kita bisa memalsukan pikiran demi membenarkan tindakan, tapi tidak hati. Secanggih apa pun argumen untuk membungkus perbuatan zalim, ia tak akan bisa meredam kegelisahan suara hati.
Dalam Islam, hati menduduki posisi sentral. Al-Quran Surah Al-Syu’ara ayat 88-89 menyatakan hanya orang dengan hati bersih yang bisa menghadap Allah di hari kiamat. Al-Quran juga sering menggambarkan orang-orang kafir dan munafik dengan mereka yang hatinya sudah tertutup dan mati.
Mereka bisa jadi fasih membaca Al-Quran dan rajin beribadah. Tapi karena terpenjara nafsu “holier than thou” (spirit sok suci), mereka tidak toleran terhadap perbedaan pendapat dan bahkan mengafirkan orang di luar kelompok mereka. Al-Quran menyatakan, mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya (hati itu) untuk memahami (yafqahun) (ayat-ayat Allah) (QS Al-A’raf: 179).
Melalui penceritaan sejarah Nabi, Husein menunjukkan bagaimana Nabi berdakwah dengan “hati”. Hasilnya, dakwah beliau “berhati hangat”, tidak “berhati keras”, sehingga “menyentuh hati”. Dalam kata-kata Husein Ja’far, Nabi tak hanya menghukum tapi memberi solusi; memberi kabar gembira dan tidak menakut-takuti; mempermudah dan tidak mempersulit; serta mempersatukan dan tidak memecah belah.
Selain singkat dan sederhana, uraian buku ini mengalir, dengan kisah-kisah Nabi, sahabat, dan para sufi yang dikutip di dalamnya. Husein juga menyentuh bukan saja aspek fikih tapi sosial-kemasyarakatan dan tasawuf. Buku ini bisa menjadi gerbang bagi generasi milenial untuk melihat Islam lebih utuh.[]