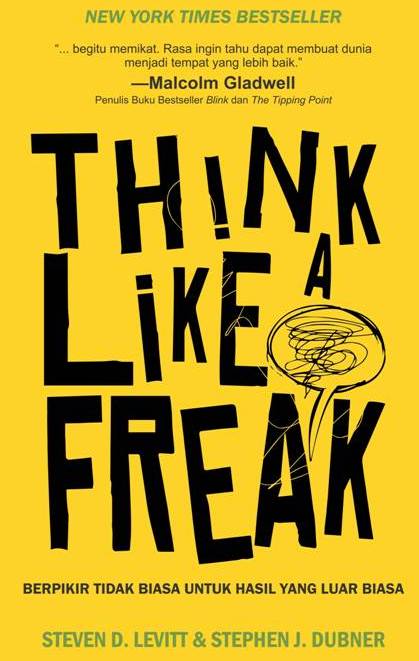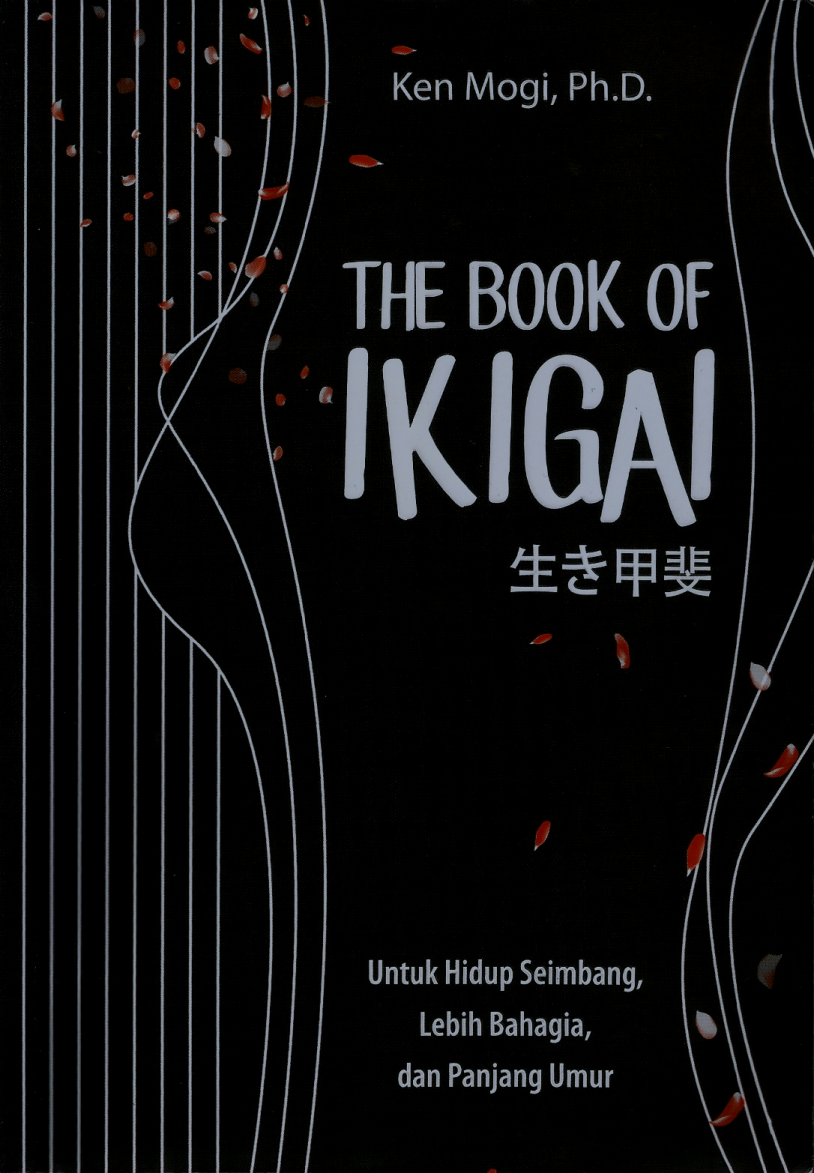Kita cenderung tak suka dibilang “kekanak-kanakan”. Tapi bagi Levitt dan Dubner, berpikir dan bersikap seperti anak-anak bisa memberi sudut pandang dan cara baru dalam menyelesaikan persoalan.
Kita biasanya merasa terhina jika dibilang, “kekanak-kanakan”. Istilah “kekanak-kanakan” lekat dengan stigma “kondisi belum dewasa” secara sosial dan emosional. Bukan cuma distigmakan, dalam psikologi, “kekanak-kanakan” dianggap sebagai “gangguan kepribadian” (personality disorder). Anak-anak dianggap suka berbohong, mudah marah, kurang bertanggung jawab, ingin selalu menjadi pusat perhatian (narsis), suka menyangkal, dan sederet sifat buruk lainnya. Nah, jika masih memiliki sifat-sifat itu sementara usia beranjak dewasa, anda biasanya akan disebut “kekanak-kanakan”.
Benarkah demikian? Belum tentu juga. Anda tentu pernah membaca atau mendengar anekdot “The Emperor’s New Clothes” karya pengarang Denmark legendaris, Hans Christian Andersen. Dalam cerita itu, siapakah yang berani mengatakan bahwa sang kaisar tidak mengenakan apa-apa? Seorang anak, bukan?
Lihat, anak-anak justru manusia paling berani dan jujur dalam menyatakan sesuatu sebagaimana adanya ketika sebagian besar orang dewasa memilih untuk berbohong karena cemas akan kelaziman sosial. Orang dewasa justru harus selalu menekan kebenaran ketika kebenaran itu dia rasakan akan membuatnya tak nyaman di hadapan pandangan umum. Itulah kenapa filsuf Inggris, Aldous Huxley, suatu waktu justru pernah berkata, “Rahasia seorang genius adalah membawa spirit anak-anak hingga tua.”
Berpikirlah seperti anak-anak, demikian yang ingin dikatakan Steven D Levitt dan Stephen J Dubner melalui buku mereka Think Like a Freak: Berpikir Tidak Biasa untuk Hasil yang Luar Biasa (Noura Books: 2016). Ini buku ketiga duet kepenulisan Levitt (ekonom University of Chicago) dan Dubner (jurnalis New York Times). Keduanya sebelumnya menghasilkan dua best seller, Freakonomics dan SuperFreakonomics.
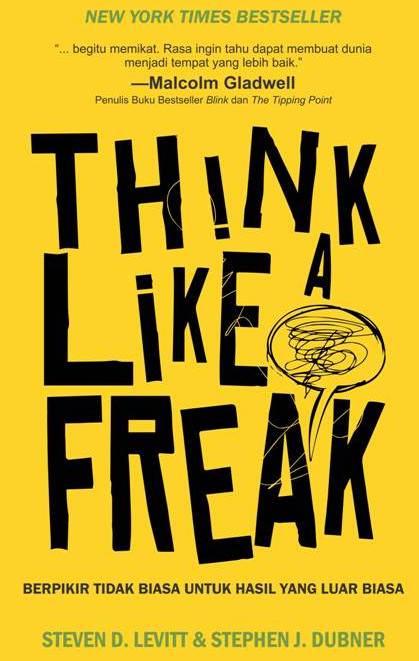
- Judul Buku: Think Like a Freak: Berpikir Tidak Biasa untuk Hasil yang Luar biasa
- Penulis: Steven D Levitt dan Stephen J Dubner
- Penerbit: Noura Books
- Terbit: 2016
- Tebal: 270 halaman
Bagi Levitt dan Dubner, berpikir seperti anak-anak sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah. Anak-anak kerap mengajukan pertanyaan sederhana dan konyol yang kadang diabaikan orang dewasa karena orang dewasa merasa malu menanyakannya. Mengajukan pertanyaan sederhana dan mendasar, menurut Levitt dan Dubner, justru lebih baik daripada mengajukan pertanyaan besar dan “canggih”. Itu karena persoalan besar merupakan jalinan dari persoalan-persoalan kecil. Memicu perubahan dalam persoalan besar mau tidak mau harus dimulai dari memicu perubahan dalam persoalan kecil, dan melakukan yang kedua jauh lebih mudah daripada yang pertama.
Anak-anak biasanya mengajukan pertanyaan karena terdorong oleh rasa ingin tahu sementara orang dewasa seringkali oleh keinginan memenangkan perdebatan atau argumen. Orang dewasa karenanya berupaya mengajukan pertanyaan yang “canggih”. Kata canggih dalam bahasa Inggris adalah sophistication. Levitt dan Dubner bilang kata ini berasal dari kata sophist yang dalam sejarah filsafat merujuk kepada kelompok tukang retorika keliling yang memiliki reputasi buruk karena mereka lebih peduli untuk memenangi perdebatan daripada mencapai kebenaran.
Oleh karena itu, kecanggihan berpikir justru malah bisa menghambat tujuan pemecahan masalah. Ia tidak berangkat dari kejujuran untuk melihat masalah sebagaimana adanya tapi dari prasangka, baik sosial, kultural, maupun intelektual. Prasangka-prasangka inilah yang bisa menyingkirkan kemungkinan solusi yang lebih baik tapi tampak tak cukup canggih.
Satu hal lain dari anak-anak adalah semangat mereka untuk bermain-main dan bersenang-senang. Menurut Levitt dan Dubner, anak-anak tidak takut untuk menyatakan suka atau tidak suka, bosan atau tidak bosan. Semangat bersenang-senang pada anak-anak, jika dibawa terus hingga dewasa, sebenarnya bisa membuat kita menikmati apa yang kita lakukan. Kondisi ini kemudian bisa melejitkan potensi terpendam kita. Levitt dan Dubner mengatakan, orang-orang besar di bidangnya tak hanya berbakat di usia muda tapi juga bisa menikmati pekerjaan mereka karena mereka mempertahankan semangat bersenang-senang.
Dalam buku ini, Levitt dan Dubner mengajukan contoh-contoh cerita, peristiwa, dan data, untuk mendukung argumen mereka. Misalnya, mengapa hanya 17 persen pesepakbola profesional yang menendang penalti ke tengah gawang, padahal data statistik menunjukkan kiper cenderung lebih sering melompat ke kiri (57 persen) dan kanan (41 persen) gawang? Itu karena, menurut mereka, para pesepakbola profesional—termasuk yang berkelas dunia—tak ingin terlihat bodoh. Jika menendang penalti ke tengah gawang, dan tendangan itu gagal, ia akan tampak bodoh di mata fans karena kiper lawan tak harus bersusah payah menyelamatkan tendangannya.
Tidak mau terlihat bodoh adalah ciri khas orang dewasa yang sudah kehilangan sifat-sifat ajaib anak-anak. Anak-anak tak peduli untuk melakukan hal-hal yang berpotensi terlihat bodoh. Bersikap seperti ini, menurut Levitt dan Dubner, berpotensi melahirkan sudut pandang dan cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah.
Karena ingin tampak pintar dan mumpuni, orang dewasa biasanya sulit mengatakan, “saya tidak tahu”. Mengatakan itu bisa memalukan bagi orang dewasa. Menurut Levitt dan Dubner, kondisi ini terutama dialami oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang bisnis dan politik. Efek negatif dari sulitnya mengakui “saya tidak tahu” adalah kita tak akan pernah tergerak untuk mempelajari hal-hal baru. Kita menjadi cupet, degil, nyaman berada dalam gelembung sendiri, sok tahu, dan ujungnya menyengsarakan banyak orang.
Levitt dan Dubner menceritakan penelitian yang dilakukan profesor psikologi Universitas Pennsylvania, Philip Tetlock. Dari ribuan data prediksi ekonomi dan politik 300 pakar selama 20 tahun yang dikumpulkan, Tetlock menemukan bahwa akurasi prediksi mereka tak lebih daripada “monyet yang bermain dart” atau tebak-tebakan. Pertanyaannya, mengapa para pakar itu berani mengajukan prediksi? Mengapa mereka tak cukup mengatakan, “saya tidak tahu”? Ya, itu tadi karena mereka malu mengakui tidak tahu.
Contoh lain yang disampaikan Levitt dan Dubner adalah invasi Amerika Serikat atas Irak pada 2003. Kita tahu perang ini dilancarkan karena klaim Amerika bahwa Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal. Klaim itu kemudian terbukti palsu, padahal perang telah membantai ratusan ribu warga Irak dan 4.500 serdadu Amerika serta menghabiskan triliun dolar. Andai saja, buku ini bilang, politisi mengakui bahwa mereka tidak benar-benar tahu kebenaran klaim itu, perang yang menyengsarakan banyak orang itu tak akan terjadi.
Berlagak tahu demi menyelamatkan reputasi sendiri berdampak demikian merusak. Sayangnya, kata Levitt dan Dubner, orang-orang sok tahu itu bisa melenggang bebas dari konsekuensi kedegilan mereka.
Orang-orang seperti itu juga seringkali tak bisa menerima kegagalan dan pada gilirannya menolak berhenti, alias pantang mundur. Bagi mereka gagal dan berhenti sama saja dengan mengakui diri sebagai pengecut atau pecundang.
Persepsi seperti itu, bagi Levitt dan Dubner, keliru. Kegagalan bukanlah aib. Dalam sains, ketika gagal dan menemui jalan buntu, anda sebenarnya sudah memberi kontribusi karena orang lain setelah anda tak perlu melalui jalan yang sama, yang buntu itu. Kegagalan juga bisa membuat anda mempelajari hal-hal baru karena kegagalan memberi umpan balik, dan tak ada proses belajar tanpa umpan balik.
Menolak menyerah bisa berakibat sangat fatal. Buku ini menceritakan kembali insiden kecelakaan pesawat ulang-alik Challenger pada 28 Januari 1986. Jauh sebelum hari peluncuran, tim insinyur yang dikontrak NASA sudah memberi saran agar peluncuran dihentikan sebab mereka khawatir dengan kondisi cincin-O yang menyatukan bagian-bagian roket penyimpan bahan bakar. Namun, petinggi NASA menolak menyerah dan menentang saran itu. Akibatnya, Challenger meledak setelah 73 detik meluncur. Tujuh awaknya, yang tentu saja astronot-astronot terbaik NASA, tewas. Penyelidikan setelah insiden menemukan bahwa Challenger meledak karena kerusakan pada cincin-O tadi akibat suhu cuaca yang dingin.
Berpikir seperti anak-anak akan membuat anda tampak aneh di tengah banyak orang. Banyak orang bisa jadi akan membenci anda karena bersikap seperti itu. Tapi, menurut Levitt dan Dubner, berpikir seperti anak-anak—yang kemudian buku ini sebut berpikir seperti orang aneh—sebenarnya berpikir sederhana, mendasar, dan mengikuti akal sehat. Sayangnya, di usia dewasa, banyak orang kehilangan spirit ini karena membiarkan dirinya dikuasai kenyamanan serta prasangka sosial, kultural, moral, dan intelektual.
Berpikir seperti orang aneh yang dipaparkan buku ini adalah berpikir outside the box. Saran-saran untuk berpikir outside the box sudah banyak ditulis atau disampaikan. Yang membuat buku ini unik adalah cerita-cerita dari peristiwa-peristiwa nyata yang terasa relevan. Meskipun bukan hal baru, Levitt dan Dubner setidaknya mengingatkan kita dengan cara khas. Seperti yang dikatakan oleh Huxley, kita harus tetap membawa semangat dan roh “kekanak-kanakan” sampai tua. Sebab dalam roh anak-anak, api antusiasme tak pernah padam.
Hidup kekanak-kanakan![]