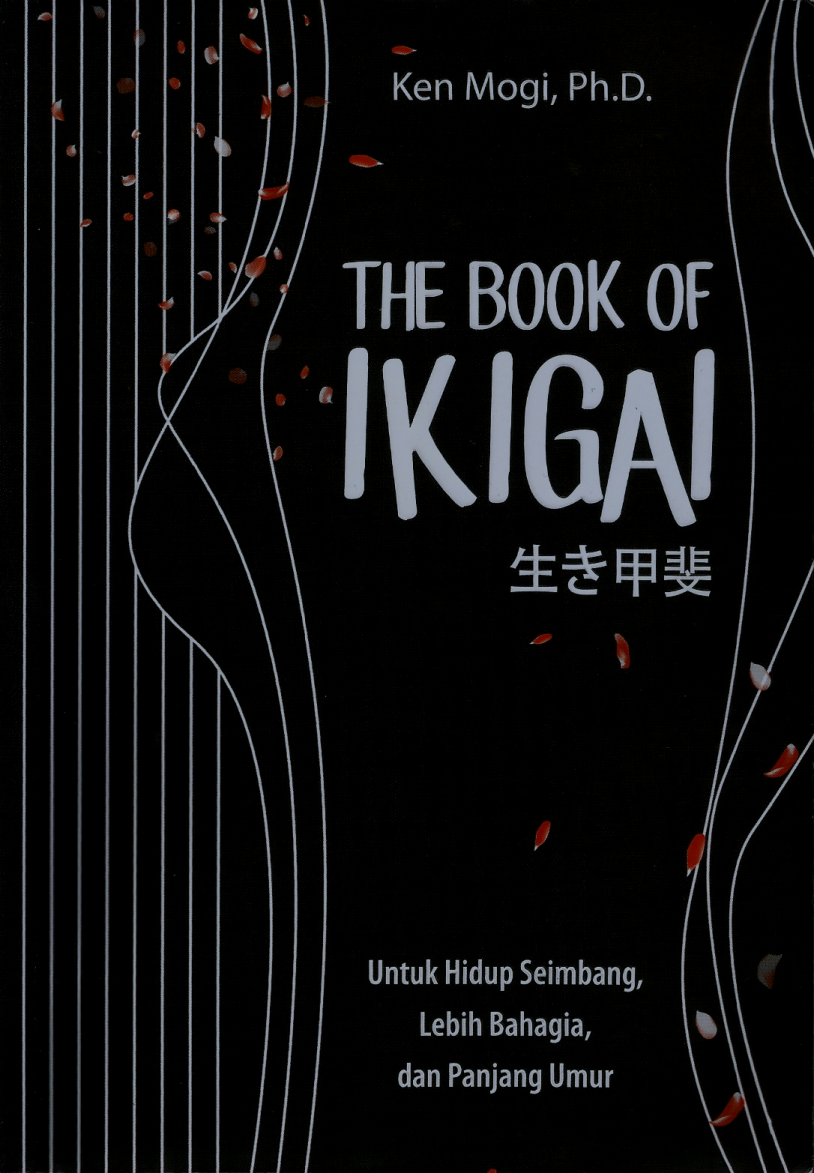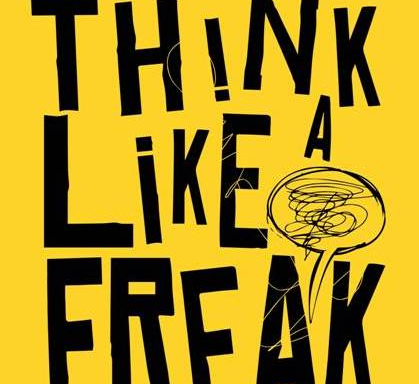Buku Ali Zaenal Abidin ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam periode quarter life crisis atau midlife crisis. Benarkah kebahagiaan itu tujuan hidup ini? Buku ini menjawab, bukan. Lalu apa tujuan hidup?
Belakangan ini kita sering mendengar istilah quarter life crisis. Para psikiater, psikolog, motivator-penulis pengembangan kepribadian adalah di antara “juru bicara” istilah tersebut. Mereka mendefinisikannya sebagai krisis psikologis yang dialami seseorang ketika ia berusia antara 18 sampai 30 tahun. Mereka bilang, orang yang mengalami quarter life crisis akan cemas, bingung, dan galau karena ketidakpastian hidupnya saat ini dan di masa depan, entah itu yang berhubungan dengan karir, kehidupan sosial, ataupun relasi emosional (percintaan).
Sebelumnya kita juga mengenal frasa midlife crisis atau krisis paruh baya. Seperti halnya quarter life crisis, krisis paruh baya adalah krisis psikologis. Hanya bedanya, krisis ini terjadi antara usia 45 hingga 65 tahun. Kecemasannya lebih berhubungan dengan kematian yang menjelang, kurangnya pencapaian dalam hidup, dan keinginan untuk mengubah keputusan atau pilihan yang dianggapnya salah di masa lalu.
Terlepas dari perbedaannya, baik quarter life crisis ataupun midlife crisis sama-sama problem psikologis yang berkaitan dengan kecemasan akan ketidakpastian. Dalam bukunya, Karena Bahagia Bukan Tujuan, Terus Hidup Mau Ngapain?, pelatih pengembangan diri, Ali Zaenal Abidin, menulis bahwa cara terbaik menghadapi dua krisis itu bergantung kepada persepsi atau cara pandang kita. Jika hanya berfokus pada keduanya sebagai krisis, kita hanya akan memperpanjang periode kecemasan yang ditimbulkannya. Ali menyarankan kita memandang kedua periode itu sebagai alarm yang mengingatkan kita agar memperbaiki diri, di antaranya dengan mengonsumsi asupan-asupan psikologis yang sehat.
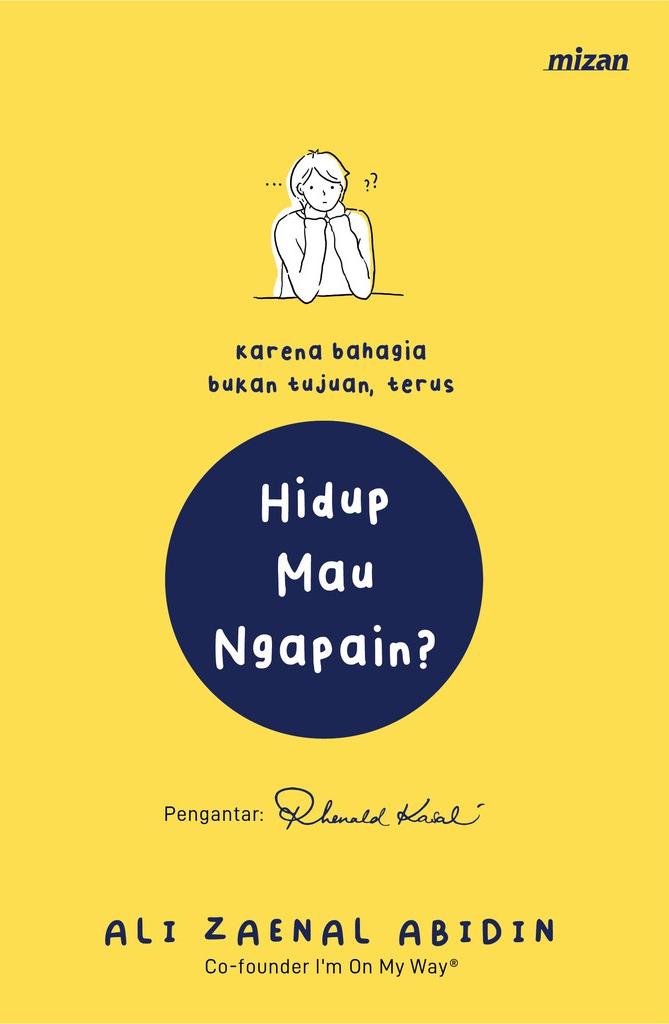
- Judul Buku: Karena Bahagia Bukan Tujuan, Terus Hidup Mau Ngapain?
- Penulis: Ali Zaenal Abidin
- Penerbit: Mizan
- Terbit: Cetakan I, April 2021
- Tebal: 173 halaman
Salah satu yang memicu kecemasan seseorang ketika ia memasuki periode quarter life crisis adalah pencarian akan tujuan hidup. Dari penjelasan Ali dalam bukunya ini, setidaknya ada dua kekeliruan yang membuat pencarian itu seakan berputar-putar dalam labirin kecemasan.
Pertama, kita cenderung membebani pikiran kita dengan pertanyaan-pertanyaan teknis, seperti “bagaimana melakukannya”, “dari mana uangnya”, atau “siapa yang akan membantu mewujudkannya”. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan membuat kita tak beranjak ke mana-mana. Sebab, pertanyaan itu ada pada bagian “menjalani tujuan hidup” dan bukan pada bagian “menemukan tujuan hidup”.
Untuk menemukan tujuan hidup, kita harus menyelami hati nurani dan bertanya kepadanya, apa yang ingin kita lakukan dalam hidup ini. Sayangnya, di zaman sekarang, menurut Ali, hal itu sulit dilakukan karena sebagian besar generasi milenial tak meluangkan waktu untuk berefleksi diri, merenung, dan berkontemplasi agar makin memahami dan mengenal diri mereka.
Kekeliruan kedua adalah kecenderungan kita menyamakan tujuan hidup dengan profesi. Kecenderungan seperti ini, selain bisa mengurangi peluang, juga bisa membatasi potensi kita dalam mencapai tujuan hidup. Ali memberi contoh, seseorang yang tujuan hidupnya membantu penderita kanker tidak mesti menjadi dokter. Orang itu bisa tetap menjalani tujuan hidupnya dengan menjadi peneliti, dokter sekaligus peneliti, atau mungkin profesi lain yang bisa membantunya menjalani tujuan hidup itu. Mungkin dia bisa menjadi perawat khusus kanker, aktivis yang berkampanye untuk perawatan atau pencegahan kanker, atau sukarelawan di rumah-rumah perawatan pasien kanker.
Profesi, menurut Ali, hanya salah satu alat atau metode yang bisa kita pilih atau ciptakan untuk menjalani tujuan hidup. “Jangan pernah batasi tujuan hidupmu hanya dengan satu profesi. Karena itu artinya kamu membatasi potensimu sendiri.”
Karena Bahagia Bukan Tujuan berupaya mengubah cara pandangan yang kadung dianggap wajar di tengah masyarakat. Misalnya, jika ditanyakan kepada orang-orang, apa yang mereka cari dalam kehidupan ini, sebagian besar dan bahkan mungkin semua akan menjawab mereka mencari kebahagiaan. Padahal, menurut Ali, kebahagiaan itu bukan tujuan hidup. Menjadi bahagia adalah hadiah dari menjalani tujuan hidup (menjalani apa yang menjadi passion kita).
Karena kebahagiaan menjadi tujuan, ditambah persepsi bahwa tujuan hidup identik dengan profesi, kita seringkali mempersempit “lokasi-lokasi” di mana kebahagiaan itu berada. Kita mencari kebahagiaan dalam satu hal: satu profesi, satu lingkungan pergaulan, dan bahkan satu hubungan. Ketika semua itu tak berjalan lancar, kita merasa tak menemukan kebahagiaan.
Bagi Ali, kebagiaan itu ada di banyak hal. Selama kita menjalani tujuan hidup yang telah kita temukan, selama itu pula kita akan merasakan kebahagiaan (kepuasaan batin). Dia menganalogikan ini dengan seekor anjing yang berusaha mengejar dan menangkap bola salju yang dilemparkan. Saat bola salju jatuh ke tanah bersalju dan hancur berkeping-keping, anjing itu tetap bersemangat dengan mengitari kepingan-kepingan bola salju yang sudah pecah itu. Anjing itu tidak menyadari bahwa di sekitarnya ada begitu banyak salju. Demikian pula, karena terlalu fokus mencari kebahagiaan di satu “lokasi”, seseorang tidak menyadari bahwa begitu banyak kebahagiaan lain di sekitarnya.
Apa yang dipaparkan Ali dalam buku ini berangkat dari “krisis eksistensial” manusia modern. Frasa “krisis eksistensial” mulai dibicarakan ketika muncul gelombang kritik terhadap modernisme dalam filsafat Barat pada akhir Abad ke-19, terutama melalui para filsuf aliran eksistensialisme seperti Søren Kierkegaard dan Friedrich Nietzsche, yang kemudian diwarisi oleh Jean Paul Sartre dan karib sekaligus rivalnya, Albert Camus.
Begitu menyadari eksistensi kita di dunia material ini, kita mulai menghadapi problem memilih apa yang harus kita lakukan dengan apa yang telah dilakukan terhadap kita. Kita harus memutuskan apa arti eksistensi kita dan apa yang akan kita perbuat dengannya.
Bagi Sartre, misalnya, krisis eksistensial disebabkan manusia diciptakan tanpa tujuan atau alasan: tanpa makna (meaningless). Tidak ada otoritas yang merancang kehidupan manusia untuk suatu tujuan (esensi). Inilah yang menjadi dasar filosofinya tentang “eksistensi mendahulu esensi”. Tapi, masih menurut Sartre, manusia pada saat yang sama memiliki hasrat untuk mencari makna tentang segala hal, termasuk makna keberadaan dirinya. Di sinilah muncul paradoks yang memicu krisis eksistensial.
Namun, Sartre dan para eksistensialis lain tidak melihat hal itu sebagai keputusasaan melainkan pembenaran untuk menjalani kehidupan. Jika kita eksis tanpa tujuan atau esensi tertentu, kitalah yang menciptakan tujuan kita melalui keberadaan kita: pikiran dan perbuatan kita. Dengan kata lain, hanya melalui pilihan yang kita buat dan tindakan yang kita ambil dalam hidup ini, kita mendefinisikan siapa diri kita dan apa arti hidup kita. Di titik ini, Sartre ingin mengatakan bahwa inheren dalam ketidakbermaknaan eksistensinya, manusia justru memiliki kebebasan memilih untuk menjadi siapa, bagaimana menjalani hidup, dan apa yang penting bagi dirinya.
Persoalan selanjutnya, saking banyaknya pilihan dalam kehidupan ini membuat manusia kerap dilanda kecemasan. Seringkali kecemasan itu dijawab dengan semata tidak memilih (yang sebenarnya juga sebuah pilihan) atau memilih menyesuaikan diri dengan keinginan kerumunan atau konstruksi sosial dominan (budaya atau keyakinan). Semua itu tetap tidak menyelesaikan kecemasan tadi.
Situasi itulah yang dijelaskan Sartre melalui istilahnya yang terkenal, hell is other people. Maksudnya, manusia dipaksa melihat eksistensi dirinya melalui perspektif eksternal yang terlepas dari dirinya. Di sini, kesadaran manusia tidak hanya melihat dirinya sebagai entitas subjektif tapi sekaligus objek dari persepsi (the look) yang lain (the other). “Diri dihadirkan kepada kesadaran sebagai diri yang menjadi objek bagi yang lain. Itu berarti, saya sadar akan diri saya sekaligus melarikan diri darinya,” tulis Sartre dalam Being and Nothingness.
Dengan kata lain, manusia seringkali memahami dirinya melalui bagaimana orang-orang lain memandang dirinya. Ia mencari tujuan hidup yang bisa mendefinisikan dirinya melalui konstruksi sosial yang dominan di tengah masyarakat. Ia tidak mencari itu di dalam dirinya sendiri.
Dalam kacamata Sartre, hell is other people merupakan penyebab munculnya krisis eksistensial atau yang disebut tadi sebagai quarter life crisis atau midlife crisis. Di era media sosial, hell is other people makin merajalela karena disebarkan secara masif (baca: diviralkan) dalam hitungan detik. Banyak orang cenderung mengukur dirinya dengan apa yang ditampilkan di media sosial: karir, gaji, kuliah, rumah, dan gaya hidup. Hidup yang tak sesuai standar yang disajikan di media sosial dianggap sebagai kegagalan dan kesia-siaan, padahal realitas yang dipertontokan media sosial adalah hiperrealitas atau simulasi atas realitas, bukan realitas sejati.
Sartre karenanya dikenal dengan upaya filosofis sepanjang hidupnya untuk “kembali kepada diri” (return to the self) atau menjadi “diri yang otentik”. Kita mungkin tak setuju dengan pandangan eksistensialisme Barat yang cenderung agnostik—karena antara lain berangkat dari pemberontakan atas hegemoni Gereja. Kita misalnya membutuhkan informasi yang cukup untuk membuat pilihan yang tepat. Bagi orang beragama, wahyu berperan memberi informasi tersebut meskipun manusia tetap diberi kebebasan memilih.
Namun, pandangan eksistensialisme seperti yang dikemukakan Sartre mengingatkan kita untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki, tidak dikekang oleh anggapan banyak orang atau konstruksi sosial yang dominan. Eksistensialisme Sartre juga menunjukkan bahwa kita sendirilah yang bertanggung jawab atas apa yang kita pilih dan lakukan, dan bukan orang lain.
Kembali kepada diri sendiri atau menjadi manusia yang otentik sebenarnya dalam bahasa agama adalah menjadi manusia sesuai fitrah: manusia yang mengaktualkan semua potensi dirinya: potensi fisik, akal, hati, dan jiwanya. Dramawan Oscar Wilde suatu waktu pernah berkata, “Jadilah diri sendiri karena diri-diri yang lain sudah ada yang punya.”
Apa yang dikemukakan Ali dalam bukunya ini sebenarnya juga “kembali kepada diri”. Misalnya, orang menganggap dirinya menderita karena apa yang telah diperbuat orang lain terhadap dirinya atau faktor lain di luar dirinya. Padahal, menurut Ali, penderitaan itu terus dirasakan karena diri orang itu terus mengulang-ulang perasaan sakit yang pernah dialami. “Merasakan sakit itu satu kali. Tapi merasa menderita adalah saat kamu memperpanjang dan mengulang-ulang kembali rasa sakit itu di otak lagi dan lagi,” tulis Ali.
Kita harus menyelami diri untuk bisa memahami siapa kita dan memilih apa tujuan hidup kita. Apa pun pilihan kita, kita tak pernah tahu hasilnya sampai kita memilih. Apa pun hasilnya nanti yang pasti kita sudah memilih berdasarkan kehendak diri dan bukan ingin menyenangkan atau menyesuaikan diri dengan konstruksi sosial. Jadi, persoalan memilih dalam kehidupan ini bukanlah soal apakah nanti pilihan itu baik atau buruk. Selama dalam prosesnya kita tak menyakiti orang lain, dan pilihan itu merupakan kehendak diri dan bukan karena tekanan orang lain atau masyarakat, maka pilihan itu akan mendatangkan kebahagiaan.
Ditulis dengan gaya populer, Karena Bahagia Bukan Tujuan, Terus Hidup Mau Ngapain? menarik untuk dibaca, terutama oleh generasi milenial dan Z. Buku ini juga menjawab persoalan-persoalan pelik yang tak jarang membuat kita galau dengan praktis, seperti dalam bentuk “Q and A”.[]