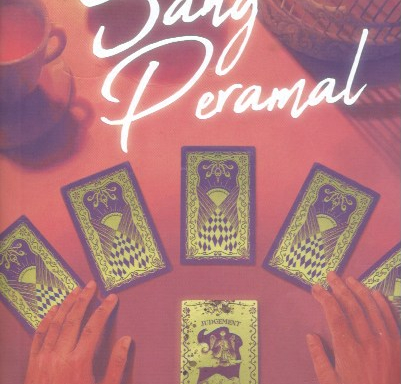Perlawanan para “perempuan” dalam Sihir Perempuan karya Intan Paramaditha berasal dari kedalaman jiwa mereka. Jiwa mereka bisa mengasihi tapi juga bisa meneror dan membunuh. Tak ada yang bisa menghentikan mereka karena, di “dunia gelap”, jiwalah yang berkuasa.
PEREMPUAN menghadapi anggapan sosial negatif lebih kerap daripada laki-laki. Perempuan yang bercerai bisa dipandang tak pandai membahagiakan suami. Perempuan yang berselingkuh dengan suami perempuan lain disebut “pelakor” (perebut laki orang), dan tampaknya tak ada istilah untuk laki-laki perebut istri orang. Perempuan yang berhubungan seks di luar nikah bisa dicemooh “pelacur” sementara laki-laki bisa melanjutkan hidup tanpa embel-embel atau stempel sosial apa pun. Pandangan negatif itu bahkan memasuki wilayah fisik yang tak bisa diubah, seperti menstruasi.
Pandangan negatif itu sepanjang sejarah hidup manusia makin terpatri dalam pikiran kebanyakan orang, tak terkecuali perempuan itu sendiri. Sepanjang sejarah pula, perempuan mencoba menghindarinya. Perempuan harus sempurna, sebagai anak, adik, istri, pegawai, dan ibu. Jika tak mampu, mereka terkadang memilih hidup dalam kepura-puraan.
Intan Paramaditha mencoba melawan pandangan itu dalam kumpulan cerpen Sihir Perempuan. Tapi, perlawanan tidak dinyatakan dalam “dunia terang” melainkan ditunjukkan dalam “dunia gelap”. Jangan salah paham! Saya tak memahami “dunia terang” sebagai kebaikan sedangkan “dunia gelap” sebagai kejahatan—seperti umumnya terpahami dari cerita-cerita silat. “Dunia terang” adalah realitas materiil yang dipahami oleh konstruksi sosial tertentu sementara “dunia gelap” adalah realitas jiwa, yang tak terbatas dan tak terperikan. Dan, di “dunia gelap” itulah, Intan berkisah.

- Judul Buku: Sihir Perempuan
- Pengarang: Intan Paramaditha
- Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama
- Terbit: April 2017
- Tebal: 170 halaman (edisi digital)
“Pemintal Kegelapan” membawa kita ke dalam misteri (salah satu “dunia gelap”) yang dihadapi sang narator sejak masa kanak-kanak. Kita terbawa atmosfer keingintahuan yang sama dengan sang narator. Ketika cerita menjelang akhir, Intan memelintir plot. Cerpen ini mencengkeram kita sejak awal dalam sebuah rasa penasaran lalu mengelokkannya sedemikian rupa sehingga menghadirkan teror.
Bagi saya, cerpen ini mengungkap kemampuan jiwa perempuan menyerap segala derita—kerinduan, kehilangan, konstruksi sosial masyarakat—sehingga mengubah dirinya menjadi “misteri” yang begitu dekat tapi tak pernah kita sadari. Apakah perempuan memiliki vitalitas sedemikian rupa sehingga mampu menanggung semua itu? Tampaknya begitu. Saya bukan psikolog. Tapi, bukankah hanya mereka yang mampu menanggung “derita” mengandung dan melahirkan kehidupan ke dunia ini?
Dalam “Vampir”, Intan menyisipkan teknik bercerita sudut pandang orang kedua meskipun narator utamanya lebih dominan “aku”. Ini bukan cara bercerita baru tapi jarang digunakan pengarang sebab lebih mudah mengembangkan cerita dan karakter berdasarkan sudut pandang orang pertama dan ketiga. Karakter orang kedua seperti tak bisa berlama-lama berada dalam plot. Keberadaannya seakan selalu bergantung kepada karakter lain. Cerita dari sudut pandang orang kedua juga tak sesimpel Anda bercerita kepada “kau” sebagai “aku” tapi “aku” harus menyelami perasaan dan pikiran “kau”.
Meskipun begitu, ada contoh sukses cerita sudut pandang orang kedua, yaitu serial buku anak-anak Choose Your Own Adventure pada 1970-an hingga 1990-an. Model bercerita ini bahkan sudah memasuki sinema televisi, salah satunya Black Mirror: Bandersnatch yang ditayangkan Netflix. Intan sendiri kemudian mengeksploitasi lebih jauh gaya bercerita ini dalam novelnya Gentayangan: Pilih Sendiri Petualangan Sepatu Merahmu (2017).
Kembali ke “Vampir”, cerpen ini memiliki dua narator “aku” yang bercerita kepada kita dari dua realitas yang tampaknya berbeda. Salah satu narator bahkan menyanggah pikiran narator lain yang disebutnya “kau”. Sanggahan inilah yang menciptakan gaya bercerita sudut pandang orang kedua.
Saya menginterpretasi kedua narator itu adalah satu karakter yang sama. Yang satu adalah karakter dari “dunia terang”: perempuan yang mencoba tetap rasional dan profesional menghadapi tekanan relasi timpang dengan atasannya: seorang pria muda, tampan, kaya tapi beristri. Sementara yang lain adalah karakter dari “dunia gelap”: perempuan yang berupaya membebaskan hasrat sensual dan seksualnya. Ya, cerita ini menyiratkan pertentangan dua ego di dalam satu karakter, mirip cerita klasik Dr Jekyll and Mr Hyde.
Salah satu narator yang narasinya ditandai dengan tulisan tercetak miring sebenarnya tak sekadar membebaskan hasratnya lantas menjadi subordinat sang bos dalam permainan hasrat. Tapi, dia membalik relasi timpang itu dan menjadi pengendali hidup atasannya. Dia tak semata melawan laki-laki tapi menghisap dan menaklukkannya.
Dalam “Mak Ipah dan Bunga-Bunga”, Intan kembali menggunakan sudut pandang orang kedua. Narator, Marini, menceritakan sudut pandang Mak Ipah bukan sebagai “dia” tapi “kau”. Tapi bukan hanya itu. Si narator juga bisa mengungkapkan apa yang dipikirkan dan dirasakan Mak Ipah.
Cerpen ini paling meneror saya di antara cerpen-cerpen lain. Bukan hanya plotnya yang dikelokkan Intan tapi juga penggunaan simbolisme di dalamnya. Mak Ipah menanam bunga-bunga, dan bunga-bunga itulah yang menghisap habis bau busuk si pemetik bunga. Luar biasa. Cerpen ini sekali lagi ingin menyatakan bukan hanya jiwa perempuan itu misterius tapi ia juga mampu menyimpan misteri sepanjang hidupnya.
Dalam cerpen ini, Intan juga menyisipkan subplot tentang pesta “ngunduh mantu”. Dalam pesta itu, para perempuan, termasuk pengantin perempuan, memasak di dapur sementara para lelaki mengobrol sambil merokok dan menikmati kopi di beranda. Lukisan realitas yang lazim kita temui. Tapi, Intan menggugat kelaziman itu. Mengapa pengantin perempuan harus tampak sibuk di dapur sementara pasangannya asyik bercengkerama dengan pria lain di beranda? Apakah memang posisi perempuan di situ? Lebih jauh, mengapa kaum perempuan harus berpeluh dan berjelaga di dapur sementara kaum pria asyik mencicipi penganan? Bukankah dalam sebuah pesta, siapa pun harus menikmatinya?
Cerpen “Perempuan Buta Tanpa Ibu Jari” mendekonstruksi Cinderella, dongeng rakyat dunia tentang penderitaan yang berakhir bahagia dari seorang gadis baik hati dan tidak sombong. Jika Anda penggemar dongeng ini, dengan berbagai variasinya di banyak negara, cerpen ini akan meneror Anda. Pertama tentu saja Cinderalla dalam cerpen ini (yang Intan beri nama Sindelarat) bukan protagonis. Sang protagonis justru dua saudari tirinya, dengan salah satunya menjadi narator. Tapi, yang utama ingin disampaikan cerpen ini, menurut saya, adalah gugatan mengapa perempuan harus menindas satu sama lain hanya demi mendapatkan seorang laki-laki meskipun laki-laki itu seorang pangeran tampan nan baik hati.
Selain itu, Anda akan dibawa oleh cerpen ini menuju alternatif akhir dongeng tersebut. Sindelarat dan sang pangeran tidaklah “live happily ever after” (bukankah banyak hubungan berkubang dalam benci dan derita). Sang pangeran—karena tradisi bangsawan di mana pun—memiliki gundik. Lalu, kecantikan dan kemolekan tubuh Sindelarat memudar karena harus terus melahirkan anak setelah ia hanya bisa memberi sang pangeran anak demi anak perempuan yang tak bakal menjadi pewaris kerajaan. Kebaikan hati Sindelarat juga hanyalah pencitraan demi ambisinya mendapatkan sang pangeran. Bukankah dalam kenyataan, manusia kerap lebih menyukai kebaikan yang palsu daripada keburukan yang jujur?
“Mobil Jenazah” membawa ingatan saya kepada sebaris lirik lagu country If I Die Young dari The Band Perry—meskipun cerpen ini menyinggung komposisi klasik Moonlight Sonata gubahan Beethoven yang mendirikan bulu kuduk itu. Sebaris lirik itu mengatakan, Funny when you’re dead, how people start listenin. Saat kita mati, kata lirik itu, barulah orang mendengar kita. Di sisi lain, lirik itu, menurut saya, juga ingin mengatakan bahwa hanya saat mati, kita baru bisa mendengar suara hati kita sendiri dan melihat kenyataan sejati di sekitar kita.
Dan itulah yang terjadi pada Karin dalam “Mobil Jenazah”. Saat hidup, Karin adalah perempuan sukses dalam rumah tangga, karir, dan pengasuhan anak. Dia perempuan berstrategi, katanya, yang tak ingin ada sedikit hal pun meleset dalam hidupnya. Bahkan, dengan sinis, dia berkata, “Aku menikmati pandangan iri orang lain terhadap berbagai aspek hidupku.” Ketika kecacatan menghampiri hidupnya, seperti suaminya yang berselingkuh, Karin bersedia menjadi siapa pun agar penampakkan hidupnya yang sempurna di mata orang lain tetap terjaga. “Acting is believing”, katanya.
Hidup Karin dengan begitu adalah kepura-puraan, dan bukankah itu yang ingin dilihat sebagian besar orang: sebuah kesempurnaan yang pura-pura. Karin yang pura-pura sebenarnya tengah menjalani hidup dalam sorotan lensa mikroskop yang dibuat oleh pandangan sosial tertentu: bahwa istri harus tetap setia dalam pernikahan meskipun suami main mata dengan perempuan lain. Sebab, suami berselingkuh karena istri tak mampu membuatnya bahagia. Sebab, perceraian itu memalukan. Dan pandangan sosial bahwa orang tua sukses adalah yang anak-anaknya memperoleh predikat terbaik di sekolah, berkuliah di perguruan tinggi dan jurusan favorit, serta memiliki masa depan gemilang di dunia kerja. Ketika tahu dia mati, Karin pun melihat selaksa cacat dalam hidupnya berdesak-desakan ingin keluar dari kotak pandora yang selama ini ia coba tutupi rapat-rapat.
Dengan menggunakan kisah horor tentang mobil jenazah pencabut nyawa, Intan membuat cerpen ini gelap dan memikat. Mobil jenazah seakan menemani perjalanan kesadaran Karin tentang kehidupan dan kematiannya. Kehidupannya adalah kematian kesadarannya sementara kematiannya justru kebangkitan kesadarannya.
Lalu, narasi oksimoron hadir dalam “Pintu Merah”. Perhatikan bagaimana narator melukiskan pelangi sebagai merah, cokelat, dan ungu lebam. Lalu luka pun ia sandingkan dengan keindahan. “Seindah luka yang menganga,” katanya. Senyum pun tetap merekah justru saat darah mengalir dan daging terkoyak.
Itulah lukisan Dahlia, karakter utama cerpen ini. Dia anak perempuan bungsu yang merawat ayahnya, lelaki tua bekas penguasa yang sakit-sakitan. Kakak-kakaknya telah meninggalkan rumah dan hanya menyumbang biaya hidup. Dahlia terperangkap dalam rumah tua itu, tak punya kehidupan seperti gadis lain seusianya: bermain, bersolek, dan berkencan. Ayahnya menganggap Dahlia anak terbaiknya, si penurut yang tak pernah memberontak seperti kakak-kakaknya.
Tapi, tahukah Anda, setiap orang yang Anda temui adalah manusia yang tengah bertarung di medan laganya masing-masing. Dan, Dahlia punya pertarungannya sendiri; pemberontakannya sendiri. Ia tampak penurut di mata ayahnya. Tapi di kedalaman jiwanya, ia pemberontak yang menganggap ayahnya tak lebih daripada sekadar pencundang tua yang bergantung kepada dirinya. Ia adik kecil yang penyabar di mata kakak-kakaknya. Tapi di balik kesabaran itu, ia menyimpan api kerinduan akan kebebasan dan petualangan—yang dia temukan di balik pintu merah.
Hati-hati memperlakukan orang! Kita mungkin terbiasa menilai seseorang tak signifikan. Tapi, tiap manusia punya jiwa: nilai keberadaannya. Tak ada yang pernah mengerti kedalaman anugerah Tuhan yang satu ini. Meskipun riaknya tampak tenang, di kedalaman ia bisa jadi menyimpan magma yang tiap saat bisa menggelegak, meledak, dan memicu tsunami.
Intan menggambarkan kedalaman jiwa itu melalui lubang mata pada bayangan wajah perempuan di sumur di balik pintu merah. Ya, orang kerap mengatakan mata adalah jendela menuju jiwa manusia.
Cerpen “Misteri Polaroid” tak menghadirkan teror. Ia semata horor tentang hantu perempuan yang tertangkap kamera Polaroid seorang fotografer profesional. Di sini, Intan menurut saya hanya ingin bercerita menyeramkan. Tak ada yang baru: kisah hantu terekam kamera dan perempuan yang bunuh diri karena dipaksa kawin. Lalu, apa pula hubungan cerita seram itu dengan subplot tentang fotografi dan kehidupan model, yang harus menderita demi penampilan sempurna di hadapan kilatan blitz?
Tak semua cerpen dalam kumpulan ini mudah dipahami. Salah satunya adalah “Jeritan dalam Botol”. Intan menjejali cerita ini dengan metafora: burung yang membakar diri (tampaknya burung mitologi foniks); kain gendongan bayi penghubung jiwa; ruangan putih polos tak berpintu yang menghisap seseorang ke dalamnya; jeritan dalam botol, dan banyak lagi.
Saya menginterpretasikannya menceritakan perempuan yang dianggap masyarakat sebagai tukang tenung. Pekerjaannya adalah menggugurkan kandungan (“melenyapkan nyawa”). Pelanggannya para pekerja seks, ibu rumah tangga, hingga perempuan “baik-baik” yang menanggung beban persepsi masyarakat.
Masyarakat pada umumnya menista para pelaku aborsi. Tak peduli apa pun dalih mereka. Tapi, pernahkah kita untuk sebentar saja menunda penghakiman dan mencoba mendengarkan penjelasan mereka? Setidaknya untuk sekadar berbagi beban berat yang mereka tanggung. Dan Sumarni, karakter tukang teluh (yang tampaknya juga dukun beranak) dalam cerpen ini, melakukan itu. Ia menampung suara-suara perempuan yang terpaksa membunuh bayi-bayi mereka dalam botol.
Namun, karena terlalu banyak metafora dalam cerita ini, penuturannya tak mengalir; tak terlalu natural. Pembaca, setidaknya saya, dipaksa untuk mengernyitkan dahi mengais makna dalam kegelapan metafora yang disemburkan Intan.
Kasus serupa terjadi dalam cerpen “Darah” meskipun dalam kadar yang lebih sedikit. Intan di sini mengajak kita merenungi darah dan tubuh perempuan—ya hanya perempuan yang akrab dengan darah: saat menstruasi, melahirkan, atau persetubuhan pertama. Semua momen itu berdarah-darah.
Darah yang keluar dari tubuh perempuan menjijikkan dalam pandangan banyak orang, dan karenanya coba ditutupi, dengan pembalut, misalnya. Darah itu pula yang menandai momen saat perempuan dijejali banyak aturan dan norma agama serta kesusilaan—sesuatu yang tak pernah dialami laki-laki. Dan darah itu juga yang, dalam konstruksi sosial tertentu, bisa memisahkan mana perawan dan pelacur.
Darah itu dibenci tapi juga dicari oleh laki-laki demi sebuah kebanggaan bahwa dia telah mereguk kenikmatan dari cawan suci. Darah itu juga ditunggu-tunggu laki-laki yang tak ingin menanggung konsekuensi dari pelampiasan libidonya.
Mengapa semua keruwetan soal darah ini ada? Bukankah darah di tubuh perempuan adalah sumber kehidupan? Itulah yang ingin dipertanyakan Intan melalui cerpen ini. Dengan menambahkan plot horor berupa dongeng hantu perempuan yang menjilati darah pada pembalut di toilet, cerita ini cukup mencekam meskipun tak terlalu menghadirkan teror seperti cerpen-cerpen lain. Penuturan dalam cerita ini pun kurang mengalir karena cukup banyak metafora di dalamnya. Metafora itu biasanya ditempatkan dalam imajinasi atau arus kesadaran karakter-karakternya.
Cerpen-cerpen dalam kumpulan ini memang kerap menggunakan perangkat-perangkat susastra untuk memprovokasi perasaan dan pikiran pembaca kepada pengalaman imajinatif, khayali, dan surealis, seperti oksimoran, metafora, dan simbolisme. Ini menyiratkan Intan hendak melakukan perlawanan terhadap bahasa yang jelas; bahasa yang terang, yang menurut kajian feminisme dikonstruksi oleh phallocentrism (pandangan bahwa laki-laki adalah pusat segalanya, termasuk dalam pembentukan bahasa). Intan ingin melawan itu tidak di “dunia terang” tapi di “dunia gelap”. Sebab, di “dunia terang”, kuasa phallus begitu hegemonik.
Beranjak ke “dunia gelap” tak hanya dilakukan melalui penggunaan perangkat susastra. Intan juga melakukannya dengan menyisipkan mitologi, urban legend, cerita rakyat, dan bahkan antropomorfisme.
“Sejak Porselen Berpipi Merah Itu Pecah” adalah contoh penggunaan antropomorfisme meskipun itu tak mendominasi cerita. Dia ujung cerpen ini, si narator bisa membaca dan mengutarakan pikiran dan perasaan seekor kucing dan sebuah boneka porselen. Lalu, dalam “Sang Ratu”, pembaca dibombardir dengan mitologi Yunani dan Jawa: dari Medusa, Siren, hingga Nyi Roro Kidul (permaisuri abadi raja-raja Jawa dari alam lelembut).
Kucing, boneka porselen, Medusa, Siren, dan Roro Kidul adalah representasi “dunia gelap”; dunia non-manusia (dunia terang). Di “dunia terang”, mereka bukan apa-apa dan siapa-siapa. Tapi, di “dunia gelap”, mereka adalah bagian dari kemungkinan tak terbatas, yang tak bisa dikendalikan oleh kuasa dari “dunia terang”.
Lantas, apakah melakukan perlawanan di “dunia gelap” merupakan pertanda fatalisme karena kekalahan di “dunia terang”? Tidak, menurut saya. Itu justru sebuah kesadaran radikal. Di “dunia terang”, kebenaran ditentukan oleh kuantitas: seberapa banyak dukungan orang, seberapa besar pengaruh, dan seberapa kaya—semuanya serba jumlah. Di “dunia gelap”, semua itu tak berlaku. Kebenaran di sana akan kembali kepada sumbernya: jiwa.
Karena itulah, di dunia terang kita sebenarnya tak pernah dituntut untuk memenangkan kebenaran. Kita hanya diminta menyatakan dan menunjukkannya. Para nabi dan orang-orang bijak dalam sejarah “dunia terang” kerap mengalami kekalahan dan kejatuhan. Tapi, mereka tak mutung. Sebab, mereka tahu kemenangan bukanlah bagian dari tugas mereka. Tugas mereka hanyalah menyatakan dan menunjukkan kebenaran.
Begitupun dengan perlawanan para “perempuan” dalam Sihir Perempuan. Kedalaman jiwa merekalah yang melawan, memberontak, dan menggugat. Jiwa mereka bisa mengasihi tapi juga bisa meneror dan membunuh. Tak ada yang bisa menghentikan mereka karena, di “dunia gelap”, jiwalah yang berkuasa.
Di titik ini, saya teringat dengan ulasan Annemarie Schimmel bahwa kata jiwa dalam teks Islam justru bergender feminin. Karenanya, saya ingin mengatakan bahwa Sihir Perempuan sebenarnya tak hanya berkisah tentang jiwa perempuan dalam pengertian seks biologis, tapi jiwa manusia, siapa pun dia. Karenanya, Sihir Perempuan merupakan gambaran feminitas jiwa manusia yang merindukan kebenaran dan keadilan.[]

Intan Paramaditha
Intan Paramaditha (Bandung, 15 November 1979) adalah pengarang dan akademisi. Dia menerbitkan kumpulan cerpen Sihir Perempuan di usia 25 tahun. Lima dari sebelas cerpen dalam kumpulan ini pernah dimuat di Kompas dan Koran Tempo pada 2004 dan 2005. Kumpulan ini masuk jajaran 5 besar Kusala Sastra Khatulistiwa 2005.
Intan sejauh ini kerap menyajikan genre horor dan misteri yang bertemakan gender dan seksualitas, serta kaitan keduanya dengan budaya dan politik. Pada 2010, bersama Eka Kurniawan dan Ugoran Prasad, dia menghasilkan kumpulan cerpen bergenre horor Kumpulan Budak Setan, yang merupakan pembacaan ulang atas karya-karya Abdullah Harahap, pengarang horor produktif di era 1970 hingga 1980-an.
Pada 2013, cerpennya “Klub Solidaritas Suami Hilang” memperoleh penghargaan sebagai salah satu Cerpen Terbaik Kompas. Pada tahun yang sama, bersama Naomi Srikandi, Intan menerbitkan naskah drama Goyang Penasaran: Naskah Drama dan Catatan Proses.
Pada 2017, Intan menyelesaikan novel pertamanya, Gentayangan: Pilih Sendiri Petualangan Sepatu Merahmu. Format novel ini bisa dibilang baru dalam kesusastraan Indonesia karena pembaca bisa memilih sendiri alur cerita di dalamnya dengan akhir cerita yang berbeda. Novel ini terpilih sebagai Karya Prosa Terbaik Tempo 2017 dan 5 besar Kusala Sastra Khatulistiwa 2018.
Karya Intan telah diterbitkan dalam bahasa Inggris, yaitu kumpulan cerpen Apple and Knife dan novel The Wandering (Gentayangan). Keduanya diterjemahkan oleh Stephen J Epstein dan diterbitkan Harvill Secker.
Sebagai akademisi, Intan mengajar kajian media dan film di Macquarie University, Sydney, Australia, setelah menyelesaikan program doktoral di New York University, Amerika Serikat.[]