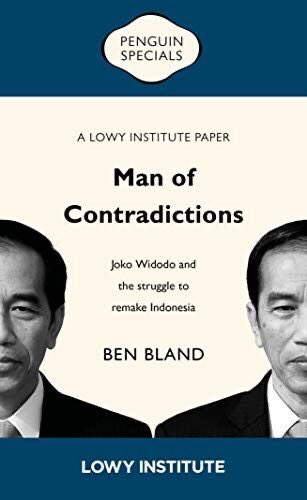Buku ini mencoba mencari tahu mengapa pemerintahan Jokowi penuh dengan kontradiksi. Buku ini kemudian juga mencari jawaban mengapa jurnalis dan analis Barat kerap salah memahami politik Indonesia.
BEN Bland, eks jurnalis Financial Times di Indonesia dan kini Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute, meluncurkan buku Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia. Ben bilang bukunya adalah biografi pertama Presiden Jokowi dalam bahasa Inggris.
Selamat, Ben! Buku Anda memicu perbincangan di mana-mana, dari media massa arus utama negeri ini sampai kanal YouTube filsuf-seleb Rocky Gerung. Hanya Istana yang tampak masih adem ayem.
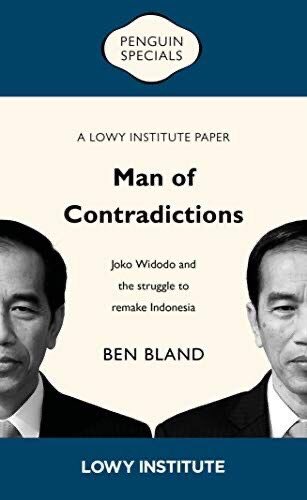
- Judul Buku: Man of Contradictions: Joko Widodo and the struggle to remake Indonesia
- Penulis: Ben Bland
- Penerbit: Penguin Specials
- Terbit: 1 September 2020
- Tebal: 192 halaman (e-Book)
Karena buku Anda ditulis dalam bahasa Inggris, Istana mungkin menganggapnya tak bakal berdampak signifikan bagi publik Indonesia. Toh, Anda pun tampaknya ingin lebih berbicara kepada pengambil kebijakan, pengusaha, dan analis dari luar negeri dengan buku ini.
Baik, Ben. Dalam buku ini, Anda berupaya mencari tahu mengapa Jokowi yang awalnya digambarkan bak ksatria jedi pendobrak kemapanan oligarki lama (A New Hope, majalah Time bilang) ternyata kini justru seperti sosok Darth Vader, pelayan setia kuasa gelap itu. Dia dulu menunjukkan dirinya tak berambisi kekuasaan tapi kini calon “godfather” dari sebuah bakal dinasti politik.
Dia dulu dikenal sebagai pemimpin antikorupsi. Setidaknya begitulah kata putus para juri Bung Hatta Award. Tapi, dia kini malah berperan besar dalam melemahkan lembaga antikorupsi paling populer di mata rakyat.
Dalam kampanye, para pendukungnya menggembar-gemborkan dia pengusung obor pluralisme dan moderasi Islam. Tapi, jangankan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap warga minoritas, dia malah menjadikan figur konservatif (meskipun berasal dari NU yang moderat) sebagai pendampingnya (terlepas apakah itu pilihan dia atau koalisinya). Orang-orang luar negeri, menurut Anda, juga dulu berharap dia bakal menghadirkan liberalisasi ekonomi tapi ternyata dia tak kalah proteksionis dengan para pendahulunya.
Saya membaca kekecewaan Anda dalam buku ini, Ben. Harapan Indonesia menjadi suar demokrasi di Asia ternyata makin pudar. Begitulah kira-kira pandangan Anda dan kolega tentang Indonesia hari-hari ini.
Dan karena itu, Anda kemudian juga mencari jawaban mengapa jurnalis dan analis Barat kerap salah memahami Jokowi pada khususnya dan politik Indonesia pada umumnya. Dalam kesimpulan, Anda mengakui bahwa Anda dan para kolega cenderung mencari penyebab tunggal dari fenomena politik Indonesia yang kompleks, berupaya memasukkannya ke dalam kerangka teori-teori Barat. Hasilnya, menurut Anda, adalah analisis yang seringkali menyederhanakan atau membesar-besarkan suatu fenomena.
Kesadaran, atau katakanlah pencerahan, yang Anda alami, Ben, sebenarnya bukan hal baru. Anda dalam buku ini menyebut Benedict Anderson. Ya, mendiang Ben yang satu itu sudah menyadari hal serupa dalam banyak karyanya tentang Indonesia, terutama Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia (1990) yang juga Anda kutip. Peter Britton juga demikian. Ketika mencoba memahami sikap dan perilaku militer Indonesia, Britton mengulik etika ksatria dari legenda Jawa dalam Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia (1996).
Kalau Anda merasa bingung dengan politik di negeri ini setelah satu dekade tinggal di sini, kami sudah hidup dengan “kebingungan” itu sedari lahir, Ben. Sejak negeri ini merdeka, politisi dan elite kami selalu bilang Indonesia unik, tak bisa didefinisikan dengan teori-teori Barat. Bagi Sukarno, demokrasi kami adalah “demokrasi terpimpin”. Suharto kemudian punya istilah “demokrasi Pancasila”. Mohamad Hatta mengatakan demokrasi kami adalah adonan dari liberalisme, sosialisme, dan Islam. Lalu, seperti Anda tulis dalam buku ini, Jokowi menyebutnya dengan “demokrasi gotong-royong”.
Apa makna semua itu bagi kami? Jujur, kami tak tahu dan kadang juga tak peduli. Bukankah setiap bangsa, dan kemudian setiap negara, sama unik dan kompleksnya?
Yang kami tahu semua politisi dan partai itu sama meskipun warna mereka merah, kuning, hijau di langit yang biru. Semuanya anti-komunis tapi ogah dibilang liberal atau pro-pemodal. Semuanya tak mau hanya disebut “Islamis” tapi juga ingin punya label nasionalis. Maka, partai-partai itu memunculkan istilah hibrid: Islam-nasionalis atau nasionalis-religius.
Jadi, jika Edward Aspinall1 (dalam ulasannnya atas buku Anda) bilang Indonesia saat ini sedang mengikuti tren global, di mana muncul rezim hibrid (lahir dari prosedur demokrasi tapi cenderung otoriter), itu tak sepenuhnya keliru. Persoalannya, kami sudah hidup dengan hibriditas itu sejak lama sebelum orang-orang macam Recep Tayyip Erdogan, Jair Bolsonaro, atau Donald Trump muncul. Orang Turki, Brazil, dan Amerika pun sudah tahu apa yang akan dilakukan ketiga politisi itu ketika mereka berkuasa. Sementara, kami belum tahu apa-apa saat harus memilih Jokowi atau Prabowo. Janji-janji mereka berdua sulit dibedakan.
Jadi, Ben, karena harus memilih (sebab golput bisa dianggap sakit jiwa), kami akhirnya memilih berdasarkan penampilan dan pencitraan, bukan karena tahu akan mereka bawa ke mana Indonesia. Jokowi kemudian menang karena, seperti yang Anda tulis, piawai menampilkan citra dekat dengan rakyat, sederhana, dan berwajah ndeso. Sebagian besar kami saat itu mungkin sudah bosan dengan penampilan pemimpin yang serba rapi, gagah-bak-serdadu, dan serba tertata sikap dan perilakunya.
Selain itu, Prabowo jadi pecundang karena terlalu menggebu-gebu dan berambisi. Ini tak sesuai dengan “budaya” kami. Kami ini bangsa yang harus menyimpan rapat-rapat ambisi dan keinginan. Kalaupun suatu saat ambisi itu mau tidak mau terungkap, politisi kami paling jago mencari dalih. Dan dalih mereka pun sungguh mulia: “demi bangsa dan negara”; “kalau kompeten, mengapa tidak”; “karena rakyat menginginkan”.
Anggaplah ada perbedaan antara Jokowi dan Prabowo, terutama karena Prabowo membawa rombongan garis keras sebagai pemandu soraknya. Tapi, apa pun perbedaaan itu, keduanya pada akhirnya berada dalam satu gerbong kekuasaan yang sama. Sang jenderal kini anak buah sang pengusaha mebel. Kelokan plot yang luar biasa, bukan? Tapi, jujur, sebagian kami tak kaget, Ben. Pendukung Jokowi bahkan punya dalih bijak, yang diambil dari filosofi Jawa—yang juga Anda kutip dalam buku ini: menang tanpa ngasorake.
Saya yakin Anda sudah pernah membaca Manusia Indonesia yang ditulis Mochtar Lubis, dan dibacakannya dalam pidato kebudayaan pada 1977. Karakter pertama dari enam karakter orang Indonesia dalam buku itu, menurut saya, cukup bisa menjelaskan mengapa Anda dan kolega Anda kerap salah memahami politik Indonesia.
Karakter pertama itu, kata Mochtar Lubis, adalah munafik. Diksi Mochtar terlalu kasar di telinga orang Indonesia. Saat menuliskan itu, Mochtar mungkin sedang tidak menjadi orang Indonesia.
Saya, yang masih orang Indonesia, mencoba menghaluskan kata munafik itu dengan omong kosong. Ya, politisi kami mahir merapal omong kosong dan kebetulan kami menyukainya. Omong kosong bukan menipu, Ben. Ia juga bukan berbohong. Omong kosong itu, kata Harry G Frankfurt, pembicaraan yang pembicaranya sendiri tak peduli kepada kebenaran ucapannya.
Begitulah politisi kami, Ben. Suatu waktu, mereka bisa berbusa-busa bicara Pancasila yang sarat beban nilai sosialisme tapi di saat yang sama ngotot menggolkan omnibus law yang menghebuskan napas neoliberalisme. Urat-urat leher mereka bisa tampak keluar saat sedang berkhotbah soal nasionalisme. Tapi, di depan investor luar negeri, mereka mengatakan negeri ini siap menggelar karpet merah selebar-lebarnya buat modal asing.
Presiden Jokowi juga tak berbeda. Baru-baru ini, dia mengeluhkan birokrasi yang gemuk sehingga anggaran negara cekak. Tapi, Anda pasti tahu—dan ini juga Anda tulis dalam buku ini—bahwa Jokowi-lah yang justru membuat birokrasi tak ramping. Dia mengangkat 12 wakil menteri. Ditambah 34 menteri dan sejumlah pejabat setingkat menteri, pemerintahannya menjadi salah satu yang tergemuk sejak era Demokrasi Terpimpin. Itu belum cukup. Dia juga menunjuk belasan staf khusus Istana, termasuk di antaranya “staf khusus milenial” yang beberapa waktu lalu memicu kontroversi.
Jadi, ini bukan soal berbohong tapi soal tak pernah satunya perkataan dan perbuatan. Itulah omong kosong, Ben. Pelaku omong kosong tak peduli dengan kebenaran ucapannya sementara pembohong peduli, dan karena itu berbohong.
Karena itu, Anda sudah tepat ketika menulis janji-janji Jokowi lebih merupakan kumpulan kata daripada komitmen kepada maknanya (there were formulaic statements rather than commitments to meaningful action). Saya sependapat dengan Anda.
Tapi, seperti juga Anda simpulkan dalam buku ini, itu bukan masalah seorang Jokowi. Itu masalah politik Indonesia secara umum. Itulah penyakit kronis politisi kami sejak dulu sampai sekarang. Mereka, seperti orang Jawa bilang, isuk tempe sore dele (pagi tempe, sore kembali jadi kedelai).
Politik kami sonder ideologi, Ben. Kiri-kanan oke. Politisi kami tak punya prinsip nilai yang ajeg. Keajegan mereka adalah pragmatisme, dan itulah ideologi mereka. Mereka seperti pedagang kepepet. Butuh uang dan siap nego.
Ini persis seperti yang Anda tulis bahwa untuk memahami Jokowi, orang harus melihatnya sebagai “Jokowi si pedagang mebel” bukan “Jokowi sang presiden”. Anda juga mengutip kata-kata seorang menteri (yang Anda wawancarai) bahwa politik di Indonesia itu tentang memikat orang kepada profit, bukan ide apalagi ideologi. Jadi, ketika seorang penanggap menulis buku Anda kurang menggali latar belakang ideologi Jokowi2, Anda sebenarnya sudah menjelaskan mengapa demikian.
Jangan keliru, Ben! Itu bukan berarti politisi di negeri-negeri Barat lebih baik daripada politisi kami. Tapi, politisi Barat setidaknya “jujur” dengan niat mereka. Trump dalam kampanye jelas-jelas menyatakan akan membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko atau menempuh kebijakan anti-imigran lainnya. Dia juga terang-terangan mengatakan tidak setuju dengan keterlibatan Amerika dalam kesepakatan nuklir Iran, dan bertekad membalik arah.
Pada akhirnya, ketika Anda menulis bahwa sudah saatnya kini kita berhenti mengatakan Indonesia berada di persimpangan jalan, saya sepenuhnya setuju, Ben. Indonesia memang tak sedang berada di persimpangan jalan, tapi dalam sebuah labirin.
Kami orang yang berupaya mencari jalan keluar tapi pada akhirnya terus kembali ke tempat semula. Masalah di negeri ini, Ben, terus berputar dari situ ke situ lagi. Anda juga menulis demikian dalam buku ini. Setelah 75 tahun merdeka, Indonesia masih terperangkap dalam persoalan yang sama soal dasar ekonomi, sistem politik, sistem hukum, dan peran agama dalam negara. Itu-itu saja persoalannya.
Jadi, dengan mengutip filosofi Jawa yang sering diucapkan Presiden Jokowi, saya ingin mengatakan, ojo kagetan, Ben![]
1Edward Aspinall, “Zeitgeist’s man” dalam https://insidestory.org.au/zeitgeists-man/, diakses pada 9 September 2020.
2Nava Nuraniyah, “The (un)making of Joko Widodo”, dalam https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/debate/man-of-contradictions, diakses pada 9 September 2020.