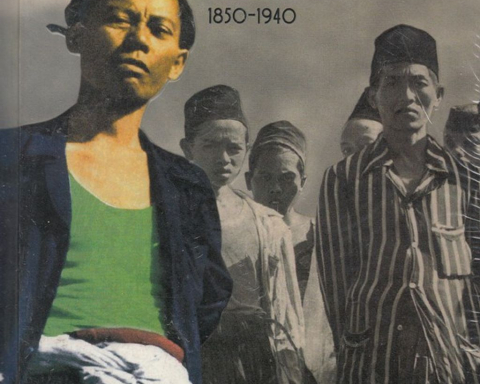Cerpen Kuntowijoyo
Catatan Redaksi: Cerpen ini memperlihatkan kredo kepengarangan Kuntowijoyo, yang ia sebut “sastra transendental”. Ia seperti mengkritik spirit kapitalisme Weberian bahwa kebahagiaan itu hanyalah: kerja, kerja, kerja!
AYAH baru saja dipindahkan ke kota ini, setelah bertahun mengajukan permohonan. Katanya, supaya aku mengenal hidup lebih luas dan tidak terkurung dalam lingkungan dusun yang sempit. Sehari setelah kami pindah, ayah sudah mulai bekerja dan sore hari baru ia kembali.
Ayahku tampak lebih segar, sekarang. Badannya tinggi besar dan kukuh, tidak terlelahkan oleh kerja apa pun. Bukan main senang hati ayah mendapatkan pekerjaan di kota. Ayah sibuk dengan pekerjaan, karena malas adalah musuh terbesar laki-laki, kata ayah. Benar, di desa kita banyak tetangga tetapi membuat pikiran banci. Dan itu ayah tidak suka. Kesibukan ayah membuatnya tidak mengenal tetangga, hanya ibu sudah mulai banyak kawan, seperti biasanya ibuku di mana pun kami ditempatkan. Ayahku mengangguk saja pada orang sekitar bila kebetulan berpapasan, lalu buru-buru masuk rumah. Ibu sudah sering mendesak agar ayah suka bergaul dengan masyarakat. Kita hidup bersama orang-orang lain, kata ibuku. Namun, kami sekeluarga belum juga mengenal tetangga kami yang terdekat.
Kabarnya yang tinggal di rumah tua berpagar tembok tinggi itu adalah seorang kakek yang hidup sendiri. Rumah itu terletak di samping rumahku. Pagar tembok tinggi menutup rumahnya dari pandangan luar. Hanya ada satu pintu masuk dari muka, ditutup dengan anyaman bambu yang rapat. Aku belum pernah melihat kakek itu. Setelah kucoba naik ke pagar tembok, melalui sebuah pohon kates di pekaranganku, terbentanglah sebuah pemandangan: Sebuah rumah Jawa. Bersih seperti baru saja disapu, dan alangkah banyak bunga-bunga di taman! Hari itu aku belum berhasil melihat penghuninya. Tidak pernah seharian penuh aku di rumah, ibuku menyuruh aku pergi sekolah pagi dan sore hari harus mengaji. Hari-hari Minggu pertama habis untuk mencari saudara-saudara baru di kota ini.
Keinginanku untuk mengenal kakek itu tidak pernah padam. Kau lihatlah, lubang-lubang pada pagar anyaman bambu itu ialah akibat perbuatanku. Aku mengerjakannya di siang hari sepulang dari sekolah. Pernah ketika aku mengintip-intip pintu pagar dari bambu itu, kawanku menegur, “Sedang apa kau ini? Hati-hati dengan dia. Sebentar lagi tanganmu sakit. Tunggu sajalah!”
Ketakutan menyerang aku. Apakah aku akan sakit karena mencoba membuka pintu pagar rumah ini?
“Siapa bilang?” kataku berani.
“Semua orang !” dijawabnya. “Kau kualat. Dia keramat!”
Aku ditinggalkannya, berdiri dekat pagar itu. Ketakutanku mendesak-desak. Aku lari puntang-panting ke rumah. Ayahku sudah duduk di kursi dengan selembar koran. Aku tenang kembali. Baru tersadar bahwa tas sekolahku tertinggal di pagar rumah samping itu. Sore hari aku memberanikan diri untuk mengambil tas yang tertinggal. Dan tas itu masih di sana! Tidak di mana pun di dunia ini, kecuali di pintu pagar itu, sebuah tas berharga akan selamat dari incaran orang.
Tentang kejadian itu kawan-kawanku mengatakan, tidak seorang pun berani mengambil, itu sudah pasti. Siapakah orangnya mau membunuh diri dengan upah sebuah tas sekolah? Lebih susah mencari sebuah nyawa daripada sebuah tas sekolah! Tidak satu pun toko menjual nyawa, tetapi semua toko menjual tas. Tentu saja!
Sejak itu niatku untuk mengetahui agak reda. Menyelidiki dengan mata sendiri, berbahaya! Tinggallah aku bertanya pada orang-orang lain. Keterangan orang tidak begitu jelas. Orang mengatakan, sekali seminggu ia ke luar berbelanja. Orang lain mengatakan ia berbelanja sebulan sekali. Orang mengatakan, ia mempunyai anak di kota lain. Orang lain mengatakan ia tidak beristri. Tidak seorang pun tahu pasti tentang dirinya.
Barangkali di antara kawan bermain hanya akulah yang mempunyai keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang kakek itu. Kawan lain sudah tidak acuh lagi. Aku sudah bosan bertanya, selain mereka juga tidak memberi keterangan jelas. Mereka akan mengejekku dengan mengatakan: “Biarlah kau jadi cucunya!”
Pernah pula aku bertanya pada ayahku. Ayahku melemparkan koran dari tangannya dan meninggalkan aku. “Untuk apa, heh !” jawabnya. Itu adalah ucapan ayah yang sering kudengar. “Bertanyalah tentang lokomotip, misalnya. Atau mobil. Jangan tentang kakek-kakek sebelah rumah.”
Aku sendirian saja di dunia, dengan keinginanku untuk mengetahui.
Tiba-tiba aku pun mengenalnya dari dekat. Begini: Pada musim layang-layang angin bertiup kencang. Jalanan muka rumahku tidak banyak kendaraan. Polisi membiarkan anak-anak main layang-layang di situ. Kami suka berkumpul pada sore hari. Di bagian ini angin dengan bebas berjalan, pepohonan tidak banyak.
Sore hari Jumat aku tidak pergi mengaji. Di tanganku sebuah layang-layang buatanku yang terbagus, dengan benang gelasan. Udara meruah menerbangkan layang-layangku. Dari kampung lain menyembul pula layang-layang. Layang-layangku terputus. Kawan-kawan bersorak dan lari mengejar. Itu layang-layangku yang terbagus, aku berdiri saja memandangi. Tiba-tiba pundakku terasa dipegang. Aku terkejut. Seorang laki-laki tua dengan rambut putih dan piyama. Ia tersenyum padaku: “Jangan sedih, cucu,” katanya.
Suara itu serak dan berat. Sebentar darahku tersirap. Aku teringat rumah tua berpagar tembok tinggi. Mataku melayang padanya. Di tangannya setangkai bunga berwarna ungu. Tubuhku seketika menjadi dingin.
“Jangan sedih, cucu. Hidup adalah permainan layang-layang. Setiap orang suka pada layang-layang. Setiap orang suka hidup. Tidak seorang pun lebih suka mati. Layang-layang bisa putus. Kau bisa sedih, kau bisa sengsara. Tetapi engkau akan terus memainkan layang-layang. Tetapi engkau akan terus mengharap hidup. Katakanlah, hidup itu permainan. Tersenyumlah, cucu.”
Ia menjangkau tangan kananku. Membungkuk, dan tanganku diciumnya. Aku tidak berdaya. Bunga itu dipindahkan ke tanganku. Aku menggenggamnya, seolah dalam impian.
Ia menarik tanganku dan aku mengikutinya. Di tangan kananku setangkai bunga. Ketika aku sempat menyadari, kulihat pintu pagar rumah tua itu. Pasti, dialah kakek itu! Ya, Allah! Aku menjerit sekerasnya. Teriakan itu tersumbat di kerongkonganku. Aku meronta. Ia memegangiku lebih kuat. Tertawa terkekeh. Aku meronta dan tertawanya yang serak itu alangkah kerasnya.
Ibu membawaku pulang. Aku tidak begitu sadar, tiba-tiba ibu sudah menuntun aku. Di rumah kulihat ayah membaca di kursi. Aku merasa tenang. Aku sangat malu.
“Untuk apa teriak-teriak, heh!” kata ayah menyambutku. Ia mengamati aku dari atas ke bawah. Ia berdiri dan menjangkau tangan kananku, katanya pula: “Untuk apa bunga ini, heh!”
Aku tidak tahu karena apa, telah mencintai bunga di tanganku ini. Ayah meraih, merenggutnya dari tanganku. Kulihat bungkah otot tangan ayah menggenggam bunga kecil itu. Aku menahan supaya tidak berteriak.
“Laki-laki tidak perlu bunga, buyung. Kalau kau perempuan, bolehlah. Tetapi engkau laki-laki!”
Ayah melemparkan bunga itu. Aku menjerit. Ayah pergi. Ibu masih berdiri. Aku membungkuk, mengambil bunga itu, membawanya ke kamar. Tangkai bunga itu patah-patah. Selembar daun bunganya luka. Aku menciumnya. Lama. Lama sekali.
Malam itu aku tidak mau makan. Ibu masuk kamar dan membujuk. “Tentu saja kau boleh memelihara bunga,” kata ibu. “Bagus sekali bungamu itu. Itu berwarna violet. Bunga ini anggrek namanya. Aku suka bunga. Kuambil vas, engkau boleh mengisinya dengan air. Dan taruh bunga itu di dalamnya. Kamar ini akan berubah jadi kamar yang indah! Setuju?”
Ketika aku bangun pagi, aku merasa telah bersahabat baik dengan kakek itu. Aku ingat betul: tangan kurus dengan otot menonjol, rambut putih, suara serak.
Berangkat sekolah aku lewat di muka pintu pagarnya seperti biasa, tetapi dengan perasaan bersahabat. Kepada pintu pagar itu aku tersenyum, maksudku pada kakek, sahabatku yang baru itu. Aku merindukannya.
Aku mencari-cari kesempatan untuk bertemu dengan kakek. Pulang sekolah aku memanjat tembok pagar dari sebatang pohon kates, berjalan mondar-mandir di atas, mengintai rumah tua itu. Sesaat aku melihat kakek di dalam rumah itu. Aku memanggilnya. Dan sungguhpun tak terduga ia keluar juga. Ia berdiri di bawah, dekat tempatku di atas tembok, tersenyum. Ia seorang yang ramah, baik hati dan penyayang anak pula.
“Turunlah, cucu. Ada sebuah tangga. Tunggu, ya!”
Aku turun dengan sebuah tangga. Untuk pertama kali, di pekarangan rumah sebelah. Kakek tertawa terkekeh. Ia mengelus kepalaku. Meniup dengan mulut di ubunku. “Engkau jadi orang gede, cucu!” katanya. “Aku yakin. Matamu menunjukkan itu!”
Tanganku dia bimbing, kakiku berjalan dengan langkah cepat mengikutinya. Kami duduk di ruang tengah. Ada kursi-kursi di sana. Aku dimintanya duduk di sampingnya.
“Duduklah, cucu. Di samping kakek. Nah, siapa namamu?”
Aku
sebutkan namaku, sambil mataku melayang ke sekitar. Semuanya
penuh bunga. Aku menatap wajah kakek, kerut-merut kulit tua.
Kataku: “Banyak sekali bunga, Kakek?”
“O, ya, banyak. Aku suka bunga-bunga.”
“Belum pernah kulihat yang sebanyak ini, sebelumnya.”
“Tentu saja. Kenapa tidak sejak dulu datang ke sini?”
“Kenapa Kakek tidak datang ke rumahku?”
Ia tertawa, mengusap-usap kepalaku. “Pintar, ya. Kau sering memanjat pagar itu, bukan?”
“Ya.” Ternyata kakek mengetahui tingkahku. “Siapa memberi tahu?”
“Mataku, cucu.”
“Hanya untuk melihat-lihat saja, Kek.”
Ia tertawa, terguncang badannya. “Tentu saja aku tahu, itu. Kau anak baik, cucu. Karena, mata batinku lebih tajam dari mata kepalaku.”
Aku mulai tenteram duduk di sampingnya. Tidak ada lagi yang harus dikhawatirkan. Kami bersahabat baik. Entahlah, rasanya amat menyenangkan duduk bersamanya di sini. Bayanganku yang lama telah hilang: Aku merasa kerasan. Agak dingin udara di sini, angin sejuk. Bunga-bunga merah, biru, kuning, ungu. Daun-daunnya hijau. Kumbang terbang antara bunga-bunga. Tanah basah. Daun bergoyang, bayang-bayang matahari. Oya, ayam jantan berkeliaran antara bunga-bunga, berbulu indah dan lagi lari memburu betina. Di pojok keduanya berhenti. Kakek menarik napas panjang.
“Isteriku sudah tidak ada lagi, cucu. Di sini aku hidup sendiri. Aku punya anak, cucu. Tapi mereka jauh di kota lain. Maukah kau menjadi cucuku, sahabat kecilku?”
Aku mengangguk.
“Jangan khawatir, cucu. Anggaplah di sini rumahmu. Datang-datanglah ke sini, bila kau senggang. Terimalah kakekmu, ya. Kita bisa duduk di sini, melihat taman. Aku punya banyak bunga di sini. Hidup harus penuh dengan bunga-bunga. Bunga tumbuh, tidak peduli hiruk-pikuk dunia. Ia mekar, memberikan kesegaran, keremajaan, keindahan. Hidup adalah bunga-bunga. Aku dan kau adalah salah satu bunga. Kita adalah dua tangkai anggrek. Bunga indah bagi diri sendiri dan yang memandangnya. Ia setia dengan memberikan keindahan. Ia lahir untuk membuat dunia indah. Tataplah sekuntum bunga dan dunia akan terkembang dalam keindahan di depan hidungmu. Tersenyumlah seperti bunga. Tersenyumlah, cucu!”
Dan aku tersenyum. Pikiranku melambung jauh, ke sebuah dunia yang asing, yang penuh dengan rahasia tetapi mengasyikkan.
Siang itu kami bermain-main di antara bunga-bunga. Kakek bercerita banyak tentang bunga. Satu-persatu ia uraikan dari mana bibit bunga, memelihara, mengawinkan. Kami asyik sekali. Pengetahuannya tentang bunga sungguh mengagumkan. Bunga-bunga tanaman kakek memenuhi halaman muka, samping belakang. Dan di dalam rumah. Rumah itu adalah taman bunga. “Rumah ini sebagian kecil dari sorga,” katanya.
Sore hari aku pulang dengan bunga-bunga di tangan. Aku kembali lewat pagar tembok. Kakek mengantarkanku ke tangga dan memegangku erat-erat. “Hati-hati cucu!” dan ia menepuk pantatku pelan. Di atas pagar aku berdiri, mencium bunga di tangan, melambai pada kakek lalu menuruni pohon kates. Aku berlari kecil menyembunyikan bunga.
Sampai di pintu ayahku telah berdiri di sana. Aku tersadar. Hari sudah sore dan lupa mengaji.
“Engkau harus mengaji, tahu. Dari mana?” ayah menegur dengan suara berat dan dingin. Aku berdiri saja. Ingin aku menyembunyikan setelitinya bunga-bunga di tanganku. Ayah terlanjur melihat. Aku diam. Ayah tidak suka dibantah.
“Kau pergi mencari bunga-bunga itu. Untuk apa, heh!?”
Tenggorokanku tersumbat. Aku diam. Diam. Tidak berani menatap wajah ayah.
“Di mana carinya?”
Tetapi aku harus menyembunyikan dari mana asal bunga-bunga-ku itu. “Di sungai, yah,” kataku membohong.
Ayah merampas bungaku. Dan membuangnya ke sampah. Perasaan yang kemarin datang lagi. Aku ingin mengambilnya kembali.
“Engkau mulai cengeng, buyung. Boleh ke sungai, untuk berenang. Bukan mencari bunga, begitu!”
Setelah lewat dari pengawasan ayah aku menjemput bunga itu dari sampah, dan kubawa ke kamarku. Ya, dengan ayah aku harus berhati-hati. Dengan ibu aku baik-baik saja. Ibuku kurasa amat senang, aku jadi kerasan di rumah. Di kamarku selalu terlihat vas dengan bunga-bunga. Ayah belum pernah memerlukan menjenguk kamarku. Itu menyenangkan. Ayah terlalu sibuk untuk mencampuri urusanku.
Aku mulai segan bertemu dengan ayah. Seperti ada orang lain dalam rumah bilamana ayah ada. Kehadiran ayah menjadikan aku gelisah. Pasti, ayah akan datang dengan baju kotor bergemuk. Seluruh badan berlumur minyak hitam. Bungkah-bungkah badan menonjol. Terasa rumah jadi bergetar oleh kedatangan ayah. Kadang kulihat ayah menggosokkan tangan kotor itu pada dagu ibu, tapi ibu bahkan tersenyum padahal aku sangat kasihan melihatnya.
Kalau ayahku pulang, aku cepat ke kamar. Di kamar, menatap bunga-bunga sangat lain dengan melihat wajah ayah. Menggelisahkan bila ayah memanggilku. Tetapi bila ia memerlukanku, pastilah aku cepat menghadap, sebab aku selalu tinggal di kamar.
Beberapa hari berlalu. Sejak hari yang malang itu aku berhati-hati. Aku tahu kapan ayah biasanya pulang kerja. Dan waktu itu aku berusaha di rumah. Pergi ke rumah sahabat tuaku yang baik itu aku harus pada waktu yang tepat. Kukira ayah ibu tidak mengetahui tingkah lakuku. Satu kali ayah memanggilku. Aku ke luar dari kamar.
“Dari mana?” ia bertanya.
“Di rumah. Di kamar.”
“Untuk apa di kamar, heh. Laki-laki mesti di luar kamar!”
Ayah menyuruh ibu supaya aku disuruhnya bermain di luar. “Engkau mesti memilih permainan yang baik,” kata ibuku. “Ayahmu menyuruhmu main bola. Atau berenang. Kalau tidak mau, kau akan dibawanya ke bengkel.” Dan beberapa hari kemudian, sebuah bola dari kulit yang bagus tersedia di rumahku. Ayah menyediakan pula sebuah alat olah raga. Ayah memberi contoh bagaimana memakainya. Tetapi mengangkatnya saja aku tak berdaya.
Bagiku sungguh lebih enak tinggal dalam kamar. Kawan-kawan datang mengajakku bermain. Tetapi aku menolak. Permainan hanya bagi anak-anak kecil. Apakah yang lebih menyenangkan daripada bunga dalam vas?
Sahabatku terdekat ialah kakek. Kami banyak bertukar pikiran. Sungguh ia orang tua yang pandai. Pasti aku mengunjunginya setiap hari. Bagiku tidak ada kewajiban lain yang mengikat kecuali ke sekolah dan mengaji. Selebihnya untuk kami berdua: Aku dan sahabat tuaku itu. Ayah ibu akan memarahiku apabila aku melupakan sekolah atau mengaji. Ayahku akan memanggil aku. Disuruhnya aku berdiri menyaksikan wajahnya. Sebuah neraka terlintas dalam kepalaku bila ayah marah. Pada kakek lain sekali. Orang tua itu hanya dapat tersenyum. Ia jauh lebih baik hati daripada ayah. Ia, katanya selalu, memandang dunia dengan senyuman di bibir dan ketenangan jiwa.
Suatu hari aku ke sana. Hari itu siang. Aku duduk di ruang depan seperti biasa. Ada sebuah jambangan bunga dengan bunga di dalamnya. Bunga-bunga mengapung di atas air bening. Jambangan itu sangat bagus. Seperti dari kaca dengan ukiran. Diletakkan pada sebuah meja rendah dengan empat kaki. Kakek menatap bunga-bunga itu, katanya: “Katakanlah cucu, apakah yang lebih baik daripada ketenangan jiwa?”
“Tidak ada, Kek,” kataku, keluar begitu saja dari kesadaranku. “Tidak ada yang lebih dari itu.”
“Bagus. Tidak kusangka kau akan sepandai ini, cucu.” Ia menepuk pundakku. Kemudian membenarkan letak duduknya dan kembali menatap bunga-bunga itu. “Segalanya mengendap. Cobalah lihat, cucu. Bunga-bunga di atas air ini melambangkan ketenteraman, ketenangan dan keteguhan jiwa. Di luar, matahari membakar. Hilir mudik kendaraan. Orang berjalan ke sana ke mari memburu waktu. Pabrik-pabrik berdentang. Mesin berputar. Di pasar orang bertengkar tentang harga. Tukang copet memainkan tangannya. Pemimpin meneriakkan semboyan kosong. Anak-anak bertengkar memperebutkan layang-layang. Apakah artinya semua itu, cucu? Mereka semua menipu diri sendiri. Hidup ditemukan dalam ketenangan. Bukan dalam hiruk-pikuk dunia. Tataplah bunga-bunga di atas air itu. Hawa dingin menyejuk hatimu. Engkau menemukan dirimu. Engkau akan tahu, siapakah dirimu. Katakanlah, apakah yang lebih baik dari ketenangan jiwa dan keteguhan batin, cucu.”
Aku mendengarkan sebaik-baiknya. Ia mengatur napas lalu berdiri. “Nah, sudah sampai waktunya kita jalan-jalan!”
Kami berjalan, menerobos pohon-pohon bunga. Pada setiap bunga kakek menjentik, tertawa. “Bagus, bagus sekali. Bagus sekali, bukan, cucu?” Aku tersenyum. “Ya, dunia ini indah seperti bunga mekar. Membuat jiwa tenang. Ini dunia kita!”
Siang itu aku pulang dengan bunga-bunga mawar di tangan. Menaiki tangga, meloncati pagar tembok. Sampai di rumah aku mengambil sebuah panci dari dapur itu, memasukkan air sebanyak-banyaknya. Hati-hati kubawa ke kamar. Kutaruh ia di kamarku, dekat pintu. Bunga mawar kutabur di atas air, mengambang. Bayang-bayang melekat di dalam air, di permukaan. Sebagian bunga itu tercelup dalam air, menimbulkan lekuk di permukaannya. Warna merah di atas bening air. Air itu bening dan tenang. Dan bunga-bunga itu! Mataku tak akan terpejam menatapnya. Aku duduk di kursi. Sebuah kesejukan yang menenteramkan lambat-lambat masuk dalam jiwaku. Aku berdamai dengan kehidupan. Apakah yang lebih baik daripada ketenangan jiwa dan keteguhan batin? Sungguh aku bersyukur, berkenalan dengan kakek itu.
Ibu masuk ke kamarku. Panci itu di muka pintu, tidak luput dari pandangannya. “Makanlah!” kata ibu. “Tetapi apakah artinya ini?” Ia memandang pada panci dan bunga itu.
Aku menarik napas panjang. Duduk di atas kursi. Kataku sabar: “Ibu. Katakanlah, apa yang lebih baik daripada ketenangan jiwa dan keteguhan batin?”
Ibu berdiri kaku. Memandangku seperti bukan anaknya. Mataku ditatapnya dalam-dalam. Aku tahu, ibuku terkejut. Kelakuanku bagi ibu adalah sesuatu yang baru, tentu saja; karena ibu datang dari dunia hiruk-pikuk. Ia memandang seperti tidak mengenalku, mengamatiku penuh perhatian. Aku adalah manusia baru. Ibu memanggil namaku. Aku menjawabnya sopan. Ia memanggil lagi. Dan aku menjawab sebaik-baiknya. Kemudian ibu pun pergi. Masih sempat kulihat: Mata ibu merah seperti menangis. Kukira ibu sedang sedih. Kenapa harus sedih? Aku mengikutinya. Ibu duduk dekat tungku dapur dengan muka menunduk. Pasti ia sedih. Untuk apa ibu bersedih? Aku mendekat. Kataku: “Ibu, kenapa sedih? Tersenyumlah! Hidup adalah permainan.” Ibu diam. “Engkau bisa sengsara. Tetapi sadarlah, hidup adalah permainan. Ketahuilah, sesungguhnya…” Aku berhenti bicara. Ibu memutar badannya. Katanya memerintah: “Pergi ke kamar, kataku!”
Aku pun pergi ke kamar, menanti hari sore.
O, ya: Sore hari itu aku pergi mengaji ke masjid. Tidak lupa aku membawa sekuntum melati di saku. Itu menenteramkan jiwa. Setiap kali aku dapat mengeluarkannya dan mencium sepuasku. Pengajian itu bernama Al-Ma’ruf, artinya kebaikan. Mereka belajar menjadi baik. Tetapi sebutlah, siapa di antara mereka mempunyai ketenangan jiwa dan keteguhan batin? Tidak seorang pun, kecuali aku! Sore itu aku duduk di serambi masjid. Siapakah orangnya bisa tersenyum melihat anak-anak memperebutkan kelereng dalam permainan? Aku melihat keasyikan itu, anak-anak yang didorong oleh nafsu. Aku tersenyum dalam ketenangan. Jiwaku dikuasai oleh ketenangan batin yang mengasyikkan. Tidak ada niatku untuk bermain. Lebih baik duduk tenang, tersenyum memandang segala hiruk-pikuk dunia.
Ketika aku pulang mengaji, lantai di kamarku penuh air. Dan bunga-bunga itu! Bunga-bunga itu melengket pada ubin dengan basahan air yang merata. Ternyata panci itu tumpah. Tiba-tiba ayah memegang kudukku. “Untuk apa bunga-bunga ini, buyung?” tanyanya.
Di depan ayahku, aku tidak bisa apa-apa. Tangannya yang kasar, penuh nafsu untuk menghancurkan, memegang pundakku. Aku bungkam. “Ayo!” perintah ayah. “Buang jauh-jauh bunga-bunga itu, heh!”
Aku membungkuk, memungut bunga-bunga. Dari mataku keluar air mata. Aku ingin menangis, bukan karena takut ayah. Tetapi bunga-bunga itu. Aku harus membuangnya jauh-jauh dengan tanganku! Bunga-bunga itu penuh di tanganku.
“Mana.”
Aku mengulurkan pada ayah. Diremasnya bunga-bunga itu. Jantungku tersirap, menahan untuk tenang. “Dan bersihkan air ini sampai kering, buyung!” sambungnya.
Aku baru bebas dari raksasa itu ketika sudah habis mengeringkan lantai. Sesudah membersihkan kamar, aku meloncati pagar. Lalu menangis di pangkuan kakek. Ia mengusap kepalaku. Sahabat tuaku sangat baik kepadaku.
“Cup, cup, diamlah,” katanya. “Harap tidak lagi menangis, kau. Kalau nafsu mengalahkan budi, orang tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Perbuatannya menjadi kasar, karena dorongan nafsu. Perbuatan itu menimbulkan kesengsaraan. Dunia rusak oleh nafsu. Tenanglah.” Aku mulai meredakan tangisku. “Menangis adalah cara yang sesat untuk meredakan kesengsaraan. Kenapa tidak tersenyum saja, cucu? Tersenyumlah. Bahkan sesaat sebelum orang membunuh kita. Ketenangan jiwa dan keteguhan batin mengalahkan penderitaan. Mengalahkan, bahkan kematian pun!”
Aku sadar, menangis ialah kesia-siaan. Aku tersenyum. Kakek menghapus airmata dari kulit-kulit mukaku. Saputanganku semerbak wangi bunga. Aku menghirup sekuatnya wewangi itu. Dan habislah penderitaan.
“Kalau jiwamu tenang, perbuatanmu sopan. Kalau jiwamu gelisah, perbuatanmu kasar,” kakek mencium ubun-ubunku.
Aku segera pulang. Pastilah ayah akan menghukumku bila tahu aku meloncat ke rumah sebelah. Aku kembali ke kamar melewati jendela, lalu menutup pintu rapat-rapat. Ayah tidak akan banyak tahu apa yang kukerjakan. Sampai sore ia di bengkel. Malam hari sehabis makan, ada saja kerjanya. Atau tidur. Hanya ibu di rumah dan ia lebih halus daripada ayah. Tidak usah cemas menghadapi ibu.
Tampaknya ibu sangat senang padaku, karena aku mulai bertingkah halus. Kamarku selalu bersih. Tersedia bunga-bunga. Setidaknya dengan usaha keras agar ayah tidak sempat melihat. Aku sudah punya jambangan bunga sendiri, tidak mengganggu lagi alat rumah tangga ibuku. Tempat tidurku rapi. Masuklah ke kamarku, kapan saja, bau harum bunga! Dan mataku takkan puas-puasnya menikmati warna indah bunga-bunga.
***
Aku baru di dalam kamar, pada suatu siang, ketika ibu dengan tergesa masuk. Ibu berkata dengan gugup: “Keluarlah, cepat, peganglah apa saja. Sapu atau apa. Cepatlah!”
Aku tidak tahu maksud ibuku. Terpaku saja. Dan di depanku telah berdiri ayah, dengan baju kotor dan tubuh berlumur gemuk. Bau anyir memenuhi kamar. Sebuah mobil berhenti di jalan, tepat di muka pintu pagar rumahku.
“Buyung, coba mana tanganmu. Dua-duanya!”
Aku mengulurkan tanganku. Putih bersih. Lambang ketenangan batin dan keteguhan jiwa. Sayang, ayah menangkap tanganku. Kulihat sesaat gemuk mengotori telapak tanganku.
“Tanganmu mesti kotor, seperti tangan bapamu, heh!” Ayah lalu meratakan gemuk di tangannya pada tanganku. Aku tidak melawan. Ayahku adalah nafsu. Aku tersenyum.
Ibu berdiri saja, ia tidak berbuat apa-apa. Aku makin lebar tersenyum. Kulihat ibuku pucat ketika memandangku. Kenapa ibu pucat begitu? Tersenyumlah! Tanganku kotor sampai lengan. Ayah menampar kedua pipiku.
“Untuk apa tangan ini, heh?” katanya sambil mengangkat kedua tanganku dengan kedua tangannya. Aku tidak tahu, jadi diam saja. “Untuk kerja!” sambung ayah. “Engkau laki-laki. Engkau seorang laki-laki. Engkau mesti bekerja. Engkau bukan iblis atau malaikat buyung. Ayo, timba air banyak-banyak. Cuci tanganmu untuk kotor kembali oleh kerja, tahu!”
Kulihat kembali tanganku, kotor. Ayah pergi dengan mobil yang di depan tadi. Ibuku menatapku, sementara aku belum menyadari apa yang terjadi. Katanya: “Turutlah ayahmu, Nak.”
Aku suka kebersihan. Mencuci tangan adalah baik. Aku lari ke sumur. Terbayang: ayahku, kakek, ibuku. Aku membawa sebagian air ke kamar, untuk jambangan bungaku.
Ayahku membawa alat-alat bengkel ke rumah. Di pelataran rumahku dipasang sebuah gubug. Alat-alat itu ditaruh di sana. Ayah mulai pulang pada siang hari. Sehabis makan ia bekerja di bengkel muka rumah, memukul-mukul besi. Seperti dalam bengkel, rumahku jadi gaduh. Kawan-kawan ayah membantunya, dengan pukulan-pukulan besi. Sekali ayah membawa dinamo dan dung-dung-dung mesin itu memenuhi udara. Sesekali ayah memerintah padaku, “Buyuuung, berdiri kau di situ! Lihatlah, mereka yang membangun dunia!”
Aku akan berdiri mengawasi kesibukan. Keringat. Gemuk. Tangan-tangan berotot. Baju kotor. Gemuruh besi. Telingaku bising dan kubayangkan dengan jelas: orang yang gelisah dalam hidupnya.
Pada kesempatan yang tak terlihat oleh ayahku aku akan lari ke kamarku, menutup pintu dan menatap bunga-bungaku. Lupalah aku, di luar orang berkeringat. Kesibukan itu sungguh memuakkan aku. Kalau aku masih terganggu juga di kamar, aku akan meloncat lewat jendela. Menuju ke pagar. Dan kukatakan pada kakek, “Dengar hiruk-pikuk itu, Kakek?”
“Jangan hiraukan, cucuku. Biarlah orang gelisah. Engkau dan aku di sini, dikelilingi bunga-bunga. Dua buah cahaya menyala dalam kepekatan malam.”
Waktu itu siang hari. Barangkali salah menyebut. Kataku, “Tetapi, apakah ini malam hari, Kek?”
“Segala nafsu adalah malam yang gelap, cucu.”
“Ya, sedangkan kita budi. Bukan nafsu. Begitu kan, Kek?”
“Ya. Dan perbuatan kita mencerminkan ketenangan jiwa.”
“Dan keteguhan batin!” aku segera menyahut.
Kami menyusuri kebun bunga. Hiruk-pikuk di rumahku terdengar pula dari sini. Tetapi kata kakek, tidak terdengar oleh telinga batin kami.
Ternyata ayah mengetahui tingkahku. Jambangan bunga pecah, bunga tercecer, air mengalir ke seluruh kamar. Aku tersenyum menyaksikan semuanya. Ayahku sudah berdiri dekat.
“Akulah yang memecahkan, buyung. Untuk apa, heh? Manusia tidak bisa hidup hanya dari bunga. Ke sini!” Aku menurut dengan ketenangan yang mengagumkan sendiri. Ayah memerintah, “Kau harus berdiri di sini. Aku akan membuat sebuah sekrup. Lihat! Dan besok kau harus mengerjakan sendiri. Awas ya, kalau sampai tidak bisa.”
Aku mengawasi. Masuk dalam kepalaku apa yang kulihat. Ayah tahu. Ia menatapku. “Apa yang kaupikirkan, heh?”
Aku harus berani mengatakan sesuatu, bahkan pada ayahku. Jadi kukatakanlah dengan tergagap, “Ayah, sesungguhnya tidak ada yang lebih baik daripada ketenangan jiwa dan…”
“Diam! Untuk apa, heh? Ayo, pegang palu ini!” Ia menyodorkan palu. “Pukul besi ini sampai jadi kepingan tipis. Kerjakan!”
Aku mengalah. Palu kupegang. Dan sesore itu keringatku bercucuran. Tanganku bengkak. Aku terus bekerja, takut pada ayah. Sore hari ayah menyuruhku berhenti. Ibu menyambutku dengan ramah.
“Jangan membantah ayahmu, Nak. Cepatlah mandi. Ah, hampir lupa: Kau harus mengaji.”
Ayah ialah sebangsa laki-laki kasar. Ia mensita seluruh waktuku. Aku mengunjungi kakek pagi saja sebelum sekolah. Dan itu hanyalah sebentar. Ketika itu kakek sedang menyirami bunga. Aku menegurnya: “Sedang apa, Kakek?”
“Menyiram kehidupan, cucu,” ia menoleh padaku. “Engkau banyak pekerjaan sekarang, cucu?” Aku mengangguk.
Terlintas di kepalaku untuk bertanya sesuatu. “Apa kerja Kakek yang sebenarnya?”
Kakek berhenti. Mengawasi aku, lalu katanya, “Sekarang ini? Menyiram bunga, cucu.”
“Ya, tetapi apa sebenarnya pekerjaan Kakek?”
“Pekerjaanku, cucu?” Ia berhenti. “Oya, mencari hidup sempurna.”
“Di mana dicarinya, Kek?”
“Dalam ketenangan jiwa.”
“Ya, tapi di mana?”
“Di sini, dalam bunga-bunga!”
Aku teringat harus ke sekolah. Cepat aku minta diri. Pulang sekolah ayah menyuruhku kerja di bengkel. Ia tidak membiarkan aku berhenti sekejap pun. Ia akan menegur setiap kali melihatku berhenti. “Bekerjalah. Jangan biarkan tanganmu menganggur, buyung.”
Aku jadi teringat pada kakek. “Ayah,” aku bertanya pada ayahku, “kenapa tidak mencari hidup sempurna?”
Ayah berhenti. Menatapku. Ia melihat mataku. “Ya,” katanya, “aku mencari itu, buyung.”
“Di mana dicari, yah?”
“Dalam kerja!”
“Ya, tetapi di mana itu?”
“Di bengkel, tentu.”
Ia berdiri kukuh, dengan wajah membakar. Aku teringat sebuah lokomotip hitam berdiri kuat di atas rel. Menderu dengan gerbong berderet di belakangnya.
“Engkau mesti bekerja. Sungai perlu jembatan. Tanur untuk melunakkan besi perlu didirikan. Terowongan mesti digali. Dam dibangun. Gedung didirikan. Sungai dialirkan. Tanah tandus disuburkan. Mesti. Mesti, buyung! Lihat tanganmu!” Tiba-tiba ayah meraih tanganku. “Untuk apa tangan ini, heh?” Aku berpikir sebentar. “Untuk apa tangan ini, buyung?” tanya ayah mengulang.
Kemudian aku menemukan jawaban. “Kerja!” kataku.
Ayah tertawa tergelak. Mencium tanganku. Ia menampar pipiku keras, mengguncang tubuhku. Kulihat wajah hitam bergemuk itu memancarkan kesegaran. Aku menyaksikan seorang laki-laki perkasa di mukaku. Menciumi aku. Dan ia adalah ayahku sendiri. Malam hari aku pergi tidur dengan kenang-kenangan di kepala: Kakek ketenangan jiwa kebun bunga; ayah kerja bengkel; ibu mengaji masjid! Terasa aku harus memutuskan sesuatu. Sampai jauh malam aku baru akan tertidur.
Bagaimanapun, aku adalah anak ayah dan ibuku.
Ngawonggo, 30-12-1968
[Dinukil dari: Cerita Pendek Indonesia 4, Satyagraha Oerip (editor), (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), 1979, hal. 138-151]
Ulasan Singkat
SEBAGAIMANA tertera pada titimangsa di akhir cerpen, “Dilarang Mencintai Bunga-Bunga” selesai ditulis Kuntowijoyo pada akhir 1968. Cerpen ini kemudian diterbitkan majalah Sastra pada Maret 1969. Majalah ini pula yang menahbiskan cerpen ini sebagai cerpen terbaik pada tahun tersebut.
Cerpen ini memperlihatkan kredo kepengarangan Kunto, yang ia sebut “sastra transendental” atau “sastra profetik” . Tak lama setelah cerpen ini, Kunto menyelesaikan novel Khotbah di Atas Bukit, yang kemudian diterbitkan harian Kompas pada 1971 sebagai cerita bersambung.
Terdapat kemiripan antara “Dilarang Mencintai Bunga-Bunga” dan Khotbah di Atas Bukit. Selain salah satu karakter utamanya adalah seorang tua atau kakek, keduanya juga berbicara tentang perburuan kebahagiaan atau kesempurnaan hidup.
Memang tidaklah keliru jika cerpen ini juga dinilai sebagai kritik atas peran gender. Misalkan, bagaimana buyung dipaksa ayahnya untuk berperilaku sebagaimana persepsi orang tentang laki-laki. “Laki-laki tidak perlu bunga, buyung. Kalau kau perempuan, bolehlah. Tetapi engkau laki-laki!”
Namun, cerpen ini menyimpan tema lain yang tampaknya lebih dominan. Ia alegori dari dua pandangan tentang kebahagiaan, sebagaimana juga yang Kunto ketengahkan dalam Khotbah di Atas Bukit.
Sang ayah mewakili pandangan Max Weber bahwa kerjalah yang mendatangkan kebahagiaan di dunia ini. Kita tahu pandangan Weber inilah yang menggerakkan spirit kapitalisme: kerja, kerja, kerja.
Kunto pun menggambarkan sang ayah bak sebuah mesin (selain gambaran realis tentang perbengkelan): berkeringat, kotor dengan gemuk, bongkahan otot, dan tak pernah lelah bekerja. Ketika bertanya kepada ayah, di mana ayahnya mencari kesempurnaan hidup, buyung mendapat jawaban: dalam kerja. “Engkau mesti bekerja. Sungai perlu jembatan. Tanur untuk melunakkan besi perlu didirikan. Terowongan mesti digali. Dam dibangun.”
Tapi, buyung merasakan kegelisahan dan keterasingan. Ayahnya dingin, kasar, dan tak berbaik hati. “Seperti ada orang lain dalam rumah bilamana ayah ada. Kehadiran ayah menjadikan aku gelisah.”
Buyung menemukan ketenangan di dekat kakek, orang tua sebelah rumahnya. Pandangan kakek tentang kebahagiaan dan kesempurnaan hidup merefleksikan para filsuf stois.
Kebahagiaan ada di dalam jiwa, ketenangan batin. Mereka yang hiruk-pikuk memburu harta hanyalah menipu diri, kata si kakek. Itu semata dorongan nafsu, hasrat, dan ambisi, dan inilah yang justru menjadikan manusia gelisah, kasar, dan menderita.
“Kalau nafsu mengalahkan budi, orang tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Perbuatannya menjadi kasar, karena dorongan nafsu. Perbuatan itu menimbulkan kesengsaraan. Dunia rusak oleh nafsu.”
Bagi Stoisisme, memburu kekayaan adalah kesia-siaan sebab ia berada di luar kendali manusia. Kekayaan justru mendatangkan kegelisahan dan kesulitan karena ia amat rapuh, bisa hilang kapan saja. Makin kaya, seseorang justru makin tak tenang.
Gambaran bunga, yang indah pada dirinya dan menggembirakan orang lain, menyatakan bahwa kebahagiaan itu ada pada diri kita bukan pada hal-hal di luar diri. Apa pun yang kita hadapi di luar selalu akan mendatangkan kebahagiaan jika jiwa kita tenang. Tersenyumlah selalu, kata kakek.
Namun, pada akhirnya, buyung tak kuasa bebas dari kuasa sang ayah (simbol spirit dan etos kapitalisme). Alam bawah-sadarnya bahkan mengatakan: kerja!
Kita memang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi, spirit Weberian yang memuja kesuksesan material sebagai anugerah Tuhan justru membuat kita kian tak bisa menikmati hidup dari hasil kerja kita. Kita dituntut untuk memiliki ini-itu sehingga harus terus bekerja, lebih banyak dan keras.
Sebenarnya tak ada kewajiban kita untuk memenuhi tuntutan itu, yang bukan kebutuhan hidup. Tak ada pula yang memaksa kita. Tapi, tanpa sadar, kita dipaksa oleh standar-standar kehidupan yang dikonstruksi oleh pandangan sosial tertentu.[]

Kuntowijoyo (1943-2005)
LAHIR di Sorobayan, Bantul, Yogyakarta, dan dibesarkan di Ngawonggo, Klaten, Surakarta, Kuntowijoyo adalah pengarang dan akademisi. Dia menamatkan studi di Fakultas Sastra UGM Yogyakarta jurusan sejarah. Di bidang yang sama, dia meraih gelar master dan doktor, masing-masing dari Connecticut University dan Columbia University. Selain mengarang, ia guru besar dan peneliti senior sejarah di UGM.
Sejak di sekolah menengah, Kunto sudah menyukai karya fiksi. Dia melahap karya Hamka, Pramoedya Ananta Toer, Charles Dickens, dan Anton Chekov. Di bangku pendidikan menengah ini pula, Kunto memulai menulis cerpen, drama, esai, dan novel.
Pada 1964, ia menerbitkan novel pertamanya Kereta Api yang Berangkat di Pagi Hari. Pada 1967, majalah sastra Horison menerbitkan cerpen pertamanya. Ketika berkuliah di Amerika Serikat, Kunto baru menulis puisi. Dua kumpulan puisinya, Suluk Awang-Uwung dan Isyarat, terbit pada periode ini.
Pada 1991, Meningo-Ensefalitis (inflamasi pada selaput otak) menyerang Kunto dan menyebabkannya kehilangan sejumlah kendali motorik serta kesulitan berbicara. Tapi, kondisi ini tak menghalanginya untuk tetap berkarya. Pada periode 1995 hingga 1997, cerpen-cerpennya berturut-turut masuk dalam kumpulan cerpen terbaik Kompas, seperti “Lelaki yang Kawin dengan Peri”, Pistol Perdamaian”, dan “Anjing-anjing Menyerbu Kuburan”. Kumpulan puisinya Makrifat Daun, Daun Makrifat juga terbit pada 1995. Pada 2001, Kompas menerbitkan novelnya Mantra Penjinak Ular sebagai cerita bersambung.
Selain mengarang, Kunto aktif di bidang kebudayaan dengan mendirikan Lembaga Kebudayaan Seniman Islam (Leksi) bersama Ikranagara, Arifin C Noer, Dawam Rahardjo, Chaerul Umam, Amri Yahya, Sju’bah Asa, dan Abdul Hadi WM. Dia juga ikut mendirikan Center for Policy Reserach and Study bersama Amien Rais. Kunto juga seorang aktivis Muhammadiyah meskipun tetap kritis terhadap ormas Islam terbesar kedua itu. Dalam satu kesempatan, Kunto mengatakan, Muhammadiyah adalah institusi budaya tanpa budaya.
Di bidang kesusastraan dan ilmu sosial, Kunto pernah mewacanakan gagasan “sastra transendental” dan “ilmu sosial profetik”. Sastra transendental, menurut Kunto, tak hanya memotret realitas tapi juga mencoba mentransformasikannya menuju cita-cita ideal.
Karya-karya fiksi Kunto mengisyaratkan kredo kepengarangannya tersebut. Sebagai contoh adalah novel Khotbah di Atas Bukit (1971) dan cerpen “Dilarang Mencitai Bunga-Bunga” (1969), yang menggondol hadiah pertama majalah Sastra.
Setelah lama mengindap Meningo-Ensefalitis, Kunto akhirnya menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Sardjito, Sleman, Yogyakarta, pada 22 Februari 2005, setelah sehari sebelumnya mengeluh kesulitan bernapas. Dua karya non-fiksi dan satu cerpennya terbit setelah kematiannya.
Selain dari dalam negeri, Kunto menerima sejumlah penghargaan dari luar negeri. Pada 1999, ia menerima SEA Write Award dari kerajaan Thailand. Ia juga mendapat penghargaan dari Majelis Sastra Asia Tenggara (Mastera) pada 2001 atas novelnya Mantra Penjinak Ular.[]