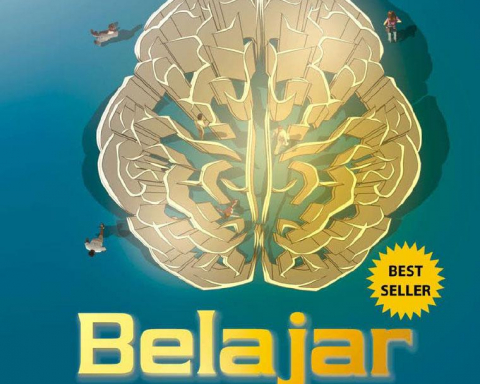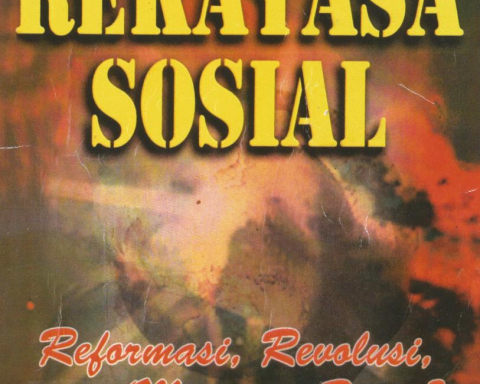Penerbit Mizan menerbitkan ulang Islam Alternatif (1986) dan Islam Aktual (1991) karya Jalaluddin Rakhmat. Masih relevankah substansi dua buku itu dengan masa kini?
Penerbit Mizan menerbitkan ulang dua karya Jalaluddin Rakhmat, cendekiawan Muslim, pendidik, dan politisi yang mangkat pada awal 2021. Dua karya itu, Islam Alternatif (terbit pertama kali pada 1986) dan Islam Aktual (terbit pertama kali pada 1991) bisa dikatakan dua literatur yang ikut mewarnai gairah intelektualisme Islam pada era akhir 1980-an hingga akhir 1990-an. Mungkin tak ada pelajar Muslim pada dekade tersebut yang tak membaca dua karya Kang Jalal ini.
Kita bisa menilai penerbitan ulang itu sebagai penghormatan Mizan kepada kontribusi Kang Jalal bagi pemikiran Islam, khususnya di Indonesia. Tapi, apakah tema-tema yang dibahas dalam antologi artikel koran, ceramah, dan makalah itu masih relevan bagi situasi Muslim Indonesia saat ini? Saya berharap jawabannya adalah “tidak”. Jika “ya”, pemikiran dan keberagamaan Muslim Indonesia justru tidak berkembang, stagnan, karena Kang Jalal mengajukan banyak kritik terhadap fenomena keberagamaan Muslim dalam dua buku itu.
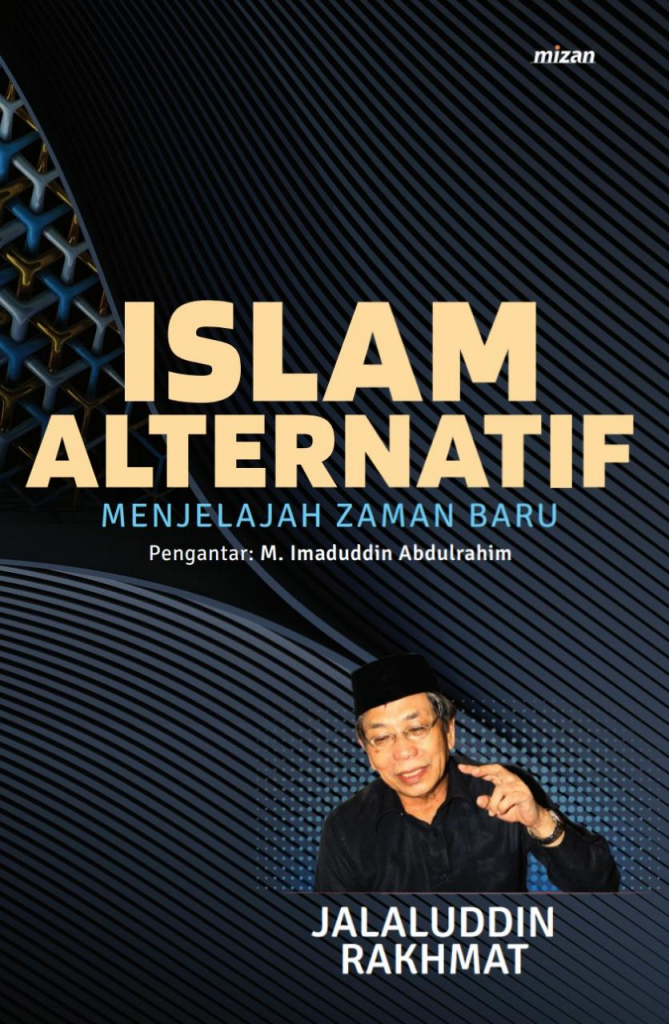
- Judul Buku: Islam Alternatif: Menjelajah Zaman Baru
- Penulis: Jalaluddin Rakhmat
- Penerbit: Mizan
- Terbit: Edisi Kesatu, Cetakan I, November 1986; Cetakan XI, September 2003; Edisi Kedua, Cetakan I, Maret 2021
- Tebal: 301 halaman
Setelah kembali membaca dua karya itu, saya sayangnya mendapati tema-temanya masih relevan. Lontaran-lontaran “nakal” Kang Jalal masih bisa kita lihat dalam corak dan pola keberagamaan Muslim Indonesia saat ini.
Kita masih saja bertikai hanya gara-gara perbedaan pandangan keberagamaan, atau bahkan perbedaan mazhab fikih. Bahkan, berkat ekspansi media sosial, urat saraf kelahi kita makin menegang.
Kang Jalal—sebagaimana pemikirannya yang kemudian dia tuangkan dalam Dahulukan Akhlak di Atas Fikih (2007)—dalam dua buku ini konsisten menyatakan bahwa perbedaan pendapat (bukan hanya soal fikih) adalah fenomena keberagamaan alamiah. Karena perbedaan itu alamiah, upaya menyatukan perbedaan itu bisa dikatakan mustahil dan bahkan akan sia-sia belaka. Karena perbedaan itu alamiah, maka hal yang bisa kita lakukan adalah mendekati satu sama lain: berdialog dan mempelajari pemahaman-pemahaman keberagamaan yang berbeda-beda tersebut. Meminjam kata-kata Kang Jalal, Muslim tidak semestinya terlalu takjub dengan mazhab atau kelompoknya sendiri dan mau membuka diri terhadap mazhab lain.
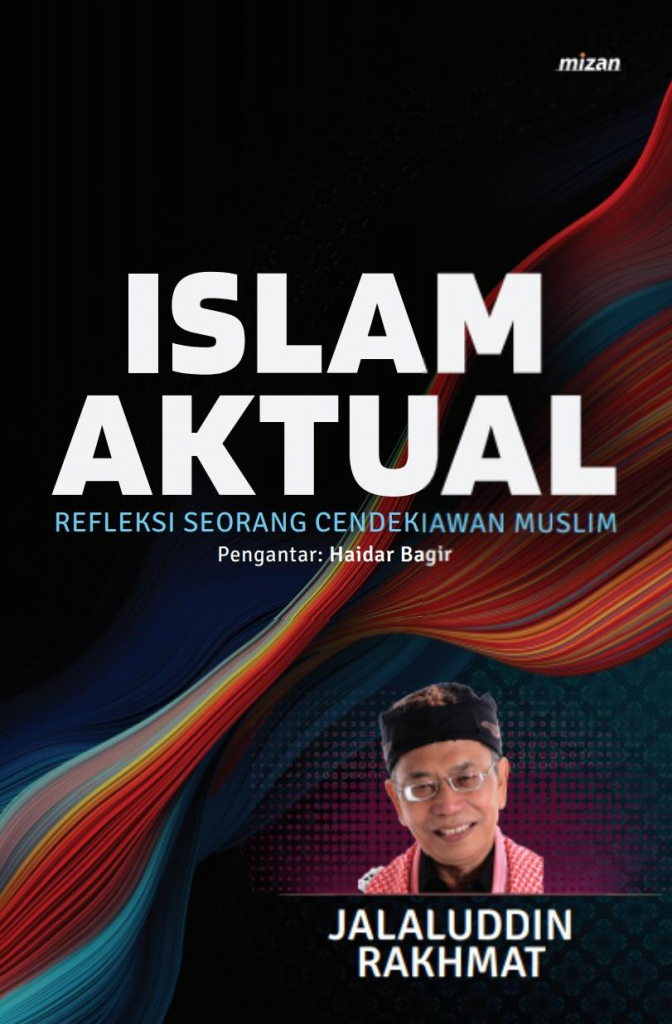
- Judul Buku: Islam Aktual: Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim
- Penulis: Jalaluddin Rakhmat
- Penerbit: Mizan
- Terbit: Edisi Kesatu, Cetakan I, Mei 1991; Cetakan XII, Agustus 2000; Edisi Kedua, Cetakan I, Maret 2021
- Tebal: 347 halaman
Bagi Kang Jalal, perbedaan pemahaman keberagamaan itu alamiah karena ajaran agama turun dalam konteks ruang-waktu. Manusia dengan beragam latar belakang sosio-historisnya masing-masing berupaya menafsirkan nash, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi. Perbedaan periwayatan hadis dan ushul al-fiqh mengarah kepada perbedaan prosedur penarikan kesimpulan. Dan semua itu tak bisa dihindari.
Meskipun demikian, Kang Jalal menekankan bahwa perbedaan tidak niscaya melahirkan perpecahan. Jika perbedaan itu keniscayaan manusiawi, maka perpecahan sebaliknya. Perpecahan bukan sesuatu yang alamiah, dan bahkan bukan takdir.
Dia secara khusus menyoroti hadis yang kerap dikutip untuk menjustifikasi perpecahan di kalangan Muslim: “Orang Yahudi pecah menjadi tujuh puluh satu golongan, orang Nasrani sudah pecah menjadi tujuh puluh dua golongan, dan akan pecah umatku menjadi tujuh puluh tiga golongan. Semua masuk neraka, kecuali satu golongan saja.” Dia mengungkap, dari sisi rantai periwayatannya, hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah nama yang lemah (kredibilitas dan kapabilitasnya). Dari sisi substansi, justru ada hadis lain yang jalur periwayatannya lebih kuat, yakni: “Akan pecah umatku menjadi tujuh puluh tiga golongan. Semua masuk surga kecuali satu.”
Jadi, dengan mempertimbangkan substansi hadis kedua, ‘perpecahan’ (baca: perbedaan pendapat), seberapa pun banyaknya, tetap dapat membawa manusia menuju surga. Hanya pendapat yang jelas-jelas membenarkan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya yang membawa orang ke neraka.
Tema lain yang juga disinggung dalam dua buku ini adalah posisi perempuan dalam Islam. Dalam Islam Aktual, Kang Jalal menyatakan kita hidup dalam “dunia laki-laki”. Persepsi masyarakat di dunia adalah perempuan diciptakan untuk menyenangkan laki-laki dan memberi mereka keturunan. Di zaman jahiliah, di tanah Arab, ada praktik pembunuhan anak perempuan yang disebut wa’dul banat sedangkan di zaman modern disebut abortus provocatus, dan mayoritas korbannya adalah janin perempuan. Sebab, menurut sejumlah studi, orang cenderung lebih memilih anak laki-laki ketimbang anak perempuan.
Di tengah-tengah persepsi patriarkis itu, Nabi Islam justru punya persepsi “ganjil”. Ketika ditanya siapa manusia yang paling layak mendapatkan pengkhidmatan dan penghormatan, Nabi malah menjawab tiga kali, ibu, ibu, dan ibu. Baru setelah itu, bapak disebut. Ini menunjukkan bahwa Islam datang dengan tujuan mengubah persepsi patriarkis yang dominan itu sesuai dengan konteksnya.
Yang menarik dari tema ini juga pembahasan Kang Jalal mengenai hijab, atau cara berpakaian perempuan Muslim. Kita tahu pada dekade 1980-an dan 1990-an, muncul gairah menggunakan hijab atau jilbab. Fenomena ini tak jarang menghadapi penentangan, seperti pelarangan penggunaan hijab di sekolah (bahkan melalui surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan kala itu) atau tempat kerja. Budayawan Emha Ainun Nadjib sempat memunculkan kampanye “Gelombang Lautan Jilbab” melalui puisi dan pementasan teaternya untuk melawan penentangan terhadap penggunaan jilbab.
Dalam Islam Alternatif, Kang Jalal seakan mempertebal gairah itu dengan menyebut busana Muslimah itu “modus ideologis”. Ketika memilih mengenakan hijab, menurut Kang Jalal, seorang perempuan Muslim menstabilkan citra-dirinya. Ia telah memilih perannya secara tegas sebagai perempuan Muslim. Ia telah beralih dari role-confusion ke role-playing. Saat mengenakan hijab, seorang perempuan Muslim secara emosional akan bertindak sesuai norma ajaran agamanya.
Kini, di Abad ke-21, pengenaan jilbab atau hijab memperoleh kebebasan. Kita bahkan saat ini sulit menemukan perempuan tak berjilbab di sekolah-sekolah atau kantor-kantor publik. Tapi, pada saat yang sama, muncul fenomena anyar modus berjilbab yang tampaknya bertentangan dengan “modus ideologis”-nya Kang Jalal dan “modus perlawanan budaya, sosial, dan bahkan politik” dalam Gelombang Lautan Jilbab-nya Emha.
Hijab kini makin terkomodifikasi sebatas produk feysen dan gaya hidup yang terindustrialisasi. Tren “hijaber”, festival hijab, dan peragaan busana Muslimah adalah sebagian dari indikasinya. Perempuan mengenakan hijab bukan lagi berangkat dari kehendak menegaskan citra-diri dan perannya di tengah masyarakat (sebagaimana diungkap Kang Jalal) tapi lebih sebagai mode. Maka, terlihat fenomena berhijab musiman: lepas-pasang hijab bergantung kepada situasi, kondisi, dan momen.
Di sisi lain, fenomena berbeda muncul, yakni modus berhijab untuk mempertegas “identitas-diri” dan mengeksklusifkan diri dari kelompok perempuan lain. Hijab model tertentu dianggap sebagai batas antara keimanan dan kekafiran; antara surga dan neraka. Tren pengafiran atau takfiri (yang makin didorong oleh penggunaan media sosial) juga tak jarang berangkat dari soal berbusana ini.
Dua fenomena tersebut tentu saja tidak dibahas oleh Kang Jalal dalam dua buku ini. Kali ini, tema yang dia bahas terkait hijab justru mendorong kita untuk bercermin kembali ke masa-masa saat hijab menghadapi penentangan. Apakah berhijab hanya sekadar untuk bergaya? Apakah berhijab cukup menjadi penanda kesalehan seseorang? Apakah setelah memperoleh kebebasannya, hijab kini menjadi alat diskriminasi atas kelompok lain?
Dalam dua buku ini, Kang Jalal juga membahas tema kemiskinan. Dia mengatakan, semua orang bersepakat bahwa kemiskinan adalah masalah sosial. Persoalannya, orang berbeda-beda dalam melihat apa penyebab dan bagaimana mengatasi kemiskinan.
Kelompok konservatif memandang kemiskinan tidak bermula dari struktur sosial, melainkan kharakter khas orang-orang miskin itu sendiri. Orang menjadi miskin karena tidak mau bekerja keras, boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa wiraswasta, fatalistik, dan tidak ada hasrat berprestasi.
Kelompok liberal memandang kemiskinan lahir karena kurangnya akses, peluang, dan kesempatan. Bila kondisi sosial-ekonomi diperbaiki, dengan menghilangkan diskriminasi dan memberi peluang yang sama, maka kemiskinan itu bisa segera diatasi.
Kelompok radikal berbeda dengan pandangan kedua kelompok di atas. Orang menjadi miskin bukan karena malas atau bukan hanya karena tidak ada peluang, tapi karena memang dilestarikan untuk miskin oleh struktur sosial dominan. Meskipun akses dibuka dan peluang diberikan, orang miskin tetap tidak akan naik kelas karena garis permulaan (start) mereka tidak sama dengan orang berharta. Yang diperlukan bukan hanya akses atau kesempatan, tapi juga kebijakan afirmasi atau keberpihakan kepada orang miskin.
Ajaran Islam (meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit oleh Kang Jalal) tampaknya melihat kemiskinan seperti kelompok ketiga. Hadis Nabi, “ kalian diberi rezeki dan ditolong oleh orang-orang kecil di antara kalian,” mengimplikasikan bahwa, kapan pun menikmati keleluasaan dan kenikmatan, kita wajib memerhatikan orang miskin karena berkat orang miskinlah, orang kaya bisa memperoleh kekayaannya. Perhatian kepada orang miskin bukanlah bentuk kebaikan tapi kewajiban. Itu utang orang kaya yang wajib dibayarkan kepada orang miskin. Sebaliknya, jika abai kepada orang miskin, kita berarti telah melakukan kezaliman.
Itulah mengapa, ketika berbicara tentang zakat-sedekah, Al-Quran menggunakan kalimat imperatif: Ambillah dari harta-harta mereka…Artinya, dalam konteks kebijakan publik, negara harus menuntut kewajiban itu melalui mekanisme zakat-pajak. Negara tidak bisa berdiam diri dan mengatakan, kami telah memberi peluang yang sama kepada rakyat. Negara harus bergerak menuntut harta orang kaya untuk kemudian mengelolanya dalam bentuk kebijakan-kebijakan publik yang berpihak kepada orang miskin.
Mekanisme “pengambilan” itu juga tidak bisa diserahkan kepada kebaikan atau kedermawanan individual orang kaya. Jika itu yang terjadi, seperti diuraikan Masdar F Masudi dalam Pajak itu Zakat (2010), maka dominasi satu kelompok atas kelompok lain dalam struktur sosial akan tetap lestari. Orang kaya, dengan ‘kebaikan’ dan ‘kedermawanan’ itu, merasa bisa mengendalikan orang miskin.
Masih banyak tema lain yang dibahas oleh Kang Jalal dalam buku ini—dan tidak mungkin dijabarkan seluruhnya dalam ulasan singkat ini. Selain isinya masih relevan, gaya penulisan sederhana plus rujukan kepada sejumlah bahan bacaan lain menjadikan dua buku ini perlu dibaca generasi milenial. Dari dua buku ini, kita juga bisa mencatat pemikiran-pemikiran keislaman dan keindonesiaan Kang Jalal dalam menyoroti fenomena sosial keberagamaan pada dekade 1980-an dan 1990-an—yang sayangnya masih ada hingga kini.[]