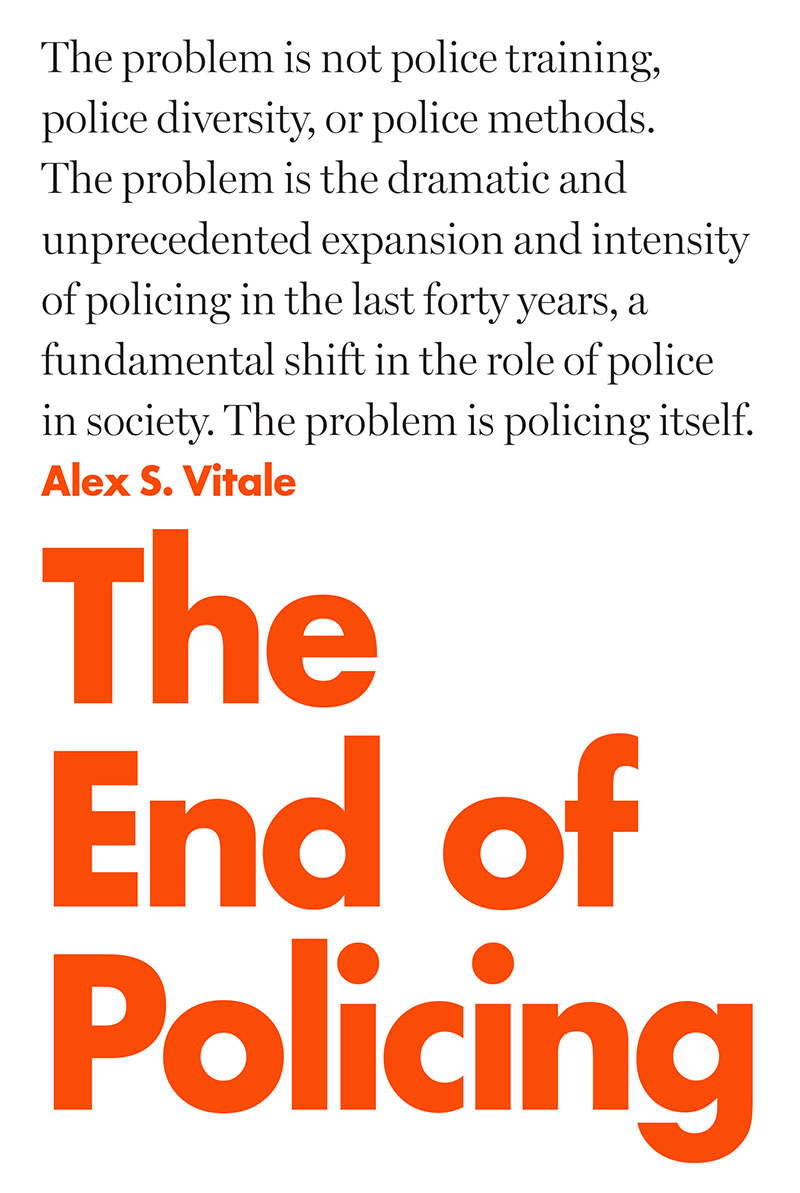Tiap kali warga marginal sekarat di tangan polisi, politisi dan aktivis menyeru reformasi kepolisian. Tapi, sosiolog Alex S Vitale menolak ikut dalam kor tersebut. Dalam The End of Policing, dia menukik ke jantung persoalan: benarkah polisi lahir untuk “melindungi dan melayani” masyarakat?
GEORGE Floyd, pria kulit hitam, meratap tapi ratapannya tak digubris Derek Chauvin. Polisi kulit putih di Minneapolis itu terus menekan tempurung lututnya ke leher Floyd. “Saya tak bisa bernapas, tolong,” kata Floyd terus meratap dengan sebagian mulut menempel pada aspal jalanan. Setelah lebih dari delapan menit, ratapan bekas satpam restoran di klub malam—jadi penganggur gara-gara wabah Covid-19—itu tak terdengar lagi. Tubuh besarnya tak bergerak. Tapi, Chauvin belum juga melepas lututnya meskipun sejumlah orang di sekitar meminta dia mengecek nadi manusia malang di bawahnya.
Kita tahu kisah selanjutnya. Floyd akhirnya meregang nyawa, dan Amerika Serikat membara. Ribuan demonstran turun ke jalan-jalan di Minneapolis sehari selepas nyawa melesat dari tubuh Floyd pada 25 Mei 2020. Satu kantor polisi dibakar. Sejumlah toko dirusak dan dijarah. Protes menyebar hingga ke 400 kota di seantero negeri.
Mereka membawa poster-poster bertuliskan, “I can’t breath”. Lima tahun lewat, Eric Garner, juga pria kulit hitam, meratap sama saat berada di ambang maut akibat cekikan kuat seorang polisi kulit putih, Daniel Pantaleo. “I can’t breath” bak jerit dari liang lahad, bukan hanya Floyd dan Garner, tapi juga sederet nama lain: Tami Rice, John Crawford, Anthony Hill, Antonio Zambrano-Montes, dan Jason Harris. Jangan lupakan juga Michael Brown di Ferguson, Missiouri, yang kematiannya karena ditembak polisi hingga 14 kali memicu tiga gelombang protes sejak 2014 hingga 2015.
Setelah kematian Floyd, kita mendengar seruan-seruan politisi dan aktivis Amerika. Mayoritasnya kembali merapal mantra lama: “reformasi polisi”. Polisi harus dilatih menggunakan kekerasan “proporsional”. Prosedur penangkapan ketat harus dibuat. Metode komunikasi dengan publik harus ditingkatkan. Dan bla… bla… bla… Seruan itu sudah lama kita dengar, dan selalu begitu tiap kali warga miskin sekarat di tangan polisi.
Profesor sosiologi Brooklyn College, Alex S Vitale, menolak ikut dalam paduan suara seruan reformasi polisi. Dalam bukunya, The End of Policing, Alex menukik tajam, dan bertanya apakah masyarakat membutuhkan polisi? Benarkah polisi lahir untuk “melindungi dan melayani” (to protect and to serve) publik, seperti moto banyak kepolisian di berbagai negara?
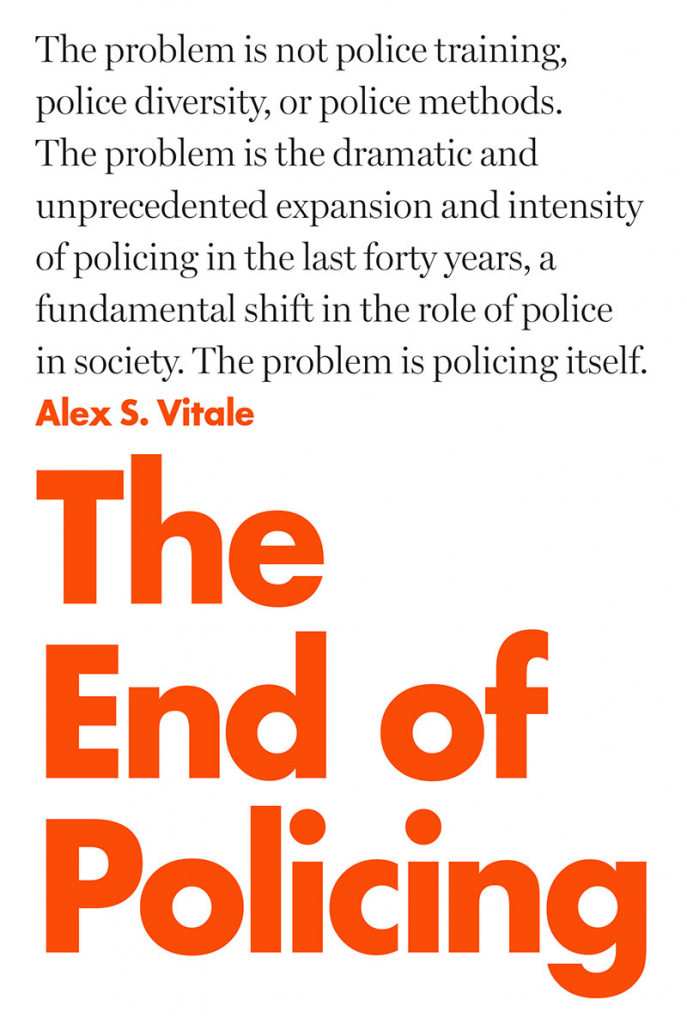
- Judul Buku: The End of Policing
- Penulis: Alex S Vitale
- Penerbit: Verso Books
- Terbit: 2017
- Tebal: 187 halaman (ePub)
The End of Policing menarik karena berangkat bukan dari terminal yang sama dengan kajian lain tentang polisi. Ia menolak latah, selalu mengulang solusi sama. Ia memilih memprovokasi pikiran kita dengan mengajukan pertanyaan radikal tersebut.
Di bagian awal, Alex memperkuat pertanyaan radikal itu dengan menjelaskan mengapa dan bagaimana seruan reformasi polisi pada akhirnya gagal, dan bahkan kerap berujung kepada penambahan anggaran untuk kepolisian. Program reformasi polisi, seperti pelatihan penggunaan kekerasan (di Indonesia ada pelatihan HAM untuk polisi), pembuatan standar prosedur ketat, perekrutan anggota dari latar belakang beragam, pengembangan polisi warga, dan peningkatan akuntabilitas serta transparansi, tak menyentuh problem nilai dan institusional pemolisian. Alex lalu menjelaskan kedua problem itu dari latar sosio-historis kelahiran kebijakan pemolisian dan lembaga bernama kepolisian.
Sebelum menuju pemikiran Alex, kita sebaiknya mengingat bahwa problem pemolisian tak terisolasi di Amerika, negara demokrasi yang katanya sudah mapan itu. Ini terjadi di banyak negara. The End of Policing memang lebih berfokus pada persoalan di Amerika meskipun masih menyinggung problem serupa di negara “anak baru” demokrasi, seperti Nigeria dan India.
Indonesia pun menghadapi masalah polisi dan pemolisian. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat 16 warga meninggal di tangan korps baju coklat sepanjang 2016-2019. Sayang, berita media yang mengutip rilis YLBHI tak melaporkan berapa kasus kematian yang akhirnya diusut tuntas. Belum lagi catatan korban luka-luka akibat penyiksaan polisi saat interogasi. Di Amerika, angkanya memang lebih besar. Alex mencatat 1.080 orang Amerika meninggal akibat kekerasan polisi pada 2016. Sebagian besar korban warga kulit hitam dan warga non-kulit putih miskin. Seperti juga di Amerika, politisi dan aktivis di Indonesia selalu kembali kepada kor klasik: reformasi polisi.
Di bagian kedua, Alex memaparkan argumen tentang problem nilai dan institusional. Pandangan umum cenderung bersimpati kepada keberadaan polisi. Polisi dipandang bagian tak terhindarkan dari struktur sosial masyarakat. Polisi adalah penegak hukum, pengusung pedang keadilan. Citra positif itu membuat kita memandang kekerasan polisi hanya ulah ‘oknum’. “Selalu ada apel busuk dalam sekeranjang apel”, kira-kira begitu kata sebagian orang. Apel busuk inilah yang mesti lebih banyak dilatih, lebih banyak dicekoki modul standar prosedur operasi, dan bahkan ditingkatkan gajinya agar “tak mencari duit di jalanan” (mengutip alasan Menteri Keuangan Sri Mulyani meningkatkan anggaran kepolisian).
Citra positif itu disadari atau tidak terbentuk melalui budaya populer, terutama film. Siapa yang tak bakal jatuh cinta dengan Clint Eastwood dalam Dirty Harry atau Mel Gibson dalam Lethal Weapon? Meski brutal, toh kedua karakter polisi yang mereka perankan tetap memburu dan membasmi penjahat. Ini seperti memahat asumsi dalam pikiran kita bahwa polisi itu memang punya tugas mulia menangkap orang jahat dan melindungi warga. Demi tugas mulia itu, mereka menghadapi risiko besar. Pada gilirannya, saat mereka salah menembak atau membunuh orang meskipun korban hanya menjual sekotak rokok tak berpita cukai (Garner) atau menggunakan sedikit dolar yang diduga palsu (Floyd), kita terkadang masih bisa memaklumi dan bahkan membela polisi.
The End of Policing membongkar asumsi yang lama bersemayam di alam bawah sadar kita. Buku ini menunjukkan bahwa “polisi pelayan dan pelindung” masyarakat itu cuma mitos. Pemolisian mendapatkan suntikan nilai dari teori “jendela-pecah” (broken-window theory) yang pertama kali diformulasi krimolog James Wilson dan George Kelling pada 1982. Teori ini sederhananya begini: jika ada mobil ditinggal di jalanan dengan pintu terkunci dan jendela tertutup, maka tak akan ada orang menjarah dan merusaknya. Sebaliknya, jika jendela mobil itu pecah atau terbuka, dipastikan bakal ada orang yang menjarah atau merusaknya. Teori ini, menurut Alex, menganggap sebagian besar manusia jahat dan punya kecenderungan laten merusak serta tak bisa mematuhi norma sosial. Itulah mengapa teori ini kemudian mendorong penegakan kepatuhan kepada norma sosial melalui kekuatan pemaksa: polisi.
Polisi menjadi satu-satunya institusi sipil yang sah menenteng pistol dan melakukan kekerasan. Yurisprudensi di Amerika bahkan mengamini bahwa polisi bisa menginisiasi kekerasan jika mempersepsi ada bahaya datang mengancam keselamatan jiwanya. Persepsi bisa dipicu oleh apa saja, terutama oleh asumsi dalam teori “jendela-pecah” yang sarat dengan prasangka sosial. Laporan media menyebutkan polisi rekan Chauvin sudah menondongkan pistol kepada Floyd meskipun Floyd belum menunjukkan manuver fisik untuk melawan.
Bagi Alex, teori tersebut menyembunyikan faktor penting pendorong orang melakukan kejahatan: ketimpangan sosial dan kondisi-kondisi buruk yang lahir darinya, seperti pengangguran, ketiadaan tempat tinggal layak, dan layanan kesehatan memadai. Tak hanya menyembunyikannya, teori tersebut bahkan mengalihkan beban masalah sosial itu ke atas pundak korbannya sendiri: masyarakat miskin.
Teori “jendela-pecah” mengonfirmasi latar sosio-historis kelahiran polisi. Literatur yang sering digunakan dalam menjelaskan pembentukan polisi merujuk kepada Sir Robert Peel, seorang baron di Kerajaan Britania Raya. Dalam posisi sebagai Menteri Pertama untuk Irlandia, Peel membentuk Royal Irish Constabulary untuk mengantisipasi dan memadamkan pergolakan sosial di Irlandia pada awal Abad ke-19. Kekuatan ini berperan mempertahankan sistem agrikultul kolonial Inggris di wilayah pedesaan Irlandia selama satu abad, yang mengakibatkan kemiskinan, kelaparan, dan penggusuran meluas di kalangan petani.
Merasa formula tersebut sukses, Peel menerapkannya di Inggris saat menjadi Menteri Dalam Negeri. Pemicunya serupa: protes militan buruh di Manchester pada 1819. Protes ini berujung pada pembantaian lusinan buruh, dan dikenal dalam sejarah dengan “Pembantaian Peterloo”. Revolusi Industri yang menyapu daratan Eropa memicu ketimpangan sosial. Gerakan-gerakan kelas pekerja pun tumbuh bak cendawan di musim hujan. Penguasa, elite, dan para baron tak bisa lagi mengandalkan militer karena risikonya telalu besar: kerap memicu lebih banyak pemberontakan. Paramiliter partikelir dan preman juga tak cukup banyak jumlahnya untuk menghadapi protes, dan bakal menguras terlalu banyak pundi-pundi mereka. Dalam konteks inilah, Peel membentuk London Metropolitan Police, yang kemudian menjadi cikal bakal dan model pembentukan polisi di banyak kota di Inggris, dan lalu diekspor ke banyak negara.
Di Amerika, sejarah polisi berakar lebih dalam lagi pada perbudakan dan kolonialisme. Anda tentu mengenal Texas Rangers, polisi khas Negara Bagian Texas. Institusi ini terkenal terutama karena peran sebuah film yang dibintangi Chuck Norris. Tapi, tak banyak orang tahu Texas Rangers memiliki sejarah berdarah-darah di Amerika.
Texas Rangers dibentuk oleh pendatang kulit putih di Texas, utamanya untuk memburu warga pribumi Meksiko dan Indian yang menyerang tanah dan mencuri ternak. Lambat laun kekuatan ini masuk ke dalam sistem pemerintahan, pertama-tama di bawah pemerintahan Meksiko, lalu Republik Independen Texas, dan akhirnya Negara Bagian Texas. Di masa integrasi Texas ke dalam federasi, Texas Rangers berperan menyingkirkan kelompok separatis Meksiko yang bangkit karena sudah lelah tanah mereka terus dijarah orang kulit putih. Pada era 1960 dan 1970-an, Texas Rangers digunakan penguasa untuk memberangus gerakan petani Meksiko-Amerika yang menuntut hak ekonomi dan sosial mereka. Para rangers ini biasanya mendatangi rapat-parat dan kemudian membubarkannya dengan kekerasan, mengintimidasi para pendukung gerakan, dan memenjarakan pemimpinnya.
Abad ke-20 menyaksikan modernisasi polisi di tangan orang bernama August Vollmer. Dia eks serdadu perang Filipino-Amerika; lagi-lagi hasil didikan kolonialisme. Vollmer berperan besar dalam memberangus perlawanan pendukung Republik Filipina atas kolonisasi Amerika. Kembali ke tanah airnya, Vollmer menjadi kepala polisi di Berkeley, California. Dia menerapkan kisah sukses di negeri jajahan; memperlengkapi polisi dengan berbagai persenjataan dan taktik khas militer, sejumlah teknologi semacam radio patroli, pembacaan sidik jari, dan banyak teknik lain yang kini menjadi standar kepolisian modern. Karena ini, ia kemudian dikenal sebagai “Bapak Polisi Modern”.
Dengan mengungkap latar sosio-historis ini, Alex ingin mengatakan bahwa polisi sejak dalam buaian tidak dilahirkan sebagai kekuatan netral yang “melindungi dan melayani” publik. Ia lahir dari kekuatan sosial yang mengendalikan tiga lapis penindasan di Abad ke-19: perbudakan, kolonialisme, kelas pekerja di era Revolusi Industri. Meminjam kata-kata Mark Neocleos dalam The Fabrication of Social Order: A Critical Theory of Police Power, Alex menyimpulkan, “Polisi ada untuk memfabrikasi ‘tatanan sosial’, tapi ‘tatanan’ ini bertumpu pada sistem penghisapan—dan ketika penguasa elite merasa sistem ini dalam bahaya, entah karena kebangkitan para budak, pemogokan, atau kejahatan serta kerusuhan di jalanan, maka mereka akan bersandar kepada polisi untuk mengendalikan semua itu.” Alex seolah ingin mengatakan, saat mendengar moto “melindungi dan melayani”, kita seharusnya bertanya, siapa yang akan mereka lindungi dan layani?
Dalam perkembangannya sejak era pascaperang, polisi tak pernah bisa melepaskan diri dari latar sosio-historis kelahirannya. Kejahatan besar, serius, dan luar biasa tak pernah benar-benar menjadi perhatian utama mereka. Alex mengatakan, bagaimana tak seorang pun bankir yang terlibat skema kecurangan finansial dalam krisis 2008 dipenjara. Padahal, krisis tersebut menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, tabungan, dan rumah. Mengutip tiga riset yang dilakukan Jonanthan Simon (Governing Through Crime), Michelle Alexander (The New Jim Crow), dan Jeffrey Reiman (Rich Get Richer and the Poor Get Prison), Alex menyatakan, apa yang dianggap kejahatan dan menjadi fokus kendali dibentuk oleh kecemasan kelas berpunya terhadap potensi pergolakan sosial-politik dan apa yang mereka persepsi sebagai “tatanan” dan “ketertiban”. Kejahatan kelas tak berpunya—sekalipun itu minor—akan dihadapi dengan pemolisian agresif. Sebab, seperti asumsi dalam teori “jendela-pecah”, kelas masyarakat ini memiliki kecenderungan laten destruktif.
Melalui riset pustaka dan sejumlah wawancara, Alex menunjukkan sebagian besar waktu dan sumber daya polisi dihabiskan untuk mengurusi “kejahatan kecil” yang dilakukan warga miskin dan marginal. Kejahatan minor ini biasanya adalah problem sosial, seperti ketunawismaan, kesehatan mental, penyalahgunaan narkotika, pelacuran (dengan target utama kaum perempuan), dan konflik antargeng. Semuanya ditangani polisi dengan pemolisian agresif, seakan bisa selesai dengan metode pemolisian berujung pemenjaraan. Kalaupun ada pelaku yang datang dari kelas berpunya, penanganannya cenderung lebih persuasif. Jika terjadi proses pemidanaan, hukumannya akan sangat ringan dan dalam prosesnya narapidana kaya ini bakal menerima pengurangan hukuman hingga bisa lebih cepat keluar dari terungku, secepat Appel merilis seri terbaru iPhone.
Seiring kian banyak legislasi yang memidanakan perbuatan, kian luas pula peran polisi dalam masyarakat. Saat ini, polisi mengurusi nyaris segala aspek kehidupan, dari mulai apa yang kita makan atau minum, siapa yang kita tiduri, hingga apa yang kita tulis di media sosial. Setiap persoalan sosial seperti menuntut keterlibatan polisi. Apa yang disebut community policing justru meminta warga melaporkan apa pun yang terjadi kepada polisi. Bagi Alex, ini justru menunjukkan kegagalan masyarakat membangun kekuatan sosialnya sendiri. Di Indonesia, kita melihat bagaimana banyak orang sekarang sedikit-sedikit melapor ke polisi meskipun sekadar gusar oleh cuitan di Twitter. Kita kehilangan kemampuan berbicara dan berkomunikasi dengan satu sama lain, sehingga membutuhkan kekuatan pemaksa seperti polisi yang berperangkat pistol, pentungan, dan borgol. Ini bukan kemajuan tapi kebangkrutan sosial manusia modern.
Bahkan, seandainya pun kita percaya sekolompok polisi memiliki niat baik, reformasi polisi tak akan menyelesaikan problem ini tanpa menyentuh akar ketimpangan sosial. Bagaimanapun, dalam kondisi timpang, orang-orang miskin dan marginal selalu berada dalam situasi yang memaksa mereka lebih dekat dengan urusan pemolisian. Dan polisi selalu berada dalam posisi sikap yang siap mempertahankan apa yang dipersepsi kelas elite sebagai “tatanan” dan ketertiban”. “Law and order”, begitu kata mereka.
Ini jelas terlihat pada kegagalan program reformasi peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Alex menunjukkan data bahwa angka polisi yang didakwa dan kemudian divonis bersalah atas kekerasan sangat kecil. Secara prosedural, proses pembuktian kasus seperti ini bak menegakkan benang basah meskipun polisi di Amerika sudah dilengkapi dengan kamera pada dashboard mobil patroli dan tubuh mereka. Saksi yang bisa menjerat polisi hanya datang dari rekan mereka sendiri, atau dalam kasus yang amat jarang dari kamera-kamera tersebut. Jaksa penuntut juga pada umumnya tak bergairah mengusut dan menuntaskan kasus melibatkan polisi karena, dalam sistem pidana, polisi adalah sejawat mereka.
Di bagian akhir, Alex sampai pada kesimpulan bahwa reformasi sejati bagi kepolisian adalah berinvestasi kepada upaya mengatasi ketimpangan sosial. Alex mengusulkan pengurangan signifikan anggaran kepolisian yang tiap tahun meningkat di Amerika (juga di Indonesia). Anggaran itu kemudian dialihkan kepada program-program sosial seperti perumahan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, rehabilitasi pecandu narkotika, dan program lain yang pada intinya memberi warga marginal akses kepada pengambilan kebijakan publik demi memperbaiki lingkungan kehidupan mereka.
Buku ini menyajikan kajian cukup komprehensif tentang pemolisian dan masalahnya, dari mulai kekerasan, pemolisian dan pemenjaraan berlebih. Dengan data dari berbagai riset, Alex juga mengajukan pemikiran alternatif, dan terkadang radikal. Tapi dari semua itu, Alex secara provokatif menggugah pikiran kita untuk bertanya, apa sebenarnya kebutuhan kita akan pemolisian? Apa sebenarnya tugas penting polisi, sehingga lembaga ini benar-benar dibutuhkan? Meski buku ini berfokus pada kasus-kasus di Amerika, penjelasan di dalamnya mencerminkan banyak hal yang juga terjadi di Indonesia.[]