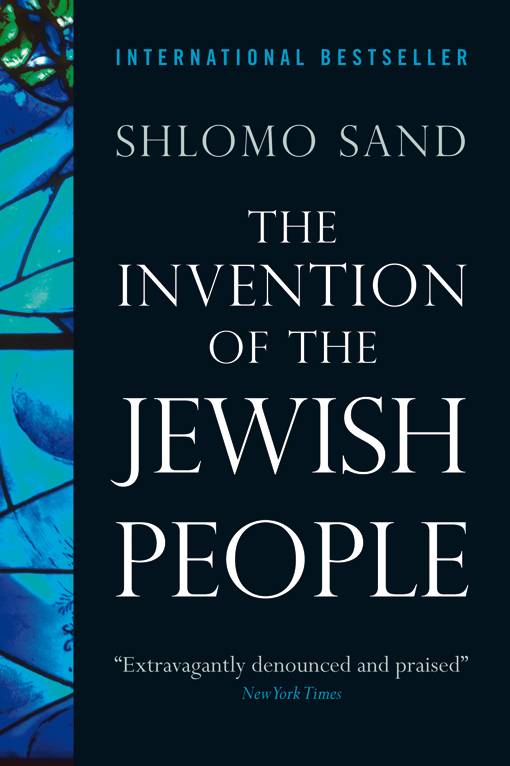Dengan menelusuri catatan sejarawan awal Yahudi, Shlomo Sand berkesimpulan bahwa penduduk asli Palestina adalah keturunan bangsa Yahudi Kuno. Sebaliknya, imigran Yahudi tak pernah memiliki afinitas historis dengan Tanah Yang Dijanjikan.
KETIKA Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendeklarasikan bahwa Yerusalem ibukota Israel secara sepihak pada 6 Desember 2017, muncul argumen yang membela deklarasi itu dengan dasar teks suci (sejarah biblikal). Argumen itu menyatakan Yerusalem adalah hak waris bangsa Yahudi karena kota suci itu dibangun Raja Daud 4.000 tahun lalu. Dalih lain menyatakan hak kembali “diaspora” Yahudi ke Yerusalem adalah ide Tuhan dalam Alkitab, dan ide itu mewujud sejak pendirian negara Israel pada 1948.
Narasi biblikal Israel dan pendukungnya tersebut tampak tak lekang oleh waktu, bahkan ketika argumen rasional-sekuler di zaman kiwari lebih banyak digunakan dalam mempertahankan klaim kebenaran. Ada dua kemungkinan mengapa narasi teks suci terus dipertahankan untuk menjustifikasi keberadaan Israel di Tanah Historis Palestina. Pertama, teks suci adalah masalah keyakinan yang klaim kebenarannya seakan tak perlu diuji lagi. Kedua, mungkin saja argumen biblikal tinggal satu-satunya yang tersisa bagi Israel dan kalangan Zionis.
The Invention of the Jewish People karya Shlomo Sand adalah satu di antara sejumlah buku yang berupaya membongkar argumen biblikal Zionisme. Dalam buku ini, Sand fokus membahas autentisitas “pembuangan” dan “dispora”, dua narasi biblikal yang tampak menjadi sihir ampuh bagi Zionisme dan pendukungnya.

- Judul Buku: The Invention of the Jewish People
- Penulis: Shlomo Sand
- Penerbit: Verso
- Tahun Terbit: 2009
- Tebal: 343 halaman
Sand kini profesor sejarah di Universitas Haifa, Israel. Dia aliyah (imigran Eropa Timur) dan pernah menjadi serdadu Israel dalam Perang Enam Hari 1967 — perang yang berhasil menganeksasi Yerusalem. Lepas dari dinas kemiliteran, Sand justru bersahabat dengan Mahmoud Darwish (1941-2008), penyair Palestina yang kerap membuat marah pejabat Israel dengan puisi-puisinya. Bahkan, Darwish sempat menulis puisi untuk Sand berjudul “A Soldier Dreams of White Lilies”.
Sebagai sejarawan, Sand digolongkan orang ke dalam “New Historian”, barisan sejarawan yang melawan arus utama historiografi Israel. The Invention sendiri laris manis sekaligus mendatangkan kecaman hingga acaman bagi Sand.
Dari judulnya, The Invention seakan ingin menyatakan bahwa Yahudi adalah “bangsa jadi-jadian”. Persisnya bukan itu yang dimaksud Sand. Dengan mengeksplorasi konsep kebangsaan modern — terutama yang dilahirkan oleh Ben Anderson dalam Imagined Communities (1983) — Sand sejatinya ingin menyatakan bahwa semua bangsa di dunia pada dasarnya lahir dari proses simultan imajinasi, penemuan, dan penciptaan-diri (self-creation).
Dengan demikian, kelahiran suatu bangsa adalah proses yang teramat sekuler, atau bukan ide Tuhan. Karena itu, bagi Sand, afinitas keagamaan (seperti diimplikasikan dalam dogma “Bangsa Pilihan Tuhan” atau “Tanah yang Dijanjikan”) tak bisa diterjemahkan ke dalam klaim hak kesejarahan dan kepemilikan teritorial. Batas-batas inilah yang menurut Sand kabur di tengah masyarakat Israel dan memang sengaja dibuat kabur.
Dengan konsep tersebut, Sand membedah dua narasi biblikal tentang “pembuangan” dan “diaspora”. Dalam The Invention, Sand menunjukkan bahwa, alih-alih mendukung, kedua narasi itu malah merontokkan klaim eksklusif Zionisme atas Tanah Historis Palestina, baik secara historis maupun sosiologis.
Zionisme berpandangan bahwa setiap Yahudi saat ini adalah keturunan langsung dan eksklusif dari Yahudi kuno yang menerima Taurat di Gunung Sinai 4.000 tahun silam. Mereka beremigrasi dari Mesir ke Tanah yang Dijanjikan (baca: Palestina) dan kemudian dua kali terbuang, pada Abad ke-6 Sebelum Masehi dan 70 Masehi.
Selama 2.000 tahun, bangsa Yahudi mengembara di negeri-negeri asing: Yaman, Maroko, Spanyol, Jerman, Polandia, dan Rusia. Riwayat pun bercerita bahwa betapa pun jauhnya mengembara, mereka tetap bisa saling menjaga kemurnian darah.
Mereka pun tetap merawat rindu kepada “Tanah yang Dijanjikan” bukan sekadar sebagai tanah suci (holy land) tapi juga tanah air (homeland). Palestina — Tanah yang Dijanjikan itu — adalah negeri perawan; negeri tanpa bangsa untuk bangsa tanpa negeri. Negeri itu juga terus menanti penduduk aslinya selama 2.000 tahun. Maka, perang yang digelar kaum pengembara untuk mendapatkan hak lahir mereka atas negeri itu adalah keadilan sementara perlawanan penduduk lokal adalah kejahatan (terorisme).
Dalam The Invention, Sand berpendapat bahwa interpretasi di atas adalah hal baru, berkembang pada akhir Abad ke-19 dan awal Abad ke-20. Tafsiran tersebut diterima begitu saja tanpa reserve di kalangan akademisi Israel. Tak pernah ada yang mempertanyakan konsep-konsep dasarnya. Setiap kali ada penemuan yang menyimpang dari tafsir dominan tersebut akan ditolak atau setidaknya dipinggirkan.
Pemisahan antara fakultas sejarah umum dengan fakultas sejarah Yahudi-Israel dalam institusi akademik Israel merupakan contoh dari sikap defensif tersebut. Kemunculan kelompok sejarawan “New Historian” pada akhir 1980-an — termasuk di antaranya Sand — hanya memicu perdebatan terbatas, dan itu pun bukan di kalangan sejarawan arus utama tapi di lingkaran non-sejarawan, seperti sosiolog, orientalis, linguis, ilmuwan politik, sastrawan, dan arkeolog.
Sand bahkan mengakui bahwa dia harus menunggu hingga gelar profesornya diberikan sebelum memutuskan untuk menerbitkan The Invention. Dia mengatakan, selalu akan ada harga yang harus dibayar oleh akademisi Israel yang menentang arus dominan historiografi Israel.
Menurut Sand, “Pembuangan” dan “diaspora” adalah kata kunci dalam konsepsi Zionisme. Tanpa pembuangan, tak akan ada kaum diaspora Yahudi yang mengembara selama 2.000 tahun. Tanpa diaspora, maka tak akan ada aspirasi “pulang” ke bukit Zion.
Dalam penelusurannya, Sand mengandalkan catatan sejarawan awal Yahudi untuk membedah “pembuangan” dan “diaspora”. Bahkan, Sand berani menyatakan bahwa Alkitab Ibrani baru dipandang sebagai “teks historis” pada paruh kedua Abad ke-19. Sebelum itu, Yahudi memandang Alkitab Ibrani (atau Tanakh1Tanakh adalah teks suci kanonik Yahudi yang juga merupakan sumber tekstual bagi Perjanjian Lama dalam Kristianitas.) sebagai semata “karya teologis” yang memberi inspirasi spiritual.
Sand juga menunjukkan, saat Theodore Herzl menggelar konferensi Zionis pertama di Basel, Swiss pada akhir Abad ke-19, hanya sebagian kecil rabbi yang datang. Sementara, mayoritas rabbi — baik dari kelompok orotodoks, konservatif, ataupun progresif — menentang rencana Herzl. Itulah mengapa konferensi diselenggarakan di Basel, bukan Munich, Jerman, seperti yang direncanakan sebelumnya. Padahal, ketimbang Basel, Munich merupakan kota di Eropa dengan populasi Yahudi terbanyak saat itu.
Dengan demikian, sebelum paruh kedua Abad ke-19, tafsir Zionisme terhadap narasi Alkitab adalah asing bagi umat Yahudi. Keyakinan Haredi Yudaisme (Ordotoks) — yang menjadi basis bagi gerakan Yahudi anti-Zionis — justru menyatakan bahwa “Eretz Israel” atau “Tanah yang Dijanjikan” itu ada di dalam hati setiap pengiman Yudaisme bukan pada peta geografis. Konsep “Eretz Israel” pada gilirannya adalah konsep teologis bukan politik. Seperti dikatakan Sand, “Eretz Israel” adalah “tanah suci” (holy land) bukan “tanah air” (homeland).
Salah satu gugatan utama Sand dalam The Invention adalah upayanya menelusuri jejak sejarah “pembuangan kedua” Yahudi dari Palestina pada 70 Masehi. Eksodus kedua itu diyakini terjadi menyusul pemberontakan penduduk Yahudi yang digerakkan kelompok Zealot terhadap kekuasaan Romawi. Pemberontak yang sempat menguasai Yerusalem sejak 66 Masehi akhirnya dihancurkan oleh tentara Romawi di bawah pimpinan kaisar masa depan Titus. Kemenangan Titus dipercaya diikuti dengan penghancuran Kuil Kedua dan pembuangan bangsa Yahudi.
Flavius Josephus yang lahir di Yerusalem dengan nama Yosef ben Matityahu adalah sejarawan Yahudi pada Abad Pertama Masehi di Judea, kota Yahudi yang ketika itu dikuasai Kekaisaran Romawai. Pada 66 Masehi, ketika pemberontakan meletus, Yosef adalah salah satu pemimpin Zealot. Namun setahun kemudian, dia berpindah kubu, menjadi orang kepercayaan Kaisar Vespasian (ayah Titus). Pada 69 Masehi, Yosef pun mengambil nama keluarga Sang Kaisar: Flavius.
Pada 70 Masehi, ketika pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus mengepung Yerusalem selama kurang lebih tujuh bulan, Josephus bekerja untuk Titus sebagai penerjemah. Dengan peran inilah, dia merekam sejarah pengepungan Yerusalem dalam bukunya Wars of the Jews2Bagian awal karya Flavius Josephus, Wars of the Jews, banyak diwarnai riwayat biblikal. Meskipun demikian, karya itu kerap menjadi rujukan bagi sejarawan Yahudi berikutnya.. Dalam catatannya itu, Josephus menggambarkan penderitaan yang dialami penduduk Judea menyusul pengepungan Titus, dari penahanan 97.000 orang hingga pembantaian 1,1 juta orang.
Menurut penelusuran Sand, catatan Josephus adalah satu-satunya sumber sejarah dari tragedi yang setiap tahun diperingati orang Yahudi dengan berpuasa Tisha B’Av itu. Meskipun memerinci akibat tragis dari pemberontakan Zealot, Wars of the Jews tak sepatah kata pun menyebut “pembuangan” penduduk Judea secara masif. Bahkan, Sand juga menemukan bahwa tak ada satu pun sejarawan Romawi yang menyebut “pembuangan” dari Judea. Juga tak ada jejak arkeologis yang bisa ditemukan terkait dengan populasi pengungsi dalam jumlah besar di sekitar Judea di penghujung pemberontakan Zealot.
Survei arkeologis yang dilakukan arkeolog Israel justru menunjukkan bahwa Josephus terlampau membesar-besarkan angka demografi dalam bukunya. Sand pun menyatakan bahwa lebih aman untuk berasumsi bahwa penduduk Judea ketika itu tak lebih daripada setengah juta jiwa. Apalagi, dalam buku Josephus, dampak pengepungan Titus diriwayatkan tak sampai memengaruhi seantero Judea, hanya Yerusalem dan beberapa kota di sekitarnya.
Setelah Josephus, sejarawan Yahudi lain yang ditelusuri Sand juga tak benar-benar meyakini “pembuangan” masif telah terjadi setelah pengepungan Yerusalem. Heirich Graetz3Heirich Graetz, Yahudi Polandia, termasuk sejarawan pertama yang menulis sejarah Yahudi secara komprehensif. Magnum Opus-nya History of the Jews memantik ketertarikan dunia kepada sejarah Yahudi. (1817-1891) dan Simon Dubnow4Simon Dubnow, Yahudi Belarusia, banyak menulis tentang sejarah Yahudi, terutama yang berkaitan dengan komunitas Yahudi di Eropa timur. (1860-1941) cenderung lebih berasumsi bahwa penghacuran Kuil Kedua “semestinya” memicu “pembuangan”. Tapi, keduanya secara eksplisit mengindikasikan, alih-alih terjadi secara massal, “pembuangan” hanya dialami sebagian penduduk Judea, terutama kelompok elite pemberontak Zealot.
Bahkan, sejarawan generasi berikutnya, Yitzhak Baer5Yitzhak Baer, Yahudi Jerman, yang pada 1930 bermigrasi ke Palestina dan menjadi profesor sejarah Yahudi di University of Hebrew di Yerusalem. (1888-1980) memunculkan apa yang disebut “kejutan kronologis”. Baer menunjukkan, meskipun terjadi pengepungan Yerusalem dan penghancuran Kuil Kedua oleh Titus, komunitas Yahudi tetap hidup dan berkembang di Palestina.
Berdasarkan penelusuran sumber-sumber awal tersebut, Sand menyimpulkan bahwa rezim Romawi tak pernah membuang seluruh penduduk Judea seperti yang selama ini diyakini. Sebab, tak ada keuntungan bagi penguasa Romawi untuk mengusir penduduk Yahudi (para pekebun, petani, pekerja, dan pembayar upeti). Penguasa Romawi bisa sangat kejam terhadap kelompok pemberontak: menahan mereka, menghukum mati, menjadikan mereka budak belian, dan mungkin mengusir mereka keluar. Tapi, jelas penguasa Romawi tak mengusir seluruh penduduk dan juga tak memiliki sarana untuk melakukan itu, seperti truk, kereta api, atau kapal yang tersedia di zaman modern.
Jika demikian, muncul pertanyaan. Bagaimanakah perkembangan komunitas Yahudi di Palestina setelah peristiwa pengepungan Yerusalem? Lalu, siapakah Yahudi yang tersebar di Mediterania — di selatan Eropa, di utara Afrika, dan di barat Asia?
Sand mengulas dua pertanyaan tersebut dalam salah satu bagian terpanjang dalam bukunya. Tapi, di sini hanya akan dipaparkan dua argumentasinya tentang “Fellahin” dan “Khazar”.
Sand memulai ulasannya dengan mengutip sabda Daniel — seorang nabi Yahudi yang diriwayatkan terbuang ke Babel dalam “Penangkapan Babilonia” pada Abad Ke-6 Sebelum Masehi6Makam Daniel diyakini berada di Susa, Iran.. Dalam Kitab Daniel — bagian dari Perjanjian Lama yang diakui, baik oleh Yahudi maupun Kristianitas — Daniel bernubuat, “…dia akan kembali dan menunjukkan perhatian kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus.”7Daniel 11:30
Menurut Sand, kutipan salah satu nubuat Daniel itu — terutama pada frasa mereka yang meninggalkan perjanjian kudus — ditafsirkan kalangan rabbi sebagai “pengikut Ismail di Yerusalem” dan “Yahudi yang meninggalkan ajarannya”. Penafsiran itu memikat Abraham Polak8Abraham Polak, Yahudi Ukraina, salah satu sejarawan ternama Israel modern. Tak hanya mengusai literatur Yahudi, Polak juga mendalami literatur Arab dan Islam. (1910-1970), sejarawan Yahudi yang pertama kali mendirikan departemen sejarah Timur Tengah di Tel Aviv University.
Pada 1967, dalam bukunya The Origin of The Arabs of The Country, Polak — yang seorang Zionis tulen — memandang bahwa penduduk asli Palestina akan menjadi problem akut bagi negara Israel di masa depan. Pada saat tak ada seorang Zionis pun yang berani berbicara tentang nubuat Daniel di atas, Polak justru menjadikan nubuat itu dasar dari hipotesisnya tentang asal-usul penduduk asli Palestina.
Dia berpendapat bahwa populasi asli Palestina adalah umat Yahudi yang dalam ribuan tahun telah mengubah keyakinan dari Yudaisme ke Islam — “pengikut Ismail di Yerusalem”. Polak menyadari bahwa dalam ribuan tahun populasi di Palestina, yang merupakan wilayah di persimpangan antara Sungai Yordania dan Laut Tengah, hampir pasti berbaur dengan populasi negeri jiran dan penguasa yang datang dan pergi. Yunani, Persia, Arab, Mesir, dan kaum Salib tercatat pernah datang ke Palestina dan berbaur dengan penduduk asli.
Polak sebenarnya bukan yang pertama mengajukan teori “Islamisasi massal penduduk Judea”9Perlu dicatat bahwa, selain berpindah keyakinan dengan menganut Islam, sebagian penduduk lokal Palestina juga memeluk Kristianitas.. Israel Belkind (1861-1929), sejarawan Zionis dan aliyah pertama yang bermigrasi dari Belarusia, dalam buku The Arabs in Eretz Israel (1928), juga menulis tentang hubungan historis yang dekat antara penduduk asli Palestina di masa kuno dengan penduduk lokal pada masanya.
“Sejarawan terbiasa mengatakan bahwa setelah penghancuran Yerusalem oleh Titus, Yahudi berserakan di seluruh dunia dan tak lagi menempati negeri mereka,” tulis Belkind. “Tapi ini juga merupakan kesalahan historis, yang harus dibuang dan fakta yang sebenarnya mesti ditemukan.”
Sayangnya, menurut Sand, teori Polak dan Belkind yang merupakan studi ilmiah yang valid diabaikan sejarawan arus utama Israel. Bahkan, departemen sejarah Timur Tengah yang didirikan Polak tak pernah berani meneruskan warisan pendirinya itu. Tak pernah ada riset yang dilakukan untuk mengulas isu ilmiah tersebut.
Teori Polak dan Belkind — diistilahkan Sand dengan “Fellahin” (petani) — menunjukkan keberlanjutan kehidupan penduduk asli Palestina sejak era kekuasaan Romawi hingga saat ini. Masyarakat kelas menengah-atas, seperti bangsawan dan agamawan, boleh jadi meninggalkan Palestina karena keinginan sendiri atau terpaksa. Namun, penggarap tanah Palestina tetap melekat dengan negeri itu.
Menurut Sand, sejumlah temuan memperkuat kesimpulan tersebut. Dia menyebut, antara lain, nama-nama tempat — seperti desa dan tempat pemakaman — yang berasal dari bahasa Ibrani tetap dipertahankan hingga kini. Dialek bahasa Arab orang Palestina juga banyak bercampur dengan kata Ibrani dan Aramaik, sehingga membuatnya unik jika dibandingkan dengan dialek asli Arab atau dialek Arab di negeri lain.
Karena itu, Belkind menyatakan bahwa imigran Yahudi sebenarnya menemukan kembali saudara mereka yang hilang. “Orang baik dari bangsa kami…dari darah dan daging kami sendiri,” tulisnya. Dia pun menyarankan agar imigran Yahudi menyatu dengan penduduk lokal — alih-alih mengusir — dan membangun masa depan bersama.
Pada 1918, dua anak muda Zionis, David Ben-Gurion (1886-1973) dan Yitzhak Ben-Zvi (1884-1963), dalam buku karya mereka Eretz Israel in the Past and in the Present, juga meyakini bahwa populasi lokal Palestina adalah keturunan bangsa Yahudi kuno. Ben-Gurion kelak menjadi perdana menteri pertama Israel sedangkan Ben-Zvi menjabat presiden kedua negara itu.
“Fellahin (penduduk asli Palestina–penulis) bukanlah keturunan dari penakluk Arab, yang mengambil alih Eretz Israel dan Suriah pada Abad Ketujuh Masehi. Penakluk Arab tak menghancurkan populasi agraris yang mereka temui di negeri ini. Mereka hanya mengusir keluar penguasa asing Byzantium, dan tak menyentuh populasi lokal. Arab juga tak berniat bermukim…Mereka tidak mencari tanah baru yang di atasnya akan ditempatkan petani mereka. Kepentingan mereka di negeri ini adalah politik, agama, dan materi: untuk berkuasa, menyebarkan Islam, dan mengumpulkan pajak,” demikian tulis Ben-Gurion dan Ben-Zvi.
“Pandangan bahwa, setelah penaklukkan Yerusalem oleh Titus, bangsa Yahudi sama sekali tidak menggarap tanah Eretz Israel adalah ketakpedulian yang sempurna terhadap sejarah dan literatur kontemporer Israel…petani Yahudi, seperti petani lainnya, tidak mudah dipisahkan dari tanah mereka, yang telah diairi dengan keringat mereka dan nenek moyang mereka…terlepas dari penderitaan dan penindasan, populasi desa tetap tak berubah,” lanjut Ben-Gurion dan Ben-Zvi.
Mereka berdua menuliskan pendapat tersebut 30 tahun sebelum deklarasi pendirian negara Israel, yang menegaskan bahwa seluruh populasi lokal harus disingkirkan. Menurut Sand, pandangan moderat terhadap penduduk lokal Palestina, seperti yang ditulis Ben-Gurion dan Ben-Zvi, dalam perkembangannya raib dari jejak sejarah menyusul kekerasan demi kekerasan yang memicu kebangkitan nasionalisme di kalangan penduduk lokal pada akhir 1930-an.10Pada periode ini, pecah pemberontakan lokal penduduk Palestina dan mulai muncul benih-benih nasionalisme Palestina.
Sementara itu, untuk pertanyaan kedua, Sand mengajukan teori bahwa, sejak Abad ke-2 Sebelum Masehi hingga Abad ke-2 Masehi, Yudaisme justru agama yang paling banyak didakwahkan sehingga menyebar ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Yudaisme pun menyebar di seantero Timur Tengah dan sekitar Laut Tengah. Catatan Josephus dan sejarawan Romawi, seperti Horace, Seneca, Juvenal, dan Tacitus menunjukkan bahwa penguasa Romawi mencemaskan penyebaran Yudaisme di luar Palestina.
Sand menuliskan beberapa contoh kerajaan yang raja dan rakyatnya mengubah keyakinan mereka ke Yudaisme, seperti Himyar di Yaman pada Abad ke-5. Bahkan, keturunannya mampu mempertahankan keyakinan Yudaisme mereka melewati masa kekuasaan Islam hingga hari ini. Kemudian, ada bangsa Berber di Afrika Utara yang sebagiannya berpindah keyakinan ke Yudaisme. Bahkan, menurut catatan yang ditelusuri Sand, Yahudi Berber ikut membantu pasukan Muslim di bawah pimpinan Thariq bin Ziyad menaklukkan Semenanjung Iberia. Simbiosis unik Yahudi-Muslim11Antara lain dipicu persekusi penguasan Kerajaan Spanyol terhadap Yahudi. ini membentuk apa yang disebut sebagai budaya Arab-Hispanik.
Konversi ke Yudaisme paling signifikan, menurut Sand, terjadi pada Abad ke-8 Masehi di Khazar, kerajaan yang terletak antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Penyebaran Yudaisme ke kawasan Kaukasus hingga Rusia dan Eropa timur itu pun membentuk komunitas Yahudi berbudaya Yiddish12Yiddish adalah bahasa Slavic-Jerman yang digunakan Yahudi Eropa timur dan mengadopsi banyak kosakata Ibrani.. Komunitas inilah berikut keturunannya yang menjadi mayoritas warga Israel sekarang atau yang dikenal dengan Yahudi Ashkenazi.
Kompleksitas asal-usul orang Yahudi di Israel modern sangat jarang diakui oleh historiografi utama di Israel, untuk kemudian dimarjinalisasi dan dihapus sepenuhnya dari memori publik. Pasukan Israel yang merebut Yerusalem pada 1967 percaya bahwa mereka keturunan langsung dari kerajaan biblikal Daud alih-alih keturunan dari para ksatria Berber atau penunggang kuda Khazar.
Adalah Arthur Koestler13Arthur Koestler lebih dikenal sebagai sastrawan ketimbang sejarawan. (1905-1983), penulis Israel modern, yang menyimpang dari kemapanan historiografi itu ketika pada 1976 menulis buku kontroversial The Thirteenth Tribe: The Khazar Empire and Its Heritage. Dalam buku itu, dia meyakini bahwa orang Israel adalah keturunan Khazar, bukan keturunan Yahudi kuno yang hidup di Kanaan 4.000 tahun lalu. Koestler adalah pionir Zionisme di masa mudanya, bahkan pendukung utama pemimpin Zionis sayap kanan Vladimir Jabotinsky. Tapi, seiring waktu, Koestler kecewa dengan proyek pemukiman dan nasionalisme Yahudi lalu banyak menulis untuk menentang rasisme dan anti-Semitisme.
“Mayoritas Yahudi yang bertahan hidup di dunia berasal dari Eropa timur — dan dengan begitu mungkin berasal dari Khazar. Jika demikian, itu berarti bahwa nenek moyang mereka tidak datang dari Yordania tapi dari Volga, bukan dari Kanaan tapi dari Kaukasus, yang pernah dipercaya sebagai tempat kelahiran ras Arya; dan bahwa secara genetik mereka lebih dekat kepada suku Hun, Uighur, dan Magyar ketimbang kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jika ini persoalannya, maka terminologi anti-Semitisme menjadi tak bermakna, karena didasarkan pada kesalahpahaman dari para pembunuh dan korbannya,” tulis Koestler.
Pada dekade 1970-an, pernyataan seperti itu tentu pukulan hebat terhadap imajinasi utama Yahudi. Tanpa klaim “keturunan Yahudi kuno” yang “terbuang” dari “Tanah Yang Dijanjikan” dan “mengembara” untuk “pulang”, maka tak akan ada justifikasi untuk menganeksasi Yerusalem dan membangum permukiman ilegal di Tepi Barat, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan, dan bahkan Semenanjung Sinai. Sebab, menurut Sand, seluruh enigma Zionisme terletak pada mitologi tentang keabadian sebuah “etnik”.
Maka, tak heran jika setelah bukunya terbit, Koestler dikecam habis-habisan. Dia dinyatakan sebagai Yahudi pengkhianat. Bukunya dianggap sebagai aksi anti-Semit yang dibiayai oleh orang Palestina. Organisasi Zionis Dunia juga menganggap Koestler hanya mencari sensasi.
Sand, dalam The Invention, mengungkap bahwa Koestler sebenarnya bukanlah yang pertama mengungkapkan “teori Khazar”. Hipotesis Khazar — yang sejak dekade 1970-an dicaci di Israel sebagai berbau skandal, konspiratif, memalukan, dan anti-Semit — telah lama diterima di lingkaran sejarawan, baik Zionis maupun non-Zionis, meskipun tak pernah menjadi semacam konsensus karena adanya tekanan yang kuat dari etnosentrisme di tengah gencarnya proyek nasionalisme Yahudi.
Hipotesis Khazar juga memicu debat di kalangan ahli genetika. Hary Ostrer, ahli genetika Yeshiva University, New York City, mencoba membantah hipotesis itu. Dia mengklaim risetnya menemukan bahwa populasi Yahudi di dunia adalah homogen, memiliki akar yang sama dari Timur Tengah ketimbang dari Eropa timur. Namun, ahli genetika dari University of University of Sheffield, Eran Elhaik, menyatakan riset Ostrer bermasalah dan dua kali risetnya justru menguatkan hipotesis Khazar. Elhaik menyatakan, karena populasi Kaukasus relatif terisolasi sebelum kejatuhan Imperium Khazar, maka orang Yahudi Eropa timur berbagi asal-usul yang sama dengan populasi Kaukasus.
Sand menilai nyaris mustahil membuktikan kemurnian ras atau etnik, lebih-lebih dengan menggunakan studi genetik. Studi seperti itu, dia bilang, hanya bisa mencapai sedikit “kebenaran”. Sebab, selama ribuan tahun, sebuah ras (istilah yang menurut Sand sudah tak layak lagi dipakai di Abad ke-21) sudah berbaur dengan ras lain, sehingga argumentasi “kemurnian ras” nyaris mustahil untuk dipertahankan.
Pada akhirnya, The Invention menunjukkan bahwa ia bukanlah karya tentang pergumulan etnik dan genetik. Tesis Sand justru ditopang argumentasi yang seratus persen sekuler, yakni politik dan hak asasi manusia. Inilah raison d’etre Sand yang dia ulas di bagian akhir bukunya. Argumentasi historis yang dia ajukan di awal sebenarnya lebih merupakan penelusuran atas karya-karya awal sejarawan, baik Yahudi maupun non-Yahudi.
Bagi Sand, Israel hari ini bukanlah sebuah demokrasi melainkan “etnokrasi liberal”. Masyarakat Israel memang terbuka dan liberal tapi pada saat yang sama negara mereka hanya mengakui Yahudi sebagai bangsanya, bukan yang lain. Walhasil, warga non-Yahudi — baik itu Muslim, Kristen, dan “yang lain” — akan selalu dipinggirkan oleh negara.
Hak utama mereka, yakni pengakuan sebagai bagian dari bangsa Israel, diingkari oleh negara. Kebangsaan Israel selalu “Yahudi” dan bukan “Israel”. Sebab, baik dalam deklarasi kemerdekaan dan konstitusi, Israel adalah “negara Yahudi” bukan “negara Israel”. Bangsa Israel didasarkan pada etnik bukan pada kewarganegaraan.
Sensus 2015 menunjukkan, dari 8,7 juta populasi Israel, 75 persen adalah Yahudi (dari berbagai latar, dengan yang terbesar adalah Ashkenazi), 20 persen Palestina (baik Muslim maupun Kristen), dan 5 persen diistilahkan dengan “yang lain”. “Yang lain” ini terdiri dari keturunan Yahudi bukan dari garis ibu (yang sesuai hukum tak diakui sebagai Yahudi) atau imigran non-Yahudi. Dua kelompok ini, menurut Sand, tak dianggap sebagai “Yahudi” karena menolak menganut Yudaisme.
Karena itu, menurut Sand, keganjilan utama — khususnya terkait Hukum Kembali (Law of Return) — di negara Israel hari ini adalah, warga Yahudi non-Israel memiliki hak kembali ke Israel meskipun mereka memilih hidup di negara lain. Tapi, pada saat yang sama, seorang Kristen di Nazareth, misalnya, tak memilik hak untuk mengklaim sebagai bangsa Israel meskipun leluhurnya telah hidup di kota itu dari generasi ke generasi.
Setelah 60 tahun lebih berdiri, Israel tetap menolak untuk menerima bahwa negara ini harus ada demi seluruh warganya. Bagi seperempat populasi negara ini, yang tak dianggap sebagai orang Yahudi, Israel bukanlah negara mereka secara hukum. Pada saat yang sama, Israel menampilkan dirinya sebagai tanah air bagi seluruh orang Yahudi di dunia, bahkan jika mereka adalah warga negara lain.
Akibatnya, menurut Sand, terjadi diskriminasi dalam kebijakan negara terhadap penduduk Israel non-Yahudi. Rezim hanya memfokuskan pembangunan di wilayah yang dihuni komunitas Yahudi. Sementara, wilayah komunitas Palestina diabaikan, padahal Israel sejak 1948 terus mengambil paksa tanah-tanah orang Palestina.
Kebijakan dan prinsip “etnokrasi” Israel, menurut Sand, tak bisa dipertahankan. Israel harus menjadi negara demokrasi yang mengakui semua warganya — terlepas dari latar belakang ras dan agama — sebagai bangsa dan warga negara jika ingin tetap eksis. Jika tidak, Sand khawatir Israel akan menghadapi tuntutan kesetaraan yang berujung kepada pembubaran negara itu.[]