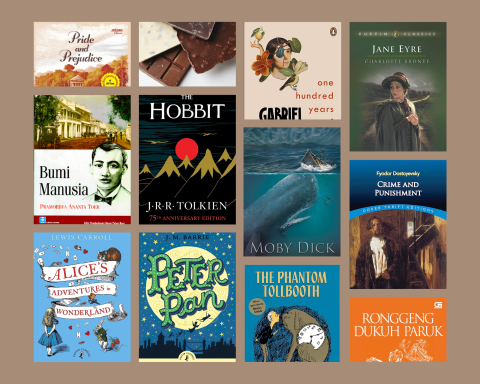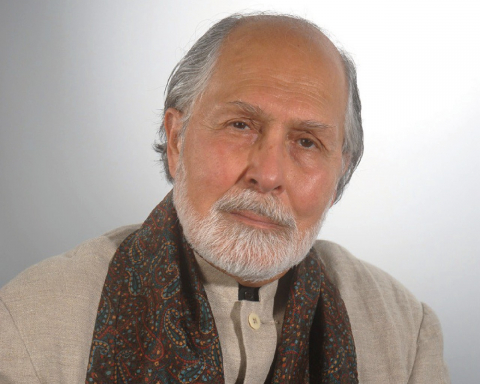Oleh Jacob Silverman
Catatan redaksi: Jacob Silverman berpendapat internet dan media sosial menciptakan lingkungan literasi di mana penulis lebih dielu-elukan karena biografi pribadi atau pengikut online mereka daripada karya mereka, membuat kritik dan ulasan objektif sulit bertahan.
PENGARANG Emma Straub memiliki 9.182 pengikut di Twitter. Tampaknya itu banyak bagi seorang pengarang yang novel pertamanya, Laura Lamont’s Life in Pictures, belum lagi terbit. Dan Emma Straub benar-benar piawai di Twitter. Dia lucu dan memesona serta menunjukkan antusiasme besar kepada buku dan cerita sesama penulis dan kritikus dalam lingkungan sosialnya. Di luar Twitter, Straub menulis bagi banyak penerbitan buku. Dia anak novelis Peter Straub, dan menjalankan perusahaan desain kecil dengan suaminya yang menghasilkan poster bagi siapa pun, dari mulai Passion Pit hingga Jonathan Lethem.
Di hari lain, Straub mempos foto dirinya mengenakan mahkota besar berbunga sambil menggenggam bukunya yang baru saja keluar dari percetakan. Dia menandatangani pos itu, “Yours, in love with everyone, Emma.” Di Twitter dan Tumblr, pos itu di-RT dan di-Like serta direspons dengan kehebohan oleh teman dan sesama penulis serta fan, termasuk akun Twitter situs web literasi The Rumpus; pengikut Straub di Facebook tahu bahwa situs itu telah memilih buku tersebut untuk klub buku bulanan mereka.
Katakanlah anda bagian dari jejaring penulis, pecinta fiksi, editor sastra, dan pembaca di dunia media sosial, dan ditugaskan untuk mengulas Laura Lamont’s Life in Pictures. Bagaimana jika anda tak menyukai buku itu? Atau bagaimana jika anda menyukainya tapi bukan tanpa syarat? Apakah anda akan mengatakan demikian? Akankah anda mengkritik novel Straub setelah menyaksikan hidupnya terpaparkan sedemikian rupa di media sosial dalam setahun terakhir—bahkan mungkin setelah menerima dan mengagumi kata-kata dan keramahan kecil dari Straub.
Bagi yang belum mengalami, ini mungkin terlihat tak relevan, atau bersifat teramat pribadi yang bisa membuat dunia literasi New York tak tertahankan. Sebagai orang yang relatif baru datang ke New York, saya bisa mengatakan keduanya benar. Tapi ini juga penting, karena situasi seseorang seperti Straub melambangkan masyarakat yang saling mengagumi, dan itulah dunia kesusastraan saat ini, terutama di dunia maya.
Saya tentu saja menggunakan Straub sebagai ilustrasi alih-alih sebuah subjek kritik (saya bisa saja memulai esai ini dengan sejumlah pengarang lain yang buku mereka baru saja atau akan terbit dan yang juga pengguna aktif media sosial, seperti Jami Attenberg, Nathan Englander, Cheryl Strayed, dan J Robert Lennon). Saya belum membaca novel Straub, dan benar saja ulasan-ulasan awal (sepertinya jujur) bernada positif. Dan saya setidaknya tidak sedang mengatakan bahwa persona Straub di media sosial itu palsu—dia tampak benar-benar menyenangkan, dan bukankah kegunaan media sosial memang untuk membuat koneksi dengan orang yang tertarik pada hal yang sama dengan anda? Tapi jika anda meluangkan waktu menjelajahi dunia literasi Twitter—atau blog—anda akan secara positif dikepung oleh keramahan dan antusiasme terus menerus yang mungkin membuat anda percaya bahwa semua buku baru itu indah dan bahwa setiap penulis adalah penggemar terbesar penulis lainnya. Ini tidak hanya dangkal tapi juga tak benar, dan ini memiliki efek mengerikan pada budaya literasi, yakni menciptakan lingkungan di mana penulis lebih dielu-elukan karena biografi pribadi atau pengikut online mereka daripada karya mereka dalam buku.
Pada suatu masa, para kritikus pernah melakukan satu peran di media cetak dan peran lainnya dalam kehidupan—Rebecca West bisa menyerang buku seseorang di pagi hari lalu makan malam bersama penulisnya di malam hari. Media sosial telah meruntuhkan batas-batas ini. Lebih jauh, kekuatan sentrifugal puja-puji media sosial—retweet, like, favorite, dan kewaspadaan-diri yang menyertai setiap ucapan publik—membuat kritik apa pun sulit untuk bertahan.
Tidak berbagi pesta kehebohan online dunia literasi bisa terasa aneh dan menandakan seseorang bakal tak disukai atau (serangan terburuk di zaman ini) tak diikuti. Rasionalisasi semacam ini mungkin sebagian besarnya terjadi dalam otak insting kita, tapi saya berpendapat bahwa itulah alasan mengapa dunia kesusastraan—sebuah komunitas yang terkenal terpencil—mulai terperosok ke dalam klub-kluban dan kesopansatunan.
Dan mengapa tidak, anda mungkin akan berkata demikian. Mengapa tidak para pengarang dan pecinta literasi membangun sebuah lingkungan yang sepenuhnya nyaman dan aman? Ketika datang waktunya buku anda diterbitkan atau anda akhirnya mendapatkan keistimewaan besar itu, bukankah anda juga menginginkan tepuk tangan meriah? Tapi tepuk tangan meriah terus-menerus itu membuat semakin sulit saja untuk mendengar suara-suara pendapat yang berbeda—kritik skeptis dan rewel yang mungkin menyakitkan bagi penulis tapi membuat budaya literasi menjadi bersemangat dan bermanfaat.
Dalam beberapa tahun terakhir, ruang simbiosis jurnalisme dan penerbitan secara khusus terampil memicu ketakutan akan kehancuran diri mereka sendiri, ketika mereka bersiap untuk bertekuk lutut di hadapan gergasi-gergasi kaya raya macam Google dan Amazon. Tapi tak seperti jurnalisme, penerbitan sebenarnya tak tampil terlalu buruk—memang tak baik, anda bisa mengatakan itu, tapi tentu saja tak sedang meluncur tajam. Didorong oleh self-publishing, penjualan buku relatif stabil; buku elektronik telah lepas landas; dan industri buku tampaknya belajar cukup banyak dari bisnis musik, yang kegagalan Luddite-nya untuk merangkul distribusi digital pada masa-masa sangat awal menjadi kisah peringatan penting dari industri media. Sementara, dunia penerbitan terancam pada sisi kritik dan ulasannya, dalam budaya yang seharusnya mendukungnya.
Meskipun rubrik-rubrik buku telah hilang dari banyak suratkabar dalam dekade terakhir, blog, majalah, dan jurnal online yang beroperasi dengan anggaran minim—situs-situs seperti Quarterly Conversation, Boston Review, Full Stop, dan Los Angeles Review of Books—mulai muncul mengisi kekosongan, bersama dengan beberapa nama abadi (blog The New York Review of Books seringkali sama bagus dengan edisi cetaknya).
Namun, atomisasi jurnalisme kesusastraan—dan masalah yang menyertainya, yaitu mendapatkan bayaran untuk itu—telah membuatnya tampak terkepung. Para pengulas menanggapi ini dengan memutar arah, tampaknya berpikir bahwa mereka akan mendapatkan lebih banyak pembaca (dan dukungan kelembagaan) dengan “madu” daripada dengan argumen, pendapat yang berbeda, atau orisinalitas. Editor juga ikut terlibat, karena beberapa publikasi sama sekali tidak memuat ulasan negatif, bahkan memperlakukan kritik sebagai pekerjaan membunuh reputasi. Lev Grossman dari Time mengatakan bahwa dia tak akan mengulas buku yang tidak dia sukai. Dia baru-baru ini menulis sebuah esai berjudul “I Hate This Book So Much: A Meditation”, yang di dalamnya dia menghilangkan setiap detail yang mungkin digunakan untuk mengidentifikasi buku atau penulisnya. Untuk beberapa saat, feature utama buku pada NPR.org sempat menyebut dirinya “Books We Like”, dan ulasan negatif tak disarankan; sejak saat itu, suara-suara kritis merembes pelan-pelan ke dalam situs itu tetapi masih jarang. Media-media lain mencoba menetek page view (dan biaya afiliasi Amazon) dengan menayangkan slide, daftar-daftar buku, dan postingan tamu dari penulis terkenal yang terbaca seperti salinan dari jaket sampul sebuah buku. Semua ini kemenangan bagi humas penerbitan, tetapi tidak bagi pembaca.
Pengulas tak semestinya menjadi mesin rekomendasi, namun kita cukup puas dengan peran itu, sebagian karena dorongan komunalisme Twitter. Keutamaan kita atas algoritma Amazon dan Barnes & Noble, dan keamatiran (beberapa di antaranya harus diakui cukup bagus dan bermanfaat) dari situs-situs seperti GoodReads, adalah bahwa kita para profesional dengan opini beragam nuansa dan berpengetahun. Kita dibayar untuk bersikap skeptis, bahkan pesimistis, sehingga antusiasme kita semakin berarti ketika ia didapatkan dengan layak. Para pengulas hari ini cenderung mengglorifikasi perdebatan lama antara William F Buckley dan Gore Vidal atau Noam Chomsky (videonya ada di YouTube), tetapi mereka sendiri tak mau terlibat dalam pertarungan intelektual semacam itu. Mereka memuji serangan agresif Norman Mailer dan Pauline Kael, tapi kebanyakan dari jauh. Mailer dan Kael adalah teman sekolah pemberontak kalian: objek pemujaan, mungkin, tapi bukan tiruan. Bagaimanapun, semuanya menjadi sangat berantakan, dan seseorang mungkin terluka.
Sebaliknya, mengutamakan puja-puji dan antusiasme buta adalah sentimen dominan saat ini. Seolah ingin mencerminkan budaya di sekitarnya, kritik menggigit sudah dianggap identik dengan serangan; semuanya menjadi bersifat pribadi—kecintaan seseorang kepada sebuah buku bisa dipertukarkan dengan perasaan seseorang kepada pribadi penulisnya. Para kritikus mengantisipasi dengan semangat buku-buku yang belum mereka baca; mereka menandai akun Twitter penulis sehingga penulis mengetahui ulasan mereka; mereka terobsesi dengan pujian berhuruf serba kapital, karena itulah cara mereka meningkatkan jumlah pengikut dan menegaskan tempat mereka dalam komunitas saling mengagumi ini, yaitu dunia kesusastraan online. Dan, tentu saja, kritikus, kebanyakan dari mereka, adalah pekerja lepas dan haus akan pekerjaan, ingin menarik perhatian penggemar dan juga pembaca; dan untuk terhubung dengan mereka, para kritikus harus menjadi mereka.
Twitter dan Tumblr membentuk suprastruktur dunia kesusastraan saat ini. Festival dan toko buku independen menghilang, jadi di sinilah kita berkumpul, memungkinkan kita merobohkan geografi dengan mengorbankan pemikiran yang hening. Di sinilah tautan dibagikan, rekomendasi dipertukarkan, berita disebar, serta kontak dan pertemanan dibuat. Di sinilah juga setiap orang menjual dirinya dan perdebatan serta perbedaan pendapat mudah dihilangkan. Seperti yang baru-baru ini ditulis oleh Mark Athitakis, blogger literasi, bahwa “Twitter secara otomatis menjadi mesin afirmasi. Menjadi lebih mudah bergairah daripada berdiskusi.”
Dan afirmasi adalah isyarat lazim dari internet. Kita me-like, favorite, dan memuji sepanjang hari; itulah pertunjukan dukungan dan persetujuan, serta permohonan kecil untuk perhatian: Lihatlah saya, saya juga me-like ini. Follow back? Di Tumblr, yang telah menjadi rumah favorit bagi para penulis dan telah mengambil peran kurator sastra, mempromosikan konten dan mensponsori acara, perbedaan pendapat tak diproduksi lagi. “Kami tak ingin membiarkan perasaan Anda terluka di Tumblr,” kata seorang desainer Tumblr baru-baru kepada New York Times Magazine. David Karp, pendiri Tumblr, sangat bersemangat dengan ikon hati pada situsnya: “Semua orang mencintai semua orang, melalui suatu rangkaian.”
Masalahnya, like adalah jalan buntu kritik, sebuah percakapan tanpa hasil. Ia pendapat tanpa bukti—atau sikap tanpa pendapat. Untuk setiap “+1”, “INI”, atau “<3” yang kita tawarkan pada twit sanjungan seseorang, sebuah perasaan diungkapkan tanpa bicara sama sekali. Dan dalam ulasan atau esai berikutnya, itu akan ditampilkan.
Budaya literasi yang lebih baik adalah budaya yang tidak begitu bergantung kepada kekaguman personal dan afirmasi timbal balik. Ia tak akan memperlakukan kritik atau ketidaksetujuan sebagai racun. Kita tak ingin disukai berlebihan. Kita menoleransi ulasan menusuk, beberapa perdebatan sengit, dan kritik pedas, karena semua itu membuat budaya kita lebih menarik dan karena semua itu seringkali merupakan refleksi yang lebih tulus dari kecintaan kita. Jika kita banyak berpikir dan sedikit berantusias, dan saat saya benar-benar menyukai Laura Lamont’s Life in Pictures, maka anda akan lebih cenderung mempercayai saya.[]
Jacob Silverman adalah penulis Terms of Service: Social Media and the Price of Constant Connection.
(Artikel ini diterjemahkan dari “Against Enthusiasm: The epidemic of niceness in online book culture” yang terbit dalam situs web majalah Slate pada 4 Agustus 2012)