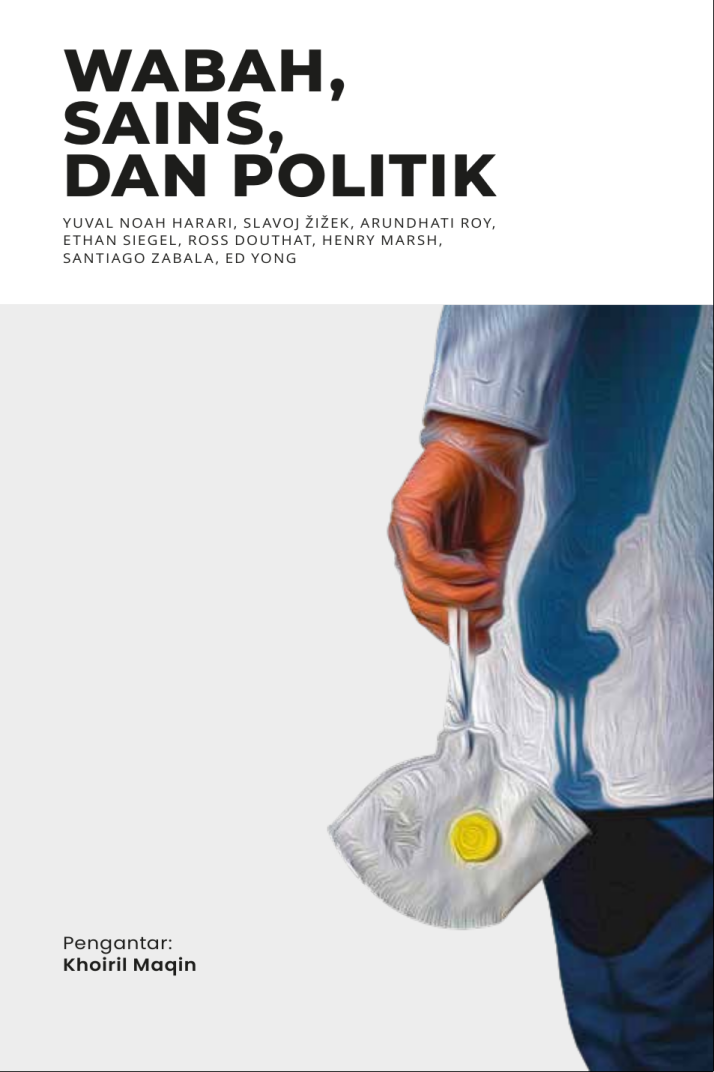Di masa pandemi, muncul suara-suara keraguan atas sains dan bahkan upaya pembenturan sains dengan agama. Benarkah sains berkontribusi dalam ketidakpastian hari ini? Jangan-jangan kekisruhan ini ulah politisi tak bertanggung jawab yang meremehkan sains?
WABAH, Sains, dan Politik merupakan terjemahan kumpulan artikel penulis dari berbagai latar belakang. Ada Ethan Siegel, seorang astrofisikawan sekaligus penulis sains; Ross Douthat, kolumnis The New York Times; Henry Marsh, pensiunan dokter di Amerika Serikat; Yuval Noah Harari, sejarawan dan penulis buku laris Sapiens: A Brief History of Humankind; Arundhati Roy, aktivis politik cum novelis yang beken lewat The God of Small Things; Santiago Zabala, filsuf Spanyol; Slavoj Zizek, filsuf nyentrik Slovenia; dan Ed Yong, penulis-jurnalis sains. Artikel-artikel mereka diterjemahkan, dikumpulkan, disusun, dan diterbitkan dalam bentuk buku elektronik (yang bisa diunduh gratis) pada Juni 2020 oleh Antinomi Institute, sebuah komunitas pemikiran berbasis di Yogyakarta.
Artikel-artikel tersebut pernah terbit di media-media berbahasa Inggris selama periode pandemi, sekitar Februari hingga April. Meskipun para penulisnya datang dari beragam latar belakang, terlihat ada benang merah dalam pembahasan mereka. Mereka mengulas pergulatan sains dan politik di masa pandemi ini.
***
SARS-Cov-2, jenis baru virus Korona pemicu sindrom pernapasan Covid-19, telah membunuh nyaris setengah juta manusia di seantero bumi sejak enam bulan serangan pertamanya. Orang-orang resah karena menghadapi pilihan paling brutal dalam hidup mereka: kembali beraktivitas normal dengan risiko terpapar virus—dan kehilangan nyawa—atau tetap melakukan penjarakan sosial dengan konsekuensi kehilangan pendapatan. Kedua pilihan itu menghadirkan ketidakpastian.
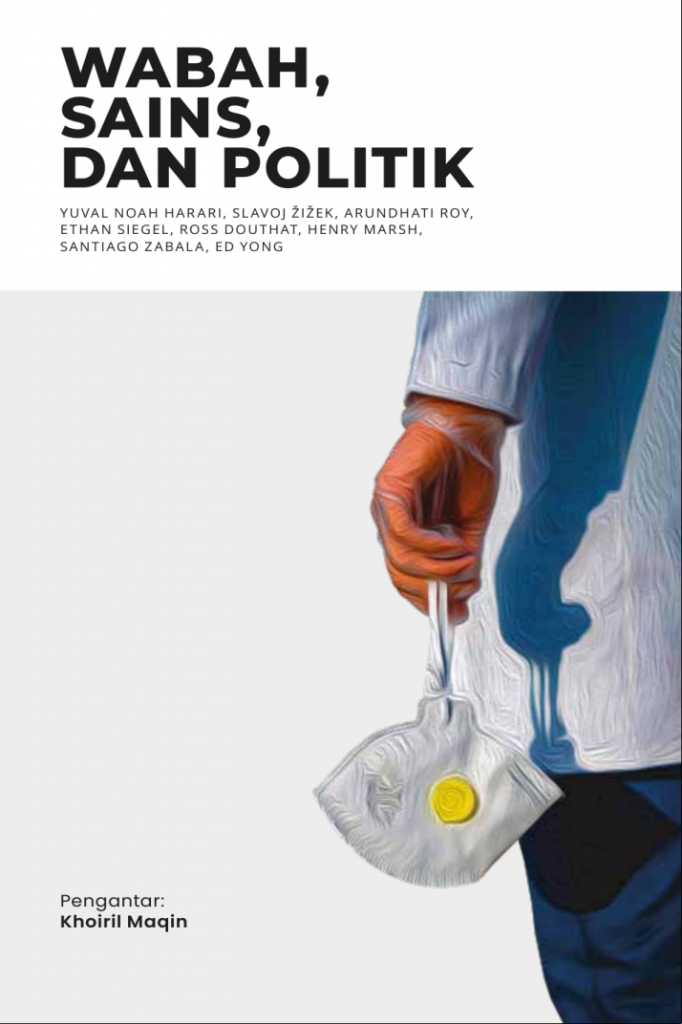
- Judul Buku: Wabah, Sains, dan Politik
- Penulis: Yuval Noah Harari, Slavoj Zizek, Arundhati Roy, Ethan Siegel, Ross Douthat, Henry Marsh, Santiago Zabala, Ed Yong
- Penerbit: Antinomi Institute
- Terbit: Juni 2020
- Tebal: ix + 136 halaman
Lalu, muncul suara-suara keraguan atas kemampuan sains. Baiklah, sains memang alat terbaik yang dimiliki manusia sejauh ini untuk memahami apa yang terjadi. Tapi, sains tak kuasa mendatangkan kepastian yang dibutuhkan hari-hari ini. Kita tak bisa lagi menunggu kota dikunci dan kegiatan ekonomi dibatasi. Kita bisa mati kelaparan. Kira-kira begitu kata suara-suara itu.
Orang-orang yang ragu itu, menurut Ethan Siegel (“Tiga Cara Sains Membimbing Kita Melawati Pandemi Covid-19), tak menyadari bahwa sains bukan hanya tentang informasi mutakhir soal pandemi ini. Sains juga tentang informasi bagaimana ia bekerja. Para peragu itu mungkin lupa bahwa apa yang dicapai sains dalam waktu kurang dari sebulan sejak kasus pertama Covid-19 (identifikasi varian virus; pengurutan DNA-nya; bagaimana virus menular; dan seberapa mudah penularannya) bisa terjadi karena pencapaian sains sebelumnya. Berkat pencapaian ini, kita sekarang bisa mengetahui dan melakukan cara-cara pencegahan penularan. Kita tak perlu menanti hingga nyawa 200 juta orang melayang seperti saat Black Death menyerang tujuh ratus tahun lalu. Kita tak perlu menunggu hingga 50 juta manusia masuk kuburan seperti saat Flu Spanyol menginfeksi satu abad yang lewat.
Riset-riset di masa lalu—dalam bidang fisika, zoologi, genom manusia, virulogi, imunologi, psikologi, dan antropologi—semuanya mengantarkan manusia kepada kondisi hari ini. Riset-riset dasar itu dulu tak terpahami sebagai sesuatu yang penting; sesuatu yang bakal memiliki manfaat aplikatif dalam kehidupan manusia, terutama di bidang kedokteran. “Kemajuan mutakhir yang kita perjuangkan hari ini dibangun di atas tulang punggung riset lintas disiplin yang digerakkan rasa ingin tahu.”
Jika membiarkan keraguan itu tumbuh menjadi penghakiman atas sains, kita justru kehilangan peluang untuk membangun pemahaman lebih baik dalam menghadapi krisis serupa—atau bahkan lebih dahsyat—50 atau 100 tahun ke depan. Siegel pun menyarankan kita melihat Covid-19 sebagai momen terbaik untuk menggandakan investasi terhadap sains dan pengetahuan. “Investasi yang kita lakukan hari ini akan membawa kita pada pengetahuan esok hari, dan sebagai imbalannya, alat-alat dan teknik-teknik masa depan yang akan mengantarkan kita ke dunia yang lebih baik untuk semua manusia.”
Itu tak berarti melebih-lebihkan sains dan menganggapnya bisa menyelesaikan seluruh persoalan. Tapi, di dalam kabut ketidakpastian, menurut Ross Douthat (“Dalam Kabut Korona, Tidak Ada Pakar”), masih lebih baik percaya kepada sains daripada “bualan” acak di media sosial.
Douthat menyampaikan analogi menarik tentang situasi ini. Kita saat ini seperti berada dalam ruang bawah tanah yang gelap. Lalu datang seberkas sinar menembus kegelapan. Itulah sains. Segaris cahaya itu tak menerangi seluruh ruang. Tapi dengan bantuannya, kita meniti jalan keluar; dengan meraba-raba, tersandung, dan terjatuh.
Persoalannya, kata Douthat, para politisi mencoba mencegah berkas cahaya itu masuk. Sains dikepung informasi palsu buzzer dan influencer bayaran politisi. Henry Marsh (“Covid-19 dan Dilema Seorang Dokter”) menyoroti bagaimana kebijakan politisi sebelum pandemi ini menyumbang pada kegagalan antisipasi. Pemotongan dan minimnya anggaran kesehatan membuat fasilitas kesehatan kedodoran: kekurangan dokter, tenaga medis, mesin ventilator, baju pelindung kesehatan, dan masker.
Para politisi tidak peduli dan bahkan di antaranya meremehkan wabah ini. Presiden Brasil Jair Bolsonaro menyebutnya cuma fantasi dan pilek biasa. Perdana Menteri Narendra Modi baru menetapkan karantina pada 23 Maret, padahal kasus pertama di India telah diketahui pada 30 Januari. Penetapan karantina tiba-tiba tanpa kesiapan jaring pengaman sosial, menurut Arundhati Roy (“Pandemi adalah Sebuah Pintu Gerbang”), membuat orang melarat kelaparan di jalanan dan gubuk-gubuk kumuh. Sebagian mereka terpaksa pulang ke kampung halaman dengan berjalan kaki menempuh ratusan kilometer. Beberapa lalu mati di tengah jalan. Yang lain dipukuli dan dihinakan polisi yang menetapkan jam malam. Bantuan pemerintah baru belakangan datang, dan itu pun dengan foto wajah Modi pada bungkusannya.
Kalaupun ada kebijakan darurat yang diambil, menurut Santiago Zabala (“Pandemi Korona sebagai Ancaman bagi Penguasa Populis”), para politisi lebih memilih meredam gejolak pasar daripada membantu warga miskin dan kelas pekerja. Santiago melihat virus ini telah menyingkap “retakan-retakan besar” sosial-ekonomi yang selama ini coba ditutupi para politisi. Bukanlah sains yang membuat penanganan pandemi centang perenang tapi politisi.
Politisi yang mencoba mengatakan jangan panik, kata Slavoj Zizek (“Mimpi Saya tentang Wuhan”), sebenarnya panik. Mereka tahu informasi sains punya kemungkinan benar tapi mencoba menutupinya karena agenda politik mereka, entah itu pemilihan menjelang atau upaya meloloskan undang-undang di parlemen. Zizek menguliti lapisan makna di balik imbauan “jangan panik”. Imbauan itu justru membuat kepanikan datang di saat tak tepat. Setelah terjadinya wabah SARS dan Ebola, sains sudah memperingatkan kita tentang kemungkinan serangan wabah baru, yang persoalannya bukan lagi “jika” tapi “kapan”. Anehnya, politisi tak menganggapnya serius dan mempersiapkan antisipasinya. Di sini, seakan Zizek ingin mengatakan seharusnya “kepanikan” terjadi saat itu, dan bukan saat ini yang sama sekali tak membutuhkan kepanikan.
Akibatnya, menurut Marsh, dokter dan tenaga medis bagai diumpankan menjadi korban. Bukan hanya paling berisiko terpapar virus, mereka juga dipaksa menghadapi dilema moral terkejam sepanjang karir: memutuskan siapa yang bisa bertahan hidup dan siapa yang akan mati.
“Kami memiliki sedikit sekali pilihan selain menerapkan pilihan kejam dan buruk hitung-menghitung ala utilitarian, terlebih bertentangan dengan konsep ideal sucinya sebuah kehidupan. Berapa lama lagi seorang pasien harus diupayakan bertahan hidup? Apakah mereka memiliki tanggungan hidup?.. Dan bahkan, tidak jarang ada peraturan tidak tertulis ‘siapa cepat, dia dapat’.”
Yuval Noah Harari (“Akankah Virus Korona Mengubah Sikap Terhadap Kematian? Justru Sebaliknya”) berpandangan bahwa “musuh” sains saat ini bukanlah agama dan para agamawan, tapi politisi. Sejarah hari ini tak lagi mementaskan pertarungan epik antara agama dan sains, tapi antara sains dan politisi tak bertanggung jawab. Mereka yang paling setia kepada agama, kata Harari, justru kali ini percaya kepada sains.
“Gereja Katolik memerintahkan jemaatnya untuk menjauh dari gereja. Israel menutup sinagog-sinagognya. Republik Islam Iran menganjurkan rakyatnya untuk tidak mengunjungi masjid. Candi-candi dan semua sekte menunda seremoni mereka. Dan semua itu karena ilmuwan telah membuat perhitungan ilmiah dan merekomendasikan penutupan semua tempat suci tersebut.”
Yang menarik, suara anti-sains justru datang dari kalangan agamawan yang dekat dengan kekuasaan. Pendeta yang memimpin pengajian Bibel mingguan di Gedung Putih berpendapat bahwa pandemi ini hukuman Tuhan untuk homoseksualitas. Roy juga menunjukkan bagaimana pendukung partai sayap kanan berkuasa, BJP, memanfaatkan isu sektarian untuk menutupi kegagalan Modi mengantisipasi wabah. Ketika media arus utama memberitakan kelompok Muslim Jamaah Tabligh mengadakan pertemuan di Delhi sebelum karantina, stigmatisasi segera menyebar luas, bahwa Muslim mengundang virus ini masuk ke India sebagai senjata jihad.
Dengan segala kekisruhan tersebut, Roy mengatakan pandemi ini memberi kita gerbang portal menuju dunia baru; sebuah keterputusan dari dunia lama. Persoalannya, apa yang akan kita bawa melewati gerbang tersebut menentukan wajah dunia baru itu.
“Kita bisa memilih untuk berjalan melaluinya, dengan tetap membawa sisa-sisa dari prasangka dan kebencian kita, keserakahan kita, bank data dan ide-ide lawas kita, sungai-sungai yang kering dan langit-langit yang penuh dengan asap. Atau kita bisa berjalan dengan enteng, dengan sedikit barang-barang bawaan, dan bersiap untuk membayangkan dunia yang lain.”
Jika Roy tak merumuskan das sollen pada dunia baru nanti, Harari dan Zizek masing-masing mengajukan “solidaritas global” dan “komunisme global”. Harari (“Dalam Perang Melawan Virus Korona, Umat Manusia Kekurangan Pemimpin”) mengatakan negara-negara tak bisa lagi saling mengisolasi diri; bertindak atas kemauan sendiri. Mereka harus membangun “solidaritas global”: saling membantu dalam penyediaan alat-alat kesehatan, menolong secara ekonomi, dan yang terpenting berbagi informasi sains. Sebab, kata Harari, kekuatan manusia melawan patogen adalah informasi sains.
Kesehatan saat ini bukan lagi urusan lokal-nasional, tapi global. Kesehatan di Cina dan Iran akan menyelamatkan warga di Amerika dan Israel. Sayangnya, menurut dia, kebajikan sederhana ini luput dari perhatian politisi. Solidaritas global juga baru bisa dibangun jika ada rasa saling percaya. Lacurnya, menurut Harari, rasa saling percaya hari-hari ini dirusak oleh politisi yang meremehkan sains.
Zizek (“Komunisme Global atau Hukum Rimba, Virus Korona Memaksa Kita untuk Memilih”) datang dengan ide “komunisme global”. Dia tahu istilah itu akan ditertawakan banyak orang. Yang dia maksud dengan “komunisme” di sini adalah bentuknya yang paling sederhana: solidaritas dan kolektivitas. Bagi Zizek, ada ironi ketika Amerika selalu membangun koalisi internasional untuk memuntahkan rudal ke negara-negara lain tapi gagal melakukan hal serupa untuk melawan virus. “Komunisme global”, dalam bayangan Zizek, juga tak hanya melibatkan negara-negara tapi aktor-aktor individu yang lepas dari kendali negara.
Kebutuhan kita kepada “solidaritas global” versi Harari atau “komunisme global” ala Zizek didorong oleh kenyataan—seperti diungkapkan Roy, Zizek, dan Santiago—bahwa kapitalisme dan pasar bebas yang tak terkendali itu terbukti semaput di hadapan musuh mikroskopis. Kita, kata mereka, membutuhkan bentuk lain yang berbasis solidaritas dan kolektivitas. Jika itu tak dilakukan, Zizek bilang pilihan yang tersedia hanyalah survival of the fittest.
***
INISIATIF Antinomi Institute menerjemahkan dan menerbitkan tulisan-tulisan ini dalam bentuk buku layak diacungi jempol. Di tengah seliweran informasi serba instan dan kabur di media sosial, artikel para pemikir di atas bisa menjadi bahan perenungan kita untuk memahami realitas yang tengah menyingkap hari-hari ini. Beberapa penerjemahan terbaca agak ganjil, tapi secara keseluruhan mengalir, terutama untuk artikel Harari “Akankah Virus Korona Mengubah Sikap Kita Terhadap Kematian? Justru Sebaliknya” dan artikel Roy “Pandemi adalah Sebuah Pintu Gerbang”.
Tanpa mengecilkan artikel lainnya, dua artikel itu juga paling menggugah. Harari memprovokasi kita dengan sinisme khasnya terhadap agama. Harari seakan memandang agama dan sains berada pada lajur linear perjalanan sejarah, di mana peran yang datang lebih dulu (agama) digantikan oleh yang datang kemudian (sains), dan bukan pada gerakan spiral yang bisa digambarkan dari idealisme historis Hegelian di mana agama dan sains terus saling berdialektika.
Tapi di titik tertentu, dia mengatakan sains masih memiliki keterbatasan, sehingga manusia bagaimanapun harus mengakui kefanaannya. Meskipun demikian, Harari tetap menyimpan harapan bahwa di suatu masa kelak (dia bilang satu atau dua abad ke depan) sains akan mengembangkan kehidupan manusia tanpa batas; bebas dari kungkungan “kausalitas metafisik”.
Sementara itu, Roy—seperti juga bisa terbaca dalam novelnya The God of Small Things—menulis sangat kelam dan terkadang menghadirkan humor gelap. Melalui pengamatannya yang jeli, kata-katanya melukis kesuraman kondisi warga miskin dan minoritas di India, negerinya sendiri.[]