Film dokumenter ini secara implisit menunjukkan bahwa, saat true crime terjadi, polisi justru bagian dari masalah. Korban kembali menjadi korban untuk kesekian kalinya akibat prasangka sosial dan ketidakmampuan polisi.
RICHARD McCann, 5 tahun, menemukan keanehan yang menyenangkan pada pagi hari, 30 Oktober 1975. Orang-orang datang ke rumahnya, memperhatikannya, dan membuatkan minuman cokelat untuk dia dan tiga saudaranya, yang usia mereka tak berbeda jauh dengannya. Kemudian seorang polisi memasuki rumah, mendudukkan mereka, dan mengatakan, “Ibu kalian telah ke surga.”
Itulah ingatan yang tersisa dari Richard tentang pagi yang mengubah hidupnya, dan juga hidup sebagian rakyat Inggris. Pagi itu, sang ibu, Wilma McCann, menjadi korban pembunuhan pertama Peter William Sutcliffe atau yang dijuluki media dan polisi sebagai “The Yorkshire Ripper” (Si Pencabik dari Yorkshire). Selama lebih daripada lima tahun, Sutcliffe melenggang bebas menyerang dan mencabik-cabik 22 perempuan—sembilan di antaranya bertahan hidup.
Kisah perburuan terhadap Sutcliffe—dianggap sebagai investigasi terbesar dan termahal dalam sejarah kriminalitas di Inggris—menjadi premis film dokumenter terbaru Netflix, The Ripper. Julukan tersebut, seperti Anda mungkin pikirkan, memang mengacu kepada “Jack the Ripper”, jagal termasyhur dari era Victorian (1888) yang identitasnya hingga kini tak terungkap. Seperti “Jack the Ripper”, Sutcliffe menghujani tubuh korbannya dengan belasan hingga puluhan tusukan setelah meremukkan kepala mereka. Tapi, jika “Jack the Ripper” beraksi di kawasan East End London—tepatnya distrik Whitechapel—sebagian besar korban Sutcliffe berada di kawasan metropolitan Yorkshire Barat (Inggris Utara), seperti Leeds dan Bradford, dan dua korban lain ditemukan di kawasan Manchester Raya.
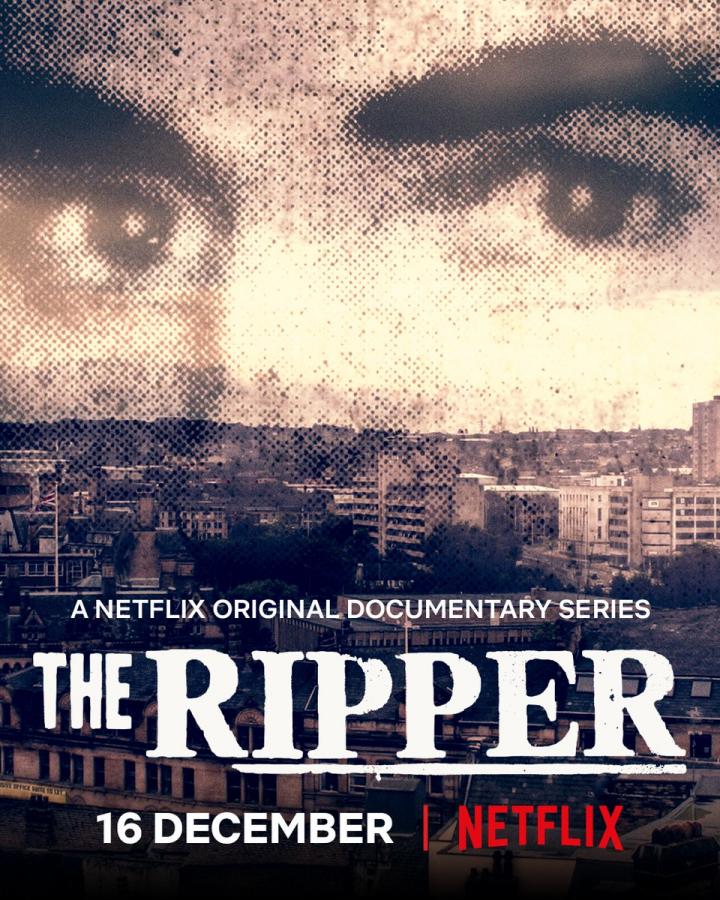
- Judul Film: The Ripper
- Sutradara: Jesse Vile, Elena Wood
- Genre: Serial Dokumenter
- Rilis: 16 Desember 2020 (Netflix)
- Durasi: 4 episode (@ 57 menit)
Namun, korban selamat dan keluarga korban memprotes judul The Ripper dan menuntut Netflik melalui surat terbuka untuk mengembalikannya ke judul awal, Once Upon A Time in Yorkshire (judul ini dijadikan judul episode pertama). Mereka menilai judul The Ripper mengglorifikasi kejahatan Sutcliffe dan tidak berfokus kepada narasi para korban.
Berkebalikan dari kecemasan tersebut, sutradara Jesse Vile dan Elena Wood justru mengarahkan film ini kepada hal-hal yang lebih penting daripada si pembunuh. Narasi film ini sebagian besarnya mengulas siapa para korban dan bagaimana perasaan keluarga mereka, kondisi sosial-ekonomi di kawasan Yorkshire pada masa itu, dan prasangka sosial yang mengakar di institusi kepolisian dan di tengah masyarakat. Prasangka sosial, sebagaimana ditunjukkan dalam film dokumenter empat episode ini, pada akhirnya malah menyesatkan penyelidikan polisi. Persoalan siapa Sutcliffe dan apa yang memotivasinya menjagal 13 perempuan hanya sedikit diulas pada episode terakhir.
Sedari awal prasangka sosial terhadap korban telah merasuki penyelidikan polisi. Hanya karena dua korban pertama, Wilma McCann dan Emily Jackson, ditemukan di dekat kawasan “lampu merah” Chapeltown, polisi dengan mudahnya mengasumsikan mereka pekerja seks dan pelaku hanya menarget pekerja seks. Asumsi ini pula yang membuat polisi dan pers menjuluki pelaku dengan “The Yorkshire Ripper” karena “Jack the Ripper” menyasar korban dengan profesi serupa. Dari sisi media, julukan ini juga menjual. Media seakan ingin memicu sensasi di benak para pembacanya bahwa telah muncul reinkarnasi jagal legendaris dari era Victoria tapi kali ini ia beraksi di Chapeltown, Yorkshire, bukan di Whitechapel, London.
Melabeli korban si jagal sebagai pekerja seks mungkin menimbulkan semacam rasa aman bagi masyarakat. Siapa yang peduli dengan nasib mereka? Toh, kekerasan terhadap para pekerja seks seperti sudah menjadi sarapan sehari-hari. Alan Whitehouse, seorang jurnalis Yorkshire Post yang diwawancarai film ini, mengatakan pembunuhan terhadap perempuan pekerja seks hanyalah “pembunuhan ikan dan keripik”. Beritanya dicetak di koran-koran hari ini tapi besok koran-koran itu cuma bakal jadi pembungkus ikan dan keripik. Ia cuma berita kecil yang dibaca sambil lalu.
Kejahatan terhadap seseorang, siapa pun ia, tak semestinya dikaitkan dengan profesi atau latar belakang sosialnya. Prasangka sosial seperti ini menciptakan diskriminasi. Ibarat jatuh tertimpa tangga, korban dipersalahkan atas kejahatan yang menimpanya (blaming victim). Dalam dokumenter ini, digambarkan bagaimana sebagian orang menganggap para korban “layak” menjadi korban hanya karena mereka pekerja seks yang kelayapan di jalanan pada malam hingga dinihari.
Padahal, bisa jadi satu bulan, satu pekan, atau bahkan satu hari sebelumnya mereka bukan pekerja seks. Hanya karena tekanan ekonomi, mereka terpaksa melakukan itu. Inilah yang juga disoroti The Ripper. Vile dan Wood memberi konteks sosio-historis, dimana Yorkshire kala itu mengalami depresi ekonomi. Terjadi gelombang deindustrialisasi akibat invasi barang-barang impor, sehingga pabrik-pabrik tutup dan banyak keluarga kehilangan mata pencaharian.
Kalaupun pekerja seks, mereka toh tetap manusia yang berhak memperoleh perlindungan. Mengapa polisi dan media harus menyebut mereka pelacur, hama (salah satu polisi menyebut mereka pest) masyarakat, atau perempuan penikmat kesenangan (good time girl) yang meninggalkan keluarga dan anak mereka alih-alih ibu, saudara, putri, atau bibi seseorang?
Di sisi lain, rasa aman yang diberikan kepada masyarakat lewat prasangka sosial seperti itu adalah rasa aman yang semu. Ketika korban kelima, Jayne MacDonald, ternyata perempuan 16 tahun yang bekerja pada sif malam di sebuah toko kelontong, masyarakat terkejut. Ternyata si pencabik juga mengincar perempuan “tak berdosa”. Frasa “tak berdosa” digunakan pers untuk membedakan Jayne dengan empat korban lain. Masyarakat gelisah dan mulai mempertanyakan kemampuan polisi dalam mengungkap kasus ini. Kasus yang semula hanya perburuan lokal terhadap pembunuh pekerja seks berubah menjadi pembicaraan nasional di Inggris. Tapi, polisi tetap berkeras bahwa pelaku salah mengidentifikasi target karena kebetulan Jayne pulang pada dinihari dari tempat kerjanya. Kegelisahan dan ketidakpuasan publik meningkat ketika pelaku membunuh perempuan-perempuan dari kalangan kelas menengah: sekretaris sebuah perusahaan dan dua mahasiswi.
Kepala batu polisi—yang terbangun dari prasangka sosial yang akut—inilah yang justru menjadi benih kesesatan mereka dalam mengungkap kasus ini. Dalam dua episode terakhir, dokumenter ini menunjukkan bagaimana laporan-laporan polisi—yang diungkap reporter The Sunday Times Joan Smith—disesaki prasangka sosial, misogini, dan seksisme. Akibat budaya kerja seperti itu, polisi mengabaikan kesaksian sejumlah korban selamat, yang sangat mungkin bisa mengarahkan mereka kepada pelaku lebih awal, sehingga bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Para korban selamat itu diabaikan hanya karena mereka bukan pekerja seks, padahal bisa mendeskripsikan wajah dan aksen pelaku.
Kesesatan polisi makin menjadi-jadi ketika mereka begitu mudah mempercayai kiriman surat-surat dan kaset berisi rekaman suara dari seseorang yang mengaku bernama “Jack the Ripper”. Seperti “Jack the Ripper” dari era Victorian, “The Ripper” era moden ini juga menyatakan niatnya untuk membersihkan jalanan dari para pekerja seks melalui surat-suratnya. Polisi menganalisis surat dan kaset itu lalu menyimpulkan bahwa pelaku berasal dari luar Yorkshire, yakni Sunderland, dan beraksen Wearside (atau kadang disebut juga aksen Geordie). Polisi merasa mereka telah berhasil mempersempit profil buruan mereka, padahal justru tersesat. Korban-korban selamat—yang diabaikan itu—bersaksi bahwa pelaku adalah warga lokal, berasal dari Yorkshire. Tapi, karena begitu terobesesi dengan asumsi bahwa si pembunuh membenci pekerja seks, polisi tak memedulikan kesaksian tersebut.
Lebih ironis, si pelaku, Sutcliffe, pernah diinterogasi oleh polisi lima kali berkaitan dengan kasus ini. Seorang polisi bahkan memberi catatan bahwa pria 30 tahunan itu sangat mirip dengan sketsa pelaku yang pernah dibuat berdasarkan kesaksian korban selamat. Pelacakan uang 5 paun yang ditemukan di salah satu TKP juga berujung di perusahaan tempat Sutcliffe bekerja. Tapi, sekali lagi, polisi mengabaikan semua petunjuk itu karena asumsi-asumsi yang digelayuti prasangka sosial tadi.
Dokumenter ini secara implisit menunjukkan bahwa, saat true crime terjadi, polisi justru bagian dari masalah, dan bukan solusi. Masalah itu tidak bersifat individual (oknum) tapi institusional. Ia mengakar dalam budaya kerja polisi berupa prasangka sosial, baik itu yang berdasarkan atas kelas ekonomi, gender, dan ras. Sosiolog Amerika Alex Vitale dalam The End of Policing (buku yang telah kami ulas) memandang problem tersebut ada karena polisi diciptakan untuk menegakkan ketundukan—bukan keadilan—di dalam suatu masyarakat demi kepentingan kelas sosial tertentu (baca penguasa dan pemilik modal).
Problem kelahiran tersebut membuat kelas sosial tersebut membebani polisi dengan tugas-tugas yang berada di luar kapasitasnya, seperti menangani pemogokan buruh, prostitusi, dan penyalahgunaan narkotika (dan kini bahkan mimpi dijadikan urusan polisi). Masalah-masalah ini bukanlah kejahatan murni (true crime) yang bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan penegakkan hukum, terlebih yang didasarkan pada budaya balas dendam (culture of revenge) untuk memenjarakan pelaku.
Alhasil, yang terjadi adalah polisi kelebihan beban pekerjaan sedangkan tugas utama mereka, melindungi masyarakat dan menyelesaikan true crime, terabaikan. Polisi lebih sibuk menangkapi pekerja seks daripada pelaku perdagangan manusia dalam jaringan prostitusi. Polisi lebih sibuk memenjarakan pemadat daripada bandar-bandar narkotika yang seringkali malah dibekingi pemilik modal. Polisi lebih sibuk memberangus serikat pekerja daripada memburu koruptor yang menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi.
Berbeda dengan film konvensional yang menyajikan pandangan dan narasi sineasnya, film dokumenter, menurut teoritikus film Bill Nichols, merepresentasikan pandangan yang lain. Dari sisi ini, Veil dan Wood berhasil memilih sisi yang lebih substansial daripada sekadar menguliti siapa si jagal dari Yorkshire ini, sebagaimana yang biasanya dilakukan film dokumenter tentang true crime. The Ripper merepresentasikan sudut pandang korban, dalam hal ini secara umum adalah kaum perempuan. “Ini adalah kejahatan atas kaum perempuan,” begitu pernyataan seorang narasumber film ini. Ya, kaum perempuan dipaksa menaati aturan jam malam sementara pembunuhnya seakan dibiarkan bebas berkeliaran, padahal mereka adalah korban kejahatan ini. Korban kembali menjadi korban untuk kesekian kalinya akibat prasangka sosial dan ketidakmampuan polisi.[]








