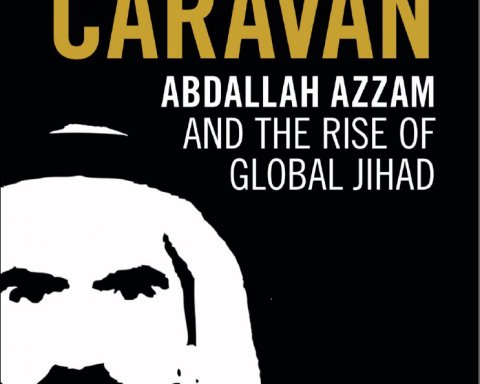Sudut pandang film dokumenter ini komprehensif, membuat kita bisa memahami apa yang terjadi pada 11 September 2001 di New York, apa yang melatarinya, dan mengapa konsekuensinya berlanjut hingga kini.
PEKAN ini, rakyat Amerika Serikat memeringati 20 tahun tragedi 9/11, atau serangan teror atas Menara Kembar World Trade Center (WTC) di pusat kota New York pada 11 September 2001 yang membunuh hampir 3.000 orang. Terkait peringatan itu, terbersit tanya di benak saya.
Apakah rakyat Amerika masih merasakan kemarahan dan hasrat balas dendam seperti setelah mengalami horor tiga jam 41 menit dua dekade lalu (sejak pesawat pertama menabrak Menara Utara pada pukul 08.55 hingga Menara Utara kolaps pada pukul 12.36)? Apakah mereka masih akan mengatakan bahwa mereka dibenci karena nilai kebebasan dan materialisme yang mereka banggakan itu? Apakah mereka masih akan menyeru agar orang-orang yang melakukan ini dan negeri tempat mereka berada dibom sedemikian rupa hingga negeri itu kembali ke zaman batu? Apakah politisi-politisi mereka masih akan mengatakan bahwa dunia harus menyaksikan murka Amerika, seperti pernah dikatakan Hillary Clinton saat itu?
Apakah mereka masih merasakan, memikirkan, dan akan mengatakan semua itu ketika war on terror atau murka Amerika itu saat ini telah mengakibatkan 929.000 nyawa melayang, 38 juta orang terusir dari kampung halaman, dan delapan triliun dolar terkuras? Apakah semua itu masih mereka rasakan ketika Taliban, kelompok yang mereka coba hancurkan, saat ini ternyata makin kuat dan kembali berkuasa di Afghanistan? Apakah semua itu masih mereka rasakan ketika Al-Qaeda, kelompok teror yang mereka buru sampai ke liang semut itu, kini bermutasi menjadi ratusan kelompok teror dengan ideologi yang sama dan bahkan lebih ekstrem?
Jawaban dari semua pertanyaan itu saya temukan dalam film dokumenter terbaru Netflix, Turning Point: 9/11 and the War on Terror. Dokumenter lima episode ini dibesut oleh Brian Knappenberger, sutradara yang kerap membuat dokumenter untuk Discovery Channel, Bloomberg, dan PBS. Karya-karya Knappenberger sebelumnya adalah We Are Legion: The Story of the Hacktivists, The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz, Nobody Speak: Trials of the Free Press, dan The Trials of Gabriel Fernandez. Dua judul terakhir masih bisa kita saksikan di Netflix.

- Judul Film: Turning Point: 9/11 and the War on Terror
- Sutradara: Brian Knappenberger
- Rilis: 1 September 2021
- Durasi: 5 episode (@ 60 menit)
Menjelang 11 September tahun ini, sejumlah dokumenter tentang 9/11 memang bermunculan di televisi dan layanan streaming. Sebut saja misalnya America After 9/11 (PBS), In the Shadow of 9/11 (PBS), NYC Epicenters 9/11➔2021½ (HBO), dan 9/11: Inside the President’s War Room (Apple TV).
Namun, dari semua itu, tak ada yang mengulas secara komprehensif tentang konteks sebelum, menjelang, dan setelah 9/11 kecuali film Knappenberger ini. Turning Point bagi saya seperti sebuah “ringkasan” sejarah visual tentang 9/11 dan “perang melawan teror”. Isinya singkat (lima episode dengan rata-rata durasi satu jam) tapi sekaligus mendalam.
Film ini tak melulu menyoroti serangan teror itu dan bagaimana respons warga serta politisi Amerika saat itu. Ia juga mundur ke dekade 1980-an ketika kebijakan luar negeri dan aksi intelijen Amerika menyiapkan karpet merah bagi kemunculan Al-Qaeda, yang kemudian kita tahu menjadi dalang 9/11. Ia pun menyoroti bagaimana “perang melawan teror” (yang merupakan respons Amerika atas 9/11) membidas tak hanya Al-Qaeda tapi juga nyawa ratusan ribu orang tak bersalah dan bahkan prinsip serta nilai Amerika sendiri.
Film ini mewawancarai puluhan sumber, dari mulai warga Amerika, politisi Amerika, intelijen serta agen federal Amerika, serdadu Amerika, politisi Afghanistan (di antaranya adalah “sang pangeran kegelapan” Gulbuddin Hekmatyar), petinggi Taliban, jurnalis, peneliti, warga Afghanistan, dan bahkan warga di perbatasan Afghanistan-Pakistan yang menjadi korban keganasan drone Amerika. Ia mengoleksi cuplikan-cuplikan rekaman video dan audio saat kejadian berikut paparan ringkas sejumlah dokumen.
Jadi, jika ingin lebih memahami apa itu 9/11, bagaimana tragedi ini bisa terjadi, serta bagaimana konsekuensinya bagi dunia (bukan hanya bagi Amerika), Anda tak boleh melewatkan Turning Point. Film ini merupakan tontonan wajib, terutama pada saat ini ketika Taliban mengambil alih Kabul dan kembali berkuasa di Afghanistan.
Dalam 20 menit pertama, film ini menceritakan momen 9/11 secara kronologis. Banyak data disajikan, dari mulai rekaman audio pengawas lalu lintas udara, rekaman kokpit pesawat yang dibajak—yang memerdengarkan suara kru dan si pembajak—hingga rekaman audio petugas pengawas komando pertahanan udara Amerika atau Norad. Semua itu menunjukkan bahwa pada menit-menit menjelang tabrakan, aparat keamanan Amerika telah mengetahui sebagian pesawat di ruang udara mereka telah dibajak. Tapi, pada saat yang sama, mereka tak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan, permintaan intersepsi oleh jet tempur F-16 direspons petugas Norad dengan keraguan: “Apakah ini latihan?”
Cuplikan-cuplikan rekaman mentah video dan foto menunjukkan kengerian yang terjadi selama hampir empat jam itu. Yang paling membekas di pikiran saya dari semua itu adalah apa yang disebut oleh media dengan “The Falling Man”. Ini foto dan rekaman video dari orang-orang yang berada di lantai pusat tabrakan hingga lantai-lantai di atasnya. Mereka hanya punya dua pilihan dan kedua-duanya fatal: membiarkan tubuh dilahap kobaran api dan paru-paru disesaki asap atau terjun bebas dari ketinggian empat ratusan meter ke aspal jalanan.
Film ini secara singkat menelusuri investigasi FBI terhadap pelaku-pelaku teror 9/11. Satu hal yang menarik dan baru-baru ini menjadi headline media massa arus utama adalah temuan FBI bahwa keberadaan sebagian pembajak pesawat di Amerika difasilitasi oleh individu-individu yang bekerja atau berhubungan dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Satu nama yang diungkap oleh Knappenberger dalam film ini adalah Omar Al-Bayoumi. Dia memberi tempat tinggal dan fasilitas lainnya kepada dua bakal calon pembajak, Khalid al-Mihdhar dan Nawaf al-Hazmi, saat keduanya tiba di San Diego kurang dari setahun sebelum 11 September 2001. Al-Bayoumi sempat ditangkap polisi Inggris dan diinterogasi oleh FBI dan CIA tapi kemudian dilepaskan begitu saja meskipun FBI meyakini orang ini adalah agen atau aset intelijen Saudi.
Keluarga korban 9/11 melalui pengacara mereka baru-baru ini menuntut pemerintah Presiden Joe Biden membuka dokumen hasil penyelidikan FBI tersebut. Pada 2016, mereka pernah berhasil menggugat informasi yang terkandung di dalam 28 dari 832 halaman laporan pemeriksaan Kongres Amerika atas komunitas intelijen Amerika.
Dokumen yang biasa disebut “The 28 Pages” itu juga berisi informasi koneksi antara para pelaku teror 9/11 dengan individu-individu yang bekerja atau berhubungan dengan pemerintahan Saudi. Karena isinya yang sensitif, pemerintahan Presiden George W Bush kala itu “menyingkirkan” ke-28 halaman itu dari laporan resmi pemeriksaan Kongres.
“The 28 Pages” memang tidak ditampilkan dalam Turning Point. Tapi, jika membacanya, kita akan mengetahui bahwa isinya berhubungan dengan dokumen penyelidikan FBI. Misalnya, dokumen itu menyebut bahwa Al-Bayoumi melalui istrinya menerima ribuan dolar per bulannya dari rekening yang berhubungan dengan rekening istri Pangeran Bandar bin Sultan, Duta Besar Saudi saat itu. Pangeran Bandar adalah nama pejabat tertinggi Saudi yang secara resmi disebut dalam “The 28 Pages”.
Tanpa menunggu hasil semua penyelidikan itu, Presiden Bush dan Kongres memutuskan untuk menyerang Afghanistan hanya dalam waktu kurang dari sepekan setelah 9/11. Pemerintahan Taliban memang menampung Osama bin Laden, gembong Al-Qaeda yang kerajaan bisnis keluarganya memiliki kedekatan dengan keluarga Kerajaan Saudi. Tapi pertanyaannya, siapakah yang pertama-tama membawa Osama dan gerombolannya ke Afghanistan? Siapa pulakah, seperti diungkap dalam dokumenter ini, yang memberi lampu hijau kepada Sudan, tempat tinggal Osama pada 1998, untuk mendeportasi taipan konstruksi itu ke Afghanistan? Jawabannya adalah Amerika sendiri.
Sejak invasi atas Afghanistan pada Oktober 2001, murka Amerika dalam jubah “perang melawan teror” itu mulai kebablasan. Dahaga rezim Bush untuk menyalakan mesin-mesin perang Amerika seperti tak pernah terpuaskan. Pada 2003, mereka menyerang Irak dengan dalih Saddam Hussein memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dan menyimpan senjata pemusnah massal. Dalih yang disampaikan Menteri Luar Negeri Colin Powel di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB itu—kita tahu kini—hanyalan bualan belaka, yang sayangnya didukung habis-habisan oleh media arus utama di Amerika dan Barat. Jika saat ini dikatakan bahwa rakyat Amerika, dan juga dunia, skeptis kepada media arus utama, maka salah satu sebabnya adalah kebohongan demi kebohongan Washington yang media bela saat itu.
Tak berhenti di Irak, Amerika tetap menggerakkan mesin-mesin perang mereka di sedikitnya delapan negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara. Militer Amerika juga tak meninggalkan Afghanistan meskipun pemerintahan Taliban jatuh tak lama setelah invasi 2001. Murka tak jua berhenti bahkan ketika mereka berhasil membunuh Osama di Abottabad, Pakistan, pada 2010. Murka Amerika makin brutal dengan pengerahan massif armada drone pada masa pemerintahan Barack Obama. Rudal-rudal Hellfire yang dilepaskan oleh armada Predator tak hanya menewaskan ribuan orang tak berdosa (sebagian besar di perbatasan Afghanistan-Pakistan) tapi juga makin menumbuhkan dukungan bagi Taliban.
Dalih memburu pelaku 9/11 sebenarnya sudah kabur sejak pertama kali Amerika menggelar perang di Afghanistan. Turning Point menunjukkan bahwa Amerika tidak mengerahkan kekuatan yang cukup untuk memburu Osama, padahal sang dalang teror itu sudah terdesak di gua-gua Tora Bora pada Desember 2001.
Makin berlanjut, perang makin tak jelas tujuannya. Sebuah laporan pemeriksaan inspektorat jenderal Pentagon mengungkap bahwa jenderal-jenderal Amerika dan NATO mengaku tidak tahu tujuan perang mereka. Tanpa tahu tujuan, perang hampir bisa dipastikan tak akan pernah usai. Perang tanpa tujuan juga mendemoralisasi sebagian pasukan Amerika. Mereka stres dan mengalami depresi, terutama saat pulang dari tugas.
“Perang melawan teror”, seperti ditunjukkan oleh film ini, juga telah merusak nilai dan prinsip Amerika sendiri. Sejumlah kebijakan draconian lahir tak lama setelah rezim Bush menyatakan Amerika akan membalas. Semua kebijakan itu sayangnya diamini oleh Kongres Amerika tanpa reserve.
Kebijakan-kebijakan itu antara lain adalah Undang-Undang Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer (Authorization for Use of Military Force) dan Undang-Undang Patriot (Patriot Act) yang mengizinkan aparat keamanan Amerika memata-matai dan menyadap warga mereka sendiri secara massif serta menghapuskan habeas corpus, sebuah prinsip hukum yang memberi hak kepada orang yang ditahan untuk mempertanyakan alasan penahanannya. Lalu, ada Undang-Undang Komisi Militer (The Military Commissions Act) yang mengangkangi Konvensi Jenewa dan membuat ratusan orang dipenjarakan tanpa batas dan tanpa proses peradilan di Teluk Guantanamo. Daftar ini makin panjang dengan praktik penyiksaan terhadap tahanan yang disebut dengan istilah keren “enhanced interrogation techniques” dan tentu saja penahanan sejumlah orang di luar negeri tanpa sepengetahuan otoritas setempat atau yang kita kenal dengan “CIA black sites”.
Semua kebijakan itu dan praktiknya terus berlanjut hingga kini. Alberto Gonzales, penasehat hukum dan mantan jaksa agung pada pemerintahan Bush, mencoba membela semua kebijakan itu dalam dokumenter ini. Tapi, dia pada akhirnya mengakui bahwa semua itu seharusnya sudah dihentikan. Sebab, dia bilang, semua itu dibuat hanya untuk memburu pelaku 9/11.
Namun, Gonzales pura-pura buta dan tuli. Dalam semua kebijakan itu, tak ada klausul tentang batasan waktu dan target. Dia sebenarnya tahu semua itu cek kosong bagi penguasa Amerika.
Turning Point memang tidak mengungkap alasan sesungguhnya di balik “perang melawan teror” yang mengharu-biru kita selama 20 tahun. Tapi, secara implisit, film ini menunjukkan bahwa perang ini hanya bertujuan demi perang itu sendiri, dan bukan demi memburu pelaku teror 9/11.
Perang ini bertujuan demi mengisi pundi-pundi industri-industri militer Amerika, elite-elitenya, dan pejabat-pejabat institusinya. Miliaran dollar yang mengalir ke Afghanistan ternyata tak menyentuh proyek-proyek kemanusiaan atau demokratisasi tapi lebih banyak mengisi kantong para kontraktor keamanan yang berkolusi dengan elite-elite politik Afghanistan serta kroninya yang didukung oleh Amerika.
Knappenberger, seperti saya sebutkan sebelumnya, juga mundur ke dekade 1980-an sebelum Taliban muncul ke permukaan dan Al-Qaeda lahir. Intelijen Amerika dengan bantuan intelijen Pakistan dan Saudi melancarkan operasi untuk memobilisasi dukungan kepada pejuang-pejuang mujahidin yang melawan pendudukan Uni Soviet di Afghanistan. Dukungan tak hanya berupa persenjataan dan dana, tapi juga mobilisasi para ‘serdadu’ partikelir dari banyak negeri muslim di dunia, termasuk Indonesia. Mereka tak menyadari kala itu bahwa mereka tengah menanam benih-benih ekstremisme dan terorisme di Afghanistan. Para serdadu “jihadis” global itulah yang kemudian menamakan diri mereka Al-Qaeda dan menebar teror di mana-mana.
Turning Point di titik ini seakan ingin menyatakan bahwa sekali sekelompok manusia mengenal mesin pembunuh, maka pada saat itu pula mereka berpotensi untuk memendam selera membunuh dan melakukan kekerasan. Itulah yang terjadi pada Taliban dan Al-Qaeda. Ideologi ekstremisme mereka mungkin sudah ada sejak lama. Tapi, tanpa senjata, ideologi tinggallah ide-ide di dalam sel abu-abu manusia.
Ketika kembali ke situs peringatan 9/11, Turning Point menyajikan sebuah akhir yang sempurna sekaligus menjawab pertanyaan saya di atas. Saksi-saksi mata tragedi itu, baik mereka yang berada di kedua menara tersebut, para petugas polisi, maupun petugas pemadam kebakaran, kini melihat 9/11 dalam perspektif yang lebih luas. Murka itu sudah tak ada. Yang ada sesal dan kecewa kepada pemerintah mereka. Bagi mereka, di saat-saat seperti itu, rakyat Amerika justru membutuhkan pemimpin yang bisa berpikir dingin dan memutuskan respons rasional dan terukur.
Itulah yang diungkapkan Barbara Lee, satu-satunya anggota Kongres Amerika yang menolak Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer pada 2001. Saat itu, Barbara malah dicibir sebagai pengkhianat dan menerima ratusan email serta panggilan telepon yang mengancam.
Dia sejak lama tahu bahwa kebijakan “perang melawan teror” pada akhirnya akan membuat Amerika menjadi sesuatu yang dibencinya sendiri. “Perang melawan teror” tak akan menghentikan teror tapi malah menyemai benih-benih baru terorisme. Barbara ternyata benar. Kini Al-Qaeda beranak pinak menjadi ratusan sel teror yang berideologi serupa dan bahkan lebih ekstrem.
“Kebencian bukanlah respons yang baik,” kata Brenda Berkman, pensiunan kapten di dinas pemadam kebakaran New York saat mengunjungi situs peringatan 9/11. “…Hanya cinta.”[]